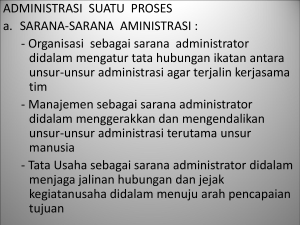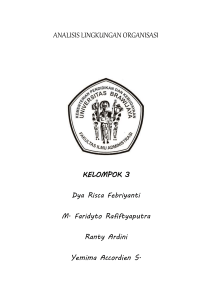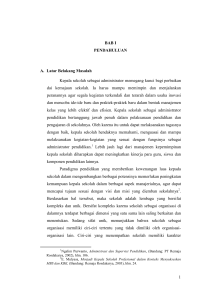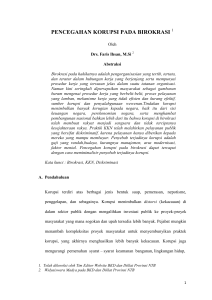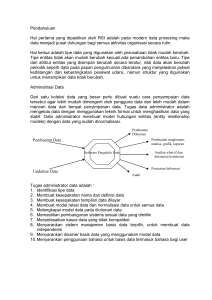Budaya Birokrasi dan Etika Pelayanan Publik
advertisement
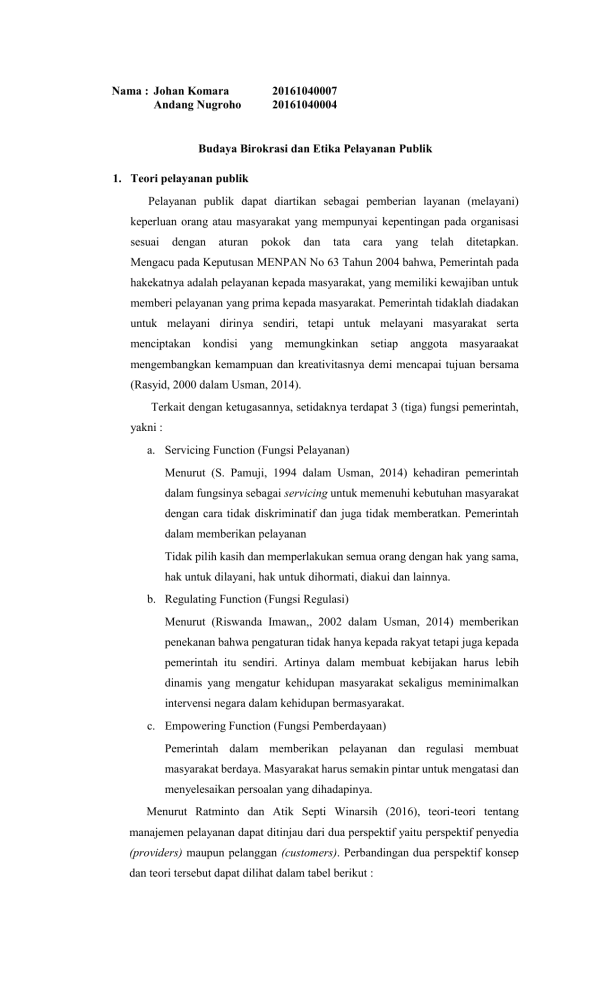
Nama : Johan Komara Andang Nugroho 20161040007 20161040004 Budaya Birokrasi dan Etika Pelayanan Publik 1. Teori pelayanan publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Mengacu pada Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2004 bahwa, Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, yang memiliki kewajiban untuk memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 2000 dalam Usman, 2014). Terkait dengan ketugasannya, setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi pemerintah, yakni : a. Servicing Function (Fungsi Pelayanan) Menurut (S. Pamuji, 1994 dalam Usman, 2014) kehadiran pemerintah dalam fungsinya sebagai servicing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Pemerintah dalam memberikan pelayanan Tidak pilih kasih dan memperlakukan semua orang dengan hak yang sama, hak untuk dilayani, hak untuk dihormati, diakui dan lainnya. b. Regulating Function (Fungsi Regulasi) Menurut (Riswanda Imawan,, 2002 dalam Usman, 2014) memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada pemerintah itu sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat. c. Empowering Function (Fungsi Pemberdayaan) Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan regulasi membuat masyarakat berdaya. Masyarakat harus semakin pintar untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2016), teori-teori tentang manajemen pelayanan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu perspektif penyedia (providers) maupun pelanggan (customers). Perbandingan dua perspektif konsep dan teori tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : Konsep dan Teori Perspektif Manajemen Pelayanan Providers 1. Momen Kritis Pelayanan (moment of truth) dari Albrecht dan Bradford (1990). - Harus ada kesesuaian atau kompatibilitas antara tiga faktor dalam pengelolaan moment of truth, yaitu: a. Konteks pelayanan b. Referensi yang dimiliki oleh anggota yang dimiliki oleh anggota organisasi c. Referensi organisasi penyelenggara pelayanan. 2. Lingkaran Pelayanan dari Albrecht dan Bradford (1990) - Dalam memberikan pelayanan yang terbaik, produsen harus memandang produk atau jasa layanan yang konsumen kita berikan memandang sebagaimana produk atau jasa layananan tersebut. 3. Model Segitiga Pelayanan dari Albert dan Zemke (1990) - Sinergitas sistem, SDM, strategi akan menentukan keberhasilan manajemen kinerja pelayanan publik 4. Kep MenPAN No 63 Tahun 2004 - Adanya survey berkala tentang indeks kepuasan masyarakat - Pengawasan partisipatif 5. Sebelas Prinsip dari Viljoen (1997) - Identifikasi kebutuhan konsumen - Pelayanan terpadu - Sistem yang mendukung - Semua pelayanan karyawan bertanggungjawab atas Customers - Tangani keluhan - Terus berinovasi - Karyawan sama pentingnya dengan konsumen - Tegas dan ramah terhadap konsumen - Interaksi khusus dengan pelanggan - Kontrol kualitas 6. Gap Model dari Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) - Gap persepsi manajemen - Gap persepsi kualitas - Gap penyelenggaraan pelayanan - Gap komunikasi pasar - Gap kualitas pelayanan 7. Teori Exit & Voice dari Albert Hirschman (Jones, 1994) - Kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme ‘exit’, yang berarti bahwa jika pelayanan public tidak berkualitas maka konsumen/klien harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan public yang lain yang disukainya. Sedangkan mekanisme ‘voice’ berarti adanya kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan public. 8. Citizen Charter - Dokumen yang berisi hak & kewajiban antara providers and customers 2. Menjelaskan budaya pelayanan publik. Menurut (Denhardt & Denhardt, 2007) bahwa pemerintahan tidak boleh dijalankan seperti sebuah bisnis, tetapi harus dijalankan seperti sebuah demokrasi (government shouldn’t be run like a business, it should be run like a democracy). Artinya bahwa pemerintah dalam memperlakukan dan melayani masyarakat tidak memposisikannya murni sebagai customer dan hanya mengejar profit tetapi lebih dari itu juga harus memperhatikan masyarakat yang memiliki hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Salah satu faktor yang harus ada agar dapat diselenggarakan pelayanan yang berkualitas adalah adanya budaya pelayanan yang beorientasi kepada kepentingan pelanggan atau pengguna jasa. Dalam konteks pelayanan publik berarti budaya pelayanan yang beorientasi kepada kepentingan masyarakat. Terkait dengan budaya organisasi, Sethia dan Glinow dalam bukunya Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2016), membagi tipe budaya organisasi berdasar perhatiannya terhadap orang dan perhatiannya terhadap kinerja. Secara visual perbedaan diantara empat model dapat digambarkan sebagai berikut : Manusia Caring Integrative Apathetic Exacting Kinerja Penjelasan - Caring culture : Tingkat kepedulian terhadap hubungan antar manusia tinggi Tingkat kepedulian terhadap kinerja rendah - Apathetic culture : Tingkat kepedulian terhadap hubungan antar manusia rendah Tingkat kepedulian terhadap kinerja rendah - Integrative culture : Tingkat kepedulian terhadap hubungan antar manusia tinggi Tingkat kepedulian terhadap kinerja tinggi - Exacting culture : Tingkat kepedulian terhadap hubungan antar manusia rendah Tingkat kepedulian terhadap kinerja tinggi 3. Menjelaskan budaya birokrasi pelayanan publik. Dengan mengacu pada pengelompokan tipe budaya pelayanan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tipe budaya yang ada di dalam organisasi publik indonesia adalah tipe caring culture. Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2016) organisasi publik di Indonesia biasanya memiliki perhatian yang sangat rendah terhadap kinerja namun memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap hubungan antar manusia. Hal ini tampak dari ciri-ciri birokrat sebagai berikut : - Lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada klien atau masyarakat - Lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat - Meminimalkan resiko dengan cara menghindari untuk mengambil inisiatif - Menghindari tanggung jawab - Menolak tantangan - Tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya Budaya ini tidak cocok dalam pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian harus diadopsi budaya baru yang lebih sesuai dan kondusif dengan manajemen pelayanan publik. Dari keempat tipe budaya organisasi tersebut diatas integrative culture adalah yang terbaik. Menurut Osborne dan Gaebler dalam bukunya Reinventing Government / Mewirausahakan Birokrasi, ada sepuluh semangat kewirausahaan yang perlu untuk di adopsi oleh birokrat pelayan publik, antara lain sebagai berikut : - Mengarahkan ketimbang mengayuh - Memberi wewenang kepada masyarakat - Menyuntikkan persaingan dalam pemberian pelayanan - Menciptakan organisasi yang digerakkan oleh misi ketimbang oleh peraturan - Lebih berorientasi pada hasil bukan input - Berorientasi pada pelanggan, bukan birokrasi - Berorientasi wirausaha - Bersifat antisipatif - Beorientasi pada pasar Mengadopsi 10 prinsip wirausaha sebagaimana yang disampaikan Osborne dan Gaebler dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun perlu dipertimbangkan konsep new public service yang disampaikan oleh Denhardt bahwa pelayanan publik tidak seyogyanya dilaksanakan 100% seperti bisnis, tetapi juga mempertimbangkan terutama yang berkaitan dengan hak sipil dan kewajiban pemerintah dalam memfasilitasi hak tersebut. Untuk menciptakan atau mengembangkan budaya pelayanan di kalangan pegawai negeri pemerintah melalui Kemen PAN no 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara, yang antara lain disampaikan nilai-nilai kerja sebagai berikut : a. Komitmen dan konsistensi b. Wewenang dan tanggung jawab c. Keikhlasan dan kejujuran d. Integritas dan profesionalisme e. Kreativitas dan kepekaan f. Kepemimpinan dan keteladanan g. Kebersamaan dan dinamika kelompok kerja h. Ketepatan dan kecepatan i. Rasionalitas dan kecerdasan emosi j. Keteguhan dan ketegasan k. Disiplin dan keteraturan kerja l. Keberanian dan kearifan m. Dedikasi dan loyalitas n. Semangat dan motivasi o. Ketekunan dan kesabaran p. Keadilan dan keterbukaan q. Penguasaan IPTEK 4. Menjelaskan efektivitas pelayanan publik Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dan jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasiorganisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi pelayanananya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai programprogram pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan (termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya proses panjang dan berbelit-belit apabila masyarakat menyelesaikan urusannya berkaitan dengan pelayanan aparatur pemerintahan . Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik). Oleh karena itu, guna menanggulangi kesan buruk birokrasi seperti itu, birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain : a. Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan b. Birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat) c. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu. d. Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu (change of agent ) pembangunan e. Birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya lebih desentralistis, inovatif, flrksibel dan responsif. Dari pandangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan pelayanannya sesuai yang diharapkan masyarakat pelanggannya. Sedangkan dalam kontek persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency). 5. Menjelaskan landasan etika pelayanan publik. Menurut Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadaminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu etika (1) sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules of conduct; dan (3) penelitian tentang unsur pertama dan kedua diatas (lihat Denhardt, 1988: 28). Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin. Dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. administrasi, Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dsb.Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan public (public service) identik dengan public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (lihat J.L.Perry, 1989: 625). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab. Karya Denhardt yang berjudul The Ethics of Public Service (1988) merupakan contoh dari pandangan ini, dimana pelayanan publik benar-benar identik dengan administrasi publik. Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standards (kode etik), atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (lihat Denhardt, 1988). Berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik diatas maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik (delivery system) yang didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan. Masalah tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, meskipun telah disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Etika sering dilihat sebagai elemen yang kurang berkaitan dengan dunia pelayanan publik. Padahal, dalam literatur tentang pelayanan publik, etika merupakan salah satu elemen yang sangat menentukan kepuasan publik yang dilayani sekaligus keberhasilan organisasi pelayanan publik itu sendiri. Elemen ini harus diperhatikan dalam setiap fase pelayanan publik mulai dari penyusunan kebijakan pelayanan, desain struktur organisasi pelayanan, sampai pada manajemen pelayanan untuk mencapai tujuan akhir dari pelayanan tersebut. Dalam konteks ini, pusat perhatian ditujukan kepada aktor yang terlibat dalam setiap fase, termasuk kepentingan aktor-aktor tersebut – apakah para aktor telah benar-benar mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, dengan menggunakan nilai-nilai moral yang berlaku umum (six great ideas) seperti nilai kebenaran (truth), kebaikan (goodness), kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice), kita dapat menilai apakah para aktor tersebut jujur atau tidak dalam penyusunan kebijakan, adil atau tidak adil dalam menempatkan orang dalam unit dan jabatan yang tersedia, dan bohong atau tidak dalam melaporkan hasil manajemen pelayanan. Dalam pelayanan publik, perbuatan melanggar moral atau etika sulit ditelusuri dan dipersoalkan karena adanya kebiasaan masyarakat kita melarang orang “membuka rahasia” atau mengancam mereka yang mengadu. Sementara itu, kita juga menghadapi tantangan ke depan semakin berat karena standard penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan paradigmanya. Dan secara substantif, kita juga tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika karena penuh dengan dilema. Karena itu, dapat dipastikan bahwa pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus meningkat Setiap masyarakat atau bangsa pasti mempunyai pegangan moral yang menjadi landasan sikap, perilaku dan perbuatan mereka untuk mencapai apa yang dicitacitakan. Dengan pegangan moral itu mana yang baik dan mana yang buruk, benar dan salah serta mana yang dianggap ideal dan tidak. Oleh karena itu dimana pun kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara peranan etika tidak mungkin dikesampingkan. Semua warga negara berkepentingan dengan etika. Sebagaimana diketahui, birokrasi atau administrasi publik memiliki kewenangan bebas untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kepada birokrasi diberikan kekuasaan regulatif, yakni tindakan hukum yang sah untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen yang disebut kebijakan publik. Sebagai suatu produk hukum, kebijakan publik berisi perintah (keharusan) atau larangan. Barangsiapa yang melanggar perintah atau melaksanakan perbuatan tertentu yang dilarang, maka ia akan dikenakan sanksi tertentu pula. Inilah implikasi yuridis dari suatu kebijakan publik. Dengan kata lain, pendekatan yuridis terhadap kebijakan publik kurang memperhatikan aspek dampak dan/atau kemanfaatan dari kebijakan tersebut. Itulah sebabnya, sering kita saksikan bahwa kebijakan pemerintah sering ditolak oleh masyarakat (public veto) karena kurang mempertimbangkan dimensi etis dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik hendaknya tidak hanya menonjolkan nilai-nilai benar-salah, tetapi harus lebih dikembangkan kepada sosialisasi nilai-nilai baik – buruk. Sebab, suatu tindakan yang benar menurut hukum, belum tentu baik secara moral dan etis. Dalam wacana kebijakan publik, telah lama didengungkan akan makna pentingnya orientasi pada pelayanan publik. Titik fokusnya pun terarah pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan publik, bukan pada si pembuat kebijakan tersebut. Namun demikian semakin dikaji dan ditelaah kedalaman makna dari konsepsi pelayanan publik tersebut, maka dalam dunia nyata semakin jauh makna hakiki dari pelayanan publik tersebut diimplementasikan secara tepat. Organisasi publik (pemerintah) sebagai institusi yang membawa misi pelayanan publik, akhir-akhir ini semakin gencar mengkampanyekan dan saling berlomba untuk memberikan dan mengimplementasikan makna hakiki dari pelayanan publik tersebut, namun demikian di dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan yang diinginkan. Secara umum ada dua hal yang sangat berperan bagi organisasi pemerintah (birokrasi) di dalam mengimplementasikan konsepsi mengenai pelayanan publik tersebut. Yang pertama adalah faktor komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Disini birokrasi dituntut untuk mempunyai komitmen yang jelas melalui visi dan misi organisasi untuk melaksanakan fungsi pelayanan dengan baik. Yang kedua adalah faktor aparatur pelaksana (birokrat) yang menjalankan fungsi pelayanan tersebut. Disini setiap individu yang menjalankan fungsi pelayanan harus mengacu pada komitmen organisasional yang telah dituangkan didalam visi dan misi organisasi tersebut. Jika kedua hal tersebut dijadikan sebagai acuan di dalam pelaksanaan fungsi pelayanan, maka akan membentuk suatu etika yang dijadikan sebagai pedoman di dalam setiap perilaku birokrat untuk melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh birokrasi, maka telah terjadi pula perkembangan di dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik, yang ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari rule government yang lebih menekankan pada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi paradigma good governance yang tidak hanya berfokus pada kehendak atau kemauan pemerintah semata, tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa, baik birokrasinya itu sendiri, pihak swasta dan masyarakat (publik) secara keseluruhan. Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam bertindak etis, atau dengan kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”. 6. Konsep Etika Pelayanan Publik Bertens (2000) menggambarkan konsep etika dengan beberapa arti, salah satu diantaranya dan biasa digunakan orang adalah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak. Filsuf besar Aristoteles, kata Bertens, telah menggunakan kata etika ini dalam menggambarkan filsafat moral, yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Bertens juga mengatakan bahwa di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, karangan Purwadarminta, etika dirumuskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), istilah etika disebut sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan memperhatikan beberapa sumber diatas, Bertens berkesimpulan bahwa ada tiga arti penting etika, yaitu (1) etika sebagai nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau disebut dengan “sistim nilai”; (2) etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”; dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acapkali disebut “filsafat moral”. Pendapat seperti ini mirip dengan pendapat yang ditulis dalam The Encyclopedia of Philosophy yang menggunakan etika sebagai (1) way of life; (2) moral code atau rules of conduct, (Denhardt, 1988). Salah satu uraian menarik dari Bertens (2000) adalah tentang pembedaan atas konsep etika dari konsep etiket. Etika lebih menggambarkan norma tentang perbuatan itu sendiri – yaitu apakah suatu perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan, misalnya mengambil barang milik orang tanpa ijin tidak pernah diperbolehkan. Sementara etiket menggambarkan cara suatu perbuatan itu dilakukan manusia, dan berlaku hanya dalam pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain, dan cenderung berlaku dalam kalangan tertentu saja, misalnya memberi sesuatu kepada orang lain dengan tangan kiri merupakan cara yang kurang sopan menurut kebudayaan tertentu, tapi tidak ada persoalan bagi kebudayaan lain. Karena itu etiket lebih bersifat relatif, dan cenderung mengutamakan simbol lahiriah, bila dibandingkan dengan etika yang cenderung berlaku universal dan menggambarkan sungguh-sungguh sikap bathin. Keban (2001) mengatakan bahwa dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik (public service) identik dengan public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (J.L.Perry, 1989: 625). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab. Pemikiran tentang etika yang dikaitkan dengan pelayanan publik mengalami perkembangan sejak tahun 1940-an melalui karya Leys (dalam Keban, 1994). Leys mengatakan bahwa seorang administrator dianggap etis apabila ia menguji dan mempertanyakan standar-standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan dan tidak mendasarkan keputusannya semata-mata pada kebiasaan dan tradisi yang sudah ada. Pada sekitar tahun 1950-an mulai berkembang pola pemikiran baru melalui karya Anderson (dalam Keban, 1994) untuk menyempurnakan aspek standar yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Karya Anderson menambah satu poin baru, bahwa standar-standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani. Kemudian pada tahun 1960-an muncul kembali pemikiran baru lewat tulisan Golembiewski (dalam Keban, 1994) yang menambah elemen baru, yaitu standar etika yang mungkin mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan karena itu administrator harus mampu memahami perkembangan dan bertindak sesuai standar-standar perilaku tersebut. Sejak permulaan tahun 1970-an ada beberapa tokoh penting yang sangat besar pengaruhnya terhadap konsepsi mengenai etika administrator publik, dua diantaranya seperti yang dikatakan oleh Keban (1994) adalah John Rohr dan Terry L. Cooper. Rohr menyarankan agar administrator dapat menggunakan regime norms yaitu nilai-nilai keadilan, persamaan dan kebebasan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan cara demikian maka administrator publik dapat menjadi lebih etis (being ethical). Sementara itu menurut Cooper etika sangat melibatkan substantive reasoning tentang kewajiban, konsekuensi dan tujuan akhir; dan bertindak etis (doing ethics) adalah melibatkan pemikiran yang sistematis tentang nilai-nilai yang melekat pada pilihan-pilihan dalam pengambilan keputusan. Pemikiran Cooper bahwa administrator yang etis adalah administrator yang selalu terikat pada tanggungjawab dan peranan organisasi, sekaligus bersedia menerapkan standar etika secara tepat pada pembuatan keputusan administrasi. 7. Hakikat Pelayanan Publik Dan Etika Dalam arti yang sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik berhasil diberikan melalui suatu delivery system yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dsb. Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik (public service) identik dengan public administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik (Perry, 1989). Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititikberatkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak provider yang diberi tanggung jawab. Buku Denhardt yang berjudul The Ethics of Public Service (1988) merupakan contoh dari pandangan ini, dimana pelayanan publik identik dengan administrasi publik yang merupakan bagian dari manajemen ilmu pemerintahan. Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan professional standards (kode etik), atau moral atau right rules of conduct (aturan berperilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik. Berdasarkan konsep etika dan pelayanan publik di atas, maka yang dimaksudkan dengan etika pelayanan publik adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian pelayanan publik (delivery system) yang didasarkan atas serangkaian tuntunan perilaku (rules of conduct) atau kode etik yang mengatur hal-hal yang “baik” yang harus dilakukan atau sebaliknya yang “tidak baik” agar dihindarkan. 8. Paradigma Etika Dalam Pelayanan Publik Menurut Fadillah (2001) etika pelayanan publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Oleh sebab itu maka etika mempersoalkan ”baik-buruk”, dan bukan ”benar-salah” tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, baik dalam masyarakat maupun organisasi publik, maka etika mempunyai peran penting dalam praktek administrasi publik. Dalam paradigma ”dikotomi politik dan administrasi” sebagaimana dijelaskan oleh Wilson (dalam Widodo, 2001) menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan (public policy making) atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara, dan fungsi administrasi, yaitu berkenaan dengan pelaksanaan kebijakankebijakan tersebut. Dengan demikian kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik (political master), dan melaksanakan kebijakan politik tadi merupakan kekuasaan administrasi publik. Namun karena administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik tadi memiliki kewenangan secara umum disebut ”discretionary power”, keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek, maka timbul suatu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara ”baik dan tidak secara buruk” ? Atas dasar inilah etika diperlukan dalam administrasi publik. Etika dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat dikatakan baik atau buruk. Saran klasik di tahun 1900 sampai 1929 untuk memisahkan administrasi dari politik (dikotomi) menunjukkan bahwa administrator sungguh-sungguh netral, bebas dari pengaruh politik ketika memberikan pelayanan publik. Akan tetapi kritik bermunculan menentang ajaran dikotomi administrasi-politik pada tahun 1930-an, sehingga perhatian mulai ditujukan kepada keterlibatan para administrator dalam keputusan-keputusan publik atau kebijakan publik. Sejak saat ini mata publik mulai memberikan perhatian khusus terhadap “permainan etika” yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan. Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap kontribusinya terhadap public interest atau kepentingan umum (Henry, 1995). Hummel (dalam Widodo, 2001) mengatakan bahwa birokrasi sebagai bentuk organisasi yang ideal telah merusak dirinya dan masyarakatnya dengan ketiadaan norma-norma, nilai-nilai dan etika yang berpusat pada manusia. Sementara itu Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa birokrasi melenceng dari keadaan yang seharusnya. Birokrasi selalu dilihat sebagai masalah teknis dan bukan masalah moral, sehingga timbul berbagai persoalan dalam bekerjanya birokrasi publik. Sementara itu pemahaman mengenai pelayanan publik yang disediakan oleh birokrasi merupakan wujud dari fungsi aparat birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sehingga maksud dari pelayanan publik adalah demi mensejahterakan masyarakat. Dalam kaitan itu maka Widodo (2001) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang banyak atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi publik sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut Thoha (1998) mengatakan bahwa kondisi masyarakat saat ini terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik, yaitu dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis, dan dari caracara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1998). Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas aparat birokrasi harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, reponsif, adaptif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi, 1989). Selanjutnya pelayanan publik yang profesional adalah pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan, yaitu aparatur pemerintah (Widodo, 2001). Ciri-cirinya adalah: (1) efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran; (2) sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; (3) kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: (a) prosedur dan tata cara pelayanan; (b) persyaratan pelayanan, baik teknis maupun administratif; (c) unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan;(d) rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; dan (e) jadwal waktu penyelesaian pelayanan; (4) keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak; (5) efisiensi, mengandung arti: (a) persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk layanan yang berkaitan; (b) dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait; (6) ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; (7) responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani; dan (8) adaptif, adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami perkembangan. 9. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dari paparan tersebut di atas maka dapat pula dikatakan bahwa etika sangat diperlukan dalam praktek administrasi publik untuk dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh administrasi publik. Disamping itu perilaku birokrasi tadi akan mempengaruhi bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga masyarakat yang dilayani. Masyarakat berharap adanya jaminan bahwa para birokrat dalam menjalankan kebijakan politik dan memberikan pelayanan publik yang dibiayai oleh dana publik senantiasa mendasarkan diri pada nilai etika yang selaras dengan kedudukannya. Birokrasi merupakan sebuah sistem, yang dalam dirinya terdapat kecenderungan untuk terus berbuat bertambah baik untuk organisasinya maupun kewenangannya (big bureaucracy, giant bureaucracy), perlu menyandarkan diri pada nilai-nilai etika. Dengan demikian maka etika (termasuk etika birokrasi) mempunyai dua fungsi, yaitu: pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela; kedua, etika birokrasi sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Seperangkat nilai dalam etika birokrasi yang dapat digunakan sebagai acuan, referensi, penuntun bagi birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain adalah: (1) efisiensi, artinya tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien; (2) membedakan milik pribadi dengan milik kantor, artinya milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi; (3) impersonal, maksudnya dalam melaksanakan hubungan kerjasama antara orang yang satu dengan lainnya secara kolektif diwadahi oleh organisasi, dilakukan secara formal, maksudnya hubungan impersonal perlu ditegakkan untuk menghindari urusan perasaan daripada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan yang ada dalam organisasi. Siapa yang salah harus diberi sanksi dan yang berprestasi selayaknya mendapatkan penghargaan; (4) merytal system, nilai ini berkaitan dengan rekrutmen dan promosi pegawai, artinya dalam penerimaan pegawai atau promosi pegawai tidak didasarkan atas kekerabatan, namun berdasarkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), sikap (attitude), kemampuan (capable), dan pengalaman (experience), sehingga menjadikan yang bersangkutan cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bukan spoil system (adalah sebaliknya); (5) responsible, nilai ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; (6) accountable, nilai ini merupakan tanggung jawab yang bersifat obyektif, sebab birokrasi dikatakan akun bilamana mereka dinilai obyektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal dan mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (pelayanan publik yang profesional dan dapat memberikan kepuasan publik); (7) responsiveness, artinya birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi, tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan. Berkaitan dengan nilai-nilai etika birokrasi sebagaimana digambarkan diatas, maka dapat pula dikatakan bahwa jika nilai-nilai etika birokrasi tersebut telah dijadikan sebagai norma serta diikuti dan dipatuhi oleh birokrasi publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka hal ini akan dapat mencegah timbulnya tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme, ataupun bentuk-bentuk penyelewengan lainnya dalam tubuh birokrasi, kendatipun tidak ada lembaga pengawasan. Namun demikian harus dimaklumi pula bahwa etika birokrasi belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku KKN pada tubuh birokrasi. Hal yang lebih penting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku (manusianya). Dengan kata lain bahwa kontrol pribadi dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri setiap individu birokrat sangat berperan dalam membentuk perilakunya. Dengan adanya kontrol pribadi yang kuat pada diri setiap individu maka akan dapat mencegah munculnya niat untuk melakukan tindakantindakan mal-administrasi (penyelewengan). Menurut Keban (2001) Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki kedewasaan beretika. Di Amerika Serikat, misalnya, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah begitu meningkat sehingga banyak profesi pelayanan publik yang telah memiliki kode etik. Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik adalah kode etik yang dimiliki ASPA (American Society for Public Administration) yang telah direvisi berulang kali dan terus mendapat kritikan serta penyempurnaan dari para anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, memberi perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap sistem merit dan program affirmative action. 10. Pentingnya Etika Dalam Pelayanan Publik Saran klasik di tahun 1900 sampai 1929 untuk memisahkan antara administrasi dan politik (dikotomi) menunjukkan bahwa administrator harus sungguh-sungguh netral, bebas dari pengaruh politik ketika memberikan pelayanan publik. Akan tetapi kritik bermunculan menentang ajaran dikotomi administrasi – politik pada tahun 1930-an, sehingga perhatian mulai ditujukan kepada keterlibatan para administrator dalam keputusan-keputusan publik atau kebijakan publik. Sejak saat ini mata publik mulai memberikan perhatian khusus terhadap “permainan etika” yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan. Penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap kontribusinya terhadap public interest atau kepentingan umum (Henry, 1995). Alasan mendasar mengapa pelayanan publik harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki “tanggung jawab” atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan politik secara tepat mengenai siapa mendapat apa, berapa banyak, dimana, kapan, dsb. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki tuntunan atau pegangan kode etik atau moral secara memadai. Asumsi bahwa semua aparat pemerintah adalah pihak yang telah teruji pasti selalu membela kepentingan publik atau masyarakatnya, tidak selamanya benar. Banyak kasus membuktikan bahwa kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, partai dan bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang birokrat atau aparat pemerintahan. Birokrat dalam hal ini tidak memiliki “independensi” dalam bertindak etis, atau dengan kata lain, tidak ada “otonomi dalam beretika”. Alasan lain lebih berkenaan dengan lingkungan di dalam birokrasi yang memberikan pelayanan itu sendiri. Desakan untuk memberi perhatian kepada aspek kemanusiaan dalam organisasi (organizational humanism) telah disampaikan oleh Denhardt. Dalam literatur tentang aliran human relations dan human resources, telah dianjurkan agar manajer harus bersikap etis, yaitu memperlakukan manusia atau anggota organisasi secara manusiawi. Alasannnya adalah bahwa perhatian terhadap manusia (concern for people) dan pengembangannya sangat relevan dengan upaya peningkatan produktivitas, kepuasan dan pengembangan kelembagaan. Alasan berikutnya berkenaan dengan karakteristik masyarakat publik yang terkadang begitu variatif sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Mempekerjakan pegawai negeri dengan menggunakan prinsip “kesesuaian antara orang dengan pekerjaannya” merupakan prinsip yang perlu dipertanyakan secara etis, karena prinsip itu akan menghasilkan ketidak adilan, dimana calon yang dipekerjakan hanya berasal dari daerah tertentu yang relatif lebih maju. Kebijakan affirmative action dalam hal ini merupakan terobosan yang bernada etika karena akan memberi ruang yang lebih luas bagi kaum minoritas, miskin, tidak berdaya, dsb untuk menjadi pegawai atau menduduki posisi tertentu. Ini merupakan suatu pilihan moral (moral choice) yang diambil oleh seorang birokrat pemerintah berdasarkan prinsip justice –as –fairness sesuai pendapat John Rawls yaitu bahwa distribusi kekayaan, otoritas, dan kesempatan sosial akan terasa adil bila hasilnya memberikan kompensasi keuntungan kepada setiap orang, dan khususnya terhadap anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Kebijakan mengutamakan “putera daerah” merupakan salah satu contoh yang populer saat ini. Alasan penting lainnya adalah peluang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam pemberian pelayanan publik sangat besar. Pelayanan publik tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, atau dengan kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan nilai pemberian pelayanan itu sendiri maupun mengenai cara terbaik pemberian pelayanan publik itu sendiri. Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pemberi pelayanan publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan kepada “keleluasaan bertindak” (discretion). Dan keleluasaan inilah yang sering menjerumuskan pemberi pelayanan publik atau aparat pemerintah untuk bertindak tidak sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada. Dalam pemberian pelayanan publik khususnya di Indonesia, pelanggaran moral dan etika dapat diamati mulai dari proses kebijakan publik (pengusulan program, proyek, dan kegiatan yang tidak didasarkan atas kenyataan), desain organisasi pelayanan publik (pengaturan struktur, formalisasi, dispersi otoritas) yang sangat bias terhadap kepentingan tertentu, proses manajemen pelayanan publik yang penuh rekayasa dan kamuflase (mulai dari perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, SDM, informasi, dsb.), yang semuanya itu nampak dari sifat-sifat tidak transparan, tidak responsif, tidak akun, tidak adil, dsb. Tidak dapat disangkal, semua pelanggaran moral dan etika ini telah diungkapkan sebagai salah satu penyebab melemahnya pemerintahan Indonesia. Alasan utama yang menimbulkan tragedi tersebut sangat kompleks, mulai dari kelemahan aturan hukum dan perundang-undangan, sikap ental manusia, nilai-nilai sosial budaya yang kurang mendukung, sejarah dan latar belakang kenegaraan, globalisasi yang tak terkendali, sistim pemerintahan, kedewasaan dalam berpolitik, dsb. Bagi Indonesia, pembenahan moralitas yang terjadi selama ini masih sebatas lip service tidak menyentuh sungguh-sungguh substansi pembenahan moral itu sendiri. Karena itu pembenahan moral merupakan “beban besar” di masa mendatang dan apabila tidak diperhatikan secara serius maka proses “pembusukan” terus terjadi dan dapat berdampak pada disintegrasi bangsa. Dibutuhkan Kode Etik dalam pelayanan publik. Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti ahli hukum dan kedokteran sementara kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, etika moral Pancasila, bahkan sudah ada sumpah pegawai negeri yang diucapkan setiap apel bendera. Pendapat tersebut tidak salah, namun harus diakui bahwa ketiadaan kode etik ini telah memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengenyampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik itu sendiri lebih berfungsi sebagai alat kontrol langsung bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar ada, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Bahkan berdasarkan penilaian implementasi tersebut, kode etik tersebut kemudian dikembangkan atau direvisi agar selalu sesuai dengan tuntutan perubahan jaman. Kita mungkin perlu belajar dari negara lain yang sudah memiliki kedewasaan beretika. Di Amerika Serikat, misalnya, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah begitu meningkat sehingga banyak profesi pelayanan publik yang telah memiliki kode etik. Salah satu contoh yang relevan dengan pelayanan publik adalah kode etik yang dimiliki ASPA (American Society for Public Administration) yang telah direvisi berulang kali dan terus mendapat kritikan serta penyempurnaan dari para anggotanya. Nilai-nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, menaruh perhatian, keramahan, cepat tanggap, mengutamakan kepentingan publik diatas kepentingan lain, bekerja profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka dan transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, penggunaan keleluasaan untuk kepentingan publik, beri perlindungan terhadap informasi yang sepatutnya dirahasiakan, dukungan terhadap sistem merit dan program affirmative action. Dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia, seharusnya kita selalu memberi perhatian terhadap dilema diatas. Atau dengan kata lain, para pemberi pelayanan publik harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal, karena dapat digunakan sebagai penuntun tingkah lakunya. Akan tetapi normanorma tersebut juga terikat situasi sehingga menerima norma-norma tersebut sebaiknya tidak secara kaku. Bertindak seperti ini menunjukkan suatu kedewasaan dalam beretika. Dialog menuju konsensus dapat membantu memecahkan dilema tersebut. Kelemahan kita terletak pada ketiadaan atau terbatasnya kode etik. Demikian pula kebebasan dalam menguji dan mempertanyakan norma-norma moralitas yang berlaku belum ada, bahkan seringkali kaku terhadap norma-norma moralitas yang sudah ada tanpa melihat perubahan jaman. Kita juga masih membiarkan diri kita didikte oleh pihak luar sehingga belum terjadi otonomi beretika. Kadang-kadang, kita juga masih membiarkan diri kita untuk mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan konteks atau dimana kita bekerja atau berada. Mendahulukan orang atau suku sendiri merupakan tindakan tidak terpuji bila itu diterapkan dalam konteks organisasi publik yang menghendaki perlakuan yang sama kepada semua suku. Mungkin tindakan ini tepat dalam organisasi swasta, tapi tidak tepat dalam organisasi publik. Oleh karena itu, harus ada kedewasaan untuk melihat dimana kita berada dan tingkatan hirarki etika manakah yang paling tepat untuk diterapkan.