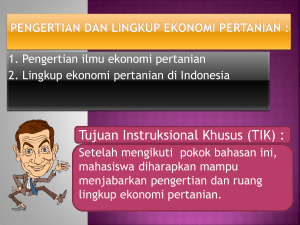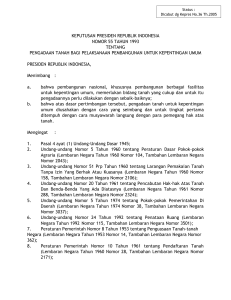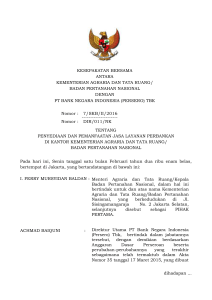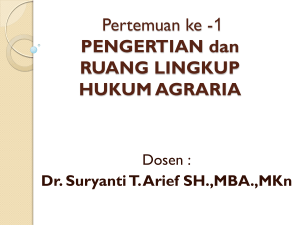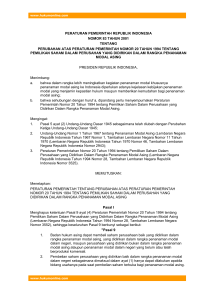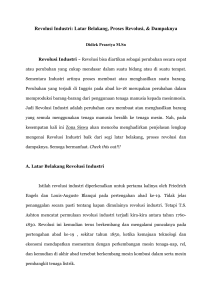bab ii tinjauan pustaka
advertisement

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Struktur Agraria: Dinamika Struktur Agraria Dulu dan Sekarang Secara kategoris, subyek agraria dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu komunitas (sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga), pemerintah (sebagai representasi negara) dan swasta (private sector). Ketiga kategori sosial tersebut adalah pemanfaat sumber-sumber agraria, yang memiliki ikatan dengan sumbersumber agraria melalui institusi penguasaan/pemilikan (tenure institution). Hubungan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan seperti sumber-sumber agraria menunjuk pada dimensi sosial dalam hubungan-hubungan agraria. Hubungan penguasaan/pemilikan/pemanfaatan membawa implikasi terbentuknya ragam hubungan sosial, sekaligus interaksi sosial, antara ketiga kategori subyek agraria.1 Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. Komunitas Sumber-sumber agraria Swasta Pemerintah Keterangan: hubungan teknis agraria (kerja) hubungan sosial agraria Gambar 1. Lingkup hubungan-hubungan agraria. 1 MT. Felix Sitorus. Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. 2002. Bandung: Yayasan Akatiga. Struktur agraria yang dapat dilihat ialah hubungan antara subyek dengan sumber-sumber agraria berkenaan dengan penguasaan lahan, pemilikan lahan dan pemanfaatan lahan. Menurut Sitorus (2002: 34-35) sumber-sumber agraria mencakup tanah, perairan, hutan, bahan tambang dan udara dalam bentangan wilayah. Sistem tenurial yang umum diterapkan petani jika dilihat dari segi penguasaan lahan ialah sistem bagi hasil (maro), sistem gadai, dan sistem sewa. Setiap sistem yang diterapkan memiliki latar belakang dan faktor yang berbedabeda, tergantung kepada “kondisi” yang dialami oleh petani pemilik dan petani penggarap (tunakisma). Mengenai pemilikkan tanah luas dan penyakapan menurut banyak pengamat disekitar abad ke-20, daerah Priangan menunjukkan suatu tuan tanah (penguasan tanah luas) yang luar biasa. Menurut Mindere Welvaart Onderzoek (MWO) dalam White dan Wiradi (1979: 17), kurang dari 6 persen dari pemilik tanah di Priangan telah menguasai hampir sepertiga dari seluruh tanah pertanian pada tahun 1905 (Haselman 1914: 37 dalam White dan Wiradi 1979: 17). Penimbunan penguasaan atas tanah-tanah luas oleh golongan tuan tanah ini tentunya bukannya melalui pemilikan, tetapi juga dengan cara penyewaan atau penggadaian yang memberikan suatu penguasaan de facto atas tanah. Mengenai angka-angka dalam MWO dalam White dan Wiradi (1979: 17) tentang proporsi pemilikan tanah yang telah menggadaikan tanah mereka, responden-responden MWO sendiri bersepakat bahwa jumlah sebenarnya adalah jauh di atas angkaangka tersebut. Pada tahun 1919, Meyer Ranneft dalam White dan Wiradi (1979: 17) menafsirkan bahwa sekitar sepertiga dari semua sawah kesikepan di Cirebon sudah tidak dikuasai lagi oleh pemiliknya, karena sudah digadaikan atau disewakan untuk jangka waktu yang lama (Arsip Nasional 1974: 21 dalam White dan Wiradi 1979: 17). Di daerah Sumedang, Garut, Cirebon dan Majalengka, golongan tuan tanah kebanyakan terdiri dari haji-haji, kepala-kepala desa dan tokoh-tokoh pribumi lainnya, sedangkan di Indramayu terdapat pula cukup banyak tuan-tuan tanah Tionghoa. Semua daerah tersebut di atas, penguasaan tanah-tanah luas dinyatakan meningkat selama periode 1880-1905 (MWO, Economie van de Desa, Preanger Regentschappen 1907: 13-18; Residentie Cirebon 1907: 13-14 dalam White dan Wiradi 1979: 17). Penyebab proses konsentrasi penguasaan tanah adalah semua sumber menghubungkannya dengan proses komersialisasi ekonomi pedesaan dan terutama dengan meningkatnya pinjaman uang, yang oleh Meyer Ranneft dilukiskan sebagai “suatu gejala khas dari masuknya lalu lintas uang ke dalam rumah tangga ekonomi petani, dan dari kekuasaan uang yang bagaikan setan” (Arsip Nasional 1974: 21 dalam White dan Wiradi 1979: 18). Perlu dicatat bahwa timbulnya golongan pemilik tanah luas sebagai akibat komersialisasi tidak disertai oleh timbulnya suatu golongan petani luas. Menurut Ploegsma, “Pemilikan tanah luas tentu tidak mengakibatkan usaha-usaha tani luas. Tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan pemilik luas disewakan atau dibagi hasilkan kepada penggarap-penggarap lain; dengan demikian, dari segi ekonomi pertanian, pola usahatani kecil-kecilan tetap bertahan” (Ploegsma 1936: 61 dalam White dan Wiradi 1979: 18). Nampaknya konsentrasi pemilikan bukanlah disertai oleh konsentrasi luas usahatani melainkan oleh suatu tingkat penyakapan yang tinggi dimana sejumlah besar petani bukan pemilik, yang masing-masing diberikan usahatani kecil atas dasar sewa atau bagi hasil. Pada permulaan abad ke-20, tingkat penyakapan di daerah Priangan termasuk diantara yang tertinggi di Jawa, sedangkan di Cirebon sedikit dibawah rata-rata (Scheltema 1931: 271 dalam White dan Wiradi 1979: 18). White dan Wiradi (1979: 19-20) menyatakan bahwa “bukanlah pola-pola penguasaan tanah merupakan hal yang statis yang tidak pernah berubah selama satu abad terakhir. Justru sebaliknya, perbandingan masa kini dan masa lalu menunjukan adanya suatu proses perubahan yang sangat dinamis, dan lagi bahwa masing-masing daerah mempunyai dinamika sendiri”. Namun demikian, agaknya penting untuk mengartikan bahwa pola-pola yang kelihatan sekarang, seperti variasi lokal dalam luas tanah bengkok, ketunakismaan, ketidakmerataan diantara pemilik tanah, timbulnya suatu golongan pemilik tanah luas, bertahannya pola usahtani kecil-kecilan berkat lembaga penyakapan, dan sebagainya. Semuanya merupakan akibat dari suatu proses dinamika yang telah dimulai pada zaman nenek moyang kita, sehingga benar-benar disebut sebagai warisan sejarah. Kegiatan sewa dan sakap ini berkembang dengan baik melalui instrumen kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap, umumnya penyewaan dan atau penyakapan didasarkan pada alasan ekonomi untuk meningkatkan usahanya. Menurut Shanin (1971) dalam Subali (2005), terdapat empat karakteristik utama petani. Pertama, petani adalah pelaku ekonomi yang berpusat pada usaha milik keluarga. Kedua, menggantungkan kehidupan mereka kepada lahan. Bagi petani, lahan pertanian adalah segalanya. Lahan dijadikan sebagai sumber yang diandalkan untuk menghasilkan bahan pangan keluarga, harta benda yang lebih tinggi, dan ukuran terpenting bagi status sosial. Ketiga, petani memiliki budaya yang spesifik yang menekankan pemeliharaan tradisi dan konformitas serta solidaritas sosial. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya keterbukaan petani berlahan luas untuk mempekerjakan petani yang tidak memiliki lahan atau berlahan sempit. Semua itu didorong oleh rasa solidaritas diantara sesama petani. Keempat, petani cenderung sebagai pihak yang tersubordinasi namun tidak dengan mudah ditaklukkan oleh kekuatan ekonomi, budaya dan politik eksternal yang mendominasi mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Husken (1998) di Desa Gondosari, Pati, Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan mengenai ciri-ciri petani di Indonesia pada saat ini. Menurut dia, ciri yang pertama adalah bahwa petani bermata pencaharian ganda, selain bertani mereka juga memiliki pekerjaan sampingan, seperti pedagang, buruh, supir. Melihat kenyataan dilapangan, pekerjaan sampingan tersebut ternyata merupakan pekerjaan pokoknya Ciri kedua, tanaman yang diproduksi petani ialah tanaman yang tidak berisiko tinggi, artinya teknologinya dapat dengan mudah dikuasai, misalnya tanaman talas, pisang, dan umbi-umbian. Pertimbangan lainnya ialah petani paham ke mana pasar bagi tanaman yang diusahakan serta menguntungkan secara ekonomi. Ciri ketiga, motif berusaha petani ialah mencari keuntungan yang dilakukan dengan mengintensifkan penggunaan lahan yang hasilnya akan dijual untuk mendapatkan uang tunai. Ciri keempat petani ialah bagian dari sistem politik yang lebih besar yang ditunjukkan oleh adanya partai-partai politik yang berpengaruh pada mereka juga terhadap kepemimpinan di desa. Adapun ciri yang terakhir adalah bahwa petani subsisten secara mutlak tidak ada, karena petani mempunyai hubungan yang kuat terhadap pasar tempat menjual hasil pertaniannya atau bahkan membeli barang di pasar untuk dijual di desanya dengan harapan memperoleh keuntungan. Menurut Elizabeth (2007: 30) penerapan paradigma modernisasi yang mengutamakan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat petani di pedesaan. Berbagai proses pelaksanaan pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian, pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta struktur pendapatan petani di pedesaan. Terkait dengan struktur pemilikan lahan, perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya: (1) petani lapisan atas; merupakan petani yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik, serta memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan; dan (2) petani lapisan bawah; sebagai golongan mayoritas di pedesaan yang merupakan petani yang relatif miskin (dari segi lahan dan kapital), hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan berproduksi, kedua lapisan masyarakat petani tersebut terlibat dalam hubungan kerja yang kurang seimbang. Sayogyo (2002: 133), bahwa …“Studi hubungan antara pola distribusi tanah dan distribusi pendapatan (diantara petani dan buruh tani pada khususnya) dalam Studi Dinamika Pedesaan SAE itu boleh dikata merupakan uji-ulang di banyak desa atas suatu temuan pokok dari studi desa kasus Yogyakarta, yang pernah dilakukan B.White sebelum tahun 1970. Hasil studi itu menemukan perbedaan strategi pola nafkah. Rumah tangga di lapisan bawah (petani gurem, buruh tani) berpola “aman dan selamatkan diri”, dilapisan di atasnya berpola “konsilidasi”, dan baru di lapisan paling atas (tanah cukup, juga peluang usaha di luar pertanian) berpola “akumulasi modal”. 2.2 Bidang Kegiatan Pertanian Sawah: Strategi Pemilik Lahan Sistem gadai hanya akan dilakukan pemilik sawah dalam keadaan yang sangat terpaksa. Tentang kontrak maro jika pemilik lahan adalah seorang ayah, maka kontrak maro dilakukan oleh seorang anak atas alasan-alasan hubungan kekerabatan, pertama untuk membantu rumah tangga ekonomi rumah tangga anak tersebut. Kedua adalah untuk mendidik anak dalam mengelola pekerjaan di sawah. Pada suatu hari dipertimbangkan sawah yang dipatronkan itu akan jatuh kepada anak tersebut sebagai warisan orang tua. Penggunaan buruh tani dari sudut pandang pemilik sawah adalah akibat pasokan buruh yang melimpah, maka tingkat upah buruh sangat bersaing. Situasi seperti ini beserta tekanan moral pedesaan untuk membantu tetangga dan hidup rukun dengan tetangga mendorong pemilik lahan untuk tidak mencari tenaga buruh dari luar kampung sendiri. Kalau kita lama hidup dalam sebuah kampung akan terasa aneh jika terjadi seorang pemilik sawah menyewa buruh tani dari kampung lain. Hal yang serupa juga terjadi dengan persewaan kerbau untuk pekerjaan membajak dan menggaru, bahkan untuk sawah-sawah yang terletak di luar kampung sendiri, para pemilik lahan tetap akan mempekerjakan para buruh yang dibawa dari kampung sendiri. Pada situasi melimpahnya buruh tani tunakisma yang mencari kerja di sawah dan meluasnya kemiskinan, pekerjaan berupah adalah semacam sesuatu yang diidam-idamkan dan memberi pekerjaan semacam itu kepada seseorang dapat dipandang sebagai sebuah kemurahan hati. Memberikan pekerjaan kepada tetangga adalah semacam pembayaran premi asuransi bagi keamanan hidup sang pemilik lahan. Dengan berbuat demikian, mereka berharap buruh tani yang mereka tolong itu akan menolong mereka pula nanti jika bila diperlukan. Masyarakat desa berpendapat bahwa hanya tetanggalah yang akan segera datang menolong mereka ketika mendapat kesusahan. Kerabat yang tinggal di kampung lain secara teknis susah untuk menolong, karena jarak tempat tinggal yang jauh. Di kampung-kampung sisi dimana lembaga formal tidak ada dalam sebagian besar orang bergantung kepada tetangga. Inilah alasan utama mengapa muncul situasi umum di pedesaan Cikalong, dan di Jawa umumnya, bahwa “The villagers place importance upon lending immediate assistance to people living nearby” (Jay 1969: 237 dalam Marzali 2003: 108). Memberikan pekerjaan dengan upah kepada seorang buruh lepas sebagai satu kemurahan hati diberikan secara terbatas. Apabila tenaga kerja keluarga di rumah tidak cukup, maka bantuan tenaga dari luar dicari pertama dari kalangan kerabat dekat, yaitu anak menantu dan saudara yang tinggal di kampung yang sama. Selain itu dari kalangan tetangga dekat. Biasanya untuk pekerjaanpekerjaan yang kecil seperti memacul waktu mempersiapkan lahan, caplak, dan menyiang, tenaga kerja dari kedua golongan ini sudah mencukupi. Hal ini juga nampaknya berlaku di tempat-tempat lain di Jawa (Marzali 2003: 108). Di luar kedua golongan di atas barulah tenaga buruh bebas diambil dari kalangan “orang lain”, yaitu orang sedesa yang bukan tetangga atau orang dari desa lain. 2.3 Kaitan Faktor Penguasaan Tanah Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat Pedesaan Hasil penelitian Amaluddin (1987) sebagaimana dikutip Syahyuti (2001) di Kendal Jawa Tengah untuk memahami kondisi pada zaman Orde Lama bahwa “perubahan sistem penguasaa tanah juga telah menyebabkan perubahan sistem produksi pertanian”. Sebelum tahun 1960, ada tiga jenis hak penguasaan tanah komunal, yaitu hak bengkok, hak banda desa, hak narawita, serta satu yang bersifat individual yaitu hak yasan. Saat itu, tanah yasan mencakup 76,7 persen dari total tanah di desa tersebut. Penerapan UUPA tahun 1960 menyebabkan konversi tanah yang semula berdasarkan hukum adat (komunal) menjadi hak milik. Hak narawita, secara de facto sudah menjadi milik individual, sehingga penjualan tanah berkembang, peluang tunakisma untuk menggarap mengecil, dan mobilitas penguasaan cenderung sentrifugal atau terpolarisasi. Bersamaan dengan itu, sistem produksi yang semula dilandasi nilai-nilai tradisional digantikan oleh sistem produksi komersial. Organisasi produksi dari sebelumnya berupa pola-pola penyakapan seperti maro, merapat, merlimo, lebotan, bawon, dan mutu digantikan dengan pola dengan penyewaan, buruh lepas, panen tebasan, dan penggilingan padi mekanis. Temuan ini didukung oleh Hayami dan Kikuchi (1987) dalam Syahyuti (2001), yang menemukan bahwa “Kesamaan dampak revolusi hijau di Indonesia dan Filipina”. Tranformasi sistem sosial pedesaan ini juga didukung oleh Temple (1976) dalam Syahyuti (2001) melihat bahwa “Adanya evolusi desa Jawa dari desa komunal (1830-1870), dilanjutkan desa tradisional (1870-1959), dan terakhir desa komersial bersamaan dengan era revolusi hijau”. Selanjutnya Amaluddin (1987) dalam Syahyuti (2001) melihat bahwa “Komersialisasi pertanian telah juga menyebabkan perubahan pola hubungan antar lapisan petani”. Kondisi sebelum tahun 1960 dimana masyarakat terbagi atas tiga lapisan sosial, yaitu sarekat (pemegang hak bengkok), sikep ngajeng (pemegang hak narawita) dan sikep wingking (tunakisma) dilandasi hubungan “patron–klien”; berubah menjadi hubungan berdasarkan nilai-nilai komersial pola tuan tanah–buruh. “Melemahnya hubungan patron klien ini bersamaan dengan menurunnya tanggung jawab lembaga desa dalam menjamin subsistensi, melalui jaminan memperoleh pekerjaan dan distribusi” (Temple, 1976 dalam Syahyuti, 2001). Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makan manusia. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah jang menghidupi segenap manusia (Tauchid, 1952: 3). Tanah merupakan faktor produksi utama dalam usaha perkebunan. Tanah diperlukan sebagai tempat tumbuh komoditi-komoditi yang akan diusahakan. Indonesia sebagai Negara Agraris, memiliki tanah subur yang sangat mendukung bagi berkembangnya usaha perkebunan maupun pertanian pada umumnya. Faktor tanah yang kaya inilah, disamping faktor tersedianya penduduk sebagai tenaga kerja, yang dahulu menarik kaum penjajah untuk menguasai tanah di Indonesia (Mubyarto, 1992: 107). Penguasaan lahan atau tanah dan kepemilikan lahan atau tanah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut Wiradi (2008) bahwa konsep antara kepemilikan, dan pengusahaan tanah perlu dibedakan. Kata “pemilikan” menunjuk pada penguasaan formal. Hak milik atas tanah berkaitan dengan hakhak yang dimiliki seseorang atas tanah, yakni hak yang sah untuk menggunakannya, mengolahnya, menjualnya dan memanfaatkan bagian-bagian tertentu dari permukaan tanah. Hal tersebut menyebabkan pemilikan atas tanah tidak hanya mengenai hak milik saja melainkan juga termasuk hak guna atas tanah yaitu suatu hak untuk memperoleh hasil dari tanah bukan miliknya dengan cara menyewa, menggarap dan lain sebagainya. Kemudian bagaimanakah keadaan diferensiasi luas pemilikan tanah? Ini harus diteliti dengan wawancara langsung dengan penduduk desa. Yang harus diperjelas ialah bukan “pemilikan tanah” dalam arti hak milik yang hanya tercatat dibuku resmi (Buku Letter C), melainkan luas tanah yang benar-benar dikuasai oleh masing-masing keluarga petani (Tjondronegoro dan Wiradi, 1984: 239). Menurut Mubyarto (1992: 107) bahwa …”Tersedianya tanah ternyata tidak selalu diimbangi oleh tersedianya tenaga kerja. Tuntutan akan tenaga kerja telah menempatkan kebijaksanaan dalam distribusi pemanfaatan lahan kepada segenap warga desa. Prinsip ini merupakan kosekuensi atas tuntutan pada upaya memperoleh tenaga kerja dan untuk memperoleh ikatan penduduk dengan desanya”. Bagaimanakah cara pengusahaan tanah yang dimiliki masing-masing rumah tangga? Dengan tenaga buruh tani atau hanya tenaga keluarga sendiri? Kalau digarap orang lain, jenis kontrak penggarapnya bagaimana, sewa-menyewa atau bagi hasil? Dan bagaimanakah hubungan pemilik tanah dengan penggarapnya? (Tjondronegoro dan Wiradi, 1984: 239) 2.4 Usahatani Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu, alam, tenaga kerja, modal dan pengelola yang diusahakan oleh perseorangan ataupun sekumpulan orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen (Soeharjo dan Patong, 1973). Strategi berasal dari kata Yunani Strategos dan Strategia, istilah strategi yang dipakai berarti pengetahuan dan seni menangani sumber-sumber yang tersedia dari suatu perusahaan (petani lapisan atas) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan (petani lapisan atas) dalam jumlah yang besar. Petani lapisan atas merupakan petani yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik, serta memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan (Elizabeth, 2007: 30). Pengelolaan atau manajemen usahatani adalah kemampuan petani dalam menentukan, mengorganisir dan mengkordinasikan faktor-faktor produksi yang dikuasai dengan sebaik mungkin sehingga mampu memberikan produksi pertanian yang diharapkan. Faktor-faktor produksi yang dikelola oleh petani adalah: lahan atau tanah garapan, alokasi penggunaan tenaga kerja, modal, dan kegiatan usahatani padi sawah. Tenaga kerja dalam usahatani sangat diperlukan dan berpengaruh terhadap penyelesaian berbagai macam kegiatan produksi usahatani. Jenis tenaga kerja dibagi menjadi tiga yaitu: tenaga kerja manusia, hewan, dan mesin. Tenaga kerja yang menjadi faktor produksi dalam penelitian ini adalah tenaga kerja manusia. Modal adalah barang atau uang yang secara bersama-sama dengan faktor produksi lain digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu produk pertanian. Sumber modal diperoleh dari; milik sendiri, pinjaman, kredit, hadiah, warisan, usaha lain atau kontrak sewa. 2.5 Kerangka Pemikiran Kajian utama diarahkan pada proses akumulasi modal petani lapisan atas. Proses akumulasi modal melalui mekanisme dan investasi surplus dari pemilik lahan tradisional, pemilik lahan modern dan pemilik lahan entrepreneur. Adapun fokus kajian peran petani lapisan atas di dalam pembangunan pedesaan pada sumberdaya dan lapangan kerja, transfer teknologi dan kelembagaan. Kerangka pemikiran pada tujuan yang ingin dicapai secara sederhana diwujudkan pada Gambar 2. Proses Akumulasi Modal: 1. Pemilik Lahan Tradisional 2. Pemilik Lahan Modern 3. Pemilik Lahan Entrepreneur Peran Petani Lapisan Atas di Pedesaan: 1. Sumberdaya dan Lapangan Kerja 2. Tranfer Teknologi 3. Kelembagaan Strategi Ekonomi Petani Lapisan Atas dalam Mengakumulasi Modal: Tipe Petani Lapisan Atas di Desa Ciasmara Keterangan: Mempengaruhi Berhubungan Gambar 2. Kerangka Pemikiran. 2.6 Hipotesis Pengarah Berdasarkan rangkaian konsep yang diutarakan serta wawasan peneliti terhadap subjek tineliti, beberapa pernyataan hipotesis yang mengarahkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian disusun di bawah ini. Beberapa hipotesis pengarah itu adalah: 1. Proses akumulasi modal melalui mekanisme surplus dan investasi surplus berupa persediaan alat-alat produksi, reproduksi dan produksi, dan bidang sirkulasi atau pertukaran uang dari rumah tangga petani lapisan atas dimana surplus di sektor pertanian diinvestasikan ke sektor non pertanian. Proses akumulasi dan investasi yang saling menunjang dari sektor pertanian ke sektor non pertanian diantara petani lapisan atas di pedesaan maka terjadi akumulasi modal. 2. Petani lapisan atas memiliki peran di dalam pembangunan pedesaan. 3. Proses akumulasi modal dan peran petani lapisan atas dapat menjelaskan strategi ekonomi petani lapisan atas dalam mengakumulasi modal. 2.7 Definisi Konseptual 1. Strategi adalah tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumberdaya perusahaan (petani lapisan atas) dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi mempengaruhi kemakmuran perusahaan (petani lapisan atas) dalam jangka panjang. 2. Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu, alam, tenaga kerja, modal dan pengelola yang diusahakan oleh perseorangan ataupun sekumpulan orang (petani lapisan atas) untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen (pasar). 3. Petani lapisan atas adalah petani yang akses pada sumberdaya lahan, kapital, mampu merespon teknologi dan pasar dengan baik, serta memiliki peluang berproduksi yang berorientasi keuntungan. 4. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. 5. Tanah adalah asal dan sumber makan manusia serta tempat tumbuh komoditi-komoditi yang akan diusahakan. 6. Modal adalah barang atau uang yang secara bersama-sama dengan faktor produksi lain digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, yaitu produk pertanian. 7. Pemilik lahan tradisional adalah petani yang mempunyai lahan sawah yang luas menggunakan sistem pertanian yang masih sederhana. 8. Pemilik lahan modern adalah petani yang mempunyai lahan sawah yang luas menggunakan sistem pertanian yang maju. 9. Pemilik lahan entrepreneur adalah petani yang mempunyai lahan sawah yang luas dan juga memiliki profesi sebagai pedagang. 10. lapangan kerja adalah kegiatan seorang petani untuk dapat bekerja agar terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga melalui pekerjaan di sektor pertanian maupun sektor non pertanian. 11. Tranfer teknologi adalah memberi penerapan ilmu pengetahuan sebagai solusi bagi masalah-masalah praktis. 12. Kelembagaan adalah kompleks peraturan-peraturan dan peran sosial yang mempengaruhi perilaku orang-orang di sekitar pemenuhan kebutuhankebutuhan penting. 13. Akumulasi modal adalah penjumlahan dari seluruh aset atau kekayaan yang dimiliki rumah tangga petani dari sektor pertanian maupun sektor non pertanian. 14. Wirausahawan (Entrepreneur) didefinisikan sebagai seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya, dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru.