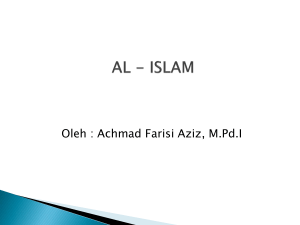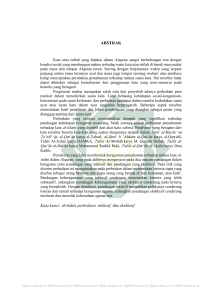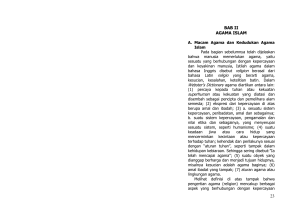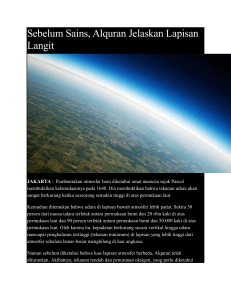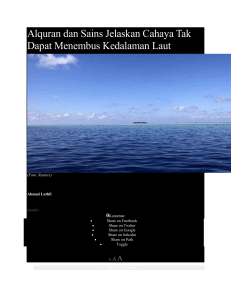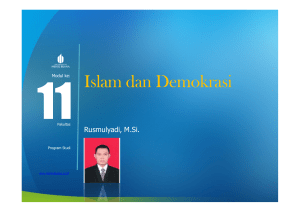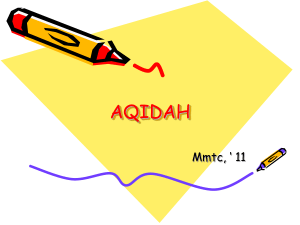PLURALITAS AGAMA (Suatu Tinjauan Teologi Sosial) Ahmad
advertisement

PLURALITAS AGAMA (Suatu Tinjauan Teologi Sosial) Ahmad Mujahid1 Abstract: To face the globalization era, Muslim need theology basis which is strong. Theology term is to help enrich the muslim knowleadge of Islam. In the thought of Islam theology, means knowleadge which is content in relation beetwen God and the universe. Later, The draft formulation of this, are; How is the book theology in relation of book and religion pluralims? To focus to this formulation, it will be presented many questions, namely: First, How is the theology of consept in the book perspective? The Second, as a book guideline, how is theology implication toward the pluralism religion? Then this writing shows that theology (tauhid) is human awareness on thier believer toward the one god which cover it’s one of essence, action, atribute (characteristic). The unity of god essence is a furitification towards God. Yet, The fluralism is to be still unitied with strong bound, namely bound of essence of God. Key Words: Theology Social, Fluralims, Religion Pendahuluan Era globalisasi adalah era gerakan penyatuan peradaban manusia tidak dapat dihindarkan berkat kemajuan teknologi komunikasi-informasi dan transfortasi. Oleh karena itu, pembauran peradaban di antara umat manusia tidak dapat dibendung dengan cara apapun. Kemestian peradaban yang demikian, seyogyanya melahirkan kemestian landasan rohaniah yang kokoh, untuk secara positif mempertahankan identitas dan memantapkan pandangan pluralitas agama, multikultural dan egalitarian yang juga merupakan kemestian alami. Dari sini ini dapat dikatakan bahwa, menghadapi era globalisasi ini, umat Islam memerlukan landasan teologis yang kukuh, demi untuk mempertahankan identitas keislaman mereka dan untuk menghadapi secara positif pembauran peradaban dan budaya dan atau pluralitasmultikultural. Istilah teologi bukan merupakan khasanah dan tradisi Islam, tetapi khasanah dan tradisi yang berasal dari Agama Kristen. Penggunaan suatu istilah yang berasal dari 1 Kandidat Doktor bidang Tafsir. Dosen Pengajar bidang Agama Islam di Universitas hasanuddin (UNHAS) Makassar. E-mail: [email protected]. agama lain terhadap Islam tidak serta merta mengandung makna negatif, apalagi jika istilah tersebut bisa memperkaya khazanah dan membantu mensistematiskan pemahaman kita terhadap Islam. Kata “teologi” sebagaimana dijelaskan dalam Encyclopaedia of Religion and Religions berarti ilmu yang membicarakan tentang Tuhan dan hubungan-Nya dengan alam semesta, namun seringkali diperluas mencakup keseluruhan bidang agama. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan pemikiran teologi Islam. Pada awal perkembangan pemikiran Islam, istilah “teologi” hanya dilekatkan pada pemikiran tentang ketuhanan yang lebih dikenal dengan istilah ilmu kalam. Tampaknya pembahasan ilmu kalam ini, cenderung melahirkan perdebatan teologis yang tidak pernah tuntas. Misalnya perdebatan antara pemahaman teologi Jabariah dan Qadariah, teologi Mu’tazilah dengan Asy’ariah. Teologi Mu’tazilah-Qadariah memberikan peranan penting dan kuat kepada manusia dan cenderung menyangkal peranan Tuhan agar manusia benar-benar bertanggung jawab. Pada sisi lain kalangan Jabariah-Asy’ariah, menganggap manusia tidak memiliki kekuasaan agar Allah tetap sebagai yang Maha Kuasa. wacana teologis tersebut menjadi pemicu munculnya konflik sosial-politik, seperti peristiwa mihnah. Subtansi perdebatan teologisnya berkisar pada apakah Alquran itu makhluk atau bukan? Apakah al-Qur’an itu qadim ataukah jadid? Peristiwa mihnah ini telah menciptakan kekerasan terhadap kebebasan intelektual manusia yang terhingga dan kemanusiaannya, khususnya terhadap penganut teologi Asy’ariyah pada masa Khalifah Abbasiyah. Berangkat dari fenomena teologis di atas, menarik untuk dikemukakan ramalan Thomas Jefferson, -seorang penyusun Deklarasi Amerika yang tidak percaya pada agama formal (Kristen pada saat itu)- yaitu bahwa agama-agama formal akan hancur dalam satu-dua abad dan akan digantikan oleh pandangan yang dianutnya yaitu citacita kebebasan beragama, pluralisme dan egalitarianisme (yang ia jadikan sebagai citacita Barat tentang negara dan masyarakat) yang ia kemudian namakan agama kemanusiaan masa depan.2 2 Nurcholish Majid, Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 134. Di negara maju, terdapat gejala sekelompok orang yang memiliki komitmen positif pada masalah sosial, tanpa memperdulikan pada keyakinannya. Fraseologinya adalah kesalehan tanpa iman (piety without faith).3 Helmut Schmidr, bekas Kansiler Jerman (Barat) dan dekan (dean) gerakan sosial-demokrat Eropa, dalam kunjungannya ke Indonesia, dengan tegas ia berkata; agama, menurut pengalaman Eropa adalah musuh nomor satu demokrasi, pluralisme dan egalitarianisme. Schmidr mengatakan; Eropa Barat ingin menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dahulu menyudahi peran agama dalam politik. Pengakuan Schmidr ini sangat mengagumi pancasila, namun ia sangat ingin tahu bagaimana merekonsiliasi sila pertama (yang menurutnya adalah agama) dengan sila keempat (yang menurutnya adalah demokrasi).4 Dari uraian di atas, diajukan rumusan sebagai pokok masalah, yaitu: Bagaimana peran tauhid sebagai inti teologi Qurani dalam hubungannya dengan pluralitas agama? Untuk mempertajam rumusan masalah tersebut maka dapat diajukan pertayaan-pertayaan berikut: Pertama, bagaimana konsep tauhid dalam Alquran? Kedua, bagaimana implikasi tauhid terhadap pluralitas agama sebagaimana petunjuk Alquran? Tauhid Sebagai Teologi Qurani Istilah tauhid tidak ditemukan dalam al-qur’an. Kata ini adalah bentuk masdar dari kata kerja transitif yaitu wahhada-yuwahhidu yang berarti mengesakan atau menyatukan. Istilah tauhid ini digunakan dalam ilmu kalam oleh kelompok mutakallim (ahli teologi) untuk mengesakan Tuhan (monoteisme). Penggunaan istilah tauhid ini, oleh kaum mutakallimin secara tepat menggambarkan inti ajaran al-qur’an, bahkan inti ajaran seluruh nabi dan rasul Allah. Meskipun kata tauhid, tidak digunakan dalam al-Qur’an, namun yang ditemukan adalah istilah ahad, wahda dan Mengenai pemikiran tentang Faith without Religion, lebih lanjut lihat Kamaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 89-100. 3 4 Nurcholish, Tradisi Islam…, h. 134-135. wahid. 5 Istilah pertama ditemukan dalam QS. al-Ikhlas (112):1-4. Istilah kedua diantaranya ditemukan dalam QS. Ghafir (40):84. Istilah ketiga digunakan dalam QS. al-Baqarah (2):163. Sebagaimana dipahami pembahasan tentang tauhid relevan dengan pembahasan mengenai Tuhan dan dalam hubungannya dengan manusia dan alam raya, karena itu dalam pembahasan ini, penulis ingin tegaskan, bahwa tulisan ini murni pengkajian tentang Tuhan dalam Alquran sebagai sorotan utama tauhid dan kemudian dihubungan dengan problematika kemanusian, seperti wacana pluralitas dan multikultural. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perdebatan teologis yang sangat pelit dan rumit, ketika mengemukakan bukti-bukti teologis mengenai eksistensi Tuhan. Oleh karena itu, kami akan biarkan Alquran berbicara sendiri; sedang penafsiran hanya akan digunakan dengan membuat hubungan antara konsepkonsep yang berbeda. Tuhan pertama kali memperkenalkan diri-Nya kepada manusia, ketika manusia masih berupa janin dalam rahim ibunya. Hal ini, dipahami dari dialog Tuhan dengan setiap janin yang ada dalam rahim ibunya, sebagaimana dikemukakan dalam Q.S. alA’raf (7):172; و إذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علي انفسهم ألست بربكم قلوا بلي شهدنا ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذذا غفلين Artinya: Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (Allah berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini ( keesaan Tuhan).” 5 Menurut Quraish Shihab, walaupun kata ahad terambil dari kata wahdah sebagaimana kata wahid, namun dari segi bahasa, kata ahad, walaupun memiliki akar kata yang sama dengan kata wahid, namun masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendir. Kata ahad hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan, baik dalam benak maupun dalam kenyataan. Kerena itu kata ini jika berfungsi sebagi sifat tidak termasuk dalam rentetan bilangan, berbeda hal dengan kata wahid yang dapat menambahnya sehingga menjadi dua, tiga dan seterusnya. Lihat Quraish Shihab, Tafsir Al-Quranul Karim, Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan turunnya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), h. 667-668. Secara global ayat di atas, mengemukakan perjanjian primordial antara Tuhan dengan manusia sejak mereka masih dalam rahim ibunya. Perjanjian yang dimaksud adalah adanya pengakuan manusia bahwa Allah adalah rabb, setelah mereka ditanya oleh Allah “alastu birabbikum? ‘Bukankah saya Rabbmu?’. Tujuan perjanjian ini adalah, agar manusia kelak, tidak berdalil bahwa yang demikian itu, tidak pernah disampaikan kepada mereka dan tidak berdalil bahwa orang tua mereka telah melakukan kemusyrikan sejak dahulu dan merekalah yang dijadikan ikutan. Dari konteks ayat tersebut diketahui bahwa, istilah pertama yang Allah gunakan untuk memperkenalkan diri-Nya kepada manusia adalah rabb. Istilah rabb, pada ayat di atas, dua kali disebutkan. Secara etimologis kata rabb berakar kata dengan huruf ‘ra’ dan huruf ‘ba’ yang berganda dengan makna memperbaiki dan memelihara sesuatu, melazimi, dan menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. 6 Dari makna tersebut, diperoleh bentuk kata rabb yang berarti pemilik, pencipta, yang memberi kebajikan kepada sesuatu, pemelihara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Tuhan dikatakan rabb karena Dia yang menciptakan, yang memelihara dan mendidik, mengatur dan yang memberi kebajikan. Jadi makna klausa alastu birabbikum dalam ayat di atas adalah bukankah Aku penciptamu, pengaturmu, pemeliharamu dan pendidikmu serta pemberi kebajikan padamu? Setiap janin (yang bakal jadi manusia) pun memberi pengakuan terhadap Allah sebagai rabb. Dari sisi ini, dapat ditegaskan bahwa, istilah rabb merupakan istilah yang sangat fungsional dalam kaitannya dengan Allah sebagai rabb dan manusia serta alam raya sebagai makhluk. Oleh karena itu, penerjemahan istilah rabb dalam arti Tuhan (dalam bahasa Indonesia) dan God (dalam bahasa Inggeris) tidak terlalu tepat. Dikatakan demikian, karena istilah Tuhan dan atau God mendistorsi makna kata rabb. Menarik untuk dikemukakan bahwa ayat tersebut, dengan tegas menjelaskan pengakuan manusia terhadap tauhid rububiyah. Tauhid ini sudah menjadi kesadaran bawaan setiap anak manusia sejak lahirnya dan sekaligus menjadi negasi terhadap syirik rububiyah. Pernyataan terakhir ini dipahami dari munasabah ayat 172 di atas dengan kandungan ayat 173 dalam surah yang sama. Dimana ayat 173 menegaskan, 6Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu’jam Maqayis al-Lughat, (Misrh, Dar al-Fikr, 1979), h. 381-382. alasan mengapa perjanjian itu ditetapkan, yaitu agar anak manusia tidak beralasan bahwa orang-orang tua mereka sejak dulu telah mensyarikatkan Allah, yang kemudian dijadikan ikutan mereka. Pengenalan diri Allah lewat kata rabb, lebih lanjut dapat dilihat dari wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad saw., yaitu; Q.S. al-Alaq (96): 1-5: اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق األنسان من علق اقرأ و ربك األكرم الذي علم با لقلم علم األنسان ما لم يعلم Kandungan ayat ini menginformasikan perintah membaca (dan atau semua aktifitas) dengan menyandarkan diri kepada Rabb (yaitu Allah) yang menciptakan. Menciptakan manusia dari ‘alaq. Bacalah dan Rabb-mu Maha Mulia. Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia adalah Rabb yang mengajari manusia lewat qalam dan mengajari manusia apa yang ia tidak ketahui. Pada ayat tersebut kata rabb dua kali dikemukakan. Pertama kata rabb digandengan dengan kata khalaqa “yang menciptakan’ dan kata rabb yang kedua dibarengi dengan kata al-Akram dan kata allama. Struktur bahasa yang demikian, menunjukkan bahwa kata rabb memiliki hubungan yang sangat erat dengan perbuatan mencipta, kemuliaan dan pengajaran (ta’lim). Sisi ini, dapat dikatakan bahwa rububiyah Allah diaktuskan dalam bentuk penciptaan, pada sifat kemulian dan pemberian pengajaran. Pemaknaan yang demikian sangat logis, karena makna tersebut inklud dalam makna kata rabb, seperti dikemukakan di atas. Uraian di atas, menunjukkan bahwa Allah memperkenalkan diri-Nya untuk pertama kalinya kepada Muhammad saw kepada manusia seluruhnya, lewat perbuatan-Nya dan sifat kelembutan-Nya, atau lewat tauhid af’al-Nya dan tauhid sifat-Nya. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa salah satu cara yang dapat digunakan dalam melakukan pengenalan kepada Allah adalah lewat kreatifitas-Nya yang penuh dengan kelembutan. Hal ini perlu ditegaskan, untuk menegasikan pandangan sebagaian orang, khususnya penulis Barat yang menggambarkan Tuhan sebagai sebuah konsentrasi kekuatan semata-mata, bahkan sebagai kekuatan yang kejam seperti seorang raja yang semena-mena. Penggambaran tentang kekuasaan dan keagungan Allah yang dibarengi dengan sifat pengasihnya yang sempurna banyak dikemukakan dalam ayat-ayat Alquran, misalnya pada Q.S. al-Naml (27):60-64. Menarik untuk dikemukakan bahwa kandungan kelima ayat tersebut selalu didahului dengan kalimat yang mengandung makna pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban; yaitu pada ayat 60 Allah bertanya ‘ أمن خاقsiapakah yang menciptakan langit…; pada ayat 61 Allah bertanya أمن جعل ‘siapakah yang menjadikan…?; ayat 62 Dia bertanya;’ أمن يجيبsiapakah yang memperkenankan doa…?: ‘ أمن يهديكمsiapakah yang memimpin kamu…?; ‘ أمن يبدؤ الخلقsiapakah yang menciptakan manusia dari permulaan…? Bentuk pertanyaan seperti ini, menurut kaedah tafsir disebut istifham ingkari. Patut dikemukakan bahwa sebelum Allah menutup firman-Nya pada lima ayat tersebut, Allah kembali menggunakan kalimat istifham inkari dengan mempertayakan “ailaahun ma’a Allah” ‘apakah bersama Allah ada ilah yang lain? Istifham ingkari yang kedua ini, merupakan penegasan kembali, bahwa kekuasaan, keagungan Allah dan kebaikan serta kasih sayang-Nya tidak ada yang dapat menyekutui-Nya dan menandingi-Nya. Selain itu, juga dapat ditegaskan bahwa penggunaan kata ilah setelah klausa ‘ أمن خاقsiapakah yang menciptakan langit…?; pada ayat 61 Allah bertanya أمن ‘ جعلsiapakah yang menjadikan…?; ayat 62 Dia bertanya;’ أمن يجيبsiapakah yang memperkenankan doa…?: أمن يهديكم ‘siapakah yang memimpin kamu…?; أمن يبدؤ ‘ الخلقsiapakah yang menciptakan manusia dari permulaan…? Menunjuk makna, bahwa setelah manusia menyadari perbuatan Allah tersebut, hendaknya manusia itu menjadikan Allah sebagai ilah. Dikatakan demikian, karena pengakuan keilahian Allah merupakan konsepsi logis dari pengakuan rububiyah-Nya. Sebaliknya pengakuaan rububiyah Allah tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dibarengi dengan pengakuan keilahian-Nya. Bertolak dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa seluruh manusia mengakui rububiyah Allah sejak dalam rahim ibunya. Tidak ada satupun anak manusia yang mengingkarinya. Itulah sebabnya dalam firman Allah, Q.S. al-Isra’ (17):67, ditegaskan bahwa: “Apabila manusia ditimpa bahaya di lautan, maka mereka akan melupakan siapa yang mereka serunya dan menyeru Allah. Namun tatkala Dia menyelamatkan mereka ke daratan, merekapun berpaling. Sungguh manusia selalu tidak berterimah kasih.” Dari kandungan ayat ini, jelas bahwa manusia sadar atau tidak sadar tidak akan mampu melepaskan dirinya dari Allah sebagai rabbnya. Pada ayat lain, ditegaskan bahwa manusia yang kafirpun, jika mereka ditanya; siapa yang menciptakan seluruh langit dan bumi? Pastilah mereka menjawab Allah.7 Sampai iblis pun yang jelas-jelas memilih ingkar kepada Allah tetap mengakui rububiyah-Nya. Buktinya adalah setelah mereka dinyatakan telah kafir oleh Allah, mereka pun memohon kepada Allah agar diberi tempo waktu yang panjang untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Permohonan mereka pun dikabulkan oleh Allah8 Setelah manusia memahami dan menyadari Af’al Allah dan Sifat-Nya dan atau Rububiyah-Nya, maka seyogyanya mereka menjadi manusia rabbaniyun. Yaitu orang yang memiliki pemahaman yang dalam tentang Perbuatan dan Sifat Allah, yang kemudian melahirkan kesadaran akan kebesaran dan keagungan-Nya. Selanjutnya mereka berusaha dengan sangat intens untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat Allah sehingga jiwanya dipenuhi dengan kerinduan yang dalam kepada Allah (Q.S. alMaidah [55]:44 dan 63; dan Q.S. Ali Imran [3]:79). Selanjutnya menarik dikaji penggunaan kata ilah dalam Alquran. Kata ilah secara etimologis mengandung makna pokok ibadah. Maka Allah dinamakan dengan ilah, karena Dia yang disembah. 9 Al-Raqiib al-Asyfahaniy menjelaskan bahwa, kata ilah berakar pada kata alaha yang mengandung arti menyembah. Lebih lanjut, ia mengemukakan beberapa pendapat yaitu: sebagian berkata bahwa kata tersebut berakar pada kata aliha yang mengandung arti mengherankan dan menakjubkan. Sebagian lagi mengatakan, bahwa akar kata ilah adalah ilaaha yang berarti yang dicintai. Pendapat lain mengatakan, dari kata laaha yang berarti terhijab.10 Jika pengertian bahasa di atas digunakan untuk menerjemahkan kalimat “la ilaha illa Allah, maka akan menunjuk makna; tidak yang disembah kecuali Allah; tidak ada yang dicintai kecuali Allah; tidak ada yang diagungkan kecuali Allah; tidak ada yang dituju kecuali Allah. Jadi kata ilah memiliki makna yang beraneka ragam, oleh karena itu, kiranya patut dipertanyakan: apakah makna-makna ilah ini ditemukan penggunaan di dalam Alquran. Pertanyaan ini diajukan karena ulama berbeda pendapat tentang 7 Lihat Q.S. al-Zumar (39):38. 8 Lihat Q.S. al-Hijr, 15: 36-44. 9 Ibn Faris Mu’jam Maqayis al-Lughat…, h. 127. 10 82-83. Al-Raghib al-Ashfahaniy, Mufradat li al-fazd Alquran, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), h. mkna ilah yang digunakan di dalam alquran, seperti yang dikemukakan oleh Quraish dalam bukunya yang berjudul Menyingkap Tabir Ilahi, asmaul Husnah dalam prespektif Alquran yaitu: “Para ulama yang mengartikan kata ilah dengan makna yang disembah, menegaskan bahwa ilah adalah segala sesuatu yang disembah, baik penyembahan itu dibenarkan oleh aqidah maupun yang tidak dibenarkan, seperti penyembahan terhadap matahari dan lain-lain. Olehnya itu, seorang muslim ketika mengucapkan kalimat la ilaha illa Allah, maka ia telah menafikan segala Tuhan kecuali Allah. Alasan yang diajukan oleh kelompok ulama di atas, adalah pengertian kebahasaan dan ditunjang dengan Q.S. al-‘Araf (7): 127. Sementara ulama lain membantah pendapat di atas, dengan mengatakan bahwa pernyataan di atas tidak lurus karena dalam kenyataannya diketahui sekian banyak zat selain Allah yang disembah, seperti matahari dan lain-lain. Keberatan mereka (kelompok ulama kedua) dibantah oleh ulama pertama, dengan mengatakan bahwa dalam kalimat syahadat itu ada sisipan antara kata ilaaha dan kata illa. Sisipan yang dimaksud adalah kata bihaq ‘yang hak’ sehingga makna syahadat tersebut adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Menurut mereka yang menolak; sisipan yang demikian tidaklah perlu. Menurut Quraish, memang ada kaidah bahasa yang menyatakan bahwa penyisipan suatu kata tidak diperlukan apabila kalimatnya dapat dipahami secara lurus tanpa penyisipan itu. Menurut kelompok ulama kedua bahwa pada mulanya kata ilah diletakkan dalam arti pencipta, pengatur, penguasa alam raya yang di dalam genggaman tangan-Nya –ayat pendukung, misalnya Q.S. al-anbiya (21): 22, 98-99; Q.S. al-Mukminun (23): 91 dan Q.S. al-Isra’ (17): 43. Menurut kelompok kedua, kata ilah dalam ayat-ayat tersebut, lebih tepat diterjemahkan dengan makna pengatur, penguasa alam raya, yang di dalam genggaman tangan-Nya segala sesuatu.”11 Sekalipun Quraish dalam konteks ini tidak memberikan penilaian yang pasti terhadap kedua pendapat tersebut, namun di bukunya yang lain ia menegaskan bahwa jika anda perhatikan semua kata ilah di dalam Alquran, niscaya anda akan temukan bahwa kata itu lebih dekat diartikan dengan penguasa, pengatur alam raya yang dalam genggaman tangan-Nya segala sesuatu, walaupun tentunya yang meyakini demikian 11 Quraish Shihab, Menyngkap Tabir Ilah:, Asma al-Husna dalam prepektif Alquran, (Jakarta: Lentera Hati, 1999), h.6-8. ada yang salah pilih ilahnya. Selanjutnya Quraish berkata; bukankah kata ilah bersifat umum, sedangkan Allah khusus untuk penguasa yang sesungguhnya. Penyikapan Quraish lebih tegas ditemukan dalam penyataannya di tempat lain, yaitu ketika ia sendiri mengartikan kalimat “Allah la ilaha illah huwa” dengan makna tiada pencipta, penguasa dan pengatur alam raya kecuali Dia….12 Menyikapi perbedaan pendapat di atas, kiranya perlu kajian ulang dan lebih mendalam terhadap penggunaan kata ilah dan hakekat maknanya dalam Alquran. Namun tidak pada tempatnya dikemukakan dalam makalah ini. Lalu, kita kembali kepada penggunaan kata Allah untuk pertama kalinya dalam penurunan wahyu, yang dikemukakan dalam Q. S. al-Ikhlas (112): 1-4: قل هو هللا احد هللا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد Kandungan ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa Allah adalah Tunggal (Esa), Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada satupun bagi-Nya saingan. Dalam surah al-Ikhlas ini, ditemukan beberapa informasi tentang keesaan Allah, yaitu keesaan Zat-Nya dan keesaan sifat-Nya, keesaan ibadah dan perbuatan-Nya serta penafian terhadap segala bentuk kemusyrikan baik syirik zati dan syirik sifati serta syirik af’ali. Keesaaan zati adalah seseorang mesti menyakini bahwa Allah itu tunggal tidak ada yang menyamai-Nya, tidak ada padanan bagi-Nya. Tegasnya mustahil ada yang serupa dengan-Nya dan bahkan penyerupaan pun tidak dapat dilekatkan pada-Nya. Sedangkan dimaksud dengan tauhid af’ali adalah bahwa Ia adalah pencipta segala sesuatu dengan sendiri-Nya dan merdeka dengan sepenuhnya. Kita kembali pada empat ayat dalam surah al-ikhlas di atas. Kandungan makna tentang keesaan-Nya, seperti telah dikemukakan di atas, ditunjuk oleh klausa “Allah ahad”; sedang frase “Allah al-shamad menunjuk tempat menggantungkan harapan dan kebutuhan. Adapun bentuk penafian atas segala kemusyrikan ditunjuk oleh kalusa “wa lam yakun lahu kufuan ahad.” Sedangkan klausa lam yalid wa lam yulad mengandung makna penafian terhadap tuduhan (anggapan) sebagian kelompok manusia bahwa Allah memiliki anak.. 12 Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 19. Menarik untuk diamati struktur bahasa yang digunakan ayat di atas. Pertama, informasi awal ayat tersebut merupakan penegasan bahwa Allah itu Esa dan kemudian diakhiri oleh klausa yang memberi makna negasi akan tandingan-Nya. Struktur bahasa yang sama ditemukan dalam Q.S. al-Hasyar (59):22-24: هو هللا اللذي ال اله اال هو اللملك اللقدوس.هو هللا اللذي ال اله اال هو علم الغيب والشهدة هو الرحمن الرحيم هو هللا الخلق البارئ المصور له.السلم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان هللا عما يشركون االسماء الحسني يسبح له ما في السموات واالرض وهو العزيز الحكيم Kandungan ayat-ayat surah al-Hasyr ini merupakan penegasan lebih lanjut dari kandungan ayat surah al-Ikhlas di atas, hanya saja dalam ayat-ayat surah al-Hasyar ini lebih banyak mengemukakan sifat-sifat Allah yaitu Dia adalah Allah, tiada ilah selain Dia yang Maha Mengetahui yang gaib dan tampak. Dia Maha Pengasih-Penyayang. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia yang Maha Merajai, Maha Suci, Maha Sejahtera, Maha Mengaruniai keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, Maha sombong. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Mencipta, Maha Mengada, Maha Membentuk. Bagi-Nya namanama yang indah. Kepada-Nyalah bertasbih apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jika kita cermati ayat surah 59 ini, maka ditemukan kesamaan struktural dengan ayat surah 112 di atas. Di mana pada 3 ayat surah 59, pada awalnya juga ditemukan informasi bahwa Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia. Jika kandungan makna ilah diartikan secara luas (tidak hanya dari segi kebahasaan tetapi juga penggunaannya dalam Alquran, seperti telah dijelaskan di atas), maka dapat ditegaskan bahwa 3 ayat pada surah 59 ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari klausa qul huwa Allah Ahad, yakni penjelasan mengenai keesaan Allah, baik keesaan Zat-Nya, Sifat-Nya, Perbuatan-Nya dan keesaan Ibadah kepada-Nya. Sedangkan akhir kandungan ayat 23 menegaskan kesucian Allah dari segala bentuk persekutuan dan penandingan. Pensucian yang demikian telah dilakukan oleh apa-apa yang ada di langit dan di bumi, hewan, tumbuhan, benda mati dan manusia. Namun sebagian manusia enggan untuk mensucikan-Nya, mereka adalah yang termasuk kelompok kontra terhadap ajaran tauhid. Demikian makna struktur ayat-ayat di atas, yaitu memuat penetapan tauhid dan sekaligus menegasikan syirik sebagai lawan tauhid. Kekuasaan dan kepengasihan Allah dapat ditemukan secara bersamaan dalam penamaan diri sebagai as-Shamad yaitu “Allah as-Shamad.” Secara etimologis kata ini berarti tujuan dan atau menuju serta kekukuhan.13 Menurut Quraish Shihab secara leksikologis kata as-Samad menunjuk berbagai macam pengertian, namun yang paling populer adalah: 1) Sesuatu yang tidak memiliki rongga lubang dan pori-pori, karena lubang dapat menjadi wadah sesuatu, sedangkan as-Shamad sedemikian kukuh dan padat sehingga tidak berlubang sedikitpun. 2) Bermakna tokoh yang terpuncak, sehingga tidak dapat diraih dan sekaligus menjadi tumpuan harapan semua pihak.14 Implikasi Tauhid Terhadap Pluralitas Agama Pada bagian ini, Pembahasan yang dikemukakan adalah bagaimana Alquran berbicara tentang fenomena pluralitas agama-agama dan multikultural. Alquran adalah kitab samawi yang diturunkan terakhir dan diwahyukan kepada penutup para Nabi dan rasul yaitu Muhammad saw. Turunnya Alquran berfungsi sebagai mushaddiq (pembenaran) bagi kitab-kitab terdahulu. Dengan demikian, kedatangan Alquran bukan sebagai pembatal kitab-kitab sebelumnya tetapi lebih sebagai pembenaran tentang inti ajaran Tuhan yang turunkan kepada para rasul dan nabi sebelumnya. Di sisi lain, Alquran juga berfungsi sebagai muhaimin (penguji) dan furqan (pengoreksi) atas penyimpangan yang terjadi dari penganut kitab-kitab tersebut. Dari sini dapat ditegaskan bahwa esensi dan subtansi ajaran Alquran sama dengan ajaran kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil dan suhuf-suhuf. Esensi ajarannya adalah tauhid. Para nabi dan rasul Allah yang diutus kepada umat manusia, semuanya membawa ajaran tauhid, termasuk inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. seperti termuat di dalam Alquran. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diperintahkan untuk beriman kepada kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelum Alquran, seperti ditegaskan dalam Q.S. Asyuura (42): 15: 13 Ibn Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughat…, h. 309. 14 Quraish, Tafsir Al-Quran…, h. 671. “…Katakanlah (Muhammad): Aku beriman kepada semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah….” Di awal kehidupan Nabi Muhammad saw. hingga akhir kehidupannya benarbenar menyakini bahwa kitab-kitab suci yang terdahulu adalah berasal dari Allah dan yang menyampaikannya adalah para Nabi dan Rasul Allah. Dengan demikian, tidak heran jika Muhammad sebagai nabi terakhir mengakui kenabian dan kerasulan Ibrahim as., Musa as., Isa as., Nuh as., dan para nabi lainnya. Penyikapan yang demikian semakin kuat pada diri Nabi Muhammad setelah tampak bahwa para pengikut kitab-kitab suci terdahulu ada yang beriman kepada Alquran dan kepada kenabiannya, seperti Waraqa bin Naufal yang telah mengetahui akan datangnya seorang nabi yang ciri-cirinya –seperti yang ia baca dalam Kitab Injil. Fenomena Waraqa ini merupakan salah satu bukti bahwa kedatangan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang membawa kitab Alquran sudah menjadi harapan dan keinginan sebagian orang yang telah memiliki kitab sebelumnya. Hal ini ditegaskan di dalam Q.S. Asy-Syu’ara (26): 192-197: “Sesungguhnya Alquran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oeh Ruhul Amin (Jibril) ke dalam hati Muhammad agar menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” Jika ayat di atas dihubungkan dengan kandungan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dalam surah yang sama, maka dapat dijelaskan bahwa ketika Alquran disampaikan kepada masyarakat Makkah -sebagai kelompok manusia yang pertama bersentuhan dengan Alquran-, maka sebagian mereka menyakini kebenaran Alquran dan kebanyakan mereka menjadi kelompok kontra Alquran. Bahkan sikap kontra mereka sangat cepat datangnya. Fenomena yang demikian itu tidak saja dialami oleh Muhammad saw ketika Alquran disampaikannya, tetapi setiap nabi dan rasul yang diutus Allah menyampaikan risalahnya maka manusia yang menjadi obyek risalah tersebut akan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok yang menerima risalah dan kelompok kontra risalah. Keterangan ini dapat dilihat dalam Q.S. 26: 69-191. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para nabi dan rasul yang diutus berhadaphadapan dengan pluralitas sosial-budaya dan sosial politik dan tentunya pluralitas agama. Jadi ketika para nabi dan rasul diutus kepada suatu umat, umat tersebut tidaklah hampa budaya tetapi padanya hidup dan berkembang pluralitas sosialbudaya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian dari kelompok umet tersebut ada yang tetap berusaha berpegang pada ajaran para nabi dan rasulnya dan sebagian lainnya melenceng dari ajaran nabi dan rasulnya. Kelompok inilah yang kemudian senantiasa berharap agar Allah mengutus kembali seorang nabi dan rasul untuk memurnikan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Ketika Allah pun mengutus nabi dan atau rasul yang baru (dan memang sebelum pengutusannya sering kali telah diinformasikan dalam kitab sebelumnya), maka kelompok inilah yang kemudian beriman dan menyakini rasul tersebut dan kitabnya. Sedang kelompok kedua yakni kelompok kontra risalah, yaitu ketika Allah mengutus nabi dan rasul baru pada mereka, mereka pun bersikap kontra terhadap rasul dan kitab yang baru tersebut. Itulah sebabnya ketika Muhammad saw menyampaikan ajaran al-Qur’an kepada masyarakat Makkah yang kemudian memperoleh tantangan dari kelompok kontra risalah, Allah kemudian menyampaikan (sebagai hiburan dan i’tibar) kepada NabiNya bahwa apa yang sedang engkau hadapi sesungguhnya telah dialami oleh para nabi dan rasul sebelummu. Sebaliknya kelompok yang mendukung dan beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad saw serta membenarkan al-Qur’an adalah mereka yang sebelumnya beriman kepada kitab Injil. Mereka mengetahui akan diutusnya seorang Nabi dan Rasul beserta ciri-cirinya, seperti kasus waraqa yang dikemukakan di atas. Dalam keterangan Alquran dapat diketahui bahwa sesungguhnya sebelum kedatangan Rasulullah saw. beserta Alquran sebagai mu’jizatnya, sebagian orang Makkah sangat menginginkan adanya agama baru seperti Yahudi dan Nasrani. Hal ini ditegaskan di dalam Q. S. as-Shaaffat (37): 168-170 dan Q.S. Fatiir (35): 42. Kandungan keempat ayat ini menegaskan bahwa sebagian penduduk Makkah biasanya berkata: seandainya di sisi kita terdapat sebuah kitab dari kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummnya, maka pasti kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa dan bahkan mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa sekiranya datang kepada kami seorang pembawa kebenaran niscaya kami akan lebih memperoleh petunjuk dari salah satu kitab yang telah diturunkan terdahulu. Namun, tatkala harapan mereka diwujudkan, justru mereka ingkar kepada kitab yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, Alquran tidak sekedar berfungsi sebagai pembenaran tetapi juga mengandung makna pemurnian ajaran. Hal ini sangat logis, karena pengutusan antara nabi dan rasul yang satu dengan nabi dan rasul yang datang sesudahnya berselang waktu lama, sehingga pemalsuan terhadap ajaran yang orisinil sangat dimungkinkan. Justru karena adanya pemalsuan ajaran tauhid inilah, maka Allah pun mengutus nabi dan rasul lainnya. Pemaknaan yang demikian, sekali lagi merupakan bukti yang konkrit dan tegas bahwa pluralitas kitab kerasulan disatukan dalam esensi tauhid. Itulah sebabnya setiap nabi dan rasul yang diutus mengajarkan tauhid. Jika Alquran berfungsi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maka kitab Injil pun berfungsi sebagai pembenar terhadap kitab Taurat dan tentunya demikian pula kitab Taurat menjadi pembenar dari kitab sebelumnya, (Q.S. 5: 46). Fungsional kitab-kitab tersebut, juga menjadi bukti sesamaan ide spiritual setiap kitab. Dari sisi ini dapat dikatakan adanya pengakuan dan pembenaran Alquran akan pluralitas kitab yang telah diturunkan kepada umat-umat terdahulu. Namun pluralitas kitab tersebut disatukan dalam ide spiritualitas tauhid yang menjadi esensi ajaran risalah Allah yang diturunkan melalui kitab-kitab-Nya kepada setiap umat manusia. Dari segi fungsi dan tanggung jawab kenabian dan kerasulan, di satu sisi Nabi Muhammad diperintahkan untuk memutuskan perkara yang dihadapi umatnya berdasarkan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Di sisi lain Allah melarang Nabi Muhammad mengikuti hawa nafsu umatnya. Larangan ini sangat logis karena, penegakan hukum dan penerapannya terhadap perkara-perkara yang membutuhkan keputusan hukum tidak akan terwujud dengan mengikuti hawa nafsu. Tugas dan tanggung jawab kenabian Nabi Muhammad saw. tersebut, juga menjadi tugas dan tanggung jawab para nabi dan rasul sebelumnya. Hal dapat dipahami dari kandungan ayat 44, 46-47 dalam surah yang sama. Kandungan ayat pertama berisi informasi bahwa Kitab Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya menjadi rujukan utama para Nabi dalam memutuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi. Sedang kandungan ayat 46-47 berisi informasi bahwa Allah mengiringi jejak para nabi yang diutus kepada umat Yahudi dengan diutusnya Isa as. Injil adalah kitabnya yang berisi petunjuk dan cahaya. Isa as. diutus untuk membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya yaitu Kitab Taurat dan diperintahkan padanya untuk berhukum sesuai dengan hukum yang diturunkan dalam Kitab Injil. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa pluralitas nabi dan rasul, selain disatukan dengan ide spiritual yang sama juga diikat dan disatukan dalam tugas dan tanggung jawab kenabian dan kerasulan yang sama yakni menegakkan hukum dan atau memutuskan perkara-perkara yang terjadi pada umat mereka berdasarkan ketetapan hukum yang diturunkan Allah dalam kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul tersebut. Berdasarkan uraian kandungan pertama dari ayat 48 surah al-Maidah di atas dapat disimpulkan bahwa; sesungguhnya Alquran mengakui pluralitas kitab yang diturunkan oleh Allah, namun pluralitas tersebut disatukan dalam satu esensi ide spiritual yaitu tauhid. Selain itu, Alquran juga mengakui kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, Alquran mengakui pluralitas nabi dan rasul, namun para nabi dan rasul tersebut disatukan dalam tanggung jawab kenabian dan kerasulan yang sama yakni memutuskan hukum terhadap perkara yang terjadi pada umat mereka masing-masing berdasarkan ketetapan hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada mereka. Demikian pula tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seluruh nabi dan rasul dengan kitab sucinya masing-masing di tengah-tengah umatnya, memiliki kemiripan dan kesamaan yakni berhadapan dengan kelompok kontra risalah, sekalipun cara penyelesaiaannya satu sama lain berbeda sesuai dengan tingkat keintelektualan umat yang dihadapinya dan sesuai dengan syir’a dan manhaj para nabi dan rasul. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai syir’atan wa minhaajan. Kata minhajan secara etimologis berarti jalan yang jelas dan berhenti. 15 Quraish mengartikannya dengan makna jalan luas. Ridha mengartikannya dengan jalan yang 15 Ibn Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughat…, h. 361. terang dan jelas. Quraish16 berkata, melalui kata minhaj, ayat di atas mengimajinasikan adanya jalan yang luas menuju syariat. Siapa yang berjalan di atas minhaj itu akan dengan mudah ia sampai kepada syariat. Baik kata minhaj dan syir’ah ditemukan dalam Alquran hanya satu kali, selain itu digunakan pula dalam Alquran kata syari’ah satu kali. Menurut penulis tampaknya kata syir’ah dan atau syari’ah lebih luas maknanya dari kata minhaj. Dengan kata lain, minhaj bagian dari syariat. Selain itu, tampaknya dalam Alquran, kata syariat lebih sempit pemaknaannya dari kata ad-din yang berarti agama. Dalam konteks ini Thabaththabai17 berkata, syariat adalah suatu jalan bagi suatu kaum dan atau seorang nabi di antara kaum dan nabi lainnya yang diberikan padanya. Sedang kata ad-din berarti suatu pola dan atau jalan Tuhan yang berlaku bagi seluruh kaum. Jadi syariat dapat mengalami pembatalan sedangkan ad-din tidak berlaku padanya pembatalan. Pandangan yang senada dikemukakan oleh Quraish, bahwa kata syir’ah dan atau syari’at dalam Alquran pemaknaannya lebih sempit dari kata ad-din yang biasa diterjemahkan dengan makna agama. Syari’at adalah jalan untuk satu umat tertentu dan nabi tertentu seperti syari’at Nuh as., syari’at Nabi Musa as., syari’at nabi Isa as. dan tentunya syari’at Nabi Muhammad saw. Sedangkan ad-din adalah tuntunan Ilahi yang bersifat umam dan untuk seluruh umat. Untuk itulah agama dapat mencakup sekian banyak syari’at.18 Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa klausa di atas mengandung makna bahwa setiap umat –baik yang historis maupun yang sedang berhadap-hadapan dengan Rasulullah saw. di Madinah ketika ayat ini turun- memiliki syir’ah dan manhaj masing-masing. Buat Nabi Nuh dan umatnya memiliki syariat dan manhaj yang khusus untuk mereka dan masa mereka, demikian pula Nabi Musa as. dan umatnya dan Nabi Isa as. dan umatnya dan seterusnya. Dari sisi ini dapat ditegaskan, bahwa pluralitas syari’at dan manhaj disatukan dalam ad-din yang satu. Dalam konteks ini relevan dengan kandungan ayat 19 dan 85 dalam surah Ali Imran. Kandungan kedua ayat ini menegaskan bahwa: “ Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam.”(ayat 19): dan “Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka 16 Quraish, Tafsir Al-Quran…, h. 676. Allamah Muhammad Thabathabai, al-Mizan fi Tafsir Alquran, (Bairut: Muassasah al‘Alamiay, 1991), h. 368-359. 17 18 Quraish, Tafsir Al-Quran…, h. 678. tidak akan diterima dari pada-Nya dan di akhirat dia akan termasuk kelompok yang merugi” (ayat 85). Menarik untuk dijelaskan bahwa makna pokok dari kata Islam adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Dengan demikian yang dimaksud dengan Din Islam dalam konteks ayat tersebut, menurut penulis adalah agama yang mengajarkan sikap pasrah dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Oleh karena itu, istilah din dalam konteks ayat di atas mencakup seluruh syari’at dan manhaj yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah. Tegasnya Alquran mengakui pluralitas syari’at dan apalagi pluralitas manhaj, namun disatukan dalam din yang satu yaitu din Islam, yakni Din yang mengajarkan kepasrahan yang total kepada Allah dan inilah sesungguhnya inti makna tauhid. Dalam konteks inilah Alquran kemudian mengajak kelompok Ahlul Kitab -yang memiliki syariat dan manhajnya masing-masing seperti yang termaktub dalam kitan Taurat dan Injil- menuju kalimat yang sama antara mereka dengan Nabi Muhammad saw dan umat Islam, seperti ditegaskan dalam Q.S. Ali Imran (3): 64: “Katakanlah: Hai ahlul Kitab marilah berpegang kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak pula sebagian kita menjadi sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang berserah diri kepada Allah (Muslim)” Yang dimaksud dengan ”kalimatin sawa” dalam ayat tersebut adalah (1) kita tidak menyembah selain Allah; (2) kita tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun dan (3) kita tidak menjadikan sebagian dari kita sebagai tuhan selain Allah. Inilah tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh setiap individu dan umat, apakah itu kaum Yahudi dan kaum Nasharah ataupun siapa saja termasuk kelompok shabiun, jika mereka ingin tergolong sebagai penganut ajaran Islam, ajaran kepasrahan secara total kepada Allah (tauhid). Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Kandungan ayat ini sejalan dengan pengakuan Alquran atas keselamatan kelompok Yahudi, Nasrani, Shabiin dan tentunya kelompok mu’min selama mereka berpegang pada tauhid, seperti dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 62 dan Q.S. alMaidah (5): 69: Kedua kandungan ayat terakhir ini menegaskan bahwa; baik kaum mu’min, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan Shabiin jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, lalu mereka beramal shaleh, maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah dan tidak ada kekhawatiran bagi mereka serta tidak pula bersedih hati. Oleh karena itu, pendapat sebagian pakar -yang karena didorong oleh desakan gagasan pluralitas-pluralisme dan besarnya perhatian mereka untuk mewujudkan kerukunan beragama,- di mana mereka kemudian berpendapat bahwa kandungan ayat 64 dalam surah ke 3, ayat 69 pada surah ke 5 dan ayat 62 pada surah ke 2, dapat menjadi pijakan bahwa penganut agama-agama dari kaum Yahudi, Nasrani dan Shabiin yang hidup sezaman dengan kenabian Muhammad saw. dan sesudahnya hingga saat ini, selama mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal shaleh, akan memperoleh keselamatan sebagaimana orang-orang mu’min adalah tertolak. Dikatakan demikian, karena keimanan mereka kepada Allah, kepada hari kemudian dan amal shaleh yang mereka kerjakan belumlah cukup hingga mereka membenarkan Alquran dan beriman kepada kenabian dan kerasulan Muhammad saw., sebagaimana dicontohkan oleh sikap dan keyakinan sebagian kelompok Ahlul kitab (yaitu pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka) yang hidup sezaman dengan Muhammad saw. dan sezaman dengan turunnya Alquran. Di mana mereka selain beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal shaleh, juga beriman kepada kebenaran Alquran dan kenabian serta kerasulan Muhammad saw. Bahkan mereka sangat ingin dipersaksikan sebagai dan digolongkan ke dalam kelompok orang-orang shaleh. Pandangan dan pernyataan eksklusif dari kaum Yahudi dan Nasrani ini, ditolak dengan tegas oleh Alquran. Alquran menegaskan dalam ayat 112 pada surah ke 2 bahwa hanya orang-orang yang menyerahkan dan memasrahkan dirinya secara total kepada Allahlah (aslama … lillahi) dan mereka berbuat ihsan (muhsin) yang memperoleh pahala dari Allah dan jauh dari kekhawatiran dan kesedihan. Kiranya jelas bagaimana implikasi tauhid terhadap pluralitas agama. Penutup Berdasarkan uraian terdahulu, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah: 1. Tauhid adalah Kesadaran manusia tentang keyakinannya akan keesaan Tuhan yang meliputi keesaan Zat-Nya, keesaan Perbuatan-Nya, keesaan sifat-Nya dan keesaan ibadah kepada-Nya. Keempat keesaan tersebut merupakan lawan dari syirik zat, syirik perbuatan, syirik sifat dan syirik ibadah. Esensi tauhid adalah pensucian terhadap Tuhan dan negasi pentasybihan. Artinya Allah Maha Esa, Maha Suci dari segala bentuk penyerupaan dan sesuatu yang serupa dengan-Nya, baik segi Zat-Nya, Perbuatan-Nya, Sifat-Nya dan Ibadah kepada-Nya. Allah tak terhingga sedangkan selain-Nya terhingga. Kesadaran tauhid Qurani yang demikian, menjadi patron segala kreativitas manusia dalam kehidupannya, baik yang bersifat amaliah maupun pemikirannya. 2. Menurut Alquran pluralitas agama, kitab, syir’ah, manhaj dan kultur merupakan suatu kemestian dan sunnatullah, namun pluralitas tersebut tetap diikat atau disatukan oleh satu ikatan yang kokoh yaitu ikatan tauhid. Jadi tidak ada pluralitas yang berdiri sendiri tanpa adanya ikatan yang menyatukannya. Inilah yang dimaksud dengan kemajemukan dalam kesatuan (ketunggalan). DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemahan al-Ashfahaniy, Al-Raghib. Mufradat li al-fazd Alquran (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992) bin Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris. Mu’jam Maqayis al-Lughat (Misrh, Dar al-Fikr, 1979) Hidayat, Kamaruddin dan Muhammad Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial. (Cet. I; Jakarta: Paramadina), 1995. Majid, Nurcholish. Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1997) Shihab, Quraish. Tafsir Al-Quranul Karim, Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan turunnya Wahyu (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayat, 1997), h. 667-668. ______. Menyngkap Tabir Ilah:, Asma al-Husna dalam prepektif Alquran, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 1999), h.6-8. ______.Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), Thabathabai, Allamah Muhammad. al-Mizan fi Tafsir Alquran, Bairut: Muassasah al‘Alamiay, 1991,