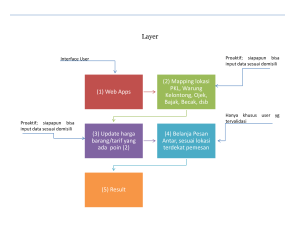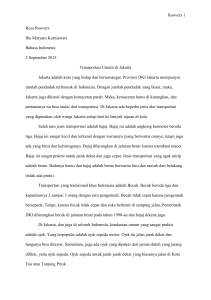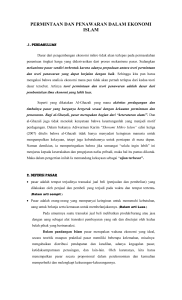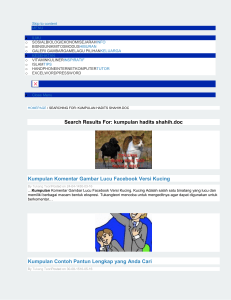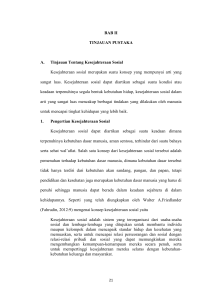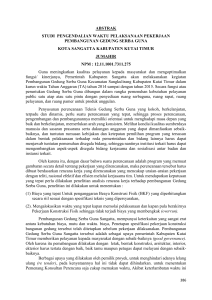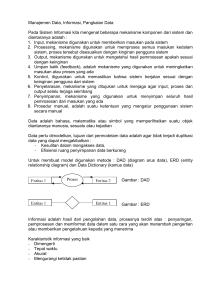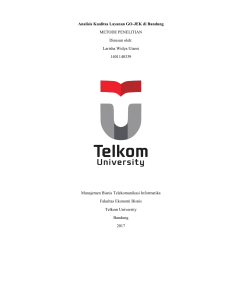kinerja pelayan publik: pengalaman beberapa negara
advertisement

SEKTOR INFORMAL : ”PARASITKAH MEREKA ATAU A NECESSARY EVIL?” (Studi Kasus : Etnografi Tukang Ojek, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur) Antonius Tarigan *) PENGANTAR Berbeda dengan tulisan –tulisan kami sebelumnya, pada kesempatan ini , penulis lebih banyak mengupas ”aspek praktis” dibandingkan dengan ”aspek teoritis” dengan mengangkat tema sektor informal (kasus tukang ojek). Secara khusus penulis merasa terbeban untuk menyampaikan informasi ini, mengingkat sektor informal (kasus tukang ojek) merupakan suatu gambaran nyata yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat kita khususnya di kawasan perkotaaan. Disamping itu, melalui studi etnografi, penulis juga telah melakukan pengamatan intensif (sekitar 1.5 bulan) terhadap tindak-tanduk, perilaku dan persoalan-persoalan yang terkait dengan dinamika sektor informal (tukang ojek). Walaupun informasi ini tidak cukup komprehensif, dari lesson drawing yang dapat dipotret kami berharap semoga tulisan ini memberikan kontribusi nyata dalam aspek perencanaan terkait pentingnya modal sosial, jenis modal sosial dan efektifitas hukum publik khususnya kepada Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Direktorat Tenaga Kerja, Direktorat Transportasi, Direktorat Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Direktorat Hukum, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, serta direktorat terkait lainnya. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan merupakan salah satu persoalan yang paling problematis dewasa ini. Pemerintah di wilayah perkotaan, apalagi kota besar semacam Jakarta, harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang terus bertambah kompleks dan menumpuk sementara kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya relatif terbatas. Demikian halnya dengan terbatasnya daya serap maupun daya tampung kota. Meningkatnya angka penggangguran, semakin eksesifnya kriminalitas, tidak memadainya sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain sebagainya adalah beberapa potret kusam yang merefleksikan ketidakramahan kawasan perkotaan. Kota juga menjadi area perebutan kue ekonomi ketika batasan-batasaan etika, moral, dan hukum menjadi semakin kabur. Salah satu permasalahan penting yang terdapat di kawasan perkotaan adalah tumbuh dan berkembangnya sektor informal. Ini merupakan sektor alternatif yang antara lain ditandai oleh (1) mudah untuk dimasuki ataupun untuk keluar, (2) ketergantungan pada sumberdaya asli atau endogenous resources, (3) kepemilikan dan pengelolaan bersifat kekeluargaan, (4) usahanya berskala kecil dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi, (5) labor-intensive dengan teknologi tradisional, (6) tidak membutuhkan keahlian tertentu sebagaimana pada sektor formal, dan (7) pasarnya bersifat kompetitif tetapi tidak disertai regulasi yang jelas (Gilbert & Gugler, 1984: 73). Pada tempat lain, Gugler (1981) juga mencatat bahwa sektor informal bersifat sangat heterogen, sulit ditarik garis pembeda yang jelas dengan sektor formal, malahan terdapat kesatuan rangkaian antara usaha berskala kecil dengan yang berskala besar, illegal dan legal serta yang produktif dengan yang kurang produktif. Aktivitas yang mereka jalankan sangat beragam, mulai dari penjaja makanan, jasa ojek, sampai *) Ir. Antonius Tarigan, M.Si adalah Kasubdit Kelembagaan Kerja Sama Pembangunan, Direktorat Kerja Sama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Kantor Meneg PPN/Bappenas dan Mahasiswa Program Doktor Universitas Indonesia “Konsentrasi Kebijakan Publik”-red Halaman 1 pada para penjual barang-barang elektronik bajakan. Mereka tidak memiliki cukup modal untuk meningkatkan skala usahanya sehingga bahkan tidak cukup untuk sekedar menghidupi keluarganya. Orientasinya bukan pada pemupukan modal, tetapi lebih pada upaya memperoleh pendapatan cash yang langsung dapat dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (Rakodi, 1993: 211). Dengan karakter ini, sektor informal bisa menjadi sarana menuju sektor formal tetapi juga bisa menjadi tujuan itu sendiri. Atau ada juga yang melihatnya sebagai proses yang tidak terakomodasi dalam kerangka institusional dan legal suatu masyarakat sebagaimana aktivitas formal lainnya (Portes, et.al., 1989: 12). Terlepas dari karakterisasi semacam itu, sektor informal telah menjadi permasalahan sendiri. Namun tidak sedikit kalangan yang melihat bahwa sektor informal juga solusi; jadi tidak sekedar masalah. Perbedaan cara pandang semacam ini sangat menentukan kebijakan apa yang akan diambil pemerintah. Pandangan pertama yang dikenal dengan “pandangan evolusionis (developmentalis)” berpendapat bahwa sektor informal akan tumbuh dan berkembang menjadi sektor formal. Dalam pandangan ini, sektor informal dapat menjadi jawaban alternatif terhadap masalah pengangguran dan kemiskinan di kota, dan karenanya, harus dikembangkan. Pandangan semacam itu terutama sangat dipengaruhi hasil penelitian ILO pada tahun 1972 yang sekaligus mempopulerkan terminologi dan jenis aktivitas tersebut. Sementara itu, pandangan kedua yang bersifat “involusionis-eksploitatif” cenderung melihat sektor informal sebagai sektor yang tidak mungkin berkembang. Kehadiran mereka hanya menjadi sasaran empuk eksploitasi sektor formal. Dengan demikian, mengembangkan sektor informal merupakan upaya yang sia-sia. Cara pandang kedua inilah yang nampaknya dominan di tanah air sehingga setiap ada masalah, maka sektor inilah yang selalu menjadi korban, atau minimal kambing hitamnya. Tidak terkecuali dalam upaya penataan kota seperti bidang transportasi. Untuk konteks Indonesia, kedua pandangan tersebut seolah menyatu. Tidak sedikit kalangan yang menunjukkan antipatinya terhadap kehadiran sektor informal, tetapi lebih banyak lagi yang menaruh empati dan simpati terhadap keberadaan kelompok tersebut. Dengan kata lain, sektor informal merupakan ‘a necessary evil’ yang menawarkan solusi sekaligus mendatangkan masalah. Guna memperjelas topik di atas, maka penelitian singkat ini akan secara khusus melihat keberadaan jasa ojek di kawasan perkotaan. Sektor usaha tersebut merupakan salah satu varian sektor informal yang juga tidak terlepas dari beberapa sinyalemen teoritis sebelumnya. Artinya, kehadiran jasa ojek bisa menjadi solusi bagi keperluan transportasi tetapi bisa juga menjadi masalah itu sendiri. Bagi penduduk yang memiliki mobilitas tinggi tetapi mengalami hambatan dalam hal transportasi, yaitu mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau terbatas aksesnya terhadap transportasi publik, kehadiran jasa ojek sangat membantu. Demikian halnya, sektor tersebut dapat menjadi alternatif bagi penciptaan lapangan kerja serta pengurangan angka penggangguran. Nilai-nilai positif-kontributif di atas juga disertai oleh berbagai gejala yang memperburuk citra jasa ojek. Media massa sering memberitakan tindak kekerasan atau pemerasan yang dilakukan tukang ojek terhadap penumpangnya. Demikian halnya, pada saat-saat dan di kawasan tertentu, operasi ojek sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Beberapa tukang ojek yang tergabung dalam suatu pangkalan bahkan bersepakat untuk menegakkan aturan sendiri, baik yang berkaitan dengan tarif jasa, zona operasi, maupun mekanisme pengaturan internal. Aturan informal tersebut tidak jarang menyerupai ‘hukum publik’ yang tidak tertulis namun bersifat mengikat. Pandangan lain melihat aturan tersebut sebagai bentuk modal sosial (social capital) walaupun dengan cakupan yang relatif terbatas. Uniknya, sebagai modal sosial, berbagai aturan tersebut tidak saja mengandung aspek-aspek positif tetapi juga aspek negatif. Aturan tersebut seringkali menimbulkan keluhan bagi penumpang akibat tarif yang tidak jelas terutama setelah jam sibuk (makin malam makin mahal), memicu konflik dengan tukang ojek dari pangkalan lain akibat pelanggaran zone operasi, dan sebagainya. Dengan lebih tegas dapat dinyatakan bahwa dalam konteks pengelolaan ojek terdapat research problem yang cukup serius di mana terjadi self paradox dalam penerapan hukum publik. Sebagai varian hukum publik, aturan-aturan tersebut seharusnya berlaku umum. Tetapi ternyata muncul eksklusivitas di mana hukum publik dikostruksi untuk konteks tertentu dan itu berlaku efektif. Dengan kata lain, juga ditemui adanya dilema antara legalitas hukum publik dengan tingkat efektivitasnya: tidak Halaman 2 semua yang bersifat legal-formal itu bisa berlaku efektif, dan sebaliknya, efektivitas suatu hukum publik tidak selalu ditentukan oleh legalitasnya. Berangkat dari uraian di atas maka penelitian ini akan melihat secara kritis – walaupun sifatnya deskriptif – berbagai hal yang berkaitan dengan dinamika jasa ojek, terutama persepsi dan perilakunya serta hubungannya dengan modal sosial dan hukum publik. Studi semacam ini semakin penting sejalan dengan berbagai langkah pemerintah untuk menertibkan ojek yang lebih sering mengalami kegagalan karena kekeliruan dalam menggunakan pendekatan. B. Setting Salah satu bentuk aktivitas sektor informal di kawasan perkotaan adalah jasa ojek yang dapat dijumpai hampir di semua lorong kawasan pemukiman, terutama di daerah pinggiran kota. Umumnya jasa usaha ini ditekuni oleh mereka yang tidak memiliki modal usaha yang cukup – bahkan sama sekali tidak memiliki modal usaha kecuali tenaga – dengan tingkat keterampilan yang pas-pasan. Mereka bekerja hampir sepanjang hari dan beberapa di antaranya menggunakan sistem rotasi atau pergantian. Artinya, satu ojek (sepeda motor) bisa digunakan oleh beberapa orang pada waktu yang telah disepakati bersama. Ada juga yang menggunakan sistem persewaan, sehingga ada setoran dalam jumlah tertentu dan pada waktu tertentu pula (biasanya harian) yang harus diberikan kepada pemilik ojek. Dengan karakter tersebut, penghasilan riil yang diterima oleh tukang ojek juga pas-pasan – untuk tidak mengatakan relatif rendah. Jumlahnya pun tidak pasti. Hal ini nampaknya bisa digunakan sebagai penjelas mengapa sektor usaha tersebut memiliki tingkat persaingan yang tinggi – walaupun agak terselubung – yang tidak jarang berakhir dengan tindakan kekerasan seperti perkelahian bahkan pembunuhan, baik antar tukang ojek maupun antar tukang ojek dengan pengguna. Tingkat kompetisi tersebut makin terasa untuk kawasan operasi yang tidak memiliki aturan atau kesepakatan bersama tentang pengelolaannya. Dampak negatifnya juga dirasakan oleh pengguna berupa kurang terjaminnya kenyamanan dan keselamatan karena perilaku kebut-kebutan guna mengejar setoran. Untuk menghindari kondisi tersebut, maka beberapa pangkalan menegakkan aturan main sendiri. Misalnya sistem antrian dan penentuan tarif. Aturan tersebut bersifat mengikat ke dalam maupun keluar. Artinya, baik tukang ojek yang menjadi anggota maupun tukang ojek dari pangkalan lain serta pengguna harus mentaati aturan tersebut. Berbagai aturan tersebut, lagi-lagi dan sampai tingkatan tertentu, justru menimbulkan problema tersendiri yang semakin memperpanjang daftar masalah di kawasan perkotaan. C. Kasus Studi ini dilakukan di Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur pada pertengahan Oktober s.d. akhir November 2001. Di beberapa titik di kawasan tersebut dapat dijumpai pangkalan ojek. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pendidikan (dari yang tidak menamatkan SD sampai yang S-1) dan suku (Betawi, Jawa, Sunda, Batak, dsb). Di beberapa pangkalan yang strategis, kehadiran mereka cukup mengganggu kelancaran lalu lintas. Ada juga yang melarang angkutan umum untuk melewati rute tertentu yang menjadi areal kekuasaannya. Hal itu sangat merugikan penumpang yang akhirnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Beberapa pangkalan ojek sudah memiliki aturan sendiri yang bersifat mengikat ke dalam maupun keluar, sedangkan yang lainnya belum memiliki aturan bersama tentang sistem pengelolaannya. Perbedaan pola pengelolaan tersebut membawa implikasi signifikan bagi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Perbedaan karakter tersebut menjadikan lokasi ini menarik untuk diteliti. ANALISIS REFLEKTIF : SEBUAH KOMPARASI A. Persepsi Tukang Ojek Persepsi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan kognisi. Persepsi seseorang, antara lain, dipengaruhi oleh pengalaman nyata dalam kehidupannya. Dipahami secara demikian, maka persepsi tukang ojek merupakan hasil interaksi mereka dengan peri Halaman 3 kehidupannya sebaga tukang ojek. Dalam kaitan dengan itu ada 3 hal yang mendapat perhatian khusus, yaitu persepsi tukang ojek terhadap pekerjaannya, persepsi tukang ojek terhadap penumpang dan persepsi tukang ojek terhadap sesama tukang ojek. Dari hasil pengamatan sepintas di kedua lokasi di atas, terlihat adanya sedikit variasi pandangan tukang ojek dalam melihat pekerjaannya. Pandangan pertama, ada yang melihat pekerjaan tersebut sebagai sekedar pelarian karena tidak adanya alternatif, sebagian lagi melihatnya sebagai warisan keluarga yang sudah ditekuni sejak lama, dan sebagian lagi menganggapnya sebagai sekedar pengisi waktu luang. Variasi persepsi tersebut dapat ditelusuri dari latar belakang sosial ekonomi para tukang ojek. Mereka yang menganggap pekerjaan mengojek sebagai pelarian adalah mereka yang terkena dampak krisis ekonomi. Sebelumnya mereka bekerja di sektor formal seperti karyawan pabrik, sopir, dan sebagainya. Karena himpitan krisis di mana gaji yang diterima relatif kecil sementara harga berbagai kebutuhan hidup terus menanjak, maka mereka pun beralih pekerjaan. Pemilihan pekerjaan sebagai tukang ojek pun merupakan bagian dari ‘gambling’. Karenanya, perilaku mereka sangat nekad. Seperti dituturkan Herry Sutanto, pemuda kelahiran Brebes, menjadi tukang ojek itu ibarat jadi: kalau berhasil bagus, kalau gagal, nggak apa-apa. Mereka berprinsip ‘berani mati di atas motor’. Pandangan kedua, ditemui khusus di lokasi Pangkalan Portal Cibubur. Mereka merupakan masyarakat asli Betawi dan pekerjaan ojek adalah pekerjaan keluarga. Yaitu bahwa bapak dan anak samasama mengojek, baik secara paralel maupun bergantian untuk menghidupi keluarganya dan hal itu sudah lama dijalani. Adanya latar sosial yang homogen inilah yang nantinya dapat dipakai sebagai basisi eksplanasi atas berbagai kekhasan yang dijumpai di pangkalan tersebut. Kedua kelompok pandangan di atas mewakili mereka yang menjadikan ojek sebagai pekerjaan tetap di mana nafkah hidupnya bergantung. Sementara itu, yang menganut pandangan ketiga adalah mereka yang menjalani pekerjaan mengojek sebagai pekerjaan sampingan. Kebanyakan dari mereka memiliki pekerjaan tetap di sektor formal. Mengojek adalah pekerjaan yang mereka lakukan sebelum atau setelah jam kantor. Walaupun terdapat variasi persepsi dalam melihat pekerjaannya, hampir semua tukang ojek – terutama mereka yang menjadikan ojek sebagai pekerjaan tetapnya –mengaku bahwa pekerjaan sebagai tukang ojek adalah pekerjaan yang menyenangkan sekaligus menjanjikan. Selain karena tingkat penghasilan yang relatif tinggi dibandingkan dengan pekerjaan di sektor lain yang menuntut kualifikasi serupa, mereka sangat menikmati kebebasan sebagai tukang ojek. Di lokasi AURI, seorang tukang ojek kadang bisa mendapatkan uang sampai Rp 100.000,- perhari. Jika penghasilan tersebut konstan maka minimal dia akan meraup Rp 3.000.000,- perbulan, suatu jumlah yang tentu saja sangat fantastis. Sedangkan di pangkalan Portal Cibubur, jumlah penghasilan hariannya relatif kecil karena penggunanya pun relatif terbatas. Yang jelas mereka sama-sama menikmati kebebasan yang tidak dijumpai kalau bekerja di sektor formal: tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menyuruh, dapat bekerja kapan saja, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa pandangan tukang ojek terhadap pekerjaannya agak variatif, baik di pangkalan Portal Cibubur yang begitu teratur maupun di pangkalan AURI yang agak semrawut. Yang berbeda adalah tingkat kompetisi. Di pangkalan Cibubur, iklim kompetisi tidak tampak. Hal itu disebabkan karena adanya pengaturan yang disepakati bersama dengan sistem antrian. Semua ojek mendapatkan kesempatan yang sama, apapun kualitas motornya. Sistem tersebut sekaligus mendorong adanya distribusi pendapatan relatif. Hal yang sebaliknya terjadi di pangkalan ojek AURI. Absennya aturan bersama menyebabkan persaingan yang begitu tinggi. Semua berebutan penumpang. Tingkat tarif pun terkadang berbeda yang sering memicu konflik dengan pengguna. Hal itu diperparah oleh tidak adanya interaksi di antara tukang ojek serta antara tukang ojek dengan pengguna. Hubungan yang terjalin adalah murni hubungan transaksional ekonomis, sedangkan relasi sosial kurang tampak. Mengenai pandangan terhadap pengguna, terdapat dua blok pandangan yang sangat kontras. Di pangkalan Portal Cibubur, sangat kelihatan adanya interaksi yang akrab antara tukang ojek dengan pengguna. Mereka sudah saling mengenal sehingga perlakuan terhadap pengguna pun lebih manusiawi. Artinya, pengguna benar-benar dilihat tidak sekedar sebagai partner transaksi ekonomis, tetapi juga sebagai Halaman 4 sesama manusia. Apabila ada sesama tukang ojek yang kurang hati-hati, maka akan diperingatkan oleh tukang ojek lainnya. Kondisi serupa tidak dijumpai di pangkalan ojek AURI. Sifat transaksional murni ditambah dengan rendahnya saling mengenal dan jalinan interaksi menyebabkan buruknya perlakukan terhadap pengguna. Mereka dapat memotong jalan seenaknya, menempuh arah yang berlawanan dengan arah lalu lintas, menjemput pengguna secara bersama-sama dan sebagainya. Hal itu tentu saja sangat membahayakan keselamatan pengguna. Lalu, bagaimana pandangan tukang ojek terhadap sesamanya? Pada aspek ini juga dijumpai kondisi yang sangat kontras. Di pangkalan ojek Cibubur, para tukang ojek adalah juga satu keluarga besar yang terikat oleh hubungan darah, persamaan latar belakang sosial budaya (orang Betawi), serta aturan dan norma yang disepakati bersama. Solidaritas di antara mereka sangat tinggi. Tegasnya, di pangkalan tersebut benar-benar terlihat adanya kekeluargaan dalam pengertian yang sesungguhnya. Hal sebaliknya terjadi di pangkalan ojek AURI. Di pangkalan tersebut, tidak dijumpai adanya kesepakatan bersama. Tingkat solidaritas pun relatif rendah. Hal itu dipengaruhi oleh variatifnya latar belakang sosial budaya mereka. Ada yang berasal dari suku Betawi, Jawa dan Sunda. Sesama tukang ojek dilihat sebagai komptitor. Hal itu berpengaruh terhadap interaksi yang terjalin di antara mereka. Tingkat kompetisi pun menjadi semakin ketat dan cenderung tidak ada saling kepedulian, apalagi solidaritas, di antara mereka. B. Perilaku Tukang Ojek Perilaku seseorang merupakan ekspresi cara pandangnya. Atau dapat juga dipahami sebagai respons ragawi terhadap rangsangan dari luar. Dalam tulisan ini, penulis beranggapan bahwa perilaku tukang ojek merupakan fungsi pandangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ditambah rangsangan lingkungan lainnya. Untuk keperluan sistematika, perilaku tukang ojek dapat dibagi ke dalam perilaku terhadap pengguna, perilaku terhadap sesama, dan perilaku terhadap aturan pemerintah. Terhadap pengguna jasa ojek, dijumpai adanya perilaku yang sangat berbeda di kedua pangkalan tersebut. Di pangkalan Cibubur, pengguna diperlakukan sebagai ‘konsumen yang berdaulat’. Mereka diperlakukan dengan ramah dan keselamatan mereka benar-benar diperhatikan. Ada 2 pola melayani pengguna di pangkalan ini, yaitu pertama, pengguna mendatangi tukang ojek, dan kedua, tukang ojek yang mendatangi pengguna. Pola kedua biasanya hanya untuk penumpang yang harus menyeberang. Perilaku yang sangat berbeda dijumpai di pangkalan AURI. Di pangkalan tersebut, penumpang diperlakukan seenaknya. “Yang penting terima duit dan saya harus segera kembali untuk merebut penumpang berikutnya,’ kira-kira seperti itulah bayangan yang ada dalam pikiran tukang ojek sehingga perilaku mereka sangat ngawur: memotong jalan seenaknya, merebut penumpang, parkir seenaknya dan sebagainya. Kondisi yang nyaris serupa juga dijumpai dalam hal perilaku terhadap sesama tukang ojek. Tidak ada basa-basi atau tegur sapa yang benar-benar ‘lepas’ di antara sesama tukang ojek. Dengan melihat sesamanya sebagai kompetitor dan tidak ada aturan yang mengarahkan perilaku mereka, maka mereka saling berebutan untuk mendapatkan pengguna dan daerah strategis, yaitu sisi jalan luar paling dalam atau justru agak jauh dari perempatan. Hal itu terjadi karena angkutan umum akan berhenti dan menurunkan penumpangnya sebelum perempatan. Sebaliknya, angkutan umum yang kosong akan berhenti tepat di perempatan untuk menunggu penumpang yang dibawa tukang ojek. Tampak ada hubungan mutualistis di antara tukang ojek dengan sopir angkutan umum, hal mana tidak terlihat di antara sesama tukang ojek. Tidak adanya aturan yang mengarahkan interaksi tukang ojek sering menyebabkan beberapa gesekan konflik di antara tukang ojek. Misalnya, untuk memperebutkan posisi strategis, sering terjadi tabrakan ringan di antara motror. Demikian halnya dengan saling membentak pada saat terjadi kemacetan sebagai akibat lanjut dari perilaku menyeberang yang cenderung ngawur. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di pangkalan Cibubur. Di sana, antara tukang ojek terdapat interaksi yang sangat akrab. Mereka selalu mengisi kekosongan dengan bersenda gurau atau permainan-permainan ringan. Tidak ada nuansa konflik dalam interaksi mereka. Yang ada adalah suasana kekeluargaan. Halaman 5 LESSON DRAWING Dalam melakukan penelitian ini, penulis menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan kesulitan menjaring data. Selain karena singkatnya waktu, penelitian etnografi mensyaratkan adanya kontak yang intensif dengan serta kepercayaan dari obyek yang diteliti. Pada tahap awal sempat timbul kecurigaan terhadap kehadiran peneliti yang dengan berjalannya waktu akhirnya hilang. Terlepas dari kendala tersebut, penelitian singkat ini mengandung beberapa aspek yang dapat dijadikan bahan pembelajaran atau yang dikenal dengan lesson drawing. Wujudnya dapat berupa pesan-pesan moral atau tawaran praktis untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tiga aspek yang dinilai penting oleh penulis dan sejalan dengan topik penelitian ini akan dipaparkan berikut ini. A. Pentingnya Modal Sosial Paparan sebelumnya, sejalan dengan kerangka berpikir yang dikembangkan di depan, semakin memperkuat argumen penulis akan pentingnya modal sosial baik sebagai suplemen maupun komplemen hukum publik. Proposisi bahwa modal sosial seharusnya menjadi elemen pokok dalam formulasi dan operasionalisasi hukum publik berangkat dari kenyataan bahwa eksesifnya peran dan posisi negara telah menjadi salah satu penyebab – bahkan penyebab utama – tidak bekerjanya kerangka institusional yang ada. Hukum publik yang paling otoritatif pun seolah kehilangan daya paksanya manakala tidak ditopang oleh modal sosial. Robert Putman – penulis yang pertama kali memperkenalkan terminologi tersebut – menemukan bahwa ternyata terdapat korelasi yang sangat signifikan antara perwujudan demokrasi dengan nilai-nilai sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Korelasi yang sama juga ditemukan dalam dinamika pembangunan sosial ekonomi. Secara sederhana modal sosial dapat didefinisikan sebagai “…the collective value of all "social networks" [who people know] and the inclinations that arise from these networks to do things for each other ["norms of reciprocity"] (Putman, 1993). Atau juga dapat dipahami sebagai “…features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit..” (La Jolla Institute, 1999). Konsepsi tersebut memperlihatkan bahwa modal sosial memiliki dua dimensi pokok yaitu jaringan sosial dan norma resiprokal. Di dalamnya terdapat dan dikembangkan sistem interaksi yang ditandai oleh kehangatan, saling berbagi informasi, kerjasama, saling membantu, gotong royong, adanya aksi kolektif, identitas bersama dan solidaritas. Nilai-nilai tersebut begitu melekat dan mengikat para anggotanya yang tidak jarang menyebar ke masyarakat atau kelompok lain di sekitarnya (bystanders). Dengan karakter yang demikian, semua anggota terikat untuk mematuhinya jika tidak ingin terkena sanksi sosial dari anggota lainnya. Untuk masyarakat dengan tingkat perkembangan sedang – atau bahkan terbelakang dalam aspek-aspek tertentu – nilai-nilai tersebut begitu dihargai sehingga sangat dipatuhi. Tipikal masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang belum terlalu terkena polusi modernisasi dengan segala implikasinya. Modal sosial tidak saja menjadi pelengkap hukum publik yang sudah ada, tetapi bisa menjadi pengganti bila terdapat kekosongan. Misalnya, sampai saat ini, belum ada aturan resmi yang mengatur aktivitas ojek: persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, bagaimana mekanisme penentuan harga, di mana mereka harus beroperasi dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, modal sosial bisa tampil sebagai pengganti sehingga keteraturan publik (public order) tetap dapat diciptakan dan ditegakkan walaupun tidak dengan kekuatan otoritatif regulasi negara. Dalam wujudnya yang paling sederhana, kehadiran modal sosial sebagai pengganti aturan publik merupakan manifestasi pergeseran peran pemerintah di mana masyarakat semakin mendapat ruang untuk mengekspresikan potensi dan kontribusinya. Walaupun sangat fungsional, modal sosial bukan tanpa kelemahan. Kelemahan utama terletak pada eksklusivitasnya. Artinya, nilai-nilai tersebut hanya berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu dan tidak untuk kelompok masyarakat lainnya. Sifat eksklusif tersebut sekaligus menjadi pembatas efektivitasnya. Dengan kata lain, modal sosial hanya efektif untuk kategori kelompok tertentu dan tidak untuk kategori lainnya. Konflik akan timbul manakala terdapat dua modal sosial yang saling bertentangan dari dua kelompok yang berbeda yang terlibat dalam arean interaksi tertentu. Dalam konteks yang demikian, modal sosial tidak dapat menjelma menjadi hukum publik – dalam pengertian tata aturan umum yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat, dan bukan hukum publik dalam pengertian aturan hukum formal pemerintah – karena adanya pertentangan nilai. Kalaupun dipaksakan maka akan timbul Halaman 6 “fenomena leviatan pluralistik” di mana masing-masing kategori modal sosial akan mengklaim sebagai yang paling otoritatif bagi kebajikan publik. Klaim yang demikian justru menjadi ancaman nyata bagi efektivitas hukum publik itu sendiri yang mau tidak mau harus diterapkan secara diskriminatif atau berstandar ganda. Eksplanasi terhadap fenomena tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan gambaran aktivitas tukang ojek sebagai referensinya, walaupun pada taraf kualifikasi justifikasi yang masih sangat terbatas. B. Jenis Modal Sosial Para tukang ojek, dengan tingkat kompleksitas aktivitas yang relatif masih rendah, memiliki nilainilai tersendiri yang mungkin hanya dipahami oleh mereka sendiri dan para penggunanya. Namun kepemilikan modal sosial itu terbatas pada lokasi di mana terjadi interaksi yang intens di antara para anggota. Dengan interaksi yang intens dimungkinkan adanya saling pengertian, terbentuknya kesepakatan bersama, solidaritas dan nilai-nilai semacamnya. Bentuk modal sosial yang mengikat secara internal ini membawa dampak yang positif, tidak saja bagi para anggotanya tetapi juga bagi pihak lain yang terlibat dalam interaksi tersebut. Misalnya dengan penumpang, penjual makanan kecil di sekitarnya, serta pihak lain yang biasa menjadikan tukang ojek sebagai sumber informasi. Kondisi itu dijumpai di pangkalan ojek Portal Cibubur. Sebagaimana digambarkan sebelumnya, tukang ojek di pangkalan tersebut sudah saling mengenal dengan baik. Mereka berasal tidak saja dari satu suku, yaitu Suku betawi, tetapi juga masih memiliki hubungan darah, kecuali 3 orang lain yang berasal dari Jawa. Dengan ikatan pertalian yang demikian, mereka dapat dengan mudah membangun kesepakatan dalam melakukan aktivitasnya. Misalnya adanya kesepakatan tentang sistem antrian, gotong royong dalam membangun pangkalan sehingga ada tempat berteduh yang cukup nyaman, dan adanya tingkat tarif yang sama. Mereka juga menegakkan kontrol sosial yang cukup efektif untuk mengatur perilaku para anggotanya sehingga tidak membahayakan pengguna sekaligus tidak merusak citra tukang ojek. Adanya kohesivitas internal juga memungkinkan terjalinnya interaksi yang baik dengan pengguna. Hal itu pada gilirannya menciptakan kenyamanan bagi pengguna sehingga tidak perlu ada rasa was-was dalam menggunakan jasa ojek. Dengan kata lain, adanya modal sosial memungkinkan terciptanya interaksi sosial yang sangat baik antara tukang ojek dengan pengguna. Jadi, tidak hanya berhenti pada hubungan transaksional yang bersifat ekonomis-instrumental. Adanya kontrol sosial yang baik sekaligus dapat menekan potensi konflik yang bisa timbul, baik di antara sesama tukang ojek, tukang ojek dengan pengguna, maupun antara tukang ojek dengan pihak lainnya. Bahkan soal tarif pun tidak pernah terjadi konflik. Kesalahpahaman soal tarif hanya mungkin terjadi dengan para pengguna baru. Kondisi tersebut sangat kontras dengan realitas yang dijumpai di Pangkalan Ojek AURI. Di pangkalan tersebut tidak dijumpai adanya varian modal sosial dalam bentuk apapun. Selain tidak adanya aturan bersama juga dijumpai rendahnya tingkat interaksi, baik di antara tukang ojek dengan pengguna maupun di antara sesama tukang ojek. Hubungan yang terjalin di antara mereka murni merupakan hubungan transaksional. Penelusuran singkat di wilayah tersebut menemukan adanya beberapa implikasi negatif yang cukup serius. Yang paling nyata adalah terjadinya kemacetan akibat ulah para tukang ojek, walaupun mereka bukan penyebab satu-satunya. Parkir yang semrawut, bahkan mengambil arah yang berlawanan dengan arah lalu lintas sebenarnya, menjadi penyebab kemacetan tersebut. Selain kemacetan, implikasi negatif lain adalah tidak adanya kontrol sosial. Semua cenderung berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya adalah lemahnya posisi tawar mereka jika harus berhadapan dengan pihak luar. Dalam negosiasi harga misalnya, tidak ada standar umum antara mereka. Terkadang mereka hanya berharap pada kemurahan pengguna. Dengan sendirinya, kalau biaya yang diberikan pengguna lebih rendah yang yang biasanya atau yang mereka harapkan maka akan terjadi konflik. Dalam kondisi itu, repotnya lagi, pengguna sering ‘mengadu domba’ tukang ojek. Misalnya dengan menyatakan bahwa mengapa ada perbedaan harga antara satu tukang ojek dengan tukang ojek lainnya. Yang dijadikan standar tentu saja lebih rendah dari yang seharusnya. Halaman 7 C. Efektivitas Hukum Publik Selama ini hukum publik merupakan domain eksklusif negara: dikonstruksi dan ditegakkan sepenuhnya oleh negara. Sementara masyarakat menjadi aktor pasif yang hanya bisa dijadikan obyek. Robert Putman melihat bahwa penyebab utama kegagalan mekanisme institusional negara dalam menyelenggarakan berbagai urusan publik adalah kepatuhan dan ketergantungan masyarakat yang begitu besar terhadap mekanisme tersebut. Jalan keluar yang ditawarkan adalah konstruksi mekanisme baru yang memungkinkan terciptanya burden-sharing antara negara dengan aktor lainnya terutama masyarakat. Dalam konteks bahasan ini, formulasi dan penegakan hukum publik dapat digeser kepada masyarakat dengan menyiapkan kerangka interaksi sehingga dapat mengakomodasi potensi dan kontribusi masyarakat. Dalam artian yang paling riil, masyarakat dapat menegakkan hukum publik dalam aspek tertentu yang dimungkinkan yang memang tidak perlu diatur oleh negara tetapi bersentuhan langsung dengan kepentingannya. Jika masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri maka ada beberapa hal positif yang dapat diraih. Dalam kasus pangkalan ojek Portal Cibubur, sangat kelihatan adanya komitmen dan rasa memiliki yang tinggi terhadap apa yang menjadi ‘hukum publik’ mereka walaupun bentuknya hanya berupa kesepakatan bersama yang menjelma menjadi aturan atau norma perilaku. Selain komitmen dan rasa memiliki, juga muncul tanggung jawab sosial, baik tanggung jawab terhadap korps tukang ojek maupun terhadap penggunanya. Adanya kontak yang intens di antara mereka semakin memperkuat efektivitas hukum publik tersebut. Aspek-aspek positif itu selaras dengan kajian beberapa ilmuwan sosial seperti Herbert Rubin dan Irene Rubin (1986) atau Jim Ife (1996) di samping Robert Putman sendiri yang terangkum dalam konsep modal sosial. Jika concern-nya adalah efektivitas hukum publik, yaitu sejauh mana hukum publik dapat diberlakukan secara efektif serta diterima dan dipatuhi secara luas oleh masyarakat, maka aspek lain yang harus disoroti – dan itulah fokus perhatian penelitian ini – adalah sejauh mana pertimbangan efektivitas mendapatkan tempat dalam kerangka perumusan hukum publik yang masih menjadi domain negara dan bersifat legal formal? Terdapat kecenderungan yang cukup umum bahwa pertimbangan efektivitas ditundukkan di bawah arogansi negara dengan implikasi semakin meluasnya ketidakteraturan di ranah kehidupan publik. Pelajaran penting dari penelitian ini, oleh karenanya, adalah bagaimana negara memposisikan dirinya secara tepat dalam pengaturan kehidupan publik sehingga masyarakat pun mendapatkan ruang ekspresi tanggung jawab sosialnya. Dalam pengertian yang paling sederhana, wujud reposisi diri tersebut adalah berupa penarikan diri dari intervensi yang tidak perlu pada ranah-ranah yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat. Dan dalam konteks ini, intervensi hanya dibatasi pada peran regulasi serta peran-peran strategis lainnya sehingga preskripsi good governance bahwa ‘the best governance is the lest government’ boleh jadi menemukan relevansinya di sini. KESIMPULAN Pertama, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara persepsi dan perilaku tukang ojek pangkalan ojek Portal Cibubur dengan persepsi dan perilaku tukang ojek di perempatan perumahan AURI. Basis eksplanasinya dapat ditemukan pada adanya ‘hukum publik’ berupa konsensus di pangkalan Portal Cibubur, hal mana tidak dijumpai di pangkalan permpatan perumahan AURI. Kedua, efektivitas hukum publik dalam mengatur kehidupan bersama selanjutnya ditentukan oleh adanya modal sosial seperti kesepakatan, ikatan emosional dan kekerabatan, solidaritas, intensitas interaksi yang cukup tinggi, serta saling percaya. Ketiga, paralel dengan kesimpulan kedua, maka dapat pula dikatakan bahwa efektivitas hukum publik ditentukan oleh (1) sejauh mana pemerintah sebagai pembentuk hukum publik mengakomodasi berbagai modal sosial yang dimiliki masyarakat sehingga terdapat semacam sistem penegakan hukum publik berbasis masyarakat lokal, (2) dibatasinya intervensi pemerintah sehingga ranah tertentu yang dapat dikelola secara mandiri dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat. Halaman 8 Keempat, jauh dari sebuah kacamata dikotomis antara “perspektif evolusionis-developmentalis dan involusionis-eksploitatif”, kehadiran sektor formal yang dalam penelitian ini direpresentasikan oleh ojek memiliki kedua nilai tersebut sekaligus. Kehadiran ojek bisa menambah permasalahan di wilayah perkotaan, terutama kemacetan lalu lintas dan praktek eksploitatif oleh pihak lain, namun sektor tersebut juga memberikan sebuah tawaran yang sangat menjanjikan bagi penciptaan lapangan kerja dengan tingkat penghasilan yang relatif memadai. Kehadirannya juga dapat mengisi kebutuhan dinamika masyarakat perkotaan yang kurang memiliki akses terhadap sarana transportasi umum. Persoalannya justru terletak bagaimana pola pengelolaan yang baik di mana modal sosial dapat menjadi penopang utamanya Halaman 9 REFERENSI Barofsky, R. 1987. Making History: Puka Pukan and Anthropological Constructions of Knowledge, Cambridge: cambrigde University Press. Gilbert, Allan, & Josef Gugler, 1984. Cities, Poverty and Development, Oxford: Oxford University Press Ife, Jim, 1996, Community Development, Melbourne: Longman La Jolla Institute, 1999. Civic Participation, Social Capital and Leadership, Memoir, January 23. Portes, Alejandro, 1989. “Word Uderneath: The Origins, Dynamics and Effects of the Informal Economy,” in Alejandro Portes, et.al., (eds.), The Informal Economy, Baltimore: The John Hopkins University Press, Pp.11-40. Putnam, Robert D., 1993. Making Democracy Work. Princeton, NJ: Princeton University Press. Putman, Robert., 1995. “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital,” in Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, January. Pp. 65-78 Rakodi, Carole, 1993. “Planning for Whom?,” in Nick Devas & Carole Rakodi, Managing Fast Growing Cities, Princeton: Princeton University Press., Pp. 207-235 Rubin, Herbert J. and Irene Rubin, 1986. Community Organizing and Development, Ohio: Merrill Publishing Company Halaman 10