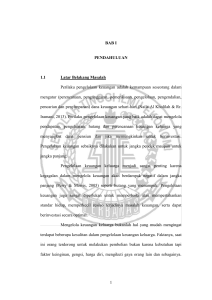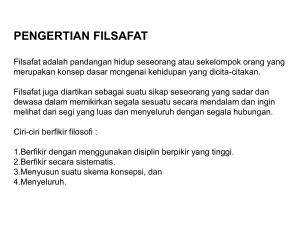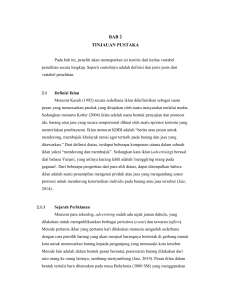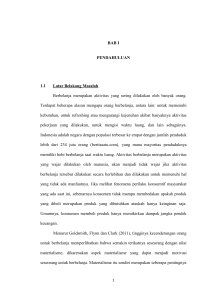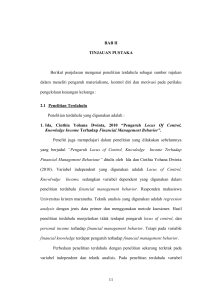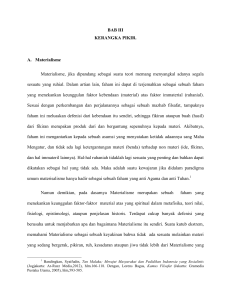2.1.2. Dimensi Materialisme
advertisement
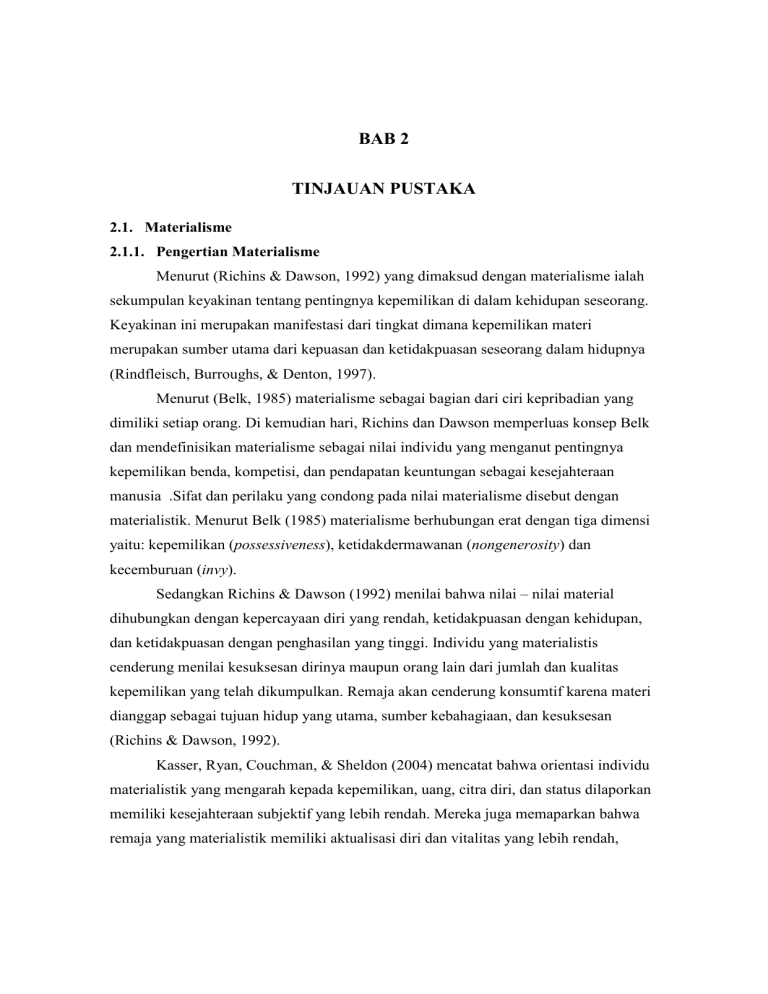
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Materialisme 2.1.1. Pengertian Materialisme Menurut (Richins & Dawson, 1992) yang dimaksud dengan materialisme ialah sekumpulan keyakinan tentang pentingnya kepemilikan di dalam kehidupan seseorang. Keyakinan ini merupakan manifestasi dari tingkat dimana kepemilikan materi merupakan sumber utama dari kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dalam hidupnya (Rindfleisch, Burroughs, & Denton, 1997). Menurut (Belk, 1985) materialisme sebagai bagian dari ciri kepribadian yang dimiliki setiap orang. Di kemudian hari, Richins dan Dawson memperluas konsep Belk dan mendefinisikan materialisme sebagai nilai individu yang menganut pentingnya kepemilikan benda, kompetisi, dan pendapatan keuntungan sebagai kesejahteraan manusia .Sifat dan perilaku yang condong pada nilai materialisme disebut dengan materialistik. Menurut Belk (1985) materialisme berhubungan erat dengan tiga dimensi yaitu: kepemilikan (possessiveness), ketidakdermawanan (nongenerosity) dan kecemburuan (invy). Sedangkan Richins & Dawson (1992) menilai bahwa nilai – nilai material dihubungkan dengan kepercayaan diri yang rendah, ketidakpuasan dengan kehidupan, dan ketidakpuasan dengan penghasilan yang tinggi. Individu yang materialistis cenderung menilai kesuksesan dirinya maupun orang lain dari jumlah dan kualitas kepemilikan yang telah dikumpulkan. Remaja akan cenderung konsumtif karena materi dianggap sebagai tujuan hidup yang utama, sumber kebahagiaan, dan kesuksesan (Richins & Dawson, 1992). Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon (2004) mencatat bahwa orientasi individu materialistik yang mengarah kepada kepemilikan, uang, citra diri, dan status dilaporkan memiliki kesejahteraan subjektif yang lebih rendah. Mereka juga memaparkan bahwa remaja yang materialistik memiliki aktualisasi diri dan vitalitas yang lebih rendah, demikian juga dengan kecenderungan lebih banyak untuk mengalami depresi dan kecemasan. 2.1.2. Dimensi Materialisme Richins & Dawson (1992) menyatakan bahwa materialisme mencakup 3 dimensi yaitu sebagai berikut: Acquisition Centrality, yaitu nilai yang menganggap bahwa penting untuk memiliki materi guna mencapai tujuan hidup. Happiness, yaitu kepemilikan sebagai keharusan untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan dalam hidup. Success, yaitu kepercayaan bahwa kesuksesan seseorang dinilai dari materi-materi yang mereka miliki. 2.1.3. Penyebab Materialisme Ada beberapa faktor yang menyebabkan materialisme (Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon, 2004) yaitu sebagai berikut: Insecurity, yaitu kecenderungan individu untuk mengatasi rasa cemas dan ragu tentang perasaan berharga, mengatasi tantangan secara efektif, dan perasaan aman terhadap dunia yang sulit diprediksi; dengan cara memiliki materi-materi dalam rangka mengatasi perasaan tidak aman (insecurity) tersebut. Keterpaparan terhadap model dan nilai materialisme, dalam bentuk pesan-pesan implisit dan eksplisit yang menampilkan pentingnya uang dan kepemilikan. Gaya hidup yang materialistik pada anggota keluarga dan teman sebaya, juga yang ditampilkan oleh media, menimbulkan materialisme pada individu. Pengiklanan dan penyebaran kapitalisme. Iklan-iklan yang terpengaruh oleh kapitalisme memperlihatkan model-model yang dapat menimbulkan perasaan inferioritas. Oleh karena itu, individu yang terpengaruh akan berusaha mengurangi rasa inferioritas itu dengan cara memiliki uang atau materi-materi lainnya yang ditampilkan oleh iklan tersebut. 2.1.4. Dampak Materialisme Ada tiga hal yang menjadi dampak dari materialisme menurut Kasser, Ryan, Couchman, & Sheldon (2004), yaitu: Competence. Individu yang materialistik mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan akan perasaan kompeten. Materialisme dihubungkan dengan rendahnya self-esteem dan narsisistik. Orang yang materialistik juga sering membandingkan dirinya dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan perasaan buruk terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, individu akan menjadi semakin materialistik, padahal riset menyatakan bahwa tujuantujuan yang bersifat materialistik berefek kecil dalam meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Relatedness. Hubungan interpersonal antara individu-individu yang materialistik relatif singkat dan ditandai dengan reaksi emosi yang ekstrim dan konflik, bukan dengan kepercayaan dan kebahagiaan. Autonomy. Autonomy adalah perasaan bahwa individu memiliki pilihan, kepemilikan, dan keterlibatan yang mendalam terhadap aktivitas individu tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materialism merupakan keyakinan utama individu bahwa uang dan kepemilikan atau kekayaan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang relative tinggi dan menonjol dalam kehidupan seseorang dibandingkan penerimaan diri, persahabatan, serta rasa kemanusiaan sehingga individu menjadi setia dan taat pada kebutuhan serta keinginan terhadap materi. Uang dan kepemilikan atau kekayaan juga dianggap sebagai sumber kebahagiaan serta kepuasan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya, dengan demikian tolak ukur kesuksesan individu didasarkan pada kesuksesan materi. Tingkat materialisme seseorang dapat dipengaruhi banyak faktor lingkungan, termasuk komunikasi keluarga, komunikasi dengan teman sebaya, dan ekspos televisi (John, 1999 dalam Clark, Martin, & Bush, 2001). 2.2. Psychological well being 2.2.1. Pengertian Psychological well being Ryff (1989) mendefinisikan psychological well being sebagai hasil atau penilaian seseorang terhadap dirinya yang merupakan evaluasi atas pengalamanpengalaman hidupnya. Berdasarkan teori Ryff (1989) mendefinisikan psychological well being sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya. Psychological well being oleh Ryff (1989) suatu keadaan dimana individu ampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontorol lingkungan eksternal, memiliki arti hidup, serta mampu merealisasikan potensi diri secara kontinyu. Menurut Ryff (1989) psychological well being adalah sebuah konsep yang berusaha untuk menggambarkan kesehatan psikologis individu berdasarkan pemenuhan kriteria fungsi psikologi positif. Individu yang memiliki psychological well being yang positif adalah orang yang mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinyu, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, maupun menerima diri apa adanya, memiliki arti dalam hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal (Papalia, Olds, & Feldman, 2009). 2.2.2. Dimensi Psychological well being Dimensi-dimensi yang membentuk psychological well-being menurut Ryff (dalam Wells, 2010) : 1. Penerimaan diri (Self-acceptance) Penerimaan diri yang dimaksud adalah kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan baik pada masa kini dan masa lalunya. Seseorang yang menilai positif diri sendiri adalah individu yang memahami dan menerima berbagai aspek diri termasuk di dalamnya kualitas baik maupun buruk, dapat mengaktualisasikan diri, berfungsi optimal dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalaninya. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki tingkat penerimaan diri yang kurang baik yang memunculkan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, merasa kecewa dengan pengalaman masa lalu, dan mempunyai pengharapan untuk tidak menjadi dirinya saat ini. 2. Hubungan positif dengan orang lain (positif relation with others) Hubungan positif yang dimaksud adalah kemampuan individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Individu yang tinggi dalam dimensi ini ditandai dengan mampu membina hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dari orang lain. Ryff menekankan pentingnya menjalin hubungan saling percaya dan hangat dengan orang lain. Sebaliknya, individu yang hanya mempunyai sedikit hubungan dengan orang lain, sulit untuk bersikap hangat dan enggan untuk mempunyai ikatan dengan orang lain, menandakan bahwa ia kurang baik dalam dimensi ini. 3. Otonomi (autonomy) Dimensi otonomi menjelaskan mengenai kemandirian, kemampuan untuk menentukan diri sendiri, dan kemampuan untuk mengatur tingkah laku. Seseorang yang mampu untuk menolak tekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah laku dengan cara-cara tertentu, serta dapat mengevaluasi diri sendiri dengan standar personal, hal ini menandakan bahwa ia baik dalam dimensi ini. Sebaliknya, individu yang kurang baik dalam dimensi otonomi akan memperhatikan harapan dan evaluasi dari orang lain, membuat keputusan berdasarkan penilaian orang lain, dan cenderung bersikap konformis. 4. Penguasaan lingkungan (environmental mastery) Individu dengan PWB yang baik memiliki kemampuan untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi fisik dirinya. Dengan kata lain, ia mempunyai kemampuan dalam menghadapi kejadian-kejadian diluar dirinya. Hal inilah yang dimaksud dalam dimensi ini mampu untuk memanipulasi keadaan sehingga sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi yang dianutnya dan mampu untuk mengembangkan diri secara kreatif melalui aktivitas fisik maupun mental. Sebaliknya, individu yang kurang baik dalam dimensi ini akan menampakkan ketidakmampuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungan luar. 5. Tujuan Hidup (purpose in life) Dimensi ini menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mencapai tujuan dalam hidup. Seseorang yang mempunyai rasa keterarahan dalam hidup, mempunyai perasaan bahwa kehidupan saat ini dan masa lalu mempunyai keberartian, memegang kepercayaan yang memberikan tujuan hidup, dan mempunyai target yang ingin dicapai dalam hidup, maka ia dapat dikatakan mempunyai dimensi tujuan hidup yang baik. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik dalam dimensi ini mempunyai perasaan bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam hidup, tidak melihat adanya manfaat dalam masa lalu kehidupannya, dan tidak mempunyai kepercayaan yang dapat membuat hidup lebih berarti. Dimensi ini dapat menggambarkan kesehatan mental karena kita. 6. Pertumbuhan pribadi (personal growth) Dimensi pertumbuhan pribadi menjelaskan mengenai kemampuan individu untuk mengembangkan potensi dalam diri dan berkembang sebagai seorang manusia. Dimensi ini dibutuhkan oleh individu agar dapat optimal dalam berfungsi secara psikologis. Salah satu hal penting dalam dimensi ini adalah adanya kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, misalnya dengan keterbukaan terhadap pengalaman. Seseorang yang baik dalam dimensi ini mempunyai perasaan untuk terus berkembang, melihat diri sendiri sebagai sesuatu yang bertumbuh, menyadari potensi yang terdapat di dalam dirinya, dan mampu melihat peningkatan dalam diri dan tingkah laku dari waktu ke waktu. Sebaliknya, seseorang yang kurang baik dalam dimensi ini akan menampilkan ketidakmampuan untuk mengembangkan sikap dan tingkah laku baru, mempunyai perasaan bahwa ia adalah seorang pribadi yang stagnan, dan tidak tertarik dengan kehidupan yang dijalani. 2.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Psychological well being Menurut Ryff dan Singer (dalam Anwar & Hidayat, 2008) faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well being seorang individu adalah sebagai berikut: a) Usia Menunjukan bahwa penguasaan lingkungan dan otonomi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya usia. Pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup menunjukkan penurunan seiring dengan bertambahnya usia. Hubungann positif dengan orang lain dan penerimaan diri secara signifikan bervariasi berdasarkan usia. b) Jenis Kelamin Menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam aspek menjalin hubungan dengan orang lain dan pertumbuhan pribadi antara pria dan wanita. Sementara penerimaan diri, otonomi dan keyakinan bahwa hidup mempunyai makna dan tujuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. c) Budaya Memperlihatkan bahwa sisi nilai budaya yang berbeda seperti individualistik mempengaruhi psychological well being pada dimensi penerimaan diri dan otonomi sedangkan pada masyarakat dengan nilai budaya kolektif menunjukkan pengaruh yang tinggi terhadap dimensi hubungan positif dengan orang lain. d) Status Sosial Ekonomi Meliputi faktor pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan dapat mempengaruhi psychological well being pada dimensi penerimaan diri memiliki tujuan dalam hidup, penguasaan lingkungan dan pertumbuhan. 2.3. Pekerja Seks Komersial 2.3.1. Pengertian Pekerja Seks Komersial Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) pelacuran atau prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai istilah yang dipergunakan untuk menunjuk pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK), seperti : Prostitusi, Pelacur, Wanita Nakal, Wanita Tuna Susila (WTS), Wanita Penghibur, Kupu-kupu Malam dan masih banyak lagi nama-nama lain untuk panggilan wanita PSK yang dikenal dalam masyarakat. Namun kesepakatan umum adalah “prostitusi atau prostitution” dan pelacuran atau PSK. Kata prostitusi berasal dari kata latin yaitu pro-situere atau prostaturee yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pengendakan (Kartini, 2005). 2.3.2. Faktor Sosio-Kultural Remaja Perempuan Menjadi Pekerja Seks Komersial Koentjoro (2004) menyatakan terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor sosio-kultural yang menyebabkan perempuan menjadi pekerja seks komersial (PSK) : 1) Orang setempat yang menjadi model pelacur yang sukses. Bahwa ketika pelacur kembali ke desanya, mereka memamerkan gaya hidup mewah dengan maksud memancing kecemburuan orang lain. 2) Sikap permisif dari lingkungannya. Bahwa ada desa tertentu yang bangga dengan reputasi bisa mengirimkan banyak pelacur ke kota. Serta banyak keluarga pelacur yang mengetahui bahkan mendukung kegiatan anak atau istri mereka karena dapat menerima uang secara teratur. Para pelacur sangat sering membagikan makanan dan materi yang dimilikinya kepada para tetangganya. Wajar jika kemudian banyak pelacur dikenal sebagai orang yang dermawan . Keadaan tersebut berangsur-angsur menimbulkan sikap toleran terhadap keberadaan pelacur. 3) Adanya peran instigator (penghasut). Instigator sering diartikan sebagai pihak-pihak tertentu yang memberikan pengaruh buruk, dalam hal ini adalah orang yang mendorong seseorang menjadi pelacur. Instigator itu sendiri diantaranya adalah orangtua, suami, pelacur, bekas pelacur atau mucikari (mereka adalah suami yang menjual istri atau orangtua yang menjual anak-anaknya untuk mendapatkan barang-barang mewah). 4) Peran sosialisasi. Di beberapa daerah di Jawa, ada kewajiban yang dibebankan dipundak anak untuk menolong, mendukung dan mempertahankan hubungan baik dengan orangtua ketika orangtua mereka lanjut usia. Jika anak perempuan dianggap sebagai padi atau barang dagangan, maka harapan orangtua semacam ini secara sadar atau tidak sadar akan mempengaruhi anak perempuan mereka. Karena pelacuran telah menjadi produk budaya, maka dapat diasumsikan bahwa sosialisasi pelacuran telah terjadi sejak usia dini. 5) Ketidakefektifan pendidikan dalam meningkatkan status sosial ekonomi. Sebagain orang memandang pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial ekonomi dan kualitas kehidupan. Ketiadaan jaminan keamanan sosial ditengah-tengah keterbatasan lapangan pekerjaan tentu menjadi sebuah masalah besar bagi rakyat yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tidak memadai. Oleh karena itu, orangtua rela mengeluarkan uang banyak untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi karena keterbatasan lapangan pekerjaan, setelah lulus pendidikan belasan tahun pun banyak anak yang tidak mendapatkan pekerjaan. Dilain pihak, perempuan muda yang menjadi pelacur ketika lulus SD, ditahun- tahun berikutnya sudah dapat membangun rumah dan menikmati gaya hidup mewah. Dalam beberapa kasus, dapat dimengerti bahwa pilihan melacur pada komunitas tertentu dianggap sebagai pilihan yang rasional. 2.4. Remaja 2.4.1. Pengertian Remaja Menurut Golinko (dalam Rice & Dolgin, 2008) “remaja” berasal dari bahasa latin yaitu ‘adolescere’ yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Dalam Kamus Psikologi, remaja merupakan suatu tahap periodisasi perkembangan manusia yang berada pada di antara usia pubertas sampai dengan memasuki usia dewasa. Batasan remaja yang digunakan untuk masyarakat Indonesia, yaitu mereka yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah (Sarlito, dalam Gunarsa, 2006). Bagi mereka yang berusia 11-24 tahun tetapi sudah menikah tidak lagi disebut remaja. Sementara mereka yang berusia 24 tahun keatas tapi belum menikah dan masih menggantungkan hidupnya kepada orang tua, masih disebut remaja (Gunarsa, 2006). 2.4.2. Batas Usia Remaja Batasan usia yang digunakan pada tahap perkembangan remaja berdasarkan Papalia, Olds & Feldman (2009) dimulai dari usia 12 tahun hingga usia 20 tahun. Berbeda dengan Hurlock (1978) yang membagi masa remaja menjadi dua tahap, yaitu masa remaja awal yang dimulai pada usia 13 hingga 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu pada usia 17 hingga 22 tahun. Adanya pembedaan yang dilakukan oleh Hurlock tersebut dikarenakan pada masa remaja akhir individu telah mencapai transisi perkembangan yang lebih mendekati masa dewasa. Sedangkan di Indonesia, untuk menentukan batasan usia masa remaja mempunyai beberapa kesulitan. Menurut Sarwono (2006), hal tersebut disebabkan oleh sulitnya menentukan umur permulaan masa dewasa. Selain itu juga karena negara Indonesia mempunyai kebudayaan yang beragam antara daerah yang satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk menentukan batasan usia remaja. Sebagai contoh di beberapa daerah di Indonesia, anak yang sudah mencapai tinggi badan menyamai tinggi badan orangtuanya sudah dianggap dewasa. Anak yang sudah dianggap dewasa akan dicarikan jodohnya dan akan dinikahkan. Namun, di daerah lain di Indonesia menggolongkan anak tersebut sebagai ‘anak tanggung’. Hal itu karena mereka bukan merupakan anakanak lagi, tetapi juga belum dipastikan bahwa mereka telah mencapai kedewasaan. Dari sudut hukum, kedewasaan ditentukan dari umur dan status pernikahan. Dengan demikian mereka yang sudah menikah walaupun usianya kurang dari 17 tahun, sudah dianggap dewasa dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Maka dari itu, batasan usia remaja yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada batasan usia remaja Indonesia yang dinyatakan oleh Sarwono (2006) sebagai batasan usia remaja untuk masyarakat Indonesia adalah 11 sampai 24 tahun dan belum menikah, dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Usia belasan tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik). 2. Dari banyaknya masyarakat Indonesia, usia sebelas tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan remaja sebagai anak-anak (kriteria sosial). 3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologis). 4. Batas usia 24 tahun merupakan batas usia maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa. 2.4.3. Perkembangan Sosial Remaja Pada Teori Erikson, usia remaja yang berada antara 10 sampai 20 tahun berada pada tahap identity versus identity confusion. Remaja dihadapkan pada pertanyaan siapakah diri mereka sebenarnya, apakah mereka, dan hendak kemana mereka menuju dalam hidupnya. Remaja dihadapkan pada peran baru dan status dewasa yang berkaitan dengan pekerjaan dan asmara. Orang tua sebaiknya memberi kesempatan pada remaja untuk mengeksplorasi peran yang berbeda dan jalan yang berbeda dalam peran tertentu. Bila remaja mengeksplorasi peran tersebut dalam cara yang baik dan mendapatkan jalan yang positif untuk diikuti dalam hidupnya, identitas positif akan terbentuk. Jika remaja kurang mengeksplorasi peran yang berda dan jalan ke masa depan yang positif tidak ditentukan maka kekacauan identitas akan terjadi (Santrock, 2003). Banyak remaja memandang teman sebaya adalah aspek terpenting dalam kehidupan mereka. Beberapa remaja akan melakukan apapun supaya menjadi anggota dalam sebuah kelompok. Bagi remaja, dikucilkan berarti stress, frustasi, dan kesedihan. Sullivan (dalam Santrock, 2003) alasan remaja memilih teman adalah mereka yang memiliki kesensitifan terhadap hubungan yang lebih akrab dan menciptakan presahabatan dengan teman sebaya yang dipilih (Santrock, 2003). 2.4.4. Kematangan Seksual Remaja Karaktertik pubertas pada laki-laki bermula dari bertambahnya ukuran penis dan testikel, pertumbuhan rambut yang masih lurus di daerah kemaluan, sedikit perubahan suara, ejakulasi pertama (karena mimpi basah atau masturbasi), rambut kemaluan tumbuh menjadi ikal, mulai masa pertumbuhan maksimum, pertumbuhan rambut ketika, perubahan suara semakin jelas dan mulai tumbuh rambut di bagian wajah (Santrock, 2003). Pada remaja putri berawal dari payudara membesar, rambut kemaluan mulai tumbuh, lalu muncul rambut di ketiak. Seiring dengan perubahan tersebut, tinggi badan bertambah, pinggul menjadi lebih lebar daripada bahu. Menstruasi pertama datang agak lambat di akhir siklus pubertas. Menstruasi awalnya tidak teratur dan mungkin juga tidak terjadi ovulasi pada setiap mesntruasi selama beberapa tahun pertama sesudah menstruasi pertama. Perubahan suara tidak terjadi dalam pubertas remaja putri (Santrock, 2003). 2.4.5. Tahapan & Perkembangan Remaja Dalam tahap dan tugas perkembangan remaja, Santrock (2003) menyatakan bahwa individu yang memasuki tahap remaja telah menunjukkan penampilan fisik yang matang sehingga mampu untuk melakukan tugas-tugas sebagai orang dewasa seperti bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Pada perkembangan kognitif remaja telah terjadi peningkatan dalam berpikir abstrak, idealistik dan logis. Pada perkembangan psikososial, terjadinya peningkatan dalam kematangan seksual remaja sehingga meningkatkan minat terhadap relasi romantis dengan lawan jenis. Pada tahap ini remaja mulai menyadari peran masing-masing sebagai individu yang bekerja dan sebagai orangtua bagi anak-anak mereka kelak. Mendukung pernyataan tersebut, Rice & Dolgin (2008) mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perubahan besar dalam hubungannya dengan teman sebaya. Remaja mulai melepaskan diri dari keluarga dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan teman sebaya. Oleh karena kemampuan kognitif sosial remaja yang semakin luas dari ketika remaja masih anak-anak, sehingga remaja memiliki pemahaman yang lebih baik tentang orang lain. Hal tersebut menjadi langkah awal remaja untuk memiliki interaksi yang lebih intim dan bermakna. Seperti halnya, ketika remaja pindah sekolah, selesai dari sekolah dasar dilanjutkan ke sekolah menengah, dan kemudian dari sekolah menengah menuju perguruan tinggi, sehingga dari adanya perkembangan fisik yang terjadi melalui kematangan seksual muncul keinginan untuk membentuk hubungan yang romantis dengan lawan jenis yang dimulai dengan persahabatan, hubungan romantis dan menuju pada pernikahan. 2.5. Kerangka Berfikir Gambar 2.1 Kerangka berpikir Sumber : Tabel Peneliti Pada penelitian ini, responden penelitian yang ingin dilihat materialisme dan psychological well being-nya adalah remaja perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Koentjoro (2004) mengatakan bahwa secara umum terdapat lima alasan eksternal yang paling mempengaruhi dalam menuntun seorang perempuan menjadi seorang pekerja seks komersial, diantaranya adalah materialisme, modeling, dukungan orangtua, lingkungan yang permisif, dan faktor ekonomi. Mereka yang hidupnya berorientasi pada materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang dikumpulkan dan kepemilikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Banyaknya pekerja seks komersial yang berhasil mengumpulkan banyak materi atau kekayaan akan menjadi model pada orang lain sehingga dapat dengan mudah ditiru (dalam Nasution & Sihaloho, 2012). Dari sekian banyaknya faktor yang menjadi pendorong bagi para remaja perempuan untuk berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK), peneliti memfokuskan faktor pendorong materialisme untuk menjadi variable pada penelitian ini. Apa yang menjadi tujuan hidup bagi seseorang mempengaruhi pencapaiannya atas kebahagiaan. Tidak semua tujuan akan membawa pada kebaikan, bahkan beberapa di antara tujuan-tujuan tersebut ada yang berdampak negatif bagi kesejahteraan hidup. Hal tersebut akan terbukti jika kita memperhatikan kondisi masyarakat kita dan juga ceritacerita yang beredar di ruang publik tentang orang-orang yang hidupnya penuh masalah karena mengejar tujuan-tujuan duniawi, seperti harta, ketenaran, dan penampilan. Fenomena semacam itu dinamakan materialisme. Menurut Richins & Dawson (1992) yang dimaksud dengan materialisme ialah sekumpulan keyakinan tetang pentingnya kepemilikan di dalam kehidupan seseorang. Keyakinan ini merupakan manifestasi dari tingkat dimana kepemilikan materi merupakan sumber utama dari kepuasan dan ketidakpuasan seseorang dalam hidupnya (Rindfleisch, Burroughs, & Denton, 1997). Secara tidak langsung, materialisme pun tidak lepas dari sistem sosial dan ekonomi yang tengah berlangsung. Materialisme erat kaitannya dengan konsumerisme (Dittmar, 2008), yang mana itu identik dengan perilaku menkonsumsi atau membeli barang-barang. Materialisme tidak hanya berwujud nilai yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap harta benda, tetapi juga dimanifestasikan dalam perilaku-perilaku yang kompleks. Di sini materialisme pun berdampak buruk dengan menimbulkan persoalan ekonomi dan lingkungan karena dorongan mengonsumsi menuntut peningkatan produksi yang mana itu berarti eksploitasi sumber daya. Materialisme pun ditandai oleh gaya hidup yang berlebih-lebihan sampai mewah, di mana tidak ada tempat bagi kesederhanaan. Materialisme sebagai salah satu sisi gelap dari perilaku konsumen (Hirschman dalam Burroughs & Rindfleisch, 2002) telah banyak diteliti oleh para ahli baik di negara-negara barat, maupun di negara-negara timur. Tingginya perhatian para ahli terhadap materialisme adalah karena materialisme dinilai telah banyak menimbulkan berbagai konsekuensi negatif terhadap kesejahteraan psikologis (psychological wellbeing) individu seperti: menurunnya tingkat kepuasan hidup (Richins & Dawson dalam Burroughs & Rindfleisch, 2002), menurunnya tingkat kebahagiaan (Belk dalam Burroughs & Rindfleisch, 2002), serta meningkatnya tingkat depresi (Kasser & Ryan dalam Burroughs & Rindfleisch, 2002). Berbagai konsekuensi negatif tersebut tentunya tidak berkesesuaian dengan tujuan awal dari individu dalam mengejar materi yakni sebagai cara untuk menunjukkan keberbasilan mereka dalam hidup, mencari kebahagiaan dan meraih apa yang disebut sebagai "good life". Psychological well-being menurut Ryff (dalam Papalia, 2008), individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang positif adalah individu yang memiliki respon positif terhadap dimensi-dimensi psychological well being, yaitu penerimaan diri (self acceptance), hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with other), otonomi (autonomy), penguasaan lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan pertumbuhan pribadi (personal growth). Peneliti berasumsi bahwa materialisme berdampak negatif pada setiap dimensi psychological well-being. Self acceptance yang rendah membuat remaja hanya fokus pada kepemilikan dan materialisme, maka akan membuat remaja tidak akan pernah puas terhadap dirinya sendiri sehingga ia akan terus menerus bekerja sebagai PSK untuk bisa memenuhi kepuasannya dalam memiliki harta benda. Remaja yang memiliki autonomy rendah hanya fokus pada kepemilikan dan materialisme, maka biasanya ia akan membuat keputusan berdasarkan penilaian orang lain, apabila menurut penilaian orang lain harta benda yang dimiliki remaja tersebut belum banyak maka ia akan menjadi terpacu untuk mencari uang lebih banyak lagi. Pada dimensi environmental mastery, remaja yang berprofesi sebagai PSK hanya fokus dengan materi saja maka ia akan sulit untuk bergaul dengan orang di lingkungan sekitarnya atau dengan suatu komunitas dan sulit untuk mengatur kehidupan sehari-harinya dengan baik, sehingga kehidupan sehariharinya terasa cukup melelahkan untuk dijalani. Pada dimensi positif relationship with others dikarenakan hanya fokus pada kepemilikan dan materialisme membuat remaja yang berprofesi sebagai PSK sulit untuk bersikap hangat dan enggan untuk mempunyai ikatan pertemanan dengan sebayanya, begitupun dengan keluarga, karena yang ia fikirkan hanya bagaimana caranya ia dapat mengumpulkan uang untuk membeli suatu barang yang diinginkannya. Pada dimensi purpose in life remaja yang berprofesi sebagai psk hanya fokus pada kepemilikan dan materialisme, sehingga remaja biasanya merasa bahwa tidak ada tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupannya agar kehidupannya lebih berarti, yang ia fikirkan hanya bagaimana ia dapat terus bertahan mendapatkan banyak uang agar memberi barang yang diinginkannya untuk memenuhi kepusannya. Sehingga pada dimensi personal growth remaja yang berprofesi sebagai PSK hanya fokus pada kepemilikan dan materialisme akan memilih untuk terus berprofesi sebagai PSK, karena remaja tersebut sulit untuk mengembangkan sikap dan tingkah laku baru, oleh karena itu remaja tersebut berfikir bahwa sikap dan tingkah laku yang dianggap nyaman hanya dengan berprofesi sebagai PSK untuk mendapatkan keuntungan berupa materi sehingga dapat memenuhi kepuasannya dalam memiliki harta benda.