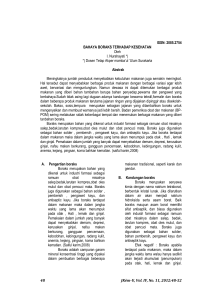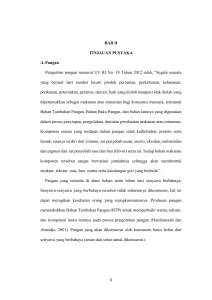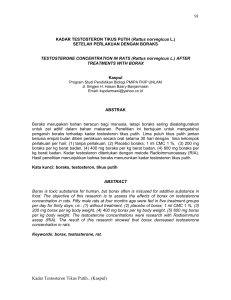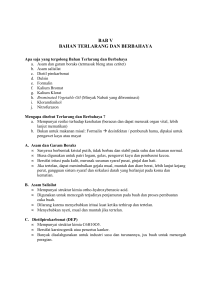Uploaded by
adamaryansyah4
Identifikasi & Penetapan Kadar Boraks dalam Bakso Sapi: Uji Kualitatif & Kuantitatif
advertisement

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN 4.1 Hasil Liat Di Lapen 4.2 Pembahasan Boraks atau natrium tetraborat merupakan senyawa anorganik yang sering disalahgunakan sebagai bahan tambahan pangan untuk meningkatkan kekenyalan, tekstur, dan daya tahan produk olahan seperti bakso, mie, kerupuk, dan lain lain.. Padahal, senyawa ini dilarang penggunaannya dalam makanan karena bersifat toksik dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius, seperti kerusakan ginjal dan hati bila dikonsumsi secara terus-menerus (World Health Organization, 2006). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, boraks tidak diperbolehkan digunakan dalam makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi keberadaan boraks secara kualitatif melalui uji nyala dan uji kertas tumerik, serta menentukan kadar boraks secara kuantitatif menggunakan metode asidimetri pada sampel bakso sapi yang diperoleh dari pasar tradisional di Ciputat, Tangerang Selatan. Hasil ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai metode analisis boraks serta kesadaran akan bahaya penggunaannya pada pangan. Pada Percobaan pertama dilakukan uji nyala untuk mendeteksi keberadaan boraks dalam sampel bakso secara kualitatif melalui pengamatan warna api. Langkah awal yang dilakukan adalah preparasi sampel dengan menimbang 10 g sampel bakso kemudian dilakukan proses pengeringan atau pemanasan awal dalam oven pada suhu 120 °C selama 6 jam. Pengeringan ini memiliki tujuan penting, yaitu untuk menghilangkan kadar air dalam sampel agar pada tahap pembakaran berikutnya tidak terjadi percikan akibat air yang mendidih serta memastikan energi panas yang diberikan terserap maksimal untuk mendekomposisi bahan organik. Apabila air masih tersisa, panas akan lebih banyak digunakan untuk menguapkan air, bukan untuk menghancurkan komponen organik yang dapat menutupi residu anorganik, sehingga hasil uji nyala atau ekstraksi dapat terganggu (AOAC International, 2019). Setelah tahap pengeringan selesai, sampel dimasukkan ke dalam tanur dan dibakar pada suhu 600 °C. Pembakaran ini bertujuan untuk mengoksidasi dan menghilangkan seluruh matriks organik dalam sampel, sehingga yang tersisa hanyalah abu atau residu anorganik. Residu anorganik inilah yang kemudian diuji untuk mendeteksi keberadaan borat, karena senyawa borat bersifat tahan terhadap panas dan akan tertinggal dalam bentuk garam borat pada abu. Tahapan ini sangat krusial karena tanpa pembakaran, sisa bahan organik dapat menghalangi pembentukan senyawa volatil borat atau mengganggu pengamatan nyala. Prosedur uji nyala dilakukan dengan meneteskan 1–2 tetes asam sulfat pekat ke atas residu abu tersebut, kemudian ditambahkan 5–6 tetes metanol. Asam sulfat berperan mengubah garam borat menjadi asam borat atau boron hidroksida, sedangkan metanol bereaksi membentuk ester volatil trimetil borat. berikut reaksinya: H₃BO₃ + 3 CH₃OH → B(OCH₃)₃ + 3 H₂O . Ester borat volatil ini sangat mudah menguap dan ketika disulut dengan api bunsen akan menghasilkan nyala hijau atau hijau kebiruan yang khas, yang merupakan indikator keberadaan boron dalam bentuk boraks (Holak, 1971; Vogel & Harris, 2010).Namun, pada hasil percobaan diperoleh nyala oranye kekuningan seperti warna api metanol biasa dan tidak muncul warna hijau khas borat. Hal ini menunjukkan bahwa uji nyala memberikan hasil negatif terhadap keberadaan boraks dalam sampel. Uji selanjutnya yang dilakukan adalah uji kertas tumerik, yaitu metode skrining kualitatif sederhana untuk mendeteksi keberadaan boraks dalam sampel pangan. Langkah awal dalam pengujian ini adalah pembuatan kertas tumerik. Kertas saring dipotong kecil-kecil untuk memperluas permukaan penyerapan, kemudian direndam dalam perasan kunyit selama 10 menit. Perendaman ini penting karena kurkumin, yaitu pigmen utama dalam kunyit, akan terserap merata ke dalam pori-pori kertas saring, membentuk lapisan indikator padat yang sensitif terhadap keberadaan boron. Setelah perendaman, kertas dikeringkan agar tidak ada pelarut tersisa yang dapat mengencerkan reaksi saat pengujian dilakukan. Proses pengeringan juga memastikan kestabilan warna dasar kuning pada kertas sebelum digunakan sebagai indikator. Prinsip dari uji tumerik ini adalah reaksi kurkumin dengan boron, di mana senyawa boron (termasuk boraks) akan membentuk kompleks berwarna merah kecoklatan yang dikenal sebagai kompleks boron kurkumin atau rosocyanine. Perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan ini menjadi indikator kualitatif adanya boraks dalam suatu sampel (Saxena et al., 2011; Sirisomboon et al., 2013). Reaksi yang terjadi : Untuk memastikan bahwa kertas indikator bekerja dengan baik, dilakukan kontrol positif dengan meneteskan larutan boraks pada kertas tumerik. Hasilnya, kertas berubah dari kuning menjadi merah kecoklatan, yang menunjukkan bahwa prosedur pembuatan kertas indikator dan reaksi kurkumin terhadap boron berjalan sesuai harapan. Pada pengujian sampel bakso, ekstraksi dilakukan dengan cara menghaluskan sampel kemudian menambahkan sedikit air untuk melarutkan senyawa borat yang mungkin terkandung di dalamnya. Larutan ekstrak tersebut kemudian diteteskan pada kertas tumerik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan warna pada kertas tumerik warna kertas tetap kuning seperti semula. Dengan demikian, uji tumerik pada sampel bakso menunjukkan hasil negatif terhadap boraks. Uji terakhir yang dilakukan dalam rangkaian penetapan boraks pada sampel bakso sapi kemasan adalah uji kuantitatif menggunakan metode asidimetri, yang bertujuan untuk mengukur jumlah senyawa basa dalam ekstrak sampel yang diasumsikan berasal dari boraks. Dalam prosedur ini, sebanyak 1,00 gram sampel bakso dihaluskan dan ditambahkan 50 mL akuades, kemudian diaduk selama 15 menit. Tahap ini penting karena pengadukan memungkinkan senyawa borat yang bersifat larut air dapat terekstraksi secara maksimal dari matriks pangan ke dalam pelarut. Rasio antara berat sampel dan volume pelarut dipilih agar proses ekstraksi berlangsung optimal dan menghasilkan larutan dengan konsentrasi terukur. Setelah diaduk, larutan disaring untuk memisahkan padatan dari filtrat, lalu diambil 10 mL filtrat sebagai sampel uji untuk memastikan volume titrasi berada pada rentang kerja yang sesuai. Langkah selanjutnya adalah penambahan 2 tetes indikator metil merah ke dalam filtrat yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Indikator ini dipilih karena sensitif terhadap perubahan pH di sekitar titik ekivalen antara larutan asam lemah dan basa lemah yang relevan dalam reaksi dengan boraks. Larutan kemudian dititrasi menggunakan larutan HCl 0,01 N hingga warna larutan berubah dari kuning menjadi pink, yang menandakan tercapainya titik ekivalen titrasi. Pada percobaan ini, volume titran HCl yang dibutuhkan untuk sampel A dan B (duplo) sama yaitu 1,0 mL, sedangkan untuk blanko (air + indikator) hanya 0,5 mL. Penggunaan blanko merupakan langkah penting karena memperhitungkan kebutuhan titran yang berasal dari pelarut dan indikator, bukan dari kandungan boraks dalam sampel. Hasil titrasi kemudian dihitung sehingga diperoleh kadar boraks sebesar 0,47%. Perbedaan antara hasil uji kuantitatif (positif) dengan uji kualitatif tumerik dan uji nyala (negatif) dapat dijelaskan melalui beberapa aspek penting. Pertama, perbedaan sensitivitas metode. Uji titrasi asidimetri memiliki sensitivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan uji visual seperti tumerik dan nyala api. Senyawa borat dalam konsentrasi sangat rendah mungkin tidak cukup untuk menghasilkan perubahan warna pada kertas tumerik atau nyala hijau khas boron, tetapi masih dapat terdeteksi dalam titrasi asam-basa (Holak, 1971; AOAC Official Methods of Analysis, 2019). Dengan demikian, meskipun hasil kualitatif negatif, hal tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa kandungan boraks benar-benar nol. Kedua, kemungkinan adanya interferensi matriks dan senyawa basa lain dalam sampel. Uji titrasi asidimetri tidak spesifik hanya terhadap boraks, melainkan mengukur semua komponen basa yang dapat bereaksi dengan asam, seperti sisa natrium karbonat, protein terionisasi, atau kontaminan alkali lain dalam produk pangan. Senyawa-senyawa ini dapat berkontribusi terhadap kebutuhan titran HCl dan terhitung sebagai “boraks” dalam perhitungan, sehingga memberi nilai lebih tinggi dari sebenarnya (Sah & Brown, 1997). Ketiga, indikator metil merah yang digunakan kemungkinan besar mengalami degradasi akibat penyimpanan yang tidak ideal. Berdasarkan informasi dari lembar data keamanan bahan kimia (SDS), indikator ini biasanya dilarutkan dalam pelarut etanol dan jika dibiarkan terbuka dalam waktu lama dapat mengalami oksidasi atau penguapan pelarut. Perubahan ini dapat menyebabkan pergeseran titik akhir titrasi, sehingga volume HCl yang digunakan menjadi tidak akurat. ibu nurul amilia selaku dosen pengampu mata kuliah juga mengonfirmasi kemungkinan ini, di mana indikator yang teroksidasi membuat perubahan warna terjadi lebih cepat atau pada pH yang sedikit lebih rendah dari seharusnya, sehingga kadar boraks yang dihitung menjadi lebih tinggi dari kenyataan. Makanan yang mengandung boraks umumnya dapat dikenali melalui perubahan karakteristik fisik yang berbeda dari produk pangan normal. Tekstur pada makanan tersebut biasanya menjadi lebih kenyal, padat, dan tidak mudah hancur, misalnya pada bakso, mi, atau kerupuk yang terasa lebih keras dan kenyal dibandingkan produk sejenis tanpa boraks. Selain itu, warna makanan tampak lebih cerah dan mengilap, karena boraks mampu menstabilkan warna bahan pangan. Produk yang mengandung boraks juga tidak mudah basi atau berjamur meskipun disimpan pada suhu ruang selama beberapa hari, akibat sifat antimikroba boraks yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (Suryanto, 2015). Ciri lain yang dapat diamati adalah bau yang kurang alami atau sedikit menyengat, serta rasa yang lebih getir dibandingkan produk yang diolah tanpa bahan tambahan berbahaya. Ketika diuji menggunakan ekstrak kunyit sebagai indikator sederhana, makanan yang mengandung boraks akan menimbulkan perubahan warna ekstrak dari kuning menjadi merah kecokelatan, menandakan adanya reaksi antara ion borat dengan senyawa kurkumin dalam kunyit (Neviranto, 1991). Oleh karena itu, ciri-ciri tersebut dapat digunakan sebagai indikator awal untuk mendeteksi adanya boraks pada produk pangan sebelum dilakukan analisis kimia lebih lanjut di laboratorium. Boraks sering digunakan secara tidak semestinya dalam produk pangan seperti bakso, mi, dan kerupuk karena dianggap dapat meningkatkan kekenyalan, memperbaiki tekstur, serta memperpanjang masa simpan produk. Penggunaan boraks tersebut memberikan dampak positif dari segi penampilan dan ketahanan pangan, karena bahan tersebut mampu bertindak sebagai pengawet dan pengenyal (Suryanto, 2015). Namun demikian, penggunaannya dalam pangan tidak diperbolehkan karena bersifat toksik dan dapat membahayakan kesehatan manusia. Secara kimia, boraks akan terurai menjadi asam borat (H₃BO₃) yang bersifat beracun apabila tertelan. Jika dikonsumsi secara berulang, boraks akan terakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada organ vital seperti hati dan ginjal. Gangguan pada sistem pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare, juga dapat ditimbulkan akibat konsumsi boraks. Selain itu, sistem saraf pusat dapat terganggu sehingga menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Pada dosis tinggi, boraks bahkan dapat menimbulkan kematian (Neviranto, 1991; Simpus, 2005). Apabila boraks (Na₂B₄O₇·10H₂O) tidak sengaja dikonsumsi, senyawa tersebut akan mengalami proses metabolisme di dalam tubuh. Setelah tertelan, boraks akan terdisosiasi menjadi ion natrium (Na⁺) dan ion borat (BO₃³⁻) di saluran pencernaan. Ion borat kemudian akan diserap oleh usus halus dan masuk ke dalam aliran darah, di mana sebagian kecil dapat berikatan dengan komponen biologis seperti protein plasma. Tubuh manusia tidak memiliki enzim khusus untuk memetabolisme boraks, sehingga senyawa ini tidak diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, melainkan akan dikeluarkan dalam bentuk aslinya atau sebagai asam borat (H₃BO₃) melalui ginjal (Neviranto, 1991). Proses pengeluaran boraks terutama terjadi melalui urin, karena ginjal berfungsi sebagai organ utama detoksifikasi zat anorganik. Sebagian kecil boraks juga dapat dikeluarkan melalui feses dan keringat, namun jumlahnya relatif sedikit. Waktu paruh pengeluaran boraks dari tubuh bergantung pada dosis yang dikonsumsi dan kondisi ginjal individu. Pada konsumsi dalam jumlah kecil, boraks dapat dikeluarkan dalam beberapa hari, tetapi jika dikonsumsi berulang atau dalam jumlah besar, boraks akan terakumulasi di organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan gangguan fungsi organ (Simpus, 2005). Oleh karena itu, meskipun tubuh memiliki kemampuan untuk mengeluarkan boraks melalui sistem ekskresi, paparan berulang tetap saja berbahaya karena dapat menyebabkan akumulasi toksik yang bersifat kronis. Pencegahan melalui pengawasan bahan pangan dan edukasi konsumen menjadi langkah paling efektif untuk menghindari dampak negatif boraks terhadap kesehatan. Sebagai pengganti boraks yang lebih aman, penelitian di Indonesia merekomendasikan beberapa alternatif bahan yang dapat memberikan efek serupa terhadap tekstur dan kekenyalan produk tanpa menimbulkan bahaya bagi konsumen (Adelia & Mardhiyyah, 2024). Bahan-bahan tersebut antara lain sodium tripolyphosphate (STPP), soda kue (NaHCO₃), air abu merang, rumput laut, serta campuran tepung-tepungan seperti tapioka dan maizena (Hartati, 2018; Adelia & Mardhiyyah, 2024). STPP dan soda kue berfungsi sebagai agen pengembang dan penguat struktur adonan, sedangkan rumput laut dan campuran tepung dapat memperbaiki tekstur serta daya kembang kerupuk (Hartati, 2018). Dengan formulasi yang tepat, penggunaan bahan-bahan ini terbukti mampu menghasilkan produk kerupuk dengan mutu yang sesuai standar SNI tanpa menggunakan boraks (Adelia & Mardhiyyah, 2024). Oleh karena itu, penerapan bahan pengganti boraks tidak hanya meningkatkan keamanan pangan, tetapi juga mendukung kepatuhan terhadap standar mutu nasional dan perlindungan kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2012). Percobaan mengenai boraks dalam pangan ini juga dapat dikaitkan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehalalan dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman: Artinya: “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Kementerian Agama RI, 2019). Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal dari segi hukum dan thayyib (baik) dari segi kesehatan dan kebersihan. Dalam penggunaan boraks, bahan ini tergolong zat berbahaya dan bukan termasuk bahan makanan yang baik bagi tubuh, sehingga penggunaannya bertentangan dengan prinsip halalan thayyiban (Muflihah, 2020). DAFTAR PUSTAKA Adelia, T., & Mardhiyyah, Y. S. (2024). Eksplorasi Alternatif Bahan Pengganti Bleng (Boraks) pada Kerupuk Puli Berdasarkan Karakteristik Fisiko Kimia Produk dan Penerimaan Sensori. Sustainability and Social Impact, 1(1), 23–31. AOAC International. (2019). Official Methods of Analysis of AOAC International (21st ed.). AOAC. Cahyadi, W. 2008. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Bumi Aksara Halim, C. (2012). Deteksi Boraks Menggunakan Kunyit sebagai Indikator Alami. Jurnal Penelitian Kimia Terapan, 4(2), 45–50. Hartati, F. K. (2018). Alternatif Pengganti Boraks pada Pembuatan Kerupuk Puli: Penggunaan Soda Kue dan Air Abu Merang. Jurnal Teknik Industri Heuristic, 15(2), 99–114. Holak, W. (1971). “Flame test for detection of boron compounds.” Journal of the AOAC, 54(4), 864–867. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (1988). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Jakarta: Kemenkes RI. Kementerian Riset dan Teknologi. (2013). Panduan Identifikasi Kandungan Boraks pada Makanan dengan Kunyit sebagai Indikator Alami. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi. Khamid, I.R. 2006. Bahaya Boraks Bagi Kesehatan. Jakarta: Penerbit Kompas. Neviranto, A. (1991). Bahaya Penggunaan Boraks dalam Makanan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Riandini, N. 2008. Bahan Kimia dalam Makanan dan Minuman. Bandung: Shakti Adiluhung. Saxena, A., Gautam, S., & Kaur, P. (2011). “Simple turmeric paper indicator for detection of borax in food products.” International Journal of Food Science & Technology, 46(5), 1031–1034. Sah, R. N., & Brown, P. H. (1997). “Techniques for boron determination and their application to the analysis of plant and soil samples.” Communications in Soil Science and Plant Analysis, 28(11-12), 843–850. Simpus. (2005). Panduan Pengawasan Bahan Berbahaya pada Pangan. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sirisomboon, C. D., Kerdpol, K., & Rattanapoltee, P. (2013). “Rapid detection of borax in food products using turmeric paper.” Kasetsart Journal (Natural Science), 47, 796–803. Suryanto, B. (2015). Analisis Kandungan Boraks pada Produk Olahan Daging di Pasar Tradisional. Jurnal Teknologi Pangan Indonesia, 6(2), 45–52. Syah, D. (2005). Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Vogel, A. I., & Harris, D. C. (2010). Vogel's Textbook of Quantitative Chemical Analysis (6th ed.). Pearson Education. World Health Organization. (2006). Borates: Environmental Health Criteria 204. WHO.