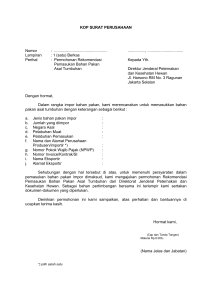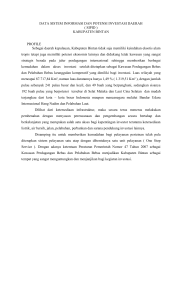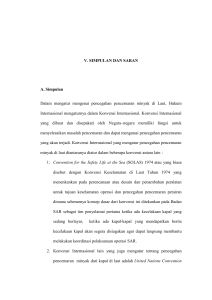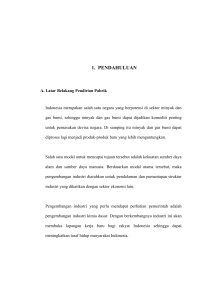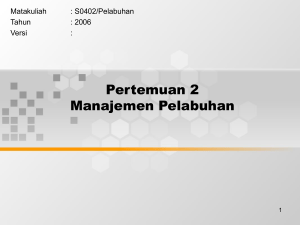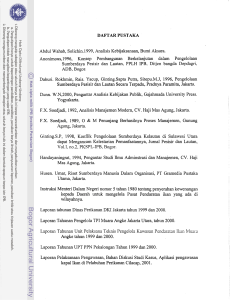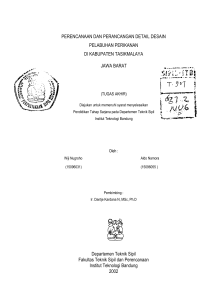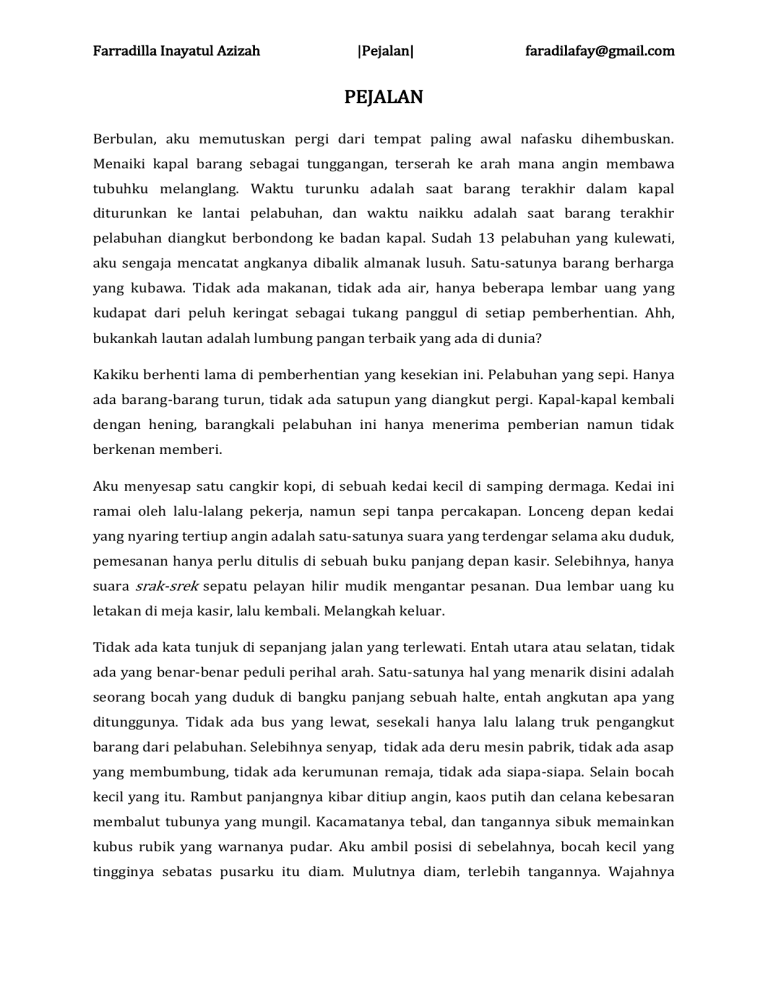
Farradilla Inayatul Azizah |Pejalan| [email protected] PEJALAN Berbulan, aku memutuskan pergi dari tempat paling awal nafasku dihembuskan. Menaiki kapal barang sebagai tunggangan, terserah ke arah mana angin membawa tubuhku melanglang. Waktu turunku adalah saat barang terakhir dalam kapal diturunkan ke lantai pelabuhan, dan waktu naikku adalah saat barang terakhir pelabuhan diangkut berbondong ke badan kapal. Sudah 13 pelabuhan yang kulewati, aku sengaja mencatat angkanya dibalik almanak lusuh. Satu-satunya barang berharga yang kubawa. Tidak ada makanan, tidak ada air, hanya beberapa lembar uang yang kudapat dari peluh keringat sebagai tukang panggul di setiap pemberhentian. Ahh, bukankah lautan adalah lumbung pangan terbaik yang ada di dunia? Kakiku berhenti lama di pemberhentian yang kesekian ini. Pelabuhan yang sepi. Hanya ada barang-barang turun, tidak ada satupun yang diangkut pergi. Kapal-kapal kembali dengan hening, barangkali pelabuhan ini hanya menerima pemberian namun tidak berkenan memberi. Aku menyesap satu cangkir kopi, di sebuah kedai kecil di samping dermaga. Kedai ini ramai oleh lalu-lalang pekerja, namun sepi tanpa percakapan. Lonceng depan kedai yang nyaring tertiup angin adalah satu-satunya suara yang terdengar selama aku duduk, pemesanan hanya perlu ditulis di sebuah buku panjang depan kasir. Selebihnya, hanya suara srak-srek sepatu pelayan hilir mudik mengantar pesanan. Dua lembar uang ku letakan di meja kasir, lalu kembali. Melangkah keluar. Tidak ada kata tunjuk di sepanjang jalan yang terlewati. Entah utara atau selatan, tidak ada yang benar-benar peduli perihal arah. Satu-satunya hal yang menarik disini adalah seorang bocah yang duduk di bangku panjang sebuah halte, entah angkutan apa yang ditunggunya. Tidak ada bus yang lewat, sesekali hanya lalu lalang truk pengangkut barang dari pelabuhan. Selebihnya senyap, tidak ada deru mesin pabrik, tidak ada asap yang membumbung, tidak ada kerumunan remaja, tidak ada siapa-siapa. Selain bocah kecil yang itu. Rambut panjangnya kibar ditiup angin, kaos putih dan celana kebesaran membalut tubunya yang mungil. Kacamatanya tebal, dan tangannya sibuk memainkan kubus rubik yang warnanya pudar. Aku ambil posisi di sebelahnya, bocah kecil yang tingginya sebatas pusarku itu diam. Mulutnya diam, terlebih tangannya. Wajahnya Farradilla Inayatul Azizah |Pejalan| [email protected] datar, entah jenis ekspresi apa yang sedang ditampilkan. Aku menututi gerakan diamnya, menatap kosong ke arah depan. Langit-langit menjelma gelap. Jalanan kota masih seperti tadi, sunyi. Bebunyian yang tersisa hanya deru nafasku yang teratur. Dingin yang gigil serentak menyerbu tulangtulang kering, yang mengecil. “Tidak ada percakapan di kota ini, selain suara pembeli membeli barang di pasar. Atau suara supir truk memberi upah pada tukang panggul di pelabuhan,” bocah kecil itu membuka suara, intonasinya pelan dan datar. Tidak ada nada emosional yang terdengar. “Orang-orang mempunyai cita-cita yang sama, melahap hari dengan katakata yang diam. Di kota ini semuanya menjelma tulisan, tidak ada siapa berkuasa di atas siapa. Kecuali kata-kata yang dimaktubkan sendiri.” Bola matanya bergerak, menelisik pada arah jembatan, tembok-tembok besar, juga pohon trembesi yang akarnya menggantung. Benar, segala sudut di sekitarku penuh dengan tempelan kertas-kertas lusuh. “Paman, rumahku berada di sudut kota ini. Setiap sudut kota adalah deretan abjad. Aku tidak tahu, apakah huruf dan sepi begitu mengasikkan. Tidak ada masa depan di kota ini, titik paling jauh kita adalah batu nisan yang lagi-lagi penuh dengan kata-kata dalam segala bentuk bahasa,” ucapnya kemudian. Dihirupnya udara yang tiba-tiba terasa sesak itu. “Orang-orang yang suka bermain dengan lisannya akan cepat kalah dengan keadaan. Tidak ada penghayatan lebih, di sana akan banyak orang yang memilih bersaing ketimbang berkawan.” Jarinya menunjuk ke arah dermaga yang sepi. “Tapi Paman, bukankah hidup adalah perjalanan? Apa tulisan-tulisan yang memenuhi dinding rumah akan membawa kita pada kehidupan yang nyata?” Aku diam, khidmat mendengarkan. Haruskah ada jawaban? “Orang-orang kota ini tak jauh beda dengan yang lain, Paman. Sama-sama disibukkan diri dengan bersaing, atau bahkan berperang. Ya, berperang dengan keadaan yang ditolak mentah-mentah.” Aku mengernyit bingung, tidak mengerti dengan kalimat terakhirnya. Apakah orang-orang kota ini begitu rumit merangkai kata? Farradilla Inayatul Azizah |Pejalan| [email protected] Bocah kecil itu beranjak dan lalu. Tanpa meninggalkan salam perpisahan. Keadaan kembali sunyi. Malam ini, angin mati. Gelap merayap. Untuk terakhir kalinya aku menghadap laut. Merentangkan tangan, mengucapkan perpisahan. Pada geladakgeladak kapal aku bersumpah atas nama diri sendiri, bahwa perjalanan yang kesekian ini akan membawaku menjadi seorang legenda. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan ganjil yang tak kutemu jawabnya dari lautan. Termasuk, Benarkah manusia hanya diberi pilihan kalah dan menang? Perlahan, kakiku menj auh dari bibir pantai. Menekuri diri sendiri sebagai seorang pejalan, mengangkat sepanjang jalan sebagai tuan. Sebelum benar pergi, kusempatkan meminjam sebuah kata, dari kertas lusuh yang tertempel di tiang besi. “Perjalanan akan menghadapkanmu pada dua hal : diri sendiri dan orang-orang yang tidak kau kenal.” Rembang, 16 Juni 2020 *Penulis adalah seorang gadis jawa yang mencintai bakpia segala rasa. Penikmat lagu Tulus ini tengah menyiapkan penerbitan sebuah buku yang tidak untuk di jual, Buku Kehidupan.