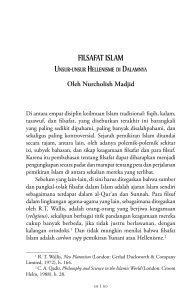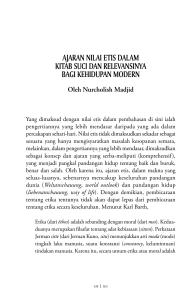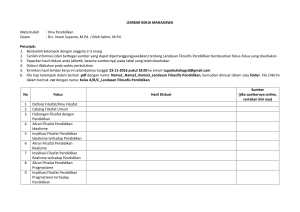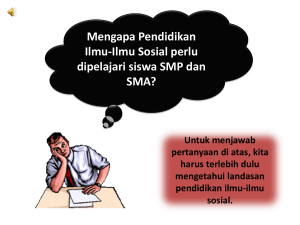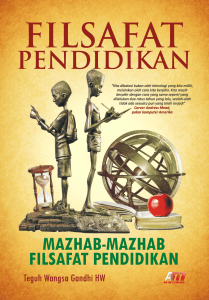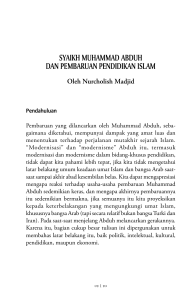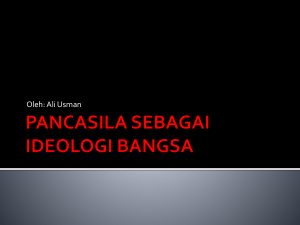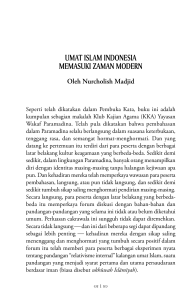Uploaded by
common.user89482
Filsafat-Pendidikan-Mazhab-Mazhab-Filsafat-Pendidikan-Cet-2-April-2014-1
advertisement

FILSAFAT PENDIDIKAN: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan Teguh Wangsa Gandhi HW Editor: Meita Sandra Proofreader: Nur Hidayah Desain Cover: TriAT Desain Isi: Maarif Penerbit: AR-RUZZ MEDIA Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo Depok, Sleman, Jogjakarta 55282 Telp./Fax.: (0274) 488132 E-mail: [email protected] ISBN: 978-979-25-4825-9 Cetakan II, 2014 Didistribusikan oleh: AR-RUZZ MEDIA Telp./Fax.: (0274) 4332044 E-mail: [email protected] Perwakilan: Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218 Malang: Telp.Fax.: (0341) 560988 Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Gandhi HW, Teguh Wangsa Filsafat Pendidikan: Mazhab-Mazhab Filsafat Pendidikan/Teguh Wangsa Gandhi HW-Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014 224 hlm, 14,8 X 21 cm ISBN: 978-979-25-4825-9 1. Pendidikan I. Judul II. Teguh Wangsa Gandhi HW Pengantar Penerbit H ingga hari ini, pendidikan dipercaya sebagai sesuatu hal yang penting. Semenjak memercayai pendidikan, dunia berubah menjadi kota-kota yang dipadati gedung-gedung besar dan panjang yang di dalamnya berisi deretan meja dan kursi. Tempat inilah yang kemudian disebut sekolah. Bermula dari tempat itulah konon pendidikan dimulai. Setiap hari, anak-anak dididik di tempat tersebut agar menjadi diri yang terdidik. Terdidik berarti hidup dalam normalisasi-normalisasi nilai yang teratur dan rutin. Konotasi kata terdidik kerap juga diidentikkan dengan diri yang berpengetahuan, tertib, dan tidak memberontak. Oleh karena itu, siapa pun yang urakan dan tidak teratur akan disadari sebagai diri yang tidak atau belum terdidik. Pendidikan kemudian menjadi syarat untuk hidup serta status sosial untuk diterima sebagai manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin terhormat dan tinggi posisi tawar status serta penghargaan sosial atas dirinya walaupun seseorang yang berijazah itu begitu buruk dalam soal pengetahuan. Mereka yang mengenyam sekolah dengan sendirinya akan memiliki kehidupan jauh lebih layak dan mapan serta jauh lebih dihormati ketimbang mereka yang tidak bersekolah. Sedangkan, mereka yang tak 5 sekolah karena tidak memiliki biaya untuk sekolah akan selalu hidup dalam mata rantai kemiskinan dan hidup situasi yang sepenuhnya tersingkirkan. Akan tetapi, berbagai kampanye tentang pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu penting guna membela kemanusiaan justru berimplikasi terbalik menjadi awal muasal lahirnya ironi. Pendidikan menjadi penyebab pertama lahirnya berbagai tindak dehumanisasi serta berbagai reduksi kemanusiaan. Nah, di sinilah tugas filsafat pendidikan dijalankan. Tugas filsafat pendidikan tidak lain adalah mengantarkan para calon guru dan para praktisi pendidikan untuk berhadapan dengan pertanyaanpertanyaan besar yang mendasari makna dan tujuan pendidikan. Untuk itu, mereka mesti akrab dengan isu-isu, semisal hakikat realitas, makna dan sumber pengetahuan, serta struktur nilai. Filsafat pendidikan membawa para pelajar pada situasi ketika mereka secara cerdas menilai tujuan-tujuan akhir alternatif, mengaitkan dengan tujuan-tujuan yang diinginkan, dan menyeleksi metode-metode pengajaran sesuai dengan tujuan. Secara holistis, tugas filsafat pendidikan itu membantu para pendidik berpikir secara bermakna tentang totalitas pendidikan dan proses hidup sehingga mereka selalu berada dalam posisi yang tepat dan dapat mengembangkan program yang konsisten serta menyeluruh sehingga para pelajar mampu menjadi diri manusia yang berkualitas. Pendeknya, filsafat pendidikan bermaksud memberi bekal kepada para pendidik untuk menjadi paham persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Dengan demikian, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dan terus mengembangkan pendidikan menjadi semakin baik. Secara etis, filsafat pendidikan membekali diri untuk melakukan pelacakan-pelacakan tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. 6 Buku ini mengajak kita mengenal dan memahami lebih dalam filsafat pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang memanusiakan dapat terwujud. Pengajar, mahasiswa, dosen, serta siapa pun yang bergelut dalam dunia pendidikan, kiranya dapat menjadikan buku ini sebagai pegangan. Akhir kata, selamat membaca. Jogjakarta, Januari 2011 Redaksi 7 Daftar Isi Pengantar Penerbit ............................................................. 5 Daftar Isi ............................................................................... 9 Prolog .................................................................................... 11 Bab I Filsafat dan Pendidikan ...................................... 19 A. Pendidikan yang Mengubah Dunia.............................. 19 B. Jalan dan Tujuan Filsafat ............................................. 30 C. Episteme Filsafat ....................................................... 35 D. Cabang-Cabang Filsafat ............................................. 37 E. Sumber-Sumber Pengetahuan ................................... 46 F. Teori-Teori Kebenaran ................................................ 50 G. Etika .......................................................................... 52 H. Logika ........................................................................ 59 I. Apakah Pendidikan Itu? .............................................. 60 J. Jalan dan Tujuan Pendidikan ....................................... 67 K. Hubungan Filsafat dan Pendidikan .............................. 70 Bab II Filsafat Pendidikan .............................................. 79 A. Pengertian Filsafat Pendidikan ..................................... 79 B. Peran Filsafat Pendidikan ......................................... 84 9 C. Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan ............................. 89 D. Metafisika Ontologi Filsafat Pendidikan ...................... 90 E. Problem Epistemologi Filsafat Pendidikan ................. 92 F. Metafisika Aksiologi Filsafat Pendidikan ..................... 105 G. Filsafat Pendidikan Socrates ...................................... 108 H. Filsafat Pendidikan Plato ............................................ 112 I. Filsafat Pendidikan Aristoteles .................................... 114 Bab III Mazhab-Mazhab Pendidikan .............................. 117 A. Aliran-Aliran dalam Filsafat Pendidikan ...................... 117 B. Filsafat Pendidikan Idealisme ...................................... 128 C. Filsafat Pendidikan Realisme....................................... 140 D. Filsafat Pendidikan Pragmatisme ................................ 144 E. Filsafat Pendidikan Progresivisme............................... 152 F. Filsafat Pendidikan Esensialisme ................................. 159 G. Filsafat Pendidikan Perenialisme ................................. 163 H. Filsafat Pendidikan Eksistensialisme ........................... 183 I. Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme .................... 189 J. Filsafat Pendidikan Behaviorisme ............................... 194 Daftar Pustaka ..................................................................... 211 Indeks.................................................................................... 215 Biografi Penulis ................................................................... 222 10 Prolog P ada 1943, ketika industrialisasi dan urbanisasi di Amerika mulai mengalami kemapanan-kemapanan yang kuat, sedangkan di sisi yang lain pendidikan makin berjalan dengan pola yang sepenuhnya progresif, di New York seorang pemikir bernama Reinhold Neibuhr1 meluncurkan sebuah karya berjudul The Nature and Destiny of Man (1943). Sebagaimana judulnya, Reinhold dalam karya tersebut mengulas sifat dasar manusia dan hidupnya serta sisi keterkaitannya dengan takdir. Dalam mengawali pembahasan buku tersebut, Reinhold di halaman pertama mengawali kalimat pembahasannya dengan sebuah kebingungan yang menawan. “Manusia,” demikian kata Reinhold, “bukanlah apa pun selain problem yang membingungkan dan problem bagi dirinya.” Pernyataan ini Reinhold buat terutama karena ia melihat betapa baginya manusia selalu lekat dengan berbagai kontradiksi dan paradoks. Di satu sisi ia terlihat sama sekali bukan sekadar binatang. Ia, bahkan jauh lebih cerdas ketimbang primata mana pun. Akan tetapi, di sisi yang lain, manusia kerap pula terlihat betapa ia hanyalah sekadar binatang 1. Reinhold Neibuhr adalah seorang teolog Protestan yang terkenal karena penelitiannya mengenai tugas dalam menghubungkan iman Kristen dengan realitas politik modern dan diplomasi. Ia merupakan penyumbang penting terhadap pemikiran mengenai perang yang legal. 11 yang dengan kesadaran yang jauh lebih tinggi. Dua sifat bertentangan ini begitu mengendalikan hidup manusia di dunia mana pun sehingga bagi hidupnya, manusia selalu menjadi problem. Pandangan Reinhold di atas tentu saja sangat bisa diterima, terutama karena kita tahu betapa tidak ada manusia yang sepenuhnya, baik dalam makna yang mutlak ataupun buruk dalam makna yang mutlak juga. Dalam banyak hal kita selalu menemukan betapa manusia senantiasa hidup dalam dua nilai itu. Suatu ketika hadir dan begitu baik, meski di hari yang lain muncul sebagai diri yang sepenuhnya buruk, bahkan begitu mengerikan. Hanya saja pandangan Reinhold di atas melahirkan berbagai pertanyaan mendasar pada kita, seputar apa dan bagaimana sebenarnya baik dan buruk bagi dan dalam diri manusia itu. Apakah manusia pada dasarnya memang terlahir dengan sifat buruk? Atau, justru sebaliknya, pada mulanya ia bersifat baik dan kemudian berubah menjadi buruk sebab berbagai hal di sekitarnya? Jika memang manusia terlahir sebagai diri yang baik, bagaimana kualitas dari sifat baik itu? Hal apakah yang bisa mengubahnya membuat menjadi buruk serta kehilangan sama sekali kebaikan-kebaikan yang dibawanya? Pertanyaan-pertanyaan yang sama berlaku pula ketika manusia dipandang terlahir sebagai diri yang memang bersifat buruk. Apakah sifat buruk dalam diri manusia itu bersifat potensial, bisa diubah, atau justru sesuatu yang telah baku? Bagaimana sebenarnya sifat-sifat buruk yang ada dalam diri manusia itu? Penyataan Reinhold dan pertanyaan kita saat ini, tentu saja bukan pernyataan dan pertanyaan pertama yang muncul untuk pertama kalinya. Kita dan Reinhold, bahkan mungkin telah menjadi diri yang kesekian triliun kalinya yang pernah menggelisahkan persoalan itu. Dari sejarah, misalnya, kita mendengar kabar bahwa terdapat kisah-kisah manusia yang baik dan kisah-kisah manusia yang buruk. Ada yang pada mulanya baik 12 kemudian berubah menjadi jahat. Terdapat pula seseorang yang mulanya jahat kemudian berubah menjadi baik. *** Di sini, baik buruk bagi manusia agaknya bersifat potensial dan bukan bagian dari eksistensi manusia, terutama karena dalam hidupnya manusia memiliki sesuatu yang bernama kebebasan. Dalam aktualitasnya, kebebasan manusia memang bersifat terbatas, terbatasi oleh kebebasan manusia di luar dirinya. Akan tetapi, dalam keterbatasannya, ia tetap memungkinkan manusia untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya termasuk pada persoalan baik dan buruk. Hanya saja, meski manusia memiliki independensi serta kebebasan yang membuatnya bisa memilih. Bersamaan dengan itu pula, manusia selalu menjadi makhluk yang selalu dipengaruhi oleh situasi, situasi ketika manusia kemudian bisa berubah menjadi diri yang sebaliknya. Artinya, dalam independensinya, manusia kemudian bisa melakukan hal-hal yang buruk. Pada sisi inilah pendidikan, guna meningkatkan kesadaran-kesadaran hidup, menjadi hal yang dipandang penting oleh sejarah. Meski sejauh upaya peningkatan dan pelestarian gagasan-gagasan nilai dan hidup yang baik dilakukan, pendidikan kemudian lebih banyak terlihat menjadi problem kemanusiaan ketimbang menjadi solusi bagi kemanusiaan. Lantas, bagaimana sebenarnya kebaikan manusia itu? Bagaimana pula dengan pendidikan? *** Jika kita memandang bahwa manusia bisa menjadi baik sebab pendidikan hal itu tentu saja ada benarnya karena memang menjadi bagian dari fakta dan realita hidup. Betapa di sebagian diri kebaikan dan 13 keburukan selalu bukan diri mana pun, melainkan bagaimana kondisi lingkungan tempat di mana masing-masing diri tinggal dan berada. Meski pandangan tersebut agaknya akan menjadi sangat berbeda dengan pandangan para eksistensialisme, betapa baik buruk dalam pandangan mereka selalu bukan hal lain, selain pilihan bebas manusia. Dari itu, meski hidup yang ada selalu menjadi hidup yang rentan dan terbatas, sama rentan dan terbatasnya dengan kebebasan manusia. Akan tetapi, semua problem tersebut selalu tidak cukup memadai untuk dijadikan alasan dan pembenar bagi perbuatan buruk yang kita lakukan. Sama tidak ada beralasannya dengan membuat keyakinan bahwa pendidikan mampu mengubah hidup manusia menjadi baik. Sehebat dan sebagus pendidikan dilangsungkan jika pihak terkait, yaitu subjek manusianya tidak ingin baik, dengan sendirinya, ia tidak akan pernah bisa menjadi diri yang sepenuhnya baik. Lantas apa makna pernyataan Aristoteles yang berkata betapa sepanjang waktu, manusia selalu terlihat baik, di satu sisi, dan buruk di sisi yang lain. Apakah itu artinya manusia bisa baik dan bisa buruk? Atau, justru sebaliknya, dalam cita-citanya yang selalu baik, manusia terkadang justru hidup dengan cara yang begitu buruk? Sulit memastikan apa maksud perkataan Aristoteles di atas. Hanya saja, dari perkataan Aristoteles yang lain, kita bisa menemukan bagaimana pandangan dan sikap Aristoteles tentang baik buruk bagi manusia. Suatu ketika, ia berkata, “Saya mencintai Plato, tapi saya lebih mencintai kebenaran.” *** Lantas, bagaimana sikap yang mesti kita pilih dengan adanya pendidikan? Apakah karena baik buruk adalah pilihan bebas kehendak manusia, pendidikan kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak penting untuk dilakukan? Sedangkan, sehebat apa pun seorang filsuf eksistensialis 14 dalam soal independensi, tetap saja ia diri yang belajar dan menerima sesuatu yang bernama pendidikan? Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah, buku filsafat pendidikan ini penulis tulis, terutama karena penulis memandang bahwa walau bagaimanapun, pendidikan tetap memiliki peran yang penting bagi hidup manusia. Hal itu sangat terkait dengan tingkat kesadaran dan pengetahuan masing-masing diri manusia: pengetahuan akan diri, dunia dan hidupnya, tidak selalu benar. Sebagian diri, bahkan hidup, dengan pengetahuan-pengetahuan yang salah termasuk di dalam menyakini tentang kebaikan. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan konsep independensi yang diserukan para eksistensial, sebaliknya justru sangat selaras. Penulis memandang terdapat banyak diri yang dengan independensinya memilih menjadi baik. Akan tetapi, karena kurangnya pengetahuan, ia kemudian terjebak dalam perilaku-perilaku yang sebaliknya. Ini bisa dicontohkan dengan keinginan untuk mandiri atau kaya. Kaya atau menjadi kaya tentu sesuatu hal yang baik. Akan tetapi, ia akan menjadi sesuatu hal yang buruk ketika orang tidak mengerti apa makna kaya dan kekayaan serta cara memperolehnya. Di sini pendidikan menjadi sesuatu yang penting meski ia tidak akan membuat dunia menjadi sepenuhnya berisi manusia yang sepenuhnya baik. Demikian semoga bermanfaat. Jogjakarta, Januari 2011 Teguh Wangsa Gandhi H.W. 15 “Dunia ini selalu komedi bagi mereka yang berpikir, tragedi bagi mereka yang berperasaan, dan jawaban: mengapa Demokritos tertawa dan Heraklitos menangis.” (Horace Walpole)2 2. Ia adalah seorang Inggris, sejarawan seni, sastrawan, antik, dan politikus. Dia diingat untuk karya Strawberry Hill, dan bangunan rumahnya di Twickenham, barat daya London yang bergaya Gothic, dan dikenal sebagai penerus Victoria. Novelnya bergaya Gothic, The Castle Otranto. Bab I Filsafat dan Pendidikan A. Pendidikan yang Mengubah Dunia Jika kita mendapat pertanyaan mengapa kita mengkaji pendidikan, tentu saja mudah untuk kita menjawabnya bahwa hal itu terkait dengan dunia kita yang sampai hari ini memang masih memercayai pendidikan sebagai sesuatu hal yang penting. Hanya saja, jika kita mendapat pertanyaan, mengapa sampai hari ini kita memercayai pendidikan, pertanyaan seperti itu tentu saja bukan pertanyaan yang mudah dicari jawabannya. Sebaliknya, ia selalu menjadi pertanyaan mendasar yang begitu sulit untuk dijawab oleh siapa pun. Ini terkait, terutama karena sepanjang ini pendidikan telah menjadi sesuatu hal yang diterima sebagai kebenaran aksiomatis, dari waktu ke waktu. Pendidikan, demikian ia kita namai, hingga menit-menit milenia ketiga Masehi pecah dan dimulai, selalu kita percayai dengan pola kepercayaan yang sama, dipandang sebagai sesuatu hal yang penting serta mesti ada dalam keberlangsungan hidup manusia di mana pun. Kepercayaan ini begitu klasik dari waktu ke waktu sehingga sulit bagi siapa 19 pun untuk mengetahui sejak kapan manusia mulai menaruh optimisme dan kepercayaannya pada pendidikan. Di Eropa, misalnya, keyakinan dan kepercayaan terhadap pendidikan kemudian memunculkan sesuatu hal, seperti school, atau pedagogie, education, andragogie, dan lain sebagainya. Sementara, di Timur, kita juga akan menemukan hal yang sama dengan Barat, dengan adanya istilah madrasah, majlis ta’lim, halaqah, pesantren, padepokan, grahavidya, dan lain sebagainya, yang kesemua itu merujuk pada tempat atau wahana pendidikan. Oleh karena itu, jika diamati, dunia, terutama sejak mulai memercayai pendidikan, berubah menjadi kota-kota yang dipadati dengan gedung-gedung besar dan panjang, yang di dalamnya berisi deretan meja serta kursi, yang diatur dengan pola lajur dan hitungan-hitungan tertentu. Sementara, di hadapan deretan meja dan bangku-bangku yang ditata dengan pola lajur tersebut terdapat papan tulis sepanjang beberapa meter, berdiri melintang, berada tepat di samping meja seorang guru. Kita hari ini biasa menyebut tempat aneh itu dengan nama sekolah, madrasah, atau school—campus jika di Eropa. Bermula dari tempat itulah, sesuatu yang bernama “pendidikan” konon dimulai. Di sana manusia dikelompokkan ke dalam dua tipe. Pertama, anak didik; dan kedua, guru atau pendidik. Anak didik atau siswa adalah diri yang dipandang harus dibimbing, diarahkan, dan dibentuk agar terarah. Sedangkan, mereka yang membimbing, mengarahkan, serta membentuk yang disebut pendidik, guru, atau teacher. Sebab, ia adalah seorang guru yang selalu dipandang sebagai diri yang berlimpah pemahaman dan pengetahuan akan berbagai hal yang ada dalam hidup dan kehidupan. Dengan demikian, dari hari ke hari, hingga tahun-tahun berganti, setiap anak dari usianya yang begitu dini, setiap hari mesti setia duduk di bangku-bangku itu agar konon bisa menjadi diri yang terdidik. Terdidik berarti hidup dalam normalisasi-normalisasi nilai yang teratur dan 20 rutin. Konotasi kata terdidik kerap juga diidentikkan dengan diri yang berpengetahuan, tertib, dan tidak memberontak. Oleh karena itu, siapa pun yang urakan dan tidak teratur akan disadari sebagai diri yang tidak atau belum terdidik. Dalam pengertian ini, sekolah menjadi ruang, tempat setiap diri diarahkan, dibentuk, atau dihabituasikan dalam keteraturan-keteraturan nilai yang telah dibakukan agar ia patuh dan tidak menjadi pemberontak. Pola-pola pendidikan seperti ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi berlaku di berbagai negeri sehingga di mana pun, tanpa terkecuali, setiap diri mau tidak mau harus masuk ruang pendidikan bernama “sekolah” atau “kampus” agar konon menjadi diri yang terdidik. Sebenarnya, tidak ada tekanan secara langsung yang memaksa seseorang mesti masuk sekolah. Akan tetapi, bagi siapa pun yang tidak masuk sekolah, akan terasing dan diasingkan oleh sosialnya. Sekolah pada akhirnya menjadi suatu tempat yang mau tidak mau diniscayakan mesti dimasuki oleh siapa pun. Sebab, tidak sekolah sama artinya akan menerima perlakuan-perlakuan sinisme dari lingkungan karena dipandang tidak atau belum terdidik. Selain itu, tanpa sekolah, mereka akan sulit bertahan hidup, terutama karena setiap tempat bekerja, selalu menjadikan sertifikasi keterdidikan atau ijazah sekolahnya sebagai syarat formal dalam menjaring para pekerja. Tanpa sekolah, berarti hidup tanpa ijazah, dan hidup tanpa ijazah berarti sulit mendapat pekerjaan. Demikian, di sini pendidikan kemudian menjadi syarat untuk hidup serta status sosial untuk diterima sebagai manusia. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin terhormat dan tinggi posisi tawar status serta penghargaan sosial atas dirinya walaupun seseorang yang berijazah itu begitu buruk dalam soal pengetahuan. Sebaliknya, sepandai apa pun seseorang, ia tetap akan sulit diterima bekerja di mana pun jika dalam hidupnya ia tidak sekolah atau tidak 21 memiliki sertifikasi pendidikan. Oleh karena itu, hanya dalam kemujuran yang sungguh-sungguh mujur sajalah, seseorang dengan tanpa sertifikasi sekolah mampu bekerja dan mendapatkan penghargaan sosial sebagaimana mereka yang terdidik (sekolah). Gejala ini telah menjadi rahasia umum yang dari ke hari terus terjadi di dalam realitas hidup yang ada. Di ruang sosial, kondisi-kondisi tersebut melahirkan berbagai kesenjangan sosial mulai dari kesenangan status, penghargaan kemanusiaan, ataupun kesejahteraan hidup. Mereka yang mengenyam sekolah dengan sendirinya akan memiliki kehidupan jauh lebih layak dan mapan serta jauh lebih dihormati ketimbang mereka yang tidak bersekolah. Sedangkan, mereka yang tak sekolah karena tidak memiliki biaya untuk sekolah akan selalu hidup dalam mata rantai kemiskinan dan hidup situasi yang sepenuhnya tersingkirkan. Di sini berbagai kampanye tentang pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu penting guna membela kemanusiaan justru berimplikasi terbalik menjadi awal muasal lahirnya ironi. Pendidikan menjadi penyebab pertama lahirnya berbagai tindak dehumanisasi serta berbagai reduksi kemanusiaan. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin diterima dan mendapatkan penghargaan secara wajar sebagai manusia ia harus memasuki ruang pendidikan. Sebaliknya, tanpa pendidikan ia tidak akan menjadi apa pun, selain manusia malang yang saban hari akan menerima sinisme serta berbagai alienasi sebab diinferiorkan sebagai diri yang tidak terdidik, kurang mengerti etika, tidak berpengetahuan, dan martabat. Kenyataan ini tentu saja tragedi, hanya saja hingga sejauh ini semua kalangan nyaris tidak lagi memedulikannya. Dalam banyak kasus, orang seolah-olah telah memaafkan hal buruk itu sebagai bagian dari keniscayaan hidup yang tak terelakkan dan mesti terjadi. Betapa dalam hidup, konon memang selalu mesti terdapat diri yang terlahir dan hidup dalam 22 ketidakberuntungan. Padahal, semua itu tidak muncul dengan sendirinya, sebaliknya lahir dari sesuatu yang bernama “pendidikan”. Sayangnya, hingga sejauh ini, tidak ada satu pun dari para pendidik atau mereka, para diri yang disebut pakar pendidikan, yang kemudian bersedia merefleksikan dan mengevaluasi kembali mengenai apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan bagi hidup manusia. Benarkah ia sungguh-sungguh sesuatu hal yang penting sehingga dianggap mesti ada di hidup mana pun atau justru ia sesuatu hal yang dianggap penting, sedangkan dalam realitanya, ia bukan sesuatu yang sama sekali memang dibutuhkan manusia? Alih-alih “pendidikan” kemudian sebagaimana temuan Charles E. Silberman, dalam karyanya Crisis in the Classroom: The Remarking of American Education telah menjadi ruang padat, yang begitu sesak dengan berbagai jawaban, namun sangat miskin pertanyaan. Sebuah situasi, menurut George R. Knight, telah menjadi penyebab utama mengapa makin ke belakang, mindlessnes makin menjamur di pelbagai belahan dunia, baik Barat ataupun Timur. Pendidikan diterima secara mapan dan tanpa kewaspadaan. Ia telah menjadi dogma suci yang tidak perlu dipertanyakan salah benar relevansi dan koherensinya. Dari dogma tersebut, berbagai diskursus pendidikan selalu hanya berkutat pada ranah-ranah praksis-pragmatis dan begitu jauh dari persoalan-persoalan mendasar pendidikan, menyangkut onto-aksiologis pendidikan, yaitu menyangkut mengenai apa dan mengapa pendidikan dilaksanakan. Di stadium ini, dalam kejelasannya, pendidikan diam-diam menjadi sesuatu hal yang paling simpang siur dan kabur makna keberadaan serta urgensitasnya. Ibarat rahim, pendidikan yang ada tidak pernah tahu dan mengerti, diri-diri manusia dengan kualitas seperti apakah yang akan dilahirkan yang itu menunjukkan bahwa pendidikan berjalan sama sekali tanpa parameter. 23 Di satu sisi, kita mungkin akan menemukan banyaknya literatur yang menjelaskan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk memperoleh kemajuan serta melahirkan peradaban. Akan tetapi, sejauh itu tidak satu pun di antara kita yang tidak pernah mendengar dengan jelas apa dan bagaimana sebenarnya kemajuan dan peradaban yang dimaksud oleh pendidikan. Ketidakjelasan ini terjadi pula pada makna etis pendidikan. Ini bisa ditemukan pada pencanangan pendidikan yang selalu dimaksudkan guna mengubah manusia menjadi baik. Pencanangan tujuan tersebut menjadi sesuatu hal yang paling aneh dan sulit dipahami, terutama karena sejauh ini tidak satu pun pendidikan mampu menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya manusia yang dipandang baik. Sedangkan, keyakinan pendidikan dalam memercayai pengetahuan sebagai instrumen utama untuk membuat manusia menjadi baik agaknya makin menegaskan betapa pendidikan sejak awal, hadir sebagai spekulasi filsafat yang begitu simpang siur. Kesimpangsiuran tersebut terjadi, terutama karena hingga sejauh ini kita tidak pernah tahu, sejak kapan pengetahuan bisa membuat manusia menjadi baik. Saat kita melakukan pembacaan-pembacaan sejarah, apa yang diyakini pendidikan dengan pengetahuan di atas justru hadir dalam gejala yang sebaliknya. Pengetahuan juga menjadi penyebab utama semakin canggihnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, pantas bagi kita untuk mengkritisi keyakinan di atas. Jika pengetahuan bisa membuat manusia menjadi lebih baik, hingga sejauh ini dunia pasti tidak lagi memiliki manusia-manusia jahat. Ini bisa kita dasarkan dengan kenyataan sejarah tempat hidup manusia sejak lama telah menjadi hidup yang begitu berlimpah pengetahuan. Sosok Hitler serta orang-orang Nazi, misalnya, tentu saja adalah orang-orang yang berlimpah dengan pengetahuan. Mereka bukanlah diri-diri yang bodoh, yang tidak mengenal logika dan pendidikan. Hanya saja, keberlimpahan tersebut tidak pula mengubah atau menghentikan 24 mereka menjadi diri yang baik. Sementara, di ruang lain, kita juga dapat menghadirkan contoh yang sama terkait dengan imperialisme di dunia ini. Para imperium atau para negeri penjajah, tidak lain adalah negeri-negeri yang tingkat pengetahuannya jauh maju ketimbang mereka yang dijajah. Mereka, para negeri imperium, bahkan mampu menciptakan alat-alat dan teknologi canggih yang tidak bisa dilakukan oleh para negeri yang terjajah. Hanya saja, kemajuan-kemajuan pengetahuan itu pun tidak pula mencegah mereka untuk tidak menjajah negeri-negeri lain yang tingkat pengetahuannya jauh di bawah mereka. Di ruang ini, pandangan pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dapat membuat manusia menjadi baik, perlu dibahas dan dikritisi lebih lanjut. Benarkah pengetahuan dapat membuat manusia menjadi baik? Ataukah, hanya sekadar membawa manusia pada pengetahuan teoretis tentang nilai-nilai yang dipandang dan disepakati sebagai kebaikan? Jika memang pengetahuan diyakini mampu membuat manusia menjadi baik, adakah seluruh pengetahuan memiliki sifat yang sama atau justru terdapat pengetahuan-pengetahuan tertentu yang bisa membuat manusia menjadi baik, dan terdapat pula jenis-jenis pengetahuan yang berimplikasi sebaliknya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dimunculkan atau pendidikan akan terus jatuh dalam ilusi-ilusi nilai serta harapan-harapan yang sama sekali tidak nyata. Seiring dengan makin kuatnya optimisme dan harapan setiap kalangan terhadap pendidikan, pendidikan justru hanya melahirkan air mata. Pendidikan pada akhirnya menjadi semacam mesin raksasa yang sepanjang waktu secara sistemastis, terus-menerus menjadi rahim dari lahirnya dehumanisasi. Dari hari ke hari, manusia semakin mengalami kehilangan tak terperi dengan hidup yang dialaminya sebab dalam 25 keberlimpahannya akan pengetahuan, hidup justru makin sulit disadari sebagai hidup. *** Sementara, mengemukanya pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan dipandang penting karena pendidikan dimaksudkan untuk membimbing, mengarahkan, dan membentuk manusia agar menjadi baik, agaknya juga sebuah pandangan sangat polemik. Sekilas, pandangan itu memang terlihat sebagai ungkapan yang tidak bermasalah. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, pandangan tersebut ternyata menyimpan polemik filsafat yang cukup rumit, terutama di ruang ontologis. Pandangan di atas pertama-tama akan membawa kita pada pertanyaan masalah otoritas pendidikan sebagai pihak yang merasa memiliki hak untuk melakukan intervensi sikap-sikap dan pilihan etika pada setiap individu manusia. Otoritas yang pada ujungnya melahirkan sebuah berbagai macam pertanyaan, mengapa manusia mesti diarahkan dan dibentuk? Adakah tanpa pendidikan, manusia tidak bisa baik atau selalu dalam kondisi jahat sehingga keberadaan pendidikan kemudian dianggap penting bagi hidup manusia? Dalam pelacakan lebih lanjut, permasalahan-permasalahan di atas akan membawa pendidikan pada pemahaman secara holistik tentang hakikat manusia, sekaligus pemahaman proporsi pendidikan-pendidikan yang memang dibutuhkan. Dengan demikian, pendidikan tidak menjadi kedok dari upaya penyeragaman dan pengerdilan manusia untuk tumbuh menjadi diri yang seragam dan tidak lagi tumbuh. Sayangnya hingga sejauh ini, sekali lagi, upaya untuk melihat lebih jauh hal-hal mendasar pendidikan tidak pernah kita temukan. Akibatnya, pendidikan ideal yang diimpikan selalu hanya jari yang menunjuk bulan. Pendidikan seperti itu mungkin ada, tetapi ia begitu jauh ada di sana dan tidak pernah ada di sini. Di sini pendidikan lebih banyak menunjuk 26 ironi dan tragedi. Ironi-ironi dan tragedi itu terus mewabah pada bidang kehidupan sehingga belakangan lahir banyak keraguan di sebagian kalangan: mengapa kita masih memercayai bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam hidup ini, sedangkan tidak ada satu pun sejarah yang menunjuk secara pasti bahwa terdapat suatu bangsa yang benar-benar memperoleh hidup sempurna sebab adanya pendidikan? *** Yunani Lama yang kerap diklaim oleh sebagian kalangan sebagai Negeri Filsafat, tempat pemikiran berlangsung begitu subur dan mendalam, misalnya, tetap saja sebuah negeri yang penuh dengan tragedi dan penderitaan. Penderitaan-penderitaan dan tragedi di sana bahkan berlangsung dengan begitu tak terbayangkan sehingga Sophocles membuat ungkapan satir, “Betapa yang terbaik dalam hidup adalah tidak pernah terlahirkan sama sekali.” Sementara, Cina sebagai daratan yang juga penuh legenda, juga memiliki wajah yang tak berbeda. Di Cina sepanjang waktu kehidupan bahkan tidak pernah berlangsung sebagai hidup yang sungguh-sungguh menawan dan indah. Dalam kemajuannya mengenai pengetahuan, Cina ribuan tahun terlibat peperangan tanpa henti yang melahirkan berbagai penderitaan yang tidak sederhana. Eropa hari ini, di satu sisi mungkin memang terlihat megah dan canggih dengan berbagai capaian-capaian teknologinya. Eropa bahkan memiliki banyak tokoh pemikir yang berhasil melahirkan berbagai macam teori tentang hidup. Akan tetapi, dalam yang seperti itu, sungguhkah pendidikan di sana telah menjadi solusi atas berbagai persoalan hidup yang ada? Adakah pendidikan telah membuat masyarakat Eropa mampu memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia ketimbang manusia di belahan dunia yang lainnya? 27 Ini tentu saja sangat relatif. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan Eropa telah berlangsung dengan jauh lebih baik ketimbang di Timur tentu saja adalah pandangan yang sangat sempit dan keliru. Sama kelirunya dengan pandangan yang mengatakan bahwa Timur telah mengalami berbagai kegagalan dalam wilayah pendidikan, terutama karena dalam lingkup apa pun, pendidikan selalu menjadi penting—tidak lain karena pendidikan berkaitan dengan persoalan mendasar manusia, yaitu dengan hidup. Dalam skala tersebut, ukuran mendasar keberhasilan pendidikan tidak lain adalah bagaimana kondisi hidup yang ada, bukan bagaimana hidup diteorikan. Hal itu sangat terkait dengan bagaimana kondisi riil kehidupan suatu masyarakat, yang itu terkait dengan beragam kualitas situasi hidup, mulai dari bagaimana nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya disadari dan dialami, kepekaan pada sesama, empatif, hingga kebutuhankebutuhan hidup lainnya yang lebih mudah diukur, seperti kesehatan fisik, sandang pangan, hiburan, keadilan, kenyamanan berpikir, dan kebebasan dalam memilih dan mengalami kepercayaannya. Dalam pengertian ini, penilaian bahwa suatu bangsa yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi masyarakat hingga tahapan begitu berlimpah belumlah bisa dianggap sebagai bangsa yang berhasil dalam soal pendidikan. Terlebih, jika dalam keberlimpahan itu telah mereduksi hidup menjadi sekadar perburuan materi, sementara hidup selalu tidak sekadar persoalan ekonomi semata. Kondisi sama juga berlaku bagi bangsa yang cenderung melihat pendidikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai hidup. Nilai-nilai itu tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pendidikan. Pengarusutamaan nilai-nilai moral yang kemudian mengabaikan perbincangan aspek-aspek materi secara rasional akan lebih banyak melahirkan kesadaran naif dan hanya melahirkan situasi hidup yang sarat dengan ironi—perilaku korup menjadi penyakit yang akan diidap setiap diri. 28 Hingga di sini pendidikan seharusnya dimaknai dan disadari secara utuh. Pendidikan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, sebaliknya mesti dirumuskan dengan hidup secara holistik. Dari itu, pertanyaan tentang apa dan bagaimana pendidikan selalu mesti dihadapkan secara lurus dengan pertanyaan apa dan bagaimana seharusnya hidup mesti diketahui, disadari, dijalani, dan dihayati. Tanpa itu, pendidikan hanya akan melahirkan air mata—seluruh pelaksanaan pendidikan tidak melahirkan solusi bagi hidup siapa pun selain makin memperburuk situasi hidup yang ada. Sayangnya, semua itu nyaris tidak pernah kita temukan. Sepanjang waktu, pendidikan tetap lebih banyak melahirkan persoalan ketimbang menjadi solusi. Di Indonesia, belakangan ini, pendidikan lebih banyak terarah pada kepentingan-kepentingan praktis hidup, yaitu melayani pasar ketimbang membangun kehidupan. Dari itu, keberhasilan-keberhasilan pendidikan selalu diletakkan dengan ukuran-ukuran pasar, bersifat pragmatis, mekanistis, dan normatif. Bertolak dari berbagai problem di atas, kita di sini agaknya perlu mengkaji lebih lanjut mengenai apa itu pendidikan, untuk apa, mengapa, serta bagaimana dalam perspektif filsafat. Dengan demikian, kita akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang hal ihwal pendidikan berikut berbagai derivasinya. *** Tugas filsafat pendidikan tidak lain adalah mengantarkan para calon guru dan para praktisi pendidikan untuk berhadapan dengan pertanyaanpertanyaan besar yang mendasari makna dan tujuan pendidikan. Untuk itu, mereka mesti akrab dengan isu-isu, semisal hakikat realitas, makna dan sumber pengetahuan, serta struktur nilai. Filsafat pendidikan membawa para pelajar pada situasi ketika mereka secara cerdas menilai tujuan-tujuan akhir alternatif, mengaitkan 29 dengan tujuan-tujuan yang diinginkan, dan menyeleksi metode-metode pengajaran sesuai dengan tujuan. Secara holistis, tugas filsafat pendidikan itu membantu para pendidik berpikir secara bermakna tentang totalitas pendidikan dan proses hidup sehingga mereka selalu berada dalam posisi yang tepat dan dapat mengembangkan program yang konsisten serta menyeluruh sehingga para pelajar mampu menjadi diri manusia yang berkualitas. Pendeknya, filsafat pendidikan bermaksud memberi bekal kepada para pendidik untuk menjadi paham tentang persoalan-persoalan mendasar pendidikan. Dengan demikian, memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dan terus mengembangkan pendidikan menjadi semakin baik. Secara etis, filsafat pendidikan membekali diri untuk melakukan pelacakan-pelacakan tentang tujuan-tujuan hidup dan pendidikan. B. Jalan dan Tujuan Filsafat Persoalan cara atau jalan menuju filsafat masuk ke dalam diskusi filsafat sejak era periode yang sangat klasik. Di era lama, persoalan-persoalan jalan atau cara menuju filsafat bahkan telah pula menjadi topik yang banyak memancing lahirnya berbagai pemikiran, mulai dari Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Dari pemikiran-pemikiran itu, kita di hari ini sekurang-kurangnya dapat menemukan konon terdapat tiga jalan untuk menuju filsafat: skeptis,3 rasa heran,4 dan kuatnya keingintahuan. 3. Hal yang pertama, yaitu skeptis, tidak lain adalah sikap anonim dari aksiomatis. Jika aksiomatis adalah sikap menerima segala hal tanpa sikap, skeptis justru sebaliknya menjadi sikap yang tidak mudah dalam menerima atau meyakini sesuatu yang dikatakan sebagai kebenaran. 4. Pandangan ini disandarkan pada perkataan Plato yang mengatakan bahwa filsafat berawal dari rasa heran. 30 Ketiga hal di atas tentu saja sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang, bahkan telah menjadi menu keseharian setiap diri di dunia kita hari ini. Dunia kita hari ini begitu sarat dengan ketiga sikap tersebut. Di satu sisi, misalnya, kita akan menemukan, betapa setiap diri yang ada telah senantiasa hidup dalam sikap skeptis yang teramat sangat ketat dan sama sekali tidak mudah percaya pada apa pun. Sementara, di sisi yang lain, mereka juga terlihat begitu dikendalikan oleh rasa heran dan rasa penasaran yang begitu berlimpah dan penuh eksplorasi. Hanya saja, pertanyaannya dalam ketiga situasi tersebut: mengapa di hari ini nasib filsafat justru menunjukkan situasi yang semakin tidak bijak? Di satu sisi, buku-buku filsafat mungkin terus ditulis dan dibaca serta dipelajari di berbagai perkuliahan. Akan tetapi, bersamaan dengan hal itu, filsafat justru menunjuk situasi yang terus mengalami pendangkalan. Dengan demikian, muncul sebuah kesan betapa keberadaan filsafat hari ini hanyalah ikon tragedi yang menegaskan betapa hidup telah dijalani dengan semangat yang justru sebaliknya. Kenyataan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar filsafat, khususnya tentang persoalan jalan atau cara menuju filsafat: adakah sesuatu yang salah dari cara-cara atau jalan yang diterapkan hari ini sehingga filsafat yang pada masa lalunya melahirkan kedalaman justru makin membawa hidup pada kedangkalankedangkalan pikir yang menyedihkan? Jika kita telaah dengan saksama, lahirnya berbagai gejala-gejala di atas sesungguhnya terkait dengan dangkal pemaknaan berbagai kalangan di dalam menyadari ketiga jalan di atas. Dalam soal skeptis, orang, misalnya lebih banyak memaknai skeptis semata-mata sebagai sikap yang mudah tidak percaya apa pun, tidak lebih dan tidak kurang. Padahal, skeptis yang menjadi jalan filsafat adalah skeptis yang lahir dari pengetahuan, bukan sebaliknya lahir dari ketidaktahuan. Oleh karena itu, jika saat sifat filsafat dominan dengan sikap meragukan, keraguan dalam filsafat bukan didasarkan pada ketidaktahuan, 31 sebaliknya lahir dari pengetahuan guna memperoleh pengetahuan yang makin utuh dan mendalam. Dalam makna ini, keingintahuan dan rasa heran yang menjadi jalan filsafat bukanlah rasa heran dan keingintahuan yang sekadarnya, sebaliknya rasa heran dan keingintahuan yang lahir dari pengetahuan. Oleh karenanya, saat Plato mengatakan bahwa filsafat berawal dari rasa heran, rasa heran yang dimaksudkan Plato bukanlah rasa heran tanpa kualitas, sebaliknya rasa heran yang lahir dari pengetahuan untuk menuju makin menjadi berpengetahuan dengan mendalam dan benar. Dari itu, jika kita lacak, kita akan menemukan betapa jalan menuju filsafat pertama-tama bukanlah ketiga hal di atas, melainkan adanya kesadaran eksistensi. Kesadaran akan keberadaan itulah jalan pertama menuju filsafat. Jalan ini memiliki tekanan etis karena saat seseorang menyadari keberadaannya, ia akan dihadapkan pada keterdesakan nilai untuk bermakna. Artinya, ia sadar kebermaknaan inilah jalan utama filsafat. Saat seseorang menyadari bahwa keberadaannya mesti bermakna ia kemudian mulai berusaha memahami apa dan bagaimana dirinya serta apa dan bagaimana hal-hal yang di sekitarnya. Tanpa kesadaran akan keberadaan rasa keingintahuan, rasa heran serta kuatnya keingintahuan tidak akan pernah memiliki makna falsafi apa pun selain hanya pelunasan libido intelektual yang kemudian berujung pada situasi-situasi gegar kosmologi. Hidup kemudian tidak lagi diketahui ujung pangkal etisnya. Dalam makna ini, berfilsafat adalah jalan untuk menuju bijak sebab dengan bijak, kita bisa memperoleh keutamaan-keutamaan hidup yang bermakna. Hingga di sini, dapat kita simpulkan bahwa jalan utama filsafat pertama-tama bukanlah rasa heran, skeptis, atau keingintahuan, melainkan rasa cinta pada kebermaknaan keutamaan hidup. Keberadaan rasa cinta itulah yang membuat para filsuf puluhan abad yang lalu kemudian sepanjang waktu terus berupaya memperoleh kebijaksanaan. Meski 32 harus dipahami, cinta pada kebijaksanaan tidak selalu secara serta-merta membuat seseorang menjadi filsuf atau menjadi seseorang bijaksana. Hanya saja semakin besar cinta seseorang pada kebijaksanaan, semakin jauh pula ia dimungkinkan untuk berfilsafat dan berpikir jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Keberhasilan filsafat selalu sama dengan keberhasilan cinta. Di dalam keberhasilan cinta dibutuhkan kemurnian dan kesetiaan. Dalam ruang pikir, kesetiaan ini akan membawa seseorang untuk secara konsisten terus melacak persoalan-persoalan yang dihadapi sehingga ia pun mampu menyikapi segala sesuatu dengan utuh dan bijak. Selain kesetiaan, berfilsafat juga membutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, seseorang tidak akan sanggup menyaksikan kebenaran lain dari yang ditemukannya, yang hal itu pasti akan membuatnya berhenti dalam kesimpulan-kesimpulan yang dangkal. Padahal, pemahaman yang hendak dicapai filsafat bukanlah pemahaman yang dangkal, melainkan pemahaman yang mendalam dan utuh. Selain setia dan rendah hati, filsafat juga menekankan kejujuran. Terdapat ungkapan menarik Plato dalam soal jujur dalam menyadari kebenaran, “Saya,” begitu kata Plato, “tentu saja cinta dengan Socrates, dia bahkan guru saya. Akan tetapi, saya jauh lebih cinta pada kebenaran.” Di sini, di masa lalunya, para filsuf selalu lahir menjadi diri pribadi yang begitu rendah hati, pandai mendengarkan pandangan dan pemikiran orang lain di sekitarnya. Mereka tahu dan sadar bahwa yang mereka cari bukan apa pun, melainkan pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam. Dari dan dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang mendalam itu, mereka kemudian mampu menyikapi segala sesuatu penuh kebijaksanaan. Filsafat dalam pengertian teknis meliputi tiga aspek, yaitu aspek aktivitas, serangkaian sikap, dan sebuah keterpaduan isi. *** 33 Sementara, pola kerja intelektual filsafat dengan didasarkan pada apa yang dilakukan para filsuf, dapat kita dibedakan menjadi beberapa tahapan, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Dalam beberapa literatur lain, tiga hal ini kerap dibedakan menjadi empat istilah, yaitu sintesis, spekulasi (merenung), preskripsi, dan menganalisis. Hanya saja, pembagian ke dalam empat tahapan ini terlihat cenderung melahirkan berbagai tumpang tindih dan melahirkan berbagai kebingungan-kebingungan asosiasi. Pembedaan tahapan ke dalam empat tipe tersebut justru lebih banyak akan melahirkan kesimpangsiuran linguistik karena ketidakmendasaran logika asosiasi makna masing-masing istilah. Dalam tahapan sintesis, misalnya, seseorang tidak mungkin lepas dari kerja-kerja spekulasi, preskripsi, sekaligus analisis. Hal ini sangat terpahami karena sebuah sintesis tidak mungkin lahir dari ruang kosong atau nir-pengetahuan. Artinya, bersamaan ketika seseorang melakukan sintesis, seseorang juga melakukan spekulasi-spekulasi serta preskripsipreskripsi dan analisis. Jika demikian adanya, relevansi pembedaan, sintesis sebagai tahapan yang berbeda dengan spekulasi, preskripsi, serta analisis menjadi hal yang sama sekali tidak relevan, bahkan akan membuat gagasan persoalan metode yang hendak dijabarkan justru menjadi semakin kabur. Dalam pemikiran itu, penulis lebih memilih aktivitas intelektual filsafat lebih tepat jika dibedakan ke dalam tiga kategori sebagaimana kita paparkan di atas, yaitu: tesis, antitesis, dan sintesis. Tesis adalah spekulasi awal, praduga ilmu atas sesuatu hal. Praduga ini tentu saja lahir dari pandangan-pandangan umum yang membuat seseorang membuat spekulasi tentang sesuatu hal. Praduga ini akan mengalami verifikasi dan falsifikasi atau tahapan antitesis. Dari verifikasi dan falsifikasi ini, kita kemudian membuat berbagai analisis sehingga melahirkan sintesis atau pandangan yang lahir dari berbagai perenunganperenungan secara mendalam dan menyeluruh. 34 Dalam konteks filsafat pendidikan, pendidikan sesungguhnya termasuk pula sesuatu yang lahir dari spekulasi atau tesis filsafat atas hidup manusia yang telah mengalami berbagai perenungan dan analisis atau mengalami antitesis dan sintesis berulang-ulang sehingga ia kemudian diterima sebagai kebenaran dan melahirkan suatu premis bahwa pendidikan penting bagi hidup manusia karena makna etisnya. Pendidikan diyakini dapat membawa manusia menjadi baik. Hal yang sama juga berlaku pada pandangan pengetahuan sebagai instrumen yang digunakan pendidikan. Dalam ruang pendidikan praksis, pandangan-pandangan di atas tidak lagi dipersoalkan karena ia telah menjadi nilai dan landasan bagi pelaksanaan aktivitas pendidikan yang ada. Hanya saja, dalam ruang filsafat, pandangan-pandangan tersebut menjadi sesuatu hal yang belum bisa diterima. Sebaliknya, ia mesti dikritisi dan dianalisis antara relevansi transformasi pengetahuan bagi perilaku etis manusia dan berbagai sikap kritis. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara perbuatan jahat dan tidak tahu itu? Adakah pula hubungan yang signifikan antara berpengetahuan dan berbuat baik. Sedangkan, dalam banyak kasus, keberlimpahan pengetahuan selalu tidak mencukupi untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak bermoral? C. Episteme Filsafat Kemudian, selain hal di atas, filsafat juga dibimbing tiga hal utama, yang kerap disebut “episteme filsafat” atau tata cara dalam berfilsafat. Pertama, ontologi; kedua, epistemologi; dan ketiga, adalah aksiologi. Ontologi kerap disadari sebagai bidang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat realitas. Kemudian, epistemologi berkenaan dengan hakikat kebenaran dan pengetahuan serta kajian tentang bagaimana kebenaran dan pengetahuan itu diperoleh. Sedangkan, aksiologi mengacu 35 pada kajian tentang persoalan nilai—mulai dari pengertian baik, buruk, dan lain sebagainya. Dari ketiga sistematika ini, filsafat umumnya dimulai dari pertanyaan ontologi, baru kemudian aksiologi, selanjutnya memasuki epistemologi. Ini bisa diandaikan, misalnya, saat salah seorang di antara kita di jalan tiba-tiba menemukan sebuah besi pipih dengan panjang 20 cm, yang sebagian sisinya tumpul, sedangkan sisi yang lain tajam. Seketika, saat melihat itu, kita pasti akan bertanya, benda apakah itu? Pertanyaan “benda apakah itu” termasuk bagian dari pertanyaan ontologis. Lalu, dari pertanyaan itu kita pun kemudian menjadi tahu bahwa benda itu disebut pisau. Kita pasti akan bertanya kembali, apakah pisau itu? Saat itu kita tidak mungkin menemukan jawaban apa pun mengenai pisau kecuali kita berusaha memahami hal ihwal pisau. Maka, kita pun bertanya secara aksiologis, “Untuk apakah pisau itu?” Begitulah pertanyaan-pertanyaan itu kemudian membawa kita berpikir tentang bagaimana cara mengetahui hal ihwal pisau—mulai dari hakikat entitasnya, bahan dasarnya, cara pembuatannya, hingga fungsi-fungsinya. Gagasan tentang tata cara dalam mengetahui hal ihwal pisau ini dalam filsafat disebut epistemologi. Sedangkan, pengetahuan tentang hakikat entitas pisau disebut sebagai pengetahuan ontologi dan hasil pemikiran-pemikiran tentang fungsi-fungsi kegunaan pisau masuk dalam ruang aksiologi. Di sini, sampailah kita pada pengetahuan filsafat pisau, yaitu pengetahuan mulai dari apa, mengapa, dan bagaimana pisau itu. Dari pengetahuan itu, kita pun kemudian mampu secara bijak menggunakan pisau sesuai dengan batas-batas fungsi, hakikat, dan asal muasal serta kapasitas pisau. Jadi, sesederhana itulah filsafat. Filsafat tidaklah rumit dan berat, tetapi begitu sederhana, bahkan mungkin selalu sederhana. Hanya saja, karena dalam perkembangannya filsafat lebih banyak hanya dipahami 36 sebagai kerja pemikiran, kemajuan filsafat menjadi kemajuan alienatif yang justru mengalienasi kesadaran para muridnya. Sifat alienasi ini belakangan sebenarnya bukan hanya menjadi gejala filsafat, melainkan juga telah menjadi gejala kolektif di banyak lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan dinilai tidak lagi memiliki makna apa pun bagi tata kehidupan yang ada selain hanya memajukan secara material. Segala sesuatu yang disadari dengan pengetahuan yang tidak utuh (tidak falsafi) akan cenderung dialami sebagai sesuatu yang tidak utuh pula. Itulah alienasi. Pengetahuan, harta, spiritual, dan politik adalah berkah kehidupan yang seharusnya tidak pernah melahirkan alienasi apa pun. Namun, karena ia dipahami secara tidak utuh (tidak falsafi), semua itu dialami pula dengan tidak utuh. Di sini, kemajuan pengetahuan yang pada mulanya sebagai berkah sebab tanpa filsafat yang benar, kemudian memunculkan situasi sebaliknya, sama dengan harta, spiritual, politik, serta berbagai hal kehidupan lainnya, yang justru menjadi penyebab utama lahirnya keterasingan dan kehancuran peradaban dimulai. D. Cabang-Cabang Filsafat Filsafat tidak lain adalah mengetahui secara utuh dan saksama, menyikapi dengan bijak, dan mengalaminya dengan penghayatan yang benar. Dari itulah, di dunia ini sebenarnya, tidak ada politik yang jahat, agama yang keliru, pengetahuan yang menyengsarakan, ataupun spiritual yang melahirkan keterasingan jika ia dipahami secara utuh dan saksama (baca: dengan filsafat yang benar). Sebaliknya, kitab suci, sesuatu yang bagi siapa pun selalu berkesan suci, jika dipahami tanpa pengetahuan yang bijak, bisa menjadi menjadi alat pembunuh yang begitu dingin dan buta. Ini tak berbeda dengan 37 agama atau sebuah sikap kebertuhanan apa pun. Di sebuah zaman, kesadaran akan Tuhan, suatu ketika memang membawa bangsa tersebut pada hidup yang begitu indah, maju, dan penuh surga. Namun, di zaman yang lain, sikap kebertuhanan yang sama justru menunjukkan situasi paling binatang di antara binatang. Atas nama Tuhan, sekelompok manusia dengan kejam membunuhi sekelompok manusia lainnya tak ubahnya membunuh kawanan binatang. Maka, dalam hidup ini, filsafat selalu tidak memadai jika diartikan sebagai sesuatu yang muncul dari rasa heran atau takjub. Sebaliknya, ia lahir dari kondisi halus bernama cinta, yaitu cinta kebijaksanaan. Di sini filsafat sesungguhnya bukanlah sesuatu yang hadir di tengah zaman ketika manusia belum berpengetahuan. Sebaliknya, filsafat lahir ketika keberlimpahan pengetahuan tidak lagi membawa manusia pada pengetahuan, sikap, serta penghayatan yang bijaksana. Filsafat bukan antitesis dari mitos. Ia bukanlah sesuatu yang hadirnya menjadi tanda bagi berakhirnya mitologi. Sebaliknya, ia hadir ketika pengetahuan dan mitologi tidak lagi memberi kesembuhan bagi hidup yang ada. Filsafat adalah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. “Sesuatu” di sini dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Jika terbatas, filsafat membatasi diri akan hal-hal tertentu saja. Akan tetapi, jika tidak terbatas, filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering dikatakan filsafat umum. Sementara itu, filsafat yang terbatas adalah filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat seni, dan lain-lainnya. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam. Maka, dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang bisa diamati oleh manusia saja, sesungguhnya isi alam yang dapat dinikmati hanya sebagian kecil saja. Ini dapat diumpamakan dengan gunung es, yaitu ruang keilmuan biasa 38 hanya akan mampu melihat yang di atas permukaan laut saja. Sedangkan, filsafat menyelami hingga ke dasar gunung, bahkan mampu meraba pada hal-hal yang ada di pikiran dan renungan yang kritis. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung. Ini adalah arti formal berfilsafat. Dua arti filsafat, “memiliki dan melakukan”, tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya. Oleh karena itu, jika kita tidak memiliki suatu filsafat dalam arti formal dan personal, kita tidak akan dapat melakukan filsafat dalam arti “kritik” dan “reflektif ” (reflective sense) meski memiliki filsafat saja tidak cukup untuk melakukan filsafat. Sikap filsafat yang baik tidak lain adalah sikap kritis dan mencari. Sikap itu adalah sikap terbuka dan toleran, serta bersedia melihat segala sudut persoalan tanpa prasangka. Berfilsafat tidak hanya berarti “membaca dan mengetahui filsafat”. Filsafat juga merupakan upaya analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dari upaya analisis logis tersebut, setiap filsuf selalu menggunakan metode analisis serta berusaha menjelaskan pemakaian bahasa yang mereka gunakan dalam filsafatnya. Sebagian kalangan berpandangan bahwa itulah tugas pokok filsafat. Hanya saja, dalam perkembangannya, filsafat dipahami sebagai satu disiplin yang berusaha mengklasifikasikan kebenaran masing-masing yang ditemukan oleh setiap disiplin. Hal ini menyangkut jenis kebenaran dalam filsafat, termasuk salah satunya kebenaran koherensi dan korespondensi. Sementara, dalam garis besarnya, filsafat memiliki beberapa cabang utama: metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. 1. Metafisika Metafisika kerap dikenal sebagai the first philosophy atau filsafat pertama yang berusaha membicarakan prinsip-prinsip yang universal atau hal-hal yang bersifat beyond nature. Di sini metafisika meninjau hakikat segala sesuatu atau hakikat realitas yang terdapat di alam ini. Metafisika 39 membicarakan watak mendasar (ultima) setiap benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung. Dari itu “ada” sebuah kata yang begitu sederhana di ruang metafisika menjadi topik bahasan yang tidak pernah sederhana. Metafisika, misalnya, akan membawa kita dalam perenungan-perenungan tentang apa dan bagaimanakah ada itu, apa dan bagaimanakah yang disebut ada? Apa dan bagaimanakah tidak ada itu, apa dan bagaimanakah yang disebut tidak ada itu? Samakah ada dan wujud? Samakah tiada dan tidak ada? Begitulah metafisika membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan kontemplatif: apakah sesuatu yang benar-benar ada itu? Apakah ia yang ada secara materi atau justru ada secara ide? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar kajian metafisika. Sepintas, pertanyaan-pertanyaan itu memang begitu sederhana sehingga siapa pun untuk kali pertama akan melihat betapa persoalan ini begitu terlihat main-main dan tidak berguna. Hanya saja, jika direnungkan lebih jauh, akan terlihat betapa metafisika memiliki peran fundamental yang bahkan tak tergantikan oleh apa pun. Metafisika menjadi dasar bagi lahirnya pemikiran filsafat apa pun, terutama karena masing-masing keberadaan selalu hadir dengan relatif. Tuhan, misalnya, selalu diyakini oleh siapa pun sebagai sesuatu yang ada. Lebih jauh, Dia bahkan selalu disadari ada di mana pun. Hanya saja, adakah keberadaan Tuhan sama dengan keberadaan sebuah gelas atau sebuah buku, misalnya. Jika Tuhan memiliki keberadaan yang sama dengan sebuah gelas atau sebuah buku, secara serta-merta Tuhan tidak lagi akan disadari sebagai Tuhan. Contoh kerelativitasan keberadaan adalah saat kita hendak minum lalu terpikirkan dalam kita gagasan tentang gelas. Bersamaan dengan pikiran kita memikirkan gelas, gelas itu tentu saja ada, tetapi keberadaan gelas dalam pikiran tersebut memiliki sifat yang berbeda dengan keberadaan gelas secara empiris. 40 Adapun dalam pembagiannya, pertanyaan-pertanyaan metafisika kerap dibedakan menjadi empat tipe: pertama, terkait dengan aspek-aspek kosmologis. Kosmologis berarti mencakup kajian tentang awal mula dan teori-teori hakikat perkembangan kosmos sebagai satu kesatuan yang teratur meski terdapat kalangan yang menganggap persoalan-persoalan ini termasuk bidang kosmogoni. Sedangkan, kosmologi lebih pada makna keberadaan alam semesta dan kehidupan yang ada secara umum. Corak ini dapat kita temukan dalam filsafat keagamaan tertentu yang terarah pada tujuan sejarah dan kosmos, termasuk tema-tema yang menyangkut persoalan hakikat ruang dan waktu. Kedua, metafisika teologis. Metafisika teologi adalah bagian dari teori keagamaan yang memperbincangkan konsep-konsep seputar Tuhan. Apakah Tuhan itu? Apakah ia sungguh-sungguh ada? Jika memang ada, seperti apakah keberadaannya? Adakah keberadaan Tuhan sama dengan keberadaan alam semesta ini, yaitu berada dalam dimensi ruang dan waktu atau justru ia memiliki keberadaan yang berbeda? Sementara, pertanyaan metafisika ketiga adalah metafisika antropologis. Di sini metafisika berkaitan dengan keberadaan manusia. Dalam Antropologi, seseorang diajak untuk bertanya dan mempertanyakan hakikat dirinya secara umum, sebagai manusia, atau secara khusus sebagai pribadi. Secara umum, ia mungkin akan bertanya sejak kapan makhluk bernama manusia itu ada dan mengalami hidup di muka bumi ini? Bagaimanakah kehidupan manusia untuk kali pertama kemunculannya? Apakah manusia terlahir sebagai makhluk yang buruk atau justru terlahir baik? Atau, bukan keduanya, sebaliknya netral? Apakah manusia memiliki jiwa? Jika manusia dikatakan memiliki jiwa, lantas apakah jiwa itu? Manusia sering dikatakan sebagai makhluk yang memiliki akal budi, lantas apakah akal budi tersebut? Di sini berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian terefleksikan ke dalam 41 berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perencanaan dan praktik pendidikan. Kemudian, metafisika ketiga adalah metafisika ontologi. Ontologi merupakan kajian tentang hakikat yang “ada” atau apa arti “ada” itu? Tugas ontologi adalah menentukan apa yang kita maksudkan sebagai sesuatu yang ada. Pertanyaan-pertanyaan ontologi antara lain: apakah realitas dasar itu materi atau justru imateri? Apakah ia bersifat tetap atau justru berubah? Apakah realitas itu bersifat independen atau justru dependen? Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno. Studi ontologi selalu terproyeksi untuk memahami apakah “ada” itu. Di Yunani, filsuf yang begitu berlimpah dalam membahas persoalan ontologi di antaranya adalah Thales , Plato , dan Aristoteles . Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka (sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri). Hakikat kenyataan atau realitas memang dapat didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang: i. Kuantitatif. Dalam sudut pandang kuantitatif, kita akan dibawa untuk bertanya: apakah kenyataan itu bersifat tunggal atau jamak? ii. Kualitatif. Sementara, dalam sudut pandang kualitatif, kita akan diajak mempertanyakan: apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti daun yang memiliki warna kehijauan atau bunga mawar yang berbau harum. Di sini kualitas berkaitan dengan situasi atau kondisi. Secara sederhana, ontologi dapat pula dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran 42 dalam bidang ontologi antara lain adalah idealisme, realisme, naturalisme, dan empirisme. Istilah terpenting dalam ontologi antara lain: “yang ada” (being), “kenyataan atau realitas” (reality), “eksistensi” (existence), “esensi” (essence), “substansi” (substance), “perubahan” (change), “tunggal” (one), dan “jamak” (many). Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris (misalnya, antropologi, sosiologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya). 2. Epistemologi Epistemologi berasal dari kata episteme (pengetahuan) dan logos (kata, pembicaraan, ilmu). Secara umum, epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji sumber, watak, dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dengan hakikat ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian atau analogi, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan pancaindra dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber-sumber kebenaran, validitas pengetahuan. Dari pengertian tersebut, epistemologi berusaha menjawab apakah itu kebenaran? Bagaimana kita mengetahuinya? 43 Di sini seseorang akan diajak memahami mungkin dan tidaknya realitas diketahui. Perbedaan landasan ontologi menyebabkan perbedaan dalam menentukan metode yang dipilih dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Akal, akal budi, pengalaman, atau kombinasi akal dan pengalaman, serta intuisi merupakan sarana mencari pengetahuan yang dimaksud dalam epistemologi sehingga dikenal model-model epistemologi, seperti rasionalisme, empirisme, rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi, dan sebagainya. Epistemologi juga membahas kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi beserta tolok ukurnya bagi pengetahuan (ilmiah), seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan intersubjektif. Pengetahuan merupakan daerah persinggungan antara benar dan dipercaya. Pengetahuan dapat diperoleh dari akal sehat antara lain melalui pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan sehingga cenderung bersifat kebiasaan dan pengulangan, cenderung bersifat kabur dan samar. Oleh karenanya, pengetahuan yang diperoleh dari akal sehat merupakan pengetahuan yang tidak teruji. Sementara, ilmu pengetahuan (sains) diperoleh berdasarkan analisis dengan langkah-langkah yang sistematis (metode ilmiah) menggunakan nalar logis. Sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, matematika, dan statistika. Metode ilmiah menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif sehingga menjadi jembatan penghubung antara penjelasan teoretis dan pembuktian yang dilakukan secara empiris. Secara rasional, ilmu menyusun pengetahuannya secara konsisten dan kumulatif, sedangkan secara empiris ilmu memisahkan pengetahuan yang sesuai dengan fakta dari yang tidak. Dengan metode ilmiah, berbagai penjelasan teoretis (atau juga naluri) dapat diuji, apakah sesuai dengan kenyataan empiris atau tidak. Kebenaran pengetahuan dilihat dari kesesuaian artinya dengan fakta yang ada, dengan putusan-putusan lain 44 yang telah diakui kebenarannya dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. Jika seseorang ingin membuktikan kebenaran suatu pengetahuan, cara, sikap, dan sarana yang digunakan untuk membangun pengetahuan tersebut harus benar. Apa yang diyakini atas dasar pemikiran mungkin saja tidak benar karena ada sesuatu di dalam nalar kita yang salah. Demikian pula, apa yang kita yakini karena kita amati, belum tentu benar sebab penglihatan kita dimungkinkan mengalami penyimpangan. Itulah sebabnya, ilmu pengetahuan selalu berubah-ubah dan berkembang. Epistemologi terkadang juga disebut “logika”, yaitu ilmu tentang pikiran. Logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika minor dan logika mayor. Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, seperti silogisme. Logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, dan kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi. *** Dalam sejarahnya, epistemologi di Yunani dipelopori para Sophis. Mereka itulah individu pertama yang secara sadar mempermasalahkan segala sesuatu. Epistemologi juga kerap dikaitkan dengan suatu disiplin yang disebut Critica. Critica adalah pengetahuan sistematis mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan yang tidak benar. Critica berasal dari kata Yunani, krimoni, yang artinya mengadili, memutuskan, dan menetapkan. Mengadili pengetahuan yang benar dan yang tidak benar memang agak dekat dengan episteme sebagai suatu tindakan kognitif intelektual untuk mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jika diperhatikan, batasan-batasan di atas tampak jelas bahwa hal-hal yang hendak diselesaikan epistemologi ialah tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, validitas pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. 45 E. Sumber-Sumber Pengetahuan Sumber-sumber pengetahuan terbagi menjadi empat: akal, hati, intuisi, serta wahyu. Indra digunakan untuk berhubungan dengan dunia fisik atau lingkungan di sekitar kita. Indra ada bermacam-macam, yang paling pokok ada lima (pancaindra), yaitu indra penglihatan atau mata yang memungkinkan kita mengetahui warna, bentuk, dan ukuran suatu benda; indra pendengaran atau telinga yang membuat kita membedakan macam-macam suara; indra penciuman (hidung), untuk membedakan bermacam bau-bauan; indra perasa atau lidah yang membuat kita bisa membedakan makanan enak dan tidak enak; dan indra peraba atau kulit yang memungkinkan kita mengetahui suhu lingkungan dan kontur suatu benda. Pengetahuan lewat indra disebut juga pengalaman bersifat empiris dan terukur. Kecenderungan yang berlebih kepada alat indra sebagai sumber pengetahuan yang utama atau bahkan satu-satunya sumber pengetahuan menghasilkan aliran yang disebut “empirisme”. Tokoh yang menjadi pelopor antara lain adalah John Locke5 (1632–1704) dan David Hume dari Inggris.6 5. John Locke lahir 29 Agustus 1632 dan meninggal 28 Oktober 1704 pada umur 72 tahun. Ia dikenal sebagai filsuf Inggris yang cukup populer, terutama dalam aliran empirisme. Sementara, dalam filsafat politik, Locke kerap dikenal sebagai filsuf liberal. Bersama Isaac Newton, Locke menjadi salah satu figur terpenting Era Pencerahan. Kehadirannya kerap dianggap tanda dari lahirnya era modern dan juga era pasca-Descartes (post-Cartesian), ketika pendekatan Descartes tidak lagi menjadi pendekatan yang dominan di dalam filsafat waktu itu. Pemikiran Locke cenderung menekankan pentingnya pendekatan empiris serta eksperimen dalam ilmu pengetahuan. Locke banyak melahirkan beragam karya, mulai dari filsafat, pendidikan, ekonomi, teologi, dan medis. Karya-karya terpentingnya antara lain Essay Concerning Human Understanding, Letters of Toleration, dan Two Treatises of Government. 6. Ia lahir di Skotlandia 26 April 1711 dan meninggal 25 Agustus 1776 pada umur 65 tahun. Hume kerap dipandang sebagai satu figur penting dalam perkembangan pemikiran filsafat Barat dan Pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya 46 Mengenai kesahihan pengetahuan jenis ini, seorang empirisis sejati akan mengatakan indra adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat dipercaya dan pengetahuan indrawi adalah satu-satunya pengetahuan yang benar. Akan tetapi, jika hanya mengandalkan pengetahuan semata-mata kepada indra, jelas tidak mencukupi. Dalam banyak kasus, penangkapan indra sering tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya, pensil yang dimasukkan ke dalam air terlihat bengkok, padahal sebelumnya lurus. Benda yang jauh terlihat lebih kecil, padahal ukuran yang sebenarnya ternyata jauh lebih besar. Bunyi yang terlalu lemah atau terlalu keras tidak bisa kita dengar. Belum lagi, jika alat indra kita bermasalah, sedang sakit atau sudah rusak. Semakin sulitlah bagi kita untuk hanya mengandalkan indra dalam mendapatkan pengetahuan yang benar. Akal atau rasio merupakan fungsi organ yang secara fisik bertempat di dalam kepala, yaitu otak. Akal mampu menambal kekurangan yang ada pada indra. Akallah yang dapat memastikan bahwa pensil dalam air itu tetap lurus dan bentuk bulan tetap bulat walaupun tampaknya sabit. Keunggulan akal yang paling utama adalah kemampuannya menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta khusus. Akal dapat mengetahui hakikat umum kucing tanpa harus Hume berpusat pada tulisan filosofi, sebagai sejarawanlah dia mendapat pengakuan dan penghormatan. Karyanya The History of England merupakan karya dasar dari sejarah Inggris untuk 60 atau 70 tahun sampai karya Macaulay. Hume merupakan filusuf besar pertama dari era modern yang membuat filosofi naturalistis. Filosofi ini sebagian mengandung penolakan atas prevalensi atas konsepsi pikiran manusia sebagai miniatur kesadaran suci; sebagaimana pernyataan Edward Craig yang dimasukkan dalam doktrin Image of God. Doktrin ini diasosiasikan dengan kepercayaan dalam kekuatan akal manusia dan penglihatan dalam realitas, yaitu kekuatan yang berisi seritikasi Tuhan. Hume sangat dipengaruhi oleh empirisis John Locke dan George Berkeley, dan juga bermacam penulis berbahasa Prancis, seperti Pierre Bayle dan bermacam figur dalam landasan intelektual berbahasa Inggris, seperti Isaac Newton, Samuel Clarke, Francis Hutcheson, Adam Smith, dan Joseph Butler. 47 mengaitkannya dengan kucing tertentu yang ada di rumah tetangganya, kucing hitam, kucing garong, atau kucing-kucingan. Akal mengetahui sesuatu tidak secara langsung, tetapi melalui kategori-kategori atau ide yang inheren dalam akal dan diyakini bersifat bawaan. Ketika kita memikirkan sesuatu, penangkapan akal atas sesuatu itu selalu sudah dibingkai oleh kategori. Kategori-kategori itu antara lain substansi, kuantitas, kualitas, relasi, waktu, tempat, dan keadaan. Pengetahuan yang diperoleh dengan akal bersifat rasional, logis, atau masuk akal. Pengutamaan akal di atas sumber-sumber pengetahuan lainnya atau keyakinan bahwa akal adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Pandangan ini melahirkan apa yang dikenal sebagai aliran rasionalisme yang dipelopori oleh Rene Descartes (1596–1650) dari Prancis. Seorang rasionalis umumnya mencela pengetahuan yang diperoleh melalui indra sebagai semu, palsu, dan menipu. Organ fisik yang berkaitan dengan fungsi hati atau intuisi tidak diketahui dengan pasti—ada yang menyebut jantung, ada juga yang menyebut otak bagian kanan. Pada praktiknya, intuisi muncul berupa pengetahuan yang tiba-tiba saja hadir dalam kesadaran tanpa melalui proses penalaran yang jelas, non-analitis, dan tidak selalu logis. Intuisi dapat muncul kapan saja tanpa kita rencanakan, baik saat santai maupun tegang, ketika diam maupun bergerak. Kadang, ia datang saat kita tengah jalan-jalan di trotoar, saat kita sedang mandi, bangun tidur, saat main catur, atau saat kita menikmati pemandangan alam. Intuisi disebut juga ilham atau inspirasi. Meskipun pengetahuan intuisi hadir begitu saja secara tiba-tiba, tampaknya ia tidak jatuh ke sembarang orang, hanya kepada orang yang sebelumnya sudah berpikir keras mengenai suatu masalah. Ketika seseorang sudah memaksimalkan daya pikirnya dan mengalami kemacetan, ia lalu mengistirahatkan pikirannya dengan tidur atau bersantai. Pada saat itulah, intuisi berkemungkinan muncul. Oleh karena itu, intuisi sering disebut 48 supra-rasional atau suatu kemampuan yang berada di atas rasio dan hanya berfungsi jika rasio sudah digunakan secara maksimal, namun menemui jalan buntu. Hati bekerja pada wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh akal, yaitu pengalaman emosional dan spiritual. Kelemahan akal terpagari oleh kategori-kategori sehingga hal ini, menurut Immanuel Kant (1724–1804), membuat akal tidak pernah bisa sampai pada pengetahuan langsung tentang sesuatu sebagaimana adanya (das ding an sich) atau noumena. Akal hanya dapat menangkap yang tampak dari benda itu (fenoumena), sementara hati dapat mengalami sesuatu secara langsung tanpa terhalang apa pun tanpa ada jarak antara subjek dan objek. Kecenderungan akal untuk selalu melakukan generalisasi (meng-umum-kan) dan spasialisasi (meruang-ruangkan) membuatnya tidak akan mengerti keunikan-keunikan kejadian sehari-hari. Hati dapat memahami pengalaman-pengalaman khusus, termasuk pengalaman yang bersifat eksistensial, yaitu pengalaman riil manusia seperti yang dirasakan langsung, bukan melalui konsepsi akal. Akal tidak dapat mengetahui rasa cinta, hatilah yang merasakannya. Bagi akal, waktu dalam hidup bahkan akan dialami sebagai sesuatu yang sama. Oleh karena itu, ukuran akal kerap bersifat general, dan ini berbeda dengan hati. Hati juga dapat merasakan pengalaman religius, berhubungan dengan Tuhan atau makhluk-makhluk gaib lainnya, dan juga pengalaman menyatu dengan alam. Pengutamaan hati sebagai sumber pengetahuan yang paling dapat dipercaya dibandingkan sumber lainnya disebut intuisionisme. Mayoritas filsuf Muslim memercayai kelebihan hati atas akal. Puncaknya adalah Suhrawardi dengan konsep Isyraqi atau iluminasionisme, yang kemudian diteruskan Mulla Shadra (1631). Di Barat, intuisionisme dikembangkan oleh Henry Bergson. 49 Selain indra akal dan hati, terdapat pula sumber pengetahuan lain yang disebut “wahyu”. Wahyu adalah pemberitahuan langsung dari Tuhan kepada manusia dan mewujudkan dirinya dalam kitab suci agama. Namun, sebagian pemikir Muslim ada yang menyamakan wahyu dengan intuisi, dalam pengertian wahyu sebagai jenis intuisi pada tingkat yang paling tinggi dan hanya nabi yang dapat memerolehnya. Dalam tradisi filsafat Barat, pertentangan keras terjadi antara aliran empirisme dan rasionalisme. Hingga awal abad ke-20, empirisme masih memegang kendali dengan kuatnya kecenderungan positivisme di kalangan ilmuwan Barat. Sedangkan, dalam tradisi filsafat Islam, pertentangan kuat terjadi antara aliran rasionalisme dan intuisionisme (iluminasionisme, ‘irfani), dengan kemenangan pada aliran yang kedua. F. Teori-Teori Kebenaran Dalam hal ini, dikenal empat parameter kebenaran yang diterima secara umum dalam filsafat, antara lain: 1. Korespondensi. The correspondence theory of truth. Dalam teori ini, kebenaran dianggap sebagai kesesuaian antara arti yang dimaksud suatu pendapat dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, pandangan apa pun yang tidak memiliki pemerian dengan realita akan dianggap salah. Sebuah pernyataan dikatakan benar jika sesuai dengan fakta atau kenyataan. Contoh pernyataan “bentuk air selalu sesuai dengan ruang yang ditempatinya” adalah benar karena kenyataannya demikian. “New York ada di Amerika ” adalah benar karena sesuai dengan fakta (bisa dilihat di peta). Korespondensi memakai logika induksi. 2. Koherensi. The consistence theory of truth. Dalam teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dan sesuatu yang lain, seperti fakta atau realitas. Akan tetapi, atas hubungan antara putusan-putusan. Dengan kata lain, kebenaran ditegaskan atas 50 hubungan antara yang baru itu dan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kita akui benarnya terlebih dahulu. Sebuah pernyataan dikatakan benar apabila konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contoh pernyataan “Jackson akan mati” sesuai (koheren) dengan pernyataan sebelumnya bahwa “semua manusia akan mati” dan “Jackson adalah manusia”. Terlihat di sini, logika yang dipakai dalam koherensi adalah logika deduksi. 3. Pragmatik. The pragmatic theory of truth. Teori ini mempunyai arti benar tidaknya sesuatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Sebuah pernyataan dikatakan benar jika berguna (fungsional) dalam situasi praktis. Kebenaran pragmatik dapat menjadi titik pertemuan antara koherensi dan korespondensi. Jika ada dua teori keilmuan yang sudah memenuhi kriteria dua teori kebenaran di atas, yang diambil adalah teori yang lebih mudah dipraktikkan. Agama dan seni dapat cocok jika diukur dengan teori kebenaran ini. Agama dengan satu pernyataannya, misalnya “Tuhan ada”, adalah benar secara pragmatik dalam pengertian pandangan itu menopang nilai-nilai hidup manusia dan menjadikannya teratur, terlepas dari apakah Tuhan itu ada dan sesuai dengan fakta atau tidak. Dari keempat teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran adalah kesesuaian arti dengan fakta yang ada dengan putusan-putusan lain yang telah kita akui kebenarannya dan tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi kehidupan manusia. 4. Aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan, logos berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai, aksiologi merujuk pada pemikiran atau suatu sistem, seperti politik, sosial, dan agama. 51 Perkembangan yang terjadi dalam pengetahuan ternyata melahirkan sebuah polemik baru karena kebebasan pengetahuan terhadap nilai atau yang dapat kita sebut sebagai netralitas pengetahuan (value free). Sebaliknya, ada jenis pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai atau yang lebih dikenal sebagai value bound. Sekarang, mana yang lebih unggul antara netralitas pengetahuan dan pengetahuan yang didasarkan pada keterikatan nilai? Bagi ilmuwan yang menganut paham bebas nilai, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih cepat terjadi karena ketiadaan hambatan dalam melakukan penelitian, baik dalam memilih objek penelitian, cara yang digunakan, maupun penggunaan produk penelitian. Sedangkan, bagi ilmuwan penganut paham nilai terikat, perkembangan pengetahuan akan terjadi sebaliknya karena dibatasinya objek penelitian, cara, dan penggunaan oleh nilai. Kendati demikian, paham pengetahuan yang disandarkan pada teori bebas nilai ternyata melahirkan sebuah permasalahan baru. Dari yang tadinya menciptakan pengetahuan sebagai sarana membantu manusia, ternyata kemudian penemuannya tersebut justru menambah masalah bagi manusia. Di sisi lain, menjadi hal yang tidak mengherankan jika seorang Carl Gustav Jung membuat satu ungkapan, “Betapa bukan lagi Goethe yang melahirkan Faust, melainkan Faust-lah yang kemudian melahirkan Goethe.” G. Etika Di beberapa literatur, etika kerap dimasukkan ke dalam aksiologi, yaitu dideretkan dengan estetika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Etika merupakan salah satu cabang filsafat tertua. Setidaknya, ia telah menjadi pembahasan 52 menarik sejak masa Socrates dan para Sophis. Di situ dipersoalkan masalah kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sebagainya. Etika dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Isi pandangan-pandangan moral ini sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah norma-norma, adat, wejangan, dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, tetapi sebuah pemikiran yang kritis dan mendasar. Tujuan etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Dalam perkembangan sejarah, etika terdiri dari empat teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedonisme, eudemonisme, utilitarisme, dan deontologi. Hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan: kebahagiaan. Selanjutnya, utilitarisme, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Selanjutnya, deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant.7 Menurut Kant, yang dapat disebut “baik” dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Misalnya, kekayaan manusia akan menjadi baik apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Sementara itu, 7. Ia bernama Immanuel Kant. Ia lahir sebagai anak keempat dari seorang pembuat pelana kuda di Kota Konigberg pada 1724 M. Konon, beberapa nenek moyangnya adalah pendatang dari Skotlandia. Dia berkembang sebagai seorang Kristen yang saleh. Kant identik dengan keluhan dan banyak mengkhawatirkan kematian dirinya. Namun begitu, Kant banyak melahirkan karya-karya filsafat, khususnya yang paling populer adalah pemikiran-pemikirannya yang mengulas persoalan etika (Abdullah, 2002). 53 cabang lain aksiologi, yaitu estetika, dibahas dalam sesi lain. Estetika membicarakan indah dan tidak indah. *** Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos. Istilah ini memiliki makna cukup mustarak (baca: beragam), kadang diartikan sebagai tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, terkadang pula diartikan sebagai adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, ataupun cara berpikir. Dalam bentuk jamak, istilah ini menjadi ta etha yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan, secara terminologis, etika memiliki tiga makna: (1) etika sebagai kumpulan nilai-nilai atau asas tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak; (2) etika sebagai nilai-nilai benar salah, baik buruk yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat; dan (3) etika sebagai ilmu pengetahuan tentang apa yang baik dan yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Etika merupakan teori tentang nilai, pembahasan secara teoretis tentang nilai, dan ilmu kesusilaan yang memuat dasar berbuat susila. Sedangkan, moral pelaksanaannya dalam kehidupan. Jadi, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia, cara memandangnya dari sudut baik dan tidak baik. Etika merupakan filsafat tentang perilaku manusia. Antara ilmu (pendidikan) dan etika memiliki hubungan erat. Masalah moral tidak dapat dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran, diperlukan keberanian moral. Sulit membayangkan perkembangan iptek tanpa adanya kendali dari nilai-nilai etika agama. Untuk itulah, kemudian terdapat rumusan pendekatan konseptual yang dapat dipergunakan sebagai jalan pemecahannya, yaitu dengan menggunakan pendekatan etika-moral, 54 setiap persoalan pendidikan Islam coba dilihat dari perspektif yang mengikutsertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, maupun masyarakat luas. Artinya, pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, dan kreatif—tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Terwujudnya kondisi mental-moral dan spiritual religius menjadi target arah pengembangan sistem pendidikan. Etika adalah filsafat yang menguraikan perilaku manusia, nilai, dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pemikiran dalam filsafat. Filsafat etika sangat besar memengaruhi pendidikan sebab tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan perilaku manusia, antara lain afeksi peserta didik. Berdasarkan pemaknaan di atas, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang memiliki sisi keterkaitan dengan nilai atau memiliki relevansi etis dapat dipandang sebagai etika. Agama, misalnya, adalah sesuatu yang tidak berbeda dengan hukum, adat kebiasaan, ataupun nilai-nilai yang berlaku dalam sosial, yang kesemuanya itu dapat dikategorisasikan sebagai etika. Itu disebabkan oleh agama, hukum, atau adat kebiasaan memiliki unsur etis atau memuat pandangan-pandangan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Bukan hanya itu yang mengacu makna di atas, etiket agaknya pun dapat pula dikategorisasikan sama dengan etika. Hanya saja, penyebutan etika di sini bukan etika dalam makna ketiga, yaitu etika sebagai ilmu, melainkan etika dalam makna pertama dan kedua, yaitu etika sebagai kumpulan nilai-nilai atau asas tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, atau etika sebagai nilai-nilai benar salah, baik buruk yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Pemaknaan ini akan berbeda manakala dirujukkan pada makna etika yang ketiga, yaitu etika sebagai ilmu yang membicarakan nilai baik 55 buruk, hak, serta kewajiban moral. Dengan mengacu makna ini, tidak semua hal yang memuat persoalan nilai baik buruk, benar salah dapat dipandang sebagai etika. Hukum, misalnya, sungguh pun ia adalah bidang yang juga membicarakan persoalan nilai, perbincangan nilai dalam hukum jauh bersifat lebih pasti dan objektif ketimbang perbincangan nilai dalam etika, yang justru bersifat relatif dan cenderung subjektif. Kenyataan tersebut terjadi juga dengan agama. Meski agama dibangun dan dihidupi dengan dan dalam kerangka etis tertentu, dengan mengacu definisi yang ketiga, agama tetap tidak bisa disebut sebagai etika. Agama yang tidak memadai disebut etika dalam makna ketiga, bersinggungan erat dengan sifat dan ruang lingkup keduanya yang sangat berbeda. Jika dibandingkan, pembahasan etika bersifat jauh lebih bebas dan lebih luas ketimbang pembahasan agama yang justru bersifat pasti. Oleh karena itulah, ulasan-ulasan nilai dalam etika kerap dipandang melampaui batasan asumsi-asumsi nilai baik buruk, salah-benar yang ada dalam agama. Meski demikian, etika tidak dapat meninggalkan agama. Hal itu terkait manakala etika tidak pernah dapat secara mandiri menyediakan nilai dan orientasi dasar bagi hidup manusia. Nilai dan orientasi hidup itu justru diperoleh etika dari sumber-sumber lain: adat istiadat, tradisi, ideologi, termasuk juga dari agama. Pola relasi ini hampir-hampir bersifat konstan dan tak terelakkan karena agama adalah salah satu sumber yang menyediakan orientasi dan nilai-nilai hidup yang itu dibutuhkan etika. Hanya saja, hubungan tersebut tidak bersifat substitutif, dalam arti bahwa yang satu dapat menggantikan yang lainnya. Oleh karena itu, walau bagaimanapun, etika tidak dapat menggantikan agama. Sebaliknya agama, dalam banyak hal membutuhkan etika. 56 Kemudian, etika sebagai ilmu yang membicarakan persoalan nilai baik buruk, salah-benar, serta hak dan kewajiban secara populer terbagi ke dalam tiga pendekatan utama: (1) etika deskriptif, (2) etika normatif, dan (3) metaetika. Etika deskriptif adalah etika yang melukiskan tingkah laku moral sebagaimana adanya tanpa berusaha menilai atau menghakimi tingkah laku tersebut. Ini bisa dicontohkan, misalnya dengan penelitian tentang bagaimana suatu adat kebiasaan serta bagaimana anggapan-anggapan, tindakan yang diperbolehkan, atau yang tidak diperbolehkan berlaku dalam suatu masyarakat. Sebuah penelitian yang mencoba melukiskan tentang apa dan bagaimana nilai-nilai yang menghidupi masyarakat Yogyakarta, misalnya, adalah penelitian yang masuk dalam kategori etika ini. Hanya saja, penelitian tersebut tidak akan lagi bisa disebut sebagai etika deskriptif manakala penelitian tersebut telah diarahkan guna memeriksa atau menjustifikasi pandangan-pandangan etis yang ada. Oleh karena itu, etika deskriptif tidak lebih dan tidak kurang semata-mata hanya mempelajari dan mendeskripsikan bagaimana moralitas individu-individu tertentu—dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultur-subkultur tertentu atau dalam suatu rentang periode sejarah tertentu. Sementara, pendekatan etika model kedua, etika normatif, adalah etika yang tidak hanya melukiskan tingkah laku moral sebagaimana adanya, tetapi juga menilai, menjustifikasi, dan mengevaluasi. Oleh karena itu, dalam etika normatif, nilai baik buruk, salah-benar tidak hanya digambarkan atau dideskripsikan, tetapi juga dievaluasi dan direfleksikan sisi relevansi etisnya. Kenyataan ini mau tidak mau membuat etika normatif berurusan dengan argumentasi-argumentasi etis dari evaluasi-evaluasi nilai yang dilahirkannya. Sebagai contoh, ketika terdapat sebuah penelitian yang meneliti tentang masih sesuai dan tidakkah kehidupan umat Islam dengan 57 nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Maka, sudah barang tentu jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian etika model normatif—sebuah etika yang jika dilihat dari ruang lingkup serta impresi aksiologinya kerap dibagi menjadi dua tipe: etika umum dan etika khusus. Dalam tipe etika normatif umum, perbincangan dan refleksi nilai-nilai etis berlangsung pada hal-hal yang bersifat umum, seperti apakah yang disebut norma etis? Mengapa norma itu mengikat kita? Atau, bagaimana hubungan antara tanggung jawab manusia dan kebebasannya? Apa yang disebut hak, kewajiban, dan lain sebagainya. Maka, perbincangan dalam etika normatif umum tidak sampai melahirkan kesimpulan etis yang bersifat normatif. Ini berbeda dengan tipe etika normatif khusus, yang justru diarahkan guna mematerialisasikan pandangan-pandangan etis ke dalam wilayah perilaku keseharian manusia. Oleh karena itu, etika normatif khusus kerap disebut sebagai etika terapan karena dimaksudkan guna menerapkan suatu pandangan-pandangan nilai tertentu dalam ruang kehidupan manusia. Dalam pengertian etika sosial Islam, dapat pula dipandang sebagai etika terapan. Kemudian, pendekatan etika yang ketiga adalah model pendekatan metaetika. Metaetika adalah bidang etika yang sepenuhnya memiliki pendekatan berbeda dengan dua pendekatan etika di awal. Jika etika deskriptif bersifat semata-mata menggambarkan bagaimana nilai-nilai etis berlaku di sebuah masyarakat, etika normatif bermaksud memeriksa nilai-nilai etis tersebut. Maka, metaetika justru lebih tertarik membicarakan sesuatu yang jauh lebih abstrak, yaitu pada bahasa etis. Dari bahasa etis tersebut, perbincangan istilah-istilah etis, seperti “apa itu baik” atau “apa itu buruk” menjadi wilayah garapan metaetika. Dalam ungkapan lain, metaetika dapat pula diungkap sebagai bidang etika yang membicarakan logika khusus dari ungkapan-ungkapan etis. 58 H. Logika Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme (Latin: logica scientia) atau ilmu logika (ilmu pengetahuan) yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika adalah cara berpikir atau penalaran menuju kesimpulan yang benar. Aristoteles (384–322 SM) adalah pembangun logika yang pertama. Logika Aristoteles ini, menurut Immanuel Kant, 21 abad kemudian, tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik penambahan maupun pengurangan. Aristoteles memperkenalkan dua bentuk logika yang sekarang kita kenal dengan istilah “deduksi” dan “induksi”. Logika deduksi dikenal juga dengan nama “silogisme”, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum atas hal yang khusus. Contoh terkenal silogisme: Semua manusia akan mati (pernyataan umum, premis mayor). Sabri manusia (pernyataan antara, premis minor). Sabri akan mati (kesimpulan, konklusi). Logika induksi adalah kebalikan deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus menuju pernyataan umum. Sebagai contoh: Sabri adalah manusia, dan ia mati (pernyataan khusus) 59 Tamam, Gobest, dan lain-lain adalah manusia, dan semuanya mati (pernyataan antara) Semua manusia akan mati (kesimpulan) *** I. Apakah Pendidikan Itu? Sejak kemunculannya yang pertama, manusia adalah spesies yang selalu dilanda polemik makna. Hal ini berkaitan dengan eksistensi manusia yang selalu bersifat labil dan tidak pernah berhenti pada satu titik. Penjelasan paling memadai dari kondisi ini terkait dengan ketidakmampuan manusia memanipulasi potensi dirinya sebagai spesies yang selalu mendamba makna dan nilai keberartian dalam hidupnya, serta dunia manusia yang selalu rentan di sisi yang lain. Dari dan dalam dua hal itulah, manusia kemudian selalu dihadapkan dengan hidup yang tidak bisa sekadarnya saja, tetapi selalu harus dirumuskan dengan kode-kode tertentu, rencana-rencana, orientasi, serta nilai-nilai yang dipandangnya bermakna dan berarti. Hanya saja, sulitnya dalam hidupnya, makna dan keberartian hidup itu tidak bisa muncul dengan sendiri, sebaliknya mesti diperjuangkan, terutama sekali diketahui. Hidup manusia adalah hidup yang selalu berkaitan dengan makna dan pergulatan mencari “kebaikan”.8 Oleh karenanya, pertanyaan 8. Kata kebaikan di sini dipahami banyak orang dengan istilah yang berbeda-beda. Salah satu yang terpenting barangkali adalah “kebahagiaan”. Setiap orang berusaha mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Beragam falsafah hidup digariskan untuk membantu manusia mencapainya. Lihat Russell, Menuju Hidup Bahagia (terj. C. Woekirsari), (Jakarta: Pantja Simpati, 1986), hlm. 11. Etika Yunani, secara garis besar, menekankan persoalan mencari kebahagiaan ini. Pembahasan yang cukup lengkap tentang etika Yunani beserta keberpusatannya pada konsep “kebahagiaan” dapat dilihat dalam Muhammad Abed Al-Jabiry, Al-‘Aql al-Akhlâqî al-‘Arabî: Dirâsah Tahlîliyyah Naqdiyyah li 60 “bagaimana saya harus hidup: mulai dari bagaimana mengalami hidup, bagaimana menyadari hidup atau hidup mesti disadari dan bagaimana bertindak dalam hidup” muncul menjadi pertanyaan fundamental yang terus mengiringi hidup manusia sejak lahir hingga mati, terutama karena hidup manusia membutuhkan orientasi dan tujuan hidup. Hidup yang baik dan bermakna bukanlah hidup yang muspra, melainkan hidup yang “menjanjikan” sesuatu untuk dicapai. Sementara, manusia selalu menjadi makhluk yang yang berbeda dengan spesies mana pun, yang secara instingtual telah terbentuk sejak mula dilahirkan. Manusia, dalam hal ini, justru selalu menjadi makhluk potensial, yang seluruhnya selalu belum terbentuk. Di satu sisi, ia memiliki kecenderungan baik, namun di sisi yang lain, ia juga memiliki kecenderungan buruk. Dalam situasi inilah, pendidikan kemudian dipandang perlu bagi hidup manusia. *** Secara harfiah, pendidikan berasal dari kata didik. Namun demikian, secara istilah pendidikan kerap diartikan sebagai “upaya”. Sedangkan, menurut W.J.S. Poerwadarminta, pendidikan secara letterlijk berasal dari kata dasar didik dan diberi awalan men-, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Istilah “pendidikan” secara terminologi didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli pendidikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh welthanscauung masing-masing. Ada yang melihat dari kepentingan atau aspek yang diembannya, dari proses ataupun dilihat dari aspek yang terkandung di dalam pendidikan, Nudhum al-Qiyam fî al-Tsaqâfah al-‘Arabiyyah, (Maroko: Dar al-Nasyr al-Maghribiyyah, 2001), hlm. 257–424. 61 dan dari fungsi pendidikan. Pendidikan dalam arti luas merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. *** Dalam sejarahnya, pendidikan kerap diungkap berasal dari istilah “pedagogi” (paedagogie, bahasa Latin) yang berarti pendidikan. Kata pedagogia (paedagogik) berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani. Pedagogia terdiri dari dua kata, yaitu paedos (anak) dan agoge yang berarti “saya membimbing”, “memimpin anak”. Sedangkan, paedagogos ialah seorang pelayan atau pemuda pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantar dan menjemput anak-anak (siswa) ke dan dari sekolah. Kata paedagogos yang semula berkonotasi rendah (pelayan, pembantu), kemudian dipakai sebagai nama pekerjaan mulia, yaitu paedagoog (pendidik atau ahli didik atau guru). Dari sudut pandang ini, pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Kemudian, dilihat dari sisi yang lain, semisal dilihat fungsinya, pendidikan kerap dipandang sebagai upaya menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa mendatang. Fungsi pendidikan yang kedua, yaitu mentransfer pengetahuan, sesuai peranan yang diharapkan; dan ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban. Adapun definisi pendidikan yang disandarkan pada makna dan aspek serta ruang lingkupnya, dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba, “Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara 62 sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama.” Kemudian, terdapat pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai suatu proses yang tidak dapat dilepaskan dari keterikatannya dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, ketika pendidikan diartikan sebagai rangkaian bimbingan dan pengarahan hidup manusia, yaitu berupa kemampuankemampuan dasar (potensi fitrah) dan kemampuan ajar (intervensi) sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan pribadinya, baik dalam statusnya sebagai makhluk individu, sosial, maupun hubungannya dengan alam sekitarnya tempat ia hidup. Asy-Syaibani, misalnya, mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Sementara, menurut Ensiklopedi Pendidikan, pendidikan berarti semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk memberikan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan keterampilannya kepada generasi di bawahnya sebagai usaha menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun ruhaninya. M. Kamal Hasan berpendapat bahwa pendidikan berarti suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik sehingga seorang Muslim disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakil-Nya di bumi. Adapun menurut Ali Asraf, pendidikan adalah suatu upaya melatih perasaan murid-murid sehingga dalam sikap, tindakan, keputusan, atau pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etika. Menurut F.J. McDonald, pendidikan adalah sebuah proses atau aktivitas yang 63 menunjukkan proses perubahan yang diinginkan di dalam tingkah laku manusia. Perbedaan ataupun kontroversi tentang definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan dianggap suatu hal yang wajar karena perbedaan tersebut dipengaruhi oleh welthanscauung masing-masing dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh para pakar tersebut. Pendidikan secara spesifik adalah pemberian bimbingan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan (Langeveld, dalam Sadulloh, 2003:54; Pidarta, 1997:10). Sedangkan, secara umum dapat diartikan sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada anak supaya anak itu kelak cakap dalam menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Sementara itu, Brojonegoro memberi makna pendidikan secara luas sebagai bentuk pemberian tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dalam arti ruhani dan jasmani. Selanjutnya, menurut tokoh pendidikan dari Indonesia, Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Pidarta, 1997:10). Berpijak dari pendidikan dalam arti khusus, setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, pendidikan dianggap selesai. Tampaknya, pendidikan yang dimaknai khusus tersebut tecermin dalam pendidikan di lingkungan keluarga. Orangtua yang terdiri dari ayah dan ibu menjadi figur sentral dalam pendidikan keluarga. Mereka bertanggung jawab memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anak-anaknya. Setelah sang anak menjadi dewasa atau menjadi manusia sempurna, bantuan pendidikan yang diberikan oleh ayah dan ibu tersebut dianggap telah selesai. 64 Dilihat dari uraian tersebut, kemunculan sekolah tidak lain karena orangtua menganggap dirinya tidak sanggup dengan sepenuh waktu mendampingi anak-anaknya belajar mencapai kedewasaan. Bahkan, akhir-akhir ini ada kecenderungan seorang ibu demi sebuah kariernya, menitipkan anak-anaknya di tempat-tempat penitipan anak. Tampaknya, mereka tidak menyadari bahwa dampak psikologis anak akan memengaruhi perkembangan di masa mendatang. Pendidikan berkaitan erat dengan segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia mulai perkembangan fisik, kesehatan keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. Perkembangan ini membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dan kehidupan alamiah menjadi berbudaya dan bermoral. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, Rupert C. Lodge, dalam bukunya Philosophy of Education (1974), menyatakan bahwa dalam pengertian yang luas pendidikan itu menyangkut seluruh pengalaman. Namun, faktanya bahwa tidak semua pengalaman dapat dikatakan pendidikan. Mencuri, mencopet, korupsi, dan membolos, misalnya, bagi orang yang pernah melakukannya tentunya memiliki sejumlah pengalaman. Akan tetapi, pengalaman itu tidak dapat dikatakan pendidikan karena pendidikan itu memiliki tujuan yang mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Banyak rumusan pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli. John Dewey, misalnya, lebih banyak mengartikan pendidikan sebagai proses pembentukan kecakapan mendasar secara intelektual dan emosional sesama manusia. Sementara, J.J. Rousseau justru melihat pendidikan sebagai pemberian bekal kepada kita apa yang tidak kita butuhkan pada masa kanak-kanak, tetapi kita butuhkan pada saat dewasa. Dalam sifat yang lain, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk memengaruhi dan membimbing anak ke arah kedewasaan agar anak 65 cekatan melaksanakan tugas hidupnya. Di sini pendidikan berlangsung dalam suasana pergaulan antara orang yang sudah dewasa (atau yang diciptakan orang dewasa, seperti sekolah, buku model, dan sebagainya) dan orang yang belum dewasa yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan proses timbal balik dari tiap individu manusia dalam rangka penyesuaian dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Terdapat pula seorang tokoh yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah proses yang berbentuk secara non-fisik dari unsur-unsur budaya yang dipelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak muda atau dalam pembelajaran orang dewasa. Mortimer J. Adler berpandangan jika pendidikan adalah proses tempat semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapa pun untuk membantu orang lain atau dirinya mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Definisi di atas dapat dibuktikan kebenarannya oleh filsafat pendidikan, terutama yang menyangkut permasalahan hidup manusia, dengan kemampuan-kemampuan asli dan yang diperoleh atau tentang bagaimana proses memengaruhi perkembangannya harus dilakukan. Suatu pandangan atau pengertian tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek pembahasan menjadi pola dasar yang memberi corak berpikir ahli pikir yang bersangkutan. Bahkan, arahnya pun dapat dikenali juga. Dari berbagai pandangan di atas dapat dilihat bahwa di kalangan pakar pendidikan masih terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan ahli pendidikan dan kondisi pendidikan yang diperbincangkan saat itu, yang semuanya memiliki perbedaan karakter dan permasalahan. 66 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana (bertahap) dalam meningkatkan potensi diri peserta didik dalam segala aspeknya menuju terbentuknva kepribadian dan akhlak mulia dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang tepat guna melaksanakan tugas hidupnya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di Indonesia, secara umum, pendidikan dalam arti luas telah tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973, “Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.” Demikian pula dalam amanat Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kedua hal tersebut kini menjadi landasan sistem pendidikan di negara kita. J. Jalan dan Tujuan Pendidikan Jalan pendidikan dilakukan dengan pengajaran atau transformasi ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan selalu akan ditemukan proses transformasi ilmu dan pengetahuan dilakukan. Pada hakikatnya, pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mentransformasikan segala nilai. Nilai-nilai yang dimaksud meliputi nilai-nilai religi, budaya, sains dan teknologi, seni, dan nilai keterampilan. Tujuan pentransformasian nilai tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan dan mengembangkan. 67 Bahkan, (kalau perlu) mengubah kebudayaan yang dimiliki masyarakat (Sadulloh, 2003:57). Untuk mencapai proses transformasi yang efektif, diperlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah harus ada hubungan edukatif yang baik antara pendidik dan terdidik. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan kasih sayang antara siswa dan guru berdasarkan kewibawaan. Kedua, harus ada metode pendidikan yang sesuai. Maksudnya adalah terdapat kesesuaian metode dengan kemampuan pendidik, materi, kondisi peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kondisi lingkungan tempat pendidikan berlangsung. Ketiga, harus ada sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, ada kesesuaian antara nilai yang akan ditransformasikan dan sarana prasarana yang dibutuhkan serta sarana tersebut harus didasarkan atas pengabdian pada peserta didik. Keempat, harus ada suasana yang memadai. Suasana yang memadai dan menyenangkan menunjang terjadinya proses transformasi nilai agar berjalan dengan baik. Jika berbicara tentang tujuan pendidikan, akan terkait erat dengan sistem nilai dan norma-norma dalam suatu konteks kebudayaan. Di dalam tujuan pendidikan, ada beberapa nilai yang perlu diperhatikan. Pertama, pendidikan haruslah bersifat otonomi, yaitu memberi kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk dapat hidup mandiri dan hidup bersama dalam kehidupan yang lebih baik. Kedua, pendidikan haruslah bersifat equity (adil), memberi kesempatan seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya dan kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Ketiga, survival, artinya dengan pendidikan menjamin pewarisan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 68 Sebagaimana yang tersebut dalam uraian sebelumnya, pendidikan secara khusus dapat diartikan sebagai pemberian bimbingan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan atau pendidikan secara luas sebagai bentuk pemberian tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan. Secara umum, manusia dewasa ialah manusia yang dianggap telah mandiri, bertanggung jawab, telah mampu memahami norma-norma serta moral dalam kehidupan, sekaligus berkesanggupan untuk melaksanakan norma dan moral tersebut. Pendidikan di Indonesia terproyeksikan pada ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafahnya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan secara umum ditujukan untuk menghasilkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang sikap dan perilakunya senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan, “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.” Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang tumbuh dan berkembang. Oleh karena tumbuh dan berkembang, manusia tidak pernah stagnan dalam hidupnya, tetapi selalu dinamis. Dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik, ia selalu bereksplorasi dengan alam dan sesamanya, serta berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam hidupnya. Untuk dapat mencapai yang terbaik, manusia terus belajar. Selama itulah pendidikan terus berjalan. 69 Sekarang orang berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi dapat dilakukan di mana saja—di sekolah, di luar sekolah (di rumah, di masyarakat), dan sebagainya. Selain itu, kegiatan belajar juga tidak hanya berlangsung pada masa anak-anak, tetapi merupakan kegiatan yang terus-menerus sampai mereka mati. Pendidikan yang demikian itu disebut pendidikan seumur hidup (long life education). Jadi, pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang berlangsung sejak manusia lahir sampai ia mati (Natawidjaya, 1979:105). Konsep pendidikan sepanjang hayat adalah semua kegiatan pendidikan dianggap sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya, seluruh sektor pendidikan merupakan suatu sistem yang terpadu. Selain itu, model pendidikan yang diterapkan bersifat adaptif, yaitu pendidikan yang dilakukan selalu mengikuti perkembangan lingkungan dan disesuaikan dengan kenyataan serta kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang telah maju tentu akan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang belum maju. K. Hubungan Filsafat dan Pendidikan Setelah kita membahas pengertian, jalan, dan tujuan filsafat serta pendidikan, apa sesungguhnya hubungan antara keduanya sehingga di sini mesti kita bahas dalam ruang bersamaan? Jika ditelaah lebih jauh, filsafat dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, baik dilihat dari proses, jalan, serta tujuannya. Hal ini sangat terpahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama sekali filsafat nilai, yaitu terkait dengan ketidakmampuan manusia di dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendamba makna—kesamaan di dalam proses, ruang etika, dan ruang pragmatis. 70 Di satu sisi, manusia selalu menjadi satu-satunya primata yang selalu menyerukan kebaikan, cinta, dan kebenaran. Namun, bersamaan dengan itu, manusia pula satu-satunya makhluk yang dapat membunuh diri dan sesamanya dengan begitu tanpa alasan sama sekali, selain hanya sebuah kesenangan. Dalam ruang inilah pendidikan bagi hidup manusia menjadi sesuatu hal yang penting untuk membawanya pada hidup yang bermakna. Dengan pendidikan, manusia akan mampu menjalani hidupnya dengan baik dan benar. Dengan demikian, ia bisa tertawa, menangis, bicara, dan diam mengambil ukuran-ukuran yang tepat. Ini sangat berbeda dengan banyak diri yang tidak terdidik. Hubungan ini menurut pakar merupakan ilmu yang paling tertua dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, mereka menyebut bahwa filsafat adalah induk semua ilmu-ilmu pengetahuan di muka bumi ini. Sementara, filsafat mengakui bahwa menurut substansinya yang ada itu tunggal, dan berada di tingkat abstrak, bersifat mutlak, serta tidak mengalami perubahan. Sedangkan, menurut eksistensinya, yang ada itu plural, berada di tingkat konkret, bersifat relatif, dan mengalami perubahan terus-menerus. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia pengalaman itu berasal mula dari satu substansi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana menyikapi segala pluralitas ini agar tidak terjadi benturan antara satu dan lainnya? Misalnya, pluralitas jenis, sifat, dan bentuk manusia, binatang, tumbuhan, dan badan-badan benda berasal dari satu substansi. Apakah yang seharusnya dilakukan agar antara manusia satu dan lainnya tidak saling berbenturan kepentingan sehingga dapat mengancam keteraturan sosial dan ketertiban dunia? Jawaban terhadap persoalan di atas adalah manusia harus bersikap dan berperilaku adil terhadap diri sendiri, masyarakat, dan terhadap alam. Agar dapat berbuat demikian, manusia harus berusaha mendapatkan 71 pengetahuan yang benar mengenai keberadaan segala sesuatu yang ada ini, dari mana asalnya, bagaimana keberadaannya, dan apakah yang menjadi tujuan akhir keberadaan tersebut. Untuk itu, manusia harus mendidik diri dan sesamanya secara terus-menerus. Bertolak dari pemikiran filsafat tersebutlah pendidikan muncul dan memulai sesuatu. Manusia mulai mencoba mendidik diri dan sesamanya dengan sasaran menumbuhkan kesadaran terhadap eksistensi kehidupan ini. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan ditekankan pada materi yang berisi pengetahuan umum berupa wawasan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan. Kesadaran terhadap asal mula dan tujuan kehidupan menjadi landasan bagi perilaku sehari-hari sehingga semua kegiatan eksistensi kehidupan ini selalu bergerak teratur menuju satu titik tujuan akhir. Berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan membangun filsafat hidup agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kehidupan sehari-hari tersebut selalu dalam keteraturan. Jadi, terhadap pendidikan, filsafat memberikan sumbangan berupa kesadaran menyeluruh tentang asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apakah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap berada di dalam dunia utopianya. Oleh karena itulah, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, guru memahami hakikat pendidikan dan pendidikan dapat dikembangkan melalui falsafah ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Pengertian filosofi pendidikan dan bagaimana penerapannya serta apa dampak dari pendidikan harus diketahui oleh guru karena pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi setiap manusia, termasuk guru di dalamnya. Jadi, seorang guru harus mempelajari filsafat pendidikan karena dengan memahami dan memaknai filsafat itu, akan 72 dapat memberikan wawasan dan pemikiran yang luas terhadap makna pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan filsafat lainnya, misalnya filsafat hukum, filsafat agama, filsafat kebudayaan, dan filsafat lainnya. Dalam pengertian tersebut, filsafat tidak lain bertujuan membawa manusia mengalami hidup yang dimilikinya dengan pandangan, pengalaman, pengetahuan, serta penghayatan yang baik dan benar. Dengan pemahaman tersebut, manusia mampu menyadari hidup yang dimilikinya dengan benar tanpa adanya. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, sedangkan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Oleh karena itu, dalam filsafat, jauh sebelum persoalan-persoalan mesti dicari jawabannya, filsafat selalu terlebih dahulu mempertanyakan sejauh mana relevansi persoalan-persoalan tersebut. Adakah ia sungguh-sungguh memang sebuah problem atau justru hanya diproblematikakan saja? Di sini, filsafat membahas sesuatu dari segala aspeknya yang mendalam. Maka, dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Sesungguhnya, isi alam yang dapat diamati hanya sebagian kecil saja, diibaratkan mengamati gunung es, hanya mampu melihat yang di atas permukaan laut saja. Sementara, filsafat mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan renungan yang kritis. Sedangkan, pendidikan merupakan salah satu bidang ilmu, sama halnya dengan ilmu-ilmu lain. Pendidikan lahir dari induknya, yaitu filsafat. Sejalan dengan proses perkembangan ilmu, ilmu pendidikan juga lepas secara perlahan-lahan dari induknya. Pada awalnya, pendidikan berada bersama dengan filsafat sebab filsafat tidak pernah bisa membebaskan diri dengan pembentukan manusia. Filsafat diciptakan oleh manusia untuk 73 kepentingan memahami kedudukan manusia, pengembangan manusia, dan peningkatan hidup manusia. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulannya dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan ruhani ke arah kedewasaan. Secara garis besar, pengertian pendidikan dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, pendidikan; kedua, teori umum pendidikan; dan ketiga, ilmu pendidikan. Dalam pengertian pertama, pendidikan pada umumnya mendidik yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pendidikan seperti ini sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Pada zaman purba, kebanyakan manusia memerlukan anak-anaknya secara insting atau naluri, suatu sifat pembawaan, demi kelangsungan hidup keturunannya. Tindakan yang termasuk insting manusia antara lain sikap melindungi anak, rasa cinta terhadap anak, bayi menangis, kemampuan menyusu air susu ibu, dan merasakan kehangatan dekapan ibu. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia. Mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman. Kegiatan mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Kegiatan mendidik adalah membudayakan manusia. Dalam pengertian kedua, pendidikan dalam teori umum, menurut John Dewey, “The general theory of education dan Philoshophy is the general theory of education.” Dia tidak membedakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan atau filsafat pendidikan sama dengan teori pendidikan. Sebab itu, ia mengatakan pendidikan adalah teori umum pendidikan. Konsep di atas bersumber dari filsafat pragmatis atau filsafat pendidikan progresif. Inti filsafat pragmatis yang berguna bagi manusia itulah yang benar, sedangkan inti filsafat pendidikan progresif mencari 74 terus-menerus sesuatu yang paling berguna hidup dan kehidupan manusia. Dalam pengertian ketiga, ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah cabang ilmu yang terkait satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan. Masing-masing cabang ilmu pendidikan dibentuk oleh sejumlah teori. *** 75 “Setiap orang nyaris selalu hanya memercayai pengalamannya.” (Empedokles, 490–435 SM)9 9. Empedokles adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Baginya, makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Bentuk-bentuk ini berubah dan makhluk-makhluk yang memiliki bentuk yang paling baik bertahan hidup. Pemikiran ini adalah bentuk seleksi alam yang merupakan mekanisme penting dalam evolusi. Bab II Filsafat Pendidikan A. Pengertian Filsafat Pendidikan Filsafat adalah keajaiban hidup yang nyaris tak terbayangkan, bahkan oleh imajinasi dan nalar terliar filsuf mana pun. Filsafat hadir dan meruang dalam hidup manusia dengan cara-cara yang sepenuhnya tak terbayangkan sehingga sejarah filsafat kerap menunjukkan betapa filsafat nyaris tak berbeda dengan sihir, penuh kejutan dan selalu memesona. Di era yang jauh, di sebuah negeri bernama Yunani, keindahan sihir filsafat dikisahkan kerap merebut pemuda-pemuda gagah untuk segera meninggalkan masa mudanya, lalu hidup dan tinggal di dunia yang sepenuhnya sunyi dan bukan apa pun. Sosok Thales dari Miletos, misalnya, adalah salah satu diri yang tersentuh dan pernah disentuh oleh keajaiban filsafat. Persentuhanpersentuhan Thales dengan filsafat berlangsung dengan cara-cara yang begitu sederhana sehingga siapa pun yang melihatnya tidak akan menyadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang ajaib. Akan tetapi, sejarah memiliki bukti yang begitu kaya, yang menunjuk betapa sejak persentuhan Thales dengan filsafat, ia hidup menjadi diri 79 yang sepenuhnya berbeda dari setiap diri yang hidup di zamannya. Ini menjadi bukti sekaligus sejarah, betapa di waktu yang sangat lama, filsafat selalu tidak pernah kekurangan aspek-aspek eksotis yang menunjuk bahwa filsafat selalu menjadi hal yang ajaib di antara semua hal yang pernah manusia temukan dalam hidupnya yang selalu rentan. Dari periode ke periode, filsafat mampu terus tumbuh dan melewati batasan-batasan ruang dan waktu yang rumit dan sulit dijelaskan. Filsafat seakan selalu eksis sehingga dalam situasinya yang terburuk dan tergelap, ia selalu mampu hadir menjadi sesuatu yang berlimpah serta mengagumkan siapa pun memahaminya. Manusia modern hari ini mungkin bisa berbangga dengan segala macam capaian dan temuan-temuannya. Hanya saja jika mau jujur, apa yang dicapai manusia modern hari ini sulit untuk dibayangkan keberadaannya, jika ribuan tahun lalu, sesuatu yang bernama filsafat tidak pernah lahir dan membuat berbagai keajaiban. Oleh karena itu, secara artifisial, apa yang hari ini manusia temukan pada dasarnya tidak lebih dari buah yang lahir dari rahim filsafat. Kenyataan itu dibuktikan dengan genealogi historis setiap ilmu yang seluruh nyaris lahir dari dan bermula dari filsafat. Luasnya bidang garapan filsafat telah melahirkan berbagai macam disiplin-disiplin baru yang mencengangkan. Dalam persoalan alam semesta, misalnya, filsafat melahirkan sesuatu yang kita kenal sebagai “kosmologi” atau filsafat yang membahas alam semesta; mulai dari asal-usul kejadiannya, entitas-entitas yang melingkupinya, serta prinsip-prinsip utama keteraturannya. Kenyataan yang sama juga terjadi pada ilmu-ilmu lainnya. Psikologi misalnya, jauh sebelum ia menjadi keilmuan yang mandiri, merupakan bagian dari filsafat, lahir ketika filsafat masuk dan mempersoalkan aspek-aspek kejiwaan manusia. Hal yang sama juga berlaku pada jenis-jenis disiplin yang dipandang modern, seperti sosiologi, politik, 80 sejarah, antropologi, linguistik, atau kedokteran, ataupun pendidikan, yang kesemua itu lahir dan bermula dari filsafat. *** Begitulah dari waktu ke waktu, filsafat terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada dunia manusia, termasuk salah satunya sesuatu yang begitu pragmatis bernama pendidikan. Sesuatu yang jika dilacak pun sesungguhnya memiliki akar gen yang sama dengan berbagai bidang lainnya, lahir dan bermula dari filsafat. Oleh karena itu, relevan jika pendidikan tidak lain adalah spekulasi filsafat akan hidup manusia. Tepatnya, saat filsafat menemukan satu pandangan bahwa hidup manusia harus baik, bermakna, dan makin berkualitas. Namun demikian, perlu diketahui bahwa di periode-periode awal, pendidikan tidak hidup secara terpisah dari filsafat. Pendidikan justru menjadi bagian yang masuk dalam filsafat. Andaipun ia masuk dalam sebuah bidang yang dapat disadari secara terpisah, pendidikan adalah bidang yang pada mulanya lahir dalam ruang etika atau filsafat nilai. Oleh karena itu, apa yang hendak dicapai oleh pendidikan selalu menjadi hal yang tak berbeda dengan apa yang hendak dicapai oleh etika, yaitu berupaya membangun hidup manusia baik dalam makna abstrak, yaitu dalam ruang kesadaran ataupun makna empiris atau dalam ruang-ruang yang bersifat mekanis. Dalam kepentingan itulah, pendidikan kemudian lahir sebagai proses pengajaran atau transformasi nilai-nilai keteladanan hidup di satu sisi dan peningkatan nilai-nilai keteladanan hidup di sisi yang lain. Makna pendidikan dalam filsafat tidak pernah menjadi sesuatu yang lain selain sebuah upaya untuk membangun tata hidup dan berkehidupan manusia yang ada. Makna fungsi ini memiliki kemiripan yang hampir sama dengan makna fungsi ilmu dan pengetahuan bagi hidup manusia, 81 yaitu bermaksud membangun agar hidup manusia semakin baik dan ideal di satu sisi, dan mampu menjaga kualitas-kualitas hidup yang telah dicapainya di sisi yang lain.10 Dari itu, secara genealogi-historis, pendidikan pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru sehingga ia dapat diklaim sebagai temuan manusia modern, sebaliknya telah menjadi sesuatu yang tua dan klasik, setua usia filsafat karena pendidikan merupakan bagian dari filsafat. Kenyataan ini menjadi argumen mengapa di era klasik para filsuf tidak pernah melahirkan istilah filsafat pendidikan, serta penjelas betapa ketika istilah pendidikan disebutkan ia telah pula mengasosiasikan makna filsafat secara otomatis. Dalam pengertian ini, pengungkapan bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat terapan, yaitu hasil ketika cara pandang filsafat masuk dan mengambil objek pendidikan, menjadi pandangan yang keliru, terutama jika ia dilihat secara geneologis, terutama karena hal itu melahirkan kesan makna bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang sepenuhnya terpisah dari filsafat atau ia berada di luar filsafat. Oleh karena itu, jika filsafat pendidikan kita konsesi mesti didefinisikan sebagai filsafat terapan, dasar pijakan bersifat metodis di satu sisi. Sedangkan, di sisi yang lain, ia menegaskan bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang dipandang sebagai bidang yang sepenuhnya bukan filsafat atau di luar filsafat. Hal itu menimbulkan perdebatan panjang yang begitu polemik. Saat pendidikan dikatakan sepenuhnya lepas dari filsafat, seseorang lebih 10. Sesuatu hal yang oleh sebagian kalangan kerap diungkap dengan istilah “utopia”. Utopia tentu saja adalah sesuatu hal yang ideal, sesuatu yang jauh, dan sulit dicapai. Dalam interes logika kebahasaan yang tinggi, sebagian kalangan bahkan merasionalisasikan bahwa utopia adalah sesuatu hal tidak mungkin bisa dicapai. Menurut mereka, saat utopi-utopi itu tercapai, ia bukan lagi disebut utopia, melainkan telah menjadi kenyataan hidup yang ada. Menginginkan terciptanya hidup yang ideal dalam hidup manusia yang serba-tidak ideal adalah sesuatu hal yang sulit diterima dengan logika. Namun demikian, uniknya hal yang tidak logis ini justru telah menjadi bagian dari hidup yang ada dan melahirkan sesuatu yang bernama pendidikan. Pendidikan selalu bermaksud membangun kehidupan manusia yang ideal dalam makna apa pun. 82 jauhnya mungkin akan bertanya, di ruang mana sebenarnya pendidikan pernah sungguh-sungguh terbuktikan lahir sebagai bidang yang sepenuhnya berada luar ruang filsafat, sedangkan siapa pun mengetahui bahwa pendidikan tidak pernah hadir selain dengan gagasan nilai serta pandangan-pandangan yang filsafat? Dalam pengkritisan tersebut, istilah “filsafat pendidikan” selalu menjadi hal yang hanya bisa diterima dalam pengandaian metodis guna menunjuk upaya-upaya cara pandang filsafat untuk mengkaji ruang pendidikan atau tepatnya ruang upaya manusia secara umum di dalam membangun hidup dan kehidupannya untuk menjadi semakin baik dan berkualitas. Pengandaian metodis ini terpahami terutama karena proses pelaksanaan upaya manusia secara umum di dalam membangun hidup dan kehidupannya untuk menjadi semakin baik dan berkualitas lebih sering berlangsung jauh dari nilai-nilai ideal yang diharapkan. Dalam berbagai kasus, upaya tersebut justru bermakna sebaliknya, yaitu semakin menjauhkan hidup manusia, baik secara individu ataupun kolektif dari tata hidup dan kehidupan yang baik dan berkualitas. Dalam realitas lapangan, ironi-ironi kontraproduktif tersebut terjadi dengan begitu sangat nyata sehingga ia bahkan tidak lagi membutuhkan argumentasi apa pun untuk membuktikannya. Penyelenggaran pendidikan menjadi penyebab utama dari lahirnya dehumanisasi. Secara ideal, pendidikan ingin membuat manusia menjadi bermoral. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendidikan terisi dan berlangsung dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dicita-citakan. Dalam konteks problem seperti inilah dunia modern kemudian mengenal istilah “filsafat pendidikan”, yaitu filsafat yang secara saksama bermaksud melihat tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan dalam pengertian-pengertian lebih mendasar dan genuine sehingga 83 proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di lapangan dapat kembali menemukan makna urgensitasnya dalam hidup yang ada. Hingga di sini, secara definitif, filsafat pendidikan tidak lain adalah penerapan upaya metodis filsafat untuk mempersoalkan konsepsi-konsepsi yang melandasi upaya-upaya manusia di dalam membangun hidup dan kehidupannya untuk menjadi semakin baik dan berkualitas. Sedangkan, tujuan upaya-upaya filsafat dalam mempersoalkan adalah guna mengarahkan penyelenggaraan pendidikan pada kondisi-kondisi etika yang diidealkan. Dalam makna lain, filsafat pendidikan adalah falsifikasi pendidikan, baik dalam makna teoretis konseptual maupun makna praktis-pragmatis yang menggejala. B. Peran Filsafat Pendidikan Dalam dunia yang secara nyaris sepenuhnya telah berisi instituasi pendidikan, kajian tentang filsafat pendidikan tentu saja menjadi kajian yang begitu penting serta fundamen. Selain membantu proses penyelenggaraan pendidikan untuk menghindari hal-hal yang kontraproduktif, kajian tentang filsafat pendidikan akan pula membawa kita pada temuan-temuan mengenai formula pendidikan secara holistik tentang apa dan bagaimana sebuah pendidikan mesti dilakukan. Dengan demikian, pendidikan benar-benar sesuatu kegiatan yang dapat dipahami makna relevansi bagi kehidupan. Adapun peran penting lain terkait idealisasi format pendidikan setiap negara selalu lahir dalam konsep etis yang berbeda. Hal ini terkait dengan perbedaan-perbedaan nilai-nilai serta kosmologi hidup masing-masing bangsa di dalam menyadari hidupnya. Dalam makna ini, kajian-kajian filsafat pendidikan dalam ruang lebih khusus, yaitu terkait dengan nilai-nilai hidup menjadi pula penting 84 dilakukan guna melahirkan konsep serta penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya selaras dengan nilai filsafat hidup bangsa yang ada. Di sini, filsafat pendidikan dapat hadir mempersiapkan konsep falsafi sesuai dengan pandangan hidup bangsa terkait sebagai landasan konseptual bagi pelaksanaan sistem pendidikan yang akan dilakukan. Tanpa filsafat pendidikan, proses penyelenggaraan pendidikan bisa akan menjadi kegiatan yang justru menghancurkan bangsa. Setiap negara memiliki corak filsafat pendidikan masing-masing sesuai dengan corak kehidupan yang tecermin dalam perilaku masyarakatnya. Negara mempunyai kewenangan menentukan landasan filsafat pendidikan sebagai arah kebijakan yang akan dicapai dalam tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Tidak ada satu negara pun yang memiliki filsafat pendidikan yang sama persis kecuali negara tersebut memiliki sejarah peradaban yang sama. Sekalipun demikian, arah dan tujuan pendidikan yang akan dicapai tetap berbeda. Di Indonesia, misalnya, filsafat pendidikan agaknya mesti dirumuskan berdasarkan corak dan budaya kehidupan bangsa Indonesia. Filsafat pendidikan di Indonesia didasarkan pada ideologi negara dan konstitusi negara. Oleh karena itu, filsafat pendidikan di Indonesia disebut “filsafat pendidikan Pancasila”. Artinya, segala kebijaksanaan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hasil akhir pendidikan pun harus mampu mencerminkan perilaku yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan perbedaan filsafat pendidikan yang dianut, setiap negara tidak seharusnya mengadopsi sistem pendidikan negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat negara tersebut. Kesuksesan negara tertentu terhadap sistem pendidikan yang diterapkan tidak selalu cocok untuk diterapkan di negara lain. Oleh karena itu, suatu negara harus bertindak bijaksana dalam menetapkan segala keputusan berkaitan dengan sistem pendidikan. 85 Filsafat pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para perencana pendidikan dan orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan. Hal tersebut akan mewarnai perbuatan mereka secara arif dan bijak serta menghubungkan usaha-usaha pendidikannya sengan falsafah umum, falsafah bangsa, dan negaranya. Pemahaman mengenai filsafat pendidikan akan menjauhkan mereka dari perbuatan meraba-raba, mencoba-coba tanpa rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Hingga di sini, filsafat pendidikan harus bisa menjawab tentang pertanyaan pendidikan yang bersifat sangat mendasar; mulai dari apakah pendidikan itu? Mengapa ia harus dianggap penting dan perlu diadakan? Apa yang hendak dicapai? Bagaimana cara terbaik merealisasikan tujuan-tujuan itu? Kemudian, secara praktis, pendidikan filsafat memiliki fungsi peranan yang sekurang-kurangnya dibedakan ke dalam empat hal utama. Keempat hal tersebut antara lain adalah menginspirasikan, menganalisis, mempreskriptifkan, dan menginvestigasi. Pertama, filsafat pendidikan menjadi ruang inspirasi, khususnya bagi para pendidik dalam melaksanakan ide-ide tertentu dalam pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, filsuf menjelaskan idenya mengenai pendidikan tersebut, ke mana diarahkan, siapa saja yang patut menerima pendidikan, bagaimana cara mendidik, serta apa peran pendidik. Sudah tentu, ide-ide ini didasari oleh asumsi-asumsi tertentu tentang anak manusia, masyarakat atau lingkungan, dan negara. Kedua, peran analisis. Dalam peran ini, filsafat pendidikan berarti memeriksa secara teliti bagian-bagian pendidikan agar dapat diketahui secara jelas validitasnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyusun konsep pendidikan secara utuh tidak terjadi kerancuan (tumpang tindih). Di sini filsafat pendidikan memeriksa bagian-bagian pendidikan secara saksama untuk mengetahui validisi pendidikan secara gamblang. Hal ini 86 dimaksudkan, selain untuk menghindari tumpang tindih serta kesimpangsiuran, juga guna mengarahkan tujuan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Francis Bacon 11, seorang filsuf Inggris dalam bukunya The Advencement of Learning, mengemukakan betapa kebanyakan pengetahuan yang dimiliki manusia selalu mengandung unsur-unsur validitas yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari, terlebih jika pengetahuan itu berisi salah satu konsep yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari itu, Bacon menggunakan logika induktif sebagai teknik krisis atau analisis untuk menemukan arti pendidikan yang dapat diandalkan. Melalui pengalaman secara kritis dengan logika induktif, akan dapat ditemukan konsep-konsep pendidikan. Ketiga, filsafat pendidikan memiliki makna preskriptif atau memberi pengarahan kepada pendidik dalam soal apa dan mengapa pendidikan itu. Hal yang dijelaskan dapat berupa hakikat manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain atau aspek-aspek peserta didik yang memungkinkan untuk dikembangkan. Proses perkembangan tersebut tergantung pada batas bantuan yang diberikan, batas keterlibatan pendidik, arah pendidikan, target pendidikan, perbedaan arah pendidikan, dan bakat serta minat anak. Hal ini, misalnya, bisa dicontohkan dengan apa yang idealisasi John Herbart dalam soal guru. Dalam karyanya berjudul Scence of 11. Viscount St. Alban pertama (lahir 22 Januari 1561, wafat 9 April 1626) adalah seorang filsuf, negarawan, dan penulis Inggris. Ia juga dikenal sebagai pendukung Revolusi Sains. Bahkan, menurut John Aubrey, dedikasinya menggabungkannya ke dalam sebuah kelompok ilmuwan yang bersejarah yang meninggal dunia akibat eksperimen mereka sendiri. Karya-karyanya membangun dan memopulerkan metodologi induksi untuk penelitian ilmiah, sering disebut metode Baconian atau, secara sederhana, metode ilmiah. Dalam masanya, metode-metode tersebut dihubung-hubungkan dengan tren kepercayaan Hermes dan Alchemy. Walaupun demikian, kebutuhannya terhadap sebuah prosedur yang terencana untuk meneliti semua hal yang alami menandai sebuah pembaruan dalam kerangka retoris dan teoretis untuk ilmu pengetahuan. Kebanyakan dari kerangka-kerangka penelitian ilmiah ini masih menjadi dasar lahirnya metodologi yang lebih baik hari ini. 87 Education, John Herbart memandang bahwa guru harus memiliki informasi yang dapat diandalkan mengenai tujuan pendidikan yang dapat dicapai dan proses belajar sebelum guru memasuki kelas. Di sini, John Herbart, dalam makna lebih umum memandang bahwa pendidikan seharusnya dikonstruksi di atas asumsi yang valid—suatu informasi yang direkonstruksi dari atau secara ilmiah. Sementara, peran yang keempat adalah peran investigatif. Di sini filsafat pendidikan memeriksa atau mengkaji kebenaran suatu teori pendidikan. Pendidik seharusnya mencari sendiri konsep-konsep pendidikan di lapangan atau melalui penelitian-penelitian. Konsep yang dipraktikkan tersebut merupakan hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan posisi filsafat hanya sebagai latar pengetahuan saja. Peran-peran di atas tentu saja peran yang bersifat masih jauh dari apa yang diidealkan. Terutama, karena peran filsafat pendidikan di sana masih bersifat pasif. Sedangkan, peran filsafat pendidikan yang bersifat aktif adalah diharapkan kajian-kajian filsuf pendidikan akan melahirkan pendidikan yang sepenuhnya falsafi serta berisi para pendidik yang juga seorang filsuf pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan selalu bereksplorasi menemukan sebuah format pendidikan yang ideal untuk diterapkan di suatu negara. Format pendidikan yang dimaksud harus sejalan dengan keadaan masyarakat tempat pendidikan itu dilaksanakan. Dalam bukunya Democracy and Education, John Dewey memandang bahwa pengalaman adalah tes terakhir dari segala hal. Mereka memandang pengalaman sebagai panji-panji semua filsafat pendidikan yang mempunyai komitmen terhadap inquiry atau penyelidik. Filsuf berfungsi memilih pengalaman-pengalaman yang cocok untuk memajukan efisiensi sosial. Filsafat pendidikan berusaha menafsirkan proses belajar mengajar menurut prosedur pengujian ilmiah dan kemudian memberi komentar tentang nilai atau kemanfaatannya. 88 Para filsuf melalui filsafat pendidikannya, menggali ide-ide baru tentang pendidikan, yang menurut pendapatnya lebih tepat ditinjau dari kewajaran keberadaan peserta didik dan pendidik maupun ditinjau dari latar geografis, sosologis, dan budaya suatu bangsa. Dari sudut pandang keberadaan manusia, filsafat pendidikan akan menimbulkan aliran Perenialis, Realis, Empiris, Naturalis, dan Eksistensialis. Sedangkan, dari sudut geografis, sosiologis, dan budaya, akan menimbulkan aliran Esensialis, Tradisionalis, Progresivis, dan Rekontruksionis. Berbagai aliran filsafat pendidikan tersebut di atas memberikan dampak terciptanya konsep-konsep atau teori-teori pendidikan yang beragam. Masing-masing konsep tersebut mendukung filsafat pendidikan. Dalam membangun teori-teori pendidikan, filsafat pendidikan juga mengingatkan agar teori-teori itu diwujudkan di atas kebenaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan. Pendeknya, teori-teori pendidikan harus disusun berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah. C. Ruang Lingkup Filsafat Pendidikan Sebagaimana telah kita bahas di depan, filsafat pendidikan adalah filsafat yang secara khusus mengambil bidang garapan pendidikan sebagai objek bahasannya. Di situ filsafat pendidikan berurusan dengan konsep-konsep serta gagasan, baik menjadi landasan ataupun panduan pelaksanaan upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan. Atau, mengulas tentang apa, mengapa, dan bagaimana pendidikan secara mendasar. Dalam makna ini, ruang lingkup filsafat terbagi ke dalam tiga ruang, yaitu (1) ruang ontologi pendidikan; (2) ruang epistemologi pendidikan; serta (3) ruang aksiologi pendidikan. Dalam ruang ontologi, filsafat pendidikan akan mengulas tentang apa itu hakikat pendidikan. Kemudian, dalam ruang epistemologi, filsafat pendidikan akan mempersoalkan mengapa dan bagaimananya pendidikan 89 itu karena pertanyaan mengapa pendidikan dianggap penting dan mesti ada dalam kehidupan manusia adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam ruang epistemologi. Adapun yang ketiga, yaitu dalam ruang aksiologi. Dalam ruang aksiologi ini, filsafat pendidikan akan mengulas makna keberadaan pendidikan dalam ruang kehidupan. Di sini filsafat pendidikan akan mempersoalkan validitasi urgenisasi umum yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Lebih jauhnya, filsafat pendidikan akan membawa kita pada ulasan tujuan-tujuan yang hendak dicapai pendidikan serta makna yang mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Ruang lingkup ini akan kita ulas dalam sub-subbab tersendiri, yang kesemuanya masuk dalam ruang metafisika filsafat pendidikan—mulai dari metafisika ontologis, metafisika epistemologi, serta metafisika aksiologi. D. Metafisika Ontologi Filsafat Pendidikan Metafisika ontologi filsafat pendidikan berkaitan dengan persoalanpersoalan mendasar tentang hal ihwal hakikat pendidikan dalam ruang filsafat. Oleh karena itu, di sini pendidikan akan dikritisi dan pertanyaan secara mendasar; Apa sesungguhnya pendidikan? Mengapa pula ia dinilai sebagai sesuatu hal yang penting bagi hidup manusia? Suatu ketika, pendidikan diartikan sebagai proses pembimbingan, pengarahan, dan pembentukan hidup agar manusia menjadi makin baik dan berkualitas. Jika ia diartikan sebagai pembimbingan , pengarahan, dan pembentukan, lalu pengarahan serta pembimbingan seperti apakah pendidikan itu? Adakah setiap pembimbingan dan pengarahan dapat diartikan sebagai pendidikan? Atau, justru terdapat kriteria-kriteria tertentu ketika pengarahan, pembimbingan, dan pembentukan dapat disebut sebagai pendidikan? 90 Sementara, di waktu yang lain, juga dijelaskan bahwa pendidikan tidak lain merupakan upaya membentuk manusia agar bermoral dan berperadaban. Hanya saja, benarkah semua pandangan itu? Benarkah pendidikan adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh penting atau justru hanya sesuatu hal dianggap penting, padahal pada dasarnya ia sesungguhnya tidak penting sama sekali? Pandangan yang mengatakan bahwa pendidikan tidak lain sebagai pengarahan, pembimbingan, dan pembentukan hidup agar manusia bermoral serta memperoleh hidup yang berkualitas, sekilas memang sangatlah logis, bahkan terdengar begitu sangat pas menawan. Akan tetapi, jika dikritisi lebih jauh, pernyataan tersebut sesungguhnya memiliki problem filosofis yang cukup serius, bahkan mencakup seluruh aspek filsafat—mulai dari sisi ontologis, epistemologis, hingga aksiologis. Di wilayah ontologis, misalnya, kita akan dihadapkan dengan problem-problem asumsi dasar atau landasan-landasan etis: mengapa manusia harus diarahkan dan dibimbing untuk menjadi baik? Benarkah untuk menjadi baik manusia mesti diarahkan? Adakah jika tidak diarahkan dan dibimbing, manusia tidak akan mampu “menjadi” baik atau belum baik atau telah selalu menjadi jahat? Ataukah, karena sejak mula manusia terlahir sebagai diri yang jahat, kemudian butuh diarahkan dan dibimbing (dididik) agar bisa menjadi baik? Jika memang benar bahwa pada dasarnya manusia itu terlahir jahat dan untuk menjadi baik, ia butuh diarahkan atau dididik, kualitas jahat seperti apakah itu yang hendak dijinakkan oleh pendidikan? Anggapan manusia sebagai spesies yang terlahir jahat dan perlu dibimbing dan diarahkan untuk menjadi baik adalah pandangan yang sulit diterima, bahkan sangat bermasalah dalam pengertian apa pun. Dalam ruang etika, misalnya, pandangan ini jelas bertentangan dengan fakta primordial manusia yang dalam kenyataannya tidak pernah lahir dengan sebagai “yang jahat” semata, sebaliknya sebagai “yang bisa jahat”. 91 Di sini ungkapan “yang jahat” dan “yang bisa jahat” jelas merupakan dua ungkapan yang berbeda. Dalam ungkapan yang kedua, kejahatan tidak pernah menjadi milik manusia secara mutlak. Kebaikan dan kejahatan atau keburukan bagi diri manusia tidak lain adalah dua hal yang bersifat potensial. Dua hal itu telah menjadi sesuatu yang terberikan sejak kemunculannya yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada satu pun manusia yang terlahir sebagai yang jahat, atau sebaliknya sebagai yang baik. Sebaliknya, ia selalu diri yang ada dalam dua potensi tersebut, yaitu sebagai yang bisa jahat dan sebagai yang bisa baik. Jika demikian adanya, di sini kita agaknya kembali pada pertanyaan awal di atas: apakah pendidikan itu sebenarnya? Dengan kepentingan mendesak seperti apakah pendidikan mesti diadakan dan diyakini sebagai sesuatu hal yang dianggap penting bagi keberlangsungan hidup manusia? E. Problem Epistemologi Filsafat Pendidikan Dunia manusia nyaris selalu menjadi dunia pendidikan. Dalam pengertian ini, dunia yang senantiasa mengakui pendidikan adalah sesuatu hal yang penting. Hal itu didasarkan pada beragam tujuan nilai, termasuk salah satunya yang utama adalah adalah tujuan-tujuan etis: untuk membuat manusia menjadi baik. Pandangan ini kemudian dilengkapi dengan berbagai penjelasan bahwa pendidikan kemudian memercayai pengetahuan sebagai instrumen utama guna mendidik manusia. Pendidikan memercayai bahwa dengan membuat manusia menjadi berpengetahuan manusia akan menjadi baik. Pandangan ini telah menjadi common sense yang diterima secara meluas di berbagai tradisi dan bangsa, bahkan juga mendapat berbagai legitimasi ortodoksial dari berbagai kepercayaan-kepercayaan lama. Dalam tradisi Islam, misalnya, kita bahkan dapat menemukan bahwa mereka 92 memiliki kitab suci yang selalu menyeru para pemeluknya agar selalu hidup sebagai manusia yang terus mencari ilmu. Ini bisa kita temukan, misalnya dengan adanya postulasi mencari ilmu dimulai dari ayunan hingga menjelang kematian. Sementara, dalam tradisi lainnya, Hindu, misalnya juga memiliki semangat dan optimisme yang sama dalam meyakini bahwa pengetahuan bisa membuat manusia menjadi baik. Vedantik bahkan menjadi kitab yang bermakna pengetahuan. Oleh karena itu, jika sepakat bahwa jalan Hindu adalah jalan Veda, agama Hindu adalah agama yang menjadikan pengetahuan sebagai jalan utama untuk seorang Hindu yang baik. Di periode lama, keyakinan terhadap pengetahuan menjadi keyakinan umum umat manusia. Manusia di setiap periode, bahkan selalu memiliki suara yang sama di dalam memercayai pengetahuan. Pengetahuan dipandang sebagai kunci kebaikan hidup. Dari pendapat tersebut, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa tanpa pengetahuan, dunia manusia tidak akan pernah sungguh-sungguh mampu berdiri menjadi dunia. Sebaliknya, ia akan menjadi ruang lengang, tempat ribuan pasang mata hidup dalam situasi yang begitu mati dan tanpa nyala apa pun. Hanya saja, sepanjang itu kita nyaris tidak pernah menelisik lebih jauh dan mencoba kritis, dengan bertanya benarkah pengetahuan dapat membuat manusia menjadi baik? Benarkah pengetahuan dapat membentuk manusia menjadi spesies yang bermoral? Jika memang pengetahuan mampu melakukan keajaiban itu, apa sebenarnya yang dimiliki pengetahuan hingga ia dapat mengubah manusia yang jahat menjadi manusia baru yang baik? *** Dalam sejarahnya, siapa pun memang tidak dapat mengingkari betapa dunia manusia selalu dunia yang lahir dari sesuatu yang oleh dunia 93 disebut sebagai pengetahuan. Cina berabad lampau, misalnya, tanpa pengetahuan sepanjang waktu tidak lebih akan menjadi kisah primata berkulit kuning, yang lahir dan hidup di atas endapan sedimen lumpur berwarna. Hal yang sama juga akan terjadi pada tradisi Indus, Mesir, Asyiria, Persia, serta Yunani. Tanpa pengetahuan, mereka bukanlah apa pun selain deretan kisah tentang bagaimana manusia, yang terus berupaya mempertahankan kehidupan fisiknya dengan pola yang begitu alami dan instingtual. Dengan tipe kecerdasan instingnya yang dinamis, manusia mungkin tetap mampu mempertahankan kelestarian spesiesnya sampai kapan pun. Akan tetapi, tanpa pengetahuan, semua pelestarian itu tidak akan berarti apa pun. Sepanjang waktu, manusia akan hidup sebagaimana kawanan burung atau sekumpulan bison yang hidup dan bertahan berdasarkan kesadaran-kesadaran insting serta kelompoknya. Tanpa pengetahuan, kehidupan manusia tidak akan pernah bergerak ke mana pun selain berputar-putar menjadi hewan yang sepanjang waktu tidak pernah mengalami ketersadaran apa pun. Manusia kemudian akan hidup dalam situasi yang paling primordial, yang berjalan dalam keteraturan waktu tubuh serta instingtualnya. Pengetahuan demikian tak ubahnya tangan halus yang ajaib. Tangan halus yang dengan diam-diam datang lalu memberi ruh bagi hidup yang sepenuhnya beku dan tidak bergeming. Pengetahuan mengubah kehidupan, tidak lagi hanya sekadar “udara”, tetapi “napas” yang hidup. Manusia yang pada mulanya hidup dengan pola apa adanya, karena pengetahuan, kemudian memulai hidupnya dengan cara serta kesadarankesadaran baru. Meskipun di era-era awal, peran pengetahuan berkisar pada aspek-aspek yang begitu pragmatis, terkait dengan berbagai pengubahan sisi praksis keberlangsungan hidup semata, lahirnya pengetahuan telah menjadi era baru yang menandai betapa gerak sejarah perjalanan manusia telah dimulai dalam pola yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. 94 Dalam fashion, misalnya, manusia yang pada mulanya hidup seperti binatang, tanpa pakaian apa pun, di era ini mulai mengalami gejala fashion, tertarik menggunakan pakaian-pakaian ala kadarnya. Dalam soal pangan, manusia yang mulanya hidup dalam pola berburu, mulai melakukan kerja-kerja produksi, termasuk salah satunya mulai mengenal cara hidup bercocok tanam. Pendeknya, sejak pengetahuan itu tiba, manusia terlahir menjadi subjek yang tumbuh dan terus mengalami perkembangan kesadaran dan terus-menerus melakukan berbagai pengubahan pada keberlangsungan hidup yang ada. Pengetahuan telah membuat manusia berubah tidak lagi sekadar primata atau hewan berkaki dua yang mampu berjalan tegak. Pengetahuan telah mengubah manusia menjadi makhluk yang juga mengenal seni tata cara menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih baik, termasuk salah satunya berkaitan dengan soal pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, serta hal-hal praktis lainnya. Secara kreatif, dalam berhubungan dengan sesamanya, pada periode itu manusia juga mengalami perkembangan signifikan. Manusia mulai menciptakan simbol-simbol verbal ataupun simbol-simbol non-verbal. Meskipun simbol-simbol itu masih begitu sangat sederhana, hal itu menjadi tanda bahwa periode hidup baru telah dimulai dengan semangat dan tatapan yang jauh lebih memiliki ruh. Kelak, di kemudian hari, gejala ini akan diungkap sebagai gejala awal manusia dalam berbahasa—era ketika untuk kali pertama manusia mulai menggunakan sistem kode atau fase pertama, tempat embrio bahasa ditemukan serta berkembang ke dalam bentuk baku yang paling secara sederhana. Pengetahuan menjadi hal yang ajaib, yang selalu berhasil mengubah manusia dari spesies yang begitu sangat hewan menjadi makhluk kreatif yang hidup dalam berbagai penciptaan. Di sini, menjadi hal yang tepat jika seorang Hegel kemudian menyadari pengetahuan sebagai wujud teoretis dari adanya ruh kehidupan 95 serta wujud abstrak dari sesuatu yang bernama “peradaban” dimulai. Pengetahuan adalah berkah yang membuat hidup manusia makin menjadi baik—hidup yang pada mulanya bukan apa pun. Pengetahuan kemudian mengalami pemaknaan menjadi keberlangsungan yang memiliki nilai, makna-makna, dan tujuan. Manusia kemudian hidup dalam visi atau penglihatan baru, ketika hidup tidak lagi dialami secara sekadarnya, semata-mata hanya sebagai gerak insting dan gejala tubuh. Sebaliknya, ruang aktual, tempat hidup selalu terarah pada proyeksi, makin pasti dan terang. Di titik inilah, untuk kali pertamanya, manusia mulai mengalami kesadaran falsafi yang paling sederhana. Maka, jika ditanyakan filsafat apa yang pertama kali lahir, jawabannya adalah pengetahuan. Pengetahuan itulah filsafat yang pertama kali manusia temukan. Pengetahuan membuat manusia menjadi bijak, baik di sisi pragmatis ataupun kesadaran. Hingga di sini pengetahuan terlihat memiliki peran yang begitu penting. Sebab, pengetahuan manusia bahkan mulai mengalami kebernapasannya dengan berbagai pertanyaan serta kegelisahankegelisahan elementer akan diri pribadi serta keberadaannya sebagai salah satu primata yang menghuni tatanan alam biosfera ini. Maka, pada periode ini, kegelisahan-kegelisahan tentang siapakah aku, dari mana, bagaimana, dan mengapa aku hadir meruang dengan begitu berlimpah, tidak ubahnya hamparan air di setiap sungai. Dengan pola yang sederhana, diam-diam serta nyaris tanpa suara, kegelisahan-kegelisahan itu terus membanjir dan menjangkiti benak setiap pribadi. Manusia mulai berpikir tentang keberadaan asal kedatangannya, arah kepulangan, dan tujuan keberadaan yang mereka alami. Perlahan dan pasti, di periode itulah manusia mulai menyadari dirinya sebagai sosok yang berbeda dari spesies lain. Mereka sampai pada perenungan-perenungan: betapa hidup yang mereka miliki bukanlah hidup yang sama dengan hidup makhluk mana pun. Manusia mulai 96 terbuka pada gagasan-gagasan baru tentang hidup. Meski bersamaan dengan tumbuhnya keterbukaan-keterbukaan itu, masa lalu masih menjadi ingatan-ingatan yang terus hidup dan tak sungguh-sungguh terlepaskan. Jauh sebelum mereka berpengetahuan, di situasi-situasi tertentu, mereka kerap bersikap seperti serigala. Mereka mendesis seperti ular, memukul-mukul dada sebagaimana gorila, atau meraung-raung sebagaimana kera. Saat makan, mereka bahkan makan dengan cara yang tak berbeda. Mereka memetik buah-buahan di hutan seperti kera, memakan daging seperti halnya serigala, harimau, singa, ataupun kucing. Di hari-hari yang lain, saat mereka tidak lagi menemukan binatang yang bisa diburu, mereka pun mengunyah rumput seperti rusa serta hewan herbivora lainnya. Namun, belakangan hal alami itu berubah. Sejak pengetahuan menghampiri, mereka tidak lagi bisa melakukan cara hidup seperti di atas. Uniknya, itu bukan karena mereka tidak mampu melakukannya, melainkan karena kesadaran-kesadaran diri mereka melarang hal itu. Kesadaran pola hidup baru telah merebut mereka untuk tinggal dan hidup dalam cara pandang yang lain. Di sebagian diri, kesadaran-kesadaran tersebut terkadang tumbuh dengan begitu kuat meski tidak selalu sama di sebagian diri yang lain. Maka, saat kenangan serta ingatan-ingatan masa lalu menyergap, mereka dilanda kegelisahan dingin dan yang tak terkatakan. Ingatan-ingatan itu tak ubahnya mimpi buruk yang terus hadir dalam tidur ataupun dalam keterjagaan. Di waktu-waktu tertentu, ketika mereka tengah mengalami diri mereka, ingatan-ingatan itu berpengaruh sedemikian kuat sehingga sebagian diam-diam memutuskan kembali dengan pola pengaturan lama. Mereka hidup dalam ketelanjangan bebas, bergerak dalam kebebasan, serta keliaran-keliaran murni. Mereka rindu situasi-situasi saat sepanjang waktu berdiri di atas tebing, lalu berteriak dan mengeluarkan suara lolongan seperti serigala. 97 Atau, situasi-situasi ketika mereka mengunyah daging dari tubuh binatang buruan meski kerinduan-kerinduan itu selalu pupus dengan sendirinya, terutama ketika kesadaran mereka berbenturan dengan kenyataan hidup, betapa mereka bukan lagi diri yang sama seperti di era masa lalu. Dalam berbagai hal, mereka mungkin masih mengenal dengan baik setiap inci kehidupan lampau yang pernah dilewati. Mereka mengingat dengan baik bagaimana cara memakan burung tanpa membunuhnya terlebih dahulu atau menggali tanah dengan jari jemari, untuk mendapatkan seekor ular guna diminum darahnya. Akan tetapi, kesadaran hidup yang disentuh tangan pengetahuan benar-benar telah menjadi koma juga spasi, yang membuat mereka tidak lagi sanggup melakukan pola pengintegrasian diri dengan cara yang sama, sebagaimana saat mereka masih hidup di masa lampau. Oleh karena itu, seluruh ingatan juga kenangan-kenangan hidup masa lampau kemudian hidup dalam ruang-ruang tersembunyi, terpendam di alam bawah sadar. Kelak, di masa-masa berikutnya, ketika mereka mulai mengalami periode-periode falsafi di fase lebih jauh, tanpa mereka sadari, ingatan-ingatan itu akan kembali hadir, meruang, serta memberikan pengaruhnya secara berlimpah, termasuk dalam upaya-upaya mereka dalam melakukan pencarian atas kegelisahan-kegelisahan hidup yang menimpa. Pengaruh itu salah satunya terekspresikan secara khas dengan adanya kebiasaan baru di antara mereka, yang tiba-tiba gemar melakukan pemujaan terhadap berbagai binatang. Ada yang mengultuskan jenis-jenis burung tertentu, ular, ada pula yang mengultuskan serigala serta hewan lainnya. Kultus atau pemujaan seperti ini menjadi gejala umum yang biasa terjadi di masyarakat kuno, di ruang ketika hidup masih berlangsung dengan cara-cara yang begitu alami dan penuh kesahajaan. Di Mesir, misalnya, terdapat pemujaan terhadap beragam jenis hewan, mulai dari kucing, ular, anjing, serta burung. Hal yang sama 98 juga terjadi di Yunani. Orang-orang Yunani memandang burung sebagai hewan yang memiliki kecerdasan tertentu. Pola-pola pemujaan seperti ini memiliki tipologi yang berbeda-beda di setiap tradisi. Di Mesir, pemujaan binatang terlihat lebih terarah pada hewan-hewan yang dipandang berkekuatan fisik, seperti buaya, ular, ataupun serigala. Periode ini berlangsung berabad-abad lamanya hingga kemudian digantikan dengan hadirnya sosok adikodrati baru yang dikenal sebagai dewa atau titan. Kemunculan para dewa atau para titan ini tidak melahirkan tatanan dunia baru sama sekali. Sebaliknya, meneruskan hidup yang ada. Perpaduan unik antara sosok adikodrati itu dan binatang-binatang yang disucikan ini melahirkan gejala yang oleh G.W.E. Hegel, disebut zoolatry atau semacam pemujaan para dewa yang digambarkan bertubuh setengah manusia dan setengah binatang. Di periode awal, kemunculan para titan atau dewa-dewa zoolatry ini semakin menguatkan posisi pentingnya pengetahuan. Pengetahuan bahkan diinsyafi sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Ini bisa ditemukan di berbagai peradaban tua dunia yang selalu menjadi tradisi yang sarat dengan kearifan serta perhatiannya yang begitu berlimpah pada sesuatu, yang oleh kita di hari ini, dikenal sebagai pengetahuan. Indus, misalnya, pada periode itu, tumbuh menjadi negeri tempat pengetahuan disadari dengan pola transendensi menakjubkan, disadari sebagai kunci menuju Tuhan. Maka, di Indus, Vidya atau Veda, yang berarti pengetahuan menjadi kitab suci yang disucikan.12 Vidya atau Veda di sini dianggap sebagai sesuatu yang suci karena dianggap sebagai perkataan Tuhan. Gambaran tidak berbeda juga terjadi di Cina, Mesir, Babilonia, Asyiria, dan Persia, tempat perhatian dan kepedulian akan pengetahuan berlangsung dengan sama berlimpahnya. Di Mesir Lama, kita akan menemukan sosok adikodrati bernama Thoth. 12. Kata ini kerap dilawankan dengan kata Avidya yang berarti tanpa pengetahuan. 99 Thoth adalah sosok menawan yang dipandang sebagai dewa pengetahuan. Ia tak berbeda dengan Ganesha atau Saraswati di dalam tradisi Indus. Thoth ini pula yang konon melahirkan tulisan untuk pertama kalinya. Selain itu, Thoth juga dipandang sebagai penemu ilmu hitung, ilmu astronomi, ilmu musik, kedokteran, hukum, olahraga, bahasa, serta semua hal yang teratribusikan ke dalam sistem pengetahuan. Di antara negeri-negeri itu, Yunani ternyata bukan negeri berbeda. Di sana kita akan menemukan adanya sosok adikodrati yang tidak berbeda dengan Thoth di Mesir atau Ganesha di India. Kesemua itu menunjukkan betapa jauh di waktu yang begitu lampau, Yunani telah pula hidup dalam kesadaran logos atau pengagungan dan penyucian pada pengetahuan. Apollo adalah titan pengetahuan, yang disadari tak berbeda dengan Thoth di Mesir atau Ganesha di Indus. *** Begitulah dunia manusia lahir dan terbangun, dari dan dengan pengetahuan. Pengetahuan telah membawa manusia pada berbagai keajaiban yang terus berkembang tanpa ada habisnya. Dalam lindungan dan sentuhan pengetahuan, kehidupan tumbuh menjadi keajaiban yang sarat dengan berbagai kesenangan serta kepuasan. Meski sayangnya, periode-periode menyenangkan ini tidak sanggup berlangsung lebih lama, dari waktu yang diharapkan. Bersamaan dengan tumbuhnya kelimpahankelimpahan itu, pengetahuan pun kemudian mulai tercemar berbagai hal yang begitu gelap. Tanpa manusia sadari, bersamaan dengan tumbuhnya pohon pengetahuan, diam-diam, sesuatu yang begitu gelap dan pekat lahir serta berkembang hingga berlimpah. Sesuatu yang gelap ini, bahkan memiliki sistem jauh lebih canggih dari capaian yang telah pengetahuan temukan. Ini terlihat manakala hal gelap ini selalu mampu mengadaptasikan diri 100 pada seluruh sistem pengetahuan-pengetahuan yang ada sehingga mereka menjadi begitu berkuasa dalam kehidupan yang ada. Di kemudian hari, “hal gelap” ini dikenal sebagai sesuatu yang bernama “hasrat”. Para sarjana modern membuat analisis betapa di era ini manusia mulai dikendalikan oleh hasrat-hasrat baru, yang tidak mereka pahami, dan belum pernah mereka rasakan, di kehidupan sebelumnya. Hasrat-hasrat itu menguat, menguasai dari segala sisi, dari sisi yang tersembunyi hingga sisi yang terlihat. Pengetahuan, sesuatu yang pada mulanya menjadi hal suci serta mampu membawa manusia dalam keselarasan-keselarasan hidup menawan, seketika berubah menjadi bengis, mengerikan, dan melahirkan hal-hal yang bersifat ilusif. Mulanya, rasio memang menjadi berkah. Namun, saat ia tumbuh menjadi besar, rasio kemudian melahirkan dilema sebab ia selalu membawa manusia pada dua medan energi kuat, yang terus saling bertentangan, antara satu sama lainnya. Secara potensial, manusia sebenarnya memiliki kebebasan memilih salah satu dari dua energi itu sehingga pengetahuan bisa diselamatkan dari berbagai pencemaran-pencemaran. Akan tetapi, sejarah sepertinya memiliki takdir yang sulit diterka centang perenangnya. Dalam hidupnya, manusia tampaknya lebih sering membuat pilihan yang salah sehingga yang dihidupinya justru energi-energi gelap yang membuat pengetahuan terus mengalami pencemaran. Pencemaran yang membuat pengetahuan kemudian kehilangan berkah dan kesembuhannya. Pengetahuan, sesuatu yang pada mulanya, tumbuh, selaras dengan semangat kehidupan yang murni, pada perkembangannya justru memunggungi kehidupan meski di beberapa negeri hal itu tidak selalu menunjuk indikasi yang sama. Namun, di banyak negeri, tumbuhnya pengetahuan selalu nyaris menjadi awal berkuasanya kekuatan gelap yang jahat dan mengerikan—kekuatan gelap yang membuat kehidupan menjadi tragedi yang penuh dengan kepedihan dan ratapan. 101 Pencemaran itu terus berlangsung hingga membawa manusia pada puncak kehidupan yang sarat dengan berbagai kekacauan. Tanda tidak lagi menunjuk pada arah yang benar. Pengetahuan berkembang di ruang-ruang yang sepenuhnya berpisah dari kehidupan yang ada. Kenyataan itu mengundang sebuah refleksi: betapa kepercayaan lama akan pengetahuan yang ajaib tidak lagi memadai untuk digunakan sebagai pijakan hidup. Pengetahuan ternyata tidak selalu menunjuk arah yang terang. Suatu ketika, dengan tanpa terduga, pengetahuan bahkan sanggup mengarah pada berbagai hal yang berlawanan. Berlimpahnya pengetahuan menjadi awal, berlangsung, dan dimulainya zaman yang sepenuhnya gelap. Di sebagian dunia yang lain, gejala ini membawa beberapa diri pada beberapa perenungan (kontemplasi) seputar pengetahuan-pengetahuan yang melahirkan kekacauan hidup atau sebaliknya. Di sini, diri-diri itu melakukan pelacakan mendasar tentang pengetahuan serta keterkaitannya dengan hidup yang ada. Sayangnya, sejauh itu kegelisahan-kegelisahan yang muncul selalu menjadi anak panah yang membentur kerasnya dinding batu. Meski di satu sisi mereka memang telah menemukan betapa pengetahuan yang tercemar itulah yang menjadikan hidup penuh dengan kekacauan, sejauh itu mereka tetap tidak sanggup menemukan akar penyebab yang membuat pengetahuan-pengetahuan itu bisa mengalami ketercemaran. Dunia mungkin butuh sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang bisa membawa manusia pada pemahaman hidup yang benar. Akan tetapi, apakah itu? Seseorang mengatakan bahwa “sesuatu itu” adalah sesuatu yang sanggup memberitahukan manusia, dalam membedakan, mana pengetahuan ilusi dan mana pengetahuan yang senyatanya. Tanpa itu, tumbuhnya pengetahuan akan terus-menerus melahirkan tragedi secara berulang dari waktu ke waktu, sejak awal kali pertama 102 manusia mulai memercayai dan menemukan pengetahuan hingga ketika manusia mulai kehilangan kepercayaan pada pengetahuan. Pengetahuan telah sedemikian tercemar sehingga kepedihan demi kepedihan tumbuh dan berkarat di setiap diri, bahkan pada setiap bocah, bersamaan dengan makin majunya perkembangan pengetahuan. Ini memang ironi yang kuat. Sesuatu hal yang menunjuk betapa sesuatu yang suci dan hangat dapat membawa manusia pada kehidupan yang agung, suatu ketika juga bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu dingin, bengis, dan tanpa mata. Maka, hidup sepenuhnya merupakan kebuntungankebuntungan perih nan busuk. Pengetahuan memang ajaib. Namun, keajaibannya senantiasa bersifat potensial. Oleh karena itu, keberlimpahan pengetahuan kerap menjadi keberlimpahan terburuk yang bisa membawa hidup jauh dari berkah dan kesembuhan. Di tengah-tengah zaman, ketika keberlimpahan pengetahuan kehilangan daya sembuhnya, filsafat untuk kali pertamanya lahir dan memulai perjalanannya dengan cara yang begitu marginal. Oleh karena itu, Yunani sesungguhnya bukanlah rahim pertama tempat filsafat lahir dan dimulai. Yunani adalah akumulasi kepedihan dan keprihatinan zaman, ketika keberlimpahan pengetahuan telah memunggungi kehidupan. Filsafat tidak muncul ketika dunia hampa pengetahuan. Filsafat justru terlahir ketika keberlimpahan pengetahuan tidak lagi memiliki kesembuhan hidup. Filsafat selalu tidak lain adalah falsifikasi dan pencarian dasar untuk menjadi bijaksana dan sembuh, serta landasan mengapa kita, manusia, mesti menyakini bahwa pengetahuan adalah kunci dari segala kebaikan hidup. Di sini jika filsafat dipandang lahir di Yunani, filsafat di Yunani tidak lahir sebagai fase pengetahuan pertama, ketika pemikiran manusia baru memasuki tahapan how to know atau ketika hidup manusia baru mengalami ketersadaran hidup di wilayah teknis pragmatis. Sebaliknya, filsafat di Yunani lahir pada fase pengetahuan kedua, yaitu masuk di 103 tahapan how to act—tahapan ketika di satu sisi dunia manusia telah sarat dengan pengetahuan, sedangkan di sisi yang lain pengetahuan telah kehilangan visi kosmologisnya. Dalam pengertian inilah, kegelisahan-kegelisahan filsafat di Yunani tidak muncul sebagai gejala filsafat yang bersifat mekanistis yang mengulas persoalan-persoalan teknis pragmatis hidup, sebaliknya bersifat abstrak teoretis, sarat dengan kosmologi dan problem-problem etika. Kenyataan ini memiliki bukti dan penggambaran banyak hal. Yunani di era-era itu, sepertinya cukup memahami betapa pengetahuan tidak pernah berimplikasi tunggal. Sebaliknya, selalu menjadi hal yang potensial. Yunani dengan kejeliannya memahami hal ihwal sejarah pengetahuan. Betapa di negeri-negeri di masa lalu, pengetahuan, selalu menjadi Dewa Janus,13 yang di satu sisi, membangkitkan hidup. Akan tetapi, di waktu yang lain, pengetahuan sanggup pula menghancurkan peradaban yang paling agung. Di Indus, pencarian-pencarian pengetahuan itu melahirkan para Rishi—sosok pelihat yang mampu mendengar suara-suara suci dan mengalami ingatan-ingatan suci. Sedangkan, di kaki Himalaya, pencarianpencarian itu melahirkan Aria Sangha atau orang yang dipandang duduk di atas garis kesempurnaan hidup. Di Cina, pencarian itu melahirkan Kong fu Tze dan Lao Tze serta berderet-deret nama tokoh yang kemudian dikenal dengan sebutan para Junzi. Junzi adalah sosok pemberani, sama pemberaninya dengan para filsuf di Yunani—meski para filsuf Yunani lebih banyak dikenal sebagai “Docta Ignoratia” atau sekumpulan orang-orang bodoh yang bijak. 13. Janus adalah nama dewa yang memiliki dua wajah. Di satu sisi, wajahnya terlihat begitu baik, tapi di sisi yang lain, wajahnya begitu menyeramkan, dan bengis. Janus ada dalam mitologi Romawi Kuno, dikenal sebagai dewa berwajah dua. Satu menghadap ke depan dan satunya ke belakang. Janus yang juga berarti pintu, gerbang, gapura, porta, lorong masuk, dewa yang penguasa segala pintu, dan pelindung segala karya. 104 F. Metafisika Aksiologi Filsafat Pendidikan Ungkapan bahwa pendidikan adalah proses pembimbingan dan pembentukan yang dapat membawa manusia menjadi baik dan memiliki hidup berkualitas sesungguhnya juga sangat berpolemik. Sebab, ungkapan itu memiliki kesan superior yang negatif. Ungkapan ini bahkan memiliki kesan makna yang bersifat sangat politis. Dengan embel-embel serta legitimasi-legitimasi tertentu, sekelompok orang kemudian menginferiorkan sekelompok orang yang lain sebagai diri yang tidak berarah serta belum bermoral sehingga harus diselamatkan, diarahkan, dan dibentuk agar menjadi baik. Di sini, pendidikan menjadi ruang kesewenang-wenangan yang paling mengerikan, ruang tempat humanisasi dan pelestarian dehumanisasi dilakukan dengan cara begitu terselubung. Ini disebabkan ketika proses pembentukan dan pengarahan itu secara otomatis akan mematikan independensi masing-masing diri. Di sini, baik buruk telah ditetapkan secara baku dan tanpa pilihan. Lebih jauh, hidup setiap diri bahkan telah diformat dan dipilihkan sedemikian rupa oleh diri-diri yang lain. Kenyataan ini tentu saja menjadi hal yang sangat menggelikan dan konyol. Dalam sebuah analogi, misalnya, pendidikan seperti ini sama halnya dengan membuat aturan bahwa setiap pohon tanpa terkecuali harus tumbuh, berakar, memiliki batang, berdahan, beranting, berdaun dengan cara yang sama, serta menghasilkan buah yang sama. Sedangkan, dalam kenyataannya, tidak setiap pohon sama meskipun mereka memiliki kesamaan-kesamaan tipikal. Itu tidak berarti membuat bahwa setiap pohon dapat disamakan secara membabi buta, misalnya semua pohon mesti tumbuh dan berbuah sama seperti halnya anggur. Oleh karena itu, tanpa terkecuali, setiap pohon kemudian “dianggurkan” (dipaksa menjadi anggur) meskipun ia sama sekali bukan pohon anggur. 105 Pola-pola seperti ini jelas hal yang sangat tidak masuk akal. Sama tidak masuk akalnya dengan memaksa setiap diri menjadi yang lain dan menjalani hidup yang bukan hidupnya. Bisa dibayangkan betapa menggelikannya jika di rimba seluruh pohon tumbuhnya dibatasi. Dalam ruang ini, pendidikan menjadi ruang pembatasan humanitas yang diproduksi secara rapi dan sistematis, yaitu setiap orang dihomogenitaskan menjadi diri yang sama dan begitu membabi buta. Memberi label “penting” pada sesuatu hal tentu saja bukan sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan, terutama jika pemberian itu dilakukan tanpa pertimbangan etika. Kita bahkan dapat memberi label “penting” pada hal yang paling sepele dan paling remeh atau sebaliknya memberi label pada sesuatu hal yang teremeh sebagai sesuatu hal yang kemudian dianggap penting. Dalam pertimbangan apa pun, pemberian label seperti itu bukanlah hal yang dibenarkan sebab ia menjadi kebohongan yang begitu sesat dan menyesatkan. Dalam pertimbangan ini, kualifikasi apa pun sesungguhnya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa didasarkan pada pemahaman-pemahaman menyeluruh dan mendasar pada kualitas-kualitas atau situasi-situasi yang meliputi sesuatu yang dikualifikasikan tersebut. Dalam pengertian ini, jika kita menganggap sesuatu hal sebagai sesuatu yang demikian, secara serta-merta kita mesti pula telah memahami dengan baik apa, mengapa, dan bagaimananya sesuatu hal tersebut dapat kita anggap sebagai sesuatu hal yang begitu penting. Hal ini tidak hanya berlaku pada satu hal, tetapi berlaku pada apa pun, termasuk salah satunya pada pendidikan. Di sini, anggapan pendidikan sebagai sesuatu yang penting bagi hidup manusia pada akhirnya menjadi sesuatu hal yang tidak pernah sederhana, sebaliknya menjadi sesuatu hal yang serius dan membutuhkan pemahamanpemahaman yang utuh meliputi aspek ontologis, epistemologis, serta aksiologis pendidikan. Meski demikian, pertama-tama kita agaknya harus 106 memahami sisi aksiologis pendidikan bagi hidup manusia atau tujuan dan fungsi mendasar yang menjadi landasan mengapa pendidikan dinilai penting dan dipandang mesti diadakan di dalam kehidupan? Fungsi yang tidak jelas itu tentu saja merupakan sebuah kekonyolan yang paling tidak termaafkan. Bagaimana bisa sesuatu hal dinilai sebagai sesuatu yang penting, sedangkan kadar fungsi serta kegunaan sesuatu hal tersebut belum diketahui? Andaipun ia masuk kategori penting, kita juga perlu mempertanyakan lebih jauh, seberapa jauh tingkat urgensitasnya? Apakah ia layak dikategorisasikan sebagai sesuatu hal yang begitu teramat penting atau justru hanya pantas dianggap sedikit penting saja? *** Sementara itu, secara praksis, berdasarkan problem-problem di atas, perlu agaknya merumuskan ulang apa, mengapa, dan bagaimananya pendidikan itu. Hal ini bisa dimulai dengan pertanyaan yang bertalian dengan apakah pendidikan itu, bagaimanakah sifat pendidikan itu? Apakah pendidikan merupakan sosialisasi? Apakah pendidikan sebagai pengembangan individu? Bagaimana mendefinisikan pendidikan? Apakah pendidikan berperan penting dalam membina perkembangan atau mengarahkan perkembangan siswa? Apakah perlu membedakan pendidikan teori dengan pendidikan praktik? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh pendidikan, mulai bagaimana proporsi pendidikan yang bersifat umum? Bagaimana proporsi pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu? Apakah peserta didik diperbolehkan berkembang bebas? Apakah perkembangan peserta didik diarahkan ke nilai tertentu? Bagaimana sifat manusia? Dapatkah manusia diperbaiki? Apakah manusia itu sama atau unik? Apakah ilmu dan teknologi satu-satunya kebenaran utama dalam era globalisasi? Apakah tidak ada kebenaran lain yang dapat dianut pada perkembangan manusia? 107 Adapun pertanyaan-pertanyaan yang bertalian dengan cara terbaik perealiasasian tujuan pendidikan, antara lain, apakah pendidikan harus berpusat pada mata pelajaran atau peserta didik? Apakah kurikulum ditentukan lebih dahulu atau berupa pilihan bebas? Ataukah, peserta didik menentukan kurikulumnya sendiri? Apakah lembaga pendidikan permanen atau bersifat tentatif? Apakah proses pendidikan berbaur pada masyarakat yang sedang berubah cepat? Apakah diperlukan kondisi-kondisi tertentu dalam membina perkembangan anak? Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam mendidik anak-anak? Perkembangan apa saja yang diperlukan dalam proses pendidikan? Apakah diperlukan nilai-nilai penuntun dalam proses pendidikan? Bagaimana sebaiknya proses pendidikan itu: otoriter, primitif, atau demokratis? Belajar menekan prestasi atau terpusat pada pengembangan cara belajar dan kepuasan akan hasil belajar? G. Filsafat Pendidikan Socrates “Kalau boleh kusarankan, sedikitlah berpikir tentang Socrates, tapi banyaklah berpikir tentang kebenaran.” (Socrates) *** Siapa yang tidak kenal Socrates? Socrates nyaris menjadi nama yang terus hidup dan populer di sepanjang periode sejarah, terutama sejak tahun-tahun pertama periode Masehi dimulai. Dalam popularitasnya yang begitu luar biasa, Socrates tetap menjadi sosok tersembunyi yang sesungguhnya tidak banyak dipahami oleh berbagai kalangan, baik dalam makna umum dalam ruang filsafat maupun makna khusus sebagai seorang manusia yang memiliki kehidupan yang tentu saja sangat pula tidak sama dengan individu lainnya. Hingga sejauh ini, siapa pun tidak akan menemukan literatur yang mengungkap makna historis Socrates dalam dunia filsafat dalam 108 penjabaran yang jauh lebih jujur. Kebanyakan literatur selalu hanya menyanjung-nyanjung Socrates sebagai filsuf besar tanpa pernah mampu mengungkapkan bagaimana sesungguhnya posisi Socrates dalam konstelasi pemikiran filsafat yang berkembang di Yunani pada waktu itu? Kenyataan tersebut selain sangat memprihatinkan, juga menjadi ironi terbesar kesejarahan kajian filsafat, terutama jika kita kaitkan dengan kenyataan filsafat sebagai bidang kajian yang berusia sangat tua. Paling tidak, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar bagaimana bisa sebuah bidang kajian yang berusia begitu tua, gagal menjelaskan konfigurasi-konfigurasi perkembangannya secara jelas. Kenyataan menjadi sebab yang membuat mengapa hingga sampai hari ungkapan Socrates yang berkata bahwa hidup yang tidak dimengerti tidak layak dijalani kerap menjadi pemikiran filsafat yang dipandang genuine. Kenyataan tersebut akan menjadi lain kisahnya jika orang mengerti betapa dua abad sebelum Socrates mengatakan hal itu, telah terdapat tujuh manusia sophis yang hidup dalam prinsip-prinsip Delphian. Salah satu prinsip Delphi ini adalah ajaran yang menyeru pada siapa pun untuk mengenali diri: kenalilah dirimu. Mengenai hal ini, Nietzsche dalam karyanya Twilight of Idols and the Anti-Christ, agaknya menjadi diri yang paling jujur dalam melihat Socrates. Meski dalam sisi yang lain, obsesi filsafatnya akan sosok ubbermench telah membuatnya tidak melihat jauh lebih saksama betapa dalam apa pun Socrates, khususnya kemartiran dalam dunia filsafat, melahirkan beragam kebijaksanaan baru yang tidak begitu menjelaskan betapa Socrates nyaris layak dikatakan sebagai filsuf. Kematiannya seakan menjadi pintu yang membuka dan menjelaskan pada khalayak betapa filsafat bukan sekadar intelektualitas atau mengerti secara logis, melainkan sebuah keteladanan akan hidup yang benar-benar mengerti dan mendalam. *** 109 Socrates adalah seorang pemikir besar kuno (470–399 SM). Gagasan-gagasan filosofisnya dan metode pengajarannya ditunjukkan untuk memberikan pengaruh yang mendalam dan abadi pada teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia Barat. Socrates yang dilahirkan di Athena adalah putra seorang pemahat dan seorang bidan yang hanya sedikit dikenal kecuali nama mereka, yaitu Sophonicus dan Phaenarete. Sepanjang hidupnya, Socrates tidak pernah menuliskan pemikiran apa pun. Dalam banyak hal Socrates lebih banyak bekerja sebagaimana para nabi, langsung terjun serta memberi contoh secara langsung akan hal-hal serta hidup yang ia maksud. Contoh itu tidak hanya ia buktikan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan yang sungguh-sungguh hidup. Menurut Socrates, hidup yang sebenarnya tidak lain adalah hidup mengatasi jasad. Dengan mengerti hidup, menurut Socrates, setiap diri akan tahu bahwa dalam hidup segala sesuatu sesungguhnya senantiasa berlangsung dengan sederhana, namun tidak pernah menjadi sesuatu yang sederhana. Misalnya, bisa dicontohkan dengan perilaku minum-minum manusia dalam hidup. Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan oleh Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seorang belajar agar dapat berpikir secara cermat, untuk menguji coba diri, dan untuk memperbaiki pengetahuannya. Seorang guru tidak memaksakan wibawa, gagasan, atau pengetahuannya kepada seorang siswa karena seorang siswa dituntut mengembangkan pemikirannya dengan berpikir secara kritis. Ini adalah suatu metode untuk meneruskan intelektualitasnya dan mengembangkan kebiasaan serta kekuatan mentalnya. Tujuan pendidikan yang sebenarnya menurut Socrates adalah untuk merangsang penalaran yang cermat dan disiplin mental yang akan 110 menghasilkan perkembangan intelektual terus-menerus dan standar moral yang tinggi (Smith, 1986:25). Dengan menggunakan metode mengajar yang dialektis ini, Socrates menunjukkan bahwa jawaban-jawaban terbaik atas pertanyaan moral menurut pendapatnya adalah cita-cita yang diajarkan oleh para pendiri agama, cita-cita yang melekat pada ketuhanan, cinta pada umat manusia, keadilan, keberanian, pengetahuan tentang kebaikan dan kejahatan, hormat terhadap kebenaran, sikap yang tak berlebih-lebihan, kebaikan hati, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, dan segala kebajikan lama. Salah satu pendirian Socrates yang terkenal: pengetahuan adalah kekuatan. Socrates yang terkenal dengan ungkapan bahwa pendidikan membuktikan bahwa keutamaan tidak dapat diajarkan dan pendidikan tidak mungkin dijalankan. Seruan alternatif Socrates ditujukan pada kemampuan manusia untuk berpikir menertibkan, meningkatkan, dan mengubah dirinya. Pengetahuan menyatakan kebajikan. Dengan demikian, lahirlah orang yang sekadar tidak berpura-pura saja terhadap cita-cita teoretis, tetapi sungguh-sungguh mengetahui dan mengerti apa yang benar karena ia telah mengalami dan menyadari konsekuensi-konsekuensi perbuatan apa yang benar. Cara Socrates pada dasarnya disebut “dialekta”. Di dalam pengajaran itu, dialog memegang peranan penting. Berbeda dengan seperti Plato, di sini Socrates tidak membangun sistem filsafat yang luas, ia bahkan tidak menggali secara mendalam bidang psikologi, emosi, motivasi, kebiasaan, dan aspek-aspek proses pengetahuan tersebut. Socrates telah memulai sesuatu hal yang jauh lebih besar dari konsep-konsep yang bisa dituliskan. Socrates membangun konsepsi-konsepsi dan metode-metode yang lebih luas, sungguh-sungguh, dan efektif. Dalam pendidikan, Socrates mengemukakan sistem atau cara berpikir yang bersifat induktif, yaitu menyimpan pengetahuan yang 111 bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang hal khusus. H. Filsafat Pendidikan Plato “Filsafat Barat tidak lain hanyalah catatan kaki dari filsafat Plato.” (Issac Newton) Plato adalah murid Socrates yang terkemuka. Ia menyerap ajaran-ajaran pendidikan Socrates serta mengembangkan ke dalam sistem filsafatnya sendiri secara lengkap. Plato ini pulalah yang mendirikan sebuah akademi, suatu pusat untuk studi. Uniknya, biaya pendirian kampus ini adalah hasil uang yang dikumpulkan teman-teman Plato di Athena untuk mengganti uang tebusan yang digunakan pedagang Mesir saat menebus Plato ketika ia jatuh dalam perbudakan. Plato lahir di keluarga aristokrat kaya. Plato kehilangan ayahnya, Ariston, yang mengaku keturunan Cadmus yang pernah berkuasa abad ke-7 SM sebagai raja terakhir Athena. Ibu Plato, Perictiones, adalah keturunan keluarga Solon, seorang pembuat undang-undang, penyair, dan pemimpin militer dari kaum ningrat dan pendiri terkemuka demokrasi Athena. Bagi Plato, pendidikan suatu bangsa harus dilaksanakan untuk kepentingan negara dan perorangan. Pendidikan harus memberikan kesempatan kepadanya untuk tampil menunjukkan kesanggupan diri pribadinya. Bagi negara, pendidikan bertanggung jawab memberikan perkembangan kepada warga negaranya agar dapat berlatih, terdidik, dan merasakan bahagia dalam menjalankan peranannya saat melaksanakan kehidupan kemasyarakatan. Di sebuah negara, idealnya pendidikan memperoleh tempat yang diutamakan serta mendapat perhatian yang paling khusus sebab ia adalah panggilan mulia yang harus diselenggarakan oleh negara. Pendidikan 112 sebenarnya merupakan suatu tindakan pembebasan dari belenggu ketidaktahuan dan ketidakbenaran. Sebab, dengan pendidikan orang-orang akan mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar. Dengan pendidikan pula, orang-orang akan mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Orang-orang juga akan menyadari mana yang patut dan mana yang tidak patut, dan yang paling dominan dari semua itu adalah bahwa pendidikan akan lahir kembali (they shall be born again). Dengan demikian, jelaslah pula bahwa peranan pendidikan yang paling utama bagi manusia adalah membebaskan dan memperbarui. Pembebasan dan pembaruan itu akan membentuk manusia utuh, yaitu manusia yang berhasil menggapai segala keutamaan dan moralitas jiwa mengantarnya ke ide yang tinggi, yaitu kebajikan, kebaikan, dan keadilan. Cita-cita Plato yang paling agung terus digenggamnya sampai akhir hayatnya. Maksud pendidikan menurut Plato tidak lain adalah menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia menjadi seorang warga negara yang baik. Di sini Plato membuat tekanan bahwa pendidikan perlu direncanakan dan diprogramkan sebaik-baiknya agar mampu mencapai sasaran yang diidamkan. Dengan pengertian lain, pendidikan yang baik haruslah direncanakan dan diprogramkan dengan baik pula, guna berhasil menunjang rencana propaganda dan sensor. Propaganda perlu untuk menanamkan program pendidikan. Pemerintah harus mengadakan motivasi, semangat loyalitas, kebersamaan, dan kesatuan cinta akan kebaikan dan keadilan. Adapun hal yang terlewatkan oleh Plato dalam bidang pendidikan terlihat pada pendidikan dasar dan pendidikan untuk kelas penghasil yang merupakan satu-satunya kelas dalam golongan karya yang sebenarnya merupakan golongan terbesar dalam negara. 113 Bagi Plato, pendidikan direncanakan dan diprogram menjadi tiga tahap berdasarkan tingkat usia. Tahap pertama adalah pendidikan yang diberikan kepada remaja hingga sampai dua puluh tahun. Tahap kedua, pendidikan dari usia dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun. Sedangkan, tahap ketiga, pendidikan dari tiga puluh tahun sampai usia empat puluh tahun. I. Filsafat Pendidikan Aristoteles “Saya mencintai Plato, tapi saya lebih mencintai kebenaran.” (Aristoteles) Manusia dalam satu sisi baik, namun buruk dalam banyak sisi. Dante mengatakan bahwa Aristoteles adalah guru semua orang pandai. Orang yang lemah selalu meresahkan keadilan dan kesetaraan. Orang kuat tak menghiraukan semua itu. Berbicara seperti orang biasa dan berpikirlah seperti orang bijak. Hanya dengan cara demikianlah setiap orang bisa memahaminya. Aristoteles adalah murid Plato. Dia adalah seorang cendekiawan dan intelek terkemuka, mungkin sepanjang masa. Umat manusia telah berutang budi padanya karena banyaknya kemajuan dalam filsafat dan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya Logika, Metafisika, Politik, Etika, Biologi, dan Psikologi. Aristoteles dilahirkan pada 394 SM di Stagira, sebuah kota kecil di Semenanjung Chalcidice yang menonjol di sebelah barat laut Egea. Ayahnya, Nichomachus, dokter yang merawat Amyntas II, Raja Macedonia, mengatur agar Aristoteles menerima pendidikan yang lengkap pada awal masa kanak-kanak dan mungkin kemudian mengajar dalam pengamatan gejala-gejala penyakit dan teknik-teknik pembedahan. Baik ayah maupun ibunya, Phaesta, mempunyai nenek moyang terkemuka. 114 Aristoteles juga menganggap penting pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan rendah, sebagaimana pada tingkat pendidikan usia muda perlu ditanamkan kesadaran aturan-aturan moral. Baginya, untuk memperoleh pengetahuan, manusia harus lebih dari binatang-binatang lain berdasarkan kekuatannya untuk berpikir, harus mengamati, dan secara hati-hati menganalisis struktur-struktur, fungsi organisme itu, dan segala yang ada dalam alam. Aristoteles memandang agar orang dapat hidup baik, ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan juga soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi supaya mengarah kepada akal sehingga dapat dipakai akal guna mengatur nafsu-nafsu. Jika akal berdiri sendiri, tidak berdaya. Sebaliknya, akal memerlukan dukungan-dukungan perasaan lebih tinggi yang diberikan seni yang benar. Di titik inilah, Aristoteles kemudian mengemukakan bahwa tujuan pendidikan yang baik adalah untuk kebahagiaan. Kebahagiaan tertinggi adalah hidup spekulatif. Oleh karena itu, pokok pendidikan bagi Aristoteles adalah pengumpulan serta penelitian fakta-fakta belajar induktif, pencarian objektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Di sini sebaiknya pendidikan memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak, mempunyai suatu sistem sekolah negeri yang wajib bagi putra-putrinya, bagi semua warga negara. Akan tetapi, sistem tersebut terdiri dari pendidikan fisik dan latihan militer. Dalam pengertian pendidikan yang lebih tinggi, ia tampak setuju dengan Plato tentang nilai-nilai matematika, fisika, astronomi, dan filsafat. Putra-putri semua warga negara sebaiknya diajar sesuai dengan kemampuan mereka, suatu pandangan mereka yang sama dengan doktrin Plato tentang keberadaan individual. Disiplin merupakan hal esensial yang digunakan untuk mengajarkan para pemuda dan kaum laki-laki 115 muda agar patuh dengan perintah-perintah dan mengendalikan gerakan hati mereka. 116 Bab III Mazhab-Mazhab Pendidikan A. Aliran-Aliran dalam Filsafat Pendidikan Saat kemunculannya yang pertama, filsafat tidak memiliki definisi lain selain sebagai cara atau seni menuju bijak. Dalam konseptualisasi ekstrem, filsafat pada periode pertama saat mulai disadari bahkan tidak, belum memiliki nama apa pun, termasuk nama filsafat. Akan tetapi, pada perkembangannya, saat minat manusia pada bahasa meningkat, filsafat kemudian mengalami fenomena kebahasaan, dan terkontroversikan dalam berbagai istilah sehingga pada akhirnya secara alami, sejarah menentukan takdirnya dengan memilih istilah filsafat sebagai nama untuk menyebut cara menuju bijak. Beberapa literatur menyebutkan penamaan tersebut mengacu paparan Plato dalam karyanya Paidros. Meski terdapat pula yang mengatakan istilah filsafat lahir pertama kali dari Pythagoras (532 SM).14 14. Pythagoras lahir di Pulau Samos. Beberapa kalangan menyebutnya sebagai anak dari salah seorang warga terkemuka bernama Mnesarchos. Terdapat pula versi yang mengatakan bahwa ia adalah putra Dewa Apollo. Samos waktu itu adalah kota pulau yang dipimpin seorang bandit tua yang kaya raya serta memiliki pasukan laut yang kuat, bernama Polycrates. Sebagai kota, Samos juga memiliki beberapa kesamaan cara dalam mempertahankan hidup yaitu selalu berdagang dengan bangsa lain. Kenyataan itu 117 Versi ini kerap menyakini penjelasan Plato tentang filsafat dalam Paidros adalah mengutip pada Pythagoras. Sebab, Pythagoras itulah pemikir yang untuk pertama kalinya mencetuskan istilah filsafat dan menolak kata Sophis sebab dipandangnya terlalu suci. Pandangan ini, misalnya salah satunya bisa kita temukan pada paparan Betrand Russell dalam karyanya The History of Western Philosophy an its Connection with Political and Social Circumstances from the Earlist Times to Present Day (1949). Russell dalam karya tersebut bahkan menulis: “Pythagoras adalah salah seorang tokoh yang paling menarik dan membingungkan sejarah. Bukan saja tradisi yang terkait dengan dirinya adalah adonan menarik, bahkan nyaris sempurna antara kebenaran dan kekeliruannya, akan tetapi bahkan dalam bentuknya yang polos dan amat gamblang dalam tradisi itu tetap menampilkan sutu latar kejiwaan yang sulit dimengerti.”15 Lepas dari kontroversi tersebut, siapa pun agaknya mengetahui bahwa di periode-periode awal sebelum masehi, dunia filsafat belum terpetakan dalam matriks-matriks sebagaimana sekarang ini, hadir dalam aneka ragam corak dan aliran. Meski kemajemukan pemikiran filsafat telah dimulai di waktu yang lama, tetapi dalam pada itu, tidak ditemukan satu indikasi betapa kemajemukan-kemajemukan tersebut kemudian melahirkan berbagai aliran-aliran atau mazhab-mazhab dari pemikiran-pemikiran filsafat aliran lain yang eksklusif. Dalam beberapa literatur tua, kita mungkin akan menemukan adanya penyebutan-penyebutan atau penamaan pada filsafat secara khusus. Akan tetapi, jika ditelaah secara saksama, hal itu tidak menunjuk pada membawa Samos selalu berhadap-hadapan dengan para penduduak kota Miletos yang juga hidup dengan cara sama yaitu berdagang. 15. Betrand Russell, The History of Western Philosophy an its Connection with Political and Social Circumstances from the Earlist Times to Present Day, (London: George Allen, UNWIN, LTD. 1949), hlm. 41 118 kekhasan sisi-sisi pemikiran filsafat. Penamaan itu lebih bersifat fungsional, semata-mata guna membedakan, antara satu pemikiran filsafat dengan pemikiran filsafat lainnya. Misalnya adanya penyebutan “filsafat Milesian”, untuk menyebut pemikiran-pemikiran yang lahir di Pulau Miletos. Penamaan ini memiliki makna yang begitu fungsional semata hanya menunjuk pada faktor tempat, ketimbang unsur yang berkait dengan kekhasan pada metode atau pemikiran filsafat yang dibawa. Dari itu jika kita melacak sejak kapan pemetaan dan munculnya aliran-aliran filsafat, dalam prediksi, pemetaan-pemetaan pemikiran filsafat dengan makna metodis sehingga melahirkan aliran-aliran dan mazhab-mazhab filsafat terpisah itu, besar kemungkinan pertama-tama dimulai di era Pythagoras.16 Hal ini terkait dengan sejarah Pythagoras yang sebab pemikiran-pemikiran filsafatnya, mesti terusir dari negerinya hingga ia tinggal di daerah sekitar Croton. Kelak, di daerah ini terbentuk perkumpulan-perkumpulan eksklusif penganut pemikiran Pythagoras. Kasus pythagorean inilah yang agaknya kemudian menstimulasi lahirnya berbagai “isme” atau aliran-aliran dalam filsafat. Meski beberapa kalangan berpandangan bahwa lahirnya aliran-aliran dalam filsafat lebih disebabkan oleh keadaan yang kondusif serta bebasnya ruang pemikiran di Yunani pada periode itu. Pandangan terakhir ini meski terasa logis, sangat bertentangan dengan berbagai fakta sejarah Yunani; mulai dari Tragedi Socrates hingga pengusiran Pythagoras. Artinya, teori yang mengungkapkan bahwa pengusiran Pythagoras yang menstimulasi lahirnya aliran-aliran dalam filsafat jauh lebih bisa diterima ketimbang persoalan kondisi Yunani sebagai negeri yang kondusif. Meski sejauh dugaan itu, kita tidak bisa memastikan secara pasti periodisasi munculnya pemetaan 16. Pythagoras memiliki reputasi perjalanan yang panjang. Sejak ia pergi dan terusir dari Samos, ia pergi dari Miletos lalu ke Mesir, daerah Sybaris, serta menyusuri daerah Italia Selatan, baru kemudian ia menetap di Croton. 119 pemikiran filsafat dalam kategori aliran-aliran atau mazhab-mazhab sebagaimana sekarang ini. Meskipun di abad pertengahan gejala-gejala penamaan aliran-aliran telah dimulai, tetap saja kita sulit memastikan secara pasti, siapa dan sejak kapan, pemetaan pemikiran filsafat dalam mazhab-mazhab itu dimulai. Sejauh ini, kajian-kajian yang mempersoalkan aliran-aliran dalam filsafat selalu hanya mengungkapkan, tentang apa dan bagaimana sejarah aliran tanpa pernah mempersoalkan sejak kapan dan siapa yang pertama kali memulai pemetaan-pemetaan aliran-aliran dalam filsafat. *** Sementara itu, aliran dalam filsafat pendidikan di berbagai literatur selalu disandarkan dengan penyadaran tipologi aliran dalam filsafat secara umum. Terlihat betapa penamaan aliran-aliran tersebut kemudian tidak sepenuhnya didasarkan pada konsistensi metodis yang jelas. Satu sisi, misalnya, kita akan menemukan adanya aliran filsafat yang penyebutannya didasarkan pada aspek-aspek ontologisnya, sedangkan di sisi yang lain kita akan pula menemukan nama aliran filsafat yang disandarkan pada aspek-aspek epistemologinya. Ketidakkonsistenan ini kerap menjadi problem tersendiri, yang memperumit upaya-upaya pengkajian pemikiran-pemikiran filsafat yang dilakukan. Semakin ke belakang, penamaan-penamaan tersebut berlangsung semakin arbiter sehingga muncul satu kesan betapa dunia filsafat, mengalami demam kebahasaan euforia peristilahan. Seiring dengan waktu, istilah-istilah tersebut pun terus bertambah jumlahnya. Gejala ini kerap diungkap sebagai gejala yang menandai bahwa filsafat makin menjadi ruang permainan bahasa dan asosiasi makna semata. Sesuatu yang belakangan oleh Heidegger kerap diratapi sebagai indikasi terkuat dari runtuhnya filsafat. Filsafat hanya bergerak pada ruang eksplorasi epistemik yang sepenuhnya tanpa ontologi serta 120 begitu positivistik. Kenyataan-kenyataan tersebut memiliki implikasi tak terhindarkan: etika selalu bermuara pada sikap nihilistik yang begitu antah berantah. Di satu sisi, manusia memang masih memiliki berbagai referensi literatur dan sejarah tentang etika. Akan tetapi, etika di sini tidak lagi memiliki perdebatan sebab ia telah berhenti pada satu pola pikir: betapa yang paling jelas dari hidup tidak lain adalah ketidakjelasan. Belakangan, filsafat seakan selalu hanya mampu bergerak pada hidup, yang dalam pengertian apa pun, selalu tidak mungkin dipastikan kemungkinannya, selain berkutat pada pandangan Heraklitus, bahwa yang ada pasti selain perubahan. Sayangnya, perubahan tersebut bukan perubahan situasi yang menyenangkan, dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik, sebaliknya selalu menjadi perubahan-perubahan konstan yang tragis, murung dan begitu tak pasti. Lahirnya Derrida dengan gagasan dekonstruksi makin menjadi penegas betapa filsafat dan hidup makin hari makin tanpa arah proyeksi yang pasti. Sementara, bersamaan dengan itu problem-problem moral dan etika manusia semakin menjadi blunder tak terpecahkan dan berlangsung dalam situasi-situasi yang begitu paradoks. Di satu sisi, dengan makin menjamurnya institusi-institusi pendidikan, dunia mungkin terkesan tengah menuju hidup yang jauh lebih baik. Akan tetapi, di balik semua itu, dunia agaknya terus sekarat, bahkan terus menuju situasi yang jauh lebih buruk. Kemerosotan-kemerosotan hidup terus mewabah hingga tahapan-tahapan yang berlebihan sehingga membuat siapa pun yang menyadari seketika akan kehilangan harapan betapa hidup akan berubah dan bergerak pada kondisi-kondisi yang jauh lebih baik. Dalam periode hidup yang terus membusuk, pendidikan sebenarnya bisa menjadi tumpuan dan harapan, ketika perubahan situasi hidup bisa berlangsung dan dimulai. Hanya saja, harapan-harapan akan perubahan itu agaknya menjadi sesuatu hal sulit untuk kita percayai lebih jauh, 121 terutama karena realitanya pendidikan yang ada mengidap sakit serta kemerosotan yang sama dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Belakangan, pendidikan makin jauh dari makna etis pendidikan. Pendidikan bahkan telah berubah fungsi menjadi industri yang sepenuhnya hidup dan dihidupi dengan dan dalam hukum-hukum ekonomis. Oleh karena itu, kerap dikatakan betapa di kampus-kampus dan sekolah-sekolah seseorang tidak akan bertemu dengan guru, sebaliknya hanya bertemu dengan seseorang pekerja yang diatur dan dilatarbelakangi dalam hukum serta motif ekonomi semata. “Guru”, demikian kita bisa menyebutnya, makin jauh dari makna guru. Hari ini guru tidak lebih hanya komponen kecil dari industri wacana bernama pendidikan. Oleh karena itu, pertemuan dengan para mahasiswa dan siswa tidak lagi memiliki sisi keterkaitan apa pun selain hanya pertemuan dengan klien yang mesti diberi layanan jasa. Kenyataan-kenyataan menjadi ironi terburuk dalam sejarah pendidikan. Di satu sisi, pendidikan dalam kampanyenya selalu mengklaim dirinya sebagai agen kemanusiaan. Namun, bersamaan dengan itu, pendidikan tidak lain adalah agen dehumanisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam jumlahnya begitu luar biasa ribuan institusiinstitusi pendidikan tersebut tidak memberikan siginifikansi perubahan apa pun pada tata kehidupan yang ada, selain makin secara pasti membawa situasi hidup untuk meniti tangga-tangga kehancuran-kehancuran dengan pola-pola yang canggih dan sulit diatasi. Di sini, kita agaknya perlu mengkaji ulang apa dan bagaimana pendidikan, terutama hal-hal yang mendasari lahirnya berbagai problem filosofis pendidikan yang ada. Semisal, ketika pendidikan belakangan telah menjadi industri tenaga-tenaga kerja. Pendidikan tidak lebih hanya perusahaan yang melayani kebutuhan pasar. Sedangkan, pasar tidak pernah memiliki visi lain selain visi ekonomi, peningkatan materialisme, citra, serta kesenangan. 122 Tanpa ekonomi, pendidikan dalam pengertian sesederhana apa pun memang akan mustahil untuk sanggup berjalan. Akan tetapi, sebaliknya jika pendidikan sepenuhnya terproyeksikan pada kepentingan-kepentingan ekonomi belaka, pendidikan dengan sendirinya telah mereduksi makna etis sendiri. Sebuah sikap yang tentu akan melahirkan berbagai keterasingan hidup serta sikap apatis pada pendidikan, terutama karena situasi-situasi akan membawa seseorang cepat atau lambat untuk bertanya, “Untuk apakah pendidikan itu jika hidup yang ada sepenuhnya tetap berlangsung dengan hukum rimba, menang-kalah dan kuat-lemah?” *** Filsafat adalah hal paling mendasar dalam hidup. Oleh karena itu, filsafat selalu menjadi landasan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Di halaman depan telah kita ulas betapa pendidikan pada dasarnya merupakan bentuk praksis yang lahir dari spekulasi-spekulasi etis filsafat atas hidup dan kehidupan manusia. Akan tetapi, tidak selalu spekulasi-spekulasi filsafat bisa diterima sebab tidak sedikit pula spekulasi filsafat yang sama sekali tidak relevan untuk diterapkan. Barat, khususnya Amerika di tahun 1930-an model pendidikan tradisional ketika guru menjadi diri yang otoritatif mungkin dipandang sebagai model pendidikan yang sama sekali tidak humanis. Terlebih, ketika siswa diposisikan sebagai subjek yang selalu dipandang tidak memiliki inisiatif, pemikiran, atau gagasan sehingga mereka selalu harus diindoktrinisasi. Pola-pola pendidikan seperti itu dipandang buruk sebab telah merebut kebebasan serta hidup para siswa itu sendiri. Dengan demikian, muncullah pendidikan model baru yang kita kenal dengan istilah “progresif ”. Teori pendidikan ini sempat mengubah wajah situasi pendidikan Amerika dalam makna yang sama sekali baru. Meskipun pada tahapan 123 perkembangannya teori model pendidikan ini juga menuai kritik yang sama kerasnya sebagaimana teori pendidikan tradisional. Kalangan progresif banyak menuai penentangan tajam dari kalangan esensialis. Para esensialis menuding bahwa kedangkalan spiritualitas sosial disebabkan oleh teori pendidikan progresif. Teori pendidikan yang selalu memprioritaskan subjek didik sebagai diri independen yang mesti selalu dalam kondisi senang saat belajar. Kesenangan (fun) dalam satu sisi memang penting bagi hidup. Siapa pun bahkan tahu tidak ada satu pun manusia yang mau memperoleh penderitaan. Akan tetapi, dalam suatu situasi, kesenangan-kesenangan itu bisa menjadi senjata pembunuh yang dengan diam-diam melumpuhkan sisi kedalaman manusia sebagai makhluk yang spiritual. Dalam pemikiran itulah, para esensialis mengecam kalangan progresif. Kenyataan ini menunjukkan betapa di Barat, pendidikan adalah sesuatu hal yang ketat dan begitu diperhatikan. *** Sementara itu, di Indonesia, pendidikan agaknya berjalan jauh lebih lamban dan terseok-seok. Dalam berbagai pengamatan, kita bahkan dengan mudah akan menemukan satu kenyataan betapa pendidikan di Indonesia nyaris bisa diungkap tanpa dasar landasan filsafat pendidikan yang disadari. Di satu sisi, kita belakangan dengan munculnya LSM, kita akan melihat betapa teori-teori pendidikan progresif diterapkan. Di berbagai wilayah yang terkena bencana, misalnya, kita akan menemukan ruang-ruang pembelajaran non-permanen yang kerap disebut Children Center. Ruang pengajaran tempat anak sepenuhnya dilibatkan secara aktif dan guru semata-mata hanya menjadi fasilitator. Pola-pola penerapan ini memiliki implikasi positif di satu sisi yang implikasi negatif di sisi yang lain, terutama karena pembebasan kebebasan dalam ruang belajar tersebut 124 akan mengalami refleksi dengan konsep kebebasan yang ada dalam lingkungan sosial mereka yang pada umumnya masih begitu normatif. Adapun dalam ruang pendidikan formal, pola pengajaran yang berlaku di Indonesia agaknya masih bersifat tradisional. Beberapa kampus mungkin telah terlihat begitu modern, bahkan memiliki fasilitas-fasilitas pendidikan mahal yang canggih. Akan tetapi, pola pendidikan yang ditetapkan masih sangat tradisional. Ini terindikasi dalam di berbagai kampus dan sekolah, tempat dosen atau guru tetap menjadi pemegang otoritas mutlak saat proses pengajaran berlangsung di kelas. Anehnya, dalam penerapan pola pengajaran yang begitu tradisional, pola penyelenggaraan pendidikan, terutama secara administratif, telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana pendidikan yang ada di negara-negara industrialisme yang maju. Makna profesi guru oleh para guru disadari dengan pola ganda. Di satu sisi sebab bayang-bayang alam bawah sadar normatif mereka, mereka selalu ingin tetap berdiri pada posisi guru dalam pola pendidikan tradisional. Akan tetapi, motif dan semangat yang dalam melakukan pengajaran justru lebih bersifat sangat industri, yaitu lebih banyak dikendalikan oleh motif-motif ekonomi. Kerancuan, ketumpangtindihan, serta ketidakjelasan pola pendidikan agaknya telah menjadi penyebab utama tempat setiap institusi pendidikan selalu melahirkan situasi-situasi kontraproduktif. Hal yang juga fenomenal melanda dunia pendidikan berlatar belakangkan agama, termasuk salah satunya pesantren. Betapa terlihat sebab kuatnya tekanan-tekanan negara akan formalisme pendidikan telah membuat pendidikan pesantren hari ini terus-menerus menyamakan dirinya menjadi tak berbeda dengan pendidikan formal non-agama, dengan kepentingan mereka bisa memperoleh formalisme yang sama dengan yang diperoleh pendidikan umum non-pesantren. Tentu saja, semua formalisme itu mudah ditebak muaranya, yaitu terarah untuk melayani formalisasi yang ada dalam ruang industrialisasi. 125 Kenyataan-kenyataan itu tentu saja sangat buruk. Namun demikian, hingga sejauh ini kita tidak menemukan kalangan yang mampu menguak karut-marut problem yang ada. Hal ini disebabkan oleh kajian tentang filsafat pendidikan di Indonesia masih menjadi kajian yang sangat lemah. Padahal, upaya pengkajian filsafat pendidikan yang baik akan membantu di dalam melihat lebih jauh kenyataan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, kita merumuskan format-format tepat pola pendidikan yang mesti dilakukan berikut berbagai pembahasan tentang kelemahan-kelemahan dari penerapan teori itu. *** Diskursus filsafat pendidikan penting dilakukan guna mengevalusi problem-problem filosofis yang ada dalam pendidikan. Artinya, meski semua pendidikan selalu dapat dipastikan berjalan dengan landasan-landasan filosofis, tidak selalu landasan-landasan itu valid dan tepat dengan situasi pendidikan serta tujuan yang hendak dicapai. Dari itulah, kita perlu mengkaji lebih jauh jenis dan ragam pandangan konsep pendidikan di berbagai aliran filsafat pendidikan. Karena dengan mendalami filsafat pendidikan itulah, pendidikan akan mampu benar-benar terevaluasi, baik dalam ranah konseptual teoretis ataupun ranah praksis pragmatis. *** Filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pewarisan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan yang lebih baik atau sempurna dari keadaan sebelumnya. Dalam pendidikan, diperlukan filsafat pendidikan. 126 Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari dan berusaha menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang bersifat filosofis. Jadi, ketika ditemui masalah atas pertanyaan-pertanyaan soal pendidikan yang bersifat filosofis, wewenang filsafat pendidikanlah untuk menjawab dan menyelesaikannya. Secara filosofis, pendidikan adalah hasil peradaban suatu bangsa yang terus-menerus dikembangkan berdasarkan cita-cita dan tujuan filsafat serta pandangan hidupnya sehingga menjadi suatu kenyataan yang melembaga di dalam masyarakatnya. Dengan demikian, muncullah filsafat pendidikan yang menjadi dasar suatu bangsa berpikir, berperasaan, dan berkelakuan, yang menentukan bentuk sikap hidupnya. Sedangkan, proses pendidikan dilakukan secara terus-menerus dilakukan dari generasi ke generasi secara sadar dan penuh keinsafan. Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran sesorang atau beberapa ahli filsafat tentang sesuatu secara fundamental. Pemecahan masalah-masalah itu kerap melahirkan perbedaan terkait perbedaan filsafat yang digunakan sehingga melahirkan kesimpulan-kesimpulan berbeda meskipun masalah yang dihadapi sama. Perbedaan tersebut dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor lain, seperti latar belakang pribadi para ahli tersebut, pengaruh zaman, kondisi, dan alam pikiran manusia di suatu tempat. Dari pemikiran filsafat yang berbeda-beda inilah, kemudian lahir sistematika yang didasarkan dengan kategori tertentu dan menghasilkan suatu klasifikasi. Dari itulah, kita kemudian menemukan sesuatu yang disebut “aliran (sistem)” suatu filsafat. Pengklasifikasian itu pun kerap berbeda-beda dan tidak sama, terkait dengan kriteria-kriteria yang digunakan. Seorang pemikir mungkin akan kita temukan membedakan aliran-aliran filsafat pendidikan ke dalam beberapa jenis tertentu dengan menyisikan beberapa jenis aliran. Sebaliknya, terdapat pula seseorang yang justru memasukkan aliran-aliran yang disisihkan itu ke dalam klasifikasinya dan mengeluarkan aliran 127 yang lain. Seorang Brubracher, misalnya, membagi aliran dalam filsafat pendidikan ke dalam beberapa bagian. Mulai dari pragmatis-naturalis, rekonstruksionisme, romantis naturalis, eksistensialisme, idealisme, realisme, rasional humanisme, skolastik realisme, fasisme, komunisme, dan demokrasi. Sebagian kalangan memuji pengklasifikasian yang dilakukan oleh Brubracher termasuk sangat teliti karena konon dilakukan untuk menghindari overlapping dari masing-masing aliran. Namun demikian, dalam amatan yang lain, kita justru banyak melihat betapa pengklasifikasian yang dilakukan oleh Brubracher memiliki beberapa kerancuan, terutama dalam tipe-tipe aliran yang ia masukkan kita akan menemukan betapa penetapan itu didasarkan dengan kriteria-kriteria ideologis. Sementara, dalam buku ini, kita akan mengkaji sembilan aliran utama filsafat pendidikan, yaitu (1) idealisme; (2) realisme; (3) pragmatisme; (4) eksistensialisme; (5) progresivisme; (6) esensialisme; (7) perenialisme; (8) rekonstruksionisme; dan (9) behaviorisme. Pemilihan jenis-jenis aliran penulis dasarkan pada kriteria aliran filsafat pendidikan yang memiliki efek metodis secara langsung pada praktik pendidikan. *** B. Filsafat Pendidikan Idealisme Istilah “idealisme” tentu saja telah menjadi istilah atau frase yang sering kita dengar, bahkan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, istilah “idealis” dalam filsafat, selalu mempunyai arti berbeda dari kata idealis dalam bahasa sehari-hari. Secara umum, kata itu dapat kita artikan sebagai seseorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika, atau agama dan menghayatinya. Sementara, di sisi yang lain, idealis dapat pula bermakna seseorang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu 128 rencana atau program yang belum ada. Seseorang yang tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan dan pembaruan hidup di negerinya dapat pula dikategorikan sebagai idealis. Idealisme terkadang digunakan untuk menyanjung atau bermakna peyoratif sebagai bentuk cemoohan kepada seseorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang mustahil dan utopis dicapai. Sementara, dalam arti filosofis, istilah “idealisme” memiliki kedekatan dengan kata ide dari kata ideal. Hal ini sesuai dengan dengan kata dasarnya, yaitu idea yang berarti abadi. Terkadang, idealisme kerap juga disebut dengan istilah lain, dengan nama mentalisme atau imaterialisme. *** Idealisme dalam filsafat adalah aliran pemikiran filsafat yang kental dengan corak metafisik. Idealisme memandang bahwa realitas itu tidak lain adalah ide-ide, akal, pikiran, atau jiwa, bukan benda-benda material ataupun kekuasaan. Gagasan tertua filsafat idealisme telah dimulai jauh sebelum periode Masehi bergulir, tepatnya di era Plato. Plato inilah pencetus pertama filsafat idealisme. Hanya saja, penamaan idealisme baru di awal abad ke-18, dikenalkan seorang pemikir Jerman, bernama Leibniz,17 pada awal abad ke-18. Leibniz 17. Nama lengkapnya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia adalah seorang ilmuwan terkemuka Jerman. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang terdidik. Ayahnya bahkan seorang guru besar di Universitas Leipzig. Di Jerman, ia dianggap sebagai pemikir besar yang memiliki pengetahuan sangat luas dalam bidang Filsafat, Matematika, Sains, Sejarah, dan Teologi. Ia dan Isaac Newton dinyatakan sebagai ahli yang mengembangkan pembedaan kalkulus. Pemikiran filsafatnya kerap disebut Monadologi. Monadologi memiliki prinsip dasar bahwa segala sesuatu merupakan satu kesatuan tak terpisah atau monad, yang eksistensinya ditegakkan oleh Tuhan, dengan begitu terdapat kontinuitas dan tak ada yang terputus dalam alam. Tak ada yang mati karena segala sesuatu adalah aktivitas-aktivitas, yang berbeda hanya derajatnya. 129 memakai dan menerapkan istilah itu untuk menyebut pemikiran Plato yang bertolak belakang dengan Materialisme Epikuros.18 Idealisme memandang bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal (mind), atau jiwa, bukan benda material. Idealisme menekankan idea jauh terlebih dulu ada ketimbang materi. Jika materialisme mengasumsikan bahwa materi adalah riil dan akal adalah fenomena yang menyertainya, idealisme memiliki pandangan sebaliknya: memandang bahwa akal itulah yang riil dan materi adalah produk sampingannya. Dari pengertian itulah, idealisme kerap dipandang sebagai filsafat yang menegasikan dunia ini sebagai realitas yang sesungguhnya dan memandang idea itulah realitas esensi yang fundamental. Dalam perkembangannya, idealisme tumbuh menjadi pandangan dunia atau metafisika yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atau sangat berhubungan dengan ide, pikiran, dan jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Kecenderungan-kecenderungan pemikiran idealisme ini lebih banyak muncul dan berkembang di belahan dunia Barat yang dimulai dengan masa pencerahan dan renaissans. Perdebatan-perdebatan filosofis telah 18. Epikuros lahir pada 341 SM dan meninggal pada 271 SM. Ia adalah adalah seorang filsuf yang mendirikan Mazhab Epikuros. Mazhab tersebut didirikan bersama teman-temannya, Metrodoros, Hermarkhos, dan Polyaenos. Mazhab Epikuros termasuk dalam salah satu mazhab yang berkembang di masa Filsafat Helenistik. Inti ajaran Epikuros adalah mengenai etika bahwa kebahagiaan hidup adalah kenikmatan. Kenikmatan adalah satu-satunya yang baik, serta menjadi awal dan tujuan hidup yang bahagia. Segala macam keutamaan, moral, misalnya, hanya memiliki arti sejauh membawa manusia pada rasa nikmat. Sementara, kenikmatan didefinisikan Epikuros sebagai keadaan negatif, yaitu tidak adanya rasa sakit dan kegelisahan hidup Menurutnya, kenikmatan indrawi memang diperlukan, namun kenikmatan yang jauh lebih penting adalah ketenangan jiwa (dalam bahasa Yunani disebut ataraxia). Cara untuk mencapai ataraxia ini adalah dengan mengalahkan rasa takut kepada kematian. 130 muncul ke permukaan sebagai aliran rasionalisme dan juga empirisme yang keduanya pada tahap tertentu telah memunculkan pandangan idealisme. 1. Idealisme Subjektif George Barkeley Pandangan ini dipelopori salah satunya oleh George Berkeley, dengan pandangan idealisme subjektifnya yang menekankan bahwa keberadaan ide harus bersandar pada akal kita. George Berkeley adalah seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat uskup di Gereja Anglikan. Ia dilahirkan pada 1685 dan meninggal pada 1753. Berkeley mengembangkan suatu pandangan pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisika yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Inti pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan. Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Sebaliknya, justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indra yang satu dan pengamatan indra yang lain. Oleh karena itu, baginya, jika seseorang mengamati meja, hal itu dimungkinkan karena ada hubungan antara indra pelihat dan indra peraba. Indra penglihatan hanya mampu menunjukkan ada warna meja, sedangkan bentuk meja didapat dari indra peraba. Kedua indra tersebut juga tidak menunjukkan jarak antara meja dan orang itu sebab yang memungkinkan pengenalan jarak adalah indra lain dan juga pengalaman. Dengan demikian, Berkeley mengatakan bahwa pengenalan hanya mungkin terjadi pada sesuatu yang konkret. *** Pandangan-pandangan Berkeley dipandang sebagai idealisme pertama dalam pengertian modern abad 18 yang menolak eksistensi 131 independen benda-benda walaupun sebelumnya kecenderungan ini telah ada dalam pemikiran Descartes tentang dunia fisik sehingga lahir sesuatu disebut sebagai rasionalisme. Namun demikian, Descartes berbeda dengan Berkeley. Dalam pada itu, Descartes lebih banyak terlihat berada pada posisinya antara rasionalisme dan empirisme, mengatakan bahwa dia mengakui realitas materi yang ada adalah sebagai apa yang kita pikirkan. Untuk itulah, selain disebut idealis, ia juga sering disebut dengan imateralis. Hal itu tampak dalam keyakinannya bahwa dunia material tidak dapat memiliki realitas independen dari pikiran kita kecuali dengan memersepsikan dunia luar yang kita lihat melalui indra kita. Baginya, jika sebuah pohon hanya berisi kumpulan sensasi dan ide, konsep pohon secara otomatis terbebas dari pohon sebagai hasil proses sensasi selanjutnya. Dari itu, Berkeley menekankan pada pandangan subjektifnya ketimbang pada dunia fisik. Sebab, baginya materi hanyalah sebagaimana yang dipahami (dipersepsi) manusia. Beberapa argumen Berkeley dalam idealisme subjektif terlihat dalam pandangannya tentang pikiran (knowledge). Dalam hal ini, ia meyakini: pertama, apa yang diketahui haruslah “ada di dalam pikiran” atau berhubungan dengan pikiran (mind); kedua, kita tidak dapat mengatakan secara positif bahwa materi yang dipahami berada bebas dari pemahaman; dan ketiga, sifat objek fisik selalu bergantung pada pengalaman dan pikiran. Ketiga pandangan ini tampak dalam kedekatannya dengan pandangannya sebagai seorang empiris. Dia berpendapat bahwa ide dihasilkan di dalam pikiran dengan sesuatu yang kita terima (kita cerap). Berkeley nyaris selalu setuju bahwa ide harus di dalam pikiran meski dia selalu menolak bahwa mereka dapat dihasilkan dari sesuatu yang material di luar kita. 132 Menurut Berkeley, kita tidak dapat mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang fisik kecuali dengan jalan ide, dan di sini kita dapat mempunyai pengetahuan yang bebas tentang sesuatu, yaitu bagian dari ide tersebut. Ketika memersepsi, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa hanya dengan apa yang kita cerap, semua persepsi yang ada dalam ide dapat kita percayai sebagai kebenaran di dalam keberadaannya. Konon menurutnya, kita tidak mempunyai pembenaran untuk memercayai adanya substansi materi yang berada di belakang ide tersebut. Tentang keberadaan ide, Berkeley memandang bahwa materi itu ada jika kita memersepsikan atau mencerap. Inilah yang kemudian dikenal dengan teori esse is percipi. Definisi bahwa suatu ide akan eksis (ada) jika kita persepsi dan cerap, tidak selalu sesuatu yang substansinya materi. Idealisme subjektif model Berkeley memandang bahwa walau bagaimanapun pikiran hanya dapat bekerja melalui tubuh. Secara tidak langsung, hal ini terlihat telah meninggalkan idealisme klasik yang memandang bahwa tubuh selalu menjadi varian sekunder setelah akal. Sejak awal, dia percaya bahwa dunia material tidak mungkin memiliki keberadaan independen kecuali dalam pikiran (subjektif idealisme) atau di dalam prosesnya. Lebih jauh lagi, hal ini mengisyaratkan bahwa realitas manusia dan nilai-nilai tujuan atau dasar dari realitas alam hanya ada dalam pikiran. Inilah yang menjadi tujuan idealisme subjektif, yaitu konsep realitas lebih ditentukan oleh pikiran daripada dunia material. Berkeley berpandangan bahwa terdapat kesatuan organik dunia yang lebih dari sekadar sebuah mesin yang dijalankan Tuhan. Berkeley memercayai ide sebagai proses atau capaian persepsi benda material, dan di sisi lain ia juga melihat Tuhan berperan dalam memberikan kebebasan. Tuhan dipandang Berkeley sebagai suatu substansi yang independen dan terbebas dari pikiran dalam diri manusia. Dia percaya bahwa substansi material tergantung pada kebebasan kita dalam memersepsi sesuatu adalah dapat dipikirkan. 133 Jika dibandingkan, Leibniz dengan monadologinya berpendapat bahwa materi adalah terkomposisi, dibuat dari sesuatu persepsi yang tidak terkomposisi, sebuah satuan kekuatan, yang disebutnya dengan “monad”. Menurutnya, “monad-monad” ini masing-masing bersifat unik. Sebagai sudut pandang atau perspektif di alam semesta, “monad-monad” ini hierarki ke dalam tubuh, jiwa “monad”, dan “monad Allah”, substansi spiritual yang tertinggi. Dalam keunikannya, “monad-monad” ini terbebas dan membentuk harmoni dalam diri mereka. Jika dibandingkan dengan Berkeley, pandangan idealisme Leibniz agaknya lebih bersifat empiris. Misalnya, terlihat dalam pandangan Leibniz, ketika ia lebih menyakini bahwa “apa yang kita tahu adalah apa yang kita rasa”. Hal ini dapat kita lihat pandangannya tentang jiwa dan juga ide yang terbentuk tanpa kontak langsung dengan dunia luar, seperti imajinasi. Menurut Berkeley, ide tidak selalu berkaitan dengan sesuatu. Kita melihat bahwa beberapa ide disebut, sebagai imajinasi, merupakan subjek bagi kehendak kita, dan di sini mungkin dapat dikatakan untuk menjadi ide. Maka, ide itu dihasilkan oleh kita. Untuk itu, kita dapat melihat pemikiran Berkeley bahwa ide dihasilkan oleh pikiran atau jiwa. Jiwa itulah yang kita bangun. Ide persepsi tidak dihasilkan oleh diri kita, tetapi harus dihasilkan di dalam pikiran kita dengan beberapa jiwa lainnya, yaitu Tuhan. Jiwa adalah satu-satunya sumber ide. Mereka satu-satunya sesuatu yang aktif. Ide selalu dicatat, menjadi pasif karena definisi. Akan tetapi, menurutnya, kita tidak mempunyai ide tentang jiwa (Tuhan). Kita mempunyai beberapa pandangan tentang mereka. Kita dapat memahami apa yang kita maksud dengan kata jiwa karena kita mengetahui bahwa kita adalah sumber dari beberapa ide. 134 2. Idealisme Immanuel Kant Pandangan Barkeley di atas berpengaruh besar bagi pendidikan modern dan memancing munculnya idealisme baru seorang Immanuel Kant (1724–1804). Pemikiran Kant muncul sebagai pemicu wisata intelektual yang paling berpengaruh dalam filsafat. Konsep idealismenya didasarkan pada pemikirannya yang rapi dan terarah dan relevan dengan idealisme. Dalam hal ini, Kant mengembangkan dualisme. Dia memercayai keberadaan realitas eksternal. Akan tetapi, di sisi lain dia berpendapat bahwa pikiran memberikan keunggulan dalam memahami itu. Lebih khusus lagi, ia berpendapat bahwa, baik pikiran maupun pancaindra, akan menghasilkan pengetahuan. Menurutnya, apa yang kita dapatkan melalui indra sebenarnya kita sendirilah yang menentukan keberadaannya sebagai sebuah pikiran (ide) atau hanya sekadar sensasi. Untuk itulah, pemikiran kosong dengan sendirinya, tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang diri kita atau kenyataan. Untuk lebih gamblang, Kant menjelaskan bahwa persepsi harus didasari dengan pengetahuan a priori—sebuah intuisi, serta adanya konsep ruang dan waktu dan juga sebab dan akibat. Karena alasan itulah, kita harus menggunakan indra. Selain itu, karena asumsi bahwa realitas ada di luar pikiran, Kant mengatakan bahwa perlu adanya pembagian kategori pada objek realitas tersebut. Karena terdapat hubungan yang sangat khusus (intim) antara akal dan pancaindra, antara pikiran dan tubuh, “pikiran” dianggap Kant sebagai suatu kegiatan. Pendapat tersebut membawa kita pada realitas kategori “pengertian” dan tidak hanya mencerminkan realitas atau cermin dengan pikiran kita, bukan hanya prasangka sebagaimana argumentasi Descartes. 135 Namun, sesuai keterbatasan yang disusun oleh sebuah kategori a priori ini, kita belajar dari kenyataan. Kita dapat meningkatkan pengetahuan kita melalui eksperimentasi dan tes. Dengan demikian, untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus dapat mencari dan belajar. Kita harus memiliki kebebasan. Karena sifat moral, Kant berpendapat bahwa determinisme materialistis merupakan rantai alasan yang menyebabkan fisik dan hukum harus palsu. Menurut Kant, pengetahuan yang mutlak benarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui indra. Akan tetapi, bila pengetahuan ini datang dari luar melalui akal murni, yang tidak bergantung pada pengalaman, bahkan tidak bergantung pada indra, yang kebenarannya a priori, menurutnya dari sinilah kita mendapatkan pengetahuan yang mutlak yang dapat dipegang kebenarannya, bahkan menjadi pengetahuan yang absolut. Di sinilah letak transenden idealisme Kant: jika kita lihat lebih jauh, pendapatnya ini mengisyaratkan akan adanya objektivitas dalam diri objek walaupun manusia tidak mampu mendapatkannya hanya dengan pancaindra dan hal tersebut hanya dapat dimengerti oleh akal murni, dengan kategori kategori a priori. Kemudian, setelah Kant, pada tahap berikutnya, Hegel terlihat menyintesis dua kecenderungan antara subjektif dan objektif idealisme sehingga muncullah sesuatu yang kelak oleh sejarah dikenal dengan istilah idealisme absolut. Menurutnya, realitas dunia tidak lain hanyalah refleksi sebuah pikiran, yang segala sesuatunya dinisbahkan pada ide dan maksud-maksud dari suatu akal yang mutlak. Idealisme mencakup pula beberapa pengertian antara lain adanya suatu teori tentang alam semesta beserta isinya adalah suatu penjelmaan pikiran. Kemudian, idealisme juga digunakan untuk menyebut eksistensi realitas, yang dipandang bergantung pada pikiran dan aktivitas-aktivitas pikiran. 136 Sementara, realitas dalam idealisme selalu disadari sebagai gejala-gejala psikis, seperti pikiran-pikiran, diri, ruh, ide-ide, pikiran mutlak, dan lain sebagainya, bukan hal yang berkenaan dengan materi. Oleh karena itu, dalam idealisme, seluruh realitas bersifat mental (spiritual, psikis). Materi dalam bentuk fisik tidak ada. Sebaliknya, yang ada tidak lain adalah aktivitas pikiran dan isi pikiran, dunia eksternal tidak bersifat fisik. Pandangan beberapa filsuf tentang idealisme salah satunya dapat ditemukan pada Schelling yang memberikan nama idealisme subjektif pada filsafat Fichte, dengan alasan bahwa dalam filsafat Fichte, dunia merupakan postulat subjek yang memutuskan. Ia menyebut pemikiran filsafatnya dengan istilah idealisme objektif. Konon, menurutnya, alam tidak lain adalah inteligensi yang terlihat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua filsafat yang mengindentikkan realitas dengan ide, akal, atau ruh. Sementara itu, Hegel terlihat menerima klasifikasi Schelling dan mengubahnya menjadi idealisme absolut sebagai sintesis dari pandangan idealisme subjektif (tesis) dan objektif (antitesis). Idealisme lain dapat kita temukan dengan adanya istilah idealisme transendental. Istilah ini digunakan untuk menyebut pemikiran-pemikiran Immanuel Kant meski di ruang lain filsafat Kant kerap pula disebut sebagai idealisme kritis. Pandangan ini mempunyai alternatif, yaitu isi dari pengalaman langsung tidak dianggap sebagai benda dalam dirinya, sedangkan ruang dan waktu merupakan forma intuisi diri kita. 3. Idealisme Epistemologis Kemudian, dikenal pula istilah “idealisme epistemologis”. Idealisme epistemologis memandang bahwa kita membuat kontak hanya dengan ide-ide atau pada peristiwa mana pun dengan entitas-entitas psikis. Idealisme personal terlihat digunakan untuk menyebut sistem filsafat Howison dan Bowne. Idealisme voluntarisme dikembangkan oleh Fouille 137 dalam suatu sistem yang melibatkan tenaga pemikiran: idealisme teistik pandangan dan sistem filsafat dari Ward. Idealisme monistik merupakan penyebutan sistem filsafat Paulsen. Sedangkan, idealisme etis adalah pandangan filsafat yang dianut oleh Sorley dan Messer. Idealisme Jerman pemicunya adalah Immanuel Kant dan dikembangkan oleh penerus-penerusnya. Idealisme merupakan pembaruan paham platonis karena para pemikir melakukan terobosan-terobosan filosofis yang sangat penting dalam sejarah manusia, hanya dalam tempo yang sangat singkat, yaitu 40 tahun (1790–1830) dan gerakan intelektual ini mempunyai kedalaman dan kekayaan berpikir yang tiada bandingnya. 4. Pendidikan bagi Para Idealis Menurut para filsuf idealisme, pendidikan bertujuan membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi (self) siswa. Karena bakat manusia berbeda-beda, pendidikan yang diberikan kepada setiap orang harus sesuai dengan bakatnya masing-masing. Kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Pendidikan liberal dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuankemampuan rasional dan moral. Pendidikan vokasional dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan suatu kehidupan atau pekerjaan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Tidak cukup mengajar siswa mengenai cara berpikir. Penting bahwa apa yang siswa pikirkan menjadi kenyataan dalam perbuatan. Metode mengajar hendaknya mendorong siswa untuk memperluas cakrawala, mendorong berpikir reflektif, mendorong pilihan-pilihan moral pribadi, memberikan keterampilan-keterampilan berpikir logis, memberikan 138 kesempatan menggunakan pengetahuan untuk masalah-masalah moral dan sosial, meningkatkan minat terhadap isi mata pelajaran, dan mendorong siswa menerima nilai-nilai peradaban manusia. Para filsuf idealisme mempunyai harapan yang tinggi dari para guru. Keunggulan harus ada pada guru, baik secara moral maupun intelektual. Tidak ada satu unsur pun yang lebih penting di dalam sistem sekolah selain guru. Guru hendaknya bekerja sama dengan alam dalam proses menggabungkan manusia, bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi para siswa. Sedangkan, siswa berperan bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Guru dalam sistem pengajaran yang menganut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi kenyataan si anak didik; harus menjadi spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa; haruslah menguasai teknik mengajar secara baik; haruslah menjadi pribadi terbaik sehingga disegani oleh para murid; dan menjadi teman para muridnya. Guru dipandang harus menjadi pribadi yang mampu membangkitkan gairah murid untuk belajar; harus bisa menjadi idola para siswa; rajin beribadah sehingga menjadi insan kamil yang bisa menjadi teladan para siswanya; menjadi pribadi yang komunikatif; mampu mengapresiasi subjek yang menjadi bahan ajar yang diajarkannya; harus ikut belajar sebagaimana para siswa; merasa bahagia jika muridnya berhasil; bersikap demokratis serta mengembangkan demokrasi; dan mampu belajar bagaimanapun keadaannya. Idealisme memandang bahwa pendidikan bagi kehidupan sosial bertujuan membentuk persaudaraan antar-sesama manusia karena dalam semangat persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekadar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia satu dengan lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sedangkan, tujuan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara 139 tujuan individual dan sosial sekaligus, yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. C. Filsafat Pendidikan Realisme “Gunung yang menjulang itu memang benar-benar sebuah gunung yang nyata dan ada. Ia bukanlah konsep atau ide yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu, ia akan tetap ada meski tidak ada satu pun manusia yang memikirkannya.” Realisme demikian aliran filsafat ini kerap dipandang sebagai sisi keping yang berbeda dari idealisme, hadir menjadi reaksi corak idealisme yang cenderung abstrak dan metafisik. Instrumen utama realisme adalah indra dan terlepas dari asumsi pengetahuan yang dikonstruksi akal pikir. Ini menjadi pembeda yang begitu tegas dengan idealisme yang justru lebih berpegang pada kondisi-kondisi mental akal pikiran. Gagasan filsafat realisme terlacak dimulai sebelum periode abad masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles (384–322 SM). Sebagai murid Plato, sedikit banyak Aristoteles tentu saja memiliki pemikiran yang sangat dipengaruhi Plato dalam berfilsafat. Dalam keterpengaruhannya, Aristoteles memiliki sesuatu perbedaan pemikiran yang membuatnya menjadi berbeda dengan Plato. Ibarat Plato memulai filsafatnya dari di sebelah selatan, Aristoteles justru memulai dari sebelah utara. Filsafat Aristoteles tampak seperti antitesis filsafat Plato yang justru memiliki corak idealisme. Oleh karena itu, jika Plato meyakini bahwa apa yang sungguh-sungguh ada adalah yang ada dalam alam idea, Aristoteles justru memandang bahwa apa yang di luar alam ide, termasuk benda-benda yang terlihat indra bukanlah idea yang lahir dari replikasi yang ada dalam pikiran atau mental. Bagi Aristoteles, benda-benda itu sungguh pun tidak ada yang memikirkannya ia tetaplah ada. Keberadaannya tersebut tidak ditentukan 140 oleh akal. Di sini fokus perhatian Aristoteles terhadap kemungkinan sampai pada konsepsi-konsepsi tentang bentuk universal melalui kajian-kajian atas objek-objek material. Kelak, ini akan menjadi dasar-dasar pertama bagi lahirnya fisika modern serta sains. Selanjutnya, realisme agaknya dipengaruhi dua filsuf terkemuka, yaitu Francis Bacon (1561–1626)19 dengan pemikirannya tentang metodologi 19. Francis Bacon lahir di London pada 1561 dalam keluarga elite yang kaya. Ayahnya adalah pegawai eselon tinggi di masa Ratu Elizabeth. Di usia 13 tahun ia belajar di Trinity College di Cambridge, namun baru tiga tahun ia keluar dan tidak menyelesaikan studinya. Di usia 16 tahun ia sempat bekerja di staf kedubes Inggris di Paris meski mesti pulang sebab kematian ayahnya. Bacon tidak memiliki warisan harta yang berlimpah. Sejak ayahnya meninggal, ia bahkan mesti mempertahankan hidupnya sebagai pengacara. Hidup mewah membuatnya terbelit utang. Beruntunglah, ia memiliki kedekatan khusus, seorang bangsawan muda yang penuh ambisi politik: Pangeran Essex. Sementara, karier Bacon dimulai sejak menjadi penulis. Kemampuan menulisnya yang memang bagus didukung kemampuan berpolitik membuatnya populer, bahkan pada 1662 dianggap sebagai sumber inspirasi oleh sekelompok elite yang tergabung dalam Royal Society of London yang berupaya menggalakkan ilmu pengetahuan. Di sana Bacon disebutkan sebagai pendiri. Dengan demikian, saat Encyclopedie yang besar itu ditulis, “Pembaruan Perancis”, para penyumbang tulisan utama, seperti Diderot dan d’Alembert, juga menyampaikan pujiannya kepada Bacon yang memberikan inspirasi terhadap kerjanya. Tulisan Bacon terpenting menyangkut filsafat ilmu pengetahuan. Di sana ia membuat pemetaan kerja besar Instauratio Magna atau Great Renewal dalam enam bagian: peninjauan ilmu pengetahuan, penjabaran sistem baru telaah ilmu, kumpulan data empiris, ilustrasi sistem baru ilmiahnya dalam praktik, kesimpulan, serta sintesis ilmu pengetahuan yang diperoleh dari metode barunya. Skema fantastis ini kerap dinilai sebagai pekerjaan terambisius sejak Aristoteles, yang tak pernah terselesaikan. Karya The Advancement of Learning (1605) dan Novum Organum (1620) dianggap penyelesaian kedua bagian dari kerja raksasanya. Novum Organum atau New Instrument menjadi buku Bacon terpenting, yang berisi metode empiris tentang penyelidikan serta kritik pada logika deduksi Aristoteles yang dipandang merosot. Dari itu, Bacon mengenalkan metode baru yang disebutnya induktif. Buku terakhir Bacon, The New Atlantis, berisi penjelasan negeri utopis yang terletak di pulau khayalan di Pasifik. Konon, buku ini terinspirasi dari gagasan utopia Sir Thomas More meski keseluruhan pokok masalah di dalamnya berbeda. Dalam buku itu, kemakmuran dan keadilan dalam negara idealnya, Bacon ungkapkan sangat terkait hasil pada hasil-hasil penyelidikan ilmiah. Sesuatu yang secara implisit ditangkap banyak kalangan sebagai pemberitahuan Bacon bahwa penggunaan inteligensia dalam penyelidikan ilmiah dapat 141 induktif serta John Locke tentang konsep akal-pikir jiwa manusia yang disebutnya sebagai “tabula rasa”, ruang kosong tak ubahnya kertas putih kemudian menerima impresi dari lingkungan. Kelak, di abad ke-20, pada 1960-an kita akan menemukan Harry S. Boudy sebagai seorang pemikir realisme modern yang selalu penuh antusias. Ini bisa kita temukan dengan karyanya yang berjudul, Building a Philosohy of Education (1961). 1. Metafisika Realisme Sebagaimana sedikit telah kita ulas, realitas merupakan sisi lain idealisme. Jika ontologis idealisme selalu merujuk bahwa yang ada adalah yang ideal atau sesuatu yang ada dan bisa dipikirkan, sebaliknya realisme justru meyakini bahwa yang ada adalah sesuatu yang bisa teramati oleh indra. Dalam pandangan tersebut, realisme menjadikan indra atau pengamatan sebagai instrumen atau epistemologi dalam memperoleh pengetahuan serta kebenaran. Para realis, termasuk Bacon, memandang bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu titik tempat bertolak dan mengambil kesimpulan darinya, melainkan ilmu pengetahuan adalah sesuatu tempat sampai ke tujuan. Untuk memahami dunia, orang mesti “mengamati”-nya. Kemudian, mengumpulkan fakta, lalu membuat kesimpulan berdasar pada fakta-fakta itu dengan cara membuat argumentasi induktif yang logis. Di sini bagi seorang realis, seribu kali sekalipun, akal memiliki ide tentang sesuatu hal. Akan tetapi, jika ia tidak bisa teramati oleh indra, sesuatu itu bukanlah sesuatu yang ada. Dalam banyak pengamatan, common sense menjadi epistemologi filsafat realisme. Cerapan indrawi menjadi sarana utama untuk memperolehnya. membuat Eropa makmur dan bahagia seperti halnya penduduk yang hidup di pulau khayalan itu. Gagasan ini membuat Francis Bacon kerap dinilai sebagai filsuf modern pertama yang sekuler, empiris, dan realis dalam soal politik. Hari ini andaikata Novum Organum dan The New Atlantis agak kurang dibaca adalah karena gagasan-gagasan di dalamnya telah diterima begitu luas. 142 Seorang W.E. Hocking dengan nada sarkastiknya membuat pernyataan, betapa sebagai watak umum dari akal, realisme adalah sebuah kecenderungan untuk menjaga diri dan preferensi hidup agar seseorang tidak mencampuri putusan tentang segala sesuatu dan membiarkan objek-objek berbicara untuk dirinya. 20 2. Realisme dan Pendidikan Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal-pikir jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong tak ubahnya kertas putih kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individu agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam realisme kerap indentikkan sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Murid adalah sosok yang mengalami inferiorisasi secara berlebih sebab ia dipandang sama sekali tidak mengetahui apa pun kecuali apa-apa yang telah pendidikan berikan. Di sini dalam pengajaran setiap siswa akan subjek didik tak berbeda dengan robot. Ia mesti tunduk dan patuh sepatuh-patuhnya untuk diprogram dan mengerti materi-materi yang telah ditetapkan sedemikian rupa. Pada ujung pendidikan, realisme memiliki proyeksi ketika manusia akan dibentuk untuk hidup dalam nilai-nilai yang telah menjadi common sense sehingga mereka mampu beradaptasi dengan lingkunganlingkungan yang ada. Sisi buruk pendidikan model ini kemudian cenderung lebih banyak dikendalikan skeptisisme positivistik, ketika mereka dalam hal apa pun akan meminta bukti dalam bentuk-bentuk yang bisa didemonstrasikan secara indrawi. 20. Hocking, Types of Philosophy, hlm. 225. 143 Realisme memiliki pula jasa bagi perkembangan dunia pendidikan. Salah satunya adalah dengan temuan gagasan Crezh, salah seorang pendidik di Mosenius pada abad ke-17 dengan karya Orbic Pictus-nya.21 Pada periode itu, temuan Orbic Pictus sempat mengejutkan dunia pendidikan dan dipandang sebagai gagasan baru. Ini disebabkan oleh paling tidak pada periode tersebut, belum ada satu pun yang memiliki pemikiran untuk memasukkan alat bantu visual seperti gambar-gambar perlu digunakan dalam pengajaran anak, terutama dalam mempelajari bahasa. Di abad selanjutnya, yaitu ke-18 menjelang abad 19, gagasan Moravi ini menginspirasi seorang Pestalozzi. Ia menghadirkan objek-objek peraga fisik dalam ruang pengajaran di dalam kelas. Corak lain kecenderungan lain pendidikan realisme adalah tekanan-tekanan hidup yang terarah ke dalam pengaturan-pengaturan serta keteraturan yang bersifat mekanistik. Meskipun tidak semua pengaturan yang bersifat mekanistik buruk, apa yang diterapkan realisme dalam ruang pendidikan melahirkan berbagai hal yang kemudian menuai banyak kecaman sebab dinilai telah menjadi penyebab berbagai dehumanisasi. D. Filsafat Pendidikan Pragmatisme Pragmatisme22 adalah aliran filsafat modern yang lahir di Amerika akhir abad 19 hingga awal abad 20. Filsafat ini cenderung lebih banyak mengabaikan hal-hal yang bersifat metafisik tradisional dan lebih banyak 21. Orbic Pictus atau Orbis Sensualium Pictus (dunia dilihat dari gambar) adalah sebuah buku untuk anak-anak yang ditulis Crezh, seorang guru di Comenius, yang terpublikasikan pada 1658. Buku ini dianggap sebagai ensiklopedi bergambar untuk anak. 22. Sebuah versi menyebutkan jauh istilah “pragmatis” pernah pula digunakan Kant “pragmatich” guna menunjuk pemikiran-pemikitan yang sedang berlaku dan ditetapkan dengan maksud-maksud serta rencana-rencana. Menurut Kant, prinsip tentang akal praktis telah menjadi merintis jalan bagi pragmatisme. 144 terarah pada hal-hal yang pragmatis kehidupan. Pragmatisme lahir di tengah-tengah situasi sosial Amerika yang dilanda berbagai problem terkiat dengan kuat dan masifnya urbanisasi dan industrialisasi. Berakhirnya Perang Dunia I dengan korban sekitar 8,4 juta jiwa secara tidak langsung telah melahirkan dampak psikologis yang begitu meluas dan memicu terjadi berbagai perubahan-perubahan bangsa, khususnya para filsuf di dalam menyadari hidup dan kehidupan yang ada. Eropa abad pertengahan kehilangan utopia hidupnya mulai dari moralitas serta spiritual. Atas nama nasionalisme dan demi mengejar keuntungan-keuntungan serta kebanggaan semu, dunia yang selama ini beradab telah membuktikan diri hadir menjadi dunia yang sepenuhnya irasional, horor, dan buta terhadap gagasan-gagasan nilai yang dibangunnya. Dalam kondisi seperti itulah, pragmatisme kemudian lahir di Amerika. Aliran ini melahirkan beberapa nama yang cukup berpengaruh mulai Charles S. Pierce 23 (1839–1914), William 23. Charles Sanders Peirce (1839–1914) dikenal sebagai pendiri pragmatisme Amerika. Oleh karena itu, terdapat istilah “Piercian” untuk menyebut pemikiran pragmatisme Charles Sanders Peirce membedakan pandangan-pandangannya dari para pragmatis lainnya. Peirce adalah seorang ahli teori logika, bahasa, komunikasi, dan teori umum tanda-tanda, sesuatu yang oleh Peirce disebut sebagai semiotika. Selain itu, ia juga mendalami logika matematika produktif luar biasa dan matematika umum dan merupakan pengembang dari psiko, fisik monistik metafisik sistem evolusi. Ia lahir dalam keluarga kelas menengah yang terpelajar. Ayahnya bahkan seorang profesor Matematika di Universitas Harvard. Pierce mulanya seseorang yang tertarik persoalan kimia dan geodesi dengan antusiasme yang cukup berlebih. Di sepanjang usianya, ia bahkan tidak selalu terlibat dalam berbagai penelitian-penelitian kimia. Persentuhannya dengan filsafat dimulai di usia 17 tahun, saat ia masih duduk sebagai salah seorang mahasiswa di Universitas Harvard. Ia tertarik dengan tulisan-tulisan Schiller tentang Pendidikan Estetis Manusia dan karya Immanuel Kant, Critique of Pure Reason. Bagi Kant, Pierce bahkan menghabiskan waktu tiga tahun dan membuat kesimpulan jika efektivitas sistem Kant disebabkan oleh apa yang disebut “logika kekanak-kanakan”. Pengalaman ini memengaruhinya dan mengerakkan dirinya untuk mengabdikan hidupnya dalam studi dan penelitian logika. Dari tahun 1860-an sampai kematiannya pada 1914, ia melahirkan berbagai karya logika yang cukup tebal dan bervariasi. Pemikiran logikanya bahkan menjadi dasar pijakan utama Schroeder 145 James24 (1842–1910), John Dewey, dan seseorang pemikir yang juga cukup menonjol bernama George Herbert Mead 25(1863– 1931). dalam melahirkan karya Vorlesungen ueber die Algebra der Logik. Peirce dianggap sebagai ahli logika terbesar pada zamannya. Oleh semua orang yang akrab dengan karyanya, ia dianggap sebagai salah satu ahli logika terbesar yang pernah hidup. 24. William James adalah seorang filsuf Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog. Ia dilahirkan di New York pada 1842. Setelah belajar ilmu kedokteran di Universitas Harvard, ia belajar psikologi di Jerman dan Prancis. Kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang Anatomi, Fisiologi dan Psikologi, dan filsafat, hingga tahun 1907. Pada 1910, ia meninggal dunia. Kedekatannya dengan persoalan psikologi di satu sisi dan fisiologi di sisi yang lain agaknya menjadi penyebab utama William James bersinggungan dengan tema-tema filsafat, serta membawanya pada karier puncak bahkan dikenal sebagai seorang filsuf modern Eropa abad ke-19. Filsafat James terlihat lebih banyak bermain di ruang antitesis. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran filsafatnya lebih banyak berupa refleksi pemikiran filsafat sebelumnya. Dalam soal kesadaran, misalnya, gagasan James terlihat sebagai upaya perlawanan dari adanya pandangan yang menyatakan bahwa kesadaran tidak bersatu dengan aspek-aspek fisis. Di sini ia justru menyatakan kesadaran selalu terikat dengan aspek-aspek fisis, dari itulah pengalaman selalu menjadi sumber pengetahuan termurni manusia. Dalam pengalaman kehidupan yang terus berubah, manusia kesadaran manusia pun berubah serta mengalami relativitas. Dalam pemikiran ini, James menolak adanya kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, serta bersifat berdiri sendiri. Bagi James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman murni. 25. Mead atau George Herbert Mead memiliki periode kehidupan yang tak jauh berbeda dengan William James atau Pierce. Ia juga dikenal sebagai filsuf Amerika yang berpengaruh, khususnya dalam aliran pragmatisme. Mead lebih banyak terlihat sebagai seseorang pakar teori sosial ketimbang seorang filsuf, terutama karena ketertarikan yang berlebih pada teori-teori sosial. Mead lahir di daerah Hadley Selatan, Massachusetts. Ia adalah anak seorang pendeta dari gereja Kongregasional yang kemudian pada 1869 pindah ke Ohio untuk bergabung dengan The Oberlin Theological Seminary untuk mengajar homiletik. Karena kepindahan itu, Mead belajar di Oberlin dari tahun 1879–1883. Kemudian, di tahun 1887–1888 ia belajar di Harvard pada seorang filsuf bernama Josiah Royce, seseorang yang begitu mendalami pemikiran Hegel dan cukup berpengaruh pada diri Mead. Selama tahun-tahun di kampus, Mead menjadi sosok seorang naturalis yang mengagumi pemikiran Darwin di satu sisi, dan Hegel di sisi yang lain. Meski selain itu, ia juga memerankan sebagai seorang Kristen yang baik, yang percaya bahwa bahwa kesaksian Kristen selalu mesti dilahirkan dalam sikap-sikap pelayanan pada kepentingan umum. 146 1. Metafisika Pragmatisme Filsafat pragmatisme secara umum dipandang berupaya menengahi pertikaian idealisme dan empirisme serta berupaya melakukan sintesis antara keduanya. Pragmatisme mendasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dari pikiran serta kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. Di sini pandangan William James tentang pragmatisme agaknya mewakili pertanyaan kita tentang pragmatisme tersebut. Pragmatisme adalah sikap memandang jauh terhadap benda-benda pertama, prinsip-prinsip, serta kategori-kategori yang dianggap sangat penting untuk melihat ke depan pada benda-benda terakhir berdasarkan akibat dan fakta-fakta.26 Dalam penjabaran William di atas, kita bisa mengetahui betapa filsafat pragmatisme selalu menjadi pemikiran filsafat yang didasarkan pada metode dan pendirian ketimbang pada doktrin filsafat yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, pragmatisme kerap pula disadari sebagai upaya-upaya penyelidikan eksperimental berdasarkan metode sains modern. Pengalaman menjadi sesuatu yang begitu fundamental dan begitu menentukan. Dalam perkembangannya, pragmatisme ini akan memengaruhi teori-teori pendidikan yang lahir setelahnya, mulai dari progresivisme, rekonstruksionisme, futurisme, serta humanisme pendidikan. Meskipun di antara aliran-aliran itu dua aliran pendidikan, yaitu progresivisme dan humanisme, pengaruh pragmatisme terlihat menggejala sangat kuat. *** Salah satu pemikiran Mead yang kerap menjadi perhatian adalah konsepnya tentang gesture. Dalam hal ini, ia menulis, “Gestures become significant symbols when they implicitly arouse in the individual making them the same responses which the explicitly arouse, or are supposed to arouse, in other individuals.” 26. William James, Pragmatism, (New York: Longmans, Green, 1907), hlm. 54–55. 147 Para pragmatis selalu menolak jika filsafat mereka dikatakan berlandaskan suatu pemikiran metafisik sebagaimana metafisika tradisional yang selalu memandang bahwa dalam hidup ini terdapat sesuatu yang bersifat absolut dan berada di luar jangkauan pengalaman-pengalaman empiris. Dari itu, bagi mereka, seandainya pun realitas adikodrati memang ada, mereka berasumsi bahwa manusia tidak akan mampu mengetahui hal itu. Pemikiran ini menunjuk bahwa epistemologi pragmatisme sepenuhnya berbasis pendekatan empiris: apa yang bisa dirasakan itulah yang benar. Artinya, akal, jiwa, dan materi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, hanya dengan mengalamilah pengetahuan itu dapat dicerap. Pengalaman menjadi parameter ketika sesuatu dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu, para pragmatis tidak nyaris pernah mendasarkan satu hal kebenaran. Menurut mereka, pengalaman yang mereka alami akan berubah jika realitas yang mereka alami pun berubah. Realitas bukanlah sesuatu yang abstrak. Sebaliknya, ia hanya sebuah pengalaman transaksional yang secara konstan akan terus-menerus berubah. Di titik inilah seorang William James kemudian berujar betapa manusia selalu hidup dalam dunia dengan tutup yang terbuka. Pandangan James ini sama dengan Dewey tentang konsep kebenaran. Bagi Dewey, kebenaran tidak lebih hanya opini yang ditakdirkan sebagai sesuatu yang dipandang benar sehingga semua orang pun kemudian berupaya menyelidikinya untuk kemudian meyakini atau menolak otoritasnya. Corak paling kuat dari pragmatisme adalah kuatnya pemikiran tentang konsep kegunaan. Makna kegunaan dalam pragmatisme lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bukan pada hal-hal bersifat metafisik. Maka, dalam pragmatisme, pengetahuan tidak selalu mesti diidentikkan dengan kepercayaan, tetapi kerap menjadi dua hal yang sama sekali terpisah. Kebenaran yang mungkin dianggap perlu dipercayai (to believe) bagi para 148 pragmatis selalu menjadi sesuatu hal bersifat personal atau pribadi dan itu tidak perlu dikabarkan pada publik. Sedangkan, hal-hal yang dianggap perlu diketahui haruslah selalu dikabarkan atau didemonstrasikan pada pengamat yang qualified dan tak berpihak. Kepercayaan memang ada dalam pengetahuan meski banyak pula kepercayaan tidak akan ditemukan siapa pun di banyak pengetahuan. Pandangan-pandangan itu semuannya terangkai oleh konsep kegunaan dan fungsi pragmatis. Oleh karena itu, para pragmatis kerap mengungkapkan betapa apa yang kita mesti ketahui keraplah bukan sesuatu yang mesti kita percayai. Dalam sisi yang lain, sebab konsep kegunaan, apa yang kita percayai tidak selalu menjadi sesuatu hal yang mesti kita ketahui. Sebab, konsep kegunaan dan fungsi kebenaran dalam pragmatisme selalu hadir menjadi relatif dan kasuistik. Sebuah kebenaran yang dipandang benar-benar valid dan berguna, di waktu yang lain bisa menjadi sesuatu hal yang sama sekali mesti dilupakan. Sementara, pandangan aksiologi pragmatisme tentu saja memiliki sisi keterkaitan erat dengan corak epistemologi mereka yang cenderung berbasis empiris serta menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan pengetahuan serta nilai-nilai yang diakibatkannya. Keberadaan konsep kegunaan dan fungsi bagi pragmatisme tidak membuat bahwa nilai-nilai etika menjadi relatif dan batal. Sebaliknya, dipandang bahwa tidak ada konsep etika yang mengikat manusia secara universal. Sementara, dalam pengamatan lebih jauh, prinsip dasar etika pragmatisme selalu didasarkan pada fungsi dan kegunaan yang dalam hal ini didasarkan pada fungsi dasar bagi sosial. Hal ini kerap membuat satu penilaian bahwa etika pragmatisme dipandang memiliki kesamaan dengan konsep “etika tradisional Eropa” meski dalam pragmatisme pembedaan baik buruk dalam makna individu dan kolektif sosial agaknya memiliki pemisahan secara sangat tersadari. Ini sangat berbeda dengan 149 etika tradisional Eropa yang nyaris tidak memiliki pemilahan ruang etis antara ruang-ruang privat dan ruang publik karena semua hal semua hal telah tereksternalisasikan ke dalam ruang publik secara sepenuhnya. 2. Pendidikan Bagi Pragmatisme Tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka berkembang, serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem-problem hidup yang mereka miliki. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman saat ia belajar di luar sekolah. Pelajar menghadapi problem yang menyebabkan lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang reflektif. Di sini kecerdasan disadari akan melahirkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan membawa mereka di dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Selain hal di atas, pendidikan pragmatisme kerap dianggap sebagai pendidikan yang mencanangkan nilai-nilai demokrasi dalam ruang pembelajaran sekolah. Karena pendidikan bukan ruang yang terpisah dari sosial, setiap orang dalam suatu masyarakat juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pendidikan yang ada. Keputusan-keputusan tersebut kemudian mengalami evaluasi berdasarkan situasi-situasi sosial yang ada. Guru, di sini sama sekali berbeda dengan para guru dalam pendidikan tradisional yang otoritatif dan mesti menekankan kepatuhan 150 pada siswa. Dalam pendidikan pragmatisme, guru menjadi pendamping subjek didik yang dipandang jauh lebih memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai problem. Ia menjadi pengarah atau pemandu aktivitas-akitivitas subjek didik di luar hal-hal yang dibutuhkan mereka, dengan pertimbangan-pertimbangan dan pengalaman yang lebih luas. Para guru juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelas pada apa yang ia merasa ia dibutuhkan. Oleh karena itu, pengajaran pragmatisme kerap sangat berbeda dengan pengajaran tradisional yang selalu mesti di ruangan, memiliki kesan begitu formal dan kaku. Pengajaran-pengajaran itu justru sering dilakukan di luar, di alam terbuka, dan berbagai tempat yang memang disukai siswa didik. Metode pengajaran pragmatis sekali lagi selalu menekankan pengalaman sebagai sesuatu yang utama. Oleh karena itu, upaya pengajaran dilakukan selalu menjadi sesuatu yang dekat dengan hidup. Seseorang yang hendak belajar tentang pertanian, misalnya, dalam pendidikan pragmatisme akan dibawa langsung di area tempat kegiatan-kegiatan pertanian dilakukan. Dalam keterlibatan langsung itu, guru akan menjadi pendamping atau pemandu yang sesekali akan menjelaskan dan memberi nasihat bagi para subjek didik. Metode ini populer dengan nama metode eksperimental. *** Sementara, untuk soal kurikulum, menurut Dewey dan kalangan pragmatis lainnya, tidak boleh dibagi dalam bidang materi yang membatasi dan tidak alamiah. Di sini kurikulum dibangun atas dasar unit-unit alamiah, tidak menimbulkan persoalan, serta melahirkan pengalaman yang menekan subjek didik. Materi-materi kurikulum pendidikan pragmatisme meliputi beberapa materi yang juga digunakan dalam pendidikan tradisional. Mulai dari seni, sejarah, hitung, dan membaca. 151 Kebijakan-kebijakan sekolah selalu menjadi kebijakan liberalisme dalam artian mereka tidak pernah khawatir dengan perubahan-perubahan sosial. Bagi mereka, perubahan adalah kenyataan yang hidup tidak mungkin dibendung. Maka, pendidikan mesti mengajarkan pada generasi di dalam mengelola perubahan dengan cara yang sehat. Sekolah di sini tidak perlu mengharuskan subjek didik dengan beban-beban yang tidak produktif, seperti menghafal serta memberikan keharusan-keharusan tertentu yang membuat mereka kehilangan sisi aktifnya sebagai subjek. Dalam banyak hal, pendidikan justru lebih banyak mengajarkan cara belajar sehingga mereka mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan hidup yang terus-menerus menimpa dunia mereka. Di sini kurikulum pendidikan pragmatis lebih banyak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan proses ketimbang muatan materi. E. Filsafat Pendidikan Progresivisme Aliran progresivisme lahir di Amerika, akhir abad 19 menjelang awal abad 20. Mula-mula, istilah ini bersifat sosiologi guna menyebut gerakan sosial politik di Amerika, ketika proses industrialisasi dan urbanisasi menjadi gejala yang begitu masif. Dalam ruang politik, gerakan-gerakan progresivisme ini di antaranya dipelopori dua tokoh, yaitu Robert La Follete27 dan Woodrow Wilson yang 27. Robert La Follette (1855–1925) mulanya bukanlah siapa pun. Di daerah tempat kelahirannya, yaitu Dane County Wisconsin, orang-orang hanya mengenalnya sebagai seorang anak yang lahir dalam keluarga petani kecil yang hidup dalam situasi ekonomi pas-pasan. Situasi hidup yang seperti itu membawa Robert La Follette meski bekerja sebagai buruh untuk kemudian bisa duduk di bangku perkuliahan Universitas Wisconcin 1875. Uniknya, sejak kecil hingga dewasa ia bukan sosok menonjol dalam makna apa pun selain hanya seorang pekerja keras yang tak mengenal lelah. Sebuah psikis yang cukup terpahami sebagai ciri dasar dari seseorang yang lahir dalam keluarga petani kecil. Namun demikian, sesuatu hal terjadi dan membuatnya lahir menjadi diri yang sepenuhnya baru. Pada 1876, 152 sepanjang waktu keduanya terus melakukan upaya-upaya pleasure pada kekuasaan-kekuasaan politik yang dipandang kontraproduktif dengan kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Sementara, di sisi yang lain, gerakan ini berupaya pula menghilangkan monopoli-monopoli ekonomi, termasuk berbagai pengupayaan pada hunian-hunian masyarakat pinggiran. Dari itulah awal mula istilah lahirnya progresivisme . Dalam perkembangannya, istilah ini kemudian digunakan pula dalam ruang pendidikan untuk menyebut aliran pendidikan yang mencoba mengkritisi pendidikan tradisional. Elaborasi mengenai hal ini salah satunya bisa temukan dalam karya Lawrence A. Cremin, dalam karyanya berjudul The Transformation of the School: Progresivism in American Education (1876–1957). John Dewey (1859–1952) adalah satu tokoh yang kerap dipandang menjadi pelopor lahirnya aliran progresivisme. Sementara, Dewey tidak lain adalah filsuf beraliran pragmatisme. Dari itu bisa dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran yang melandasi progresivisme sangat dipengaruhi pemikiran aliran filsafat pragmatisme. Sementara, pemikir lain yang memengaruhi lahirnya progresivisme antara lain Sigmund Freud,28 La Follette bertemu seseorang bernama Robert G. Ingersoll. Pertemuan itu mengubah sepenuhnya diri La Follette. “Ingersoll”, begitu La Follette biasa menyebutnya, adalah pribadi yang tepat bagi seorang pemuda yang sunyi, hidup dalam berbagai keterbatasan, dan terbelenggu pemikirannya. Pertemuannya dengan Ingersoll membuka cakrawala yang selama ini terkungkung oleh banyak hal. Sejak itu, La Follette terlibat dalam kegiatan politik yang selanjutnya membawa dirinya sebagai seorang senator yang dikenal populis. Hal yang memesona dari La Follette adalah ketika ia dan istrinya Belle La Follette, tahun 1909 membuat jurnal mingguan yang dinamainya La Follette. Jurnal mingguan ini menyuarakan ide-ide humanisme modern, mulai dari kesetaraan perempuan dan laki-laki, hak pilih bagi perempuan (www.spartacus.schoolnet.co.uk). 28. Sigmund Freud (1856–1939) lahir di sebuah daerah bernama Moravia. Namun, sepanjang hidupnya, ia tinggal di Wina. Mulanya, Freud adalah seorang yang mendapat gelar sarjana dalam ilmu bidang kedokteran. Karenanya, karier pertama yang ia geluti tidak lain adalah ilmu kedokteran. Kariernya mulai menanjak saat ia memulai penelitian tentang 153 khususnya pemikirannya tentang psikoanalisis serta pemikiran Jean Jacques Rousseau, khususnya pemikiran Rousseau yang tertuang dalam karyanya Emile (1762). Karya tersebut merebut hati kalangan progresif yang menentang campur tangan orang-orang dewasa dalam menetapkan tujuan pendidikan serta kurikulum-kurikulum subjek didik. Maka, munculnya konsep belajar Children Center lebih banyak memiliki kesesuaian dengan pemikiran Rousseau dan Freud ketimbang pemikiran John Dewey. Di Amerika pengembangan-pengembangan teori pendidikan progresivisme mencantumkan nama-nama praktisi pendidikan, seperti Charleton Whasburne, William H. Kilpatrick, Harold Rugg, dan seseorang bernama John L. Childs. Pengembangan ini memiliki pengaruh cukup kuat paling tidak berkisar mulai sejak dekade 1920-an hingga 1950-an. Adapun di tahun-tahun berikutnya ketika pendidikan yang telah mengubah wajah pendidikan Amerika ini mulai mengalami keruntuhan, terutama ketika lembaga organisasi yang menjadi motor penggerak progresif ini mati. Meskipun beberapa kalangan menilai hal itu disebabkan konsep-konsep pendidikan progresif telah diadopsi oleh nyaris seluruh institusi pendidikan di Amerika, dicampur dengan metode-metode lain dalam corak yang eklektif. penggunaan hipnotis untuk mengobati penyakit histeria. Penyelidikan itu menjadi awal kelahiran gagasan-gagasan psikoanalisisnya. Terutama, ketika ia menemukan tanda-tanda trauma pada setiap pasien histeria yang ia tangani. Salahnya, antara lain adalah tidak tersalurkannya emosi. Freud melahirkan beberapa karya yang membuatnya menjadi makin berpengaruh, yaitu The Intepretation of Dreams (1900), The Psychopathology of Erveryday Life (1904). Saat Nazi menduduki Austria, Freud mengungsi ke Inggris hingga meninggal di sana. Sebelum meninggal, ia sempat melahirkan karya-karya baru yang bersifat filosofis, yaitu Totem and Taboo (1913), Civilization and Its Discontens (1929), dan Moses and Monotheism (1939). 154 Sebagaimana kita jelaskan di atas, teori pendidikan progresivisme secara umum dipengaruhi filsafat pragmatisme, khususnya pemikiran yang dilahirkan John Dewey. Itulah ciri khas teori pendidikan ini. Ia tidak pernah menjadi sistem pemikiran yang sistematis dan konsisten, tetapi lebih banyak terpusat pada eksperimentasi-eksperimentasi yang berdasarkan investigasi-investigasi ilmiah sains modern. Hal ini sangat identik dengan pemikiran filsafat Dewey yang memandang betapa pengalaman selalu menjadi hal yang pokok dan utama. Salah satu karya Dewey yang cukup berpengaruh adalah buku berjudul The School and Society (1899). Karya ini pula yang paling banyak menjadi rujukan dalam aliran pendidikan progresivisme . Dewey29 bahkan menyadari bahwa pengalaman adalah sesuatu hal yang pokok, sebagai hasil dari pengaruh timbal balik antara organisme dan lingkungan. Dari itulah, Dewey memandang bahwa kebenaran sebagai opini yang ditakdirkan untuk disepakati dan pada akhirnya semua orang menyelidikinya. Pandangan ini membiarkan penyelidik dalam kegelapan total sehingga untuk membuktikannya ia mesti terlibat dalam mengalami dalam pengalamannya. Hanya saja, meski mereka tidak memiliki konsep pemikiran yang sistematis, kalangan progresif selalu serempak, khususnya dalam menentang penerapan pendidikan tradisional di berbagai instituasi pendidikan. Allan Ornstein, misalnya, membuat kesaksian betapa 29. John Dewey (1859–1952) lahir di Burlinton, Vermont, sebagai seorang pemuda pemalu. Namun demikian, setelah ia selesai menamatkan pendidikannya di University of Vermont, ia menjadi tokoh paling berpengaruh di Amerika. Ia mulanya mengajar sastra klasik, sains, dan matematika untuk waktu yang singkat di sekolah kelas menengah. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya hingga memperoleh gelar doktor di The John Hopkins University. Dari itu, selama sepuluh tahun ia mengajar di Universitas Michigan, sebentar kemudian di University of Minnesota dan selama sepuluh tahun lagi di University of Chicago. Dari situ ia kemudian pada 1904 mengajar di Columbia University hingga tahun 1930 dan menumpahkan pemikiran-pemikirannya pada persoalan praksis pendidikan. 155 kalangan progresif selalu gatal dalam mencerca teknik pendidikan yang di dalamnya menempatkan guru sebagai subjek utama tunggal pendidikan, sedangkan subjek didik sendiri, yaitu para siswa selalu menjadi objek yang dipandang tidak memiliki pengetahuan apa pun. Kalangan progresif juga menentang pola pengajaran yang bertumpu pada metode textbook atau metode pengajaran yang sepenuhnya terproyeksikan ke dalam buku-buku. Hal lain yang ditentang para progresif adalah kebiasaan pendidikan tradisional yang selalu melakukan proses belajar pasif, yaitu subjek didik meski dibebani dengan berbagai informasi-informasi yang harus mereka hafalkan. Penerapan hukuman-hukuman fisik sebagai bentuk pendisiplinan bagi kalangan progresif dinilai tidak tepat, sama tidak tepatnya dengan konvensi pendidikan bahwa proses pengajaran selalu dikesankan mesti dilakukan di dalam ruangan yang membuat setiap subjek didik secara otomatis akan mengalami keterasingan-keterasingan serta terjauhkan dari realitas sosial hidup yang ada. Tahun 1950 sejak runtuhnya kelembagaan yang menjadi motor bagi pengeraknya, kalangan progresif tampak tidak lagi terdengar gaungnya. Pada 1970, muncul gerakan baru yang mencoba mendaur ulang ide gagasan progresif dalam humanisme pendidikan. Mulai dari prinsip pengajaran yang terpusat pada anak, peran guru yang tidak otoritatif, pelibatan subjek didik secara aktif, serta keberlangsungan pengajaran yang sepenuhnya demokratis. Pendaurulangan metode pendidikan progresif oleh humanisme ini agaknya memiliki tekanan tujuan yang berbeda dengan progresivisme di era awal. Hal ini tekait karena di periode itu gerakan pendidikan humanisme tidak hanya menyumberkan diri pada teori pendidikan progresivisme, tetapi juga pada pemikiran eksistensialisme. Oleh karena itu, tekanan-tekanan nilai-nilai eksistensialisme, seperti pencarian makna-makna personal dalam eksistensi manusia terlihat sangat 156 memengaruhi corak dan metode pengajaran diterapkan para kalangan humanis ini. Di ruang ini, pemikiran Abraham Maslow, Arthur Combs, serta Carls Roger mendapatkan apresiasi lebih, terutama terkait dengan pemikiran mereka pada konsep-konsep humanisasi yang hendak dibangun para humanis tersebut. Kerap diungkap bahwa upaya pendidikan tidak lain adalah upaya yang terhumanisasikan secara perorangan guna menuju dan menemukan serta membangun kedirian yang sejatinya. Jika ditilik secara umum, pendidikan humanisme ini memiliki kesamaan yang begitu mirip dengan pendidikan progresivisme . Perbedaannya, humanisme di sini terlihat mendasarkan teori-teori pendidikannya pada aspek-aspek pembelaan subjek diri dari berbagai tindakan-tindakan pendidikan yang oleh mereka dipandang represif dan tidak manusia. Maka, pendidikan humanisme agaknya lebih terarah pada pembebasan psikologi ketika subjek didik tidak terkungkung oleh apa pun, termasuk perasaan-perasaan traumatis sebab tersingkir dalam kompetisi serta takut gagal. Proyeksi-proyeksi tersebut terkait dengan pandangan para humanis di dalam memandang apa dan bagaimana makhluk bernama manusia itu. Bagi mereka, setiap manusia selalu terlahir sebagai diri yang sempurna, pintar, energik, penuh dengan keingintahuan, dan menyukai belajar sehingga mereka tidak perlu diancam, disuap, atau ditekan agar mereka mau belajar. Manusia secara umum, khususnya subjek didik, akan belajar saat situasi pengajaran yang ada memang nyaman dan mambuat mereka benar-benar merasa senang dan nyaman. Sebaliknya, subjek didik tidak akan mau belajar jika mereka merasa bahwa ruang pengajaran yang ada sama sekali tidak menyenangkan dan tidak nyaman. Di sini, para humanis agaknya memandang betapa pendidikan tradisional tak ubahnya ruang penjara yang mencekam dan mengerikan sehingga dalam gerakan pendidikannya, para humanis seakan-akan tengah 157 melakukan pembebasan para narapidana setelah hidup sepanjang tahun dalam pola yang sepenuhnya penuh dengan berbagai kungkungan. Di titik ini, posisi guru sangat berbeda dengan pendidikan tradisional yang selalu otoritatif, akan lebih pada berperan sebagai fasilitator atau orang yang membantu mengantarkan siswa untuk membuat keputusan dan memperoleh apa yang mereka sukai. Dalam ruang pengajaran seperti kelas, para siswa lebih banyak bertindak dengan keinginannya sendiri ketimbang sebagaimana hal yang diinginkan guru. Dalam proses lebih jauh, guru mesti bersikap moderat dan harus mampu menerima berbagai perbedaan-perbedaan. Dalam gerakan pendidikan ini, sekolah-sekolah menjadi ruang yang benar-benar bebas gejala-gejala indoktrinisasi dan praktik-praktik otoritatif. Kurikulum-kurikulum pengajaran di dalamnya bahkan mengalami berbagai penyesuaian dengan tuntutan-tuntutan siswa. Pendeknya, pendidikan berubah menjadi ruang pembebasan anak dalam upaya menuju pribadi-pribadi yang independen dan pemberani serta tangguh dalam menghadapi hidup di dunia modern yang sarat dengan berbagai problem serta senantiasa berjalan dengan situasi labil yang konstan. Di sini, metode pendidikan humanisme menjadi pendidikan yang seratus delapan puluh derajat berlawanan dengan pendidikan tradisional: pengajaran -pengajaran yang ada selalu gagal dalam membangun hubungan-hubungan interpersonal yang hangat, penuh cinta, serta rasa harga diri yang terpuaskan. Sebaliknya, pendidikan humanisme justru diarahkan pada terciptanya hubungan-hubungan interpersonal dalam landasan cinta dan penghargaan atas perbedaan masing-masing diri. Gerakan pendidikan ini melahirkan semangat dan atmosfer yang begitu signifikan bagi perkembangan pendidikan di Amerika. Misalnya, bisa kita temukan dengan munculnya gagasan School without Failurei, yaitu sekolah terbuka tanpa kegagalan. 158 F. Filsafat Pendidikan Esensialisme Esensialisme kerap diungkap sebagai reaksi kedua terhadap progresivisme tahun 1930-an. Dengan alasan yang hampir sama dengan kalangan perenialis, kalangan esensialis menilai praktik progresivisme telah melahirkan pendidikan yang gagal, terutama karena upaya progresivisme di dalam menjadikan pendidikan sebagai usaha belajar tanpa penderitaan. Hal itu membuat manusia menjadi makin tumpul dan dangkal. Meski para esensialis juga kurang sependapat dengan perenialisme yang dipandang cenderung aristokratis dan antidemokrasi. Sebagai aliran yang berbeda dengan kontra-progresivisme , esensialisme tentu saja berbeda dengan progresivisme. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar pijakan mereka pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Sementara, istilah “esensi” oleh para esensialis diartikan sebagai ciri tetap yang ada pada setiap sesuatu yang ada. Ia adalah sesuatu yang bersifat konstan, tidak bisa berubah, kekal, dan akan selalu abadi. Pandangan ini banyak mendapat kritik dari para eksistensialis, mulai dari Nietzsche, Sartre, dan terutama sekali Stimer. Meski jika kita lacak, embrio dasar pemikiran Aristoteles memaknai esensi sebagai kata yang memiliki kedekatan makna dengan morphe yang berarti bentuk. Ada pula yang menyamakan dengan kata hyle atau model, rencana, dan ide dasar. Sementara, Karl Popper memaknai esensi sebagai lawan dari kata nominal. 159 Oleh karena itu, baginya esensialisme adalah sisi lain dari nominalisme. Dalam hal ini, Karl Popper tidak sepakat jika esensialisme dianggap sebagai lawan dari realisme. Baginya, realisme adalah sisi lain idealisme. Sementara, esensialisme dalam arti luas selalu menjadi filsafat yang mengakui keunggulan zat. Pandangan ini berbeda dengan eksistensialisme yang menyatakan “menjadi (to be)” sebagai realitas mendasar. Dalam prinsipnya, esensialisme selalu menjadi filsafat yang memang berbeda dengan perenialisme. Dasar filosofi esensialisme terutama memandang bahwa setiap jenis tertentu tidak lain adalah entitas yang memiliki seperangkat karakteristik dan sifat yang bersifat (given) atau terberikan sejak keberadaannya yang pertama kalinya. Di sini para esensialis selalu memandang bahwa segala sesuatu selalu dapat dijelaskan dengan tepat. Esensialisme selalu identik dengan generalisasi yang begitu sangat berlebih. Ini bisa dicontohkan dengan pemikiran mereka tentang manusia, bahwa sebagian sifat-sifat tertentu manusia selalu bersifat universal dan dimiliki oleh manusia lainnya tanpa dipengaruhi oleh konteks. Esensi adalah entitas dasar, bukan keberadaan yang “mengada”. Para penganut esensialis selalu meyakini bahwa esensi selalu sesuatu hal mendahului keberadaan. Pandangan itu mereka analogikakan dengan mengatakan bahwa jauh sebelum kita membuat pertanyaan tentang apa itu (latin: quit sit)? Adakah itu (an sit)? Pertanyaan pertama apakah itu pasti selalu menjadi pertanyaan yang mengarah pada esensi atau tentang keapaan (whatness). Para esensialis memandang bahwa seseorang mungkin telah bisa lahir sebagai individu yang sepenuhnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya sehingga ia menjadi diri yang terpisah. Akan tetapi, hal itu tidak membuat mereka menjadi bukan bagian dari sosial karena esensinya setiap individu selalu menjadi makhluk 160 sosial. Esensialisme memandang bahwa dunia dan kehidupan ini selalu berlangsung dalam kesempurnaan. Menurut mereka, jika terdapat kesempurnaan, hal itu selalu disebabkan keterbatasan cara pandang manusia dalam memahami dunia dan kehidupan ini. Esensialisme didukung oleh idealisme modern yang mempunyai pandangan yang sistematis mengenai alam semesta tempat manusia berada. Pandangan ini didukung aliran idealisme subjektif yang berpendapat bahwa alam semesta itu pada hakikatnya adalah jiwa atau spirit, sedangkan segala sesuatu yang ada selalu nyata dalam makna spiritual. Hal ini bertentangan dengan realisme yang justru berpendapat bahwa kualitas nilai selalu ditentukan pada apa dan bagaimana keadaannya, termasuk apa, siapa, dan bagaimana kualitas subjek yang mengalaminya. *** Esensialisme, sebagai filsafat hidup, memulai tinjauannya mengenai pribadi individu dengan menitikberatkan pada “aku”. Menurut idealisme, bila seorang itu belajar pada taraf permulaan, ia memahami “akunya” sendiri, terus bergerak keluar untuk memahami dunia objektif. Dari mikrokosmos menuju ke makrokosmos. Belajar dapat didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang sebagai substansi spiritual. Jiwa membina dan menciptakan diri. Esensialisme memandang kurikulum hendaklah berpangkal pada landasan ideal dan organisasi yang kuat. Menurut para penganut esensialisme, tugas pendidikan tidak lain adalah mengajarkan pengetahuan dasar dan keterampilan-keterampilan dasar yang berkaitan dengan pemerolehan materi dalam hidup. Dalam praktiknya, para esensialisme cenderung menekankan sesuatu yang dikenal 3 R; mulai dari reading, writing, dan arithmetic (membaca, menulis, dan berhitung). Tiga hal ini dipandang sebagai pengetahuan dasar yang begitu ditekankan dalam esensialisme. 161 Dalam esensialisme, biasanya akan diajarkan beberapa mata pelajaran yang diatur mirip dengan Membaca, Menulis, Sastra, Bahasa Asing, Sejarah, Matematika, Sains, Seni, dan Musik. Peran guru di kalangan esensialis sangat berbeda dengan di kalangan progresif yang sama sekali tidak otoritatif bahkan hanya menjadi fasilitator, sebaliknya berupaya untuk kembali menjadi menjadi otoritatif. Oleh karena itu, sikap-sikap yang ditanamkan adalah menanamkan rasa hormat terhadap otoritas, ketekunan, tugas, pertimbangan, dan kepraktisan. Esensialisme berupaya untuk mengajar siswa dengan berbagai pengetahuan sejarah melalui mata kuliah inti dalam disiplin akademis tradisional. Esensialisme juga bermaksud menanamkan pengetahuan akademis, patriotisme, dan pengembangan karakter. Pendekatan tradisional ini dimaksudkan untuk melatih pikiran, mempromosikan penalaran, dan menjamin budaya umum. George Wilhelm Friedrich Hegel30 (1770–1831) mengemukakan adanya sintesis antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesis dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menentukan adanya kualitas tertentu. 30. George Wilhelm Friedrich Hegel (27 Agustus 1770–14 November 1831) lahir di Stuttgart, dalam lingkungan keluarga yang begitu peduli dengan pengetahuan. Oleh karena itu, di usianya yang begitu dini, Hegel telah memiliki tradisi literanik yang kuat, mulai dari surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan dalam topik lainnya. Kelak, ia akan dikenal sebagai filsuf yang identik dengan metode dialektika. Sesuatu yang dalam pandangannya berada dalam situasi antara setuju dan tidak setuju, konsesi dan negasi. Namun demikian, negasi itu bagi Hegel adalah konsesi dalam pengertian yang lain. Hegel dikenal pula sebagai filsuf idealis yang berpengaruh, di antara nama-nama filsuf yang terpengaruhi pemikiran Hegel antara lain adalah Karl Marx, Sartre, Hans Kung, Bruno Bauer, dan Max Stimer. 162 Salah satu tokoh seorang esensialis yang cukup berpengaruh adalah William Bagley (1874–1946). Bagley memandang bahwa esensialisme selalu terkait dengan budaya gerakan literasi, yang oleh para esensialis dipandang sebagai nilai-nilai kebudayaan penting yang membawa manusia menjadi beradab. G. Filsafat Pendidikan Perenialisme Meski pemikiran-pemikiran teori pendidikan perenialisme telah muncul jauh di periode pertengahan, pengakuan secara resmi mengenai teori-teori pendidikan yang dihasilkan filsafat pendidikan perenialisme baru berlangsung sekitar tahun 1930-an. Terutama, ketika filsafat ini hadir sebagai bentuk reaksi keras terhadap kalangan progresif, yang dinilai telah membuat pendidikan menjadi semakin jauh dari visi hidup yang sebenarnya. Istilah “perenialisme” berasal dari bahasa latin, yaitu dari akar kata perenis atau perenial (bahasa Inggris) yang berarti tumbuh terus melalui waktu, hidup terus dari waktu ke waktu atau abadi. Maka, pandangan selalu memercayai mengenai adanya nilai-nilai, norma-norma yang bersifat abadi dalam kehidupan ini. Atas dasar itu, perenialis memandang pola perkembangan kebudayaan sepanjang zaman adalah sebagai pengulangan dari apa yang ada sebelumnya sehingga perenialisme sering disebut sebagai dengan istilah “tradisionalisme”. Perenialisme lahir sebagai suatu reaksi dan solusi terhadap pendidikan progresif dan atas terjadinya suatu keadaan yang mereka sebut sebagai krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perenialis adalah dengan jalan mundur, dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau 163 prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno, dan abad pertengahan. Kaum perenialis melawan kegagalan-kegagalan dan tragedi-tragedi dalam abad modern ini dengan mundur kembali kepada kepercayaankepercayaan yang aksiomatis, yang telah teruji tangguh, baik mengenai hakikat realitas, pengetahuan, maupun nilai, yang telah memberi dasar fundamental bagi abad-abad sebelumnya. Perenialisme mempunyai kesamaan dengan esensialisme dalam hal menentang progresivisme, tetapi penerialisme juga memiliki perbedaan dengan esenialisme antara lain dalam hal prinsip perenialisme yang religius (tyheologis), yang berorientasi pada agama. 1. Pendidikan Perenialisme Kaum perenialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu dan penuh kekacauan, serta membahayakan yang ditimbulkan akibat terjadinya krisis di berbagai dimensi kehidupan manusia (dalam pendidikan khususnya), tidak ada satu pun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan serta kestabilan dalam perilaku pendidik. Dalam pemikiran itu, untuk mengatasi dan mengembalikan keadaan krisis yang terjadi sekarang ini, perenialisme memandang bahwa jalan keluar tidak lain adalah kembali pada kebudayaan masa lampau yang dianggap cukup ideal dan teruji ketangguhannya. Untuk itulah, pendidikan sekarang harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya kepada kebudayaan masa lampau yang ideal serta telah teruji dan tangguh. Dengan kata lain, perenialisme memiliki pandangan yang bertolak (anti-) terhadap modernistik yang telah menjauh dari tradisi (kebiasaan-kebiasaan yang telah teruji ketangguhannya) dan terlalu mengedepankan logika dan rasio modernistik daripada sumber pengetahuan lainnya serta terlalu memandang sesuatu berdasarkan materi (materialistik). 164 Jelaslah jika dikatakan bahwa pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali kepada masa lampau karena dengan mengembalikan keapaan (apa yang ada, apa yang terjadi, serta apa yang menjadi tujuan) pada masa lampau, kebudayaan yang dianggap krisis ini dapat teratasi melalui perenialisme karena ia dapat mengarahkan pusat perhatiannya pada pendidikan zaman dahulu dengan sekarang. 2. Teori Pendidikan Perenialisme Perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perenialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh, baik berupa teori maupun praktik bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Maka, dapat dikatakan bahwa perenialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali, yaitu sebagai suatu proses mengembalikan kebudayaan sekarang (zaman modern atau modernistik) ini terutama pendidikan zaman sekarang ini perlu dikembalikan kebudayaan pada masa lampau. Perenialisme merupakan aliran filsafat yang mendasarkan pada kesatuan, bukan mencerai-beraikan; menemukan persamaan-persamaan, bukan membanding-bandingkan; serta memahami isi, bukan melihat luar atas berbagai aliran dan pemikiran. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa perenialisme merupakan filsafat yang susunannya mempunyai kesatuan. Susunan tersebut merupakan hasil pikiran yang memberikan kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap yang tegas dan lurus. Oleh karena itulah, perenialisme berpendapat bahwa mencari dan menemukan arah tujuan yang jelas merupakan tugas yang utama dari filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Setelah perenialisme menjadi terdesak karena perkembangan politik industri yang cukup berat, timbullah usaha untuk bangkit kembali dan perenialisme berharap agar manusia kini dapat memahami ide dan cita-cita filsafatnya yang menganggap filsafat sebagai suatu asas yang komprehensif. 165 Perenialisme dalam makna filsafat dianggap sebagai satu pandangan hidup yang bcrdasarkan pada sumber kebudayaan dan hasil-hasilnya. Filsafat perenialisme (Philosophia Perenis) memandang bahwa kepercayaan-kepercayaan aksiomatis zaman kuno (tradisi dan kebudayaan masa lampau yang ideal) dan abad pertengahan (berdasarkan penyatuan, penyamaan pemikiran) perlu dijadikan dasar penyusunan konsep filsafat pendidikan zaman sekarang. Sikap ini bukan merupakan nostalgia (rindu akan hal-hal yang sudah lampau semata-mata), melainkan telah berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan-kepercayaan tersebut berguna bagi abad sekarang. Jadi, sikap untuk kembali kemasa lampau itu merupakan konsep bagi perenialisme. Dengan kata lain, ia menganggap pentingnya pembentukan kebiasaan dalam pendidikan sekarang yang didasarkan pada kebiasaan dan kebudayaan pada masa lampau yang memiliki nilai dan idealitas serta berguna. 3. Pandangan Plato Asas-asas filsafat perenialisme bersumber pada filsafat, kebudayaan yang mempunyai dua sayap, yaitu perenialisme yang teologis yang ada dalam pengayoman supremasi gereja Katolik, khususnya menurut ajaran dan interpretasi Thomas Aquinas, dan perenialisme sekular, yaitu yang berpegang kepada ide dan cita-cita filosofis Plato dan Aristoteles. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan H.B. Hamdani Ali dalam bukunya, Filsafat Pendidikan, bahwa Aristoteles sebagai pengembang philosophia perenis, yaitu sejauh mana seseorang dapat menelusuri jalan pemikiran manusia. St. Thomas Aquinas31 telah mengadakan beberapa perubahan sesuai dengan tuntunan agama Kristen tatkala agama itu datang. Kemudian, lahir 31. Filsuf Italia Thomas Aquinas masyhur karena tulisan-tulisan teologinya, khususnya tulisan Summa Theologia-nya yang mungkin mempunyai bobot pernyataan kuasa terbesar dalam 166 apa yang dikenal dengan nama Neo-Thomisme. Tatkala Neo-Thomisme masih dalam bentuk awam maupun dalam paham gerejawi sampai ke tingkat kebijaksanaan, ia terkenal dengan nama perenialisme. Pandangan-pandangan Thomas Aquinas di atas berpengaruh besar dalam lingkungan gereja Katolik. Demikian pula pandangan-pandangan aksiomatis lain seperti yang diutarakan oleh Plato dan Aristoteles. Selain itu, semuanya mendasari konsep filsafat pendidikan perenialisme. Neo-Scholastisisme atau Neo-Thomisme ini berusaha menyesuaikan ajaran-ajaran Thomas Aquinas dengan tuntutan abad kedua puluh. Misalnya, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan cukup dimengerti dan disadari adanya. Namun, semua yang bersendikan empiris dan eksperimentasi hanya dipandang sebagai pengetahuan yang fenomenal. Maka, metafisika mempunyai kedudukan yang lebih penting. Hakikat pengertian manusia ditekankan pada sifat spiritualnya. Simbol sifat ini terletak pada peranan akal yang karenanya, manusia dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran yang fenomenal maupun yang bersendikan religi. Jadi, aliran perenialisme dipakai untuk program pendidikan yang didasarkan atas pokok-pokok aliran Aristoteles dan St. Thomas Aquinas. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ini muncul dari lingkungan agama Katolik atau di luarnya. Dengan kata lain, ia berpandangan bahwa tujuan pendidikan yang utama adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakannya dalam segala aspek kehidupan. Filsafat perenialis memandang pendidikan sebagai proses menuntun kemampuan-kemampuan yang tertidur (bakat terpendam) yang dimiliki doktrin teologi Katolik yang pernah ada. Ia terutama menjadi terkenal karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran Gereja Kristen. Sintesisnya ini termuat dalam karya utamanya, Summa Theologiae (1273). Ia disebut sebagai “Ahli teologi utama orang Kristen”. Bahkan, ia dianggap sebagai orang suci oleh Gereja Katolik dan memiliki gelar santo. 167 seseorang menjadi aktif atau nyata (real, berwujud, aplicated) tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu yang memiliki kemampuan tersebut. Perenialis berpendapat bahwa siswa (murid, anak didik) adalah subjek sekaligus inti dalam pelaksanaan pendidikan, dan guru hanya bertugas menolong membangkitkan potensi yang dimiliki anak didik yang masih tersembunyi agar menjadi aktif dan nyata, bukan membentuk atau memberi kemampuan kepada anak didik. Kaum perenialis juga percaya bahwa dunia alamiah dan hakikat manusia pada dasarnya tetap tidak berubah selama berabad-abad. Jadi, gagasan-gagasan besar terus memiliki potensi yang paling besar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di setiap zaman. Selain itu, filsafat perenialisme juga menekankan kemampuan-kemampuan berpikir rasional (logis, masuk akal) manusia sehingga membedakan dapat menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang-binatang lain. Salah satu kajian teori kependidikan perenialis mencuat sebagai sebuah pemikiran formal (resmi) pada dekade 1930-an sebagai bentuk reaksi terhadap kalangan progresif. Pada saat itu, kalangan perenialis merasakan runyamnya bangunan intelektual kehidupan bangsa karena penekanan di sekolah-sekolah terhadap keterpusatan pada subjek didik, paham kekinian, dan penyesuaian hidup. Perenialisme modern secara umum menampilkan sebuah penolakan besar-besaran terhadap cara pandang progresif. Bagi kalangan perenialis, permanensi (keajegan), meskipun pergolakan-pergolakan politik dan sosial yang sangat menonjol, adalah lebih riil (nyata) daripada konsep perubahan kalangan pragmatis. Dengan demikian, kalangan perenialis memelopori gerakan kembali pada hal-hal absolut dan memfokuskan pada ide-gagasan yang luhur-menyejarah dari budaya manusia. Ide-gagasan semacam ini telah tebukti kebasahan dan kegunaannya karena mampu bertahan dari ujian waktu. 168 Perenialisme menekankan arti penting akal budi, nalar, dan karya-karya besar pemikir masa lalu. Perenialisme adalah pendidikan klasik dan tradisional dalam suatu bentuk yang diperbarui dan lebih spesifik dalam formulasi teoretis karena kemunculannya dilatari oleh “musuh” yang nyata progresivis terhadap pendidikan. Kunci memahami protes kalangan perenialis dalam pendidikan adalah konsep pendidikan liberal. Pendidikan liberal (bebas) dalam tradisi klasik berkisar di seputar kajian yang menjadikan orang-orang (baca: subjek didik) bebas dan manusia sejati sebagai lawan dari pelatihan yang menerima (begitu saja) untuk melakukan tugas-tugas khusus dalam dunia kerja. Perenialis memandang education as cultural regression atau pendidikan sebagai jalan kembali, perjalanan mundur ke belakang, atau proses pengembalian keadaan dan kebudayaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lamapu dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh, dan ideal pada masa kuno juga pada abad pertengahan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai kebenaran yang pasti, absolut, dan abadi yang terdapat dalam kebudayaan masa lampau yang dipandang sebagai kebudayaan ideal tersebut. Selain itu, filsafat perenialis juga berpandangan bahwa ilmu pengetahuan (science, knowledge) merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif yang bersifat analisis. Jadi, dengan berpikir, kebenaran itu akan dapat dihasilkan melalui akal pikiran. Dalam kaitannya dengan pengetahuan filsafat, perenialisme menjadikan kepercayaan sebagai pangkal tolak mengenai kenyataan pengetahuan. Artinya, sesuatu itu ada kesesuaian antara pikir (kepercayaan) dan benda-benda. Sedangkan, yang dimaksud benda adalah hal-hal yang 169 adanya bersendikan atas prinsip keabadian. Oleh karena itu, menurut perenialisme, perlu adanya dalil yang logis, sehingga sulit untuk diubah atau ditolak kebenarannya. Menurut Aristoteles, prinsip-prinsip tersebut dapat dirinci secara garis besar menjadi: a. Principium identitatis, yaitu identitas sesuatu. b. Principium contradiksionis, yaitu hukum kontradiksi (perlawanan, pertentangan). Suatu pernyataan pasti tidak mengandung kebenaran dan kesalahan sekaligus, tetapi hanya mengandung satu kenyataan, yaitu salah atau benar. c. Principium exelusi tertii, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan ketiga dalam satu dalil. Apabila pernyataan atau kebenaran pertama salah, pasti pernyataan kedua benar, sebaliknya apabila pernyataan pertama benar, pernyataan yang berikutnya tidak benar. d. Principium rationis sufisientis, yaitu prinsip yang mengetengahkan jika sesuatu dapat diketahui asal muasalnya, pasti dapat dicari tujuan dan akibatnya. Menurut epistemologi Thomisme, sebagian besarnya berpusat pada pengolahan tenaga logika pada pikiran manusia. Apabila pikiran itu bermula dalam keadaan potensialitas, dia dapat dipergunakan untuk menampilkan tenaganya secara penuh. Jadi, epistemologi perenialisme harus memiliki pengetahuan tentang pengertian dari kebenaran yang sesuai dengan realitas hakiki, yang dibuktikan dengan kebenaran yang ada pada diri sendiri dengan menggunakan tenaga pada logika melalui hukum berpikir metode deduksi. Metode tersebut merupakan metode filsafat yang menghasilkan kebenaran hakiki. Kemudian tujuan dari epistemologi perenialisme dalam premis 170 mayor dan metode induktifnya harus sesuai dengan ontologi tentang realitas khusus. Menurut perenialisme, penguasaan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pertama merupakan modal bagi seseorang untuk mengembangkan pikiran dan kecerdasan. Prinsip-prinsip pertama mampu mempunyai pemahaman sedemikian karena telah memiliki evidensi diri sendiri. Dengan pengetahuan dan bahan penerangan yang cukup, orang akan mampu mengenal faktor-faktor dengan pertautannya masing-masing, kemudian memahami problema yang perlu diselesaikan dan berusaha untuk mengadakan penyelesaian masalahnya. Dengan demikian, ia telah mampu mengembangkan suatu paham. Anak didik yang diharapkan menurut perenialisme adalah anak didik yang mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran tokoh-tokoh besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol dalam bidang-bidang, seperti bahasa dan sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya telah banyak yang mampu memberikan ilmunisasi zaman yang sudah lampau. Dengan mengetahui tulisan yang berupa pikiran dari para ahli yang terkenal tersebut, yang sesuai dengan bidangnya, anak didik akan mempunyai dua keuntungan: di satu sisi mampu mengetahui apa yang terjadi pada masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar, sedangkan di sisi lain mereka mampu memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya-karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan sebagai bahan pertimbangan (referensi) zaman sekarang. Jelaslah bahwa dengan mengetahui dan mengembangkan pemikiran karya-karya buah pikiran para ahli tersebut, anak didik dapat mengetahui bagaimana pemikiran para ahli dalam bidangnya masing-masing dan 171 dapat mengetahui bagaimana peristiwa pada masa lampau sehingga dapat berguna bagi diri mereka dan sebagai bahan pertimbangan pemikiran mereka pada zaman sekarang. Hal inilah yang sesuai dengan aliran filsafat perenialisme. Tugas utama pendidikan adalah mempersiapkan anak didik ke arah kemasakan atau kematangan. Masak dalam arti hidup ranah akalnya. Jadi, akal inilah yang perlu mendapat tuntunan ke arah kemasakan tersebut. Sekolah rendah memberikan pendidikan dan pengetahuan serba-dasar. Dengan pengetahuan tradisional, seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung) anak didik memperoleh dasar penting bagi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sekolah menjadi tempat utama dalam pendidikan yang mempersiapkan anak didik ke arah kemasakan melalui akalnya dengan memberikan pengetahuan. Sedangkan, tugas utama dalam pendidikan adalah di tangan guru-guru, yaitu memberikan pendidikan dan pengajaran (pengetahuan) kepada anak didik. Faktor keberhasilan anak dalam akalnya sangat tergantung kepada guru, dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkan. Adapun mengenai hakikat pendidikan tinggi ini, Robert Hutchkins mengutarakan lebih lanjut bahwa jika pada abad pendidikan, sekarang seharusnya bersendikan filsafat metafisika. Filsafat ini pada dasarnya adalah cinta intelektual dari Tuhan. Di samping itu, dikatakan pula bahwa karena kedudukan sendi-sendi tersebut penting, perguruan tinggi tidak seyogianya bersifat utilistis. Kemudian, Robert Hutchkins mengatakan bahwa oleh karena manusia pada hakikatnya sama, perlulah dikembangkan pendidikan yang sama bagi semua orang, ini disebut pendidikan umum (general education). Melalui kurikulum yang satu serta proses belajar yang mungkin perlu disesuaikan dengan sifat tiap individu, diharapkan tiap individu itu terbentuk atas dasar landasan kejiwaan yang sama. 172 4. Tujuan Pendidikan Perenialisme Bagi perenialis, nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Sekolah pada dasarnya adalah sebuah tatanan artifisial (buatan), yaitu tempat intelek-intelek yang belum matang berkenalan dengan capaian-capaian terbesar manusia. Sekolah, seperti pandangan progresif, bukanlah miniatur masyarakat yang lebih luas. Kehidupan manusia, dalam pengertian utuhnya, dapat dijalani hanya setelah aspek rasional manusia dikembangkan. Sekolah adalah sebuah institusi khusus yang berupaya mencapai misi yang amat penting ini. Sekolah tidak terlalu berkepentingan dengan persoalan semacam pekerjaan, hiburan, dan rekreasi manusia. Ketiga hal tersebut mempunyai tempat dalam kehidupan manusia, tetapi berada di luar lingkup aktivitas pendidikan. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elite intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun ke dalam kehidupan. Sekolah bagi perenialis merupakan peraturan-peraturan yang artifisial tempat peserta didik berkenalan dengan hasil yang paling baik dari warisan sosial budaya. Kurikulum pendidikan bersifat subject centered, berpusat pada materi pelajaran. Materi pelajaran harus bersifat seragam, universal, dan abadi. Selain itu, materi pelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia sebab demikianlah hakikat manusia. Mata pelajaran yang mempunyai status tertinggi adalah mata pelajaran yang mempunyai 173 “rational content” yang lebih besar. Oleh karena itu, titik berat kurikulum diletakkan pada pelajaran sastra, matematika, bahasa, dan humonaria, termasuk sejarah (liberal art). Sedangkan, sumber dan cara mempelajari seni liberal tersebut adalah dengan cara mempelajari The Greats Book. 5. Metode Pendidikan Perenialisme Metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perenialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya yang tertuang dalam The Greats Book dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Peranan guru bukan sebagai perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai “murid” yang mengalami proses belajar sementara mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery. Ia juga melakukan moral authority (otoritas moral) atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang qualified dan superior dibandingkan dengan muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih, dan pengetahuan yang sempurna (Syam, 1984). 6. Pandangan Secara Ontologi Perenialisme Ontologi perenialisme terdiri dari pengertian-pengertian, seperti benda individual, esensi, aksiden, dan substansi. Perenialisme membedakan realitas dalam aspek-aspek perwujudannya dalam tipologi istilah ini. Benda individual di sini adalah benda sebagaimana tampak di hadapan manusia dan dapat ditangkap pancaindra, seperti batu, lembu, rumput, orang dalam bentuk, ukuran, warna, dan aktivitas tertentu, seperti manusia jika ditilik dari esensinya yang tidak lain adalah makhluk berpikir. Adapun aksiden selalu dimaknai sebagai keadaan-keadaan khusus yang berubah-ubah dan dipandang bersifat kurang penting jika dibandingkan dengan esensial, misalnya orang suka bermain sepatu 174 roda atau suka berpakaian bagus, sedangkan substansi adalah kesatuan dari tiap-tiap individu, misalnya partikular dan universal, material, dan spiritual. Dalam pengertian ini, segala yang ada di alam seperti halnya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya, menampakkan hal logis dalam karakternya. Setiap sesuatu yang ada, tidak hanya merupakan padu padan antara zat atau benda, tetapi juga merupakan unsur potensial yang aktual sebagaimana yang diutarakan Aristoteles sekaligus sesuatu yang datang bersama-sama dari sesuatu yang terkandung dalam inti (essence) dan potensialitas ini memungkinkan sesuatu menjadi ada. Uraian di atas sejalan dengan apa yang dikatakan Ir. Poedjawijatna bahwa esensi kenyataan itu adalah menuju ke arah aktualitas sehingga makin lama makin jauh dari patensialitasnya. Jika dihubungkan dengan manusia, setiap waktu manusia selalu bersifat potensial dan berubah menuju aktual. Misalnya, meskipun manusia dalam hidupnya jarang dikuasai oleh sifat eksistensi kemanusiaan, tidak jarang pula dimilikinya akal, perasaan, dan kemauannya, schula ini dapat dikurangi. Hal-hal yang bersifat partikular yang merintangi kehidupan dapat diatasi. Maka, dengan peningkatan suasana hidup spiritual ini, manusia dapat makin mendekatkan diri kepada gerak yang tanpa gerak itu, ialah tujuan dan bentuk terakhir dari segalanya. Dengan demikian, segala yang ada di alam ini terdiri dari materi dan bentuk atau badan dan jiwa yang disebut dengan substansi. Bila dihubungkan dengan manusia, manusia itu adalah patensialitas yang di dalam hidupnya tidak jarang dikuasai oleh sifat eksistensi keduniaan, tidak jarang pula dimilikinya akal, perasaan, dan kemauannya semua ini dapat diatasi. Dengan suasana ini, manusia dapat bergerak untuk menuju tujuan (teleologis) dalam hal ini untuk mendekatkan diri pada supernatural 175 (Tuhan) yang merupakan pencipta manusia dan merupakan tujuan akhir. Dengan keputusan yang bersifat ontologisme ini, kita akan sampai pada pengertian pengertian hakikat. Ontologi perenialisme berisikan pengertian benda individual, esensi, aksiden, dan substansi. a. Benda individual adalah benda yang sebagaimana tampak di hadapan manusia yang dapat ditangkap oleh indra kita, seperti batu, kayu, dan lain-lain. b. Esensi sesuatu adalah suatu kualitas tertentu yang menjadikan benda itu lebih baik intrinsik daripada halnya, misalnya manusia ditinjau dari esensinya adalah berpikir. c. Aksiden adalah keadaan khusus yang dapat berubah-ubah dan sifatnya kurang penting dibandingkan dengan esensialnya, misalnya orang suka barang-barang antik. d. Substansi adalah suatu kesatuan dari tiap-tiap hal individu dari yang khas dan yang universal, yang material dan yang spiritual. e. Menurut Plato, perjalanan suatu benda dalam fisika menerangkan ada empat kausa: • Kausa materialis, yaitu bahan yang menjadi susunan sesuatu benda, misalnya telur, tepung, dan gula untuk roti. • Kausa formalis, yaitu sesuatu dipandang dari formnya, bentuknya, atau modelnya, misalnya bulat, gepeng, dan lain-lain. • Kausa efisien, yaitu gerakan yang digunakan dalam pembuatan sesuatu cepat, lambat, atau tergesa-gesa. • Kausa finalis adalah tujuan atau akhir dari sesuatu, katakanlah tujuan pembuatan sebuah patung. 7. Epistemologis Perenialisme Perenialisme berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan adalah apa yang terlindung pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikiran 176 dan benda-benda. Benda-benda di sini maksudnya adalah hal-hal yang adanya bersendikan prinsip-prinsip keabadian. Ini berarti bahwa perhatian mengenai kebenaran adalah perhatian mengenai esensi dari sesuatu. Kepercayaan terhadap kebenaran itu akan terlindung apabila segala sesuatu dapat diketahui dan nyata. Jelaslah bahwa pengetahuan itu merupakan hal yang sangat penting karena ia merupakan pengolahan akal pikiran yang konsekuen. Menurut perenialisme, filsafat yang tertinggi adalah ilmu metafisika. Sebab sains sebagai ilmu pengetahuan menggunakan metode induktif yang bersifat analisis empiris kebenarannya terbatas, relatif, atau kebenaran probabilitas. Akan tetapi, filsafat dengan metode deduktif bersifat anological analysis, kebenaran yang dihasilkannya bersifat self evidence universal. Ia berjalan dengan hukum-hukum berpikir sendiri yang berpangkal pada hukum pertama, yaitu kesimpulannya bersifat mutlak asasi. Oleh karena itu, menurut perenialisme, perlu adanya dalil-dalil yang logis, nalar sehingga sulit diubah atau ditolak kebenarannya, seperti pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Aristoteles di atas. 8. Aksiologi Perenialisme Perenialisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supernatural, yaitu menerima universal yang abadi. Dengan asas seperti itu, tidak hanya ontologi dan epistemologi yang didasarkan atas prinsip teologi dan supernatural, tetapi juga aksiologi. Khususnya, dalam tingkah laku manusia, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya. Di samping itu, ada pula kecenderungankecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Masalah nilai itu merupakan hal yang utama dalam perenialisme karena berdasarkan pada asas-asas supernatural, yaitu menerima universal yang 177 abadi, khususnya tingkah laku manusia. Jadi, hakikat manusia itu yang pertama-tama adalah pada jiwanya. Oleh karena itulah, hakikat manusia itu juga menentukan hakikat perbuatan-perbuatannya dan persoalan nilai adalah persoalan spiritual. Dalam aksiologi, prinsip pikiran itu bertahan dan tetap berlaku. Secara etika, tindakan itu ialah yang bersesuaian dengan sifat rasional seorang manusia karena manusia itu secara alamiah condong kepada kebaikan. Jadi, manusia sebagai subjek dalam bertingkah laku telah memiliki potensi kebaikan sesuai dengan kodratnya, di samping ada pula kecenderungankecenderungan dan dorongan-dorongan ke arah yang tidak baik. Tindakan yang baik adalah yang bersesuaian dengan sifat rasional (pikiran) manusia. Kodrat wujud manusia yang pertama-tama tecermin dari jiwa dan pikirannya yang disebut dengan kekuatan potensial yang membimbing tindakan manusia menuju pada Tuhan atau menjauhi Tuhan. Dengan kata lain, melakukan kebaikan atau kejahatan, dan kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri pada Tuhan sesudah tingkatan ini baru kehidupan berpikir rasional. Dalam bidang pendidikan, perenialisme sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokohnya, seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Menurut Plato, manusia secara kodrat memiliki tiga potensi, yaitu nafsu, kemauan, dan pikiran. Pendidikan hendaknya berorientasi pada potensi itu dan kepada masyarakat agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat bisa terpenuhi. Dengan demikian, jelaslah bahwa perenialisme itu menghendaki agar pendidikan disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran sebagaimana yang dimiliki secara kodrat. Dengan memerhatikan hal ini, pendidikan yang berorientasi pada potensi dan masyarakat akan dapat terpenuhi. Ide-ide Plato ini kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dengan lebih mendekatkan kepada dunia kenyataan. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. 178 Untuk mencapai pendidikan itu, aspek jasmani, emosi, dan intelek harus dikembangkan secara seimbang. Aristoteles juga mengemukakan, kebajikan dapat dibedakan, yaitu yang moral dan yang intelektual. Kebajikan moral adalah kebajikan yang merupakan pembentukan kebiasaan, yang merupakan dasar dari kebajikan intelektual. Jadi, kebajikan intelektual dibentuk oleh pendidikan dan pengajaran. Kebajikan intelektual didasari oleh pertimbangan dan pengawasan akal. Oleh perenialisme, estetika digolongkan ke dalam filsafat praktis. Kesenian sebagai salah satu sumber kenikmatan keindahan adalah suatu kebajikan intelektual yang bersifat praktis filosofis. Hal ini berarti bahwa di dalam mempersoalkan masalah keindahan harus berakar pada dasar dasar teologis, ketuhanan. Zuhairini Arikunto di sini juga berpendapat dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, betapa tujuan pendidikan yang dikehendaki oleh Thomas Aquinas tidak lain dimaksudkan sebagai usaha mewujudkan kapasitas yang ada dalam individu agar menjadi aktualitas, aktif, dan nyata. Dalam hal ini, peranan guru pada anak didik adalah untuk mengembangkan potensi-potensi dipandang dan menentukan. Simplifikasi yang lain diberikan Robert Hutchkins dengan mengatakan bahwa sebab manusia adalah animal rasionale, pendidikan harus diarahkan guna mengembangkan akal budi agar manusia dapat dapat hidup penuh kebijaksanaan demi kebaikan hidup. Oleh karenanya, tujuan pendidikan di sekolah perlu sejalan dengan pandangan dasar di atas, mempertinggi kemampuan anak untuk memiliki akal sehat. Di sini dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh perenialis bermaksud mewujudkan agar anak didik hidup bahagia demi kebaikan hidupnya. Pengembangan akal diharapkan mampu membekali anak didik dalam mempertinggi kemampuan akal pikirannya. Prinsip ini sangat berpengaruh bagi sistem pendidikan modern, ketika 179 kecerdasan nalar kerap menjadi hal yang begitu mendapat perhatian lebih. 9. Teori Dasar Perenialisme Penganut perenialisme sependapat bahwa latihan dan pembinaan berpikir (mental disiplin) merupakan bagian dari salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar. Oleh karena itu, teori dan program pendidikan pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir dan disiplin. Asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin. Di sini, makna kemerdekaan pendidikan berarti membantu manusia menjadi dirinya, sebagai essensial self yang berbeda dari spesies mana pun. Sementara, fungsi belajar diabdikan guna mendukung aktualitas manusia sebagai makhluk rasional dan indedepen. “Learning to reason” demikian menurut istilah para perenialis. Pendidikan tidak lain adalah belajar dalam berpikir. Perenialisme percaya bahwa asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Berdasarkan penahapan itu, learning to reason menjadi hal pokok pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi. Selain belajar berpikir, pendidikan menurut para perenialis, juga sebagai persiapan hidup. Pandangan ini kerap disandarkan pada pemikiran Thomisme yang menyadari bahwa belajar untuk berpikir dan belajar demi persiapan hidup (dalam masyarakat) adalah dua langkah pada jalan yang sama dalam memperoleh kesempurnaan hidup, baik dunia ataupun surgawi. Kerap dikatakan bahwa pendidikan tidak lain adalah learning through teaching (belajar melalui pengajaran). Adler membedakan antara learning by instruction dan learning by discovery, penyelidikan tanpa bantuan guru. 180 Sebenarnya, learning by instructions menuju learning by discovery digunakan sebagai pembelajaran diri. Menurut perenialisme, tugas guru bukanlah perantara antara dunia dan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar selama mengajar. Guru mengembangkan potensi-potensi self discovery dan ia melakukan moral authority atas murid-muridnya karena ia adalah seorang profesional. Menurut perenialisme, memang kenyataan yang kita hadapi adalah dunia dengan segala isinya. Perenialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu yang dinilai indah haruslah dipandang baik. *** Perenialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad kedua puluh. Perenialisme lahir menjadi suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perenialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh dengan kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultual. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang kukuh, kuat, dan teruji. Beberapa tokoh pendukung gagasan ini antara lain adalah Robert Maynard Hutchins dan Ortimer Adler. Di Amerika, misalnya, penekanan pendidikan pada subjek didik, paham kekinian, dan penyesuaian hidup telah membuat manusia terkendalikan oleh hal-hal yang bersifat pragmatis dan temporal. Hidup kemudian bergerak menjadi patahan-patahan kesadaran yang berlangsung dengan begitu pendek dan singkat. Menurut para perenialis, progresivisme 181 telah membawa manusia pada pola kehidupan dangkal dan bersifat remeh. Manusia semakin jauh dari penghayatan-penghayatan nilai hidup yang subtil dan mendalam. Robert Maynard Hutchins dan Mortimer Adler yang menggulirkan kampanye mereka dari Universitas Chicago, tempat Hutchins menjabat sebagai rektor pada 1929 di usia ketiga puluh tahun. Pada waktu itu, keduanya adalah dosen muda yang aktif dan juga penulis produktif yang berjuang membuat opini publik agar sejalan dengan perenialisme selama lebih dari empat puluh tahun. Hutchins dan Adler telah memberikan pengaruh yang besar bagi kalangan perenialis ketika mereka bekerja mengedit karangan yang dikenal sebagai Great Books of Western World. Kumpulan karangan itu memuat seratus tulisan tentang dunia Barat yang berisi ide-ide pemikiran terbaik. Pemikiran pendidikan ini secara murni diimplementasikan di perguruan tinggi St. John di Annapolis, Marland, ketika Presiden Stringfellow Barr menjadikan karya besar tersebut sebagai referensi utama tingkat sarjana. Perenialisme pada dasarnya berakar pada pemikiran neoskolastik. Oleh karena itu, ia cenderung bersifat aristotelian. Meski di Amerika, perenialisme umumnya dikembangkan dalam pendidikan sekuler, bersamaan ketika pemikiran Thomas Aquinas tereksplorasi secara berlimpah ke dalam berbagai sekolah dan perguruan tinggi. John Maritain termasuk di dalamnya yang kemudian mengembangkan perenialisme dalam konteks khusus pengembangan pendidikan yang bersifat gerejawi. 10. Manusia dalam Perenialisme Dalam perenialisme, manusia adalah hewan rasional. Manusia dipandang memiliki kesamaan-kesamaan tipikal dengan hewan. Mereka suka dengan kesenangan dan juga suka bermain. Hal yang membedakan adalah manusia dalam hal ini memiliki kecerdasan rasional sehingga membuatnya memiliki kehidupan jauh lebih variatif ketimbang binatang 182 yang justru selalu monoton. Dengan kecerdasannya, manusia menjadi spesies yang belajar dan berkembang. *** H. Filsafat Pendidikan Eksistensialisme Eksistensialisme termasuk filsafat pendatang baru. Eksistensialisme32pertama kali dikemukakan oleh ahli filsafat Jerman, Martin Heidegger (1889–1976). Eksistensialisme merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya berasal dari metode fenomologi yang dikembangkan oleh Hussel (1859–1938). Kemunculan eksistensialisme berawal dari ahli filsafat Kieggard dan Nietzche. Kiergaard (1813–1855) menjawab pertanyaan “Bagaimanakah aku menjadi seorang diri?” Kegelisahan-kegelisahan tersebut tentu saja bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang lahir ketika dunia yang mengalami krisis eksistensial, ketika manusia melupakan individualitasnya. Kiergaard adalah satu diri yang berusaha menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut manusia (aku) bisa menjadi individu yang autentik jika memiliki gairah, keterlibatan, dan komitmen pribadi dalam kehidupan. Dari Kiergaard kemudian diteruskan oleh Nitzsche (1844–1900), filsuf Jerman. Pemikiran filsafat Nitzsche terarah pada upaya melahirkan 32. Eksistensi membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya, mampu berada, eksis. Oleh eksistensi, kursi dapat berada di tempat. Pohon mangga dapat tertanam, tumbuh, dan berkembang. Harimau dapat hidup dan merajai hutan. Manusia dapat hidup, bekerja, berbakti, dan membentuk kelompok bersama manusia lain. Selama masih bereksistensi, segala yang ada dapat ada, hidup, tampil, dan hadir. Namun, ketika eksistensi meninggalkannya, segala yang ada menjadi tidak ada, tidak hidup, tidak tampil, dan tidak hadir. Kursi lenyap. Pohon mangga menjadi kayu mangga. Harimau menjadi bangkai. Manusia mati. Demikianlah penting peranan eksistensi. Olehnya, segalanya dapat nyata ada, hidup, tampil, dan berperan. 183 narasi yang bisa menjadi jalan keluar untuk menjawab pertanyaan filosofisnya, yaitu “bagaimana cara menjadi manusia unggul (ubbermench)”. Jawabannya: manusia bisa menjadi unggul jika mempunyai keberanian untuk merealisasikan diri secara jujur dan berani. Sebagai pendatang baru, filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Pendapat materialisme terhadap manusia: manusia merupakan benda dunia, manusia adalah materi, manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Pandangan manusia menurut idealisme: manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Eksistensialisme berkeyakinan situasi manusia selalu berpangkalkan eksistensi sehingga aliran eksistensialisme penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret. Di sini bagi eksistensialisme, individu bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebenarnya, bukannya tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar, tetapi seorang eksistensialis sadar bahwa kebenaran bersifat relatif, karenanya masing-masing individu bebas menentukan sesuatu yang menurutnya benar. Sementara, dalam ruang ontologi , eksistensialisme banyak mempersoalkan makna keber-ada-an manusia yang diyakini mesti dihadirkan lewat kebebasan . Oleh karenanya, pertanyaan utama eksistensialisme nyaris selalu bersinggungan dengan persoalan kebebasan; mulai dari apakah kebebasan itu? Bagaimanakah manusia yang bebas itu? Eksistensialisme menolak mentah-mentah bentuk determinasi terhadap kebebasan kecuali kebebasan tersebut. *** 184 Sementara, di Prancis eksistensialisme dikenal lewat Jean Paul Sartre, dengan diktumnya “human is condemned to be free”. Manusia, demikian menurut Sartre, dikutuk untuk bebas. Dengan kebebasannya itulah, kemudian manusia bertindak. Dalam sisi ini, pertanyaan yang sering muncul sebagai akibat dari adanya kebebasan eksistensialis: sejauh mana kebebasan manusia itu? Atau, sesuatu yang dalam istilah dikenal “orde baru”. Apakah eksistensialisme mengenal kebebasan yang bertanggung jawab? Para penganut eksistensialisme meyakini kebebasan adalah satu-satunya universalitas manusia. Maka, batasan kebebasan setiap individu adalah kebebasan individu lain. Namun, menjadi eksistensialis bukan melulu harus menjadi seorang yang lain-daripada-yang-lain, sebaliknya menjadi sadar betapa keberadaan dunia selalu menjadi sesuatu yang berada di luar kendali manusia. Meski hal itu bukan bukan berarti membuat sesuatu yang unik ataupun yang baru yang menjadi esensi eksistensialisme. Membuat sebuah pilihan atas dasar keinginan sendiri dan sadar akan tanggung jawabnya di masa depan adalah inti eksistensialisme. Sebagai contoh, mau tidak mau kita akan terjun ke berbagai profesi seperti dokter, desainer, insinyur, pebisnis, dan sebagainya, tetapi yang dipersoalkan oleh eksistensialisme: apakah kita menjadi dokter atas keinginan orangtua atau keinginan sendiri. Eksistensialisme memiliki banyak tokoh antara lain Søren Kierkegaard tentunya, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Albert Camus, Martin Heidegger, ada yang mengatakan Friedrich Nietzsche juga, Franz Kafka, Miguel de Unamuno, Fydor Dostoievsky, dan tentu Jean Paul Sartre. Masing-masing tokoh di atas sebenarnya memiliki ide masing-masing tentang eksistensialisme. Maka, mustahil merumuskan suatu gambaran umum tentang eksistensialisme yang mencakup seluruh tokoh di atas. Di beberapa kasus, tokoh yang satu memiliki pangaruh pada tokoh yang 185 lain. Akan tetapi, akan menjadi lebih jelas jika kita melihat pemikiran masing-masing tokoh. Adapun secara umum, eksistensialisme membagi problem filsafat menjadi empat masalah filosofis: eksistensi manusia, bagaimana bereksistensi secara aktif, eksistensi manusia adalah eksistensi yang terbuka dan belum selesai, serta pengalaman eksistensial. Sedangkan, Sartre membagi eksistensialisme ke dalam dua cabang, yaitu eksistensialisme kristiani dan eksistensialisme ateis. Sartre menyatakan diri sebagai seorang eksistensialis ateis. Filsafat eksistensialisme membahas cara pengada-pengada, khususnya manusia. Sesuatu yang oleh Sartre terbagi menjadi dua, yaitu l’etre-ensoi (ada-dalam-diri) dan l’etre-pour-soi (berada-untuk-diri). L’etre-en-soi selalu menjadi keberadaan yang an sich, ada yang bulat, padat, beku, dan tertutup. Entre-en-soi menaati prinsip what it is. Perubahan pada benda yang ada dalam diri itu disebabkan oleh sebab-sebab yang telah ditentukan oleh adanya. Maka, benda etre-en-soi terdeterminasi, tidak bebas, dan perubahannya memuakkan (nauseant). Benda yang berada-dalam diri ada di sana tanpa alasan apa pun, tanpa alasan yang kita berikan padanya. Adapun, l’etre-pour-soi (mengada-untuk-diri) adalah cara ada yang sadar. Satu-satunya makhluk yang mengada secara sadar adalah manusia. Etre-pour-soi tidak memiliki prinsip identitas karena adanya terbuka, dinamis, dan aktif oleh karena kesadarannya. Di sini, manusia mesti bertanggung jawab atas keberadaannya; bahwa “aku” adalah frater, bukan bruder; bahwa “aku” imam tarekat, bukan imam diosesan; bahwa “aku” awam, bukan klerus; bahwa “aku” dosen, bukan mahasiswa; bahwa “aku” mahasiswa, bukan pengamen. Manusia sadar bahwa dia bereksistensi. Dalam membicarakan kesadaran, Sartre membagi menjadi dua, yaitu kesadaran prareflektif dan kesadaran reflektif. Kesadaran 186 prafeflektif adalah kesadaran aktivitas harian. Menurut Sartre, tidak ada “aku” dalam kesadaran prareflektif. Sedangkan, kesadaran adalah kesadaran akan diri. Selama seseorang berkonsentrasi, ia mengalami kesadaran reflektif. Kesadaran ini membuat manusia mampu membayangkan apa yang mungkin terjadi dan apa yang bisa ia lakukan. Misalnya, ketika ia sadar bahwa akan realitas hidupnya menurut Sartre seseorang akan dibawa pada sesuatu yang dinamainya “pusaran kemungkinan”. Di titik inilah kebebasan menurut Sartre menjadi sesuatu hal yang terkutuk. *** Pendeknya, eksistensialisme selalu menjadi pemikiran filsafat yang berupaya untuk agar manusia menjadi dirinya, mengalami individualitasnya. Eksistensi berarti berdiri sebagai diri sendiri. Menurut Heideggard, “Das wesen des daseins liegh in seiner Existenz.” Da-sein tersusun dari dad dan sein. Da berarti di sana, sein berarti berada. Artinya, manusia sadar dengan tempatnya. Menurut Sartre, adanya manusia itu bukanlah etre, melainkan a etre–manusia itu tidak hanya ada, tetapi dia selamanya harus membangun adanya, adanya harus dibentuk dengan tidak henti-hentinya. Menurut Parkay (1998), aliran eksistensialisme terbagi dua sifat, yaitu teistik (bertuhan) dan ateistik. Menurut eksistensialisme, ada dua jenis filsafat tradisional, yaitu filsafat spekulatif dan filsafat skeptif. Filsafat spekulatif menyatakan bahwa pengalaman tidak banyak berpengaruh pada individu. Filsafat skeptif manyatakan bahwa semua pengalaman itu adalah palsu, tidak ada sesuatu yang dapat kita kenal dari realita. Menurut mereka, konsep metafisika adalah sementara. *** 187 1. Ontologi Pendidikan Eksistensialisme Pemikiran filsafat eksistensialisme menyebutkan bahwa manusia memiliki keberadaan yang unik dalam dirinya berbeda antara manusia satu dan manusia lainnya. Dalam hal ini, telaah manusia diarahkan pada individualitas manusia sebagai unit analisisnya, dengan berfokus pada pengalaman-pengalaman individu yang di antaranya. 1. Berkaitan dengan hal-hal esensial atau mendasar yang seharusnya manusia tahu serta menyadari sepenuhnya tentang dunia tempat mereka tinggal dan hidup. 2. Menekankan data fakta dengan kurikulum bercorak vokasional. 3. Konsentrasi studi pada materi-materi dasar tradisional, seperti membaca, menulis, sastra, bahasa asing, matematika, sejarah, sains, seni, dan musik. 4. Pola orientasinya adalah keterampilan dasar menuju keterampilan yang bersifat semakin kompleks. 5. Perhatian pada pendidikan yang bersifat menarik dan efisien. 6. Yakin pada nilai pengetahuan untuk kepentingan pengetahuan. 7. Disiplin mental diperlukan untuk mengkaji informasi mendasar tentang dunia yang dialami. 8. Secara umum, eksistensialisme menekankan pada kreativitas, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realita. Eksistensialisme lebih memerhatikan pemahaman makna dan tujuan hidup manusia ketimbang melakukan pemahaman terhadap kajian-kajian ilmiah dan metafisika tentang alam semesta. Kebebasan individu sebagai milik manusia adalah sesuatu yang paling utama karena individu memiliki sikap hidup, tujuan hidup, dan cara hidup sendiri. Jadi, filsafat pendidikan eksistensialisme adalah filsafat yang memberikan kebebasan kepada setiap 188 individu untuk mendapatkan pendidikan secara autentik yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka. 2. Pendidikan Eksistensialis Eksistensialisme berhubungan erat dengan pendidikan karena pusat pembicaraan eksistensialisme adalah keberadaan manusia, sedangkan pendidikan hanya dilakukan oleh manusia. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialis berusaha memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Di sini anak didik disadari sebagai makhluk rasional dengan pilihan bebas dan tanggung jawab atau pilihan suatu komitmen terhadap pemenuhan tujuan pendidikan. Kurikulum eksistensialis cenderung bersifat liberal, membawa manusia pada kebebasan manusia. Oleh karena itu, di sekolah harus diajarkan pendidikan sosial untuk mengajarkan rasa hormat terhadap kebebasan, serta privasi masing-masing individu. Proses belajar mengajar pengetahuan tidak ditumpahkan, tetapi ditawarkan agar hubungan antara guru dan siswa direalisasikan sebagai suatu dialog. I. Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme Rekonstruksionisme berasal dari kata reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan , aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran ini dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada 1930. Mereka bermaksud membangun masyarakat baru, masyarakat yang dipandang pantas dan adil. 189 Ide gagasan mereka secara meluas dipengaruhi oleh pemikiran progresif Dewey, dan ini menjelaskan mengapa aliran rekonstruksionisme memiliki landasan filsafat pragmatisme. Meskipun mereka banyak terinspirasi pemikiran Theodore Brameld, khususnya dengan beberapa karya filsafat pendidikannya, mulai dari Pattern of Educational Philosophy (1950), Toward a reconstructed Philosophy of Education (1956), dan Education as Power (1965). Pada prinsipnya, rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perenialisme, khususnya keprihatinan mereka pada kehidupan manusia modern. Kedua aliran tersebut memandang jika kehidupan manusia modern adalah zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang terganggu, sakit, penuh kebingungan, serta kesimpangsiuran proses. Menurut pandangan rekonstruksionisme, pendidikan perlu merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang baru, untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerja sama antarumat manusia. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia atau bangsa. Oleh karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat akan membina kembali manusia melalui pendidikan yang tepat atas nilai dan norma yang benar pula demi generasi sekarang dan generasi yang akan datang sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Aliran ini memersepsikan bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang dikuasai oleh golongan tertentu. Nilai-nilai demokrasi yang sungguh bukan hanya teori, melainkan mesti menjadi kenyataan sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi, mampu meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran, serta 190 keamanan masyarakat tanpa membedakan warna ras, suku, nasionalisme, agama (kepercayaan), dan masyarakat yang bersangkutan. 1. Prinsip-Prinsip Rekonstruksionisme Para rekonstruksionis dikenal sebagai pembela dunia yang militan. Gagasan-gagasan mereka selalu menunjukkan kepedulian moral mereka pada situasi kehidupan yang tengah berlangsung. Ini, misalnya bisa kita temukan dengan pandangan dan keprihatian mereka tentang bagaimana situasi hidup manusia modern yang menurut mereka menuju keruntuhan. Hidup, khususnya pendidikan, telah diselenggarakan dengan cara dan pemikiran yang salah. Oleh karenanya, makin hari hidup dan kehidupan bukannya bertambah baik, justru malah bertambah buruk. Dunia bahkan mengalami sesuatu yang mereka sebut dalam situasi krisis yang sekarat. Satu-satunya solusi untuk keluar dari semua itu menurut mereka tidak lain adalah dengan mengubah praktik pendidikan yang ada ke dalam konstruksi-konstruksi baru. Pandangan rekonstruksionis memang memiliki banyak pemerian. Mulai dari persoalan kependudukan. Semakin menipisnya sumber daya alam, meningkatnya kesenjangan-kesenjangan global, baik secara teknologi ataupun kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme, terorisme, nasionalisme sempit, serta berbagai perilaku amoral, jelas mengancam kehidupan manusia dalam pengertian apa pun. Persoalan-persoalan yang mengerikan tersebut makin hari bukannya makin tersembuhkan atau makin berkurang, sebaliknya justru makin meningkat, baik dalam persentase kuantitatif ataupun dalam persentase kualitatif sehingga melahirkan sesuatu yang mereka sebut sebagai totalitarianisme modern, yaitu situasi ketika nilai-nilai kemanusiaan dalam sosial secara meluas hilang. Pendeknya, dunia berada di tengah kebangkrutan mengerikan. 191 Dalam ruang inilah, pada 1970-an seorang Alvin Toffler dalam merespons ledakan pengetahuan serta teknologi yang begitu sangat cepat, mengemukakan dimensi teori pendidikan baru dalam karyanya: Future Shock. Alvin Toffler merupakan salah seorang futuris yang mencoba memberikan suatu penjelasan mengenai konsep manusia di masa datang. Konsep pemikiran Alvin Toffler ini diawali dari artikelnya yang merupakan karya monumental yang dirumuskan dengan istilah “future shock (kejutan masa depan)”. Artikel ini melukiskan tentang tekanan dan disorientasi hebat yang dialami oleh manusia jika terlampau banyak dibebani perubahan dalam waktu terlampau singkat. Jelasnya, kejutan masa depan bukan lagi merupakan bahaya potensial yang masih jauh, melainkan merupakan penyakit nyata yang diderita oleh semakin banyaknya manusia. Kondisi psikologis-biologis ini dapat digambarkan dengan terminologi medis dan psikiatri. Penyakit ini ialah penyakit perubahan. Hal ini membawa kita pada sebuah kesadaran reflektif. Dalam karya tersebut, Toffler menulis, “Apa sebenarnya yang dilakukan pendidikan hari ini, tidak lain adalah anakronisme tanpa harapan.” Pendidikan berjalan hanya menjadi serangkaian praktik dan asumsi yang dikembangkan hanya melayani era industri, sedangkan situasi sosial telah memasuki periode superindustri. Akibatnya, sekolah-sekolah kita limbung. Di satu sisi mereka terus dihadapkan pada satu kenyataan bahwa masa adalah hal yang tidak mungkin untuk ditinggalkan, sedangkan di sisi yang lain, hidup telah bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, berubah dan terus berubah. Di sini hitungan lima menit tidak lagi menjadi waktu yang pendek, sebaliknya telah menjadi waktu yang begitu panjang, ketika sebuah ingatan dan kesadaran luruh karena cepatnya gerak perubahan hidup yang ada. 192 Sekolah-sekolah kita lebih sibuk mengurusi sistem yang mati daripada menangani masyarakat baru yang sedang tumbuh. Energi besarnya dipergunakan untuk mencetak manusia industrial, yaitu manusia yang disiapkan untuk bisa hidup dalam sistem yang akan mati sebelum mereka eksis. Untuk membantu mencegah kegagapan masa depan yang akan datang, kita harus menciptakan sebuah sistem pendidikan superindustrial. Maka dari itu, kita harus mencari tujuan-tujuan pendidikan dan metode-metode di masa akan datang, bukan justru di masa lalu (Toffler, 1970:353). George Knight melihat betapa Toffler menegaskan perlunya sistem pendidikan yang mampu melahirkan harapan akan hidup di masa depan sehingga peserta didik dan guru mesti mengarahkan perhatian mereka bukan pada kenyataan hari ini, sebaliknya pada nilai-nilai dan tujuan-tujuan masa depan yang hendak diraihnya. Di sini pendidikan perlu mengkaji secara serius berbagai modal sosial, potensi, dan resistensi mereka serta mampu mengembangkan konsep-konsep terpadu yang memungkinkan mereka melahirkan sistem pendidikan masa depan. Gagasan Toffler di sini banyak menginspirasi para rekonstruksionis. Meskipun ia lebih kerap dikategorikan bukan sebagai seorang rekonstruksionis, sebaliknya hanya seorang futuris. Dalam perbedaan itulah, Toffler tidak pernah memiliki keyakinan yang sama dengan para rekonstruksionis, terutama dalam optimismenya pada pendidikan. Ini sangat berbeda dengan rekonstruksionis yang selalu meyakini bahwa perubahan bisa dimulai dari pendidikan. Toffler justru memandang betapa pendidikan hanya memberikan bekal pada masyarakat dunia untuk merespons perubahan-perubahan hidup yang ada sehingga mereka bisa membuat pilihan-pilihan hidup yang cerdas. Dalam pemikiran ini, para futuris banyak melakukan berbagai pengkajian akan situasi sosial yang ada; mulai dari tatanan ekonomi, 193 politik, sosial, hingga hal-hal yang secara dekat bersinggungan dengan persoalan pendidikan. J. Filsafat Pendidikan Behaviorisme Behaviorisme atau aliran perilaku (juga disebut ‘perspektif belajar’) adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, atau perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstrak hipotetis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tetapi tidak ada perbedaan antara proses yang dapat diamati secara publik (seperti tindakan) dan proses yang diamati secara pribadi (seperti pikiran dan perasaan). Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responsnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respons atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku semakin kuat jika diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Tidak jauh dari empirisme radikal James, psikologi sebagai sains yang baru lahir juga diwakili oleh behaviorisme, diilhami “anjing Pavlov”-nya yang terkenal: eksperimen Ivan Pavlov yang mengganti stimulus daging 194 dengan bunyi lonceng sehingga ketika mendengar bunyi bel, anjing langsung meneteskan liur. Di Amerika, pelopornya adalah Burrhis Skinner, tokoh empirisme radikal, istilah yang tolong jangan dikacaukan dengan empirisme Inggris karena pandangan psikologis ini lebih berarti keutamaan pembelajaran atau pengondisian di atas elemen bawaan. Jika fokusnya perilaku, kita dapat menemukan behaviorisme radikal, tidak sekadar behaviorisme metodologis. Hal yang terakhir ini menyebutkan bahwa sumber informasi yang berharga secara saintifik hanya perilaku. Lewat fatalisme Skinner, behaviorisme mendasarkan ontologisnya pada pandangan bahwa tidak ada sama sekali keadaan mental, yang ada hanya perilaku. Mentalis, misalnya, seorang psikolog sosial, bisa memakai metode behavioral karena hanya menginginkan respons jawaban dari stimulus pertanyaan kuesioner, dan keadaan mental masih ada, tetapi dianggap tidak bisa diakses. Skinner memandang bahwa berupaya memahami di balik kulit adalah sesuatu hal yang sia-sia belaka. Hal yang diubah dari rumus lama Anton Pavlov hanyalah menggeser classical conditioning menjadi operant conditioning—dari satu stimulus tertentu menghasilkan satu respons secara proporsional atau linear, menjadi satu atau lebih stimulus, dan menghasilkan satu atau lebih respons dengan perbedaan derajat. Psikologi seperti ini kerap disebut dengan istilah “kotak hitam” karena dibangun dengan anggapan: percuma, buang waktu, dan dijamin tidak maju-maju jika ada yang mencoba membuka kotaknya. Jadi, lebih baik mengamati apa yang keluar dan masuk kotak. Kotak hitam ini menjadi teori standar hingga pertengahan abad 20, yakin bahwa orang tidak perlu memperhitungkan aktivitas atau keadaan mental sama sekali. Akan tetapi, suatu ketika, seorang behavioris Edward Tolman, menemukan bahwa tikus yang disuruh mencari jalan keluar pada sebuah maze tidak sekadar memakai stimulus-respons untuk navigasi. Tikus 195 Tolman ternyata memakai semacam representasi mental yang kompleks, semacam peta kognitif untuk mencari pintu keluar ketika tikus ditaruh di tempat yang baru dalam maze. Pada dekade 1970-an, ketika sains kognitif mulai membuka diri pada neurosains, peta kognitif tikus Tolman ditemukan oleh O’Keefe dan Dostrovsky. Caranya, dengan mengukur aksi potensial neuron di hipokampus tikus. Ada kelompok sel yang ternyata hanya teraktivasi bila tikus sedang berada di lokasi tertentu di maze. Bukan berarti hipokampus adalah lokasi peta kognitif untuk navigasi spasial (interpretasi semacam ini biasa disebut ‘teori identitas tipe’), melainkan yang bisa secara aman disimpulkan, otak ikut berperan, dan bagian bawah kulit menjadi penting dalam membangkitkan perilaku. Itu yang terjadi pada seekor tikus. Nah! Apalagi manusia! Behaviorisme dengan usulan radikalnya seperti perilaku verbal Skinner yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa manusia, mulai terasa tidak memadai, bahkan naif. “Makna” yang dijelaskan James dengan empirisme radikal memerlukan ruang penjelasan baru. Ruang ini berbentuk representasi mental yang pada perkembangan selanjutnya akan menentukan bentuk arsitektur kognitif suatu organisme, termasuk pada homo sapiens. Belajar merupakan akibat interaksi antara stimulus dan respons (Slavin, 2000:143). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pemelajar, sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pemelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa yang 196 diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pemelajar (respons) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan (positive reinforcement), respons akan semakin kuat. Begitu pula, bila respons dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement), respons juga semakin kuat. Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik: (1) Reinforcement and Punishment; (2) Primary and Secondary Reinforcement; (3) Schedules of Reinforcement; (4) Contingency Management; (5) Stimulus Control in Operant Learning; dan (6) The Elimination of Responses. Tokoh-tokoh aliran behavioristik di antaranya adalah Thorndike, Watson, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Berikut akan dibahas karya-karya para tokoh aliran behavioristik dan analisis serta peranannya dalam pembelajaran. 1. Teori Belajar Clark Hull Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respons untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun, dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis (drive) dan pemuasan kebutuhan biologis (drive reduction) penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia sehingga stimulus (dorongan) dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis walaupun respons yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah 197 laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. 2. Teori Belajar Edwin Guthrie Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum kontiguitas, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan, pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama (Bell dan Gredler, 1991). Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respons untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respons lain yang dapat terjadi. Penguatan sekadar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang, dengan jalan mencegah perolehan respons yang baru. Hubungan antara stimulus dan respons bersifat sementara karena dalam kegiatan belajar peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respons bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman (punishment) memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Saran utama teori ini: guru harus dapat mengasosiasi stimulusrespons secara tepat. Pemelajar harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajari. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. 3. Teori Belajar Skinner Seperti halnya kelompok penganut psikologi modern, Skinner mengadakan pendekatan behavioristik untuk menerangkan tingkah laku. Pada 1938, Skinner menerbitkan bukunya yang berjudul The Behavior of Organism. Dalam perkembangan psikologi belajar, ia mengemukakan teori operant conditioning. Buku itu menjadi inspirasi diadakannya konferensi 198 tahunan yang dimulai tahun 1946 dalam masalah The Experimental an Analysis of Behavior. Hasil konferensi dimuat dalam jurnal berjudul Journal of the Experimental Behaviors yang disponsori oleh Asosiasi Psikologi di Amerika. B.F. Skinner33 berkebangsaan Amerika. Ia dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Dengan proses ini, seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksanaannya jauh lebih fleksibel daripada pengondisian klasik. Gaya mengajar guru dilakukan dengan beberapa pengantar dari guru secara searah dan dikontrol melalui pengulangan dan latihan. Manajemen Kelas menurut Skinner merupakan usaha memodifikasi perilaku antara lain dengan proses penguatan, yaitu memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberi imbalan apa pun pada perilaku yanag tidak tepat. Operant conditioning adalah suatu proses perilaku operant ( penguatan positif atau negatif ) yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari percobaan yang dilakukannya. Di laboratorium, Skinner memasukkan tikus yang telah dibuat lapar dalam kotak yang disebut skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan: tombol, alat pemberi makanan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yanga dapat dialir listrik. Karena dorongan rasa lapar, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari 33. Burrhus Frederic Skinner lahir 20 Maret 1904, di kota kecil Pennsylvania Susquehanna. Ayahnya adalah seorang pengacara dan ibunya yang kuat dan cerdas adalah seorang ibu rumah tangga. 199 box, tidak sengaja tikus menekan tombol, makanan pun keluar. Secara terjadwal, tikus diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut shaping. Berdasarkan berbagai percobaannya pada tikus dan burung merpati, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respons akan semakin kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang proses belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sesederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respons yang diterima seseorang tidak sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antarstimulus itu akan memengaruhi respons yang dihasilkan. Respons yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang nantinya memengaruhi munculnya perilaku (Slavin, 2000). Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang secara benar, harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat respons tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan- 200 perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku, hanya akan menambah rumitnya masalah. Sebab, setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku, ketika reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pemelajar dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian, bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Pandangan teori behavioristik telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun, dari semua teori yang ada, teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Program-program pembelajaran, seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement), merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang dikemukakan Skinner. Teori behavioristik banyak dikritik karena sering tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan/atau belajar yang dapat diubah menjadi sekadar hubungan stimulus-respons. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respons. Pandangan behavioristik juga kurang dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi pemelajar walaupun mereka memiliki pengalaman penguatan yang sama. Pandangan ini tidak dapat menjelaskan mengapa dua anak yang mempunyai kemampuan dan pengalaman penguatan yang relatif sama, ternyata perilakunya terhadap suatu pelajaran berbeda, juga 201 dalam memilih tugas sangat berbeda tingkat kesulitannya. Pandangan behavioristik hanya mengakui adanya stimulus dan respons yang dapat diamati. Mereka tidak memerhatikan adanya pengaruh pikiran atau perasaan yang mempertemukan unsur-unsur yang diamati tersebut. Teori behavioristik juga cenderung mengarahkan pemelajar untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pemelajar menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal, banyak faktor yang memengaruhi proses belajar. Proses belajar tidak sekadar pembentukan atau shaping. Skinner dan tokoh-tokoh lain pendukung teori behavioristik memang tidak menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan pembelajaran. Namun, apa yang mereka sebut dengan penguat negatif (negative reinforcement) cenderung membatasi pemelajar untuk berpikir dan berimajinasi. Menurut Guthrie, hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Namun, ada beberapa alasan mengapa Skinner tidak sependapat dengan Guthrie, yaitu pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi (menjadi bagian dari jiwa si terhukum) bila hukuman berlangsung lama. Hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain (meskipun salah dan buruk) agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadang lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Skinner lebih percaya kepada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Penguat negatif tidak sama dengan hukuman. Ketidaksamaannya terletak pada bila hukuman harus diberikan (sebagai stimulus) agar respons yang muncul berbeda dengan respons yang sudah ada, sedangkan penguat 202 negatif (sebagai stimulus) harus dikurangi agar respons yang sama menjadi semakin kuat. Misalnya, seorang pemelajar perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Jika pemelajar tersebut masih saja melakukan kesalahan, hukuman harus ditambahkan. Akan tetapi, jika sesuatu tidak mengenakkan pemelajar (sehingga ia melakukan kesalahan) dikurangi (bukan malah ditambah) dan pengurangan ini mendorong pemelajar untuk memperbaiki kesalahannya, inilah yang disebut penguatan negatif. Lawan penguatan negatif adalah penguatan positif (positive reinforcement). Keduanya bertujuan untuk memperkuat respons. Namun, bedanya adalah penguat positif menambah, sedangkan penguat negatif adalah mengurangi agar memperkuat respons. 4. Teori Belajar Ivan Pavlov Ivan Petrovich Pavlov (14 September 1849–27 Februari 1936) dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia tengah. Pada mulanya, ia adalah seorang fisiolog, psikolog, dan dokter Rusia. Padahal, keluarganya mengharapkannya menjadi pendeta. Ia bersekolah di Seminari Teologi dan membaca Charles Darwin, yang membuatnya menyadari bahwa ia lebih cocok hidup dalam ruang ilmiah ketimbang agama. Oleh karena itu, ia pun meninggalkan seminari ke Universitas St. Petersburg. Di sana, pada 1879, ia belajar kimia dan fisiologi, dan menerima gelar doktor. Sejak itu, ia kemudian melanjutkan studinya dan memulai risetnya dalam topik yang menariknya: sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Reputasi Pavlov memiliki bermula dari studinya dalam soal pencernaan. Ia mencari proses pencernaan pada anjing, khususnya keterkaitan antara air ludah dan kerja perut. Ia berpikir bahwa kedua hal 203 itu saling berkaitan erat dengan refleks dalam sistem saraf otonom. Tanpa air liur, perut tidak membawa pesan untuk memulai pencernaan. Pavlov menemukan bahwa rangsangan luar dapat memengaruhi proses ini. Maka, ia membunyikan metronom dan di saat yang sama, ia mengadakan percobaan makanan anjing. Setelah beberapa saat, anjing itu—yang hanya sebelum mengeluarkan liur saat mereka melihat dan memakan makanannya—akan mulai mengeluarkan air liur saat metronom itu bersuara, malahan jika tiada makanan ada. Pada 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimennya dan menyebutnya sebagai “refleks terkondisi”, berbeda dari refleks halus. Pavlov menyebut proses pembelajaran ini (sebagai contoh, saat sistem saraf anjing menghubungkan suara metronom dengan makanan) dengan “pengondisian”. Ia juga menemukan bahwa refleks terkondisi akan tertekan bila rangsangan ternyata terlalu sering “salah”. Jika metronom bersuara berulang-ulang dan tidak ada makanan, anjing akan berhenti mengeluarkan ludah. Pavlov lebih tertarik pada fisiologi ketimbang psikologi. Ia melihat pada ilmu psikiatri yang masih baru saat itu sedikit meragukan. Namun, ia sungguh-sungguh berpikir bahwa refleks terkondisi dapat menjelaskan perilaku orang gila. Sebagai contoh, ia mengusulkan jika mereka yang menarik diri dari dunia bisa menghubungkan semua rangsangan dengan luka atau ancaman yang mungkin. Gagasannya memainkan peran besar dalam teori psikologi behavioris. Teori ini diperkenalkan oleh John Watson sekitar 1913. Pavlov amat dihormati di negerinya—baik di Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet—dan di seluruh dunia. Pada 1904, ia memenangkan Penghargaan Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran dalam penelitiannya tentang pencernaan. Ia adalah orang yang terang-terangan dan sering bersilang pendapat dengan pemerintah Soviet dalam hidupnya. Namun, karena reputasinya, dan juga karena bangganya penduduk negeri 204 kepadanya, membuatnya terjaga dari penganiayaan. Ia aktif bekerja di laboratorium sampai kematiannya dalam usia 86. 5. Teori Belajar Edward Lee Thorndike Edward Lee Thorndike pada mulanya seorang fungsionalis. Namun, ketertarikannya pada persoalan riset ilmiah membawanya menjadi pelopor tahapan behaviorisme Rusia dalam versi Amerika. Thorndike (1874–1949) mendapat gelar sarjananya dari Wesleyan University di Connecticut pada 1895, dan gelar master dari Harvard pada 1897. Ketika di sana, dia mengikuti kelas Williams James dan mereka pun cepat menjadi akrab. Dia menerima beasiswa di Colombia dan mendapatkan gelar Ph.D pada 1898. Kemudian, dia tinggal dan mengajar di Colombia hingga pensiun pada 1940. Dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Animal Intelligence, An Experimental Study of Associationprocess in Animal. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan, seperti kucing, anjing, dan burung. Prinsip dasar proses belajar yang dianut oleh Thorndike mencerminkan dasar belajar (learning) tidak lain sebenarnya adalah asosiasi, suatu stimulus akan menimbulkan suatu respons tertentu. Teori ini disebut dengan teori S-R. Dalam teori S-R, dikatakan bahwa dalam proses belajar, pertama kali organisme (hewan, orang) belajar dengan cara “coba-salah (trial end error)”. Jika organisme berada dalam suatu situasi yang mengandung masalah, organisme tersebut akan mengeluarkan serentakan tingkah laku dari kumpulan tingkah laku yang ada padanya untuk memecahkan masalah itu. Berdasarkan pengalaman itulah, pada saat menghadapi masalah yang serupa, organisme sudah tahu tingkah laku mana yang harus dikeluarkannya untuk memecahkan masalah. Ia mengasosiasikan suatu masalah tertentu dengan suatu tingkah laku tertentu. Seekor kucing, 205 misalnya, yang dimasukkan dalam kandang yang terkunci akan bergerak, berjalan, meloncat, mencakar, dan sebagainya sampai suatu saat secara kebetulan ia menginjak suatu pedal dalam kandang itu sehingga kandang itu terbuka. Sejak saat itu, kucing akan langsung menginjak pedal jika ia dimasukkan dalam kandang yang sama. Ciri-ciri belajar dengan metode trial and error: 1. Ada motif pendorong aktivitas. 2. Adanya berbagai respons terhadap situasi. 3. Adanya aliminasi respons-respons yang gagal atau salah. 4. Adaya kemajuan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan penelitiannya itu. Berikut ini adalah Hukum Edward Lee Therndike. a. Hukum Latihan Hukum ini pada dasarnya sama dengan hukum frekuensi milik Aristoteles: jika asosiasi (atau koneksi neural) lebih sering digunakan, koneksinya akan lebih kuat. Sedangkan, yang paling kurang penggunaannya, paling lemahlah koneksinya, dua hal inilah yang berturut-turut disebut dengan hukum kegunaan dan ketidak bergunaan. b. Hukum Efek Ketika sebuah asosiasi kemudian diikuti dengan keadaan yang memuaskan, hasilnya menguat. Begitu juga sebaliknya, ketika sebua asosiasi diikuti dengan keadaan yang memuaskan, koneksinya melemah, kecuali untuk bahasa “mentalistik” (kepuasan bukanlah perilaku) karena hal itu sama dengan pengondisian operasi milik Skinner. Pada 1929, penelitiannya telah membawanya keluar dari semua hal di atas kecuali apa yang yang kita sebut sekarang dengan “penguatan (reinforcement)”. 206 Thorndike yang dikenal karena kajiannya tentang transfer pelatihan (transfer or training), kemudian ia percaya (dan masih sering percaya) bahwa mengkaji subjek-subjek sulit meskipun Anda tidak akan pernah menggunakannya. Hal itu bagus buat Anda karena hal itu memperkuat pikiran Anda. Hal ini adalah sejenis latihan yang bisa memperkuat otot-otot Anda. Hal itu kemudian digunakan kembali untuk membenarkan cara anak belajar bahasa Latin, seperti halnya yang digunakan saat ini, untuk membenarkan cara anak belajar kalkulus. Namun, dia menyatakan bahwa hanya keserupaan objek kedua dengan yang pertama sama saja yang dapat mengarah pada pembelajaran yang meningkat hasilnya dalam subjek kedua. Jadi, bahasa Latin mungkin membantu Anda belajar bahasa Italia atau belajar aljabar mungkin membantu Anda belajar kalkulus, tetapi bahasa Latin tidak akan pernah membantu Anda belajar kalkulus atau hal-hal lain yang berbeda. 6. Teori Belajar John B. Watson Watson mendefinisikan proses belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respons. Namun, stimulus dan respons yang dimaksud harus dapat diamati (observable) dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain, seperti fisika atau biologi yang berorientasi pada pengalaman empiris semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. 7. Teori Behavioristik dalam Pembelajaran Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran hingga 207 kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik, dengan model hubungan stimulus responsnya, mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respons atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik pemelajar, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga proses belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan (transfer of knowledge) ke orang yang belajar atau pemelajar. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Pemelajar diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid. Demikian halnya dalam pembelajaran, pemelajar dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para pemelajar. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, pemelajar diukur hanya pada hal-hal yang 208 nyata dan dapat diamati sehingga hal-hal yang bersifat tidak teramati kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Implikasi teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pemelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya. Sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis-mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respons sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pemelajar kurang mampu berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur rapi dan teratur, pemelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar sehingga proses pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Pemelajar atau peserta didik adalah objek yang berperilaku sesuai dengan aturan sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar diri pemelajar. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagi aktivitas mimetic, yang menuntut pemelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Sementara, proses pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks/ 209 buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks/buku wajib tersebut. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Evaluasi menekankan pada respons pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil test. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya, bila pemelajar menjawab secara “benar” sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa pemelajar telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan pemelajar secara individual. *** 210 Daftar Pustaka Arifin, Syamsul. 1994. Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban. Yogyakarta: Aditya Media. Bell Gredler, E. Margaret. 1991. Belajar dan Membelajarkan. Jakarta: CV. Rajawali. Bertens, K. 1975. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. Degeng, I Nyoman Sudana. 1989. Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel. Jakarta: Depdikbud. Drost, J.I.G.M. 1997. Sekolah: Mengajar atau Mendidik. Yogyakarta: Kanisius. Durrant, Will. 1959. The Story of Philosophy. New York: Garden City Publishing. Falckenberg, Richard. History Of Modern Philosophy [E-Book #11100]. Faruk. 1994. Pengantar Sosiologi Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gage, N.L. dan Berliner, D. 1979. Educational Psychology. Second Edition, Chicago: Rand Mc. Nally. 211 Gagne, E.D. 1985. The Cognitive Psychology of School Learning. Boston, Toronto: Little, Brown and Company. Hadiwijono, Harun, 2010, Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Yogyakarta: Kanisius. Hegel, GWF. 1999. Lectures on The History of Philosophy Vol.III. Virginia: Thoemmes Press. HW. Gandhi, Wangsa Teguh. 2010. Tujuh Cahaya Yunani. Yogyakarta: Lukita Media. Ismaun. 2004. Filsafat Ilmu. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. _____. 2007. Kapita Selekta Filsafat Administrasi Pendidikan (Serahan Perkuliahan). Bandung : UPI. Jalaluddin dan Abdulloh Idi. 1997. Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama. Kartanegara, Mulyadhi. 2002. Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam. Bandung: Mizan. Kattsof, Louis O. 1992. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana. Kneller, George F. 1971. Introduction to Philosophy of Education. New York: Jhon Willey Sons Inc. Lavine, T.Z. 2002. Petualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre. Yogjakarta: Jendela. Light, G. dan Cox, R. 2001. Learning and Teaching Learning and Teaching in Higher Education. London: Paul Chapman Publising. Martin, Vincent. 2003. Filsafat Eksistensialisme, Kierkegaard, Sartre, Camus. Terj. Taufiqurrohman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moersaleh. 1987. Filsafat Administrasi. Jakarta: Univesitas Terbuka. 212 Moll, L. C. (Ed.). 1994. Vygotsky and Education: Instructional Implications and Application of Sociohistorycal Psychology. Cambridge: University Press. Munawwaroh, Djunaidatul dan Tanenji. 2003. Filsafat Pendidikan (Perspektif Islam dan Umum). Jakarta: UIN Jakarta Press. Natawidjaya, Rochman. 1979. Pendidikan Nasional. Jakarta: CV Kurnia Esa. Palmer, Donald D. 2007. Sartre untuk Pemula. Terj. B. Dwianta Edi Prakosa dan Stepanus Wakidi. Yogyakarta: Kanisius. Parkinson, G.H.R. (ed.). 1993. History of Philosophy The Renaissance and Seventeenth Century Rationalism. Volume IV. London: Routledge. Pidarta, Made. 1994. Landasan Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta. Power, Edward J. 1982. Philosophy of Education. New Jersey: Prentice-Hall. Inc. Prasetya. 1997. Filsafat Pendidikan Untuk IAIN, STAIN,PTAIS. Bandung: Penerbit Pustaka Setia. Russel, Betrand. 2002. Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang (alih Bahasa Sigit jatmiko, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sadulloh, Uyoh. 2003. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Saifullah, Ali. 1997. Antara Filsafat dan Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional. Sartre, Jean-Paul, 2002, Eksistensialisme dan Humanisme, terj. Yudhi Murtanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Shimogaki, Kazuo. 1993. Kiri Antara Islam Modernisme dan Posmodernisme: Telah Kritis atas Pemikiran hasssan Hanafi. Yogyakarta: LKiS. Sindhunata, 2000. Menggagas Paradigma Pendidikan Baru Pendidikan. Yogyakarta: Kanisius. 213 Soedijarto. 1993. Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan bermutu. Jakarta: Balai Pustaka. Subangun, Immanuel. 1994. Dari Saminisme ke Posmodernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiharto, I. Bambang. 1996. Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat. Yogyakarta: Kanisius. Syaripudin, Tatang. 2008. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Percikan Ilmu. Tafsir, Ahmad. 2003. Filsafat Umum. Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra. Bandung: Rosda Karya. Titus, H. Harold dan S Marilyn Smith. 1984. Persoalan-Persoalan Filsafat. Jakarta: Bulan Bintang. Wibisono, Koento. 1997. Dasar-Dasar Filsafat. Jakarta: Universitas Terbuka. Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika. SUMBER LAIN www.wikipedia.com www.episentrum.com www.wikimu.com www.marxists.org www.thersa.org 214 Indeks A Adler Mortimer J. 66 Ortimer 181 agama 37, 38, 50, 51, 54, 55, 56, 73, 93, 111, 125, 128, 162, 164, 166, 167, 191, 203 aksiologi 35, 36, 51, 52, 54, 72, 89, 90, 105, 149, 177, 178 anak didik 20, 139, 168, 171, 172, 179, 189 andragogie 20 antitesis 34, 35, 38, 137, 140, 146 antropologi 43 a priori 135, 136 Aquinas, St. Thomas 166, 167 Aristoteles 14, 30, 42, 59, 114, 115, 140, 141, 159, 166, 167, 170, 175, 177, 178, 179, 206 asosiasi 34, 120, 205, 206 B Bacon, Francis 87, 141, 142 Bagley, William 163 behaviorisme 194, 196 behavioristik 194, 197, 198, 201, 202, 208, 209 Bergson, Henry 49 Berkeley, George 47, 131 beyond nature 39 Brameld, Theodore 190 C Camus, Albert 185 Childs, John L. 154 classical conditioning 195 Combs, Arthur 157 Critica 45 D das ding an sich 49 215 deduksi 51, 59, 141, 170 dehumanisasi 6, 22, 25, 83, 105, 122, 144 dekontruksi 121 demokratis 108, 139, 156, 190 deontologi 53 Descartes, Rene 48 de Unamuno, Miguel 185 Dewey, John 65, 74, 88, 146, 153, 154, 155 Dostoievsky, Fydor 185 E education 20, 70, 74, 169, 172 eksistensi 13, 32, 43, 60, 72, 131, 136, 156, 175, 183, 184, 186 Eksistensialis 89, 189 Empiris 89 empirisme 43, 44, 46, 50, 131, 132, 147, 194, 195, 196 Epikuros 130 episteme filsafat 35 epistemologi 35, 36, 39, 43, 44, 45, 89, 142, 148, 149, 170, 177 equity 68 esensi 43, 47, 130, 159, 160, 174, 175, 176, 177, 185 Esensialis 89 esensialis 124, 159, 160, 162, 163 estetika 39, 52, 54, 128, 179 etika 22, 26, 39, 52, 53, 54, 55, 216 56, 57, 58, 60, 63, 70, 81, 84, 91, 104, 106, 121, 130, 149, 178 etika deskriptif 57, 58 etika normatif 57, 58 eudemonisme 53 F falsafi 32, 37, 85, 88, 96, 98 fatalisme 195 fenoumena 49 filsafat pendidikan 6, 15, 29, 30, 35, 38, 66, 72, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 120, 124, 126, 127, 128, 163, 165, 166, 167, 188, 189 filsafat pendidikan Pancasila 85 filsafat terapan 82 filsuf 14, 32, 33, 34, 39, 42, 46, 77, 79, 82, 86, 87, 88, 104, 109, 130, 131, 137, 138, 139, 141, 145, 146, 153, 162, 183 fisika 43, 141, 176 Freud, Sigmund 153 futurisme 147 G generalisasi 49, 160 grahavidya 20 guru 6, 20, 29, 33, 55, 62, 68, 72, 87, 110, 114, 122, 123, 124, 125, 129, 139, 144, 150, 151, 156, 158, 162, 168, 172, 174, 179, 180, 181, 189, 193, 196, 197, 198, 199, 208, 210 Guthrie, Edwin 197, 198 H halaqah 20 hedonisme 53 Hegel 95, 99, 136, 137, 146, 162, 212 George Wilhelm Friedrich 162 Heidegger, Martin 183, 185 Herbart, John 87, 88 hukum frekuensi 206 hukum latihan 206 Hull, Clark 197 humanisasi 105, 157 humanisme 128, 147, 153, 156, 157, 158 Hume, David 46 Hussel 183 Hutchins, Robert Maynard 181, 182 Hutchkins, Robert 172, 179 I idealisme 43, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 147, 160, 161, 162, 184 idealisme epistemologis 137 idealisme personal 137 idealisme voluntarisme 137 ijazah 21 ilmu budaya 43 ilmu kedokteran 43, 146, 153 ilmu pengetahuan 43, 44, 45, 46, 52, 54, 59, 71, 87, 114, 115, 139, 141, 142, 162, 167, 169, 171, 177 iluminasionisme 49, 50 indra penciuman 46 indra pendengaran 46 indra penglihatan 46 indra peraba 46, 131 indra perasa 46 induksi 50, 59, 87 induktif 44, 87, 111, 115, 141, 142, 169 industrialisasi 11, 125, 145, 152 intersubjektif 44 intuisi 44, 46, 48, 50, 135, 137 intuisionisme 49, 50 Isyraqi 49 J James William 146, 147, 148 Williyams 205 Jaspers, Karl 185 jenjang pendidikan 5, 21 K Kafka, Franz 185 Kant, Immanuel 49, 53, 59, 135, 137, 138, 145 217 kebebasan 13, 14, 28, 52, 97, 101, 123, 124, 133, 136, 184, 185, 187, 188, 189 Kieggard 183 Kierkegaard, Sﹼren 185 Kilpatrick, William H. 154 Knight George 193 George R. 23 koherensi 39, 44, 50, 51 kontemplasi 102 korespondensi 44, 50 kosmologi 32, 41, 80, 84, 104 kosmos 41 kurikulum 138, 158, 173, 189 L La Follete, Robert 152 Lee Thorndike, Edward 205, 206 Leibniz, Gottfried Wilhelm 129 Locke John 46, 47, 142, 143 logika 24, 34, 39, 45, 50, 51, 58, 59, 82, 141, 145, 164, 170 logika episteme 59 logika mayor 45 logika minor 45 M madrasah 20 majlis ta’lim 20 Marcel, Gabriel 185 Maslow, materi pelajaran 173 Mead, George Herbert 146 218 metafisika 39, 40, 41, 42, 90, 130, 131, 148, 167, 172, 177, 187, 188 metafisika aksiologi 90 metafisika epistemologi 90 metafisika ontologis 90 metode deduktif 43, 177 metode dialektis 43, 110 metode ilmiah 44, 87 metode induktif 43, 177 metode kontemplatis 43 metode positivisme 43 Miletos 79, 118, 119 monad 129, 134 Monadologi 129 moral 28, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69, 83, 111, 115, 121, 128, 130, 136, 138, 139, 174, 179, 181, 191 N Naturalis 89 naturalisme 43 Neibuhr, Reinhold 11 Neo-Scholastisisme 167 Neo-Thomisme 167 Newton, Isaac 46, 47, 129 Nietzsche 109, 159, 185 noumena 49 O ontologi 35, 36, 42, 43, 44, 89, 90, 120, 171, 177, 184 operant conditioning 195, 198, 199 otonomi 68 otoriter 108 P padepokan 20 Pavlov Anton 195 Ivan Petrovich 203 pedagogi 62 pedagogie 20 pembelajar 197, 201, 202, 203, 208, 209, 210 pembimbingan 90, 91, 105 pendidik 6, 20, 23, 30, 55, 62, 63, 68, 86, 87, 88, 89, 144, 164, 201, 208 pendidikan liberal 138, 169 pendidikan praksis 35 pengajaran 6, 30, 61, 63, 67, 81, 111, 124, 125, 138, 139, 143, 144, 151, 156, 157, 158, 172, 179, 180 perenialis 159, 163, 164, 167, 168, 169, 173, 174, 179, 180, 181, 182 perenialisme modern 168 Perennialis 89 pesantren 20, 125 peserta didik 55, 63, 67, 68, 87, 89, 107, 108, 173, 193, 198, 202, 209 Pierce, Charles S. 145 Plato 14, 30, 32, 33, 42, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 129, 130, 140, 166, 167, 176, 178 pragmatik 51 pragmatis 23, 29, 44, 70, 74, 81, 84, 94, 96, 103, 104, 126, 128, 144, 145, 148, 149, 151, 152, 168, 181 pragmatisme 128, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 190 primitif 108 progresif 11, 74, 123, 124, 154, 155, 156, 162, 163, 168, 173, 181, 190 Progresivis 89 progresivisme 128, 147, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 163, 164, 181 psikologi behaviorisme 143 psikologi belajar 194, 198, 207 punishment 198, 201 Pythagoras 117, 118, 119 R rasionalisme 44, 48, 50, 131, 132 Realis 89 realisme 43, 128, 140, 141, 142, 143, 144, 159, 160, 161, 162 realitas 6, 11, 22, 29, 35, 39, 42, 43, 44, 47, 50, 83, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 219 137, 142, 148, 156, 160, 164, 170, 174, 187 reinforcement 197, 199, 201, 202, 203, 206 rekonstruksionisme 128, 147, 189, 190, 191 Rekontruksionis 89 renaissans 130 respons 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 210 Roger, Carls 157 Rouseau, J.J. 65 Rousseau, Jean Jacques 154 Rugg, Harold 154, 189 Russell, Betrand 118 S Sartre, Jean Paul 185 Schelling 137 school 20 schula 175 sekolah 5, 20, 21, 22, 62, 65, 66, 67, 70, 115, 122, 125, 139, 150, 152, 155, 158, 168, 179, 182, 189, 192, 193 Silberman, Charles E. 23 silogisme 45, 59 Sinclair, John 51 sintesis 34, 35, 137, 139, 141, 147, 162, 167 Skinner, Burrhis 195 Socrates 30, 33, 53, 108, 109, 220 110, 111, 119 Solon 112 sophis 109 Sophocles 27 sosiologi 43, 152 stimulus 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 205, 207, 208, 209 substansi 42, 43, 48, 71, 133, 161, 174, 175, 176 survival 68 T teori belajar behavioristik 197, 201 teori pendidikan 74, 88, 89, 124, 147, 154, 155, 156, 163, 192 tesis 34, 35, 137 Thales 42, 79, 214 Toffler, Alvin 192 Tolman, Edward 195 Tradisionalis 89 tradisionalisme 163 tragedi 17, 22, 27, 31, 101, 102, 164 transfer pelatihan 207 transformasi ilmu 67 trial and error 206 U ultima 40 urbanisasi 11, 145, 152 utiliterisme 53 W wahyu 46, 50 Walpole, Horace 17 Whasburne, Charleton 154 Wilson, Woodrow 152 221 Biografi Penulis T eguh Wangsa Gandhi H.W. lahir di Gombong pada 12 Maret 1978, menempuh pendidikan di MA Al-Iman Bulus, Gebang Purworejo. Kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Tafsir Hadits serta Theologi dan Filsafat. Buku-buku yang pernah ditulis antara lain The Sun Tzu`s Art Of Loving: Seni Mencinta ala Sun Tzu (Neobooks); Menjadi Manusia: Kitab Hidup Patah Hati dan Kepedihan; Rahasia Angka Tujuh; Tujuh Cahaya Yunani (Lukita Media); Get Ur love (Grafindo); dan Michael Jackson: Legenda Superstar (Global Oceans). Sekarang tengah menyelesaikan antologi Gita Paradjati dan novel Suluk Bonang. 222