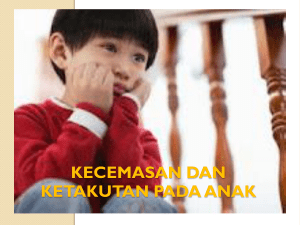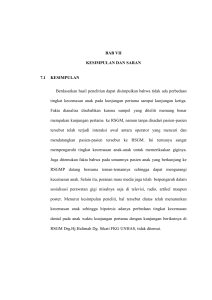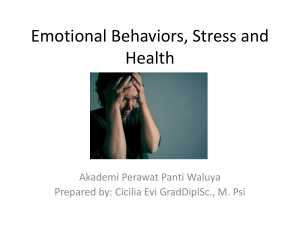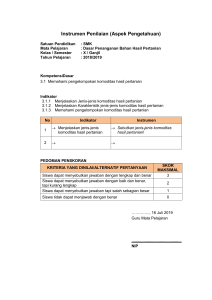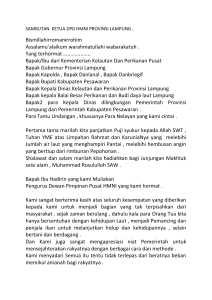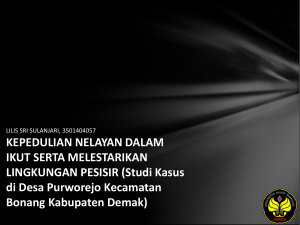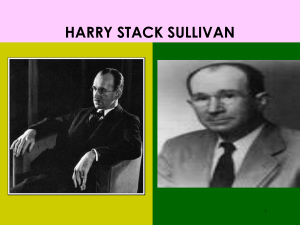Uploaded by
habimusin
Gambaran Kecemasan Nelayan Kessilampe Terkait Proyek Jalan Kendari-Konawe 2019
advertisement

BAGIAN ILMU KEDOKTERAN JIWA RSJ DR. SOEPARTO HARJOHUSODO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HALU OLEO PENGGANTI REFERAT DESEMBER 2019 GAMBARAN KECEMASAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN KESSILAMPE KECAMATAN KENDARI MENGENAI PROYEK PEMBANGUNAN JALAN KENDARI - KONAWE TAHUN 2019 PENYUSUN: Nurul Aulia Humairah Halim, S.Ked K1A1 14 087 PEMBIMBING: dr. Junuda RAF, M.Kes, Sp.KJ RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEPARTO HARJOHUSODO FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2019 BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang dimaksud dengan Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.1 Kesehata jiwa yang dimaksud salah satunya adalah Skizofrenia/psikosis dimana menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia 2018 menunjukkan proporsi rumah tangga dengan anggota yang memiliki gejala skizofrenia/psikosis di Indonesia mengalami peningkatan dari 1.7% pada tahun 2013 menjadi 7% pada tahun 2018.2 Provinsi Sulawesi Tenggara Skizofrenia/psikosissendiri masih di bawah angka proporsi nasional, yaitu 1% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 6% pada tahun 2018. Skizofrenia/psikosis di Indonesia dilihat dari tempat tinggal di tahun 2013 rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis yang pernah dipasung di pedesaan lebih tinggi sebesar 18,2% menjadi 17,7 % di tahun 2018, selanjutnya di perkotaan jumlah presentasi tahun 2013dan 2018 sama sebesar 10,7%. Selanjutnya dilihat dari pengobatan gangguan jiwa ada 84,9% yang berobat dan 15,1% tidak berobat, dan ada 51,1% pasien tidak rutin minum obat, 48,9 rutin dalam minum obat.2 Selain Skizofrenia/psikosis gangguan jiwa lain adalah kecemasan, yang mana kecemasan ini merupakan reaksi yang wajar yang dapat dialami oleh siapapun, sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam atau membahayakan. Namun jika kecemasan berlebihan dan serta tidak sesuai dengan proporsi ancamannya, maka dapat mengarah ke gangguan yang akan menghambat fungsi seseorang dalam kehidupannya.3 2 Kecemasan dapat dialami oleh setiap manusia yang dihadapkan oleh berbagai situasi yang dianggap mengancam atau membahayakan misalnya pembangunan jalan di pesisir pantai yang dapat berdampak pada mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga hal ini dapat memicu kekhawatiran/kecemasan akan dampak yang terjadi. Pembangunan jalan wisata Kendari-Konawe resmi dilakukan sejak tanggal 3 september 2019, pembangunan ini berlokasi di bibir pantai yang melewati sebagian perumahan warga dan akses untuk melaut bagi para nelayan di beberapa kelurahan di Kecamatan Kendari. Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Sulawesi Tenggara memiliki potensi perikanan di 3 wilayah administrasi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Konawe Selatan masih cukup besar. Hal ini disebabkan karena kawasan ini menempati kawasan perairan seluas 21.14,40 ha yang terdiri dari kawasan perairan pesisir Kabupaten Konawe Selatan yaitu 20.114,40 ha, Kabupaten Konawe seluas 1.295,67 ha, dan Kota Kendari seluas 376,07 ha, luas keseluruhan dengan panjang pantai yang cukup panjang dan terdapat banyak pulau-pulau kecil dan berhadapan langsung dengan Laut Banda yang terkenal akan berbagai jenis ikan berekonomis tinggi seperti tuna, cakalang, tongkol, laying, tenggiri, dan kembung serta berbagai jenis ikan karang seperti ikan kerapu dan kakap.4 Berdasarkan hasil survei awal dan wawancara pada beberapa nelayan di Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari menyatakan bahwa pembangunan jalan memiliki dampak negatif dan positif, dampak negatifnya antara lain perasaan cemas tidak mendapatkan lahan pengganti di sekitar pesisir. Oleh karena itu peneliti bermaksud menilai tingkat kecemasan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan di Kelurahan Kasilampe akibat pembangunan jalan Kendari-Konawe. B. Rumusan Masalah Bagaimana gambaran kecemasan masyarakat nelayan di Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari mengenai proyek pembangunan jalan Kendari–Konawe Tahun 2019? 3 C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui gambaran kecemasan masyarakat nelayan di Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari mengenai proyek pembangunan jalan Kendari–Konawe Tahun 2019. D. Manfaat Penelitian Mengetahui tingkat kecemasan masyarakat nelayan di Kelurahan Kasilampe Kecamatan Kendari mengenai proyek pembangunan jalan Kendari–Konawe Tahun 2019. 4 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kesehatan Jiwa Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2018 yang dimaksud dengan “Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain".1 Seseorang yang “sehat jiwa atau mental” mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Merasa senang terhadap dirinya serta a) Mampu menghadapi situasi b) Mampu mengatasi kekecewaan dalam hidup c) Puas dengan kehidupannya sehari-hari d) Mempunyai harga diri yang wajar e) Menilai dirinya secara realistis, tidak berlebihan 2. Merasa nyaman berhubungan dengan orang lain serta a) Mampu mencintai orang lain b) Mempunyai hubungan pribadi yang tetap c) Dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda d) Merasa bagian dari suatu kelompok e) Tidak "mengakali" orang lain 3. Mampu memenuhi tuntutan hidup serta a) Menetapkan tujuan hidup yang realistis b) Mampu mengambil keputusan c) Mampu menerima tanggungjawab d) Mampu merancang masa depan e) Dapat menerima ide dan pengalaman baru f) Puas dengan pekerjaannya 5 Diketahui dari Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ascobat Gani kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan mental adalah sebesar Rp 20 triliun. Jumlah pasien Jamkesmas rawat inap terbanyak di rumah sakit (RS) Kelas A pada 2010 lalu adalah Hebephrenic Schizophrenia (1.924 orang), Paranoid Schizophrenia (1.612 orang), Undifferentiated Schizophrenia (443 orang), Schizophrenia Unspecified (400 orang) dan Other Schizophrenia (399 orang). Jumlah itu belum termasuk pasien rawat jalan. Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai.5 Gangguan jiwa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di dunia. WHO (World Health Organization) menegaskan jumlah klien gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang dan paling tidak ada 1 dari 4 orang di dunia mengalami masalah gangguan jiwa. Di Indonesia jumlah klien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa dan di Jawa Barat sendiri klien gangguan jiwa mencapai 465.975 orang serta tiap tahunnya akan terus meningkat. Banyaknya kasus tentang gangguan jiwa ini bisa menghabiskan biaya pelayanan kesehatan yang besar bagi pemerintah.6 Prevalensi ganggunan mental emosional yang menunjukan gejala depresi dan kecemasan, usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Jumlah gangguan jiwa berat atau psikosis skizofrenia tahun 2013 di Indonesia provinsi-provinsi yang memiliki gangguan jiwa terbesar pertama antara lain adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (0,27%), kemudian urutan kedua Aceh (0,27%), urutan ketiga sulawesi selatan (0,26%), Bali menempati posisi keempat (0,23%), dan Jawa Tengah menempati urutan kelima (0,23%) dari seluruh provinsi di Indonesia.7 6 B. Gangguan Cemas Istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris yaitu anxiety yang berasal dari Bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku, dan ango, anci yang berarti mencekik. Kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas.8 Menurut Spil berger kecemasan terbagi dalam dua bentuk, yaitu. 1. Trait anxiety, yaitu adanya rasa khawatir dan terancam yang menghinggapi diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya tidak berbahaya. Kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian individu yang memang memiliki potensi cemas dibandingkan dengan individu yang lainnya. 2. State anxiety, merupakan kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar serta bersifat subjektif. Sedangkan menurut Freud membedakan kecemasan dalam tiga jenis, yaitu. 1. Kecemasan neurosis. Kecemasan neurosis adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan dalam diri. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, namun ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan. 2. Kecemasan moral. Kecemasan ini berakar dari konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas, di masa lampau sang pribadi pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali. 3. Kecemasan realistik Kecemasan realistik merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar.8 7 C. Pembangunan Jalan Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial untuk menjadi lebih baik yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material masyarakat itu sendiri.9 Pembangunan daerah (kabupaten atau provinsi) juga membutuhkan peran pemerintah pusat pada era desentralisasi sekarang ini. Wujud peran pemerintah pusat dalam meningkatkan perekonomian daerah dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut: 1. Pemberian insentif untuk menstimulasi investasi pada suatu wilayah; 2. Menetapkan kebijakan yang mampu menahan investasi publik untuk pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; 3. Menggerakkan mekanisme administrasi dan legislatif yang berguna untuk perkembangan bisnis ke arah yang lebih baik.10 Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pelayan publik untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, seperti: jalan, jembatan, kendaraan, terminal, pelabuhan, Bandar udara, perumahan, pasar, bank, sarana pendidikan dan kesehatan, penerangan, dan sanitasi.11 Pembangunan jalan merupakan pemicu utama tumbuhnya lapangan kerja baru di luar sektor pertanian (nonfarm) dan ini berdampak pada sumber penerimaan masyarakat bervariasi. Selain itu juga pembangunan jalan mempunyai dampak yang sangat positif dan signifikan terhadap perubahan pendapatan usaha ekonomi masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pembangunan jalan dan berdampak lanjut pada pemanfaatan lembaga bank oleh masyarakat untuk menabung.12 8 Wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi demikian akan mendorong timbulnya disparitas antar wilayah yang semakin melebar karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang cukup berlimpah. Pada wilayah pesisir, sektor perikanan mejadi sektor utama yang menjadi gantungan hidup masyarakatnya. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal dalam kaitannya dengan era perdagangan bebas ini dinyatakan secara jelas dalam GBHN TAP MPR No. IV / MPR / 1999, yang menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan di bidang ekonomi adalah untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif dan produk unggulan di setiap daerah, termasuk perikanan dan kelautan. Melihat kajian strategis yang termuat dalam kebijakan pengembangan ekonomi lokal tersebut, sudah selayaknya apabila kebijakan ini mendapat prioritas sebagai satu dasar kebijakan pembangunan nasional.13 Pelaksanaan otonomi daerah pada awal tahun 2001 merupakan momentum bagi dimulainya proses implementasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (Kabupaten/Kota) untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki keunggulan daya saing komparatif maupun kompetitif, baik untuk pasaran lokal, regional, nasional bahkan internasional.13 D. Karakteristik Nelayan Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan (Permen-KP 2019). Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengawetkannya.14 9 mengolah, dan/atau Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak di bagian Selatan garis khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan di antara 02°45’ - 06°15’ lintang selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 120°45’- 124°45’ bujur timur, Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di laut flores, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan di Teluk Bone. Sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara (74,25 persen atau 110.000 km²) merupakan perairan laut. Sedangkan wilayah daratan, mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan beberapa pulau kecil, adalah seluas 38.140 km² (25,75 persen). Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 14 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kota Kendari dan Kota Baubau.15 Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki perairan (laut) yang sangat luas. Luas perairan Sulawesi Tenggara diperkirakan mencapai 110.000 km². Perairan tersebut, sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena selain memiliki bermacam-macam jenis ikan dan berbagai varietas biota, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Berbagai spesies ikan yang banyak ditangkap nelayan dari perairan laut Sulawesi Tenggara adalah: Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan masih banyak lagi jenis ikan yang lain. Di samping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti: teripang, agar-agar, japing-japing (kerang mutiara), kerang lola (Trochus niloticus), mutiara dan sebagainya.15 Berdasarkan lapangan pekerjaan, sektor pertanian menjadi matapencaharian utama bagi penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 40,3 % dari total penduduk. Di dalam sektor pertanian terdapat subsektor perikanan yang juga menjadi salah satu mata pencaharian utama di beberapa wilayah 10 kabupaten. Perikanan yang dimaksud terdiri atas dapat subsektor perikanan yang juga menjadi salah satu mata pencaharian di beberapa wilayah kabupaten. Perikanan yang dimaksud terdiri atas dan perikanan tangkap baik di laut maupun perairan umum. Kini jumlah ini sebanyak 125.321 orang dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buton (DKP Sultra, 2014) atau sebesar 18 % dari jumlah total nelayan perikanan budidaya dan perikanan tangkap baik di laut maupun perairan umum. Kini jumlah nelayan di provinsi ini sebanyak 125.321 orang dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Buton sebanyak 22.990 nelayan (DKP Sultra, 2014) atau sebesar 18 % dari jumlah total nelayan yang ada.15 Gambar 1. Prevalensi nelayan di Sulawesi Tenggara 11 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode dan Desain Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitik yang berfungsi untuk mendeskripsikan data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. B. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2019 di Kelurahan Kasilampe, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. C. Prosedur Pengumpulan Data Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengisian kuesioner yang menggunakan Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS) untuk menilai kecemasan dan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) untuk menilai psikopatologi masyarakat nelayan di Kelurahan Kessilampe, Kecamatan Kendari. MMPI dilakukan pada nelayan tamatan SMA. Data sekunder di ambil dari data yang ada di perangkat desa. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling yaitu berjumlah 13 orang nelayan. 12 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kecamatan Kendari 16 1. Kondisi Geografis Secara astronomis, Kecamatan Kendari terletak di 3o56’27” - 3o58’44” Lintang Selatan, serta 122o34’27” - 122o37’37” Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Kendari memiliki batas-batas yaitu: a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Kendari d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kendari Barat Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Kendari 16 Luas wilayah Kecamatan Soropia 14,48 km2. Kelurahan terbesar yaitu Kelurahan Mangga Dua yaitu 4,41 km2 dan paling kecil yaitu Kerlurahan Kampung Salo yaitu 0,25 km2. 13 Tabel 1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kelurahan Tahun 2018 Jumlah Kelurahan Luas Jumlah (km2/sq.km) RW Jumlah RT 1 Kandai 0,34 6 16 2 Gunung Jati 3,51 6 14 3 Kendari Caddi 0,59 6 16 4 Kessilampe 0,62 6 15 5 Kampung Salo 0,25 4 12 6 Mangga dua 4,41 4 12 7 Mata 2,66 4 8 8 Purirano 1,84 2 7 9 Jati Mekar 0,26 6 12 Jumlah 14,48 44 112 Sumber: BPS Kota Kendari, 2018. 2. Kondisi Demografis Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Selain Sensus Penduduk, untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, BPS melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). SUPAS telah dilakukan sebanyak empat kali, tahun 1976, 1985, 1995 dan terakhir 2005. Data kependudukan selain Sensus dan SUPAS adalah proyeksi penduduk. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia (RI) termasuk Warga Negara Asing kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya. Berbeda dengan pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya, Sensus Penduduk 2010 melaksanakan metode pencacahan lengkap termasuk pula anggota rumah tangga Korp Diplomatik RI. 14 Sensus Penduduk 2010 dilakukan serentak di seluruh tanah air mulai tanggal 1-31 Mei 2010. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara de jure dan de facto. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dipakai cara de jure, dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah dengan cara de facto, yaitu dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus biasanya pada malam ‘Hari Sensus’. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/ terasing dan pengungsi.Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya. Sebaliknya, seseorang atau keluarga menempati suatu bangunan belum mencapai enam bulan tetapi bermaksud menetap di sana dicacah di tempat tersebut. Tabel 2. Banyaknya Penduduk Kecamatan Kendari Menurut Jenis Kelamin tiap Kelurahan Tahun 2018 Jenis Kelamin Kelurahan Laki-laki Perempuan Total 1 Kandai 1.876 1.800 3.676 2 Gunung Jati 2.930 2.881 5.811 3 Kendari Caddi 2.898 2.980 5.878 4 Kessilampe 2.493 2.479 4.972 5 Kampung Salo 1.509 1.556 3.065 6 Mangga dua 1.326 1.239 2.565 7 Mata 1.047 1.039 2.086 8 Purirano 707 698 1.405 9 Jati Mekar 2.126 2.052 4.178 Jumlah 16.912 16.724 33.636 Sumber : Data luas wilayah dan penduduk Kecamatan Kendari 2019 15 Tabel 3. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya menurut jenis budidaya, 2016, 2017, 2018 Jumlah Rumah Tangga Jenis Budaya 2016 2017 2018 1 Budidaya Laut - - - 2 Tambak - - - 3 Kolam - - - 4 Keramba 8 8 53 5 Jaing Apung - - - 6 Lainnya - - - Jumlah 8 8 53 Sumber : Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya 2016-2018 B. Kelurahan Kessilampe 16 1. Kondisi Geografis Kelurahan Kessilampe Luas wilayah Kelurahan Kessilampe 0,62 km2. Batas Wilayah Kelurahan Kessilampe disebelah utara Kelurahan Mangga Dua, selatan oleh Teluk Kendari, timur oleh Kelurahan Mata, barat oleh Kelurahan Kendari Caddi. Gambar 2. Peta Kelurahan Kessilampe 16 2. Demografis dan Kependudukan 17 Secara kependudukan, Kelurahan Kessilampe memilki 3.751 penduduk yang terdiri dari 1.921 laki-laki dan 1.830 perempuan. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Kessilampe sebanyak 833 Kepala Keluarga. Secara umum, suku yang ada di Kelurahan Kessilampe terdiri atas suku Bugis, Makassar, Mandar, Ambon, Minahasa, Jawa, Batak, Flores, Sunda. Rata-rata masyarakat yang tinggal di Kelurahan Kessilampe dominan suku Bugis - Bajo. 3. Mata Pencaharian Untuk rincian mata pencaharian dan jumlahnya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4. Data Mata pencaharian Masyarakat di Kelurahan Kessilampe No Jumlah Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 1 Buruh tani 205 0 2 Pegawai Negeri Sipil 100 75 3 Pengrajin industri rumah tangga 16 17 4 Pedagang keliling 55 11 5 Peternak 1 0 6 Nelayan 500 30 7 Montir 2 1 8 Bidan swasta 0 6 9 Pegawai rumah tangga 0 10 10 Dokter swasta 1 1 11 TNI 1 0 12 POLRI 7 0 13 Pensiunan PNS/TNI/POLRI 20 10 14 Pengusaha kecil dan menengah 3 2 15 Dukun kampung terlatih 2 0 16 Dosen swasta 2 0 17 Pengusaha besar 1 0 18 Karyawan perusahan swasta 87 55 19 Karyawan perusahaan pemerintah 30 28 Sumber : Profil Kelurahan Kessilampe 2019 17 C. Hasil Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kecemasan masyarakat Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari mengenai pembangunan proyek Jalan Kendari-Konawe. Kelurahan Kessilampe memiliki total penduduk 3.751 jiwa yang terdiri dari 833 KK, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.921 orang dan perempuan 1.830 orang. Sampel penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yaitu sebanyak 530 orang, Terdiri 500 orang lakilaki dan 30 orang perempuan. Tabel 5. Karakteristik Responden berdasarkan Umur Umur Jumlah Presentase (%) 26-35 2 15,38 36-45 4 30,76 46-55 6 46,15 >55 1 7,69 Total 13 100 Sumber : Data Primer, 2019 Pada penelitian ini jumlah sampel dari segi umur untuk kategori umur 26-35 tahun ada 2 responden (15,38%), 36-45 tahun ada 4 responden (30,76%), 46-55 tahun ada 6 responden (46,15%), dan >55 tahun ada 1 responden (7,69%). Tabel 6. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase (%) Tidak sekolah 1 7,69 SD 4 30,76 SMP 8 61,53 SMA 0 0 Total 13 100 Sumber : Data Primer, 2019 Pada penelitian ini jumlah sampel dari segi tingkat pendidikan untuk kategori tidak sekolah yaitu sebanyak 1 responden (7,69%), SD sebanyak 4 responden (30,76%), SMP sebanyak 8 responden (61,53%). 18 Tabel 7. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Kecemasan Tingkat Kecemasan Jumlah Presentase (%) Tidak cemas 11 78,57 Cemas Ringan 2 15,38 Cemas Sedang 0 0 Cemas Berat 0 0 Cemas Sangat Berat 0 0 Total 13 100 Sumber : Data primer, 2019 Berdasarkan tabel diatas dari 13 responden didapatkan responden yang tidak cemas sebanyak 11 responden (78,57%) dan mengalami cemas ringan sebanyak 2 responden (15,38%). Tabel 8. Hubungan Umur dan Tingkat Kecemasan pada Nelayan di Kelurahan Kessilampe Tingkat Kecemasan Karakteristik Cemas Total Cemas ringan n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 26-35 2 (100) 0 0 0 0 2(100) 36-45 4 (100) 0 0 0 0 4(100) 46-55 4 (66,66) 2 (33,33) 0 0 0 6 (100) > 55 1 (100) 0 0 0 0 1 (100) Total 11 (84,61) 2 (15,38) sedang Cemas berat Cemas Tidak cemas Responden Sangat Berat Umur (tahun) 13 (100) Sumber : Data Primer, 2019 Berdasarkan tabel 8, hasil analisis data menunjukkan bahwa dari 13 responden, terdapat 11 responden (84,61%) yang tidak mengalami kecemasan, diantara 11 responden tersebut, terdapat 2 orang (100%) dari kelompok usia 26-35 tahun, 4 orang (100%) dari kelompok usia 36-45 tahun, dan 4 orang (66,66%) dari kelompok usia 46-55 tahun, dan pada usia >55 tahun terdapat 1 orang (100%) yang tidak mengalami cemas. Kelompok usia 46-55 tahun sebanyak 2 orang (33,33%) mengalami cemas ringan. 19 Tabel 9. Distribusi Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kecemasan pada Nelayan di Kelurahan Kessilampe Tingkat Kecemasan Karakteristik Tidak cemas Cemas ringan Cemas Responden Cemas berat sedang Total Cemas Sangat Berat n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) Tidak sekolah 1 (100) 0 0 0 0 1 (100) SD 3 (75) 1 (25) 0 0 0 4 (100) SMP 7 (87,5) 1 (12,5) 0 0 0 8 (100) SMA 0 0 0 0 0 0 Total 11 (84,6) 2 (15,3) 0 0 0 13 (100) Tingkat Pendidikan Sumber : Data Primer, 2019 Berdasarkan tabel 9, hasil analisis data menunjukkan bahwa, responden dengan tingkat pendidikan yang tidak sekolah yaitu sebanyak 1 orang (100%) tidak mengalami kecemasan, untuk responden dengan tingkat pendidikan SD didapatkan 3 orang (75%) tidak mengalami kecemasan, dan 1 orang (25%) mengalami cemas ringan. Untuk responden dengan tingkat pendidikan SMP didapatkan 7 orang (87,5%) tidak mengalami kecemasan dan 1 orang (12,5%) mengalami kecemasan. 120 100 80 60 tidak cemas 40 Cemas ringan 33,33 20 25 0 0 0 0 12,5 0 26-35 tahun 36-45 tahun 46-55 tahun > 55 tahun tidak sekolah SD SMP Gambar 3. Distribusi frekuensi cemas berdasarkan umur dan tingkat pendidikan 20 D. Pembahasan Berdasarkan hasil wawancara kepala Kelurahan Kessilampe menyatakan bahwa nelayan di kelurahan Kessilampe sebagian besar menangkap ikan menggunakan kapal pancing, dan mereka biasanya melaut di Sulawesi tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Irian Jaya. Tidak hanya itu, nelayan di Kessilampe juga menggunakan perahu pancing, pukat dan jaring untuk menangkap ikan. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan, mayoritas bukanlah nelayan murni, mereka juga melakukan pekerjaan sampingan seperti, mengojek, berdagang, berkebun dan menjadi pembantu rumah tangga bagi perempuan. Pekerjaan sampingannya dilakukan apabila tangkapan ikan mereka berkurang atau sedang terang bulan sehingga sulit mendapatkan ikan, di pagisiang hari mereka melakukan pekerjaan sampingan dan di sore-malam hari mereka melaut untuk menangkap ikan. Pada penelitian ini dari begitu banyak jumlah nelayan yang terdapat di Kelurahan Kessilampe, peneliti hanya menemukan 13 nelayan, hal ini dikarenakan pada saat turun lapangan, rata-rata nelayan disana sedang melaut ke Irian Jaya, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah. Penduduk di Kelurahan Kessilampe yang bekerja sebagai nelayan, terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari yang tidak bersekolah, SD, SMP dan SMA, namun untuk responden yang berpendidikan terakhir SMA tidak ditemukan saat peneliti turun ke lapangan. Usia para nelayan juga bervariasi, mulai dari usia muda hingga usia tua. Dalam penelitian ini suku 7 dari 13 responden merupakan variasi antara bugis dan bajo, sebagian yang lain adalah suku muna dan jawa. Para responden rata-rata sudah bekerja sebagai nelayan selama 13 tahun, dalam penelitian ini, nelayan yang sudah bekerja paling lama 20 tahun dan paling cepat 8 tahun. Selain itu, para nelayan di Kelurahan Kessilampe masih menggunakan alat-alat tradisional dalam melaut, dan masih banyak dari mereka yang tidak menggunakan handphone (HP), hanya ada beberapa nelayan yang menggunakan HP komunikator sehingga mereka belum bisa menggunakan aplikasi untuk melaut seperti Global Positioning System (GPS) maupun aplikasi-aplikasi lain untuk para nelayan. 21 Pada penelitian ada 2 instrumen penelitian yang digunakan, HARS dan MMPI, tes MMPI dilakukan pada nelayan yang berpendidikan terakhir SMA, namun hal ini tidak dilakukan dikarenakan pada saat turun lapangan, nelayan yang berpendidikan terakhir SMA tidak berada di tempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 13 nelayan di Kelurahan Kessilampe, didapatkan bahwa tingkat kecemasan menggunakan Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS) didapatkan tingkat kecemasan ringan yaitu 2 responden dan 11 responden tidak mengalami kecemasan. Kecemasan ringan ini dialami oleh 1 orang nelayan yang terkena penggusuran dan 1 orang lainnya adalah nelayan yang tidak terkena penggusuran. Adapun kecemasan yang dialami nelayan yang terkena penggusuran ini adalah cemas karena takut kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan, nelayan ini takut jikalau nanti saat penggantian lahan, ia tidak mendapatkan lahan yang berada di sekitar pesisir, dan harus beralih ke pekerjaan yang lain. Adapun 1 orang nelayan yang berasal dari kelompok yang tidak terkena penggusuran merasa cemas karena khawatir rumahnya ikut tergusur dikarenakan belum ada kepastian dari pemerintah setempat mengenai penggusuran. Jumlah rumah yang terkena penggusuran yaitu sebnayak 100 rumah. Dan untuk jumlah rumah nelayan yang terkena gususr tidak diketahui. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai nelayan di Kelurahan Kessilampe dengan adanya proyek pembangunan jalan Kendari-Konawe tidak mengalami kecemasan dan tidak khawatir akan hal tersebut, hal ini didukung dengan hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap responden nelayan di Kelurahan Kessilampe yang menyatakan bahwa, proyek pengerjaan jalan Kendari-Konawe tidak membuat mereka cemas, justru mereka senang dengan adanya pembangunan jalan ini, karena hal tersebut membawa keuntungan bagi mereka, masyarakat disana dapat berdagang di pinggir jalan Kendari-Konawe untuk menambah penghasilan, selain itu masyarakat yang terkena penggusuran khawatir akan adanya pembangunan jalan ini, mereka berharap kepada pemerintah agar diberikan lahan di sekitar tempat tinggal lama mereka atau diberikan ganti yang 22 sepadan agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan masih bisa tinggal di pesisir pantai agar dapat tetap bekerja sebagai nelayan. Isu-isu yang ada saat ini adalah penggantian dana oleh pemerintah akan diberikan kurang lebih 90 juta bagi masyarakat yang terkena gusur, hal ini juga belum pasti adanya, karena hal inilah nelayan yang terkena gusur bertambah cemas dan khawatir tidak bisa memiliki rumah seperti sebelumnya. Ia khawatir jika nanti uangnya tidak mencukupi untuk kembali membangun rumah, karena saat digusur tidak serta merta mereka langsung tinggal di rumah yang baru, akan tetapi harus mulai membangun dan diwaktu itu mereka tentunya akan menyewa tempat tinggal sementara. Mereka khawatir uang penggantiannya akan habis untuk keperluan menyewa rumah, makan dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan responden yang mengalami cemas ringan dialami oleh nelayan dengan pendidikan SD dan SMP, hal ini sejalan dengan penelitian Riskiyani (2018) yang menyatakan terdapat hubungan negatif yang signifikan, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan semakin tinggi pengetahuan maka akan semakin rendah tingkat kecemasan dan semakin rendah pendidikan maka akan semakin rendah pengetahuan sehingga akan membuat kebingungan pada orang tua juga akan semakin tinggi tingkat kecemasan orang tua selain itu hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeniu, et al., (2017) bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki maka semakin rendah tingkat kecemasan orang tua.18,19 23 BAB IV SIMPULAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara tingkat kecemasan menggunakan Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS) didapatkan tingkat kecemasan ringan yaitu 15,39%, dan 84,61% tidak mengalami kecemasan. Kecemasan ringan ini di alami oleh 1 orang nelayan yang terkena penggusuran dan 1 nelayan yang tidak terkena penggusuran. Nelayan yang terkena penggusuran ini merasa cemas karena takut kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan, nelayan ini takut jikalau nanti saat penggantian lahan, ia tidak mendapatkan lahan yang berada di sekitar pesisir, dan harus beralih ke pekerjaan yang lain. Adapun 1 orang nelayan yang berasal dari kelompok yang tidak terkena penggusuran merasa cemas karena khawatir rumahnya ikut tergusur dikarenakan belum ada kepastian dari pemerintah setempat mengenai rumah-rumah yang pasti tergusur. B. Saran Perlu dilakukan evaluasi data kesehatan jiwa pada masyarakat di Kelurahan Kessilampe terkait kecemasan terhadap proyek pembangunan jalan Kendari-Konawe sampai pengerjaan proyek tersebut selesai serta perlu dipantau kembali terkait janji pemerintah dalam hal ganti untung pada masyarakat yang terkena penggusuran. 24 DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 185. Jakarta. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. Kementerian Kesehatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 3. Saleh, U. Anxiety Disorder. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas hasanuddin. 4. Tim Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. 2016. Penilaian Performa Pengelolaan Perikanan di KKPD Sulawesi Tenggara Menggunakan Indikator EAFM. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Kendari 5. Putri, A.W., Wibhawa, B., Gutama, A.S. 2015. Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). Prosiding Ks: Riset & PKM. 2(2):147-300. 6. Purnama, G., Yani, D.I., Sutini, T. 2016. Gambaran Stigma Masyarakat Terhadap Klien Gangguan Jiwa Di RW 09 Desa Cileles Sumedang. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia 2(1): 29-37. 7. Hartanti, F.P. 2018. Stresor Predisposisi Yang Mendukung Terjadinya Gangguan Jiwa Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 8. Annisa, D.F dan Ifdil. 2016. Konsep Kecemasan (Anxiery) Pasa Lanjut Usia (Lansia). KONSELOR 5(2):93-99. 9. Anggraini,Y., Domai,T., Said, A. Implementasi Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) Dalam Upaya Pembangunan Wilayah Pesisir (Studi di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang). JurnalAdministrasiPublik (JAP) 3(11):1862-1867. 10. Eko safitri ,K.H., Rustiadi,E., Yulianda,F. 2017. Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi 25 Kasus Kabupaten Jepara. Journal of Regional and Rural Development Planning 1(2):145-157. 11. Prapti,L., Suryawardana,E., Triyani,D. 2015. Analisis Dampak Pembangunan InfrastrukturJalanTerhadapPertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang. J.DinamikaSosbud 17(2):82-103. 12. Iek,M. 2013. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papusa Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 6(1): 30-40. 13. Wiranto,T. 2004. Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Laut Dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah. Deputi Menteri Negara PPN /Kepala Bappenas Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas Disampaikan Pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP pada tanggal 22 September 2004. 14. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam. 15. Deswati, R.H. Muhadjir. 2015. Dukungan Aspek Produksi dalam Sistem Logistik Ikan Nasional (Slin) Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Support Of Production Aspect In National Fish Logistics System (Slin) In The Kendari City, Southeast Sulawesi. Jurnal sosek kp 10(2) : 192-201. 16. Badan Pusat Statistik Kota Kendari. 2019. Kecamatan Kendari dalam Angka 2019. 17. Data Primer Kelurahan Kessilampe. 2018. Profil Kelurahan Kessilampe Kecamatan Kendari 18. Riskiyan.F.,M.2018.Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua Yang Mempunyai Anak Autistik Di Slb Negeri 1 Surakarta. Skripsi.Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 26 19. Jeniu, E., Widodo, D. & widiani, E., 2017. Hubungan Pengetahuan Tentang Autistik dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua yang Memiliki Anak Autistik di Sekolah Luar Biasa Bhakti Luhur Malang. Nursing News, 2(2), pp.32-4 27 Lampiran 1. Dokumentasi Gambar 4. Wawancara pada nelayan di Kelurahan Kessilampe Gambar 5.Wawancara pada kepala Kelurahan Kessilampe 28