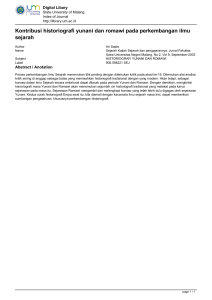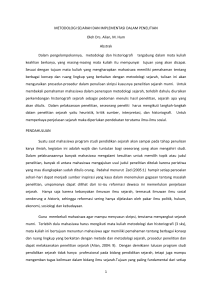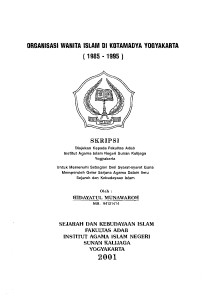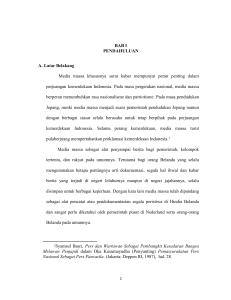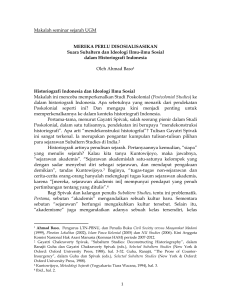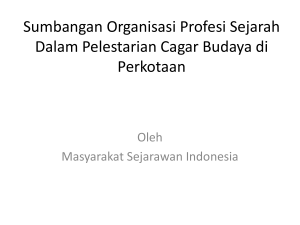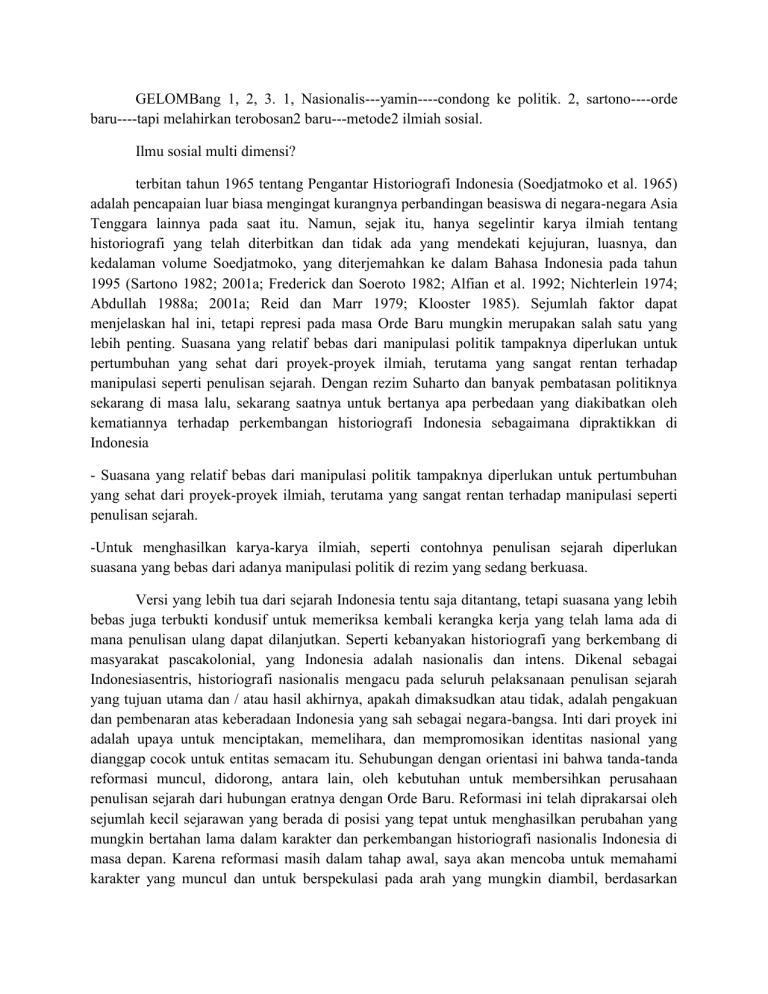
GELOMBang 1, 2, 3. 1, Nasionalis---yamin----condong ke politik. 2, sartono----orde baru----tapi melahirkan terobosan2 baru---metode2 ilmiah sosial. Ilmu sosial multi dimensi? terbitan tahun 1965 tentang Pengantar Historiografi Indonesia (Soedjatmoko et al. 1965) adalah pencapaian luar biasa mengingat kurangnya perbandingan beasiswa di negara-negara Asia Tenggara lainnya pada saat itu. Namun, sejak itu, hanya segelintir karya ilmiah tentang historiografi yang telah diterbitkan dan tidak ada yang mendekati kejujuran, luasnya, dan kedalaman volume Soedjatmoko, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia pada tahun 1995 (Sartono 1982; 2001a; Frederick dan Soeroto 1982; Alfian et al. 1992; Nichterlein 1974; Abdullah 1988a; 2001a; Reid dan Marr 1979; Klooster 1985). Sejumlah faktor dapat menjelaskan hal ini, tetapi represi pada masa Orde Baru mungkin merupakan salah satu yang lebih penting. Suasana yang relatif bebas dari manipulasi politik tampaknya diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat dari proyek-proyek ilmiah, terutama yang sangat rentan terhadap manipulasi seperti penulisan sejarah. Dengan rezim Suharto dan banyak pembatasan politiknya sekarang di masa lalu, sekarang saatnya untuk bertanya apa perbedaan yang diakibatkan oleh kematiannya terhadap perkembangan historiografi Indonesia sebagaimana dipraktikkan di Indonesia - Suasana yang relatif bebas dari manipulasi politik tampaknya diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat dari proyek-proyek ilmiah, terutama yang sangat rentan terhadap manipulasi seperti penulisan sejarah. -Untuk menghasilkan karya-karya ilmiah, seperti contohnya penulisan sejarah diperlukan suasana yang bebas dari adanya manipulasi politik di rezim yang sedang berkuasa. Versi yang lebih tua dari sejarah Indonesia tentu saja ditantang, tetapi suasana yang lebih bebas juga terbukti kondusif untuk memeriksa kembali kerangka kerja yang telah lama ada di mana penulisan ulang dapat dilanjutkan. Seperti kebanyakan historiografi yang berkembang di masyarakat pascakolonial, yang Indonesia adalah nasionalis dan intens. Dikenal sebagai Indonesiasentris, historiografi nasionalis mengacu pada seluruh pelaksanaan penulisan sejarah yang tujuan utama dan / atau hasil akhirnya, apakah dimaksudkan atau tidak, adalah pengakuan dan pembenaran atas keberadaan Indonesia yang sah sebagai negara-bangsa. Inti dari proyek ini adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempromosikan identitas nasional yang dianggap cocok untuk entitas semacam itu. Sehubungan dengan orientasi ini bahwa tanda-tanda reformasi muncul, didorong, antara lain, oleh kebutuhan untuk membersihkan perusahaan penulisan sejarah dari hubungan eratnya dengan Orde Baru. Reformasi ini telah diprakarsai oleh sejumlah kecil sejarawan yang berada di posisi yang tepat untuk menghasilkan perubahan yang mungkin bertahan lama dalam karakter dan perkembangan historiografi nasionalis Indonesia di masa depan. Karena reformasi masih dalam tahap awal, saya akan mencoba untuk memahami karakter yang muncul dan untuk berspekulasi pada arah yang mungkin diambil, berdasarkan makalah yang baru-baru ini diterbitkan dan tidak dipublikasikan, serangkaian lokakarya yang diadakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) , dan wawancara dengan sejumlah sejarawan Indonesia. Seperti kebanyakan historiografi yang berkembang di masyarakat pascakolonial, yang Indonesia adalah nasionalis dan intens. Dikenal sebagai Indonesiasentris, historiografi nasionalis mengacu pada seluruh pelaksanaan penulisan sejarah yang tujuan utama dan / atau hasil akhirnya, apakah dimaksudkan atau tidak, adalah pengakuan dan pembenaran atas keberadaan Indonesia yang sah sebagai negara-bangsa. Inti dari proyek ini adalah upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempromosikan identitas nasional yang dianggap cocok untuk entitas semacam itu. -Historiografi Indonesia pascakolonial adalah historiografi nasionalis atau Indonesia-sentris, yaitu pengakuan dan pembenaran atas keberadaan Indonesia sebagai negara-bangsa yang sah. -Tujuan dari penulisan sejarah yang Indonesia-sentris adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara, dan mempromosikan identitas nasional yang dianggap cocok untuk entitas semacam itu. Pembuatan Tradisi Negara-bangsa Indonesia relatif muda, seperti halnya historiografi yang menopang pembentukannya. Catatan sejarah umum melacak perkembangan historiografi nasionalis Indonesia hingga anti-kolonial, karya-karya sastra-historis dan pidato-pidato nasionalis awal seperti Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Sukarno (Reid 1979; Sartono 1982; Abdullah dan Surjomihardjo 1985). Hanya beberapa di antaranya yang historis dalam bentuk dan maksud, tetapi gagasan-gagasan yang dikemukakan di dalamnya tidak salah lagi menemukan jalan mereka ke dalam fondasi historiografi nasionalis yang perkembangannya mendapat dorongan di bawah perlindungan pendudukan Jepang (Klooster 1982). Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, atmosfir yang sangat anti-kolonial memajukan perkembangan historiografi semacam itu. Pada waktunya, ia mengambil posisi ortodoksi yang memastikan dampak yang langgeng pada masa depan penulisan bahasa Indonesia. Mungkin karya-karya Muhammad Yamin (1950; 1953) yang paling mencontohkan karakter umum dari tahap awal ini - romantis, ultra-nasionalistis, dan beberapa akan mengatakan pra-ilmiah. Jenis historiografi seperti ini mungkin menjadi cepat dominan, tetapi kritik tidak kurang. Soedjatmoko menonjol karena kritiknya yang fasih dan meyakinkan tentang upaya menjadikan sejarah sebagai hamba perempuan dari proyek nasionalis. Dalam suatu Seminar Nasional Pertama yang penting pada tahun 1957, ketegangan antara sejarah "ilmiah" yang secara metodologis masuk akal dan rekanrekan nasionalisnya yang memiliki informasi ideologis muncul. Diminta untuk berbicara tentang filosofi yang seharusnya menginformasikan penulisan sejarah, Soedjatmoko dan Yamin mengambil sisi yang berlawanan. Yang pertama memperingatkan dengan keras terhadap bahaya membiarkan sejarah digunakan untuk mempromosikan proyek-proyek nasionalis dan mendorong kepatuhan ketat terhadap metodologi standar sejarah (Soedjatmoko 1960). Yamin menegaskan dalam istilah yang sama kuat perlunya sejarah Indonesia ditulis dari perspektif nasionalis dan untuk membantu mempromosikan kesadaran dan persatuan nasional (Yamin 1957). Ketegangan antara posisi-posisi ini telah menjadi perlengkapan abadi dan menentukan perkembangan historiografi Indonesia. -Dalam Seminar Sejarah Nasional tahun 1957, ada filosofi yang berbeda mengenai penulisan sejarah dari Soedjatmoko dan Yamin. -Soedjatmoko memperingatkan bahayanya membiarkan sejarah digunakan untuk mempromosikan proyek-proyek nasionalis dan mendorong kepatuhan ketat terhadap metodologi standar sejarah. -Yamin menegaskan dalam istilah yang sama kuat perlunya sejarah Indonesia ditulis dari perspektif nasionalis dan untuk membantu mempromosikan kesadaran dan persatuan nasional -Pada tahun-tahun setelah kemerdekaan, atmosfir yang sangat anti-kolonial memajukan perkembangan historiografi Indonesia dan menjadi dominan untuk penulisan sejarah Indonesia ke depannya. Menurut sebagian besar laporan, tahap selanjutnya dari historiografi Indonesia paling baik ditandai dengan dominasi pendekatan ilmu sosial multi-dimensi yang dipelopori oleh Sartono Kartodirdjo dan digembar-gemborkan oleh seminar nasional kedua yang diadakan pada tahun 1970. Taufik Abdullah menunjukkan bahwa seminar pertama dikenal untuk "ide-ide besar," sementara yang kedua mengantarkan era yang ditandai oleh produksi keluaran historis empiris dan dapat dipercaya (Abdullah 2001a). Selama tiga dekade berikutnya, pengaruh "sekolah Sartono" terbukti sangat dominan sehingga Asvi Warman Adam, seorang sejarawan muda yang menjanjikan, baru-baru ini menjuluki periode ini sebagai "Gelombang Kedua." Ini mengikuti gelombang pertama, penghilangan kolonisasi, yang secara khusus ditujukan untuk menghilangkan sisa-sisa historiografi kolonial Belanda, dan digantikan oleh gelombang ketiga saat ini, yang ditandai oleh proliferasi versi sejarah yang berbeda, termasuk "sejarah para korban" yang ditulis oleh, untuk, dan dari sudut pandang mereka yang menderita kekejaman di bawah rezim Orde Baru (Adam 2000). Pendekatan multi-dimensi, ilmu sosial memiliki sejumlah karakteristik utama. Pertama, ini bertujuan untuk menjadi nasional dan berpusat pada perspektif Indonesia berbeda dengan historiografi kolonial yang mengambil penduduk asli, Indonesia, atau tempat-tempat dalam apa yang akhirnya akan menjadi Indonesia sebagai bagian dari narasi sejarah. Kedua, multidimensi dalam peristiwa-peristiwa historis dijelaskan sebagai hasil dari interaksi yang rumit antara faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, dan lainnya. Ini bertentangan dengan gelombang para sejarawan yang lebih konvensional, di antaranya Yamin menjadi teladan, yang memberi bobot “berlebihan” pada faktor-faktor politik, sehingga terlalu menekankan “orang besar” dengan mengorbankan rakyat biasa. Ketiga, pendekatan multi-dan antar-disiplin. Teori-teori dari berbagai disiplin ilmu sosial sengaja dicari untuk meningkatkan penjelasan sejarah. Sekali lagi, ini sangat kontras dengan pendekatan yang pada dasarnya non-teoretis dan deskriptif dari kelompok sebelumnya. Keempat, itu bertujuan ketat untuk mengamati standar, "ilmiah," metodologi historis. Kelima, dan mungkin bukan dengan desain, dilihat oleh pengamat seperti Kuntowijoyo, Adam, dan Bambang Purwanto sebagai apolitis, netral secara politik, atau, lebih buruk, secara politis tidak relevan. (Diskusi lebih rinci tentang pendekatan ilmu sosial dapat ditemukan di Sartono 2001a; 1994; 1982; Abdullah 1988a; 1994; 2001a; dan Abdullah dan Surjomihardjo 1985.) -Historiografi Indonesia dengan pendekatan multi-dimensi ilmu sosial bertujuan untuk menjadi nasional dan berpusat pada perspektif Indonesia. - pendekatan multi-dimensi ilmu sosial untuk menjelaskan hasil dari interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, agama, dan lainnya, tidak hanya menekankan pada faktor politik saja. -Teori-teori dari berbagai disiplin ilmu sosial sengaja dicari untuk meningkatkan penjelasan sejarah. Akun standar perkembangan historiografi Indonesia, seperti dirangkum di atas, bermasalah pada beberapa tingkatan. Hampir seluruhnya mengabaikan dominasi tradisi nasionalis yang terus-menerus diwakili oleh Yamin, sambil membesar-besarkan pengaruh aliran Sartono. Faktanya, pemerintahan diduga dari sekolah Sartono lebih seperti sebuah gambar yang diproyeksikan dari sudut tertentu yang menyajikan gambar yang sebagian dan menyesatkan. Melihat ke seluruh medan sejarah Indonesia, mencoba mengidentifikasi informasi sejarah seperti apa yang beredar dan benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat umum, kita mungkin akan terkejut bahwa sekolah Sartono yang seharusnya dominan itu tidak banyak berekspresi baik dalam buku akademik dan buku pelajaran atau media populer seperti itu. sebagai surat kabar dan majalah, semua indikator nyaman kesadaran sejarah masyarakat. (Perhatian saya di sini adalah historiografi nasionalis akademik. Lihat van Klinken [2001], yang memandang historiografi nasionalis dari sudut pandang politik dan menyamakannya dengan tradisi panjang penulisan sejarah yang diinformasikan secara ideologis di mana sejarah akademik yang serius menempati tidak lebih dari posisi marginal. Pendekatannya tidak diragukan lagi menerangi politik yang terlibat dalam penulisan sejarah selama dan segera setelah rezim Soeharto, tetapi saya percaya bahwa dalam suasana saat ini, ada harapan bahwa sejarah yang sesuai dengan standar metodologi metodologi yang ketat akan secara bertahap mengambil posisi yang lebih penting, jika tidak dominasi tertinggi. Ada sejumlah sejarawan lokal yang dilatih di jurusan sejarah Universitas Gadja Madah (UGM) di bawah bimbingan Sartono sendiri yang telah membuat jejak dalam profesi ini. Ada juga yang dilatih di luar negeri, seperti Taufik Abdullah (Cornell), Joko Suryo (Monash), dan Bambang Purwanto (SOAS), yang setidaknya secara prinsip setuju dengan serangkaian ide dan metode yang diusulkan oleh Sartono - gagasan dan metode yang diakui oleh mayoritas sejarawan Indonesia selama tiga dekade terakhir sebagai "cawan suci." Meski begitu, versi sejarah politik dan militerisasi dengan mudah mendominasi lanskap sejarah. Ini telah ditulis oleh sejarawan militer, sejarawan "populer" dari berbagai posisi ideologis, dan sejarawan Universitas Indonesia (UI). Kehadiran penganut sekolah Sartono, seperti Adri Lapian, di Departemen Sejarah UI menyulitkan untuk menggeneralisasi, tetapi pengaruh terpenting dari Nugruho Nutosusanto telah menimbulkan kesan, terutama di kalangan sejarawan UGM, yang berkonspirasi dengan Orde Baru. rezim dalam memasang dan memelihara historiografi yang disponsori negara. - versi sejarah politik dan militerisasi dengan mudah mendominasi lanskap sejarah pada masa Orde Baru. Situasi di Indonesia hampir tidak unik. Catatan perkembangan historiografi di Filipina mengungkapkan masalah yang sama. Akun-akun ini sebagian besar diproduksi oleh para sejarawan dari Departemen Sejarah Universitas Filipina, departemen dominan di negara ini. Sudah mudah bagi para penulis ini untuk menyamakan perkembangan historiografi di departemen mereka sendiri dengan pengembangan seluruh negara. Mungkin lebih bermanfaat untuk menganggap catatan historiografis yang berasal dari departemen sejarah yang dominan seperti UGM dan UP sebagai proyeksi keinginan atau keinginan kelompok dominan sejarawan, daripada sebagai peta yang dapat diandalkan dari seluruh medan historiografi. UGM dan UP sebagai universitas yang dominan diangap catatan historiografisnya sebagai proyeksi2 dalam penulisan sejarah, tetapi seharusnya itu hanya dijadikan acuan dalam penulisan sejarah saja. Domin asli de facto sejarah politik dan militerisasi dengan mudah dikaitkan dengan pengaruh kuat politik Orde Baru pada wacana sejarah dan karenanya tidak mengejutkan kita. Namun, yang menarik adalah pemisahan antara akun standar dan apa yang akan saya sebut, karena kurang istilah yang lebih baik, akun "lebih dekat dengan kenyataan". Dalam yang terakhir, aliran Sartono hanyalah satu, dan tidak dominan, dari beberapa aliran penulisan sejarah yang dapat diidentifikasi. Dalam perspektif, sejarawan militer-UI-populer berbagi dengan sekolah Sartono Indonesia-sentrisme, dan keduanya berkontribusi pada upaya pembangunan negara negara - yang pertama sebagai agen aktif dan yang terakhir sebagai mitra pasif. Secara metodologis, sejarah militer-UI-populer menyimpang dari sekolah Sartono dalam penekanan yang diakui pada "orang besar" - sejarah politik yang didominasi dan dalam preferensi untuk narasi deskriptif, non-teoritis. Secara politis, ia terbukti menerima upaya pembenaran rezim dari negara dan kurang tahan terhadap pengaruh ideologis, bisa dibilang menjadikannya penerus historiografi nasionalis dalam tradisi Muhammad Yamin. Di sisi lain, karena aspirasi untuk metodologi sejarah "ilmiah", saya cenderung menganggap sekolah Sartono lebih dekat ke jalan yang disarankan oleh Soedjatmoko. Dengan demikian ia mewakili suatu terobosan, bukan perkembangan yang tersirat dalam catatan standar, dari tradisi historiografi nasionalis sebelumnya. Saya harus mencatat, bagaimanapun, kegelisahan saya dengan apa yang tampaknya dikotomi sederhana antara sejarah "ilmiah" dan "cenderung politis". Beberapa sarjana Indonesia bersikeras pemisahan antara keduanya (Adri Lapian, wawancara 29 Oktober 2001; Soedjatmoko 1960), tetapi terlihat lebih rumit dari itu. Kritik pahit Kuntowijoyo sangat relevan di sini. “Historiografi Indonesia dalam Pencarian Identitas” baru-baru ini menonjol karena kritik tajam dan tajam yang tidak biasa bagi para sejarawan Indonesia. Itu kontroversial karena menghukum seluruh generasi sejarawan Indonesia karena kegagalan kolektif untuk melakukan fungsi sosial mereka sebagai cendekiawan, yaitu, menjadi kritik sosial. Dia mengklaim bahwa sikap netral dari pendekatan ilmu sosial dapat diterima oleh siapa pun yang berkuasa: "sejarah tidak berkontribusi apa-apa dan tidak bertentangan dengan siapa pun, sejarah aman bagi semua orang" (Kuntowijoyo 2000, 81). Justru netralitas seperti itu, seolah-olah karena kepatuhannya pada metode "ilmiah", yang membuat sekolah Sartono secara politis diizinkan dan menjadikannya sebuah ceruk dalam skema hal-hal yang didefinisikan oleh politik Orde Baru. Politik dan sejarah "ilmiah" tidak dapat dipisahkan. Kombinasi sikap politik netral dan klaim sebagai ilmiah memungkinkan sekolah Sartono mengambil posisi - sebagai pemain dominan, mengikuti akun standar, atau sebagai elemen penting, mengikuti versi "lebih dekat dengan kenyataan" - dalam sejarah historiografi Indonesia. -Perlunya pemisahan antara sejarah “ilmiah” dan politik. Upaya untuk membedakan aliran Sartono dari aliran lain dimaksudkan sebagai dasar untuk memahami upaya yang sedang berjalan untuk mereformasi historiografi Indonesia. Harus ditekankan bahwa target upaya yang sedang berjalan ini terutama adalah sekolah Sartono dan hanya yang kedua adalah seluruh Indonesiasentris. Sejarah militer-UI-populer yang merupakan sebagian besar output Indonesia-sentris era Suharto telah didiskreditkan sebagai hamba perempuan dari rezim Orde Baru. Sejak itu telah dianggap sebagai proyek intelektual yang tidak memadai, jika tidak memalukan, oleh kelompok reformis yang merupakan fokus utama dari esai ini. Reformasi yang sedang berlangsung adalah mengambil bentuk pemeriksaan ulang kritis, tetapi bukan penolakan langsung, dari sekolah Sartono, yang bertujuan untuk membersihkannya dari hubungannya dengan proyek-proyek politik dan membuatnya lebih benar dalam praktik untuk janji-janjinya. Dan sementara ada saran radikal untuk membuang kerangka nasionalnasionalis sama sekali, ada indikasi yang jelas bahwa itu akan dipertahankan. -Sejarah-militer-UI-populer merupakan output dari sebagian besar historigrafi Indonesia-sentris di era Suharto. -Oleh kelompok reformis, proyek intelektual di era Suharto dianggap tidak memadai dan diperlukan pemeriksaan ulang yang kritis. -Ada saran radikal untuk membuang kerangka nasional-nasionalis, tetapi jelas bahwa itu tidak bisa dan harus dipertahankan. Menabur Benih Reformasi Pada Oktober 2001, saya menghadiri Konferensi Sejarah Nasional ke-7 yang diadakan di Jakarta. Itu adalah yang terakhir dari serangkaian seminar / konferensi sejarah nasional yang dimulai pada tahun 1957. Pertemuan-pertemuan ini jarang diadakan - dalam beberapa dekade terakhir, setiap lima hingga enam tahun - dan karena ini adalah yang pertama di era pascaSuharto, saya berharap untuk lihat tanda-tanda perubahan atau tren baru dalam komunitas sejarawan akademik Indonesia. Tetapi sementara harapan pembalikan besar dalam studi sejarah pasti akan kecewa, ada indikasi samar bahwa perubahan mungkin akan terjadi. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI; Asosiasi Sejarawan Indonesia) membuat "deklarasi kemerdekaan" formal dan kategoris dari cengkeraman tradisional pengaruh atau kontrol negara. Dan di antara lebih dari seratus kertas yang dikirim ada dua yang menonjol. Ini ditulis oleh sejarawan pemula yang relatif muda Mestika Zed dan Bambang Purwanto, yang masing-masing dilatih di Amsterdam (Vrije U) dan London (SOAS). Makalah-makalah mereka sendiri membahas kebutuhan mendasar untuk memeriksa kembali kerangka nasionalis yang telah lama dianggap suci oleh hampir semua sejarawan Indonesia. Bertentangan dengan tradisi yang sudah mapan itu, tidak mengherankan bahwa isu-isu yang mereka angkat tidak diangkat dengan antusias dan bahwa kontinuitas alih-alih perubahan mendominasi atmosfer keseluruhan. Saya berpendapat, bagaimanapun, bahwa posisi "strategis" yang ditempati oleh para reformator (terutama Purwanto) membuat elemen perubahan yang samar-samar terlihat signifikan sebagai tanda-tanda hal-hal yang akan datang. -Makalah dari sejarawan Mestika Zed dan Bambang Purwanto, membahas perlunya memeriksa kembali kerangka nasionalis yang telah lama dianggap suci oleh hampir semua sejarawan Indonesia. - bahwa kontinuitas alih-alih perubahan mendominasi atmosfer keseluruhan. Makalah Mestika Zed, "Menggugat Tirani Sejarah Nasional" (lit. Untuk menuduh tirani sejarah nasional), menarik bukan hanya untuk apa yang dikatakan tetapi untuk bagaimana penulis mengatakannya. Dengan keengganan besar yang biasa dimiliki oleh para sejarawan Indonesia dalam tradisi pembatasan intelektual, ia ingin mengirim pesan yang radikal dan revisionis dengan cara yang begitu sopan dan miring sehingga ambivalensi penderitaannya hampir dapat diraba. Lebih dari setengah makalah ini membahas perkembangan historiografi di Prancis dan Inggris dan orang dapat dengan mudah melupakan Indonesia dalam tampilan pengetahuan. Tetapi gagasan utama, meskipun dengan susah payah menyamar, cukup jelas: bahwa gagasan tentang sejarah nasional adalah tirani dan menindas dan bahwa dengan belajar dari pengalaman negara-negara barat seperti Prancis dan Inggris, orang Indonesia mungkin dapat membebaskan diri dari tirani semacam itu. Saya percaya bahwa dia adalah sejarawan Indonesia pertama yang menyarankan dalam pertemuan formal pemecatan langsung Indonesiasentris sebagai kerangka kerja untuk studi sejarah. Namun, menjelang akhir makalahnya, sikap ambivalen penulis terungkap ketika ia membiarkan dirinya membingkai kata-kata penutupnya dalam kerangka kerja "nasional". Menurut saya, keengganan semacam itu menunjukkan kesulitan yang dihadapi oleh para sejarawan Indonesia dalam menentang tradisi historiografi nasionalis. Di satu sisi, ia mungkin yang pertama dari jenis baru sejarawan Indonesia: satu kaki dengan berani melintasi garis, yang lain terjebak di lumpur. Dalam arti lain, ia mempersonifikasikan krisis identitas di mana historiografi Indonesia telah terperangkap untuk beberapa waktu sekarang. Seperti yang dikatakan Kuntowijoyo, historiografi Indonesia sedang dalam “pencarian identitas.” Pertanyaan: jadi sebaiknya bagaimana? Apakah perlu untuk menentang dan menghilangkan tradisi historiografi nasionalis? - bahwa gagasan tentang sejarah nasional adalah tirani dan menindas dan bahwa Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara barat seperti Prancis dan Inggris. -Kesulitan para sejarawan Indonesia dalam menentang tradisi historiografi nasionalis. Mestika Zed adalah reformis yang enggan, Bambang Purwanto tentu saja tidak. Berdasarkan tulisan-tulisannya dan wawancara saya dengannya, saya dapat mengatakan bahwa ia tidak memiliki keraguan untuk mengguncang pembentukan historiografi Indonesia yang mengakar kuat. Dia sangat kritis terhadap kelemahan dalam penulisan sejarah Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh sejarawan Indonesia yang disegani seperti Sartono dan Lapian. Berbekal pemahaman tentang perkembangan teoritis baru-baru ini dalam historiografi, ia tidak berbasa-basi dalam mengungkap dan menyerang masalah yang tajam dalam konseptualisasi dan metodologi Indonesiasentris secara umum dan sekolah Sartono pada khususnya. Banyak dari komentarnya membawa rasa tidak nyaman, bahkan mengejutkan, kepada penjaga lama dan karena itu ia agak tidak populer. Di sisi lain, kritiknya yang tidak masuk akal menghembuskan angin revolusioner baru melalui medan historiografi Indonesia yang sebelumnya gersang. Setelah jeda panjang yang dipaksakan oleh penindasan intelektual selama beberapa dekade, perdebatan akhirnya kembali. Politik dan Metodologi Kritik Purwanto berfokus pada sejumlah titik kritis. Pertama adalah kegigihan impuls kolonial, dengan mengabaikan dinamika internal-lokal, dalam apa yang disebut sebagai metodologi Indonesia-sentris. Kedua adalah kecenderungan umum untuk jatuh ke dalam anakronisme dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah, dengan mana ia bermaksud menafsirkan peristiwa-peristiwa di luar konteks sejarah dan kerangka waktu yang tepat. Anakronisme seperti itu, menurutnya, menunjukkan kegagalan untuk melawan impuls politik dan nasionalistik. Ketiga adalah penekanan yang tidak proporsional pada "orang besar" dan faktor politik untuk mengabaikan dimensi lain. Keempat, ia berusaha menjelaskan masalahmasalah ini terutama dalam hal metodologis, bukan melalui politik. Terakhir, solusi yang ia usulkan adalah kepatuhan ketat terhadap metodologi historis "ilmiah". -Penekanan sentralitas kolonialisme yang tidak semestinya dan mengabaikan dinamika internallokal. -Adanya kecenderungan anakronisme dalam menafsirkan peristiwa-peristiwa sejarah, yaitu menafsirakan peristiwa-peristiwa di luar konteks sejarah dan kerangka waktu yang tidak tepat. -Terlalu banyak penekanan pada “orang besar” dan faktor politik sehingga mengabaikan faktorfaktor lain, seperti budaya, ekonomi, sosial, dll. Menjelaskan peristiwa sejarah melalui metodelogis historis-ilmiah, bukan melalui politik. Dalam “Kesadaran Dekonstruktif dan Historiografi Indonesiasentris” (Kesadaran dekonstruktif dan historiografi Indonesia-sentris) ia berangkat untuk meledakkan mitos bahwa kerangka kerja Indonesiasentris secara efektif menghapuskan sisa-sisa historiografi dan wacana kolonial. Dalam banyak tulisan-tulisan ini, ia mengklaim, sentralitas kolonialisme dapat dilihat dalam penekanan yang tidak semestinya pada kegiatan atau peran penjajah dan pemerintah kolonial dengan mengorbankan internal, dinamika lokal (2001a, 6). Purwanto menghargai karya perintis Sartono dalam memfokuskan kembali lensa sejarah jauh dari "orang besar" dan menuju kehidupan rakyat jelata, dan menyadari kontribusi besar sekolah Sartono telah membuat kemajuan keseluruhan historiografi Indonesia. Namun ia mengeluh tentang kegagalan Sartono sendiri dan sekolah pada umumnya untuk mengatasi masalah-masalah mendasar tertentu. Dalam perkiraannya, Sartono cenderung tetap terjebak dalam tema-tema anti-kolonial ketika menganalisis peristiwa-peristiwa bersejarah, mengabaikan dinamika lokal yang pada kenyataannya memainkan peran yang lebih besar. Misalnya, ia mengutip pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 yang dilihat Sartono sebagai reaksi terhadap eksploitasi kolonial. Dia membantah bahwa beberapa bukti menunjukkan pertumbuhan ekonomi sedang dialami di Banten pada tahun 1888, lima tahun setelah letusan Mt. Krakatua, dan konflik antara berbagai kelompok sosial, bukan hanya eksploitasi kolonial, harus turut disalahkan (9). Dia menemukan pengabaian yang sama dari dinamika internal dalam analisis Sartono tentang keresahan petani di pedesaan Jawa (1984) dan penerimaannya terhadap gagasan romantis tentang kehidupan desa sebagai teladan perdamaian dan ketertiban, sejauh ia mengabaikan eksploitasi yang berasal dari struktur feodal. Menurut Purwanto, Sartono tampaknya menganggap hal-hal yang dilakukan oleh VOC sebagai eksploitasi dan yang dilakukan oleh elit lokal sebagai bagian dari pengorbanan satu anggota keluarga untuk yang lain. Pada kenyataannya, menurutnya, tindakan eksploitatif yang dilakukan oleh VOC dan kemudian pemerintah kolonial hanyalah kelanjutan dari tradisi eksploitasi panjang terhadap rakyat jelata (7). Demikian pula, ia menemukan bahwa sebagian besar sejarawan Indonesia membaca novel Max Havelaar hanya melihat eksploitasi Belanda dan mengabaikan penggambaran eksploitasi yang dilakukan oleh elit pribumi dan kohort mereka (8-9). Purwanto bahkan mengkritik studi yang dilakukan oleh pengikut sekolah Sartono yang dengan cermat menunjukkan dinamika internal. Dia berpendapat bahwa Lapian menafsirkan kegiatan bajak laut (1987) dan Suhartono dari bandit pedesaan (1989) dalam kerangka anakronistik yang terlalu menganggap mereka bukan sebagai kriminal, tetapi sebagai anti-kolonial, sebagai bagian dari perjuangan nasionalis melawan penjajah ( 8). Pada kenyataannya, katanya, tidak semua perompak dan bandit ini menentang penjajah; beberapa bekerja untuk mereka (11). -Menurut Bambang Purwanto, sebagian besar sejarawan Indonesia hanya melihat eksploitasi belanda dan mengabaikan penggambaran eksploitasi yang dilakukan oleh elit pribumi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perjuangan nasionalis melawan penjajah. -Karya Lapian dan Suhartono mengenai bandit, digambarkan bandit bukan sebagai criminal, tetapi sebagai anti-kolonial. Padahal tidak semua perompak dan bandit ini menentang penjajah; beberapa bekerja untuk mereka. Dalam “Ketika Sejarah Menjadi Sekedar Alat Legitimasi” (Ketika sejarah menjadi alat legitimasi), ia mengalihkan pandangannya ke peristiwa sejarah yang lebih kontemporer untuk mengidentifikasi serangkaian masalah yang serupa. Ini rupanya ditulis untuk campur tangan dalam debat panas baru-baru ini mengenai proposal untuk menyatakan, secara hukum, bahwa Sultan Hamengkubuwono IX, bukan Soeharto, adalah penggagas nyata serangan terpadu 1949 terhadap posisi Belanda di Yogyakarta (Serangan Umum 1 Maret 1949) . Berdebat dengan keras menentang proposal tersebut, Purwanto mengajukan pertanyaan tentang implikasinya yang tidak demokratis, kurangnya dasar ilmiah / historis, dan penekanan yang tidak semestinya pada peran elit dalam analisis historis. Ia menuduh bahwa hal itu mencerminkan kegigihan budaya politik otoriter di Indonesia pasca-Orde Baru dan promosi satu pikiran yang mencegah perbedaan pendapat. Selain itu, ia mengklaim bahwa itu mengungkapkan kesalahpahaman sejarah sebagai perusahaan ilmiah dengan proses klaim dan pembenaran kebenarannya sendiri, sebuah proses yang tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi politik dan hukum (1-2). Akhirnya, ia menyesalkan ketiadaan orang biasa dan terlalu menekankan pada para pemimpin dalam catatan sejarah, seolah-olah hal-hal terjadi dalam kekosongan sosial-ekonomi dan budaya. -Sejarah sebagai alat legitimasi untuk orang besar. -Penekanan yang tidak semestinya pada peran elit dalam analisis historis. -Sejarah sebagai studi yang menggunakan analisis historis ilmiah, tidak boleh dipengaruhi oleh intervensi politik dan hukum Makalah ini patut dicatat karena pernyataannya yang meyakinkan tentang perlunya untuk menolak pengaruh politik yang tidak semestinya dalam analisis historis dan untuk mengamati metodologi historis "ilmiah". Dia menolak permintaan rakyat untuk menggantikan Suharto dengan Sultan; alih-alih merupakan produk analisis sejarah yang teliti dan sah, katanya, itu mungkin hanya hasil dari asal bukan Suharto (asalkan bukan Soeharto) atau mentalitas sejarah dendam (sejarah untuk pembalasan) yang lazim pada periode pasca-Suharto. Menurutnya, tuntutan rakyat untuk mendehem-Suhartokan catatan sejarah hanya mengulangi gerakan yang bermotivasi politik untuk menghapus sejarah Sukano yang telah dilakukan puluhan tahun sebelumnya. Dalam pandangannya, mengganti satu set mitos dengan yang lain tidak dapat diterima. Catatan sejarah harus diubah mengikuti prosedur dan standar analisis historis "ilmiah". -Penolakan dan penggantian Suharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sematamata karena adalanya mentalitas dendam sejarah, yaitu menghapus peran Suharto dalam sejarah sama seperti apa yang dilakukan pada Orde Baru terhadap peran Sukarno. -Kalau ingin merubah catatan sejarah harus mengikuti prosedur dan standar analisis historis "ilmiah". Penekanan hampir tunggal Purwanto pada kepatuhan ketat terhadap metodologi historis adalah pusat kritiknya terhadap Indonesiasentris. Tidak seperti banyak sejarawan Indonesia lainnya yang menganggap pemerintahan otoriter masa lalu sebagai alasan utama, jika tidak hanya, ketidakmampuan untuk merekonstruksi sejarah secara obyektif, ia percaya kelemahan "budaya dan struktural" dalam komunitas sejarawan akademis lebih bertanggung jawab. Secara khusus, ia menyalahkan "ketidaktahuan" dari sebagian besar sejarawan Indonesia - pemahaman mereka yang kurang dan kurangnya keterampilan dalam penggunaan metode sejarah ilmiah untuk kerentanan catatan sejarah terhadap pengaruh politik. Alasannya adalah ini: jika impuls mengendalikan rezim otoriter dan atmosfer nasionalis yang tak tertahankan dari periode pascarevolusi yang harus disalahkan, kita harus menemukan masalah anakronisme, "orang besar," dan mengabaikan dinamika lokal hanya dalam catatan sejarah yang ditulis ketika rezim otoriter memiliki andil dalam mengendalikan produksi historiografi. Alih-alih, masalah-masalah ini menjangkau hampir seluruh bentangan sejarah Indonesia. Jadi sumber utama masalah ini adalah “ketidaktahuan” metodologis dari para sejarawan Indonesia, yang membuat mereka sangat rentan terhadap pengaruh dan manipulasi politik. -“ketidaktahuan” metodologis dari para sejarawan Indonesia, yang membuat mereka sangat rentan terhadap pengaruh dan manipulasi politik. Tesis “ketidaktahuan metodologi” Purwanto adalah tandingan yang menyegarkan terhadap kecenderungan umum hanya untuk menyalahkan atmosfer yang membatasi secara politis dan nasionalistis yang telah memerintah selama sebagian besar periode pascakemerdekaan Indonesia. Namun, pemikiran tunggal yang menjadi dasar hipotesis ini membuat Purwanto rentan terhadap tuduhan reduksionisme dan jatuh datar ketika diterapkan pada dua sejarawan Indonesia yang paling disegani, Sartono dan Lapian, yang terkenal karena pemahaman teoretisnya yang sangat baik dan praktik metodologi historis. Purwanto telah dengan meyakinkan menunjukkan bahwa bahkan mereka tidak kebal terhadap "dosa" anakronisme, yang dapat dikaitkan dengan gatal nasionalisme. Bahkan sejarawan ulung seperti itu melakukan kesalahankesalahan ini menunjukkan bahwa metodologi sejarah yang baik tidak cukup untuk mencegah mereka. Kita harus ingat bahwa interpretasi merupakan bagian penting dari analisis historis dan pada akhirnya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibentuk oleh orientasi sosial-ekonomi, ideologis, moral, dan keagamaan para cendekiawan seperti halnya dengan pelatihan akademik. Dengan kata lain, masalah yang dihadapi historiografi Indonesia tidak dapat direduksi menjadi pemahaman metodologi yang tidak memadai. Suasana sosio-ekonomi dan politik tempat para sejarawan beroperasi tampaknya menjadi faktor penting dalam cara mereka menggunakan metode historis. -Sartono dan Lapian tidak kebal terhadap "dosa" anakronisme, mereka melakukan kesalahankesalahan dalam metodelogi sejarah. -Suasana sosio-ekonomi dan politik tempat para sejarawan beroperasi tampaknya menjadi faktor penting dalam cara mereka menggunakan metode historis. Inisiatif Baru Setelah menguraikan beberapa masalah yang melemahkan dengan Indonesiasentris seperti yang telah dipraktikkan dan dikonsepkan, Purwanto juga telah mulai merumuskan alternatif yang mungkin. Dia adalah satu di antara sedikit sejarawan Indonesia yang menunjukkan pemahaman dan sikap simpatik, meskipun hati-hati, terhadap masuknya teori postkolonial, poststrukturalis, dan postmodernis ke dalam domain studi sejarah. Beberapa andalan dalam bibliografinya adalah Munslow's Deconstructing History, Jenkins 'Postmodern History Reader, Post-strukturalisme dan Pertanyaan Sejarah Postridge, dan Berkhofer Beyond the Great Story. Mungkin karena kesadarannya tentang reaksi alergi rekan-rekannya terhadap "pos" apa pun, ia telah memilih untuk menggunakan terminologi dan ide proyek-proyek teoretis ini dengan hemat. Ia juga sangat selektif dalam meminjam; hanya gagasan-gagasan yang menurutnya berguna dalam upayanya mendekonstruksi sejarah Indonesia yang mendapat tempat dalam tulisan-tulisannya. Meskipun demikian, saya menemukan ini penting, tidak hanya sebagai dasar untuk kritik Purwanto, tetapi yang lebih penting sebagai indikator masa depan studi sejarah Indonesia. Demam "postie" yang melanda ilmu sosial lainnya di Indonesia sejak awal 1990-an (Heryanto 1995) akhirnya menginfeksi sejarah dan kita hanya bisa berspekulasi bagaimana itu akan mempengaruhi disiplin secara umum dan upaya untuk merumuskan kembali Indonesiasentris pada khususnya. Inisiatif lain dapat dilihat dalam “Mencari Format Baru Histroriografi Indonesiasentris Purwanto 2001: Sebuah Kajian Awal” (Mencari format baru historiografi Indonesia-sentris: Analisis pendahuluan). Makalah ini membahas keterbatasan dokumen tertulis sebagai sumber informasi sejarah, meletakkan dasar bagi usulannya untuk mengangkat sejarah lisan sebagai pilar historiografi Indonesia-sentris "baru". Dalam rumusannya, penggunaan sumber-sumber lisan dapat mengatasi "tirani arsip" yang mungkin mendasari ketahanan wacana kolonial (melalui ketergantungan yang berlebihan pada dokumen tertulis Belanda) dan narasi "sejarah tanpa manusia" yang ditandai dengan penekanan berlebihan pada elit. (yang tindakannya mengisi dokumen-dokumen itu). Namun, karakter awal dari proposal semacam itu disoroti oleh terbatasnya sejumlah masalah yang dapat diatasi dan kurangnya kesegarannya. -keterbatasan dokumen tertulis sebagai sumber informasi sejarah, mengangkat sejarah lisan sebagai pilar historiografi Indonesia-sentris "baru". -Hal ini untuk mengatasi tirani arsip dan ketergantungan yang berlebihan pada dokumen tertulis Belanda. Untuk pembahasan reformasi lebih lanjut, Purwanto memprakarsai serangkaian lokakarya pada tahun 2001. Lokakarya ini dirancang khusus untuk membahas Indonesiasentris sebagai kerangka kerja yang telah ada untuk menulis sejarah Indonesia. Peserta lokakarya termasuk sejarawan dari UGM dan universitas lain (Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sanatha Dharma), mahasiswa sarjana dan pascasarjana sejarah, dan sarjana dari disiplin ilmu sosial lainnya dan dari luar negeri. Saya menghadiri lokakarya pertama pada bulan Mei 2001, di mana para peserta secara terang-terangan bergulat dengan masalah Indonesiasentris dan membahas perlunya merumuskan kembali historiografi Indonesia. Apakah ini berarti pencabutan Indonesiasenstris atau hanya reformasi dari dalam tradisi adalah titik fokus dari diskusi yang ramah tetapi serius. Yang mengejutkan, itu adalah seorang antropolog, seorang sarjana asing, dan para peserta yang lebih muda yang mempertanyakan relevansi Indonesiasentris dalam masa globalisasi yang cepat ini, tetapi seruan untuk reformasi bukannya pencabutan dengan mudah menang hari itu. Kebutuhan akan semacam sejarah nasional ditegaskan kembali, paling tidak karena kegigihan prinsip negara-ke-negara dalam interaksi global. -perlunya merumuskan kembali historiografi Indonesia, apakah berarti pencabutan Indonesiasentris atau hanya reformasi. Tetapi yang menang adalah reformasi, bukan pencabutan. Lebih lanjut, tidak ada pertanyaan yang muncul tentang kegunaan pendekatan ilmu sosial multi-dimensi (?) yang dipelopori oleh Sartono. Sejalan dengan kritik Purwanto, penerapan pendekatan ini yang tidak tepat merupakan kesalahan. Ketidaksukaan tradisional untuk sejarah deskriptif konvensional, berpusat pada politik, mudah ditegakkan. Sebagai gantinya, peserta menyerukan pemahaman holistik tentang peristiwa dan artinya bagi orang-orang yang mengalaminya.(?) Karakter kontekstual dari Indonesiantris sebagai perspektif ditegaskan, artinya lensa penembus analisis historis akan disesuaikan tergantung pada sifat dan ruang lingkup (mikro, makro, lokal, regional, nasional) dari suatu peristiwa. Dengan kata lain, grup ini telah mencoba untuk membebaskan Indonesiasentris dari perannya yang biasa sebagai promotor dan pendefinisi apa yang “nasional” dan dengan demikian berharap untuk memisahkannya dari hubungan yang membebani dengan proyek nasionalis negara. -Memisahkan hubungan antara historiografi nasionalis dan upaya-upaya terhadap legitimasi pembenaran rezim negara. Kesimpulan Historiografi Indonesia berada pada titik kritis. Untuk semua masalah tesis "ketidaktahuan metodologi" Purwanto, mungkin memberikan sekilas ke karakter jangka panjang dan arah historiografi Indonesia di era pasca-Soeharto, terutama dalam komitmennya untuk metode sejarah "ilmiah" dan ketidakpercayaan tanpa syarat. agenda politik. Sementara sampai sekarang, sejarah pada periode pasca-Suharto sebagian besar tetap disandera oleh mereka yang memiliki sumbu politik untuk digiling, saya optimis bahwa selama proses demokratisasi di Indonesia berlanjut, historiografi akademis dan akademik dapat memperoleh posisi yang menonjol. Ini tidak akan berarti runtuhnya pengaruh nasionalis pada penulisan sejarah. Jatuhnya rezim Suharto telah memungkinkan pembubaran kemitraan historiografi nasionalis yang memberatkan dengan upaya-upaya pembenaran rezim negara. Ini telah mengurangi kecurigaan terhadap proyek nasionalis, memungkinkan ketekunan dan penemuan kembali sesuai dengan -Jatuhnya rezim Suharto berari memisahkan hubungan antara historiografi nasionalis dan upayaupaya terhadap legitimasi pembenaran rezim negara. -Tetapi bukan berarti hilangnya pengaruh nasionalis pada penulisan sejarah. perubahan karakter saat itu. Kita cenderung melihat kemitraan kreatif yang dibangun antara akademisi dan nasionalis dengan antipati yang kuat terhadap manipulasi politik yang terang-terangan. Jika atmosfir yang lebih bebas dari periode pasca-Suharto dipertahankan, kita juga harus melihat pluralitas pandangan yang dipupuk dan akhirnya dinaturalisasi. Dalam historiografi, ini berarti upaya reformasi yang sekarang sebagian besar berasal dari UGM akan diikuti oleh orang lain yang ingin membentuk masa depan. Kita harus berharap aliran tradisi historiografi yang berbeda, baik akademik maupun populer, berkembang secara paralel satu sama lain. Ini dapat muncul dari Universitas Indonesia, serta universitas regional dan Islam. Departemen Sejarah UI telah diidentifikasi secara dekat dengan rezim Orde Baru dan kelompok-kelompok Islam telah dikesampingkan melalui sebagian besar sejarah Indonesia; itu harus menarik dan relevan untuk melihat bagaimana re-orientasi historiografi mereka dapat dilanjutkan. Dilihat dari perspektif historis yang lebih luas, ide-ide reformis yang saya survei di sini bukanlah hal baru. Orang dapat dengan mudah mendengar gema Soedjatmoko, John Smail, dan J.C. van Leur, belum lagi pandangan Taufik Abdullah sebelumnya (1988b). Bahwa para penulis ini masih terlihat segar - setelah menonjol dalam wacana sejarah negara-negara lain di Asia Tenggara selama beberapa dekade - adalah pengingat yang gamblang tentang betapa sedikitnya historiografi Indonesia bergerak pada tahun-tahun berikutnya. Untuk melampaui mereka, sambil meningkatkan tolok ukur beasiswa historiografi, adalah tugas mendesak dan mendesak yang harus diselesaikan. -Pandangan penulis-penulis sejarah seperti Soedjatmoko, John Smail, dan J.C. van Leur, Taufik Abdullah masih menonjol dalam wacana sejarah negara di Asia Tenggara. Ini menunjukkan masih sedikitnya historiografi Indonesia yang berkembang di tahun-tahun berikutnya. Rommel Curaming Rommel Curaming adalah penerima Program ASIA Fellows (2001-2002) dan sekarang menjadi Ph.D. mahasiswa di Fakultas Studi Asia, Universitas Nasional Australia, Canberra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ASIA Fellows Program Ford Foundation (sekarang Asian Scholarship Foundation) untuk dana penelitian yang memungkinkan saya mengumpulkan data untuk menulis makalah ini. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Robert Cribb, Michael Montesano, Donna Amoroso, dan Bambang Purwanto karena telah membaca draf artikel sebelumnya dan menawarkan saran substantif dan editorial untuk perbaikan. Tentu saja, tanggung jawab atas kesalahan dalam makalah akhir adalah sepenuhnya milik saya.