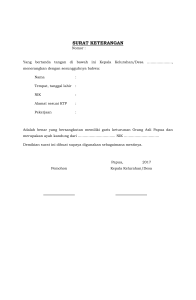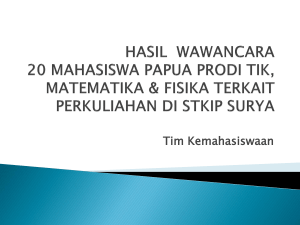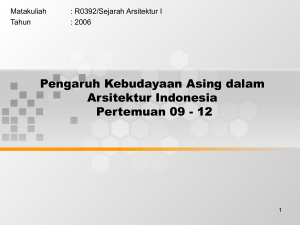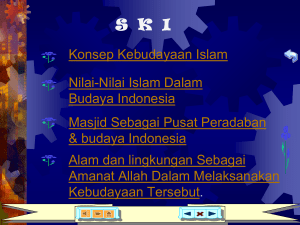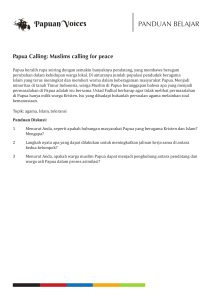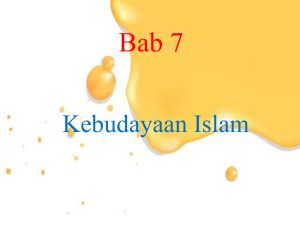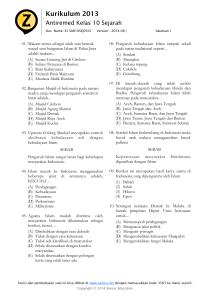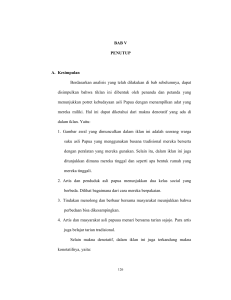Uploaded by
common.user31644
tugas jenis pemukiman berdasarkan sifatnya zahyu azari 1710003431003
advertisement

JENIS PEMUKIMAN BERDASARKAN NAMA : ZAHYU AZARI BP : 1710003431003 PRODI : T. ARSITEKTUR 1 KATA PENGANTAR Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang. Ananda panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada Ananda, sehingga Ananda bisa menyelesaikan makalah tentang Klasifikasi Kota, mata kuliah Kota dan Pemukiman Makalah ini sudah Ananda susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu Ananda menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari segala hal tersebut, Ananda sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karenanya Ananda dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata Ananda berharap semoga makalah tentang Klasifikasi Kota ini bisa memberikan manfaat maupun inspirasi untuk pembaca. Padang, Oktober 2019 Penulis 2 Daftar Isi KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... 2 JENIS PEMUKIMAN BERDASARKAN SIFATNYA ..................................................................... 4 1. PEMUKIMAN TRADISONAL ............................................................................................... 4 2. PEMUKIMAN DARURAT .................................................................................................... 11 3. PEMUKIMAN KUMUH ........................................................................................................ 13 4. PEMUKIMAN TRASMIGRASI ........................................................................................... 14 5. PEMUKIMAN REAL ESTATE (PEMUKIMAN BARU) .................................................. 18 DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................................... 21 3 JENIS PEMUKIMAN BERDASARKAN SIFATNYA 1. PEMUKIMAN TRADISONAL Perkampungan seperti ini biasa nya penduduk atau masyarakatnya masih memegang teguh tradisi lama. Kepercayaan, kabudayaan dan kebiasaan nenek moyangnya secara turun temurun dianutnya secara kuat. Tidak mau menerima perubahan perubahan dari luar walaupun dalam keadaan zaman telah berkembang dengan pesat. Kebiasaankebiasaan hidup secara tradisional yang sulit untuk diubah inilah yang akan membawa dampak terhadap kesehatn seperti kebiasaan minum air tanpa dimasak terlebih dahulu, buang sampah dan air limbah di sembarang tempat sehingga terdapat genangan kotor yang mengakibatkan mudah berjangkitnya penyakit menular. (Sumber : https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761- AR%20Bab2001.doc) Kota Tradisional Yogyakarta Lingkungan Keraton Ngayogyakarta 1. Sejarah Awal Berdirinya Kota Tradisional Yogyakarta Zaman dahulu, masyarakat Jawa khususnya masyarakat desa menyebut kota dengan istilah dalam bahasa jawa dengan sebutan nagari yang artinya kota atau keraton, karena pada awalnya kota diidentikkan dengan keraton. Dalam bahasa Sangsekerta kota dapat diartikan sebagai benteng atau pertahanan. Dalam bahasa melayu, kota diartikan sebagai benteng yang dipertahankan atas desa sebagai satu kesatuan politik,sehingga ciri-ciri kota yang menonjol adalah peran politiknya.[1] salah satukonsep tentang kota yang tercermin dipulau jawa yang terkenal dengan konsep kota tradisional yang merupakan konsep lokal dalam perkembangan kota di Indonesia. Kota tradisional adalah kota yang merupakan pusat kekuasaan tradisional, pengelolaan kota masih berada di bawah penguasa bumiputera dan belum ada campur tangan dengan bangsa asing. Konsep kota tradisional dalam konteks sejarah kota di barat yang sejajar dengan konsep kota praindustrial yaitu kota yang belum bersentuhan dengan industrialisasi. Ada kebiasaan pada zaman raja-raja, penduduk kota dan desa memberikan upeti kepada raja. Semakin banyak upeti semakin kuat financial kerajaan dan semakin banyak prasarana dibangun, demikian pula prajurit atau angkatan perangnya semakin kuat. 4 Salah satu ciri yang paling menonjol dikawasan kota tradisional, terutama Jawa adalah keberadaan keraton, Alun-alun, masjid, pasar dan tembok atau pagar keliling (benteng).dalam tatanan budaya, kota tradisional ditandai antara lain penggunaan teknologi yang masih sederhana, penggunaan teknologi ilmu pengetahuan yang terbatas, serta penggunaan sistem produksi yang masih didominasi oleh tenaga manusia dan tenaga hewan. Penggunaan ilmu pengetahuan yang terbatas ini menyebabkan proses pembangunan kota-kota tradisional memunculkan pemikiranpemikiran yang tidak rasional dan tidak bisa diterima dengan alam pikir saat ini tentang alasan dibangunnya kota tersebut. Salah satu kota tradisional di Jawa yang dalam proses pendiriannya masih berbau mitos adalah proses pendirian kota Yogyakarta oleh pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I yang tidak jauh dari mitos dan hal ramal meramal. Yogyakarta sebenarnya sudah dikenal sebelum kota Yogyakarta didirikan dan dijadikan tempat berdirinya keraton. Wilayah ini dikenal dalam babad Giyanti yang mengisahkan bahwa Sunan Amangkurat telah mendirikan Dalem diwilayah itu, yang bernama Gerjiwati oleh Pakubuwono II yang kemudian dinamakan Ayodya. Menurut cerita nenek moyang seorang kyai bernama Manganjaya memiliki sebuah buku pedoman ramalan. Dari ramalan tersebut dia menyimpulkan bahwa tempat dalam hutan beringin akan menjadi kota. Sejak saat itu dia mengumpulkan batu-batu bagi istana yang akan dibangun sebagai tanda bukti kepada raja. Namun terlepas dari ramalan tersebut kota Jogjakarta dibangun oleh mangku bumi diatas hutan beringan. Setelah perjanjian gianti ditanda tangani pada tanggal 13 februari 1755 yang menandai pembagian matara menjadi dua yaitu Yogjakarta dan surakarta yang kemudian dikawasan yogyakarta digunakan untuk membangun istana Raja serta rumah-rumah pejabat kerajaan yang kemudian dikenal dengan nama Ngayogyakarta hadinigrat dan terkenal dengan sebutan keraton Yogyakarta. Sejak didirikan pada tahun 1756 kota Yogyakarta mengalami perkembangan. Kota ini telah menjadi tempat bergabai golongan masyarakat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan selanjutnya kota Yogyakarta dipengaruhi oleh situasi kolonial, bermula dari sebuah jalan raya maka berdirilah kantor-kantor pemerintahan asing dan benteng. Kemudian muncul pemukiman Eropa club-club dan lapangan pacuan kuda. Daerah sekitar kota menjadi usah orang Eropa dalam perkebunan, pertanian terutama industri tebu. Jalan kereta dan jembatan penghubunganya banyak didirikan. Para pengrajin bumi putera mendapat 5 tempat dilingkunagn yang miskin, hal ini sejalan dengan pemerintahan asing yang merupakan bagian yang luas dalam kompleks politik, kolonial. Sehingga masa akhir abad ke-19 sampai awal abad ke 20 di Yogyakarta bertemu dua kekuatan besar yaitu kekuatan tradisional dan kolonial. Suatu proses yang menimbulkan pembaruan. 2. Struktur Kota Tradisional Yogyakarta Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Jawa dengan tipologi kota tradisional, kota ini merupakan ibukota dari Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakanpecahan kerajaan Mataram akibat ditandanganinya Perjanjian Giyanti 1755. Pangeran Mangkubumi adalah tokoh yang berperan penting dalam pendirian kota Yogyakarta. Kota ini dibangun dengan diawali pembangunan benteng kraton dengan penhuni awal adalah Sultan (Raja/Pemimpin Kerajaan), para bangsawan yaitu para staff kerajaan dan abdi dalem yaitu para pegawai kerajaan yang menghuni kawasan dalam benteng. Adapun struktur yang terdapat di kota tradisional Yogyakarta adalah sebagai berikut: Benteng Keraton (Benteng Vreedeburg): Benteng Vredeburg Yogyakarta berdiri terkait erat dengat lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Pada masa pemerintahan Belanda, benteng ini juga memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan para residen yang sedang bertugas di Yogyakarta karena kantor residen letaknya berseberangan dengan letak Benteng Vredeburg. Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia maka status kepemilikan Benteng Vredeburg juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal berdirinya benteng ini adalah milik Kraton walaupun dalam penggunaannya dihibahkan kepada Belanda (VOC). Kebangkrutan VOC pada periode 17881799 menyebabkan penguasaan benteng diambil alih oleh Bataafsche Republic (Pemerintah Belanda) dibawah Gubernur Van Den Burg sampai ke pemerintahan Gubernur Daendels. Ketika Inggris berkuasa maka benteng dibawah penguasaan Gubernur Jenderal Raffles. Status benteng sempat kembali ke pemerintahan Belanda sampai menyerahnya Belanda kepada Jepang di bulan Maret 1942. Pada tanggal 9 Agustus 1980 dengan persetujuan Sri Sultan HB IX Benteng Vredeburg dijadikan sebagai Pusat Informasi dan Pengembangan 6 Budaya Nusantara dan pada tanggal 16 April 1985 dilakukan pemugaran untuk dijadikan Museum Perjuangan, ini dibuka untuk umum pada tahun 1987. Di Luar benteng terdapat pasar tradisional Bringharjo yang letaknya berada disebelah Utara Benteng kompeni (Vreedeburg) dan satu kompleks dengan keraton. Pasar ini didrikan oleh Sultan Hamengku Buwono I. Nama pasar beringharjo ini diambil dari nama Hutan Beringin yang merupakan nama hutan cikal bakal berdirinya kota jogja. Adanya pasar ini merupakan simbol adanya aktivitas ekonomi dilingkungan keraton sebagai tempat distribusi barang dari desa ke kota serta sebagai tempat pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari hari bagi masyarakat desa dan kota. Area Pertokoan: kawasan pertokoan ini terletak di jalan Jalan yang dikenal dengan jalan malioboro, disamping jalan tersebut juga terdapat pertokoan cina yang didirikan oleh pemerintah Belanda,sehingga belakang pertokoan tersebut juga berdiri kampung pecinan. Kawasan Keraton: Kraton Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755, beberapa bulan setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti. Dipilihnya Hutan Beringin sebagai tempat berdirinya kraton dikarenakan tanah tersebut diapit dua sungai sehingga dianggap baik dan terlindung dari kemungkinan banjir. Kraton Yogyakarta dibangun oleh Pangeran Mangkubumi pada tahun 1755, beberapa bulan setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti. Dipilihnya Hutan Beringin sebagai tempat berdirinya kraton dikarenakan tanah tersebut diapit dua sungai sehingga dianggap baik dan terlindung dari kemungkinan banjir. keberadaan keraton dalam strultur kota tradisional merupakan hal yang utama, keraton Yogyakarta yang menjadi salah satu icon Jawa merupakan pusat dari budaya jawa. Tidak hanya menjadi tempat tinggal raja dan keluarganya semata, Kraton juga menjadi kiblat perkembangan budaya Jawa, sekaligus penjaga nyala kebudayaan tersebut. 7 Alun-alun: Salah satu ciri pusat kota maupun pusat pemerintahan, baik itu kerajaan maupun kabupaten ditandai dengan hamparan lapangan rumput yang cukup luas dan sepasang pohon beringin di tengahnya yang dipisahkan oleh jalan akses masuk ke kantor kabupaten yang biasanya juga menjadi kediaman dinas bupati. Lapangan inilah yang dinamakan “Alun-alun”. Namun ada perbedaan antara alun-alun keraton dengan alun-alun kabupaten (kediaman Bupati) Pada Keraton memiliki dua alun-alun, di depan dan di belakang istana. Sedangkan tempat tinggal resmi Bupati (Kabupaten) yang hanya mempunyai satu alun-alun di depan kabupaten. Kota kerajaan Tradisional dan Yogyakarta mempunyai dua buah alunalun, satu terletak di utara Keraton dan satu lagi terletak di selatan Keraton. Alun-alun Lor (utara) dikelilingi oleh bangunan di penjuru mata angin, yakni: Masjid Agung di sebelah Barat, bangunan keraton di sebelah Selatan, pasar di sebelah Utara. Hal yang menarik adalah keberadaan penjara pada sisi sebelah Timur. Konon letak penjara ini didasarkan pada pemikiran agar para terpidana segera menyadari kekeliruannya dan bertobat, karena dipenjara berseberangan dengan tempat ibadah. Disisi lain alun-alun terdapat jalan masuk terdapat di tengah-tengah membelah alun-alun. Kemudian pada sisi kanan dan kiri selalu ditanami pohon beringin yang berpagar, karena itu masyarakat (di Jawa) menyebutnya Ringin Kurung, dan biasanya Jayandaru (kemenangan) sebagian masyarakat dikeramatkan dan Kyai serta diberi nama Kyai Dewandaru (keluhuran). Sedangkan menyebutnya Ringin Kembar. Ringin Kembar mengandung makna atau pesan simbolik bahwa Raja atau Bupati bukan sekedar penguasa melainkan juga pengayom (pelindung) bagi rakyatnya. Alun-alun Kidul (Selatan) Keraton biasanya menyatu berada di dalam benteng (tembok tinggi) sebagai salah satu sistem pertahanan tempo dulu, Pada Alun-alun Kidul biasanya diselenggarakan gladen, latihan perang bagi para prajurit kerajaan secara berkala. Pada saat tertentu gladen ini digelar menjadi tontonan masyarakat. 8 Kampung kauman Kauman adalah sebuah kampung yang terletak di KElurahan Ngupasan yang terletak di kecamatan Gondomanan, Yogyakarta. di selatan Malioboro dan di utara Kraton Nyayogyakarta. Sebelah utara kampung ini dibatasi Jalan K.H.A.Dahlan, sebelah selatan dibatasi Jalan Kauman, sebelah timur dengan batas Jalan Pekapalan dan Jalan Trikora, sementara di sebelah barat dibatasi Jalan Nyai Ahmad DAhlan atau dulu dikenal dengan Jalan Gerjen. Di kampung Kauman ini terletak MAsjid Gede yang terkenal. Lapangan masjid ini selalu digunakan untuk acara tahunan grebekan pada setiap penyelenggaraan Sekaten oleh pihak keraton Yogyakarta. Dahulu merupakan tempat tinggal para abdi dalem pametakan atau Penghulu kraton yaitu abdi dalem/pegawai kraton yang mengurusi bidang keagamaan Islam di lingkungan Kraton Ngayogyakarta hadiningrat Kauman Yogyakarta dikenal sebagai basis dari organisasi Islam Muhammadiyah, karena di kampung inilah Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan. Selain K.H.Ahmad Dahlan, tokoh lain yang berasal dari kampung Kauman adalah Ki BAgus HAdikusuma. Konon, karena fanatisnya pada setiap penyelenggaraan pemilu PArtai Amanat NAsional selalu menang besar di sini. Selain itu tempat ini juga merupakan Komunitas terbesar bagi keturunan Arab di DAerah IStimewa Yogyakarta. Masjid Agung Masjid Agung Keraton Yogyakarta adalah bangunan masjid yang didirikan di pusat (ibukota) kerajaan. Bangunan ini didirikan semasa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana I. Perencanaan ruang kota Yogyakarta konon didasarkan pada konsep taqwa. Oleh karenanya, komposisi ruang luarnya dibentuk dengan batas-batas berupa penempatan lima masjid kasultanan di empat buah mata angin dengan Masjid Agung sebagai pusatnya. Sedangkan komposisi di dalam menempatkan Tugu (Tugu Pal Putih) - Panggung Krapyak sebagai elemen utama inti ruang. Komposisi ini menempatkan Tugu Pal PutihKeraton-Panggung Krapyak dalam satu poros. Bangunan Masjid Agung Keraton Yogyakarta berada di areal seluas kurang lebih 13.000 meter persegi. Areal tersebut dibatasi oleh pagar tembok 9 keliling. Pembangunan masjid itu sendiri dilakukan setelah 16 tahun Keraton Yogyakarta berdiri. Pendirian masjid itu sendiri atas prakarsa dari Kiai Pengulu Faqih Ibrahim Dipaningrat yang pelaksanaannya ditangani oleh Tumenggung Wiryakusuma, seorang arsitek keraton. Pembangunan masjid dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah pembangunan bangunan utama masjid. Tahap kedua adalah pembangunan serambi masjid. Setelah itu dilakukan penambahanpenambahan bangunan lainnya. Bangunan Masjid Agung terdiri dari beberapa ruang, yaitu halaman masjid, serambi masjid, dan ruang utama masjid. Halaman masjid terdiri atas halaman depan dan halaman belakang. Halaman masjid merupakan ruangan terbuka yang terletak di bagian luar bangunan utama dan serambi masjid. Halaman ini dibatasi oleh tembok keliling. Sedang halaman belakang masjid merupakan makam Nyi Achmad Dahlan dan beberapa makam lainnya. Ada lima buah pintu yang dapat digunakan untuk memasuki halaman masjid. Dua buah pintu terletak di sisi utara dan selatan. Sedangkan pada sisi timur terdapat sebuah pintu yang berfungsi sebagai pintu gerbang utama. Bentuk pintu gerbang yang sekrang ini adalah semar tinandu dengan atap limasan. Pada kedua sisi gapura ini terdapat dua bangunan yang disebut bangsal prajurit. Pintu gerbang dihubungkan dengan sebuah jalan yang membelah halaman depan menjadi dua bagian. Jalan ini diapit dua buah bangunan yang dinamakan pagongan. Bangunan serambi masjid dipisahkan dari halaman masjid. Bangunan pemisahan itu berupa pagar tembok keliling dengan lima buah pintu masuk. Pada sisi timur terdapat tiga buah pintu dan satu buah pada sisi utara serta selatan. Bangunan serambi ini juga dikelilingi dengan sebuah parit kecil (kolam) pada sisi utara, timur, dan selatan. Tempat/bangunan yang digunakan untuk berwudhu terdapat di sebelah utara dan selatan serambi. Bangunan serambi masjid berbentuk denah empat persegi panjang. Serambi didirikan di atas batur setinggi satu meter. Pada serambi ini terdapat 24 tiang berumpak batu yang berbentuk padma. Umpak batu tersebut berpola hias motif pinggir awan yang dipahatkan. Atap serambi masjid berbentuk limasan. Pada sebelah barat serambi ini berdiri bangunan Masjid Agung yang merupakan ruang utama salat. Ruangan masjid berbentuk denah bujur sangkar. Bangunan ,asjid didirikan di atas batur setinggi 1,7 meter. Pada sisi utara masjid 10 terdapat gedung pengajian, kamar mandi, dan WC untuk pria. Sedang yang diperuntukkan bagi wanita berada pada sisi selatan. Mihrab berada pada dinding sebelah barat. Pada dekat mihrab terdapat sebuah mimbar dan maksurah, masing-masing terletak di sebelah utara dan selatan mihrab. Atap tajug bertumpang tiga menutupi ruang utama Masjid Agung ini. Pada puncak atap terdapat mustaka. Ketiga atap masjid ini didukung oleh dinding tembok pada keempat sisi ruangan dan tiang berjumlah 36 buah. Tiang-tiang tersebut berpenampang bulat tanpa hiasan (polos). Ketiga puluh enam tiang tersebut terdiri atas empat buah saka guru, 12 saka rawa, dan 20 saka emper. (Sumber : http://sariaerahmawati.blogspot.com/2013/06/struktur-kota- tradisional.html) 2. PEMUKIMAN DARURAT Jenis perkampungan ini biasanya bersifat sementara (darurat) dan timbulnya perkampungan ini karena adanya bencana alam. Untuk menyelamatkan penduduk dari bahaya banjir maka dibuatkan perkampungan darurat pada daerahh/lokasi yang bebas dari banjir. Mereka yang rumahnya terkena banjir untuk sementara ditampatkan dipernkampungan ini untuk mendapatkan pertolongan baantuan dan makanan pakaian dan obat obatan. Begitu pula ada bencana lainnya seperti adanya gunung berapiyang meletus dan lain lain. Daerah pemukiman ini bersifat darurat tidak terencana dan biasanya kurang fasilitas sanitasi lingkungan sehingga kemungkina penjalaran penyakit akan mudah terjadi. (Sumber : https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761- AR%20Bab2001.doc) Jakarta Darurat Air Bersih Hujan belum jua menyapa Kampung Nelayan, di Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Lebaran. Untuk beroleh air air bersih, ada keluarga yang harus membeli air jerikenan sampai Rp600.000 sebulan. Jika segalon air Aqua berharga Rp18.500, uang untuk air bersih Rp600.000 yang tak hanya untuk masak itu bisa dibelikan 32 galon. 11 Merujuk tarif PAM Jaya untuk rumah tangga sederhana di grup tarif dua, harga 20 meter kubik air minum adalah Rp1.575. Dengan Rp600.000 mestinya konsumen bisa menyimpan 7.692 meter kubik air minum untuk sebulan. Dengan catatan: itu perhitungan gampangan. 12 Nama resminya memang air minum. Terjemahan dari drinking water, yang mestinya bisa langsung diminum dari keran supaya hotel tak perlu pasang maklumat peringatan di wastafel. Namun air minum pula yang jadi nama perusahaan daerah dan patokan tarif. Kita lebih mengenal air bersih — belum tentu layak minum dalam keadaan mentah. "Kampung ramai kalau hujan. Loyang, panci, ember, baskom, sampai sendok kalau bisa kita keluarin," ujar Aisyah, seorang warga, setengah berkelakar. (Sumber : https://beritagar.id/artikel/infografik/infografik-darurat-air-bersih-di-ibu-kota) 3. PEMUKIMAN KUMUH Jenis pemukiman ini biasanya timbul akibat adanya urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari kampung (pedesaan) ke kota. Umumnya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, mereka bekerja di toko-toko, di restoran-restoran, sebagai pelayan dan lain lain. sulitnya mencari kerja di kota akibat sangat banyak pencari kerja, sedang tempat bekerja terbatas, maka banyak diantara mereke manjadi orang gelandangan, Di kota umumnya sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak hal ini karena tidak terjangkau oleh penghasilan (upah kerja) yang mereka dapatkan setiap hari, akhirnya meraka membuat gubuk-gubuk sementara (gubuk liar). (Sumber : https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761- AR%20Bab2001.doc) Kawasan Kali Ciliwung, Jakarta Kawasan ini terdapat di jantung kota Jakarta. Kali yang mengalir membelah sebagian kota Jakarta ini memang sudah terkenal akan kekumuhannya yang tidak bisa diselesaikan hingga kini. Musibah banjir tidak henti-hentinya menyambangi warga 13 bantaran kali ciliwung dari tahun ke tahun. Tidak hanya media lokal, beberapa kali media internasional menyoroti kekumuhan dan buruknya tata lingkungan di tempat ini. Pemandangan di bantara kali Ciliwung memang sangat kontras dengan kota Jakarta yang terus menerus membangun gedung dan pusat perbelanjaan mewah. Hampir semua bantara Ciliwung ditimbun oleh tumpukan sampah raksasa. Sungai yang seharusnya memiliki lebar 50 meter, kini hanya menjadi selebar 8 meter akibat tumpukan sampah tersebut. Tidak heran, tempat ini menjadi tempat paling kumuh di Indonesia. (Sumber : https://www.boombastis.com/tempat-paling-kumuh/14104) 4. PEMUKIMAN TRASMIGRASI Jenis pemukiman semacam ini di rencanakan oleh pemerintah yaitu suatu daerah pemukiman yang digunakan untuk tempat penampungan penduduk yang dipindahkan (ditransmigrasikan) dari suatu daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang/kurang penduduknya tapi luas daerahnya (untuk tanah garapan bertani bercocok tanam dan lain lain) disamping itu jenis pemukiman merupakan tempat pemukiman bagi orang-orang (penduduk) yang transmigrasi akibat di tempat aslinya seiring dilanda banjir atau sering mendapat gangguan dari kegiatan gunung berapi. Ditempat ini mereka telah disediakan rumah, dan tanah garapan untuk bertani (bercocok tanam) oleh pemerintah dan diharapkan mereka nasibnya atau penghidupannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan di daerah aslinya (Sumber : https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761- AR%20Bab2001.doc) Transmigrasi Orang Jawa ke Papua Sejarah Transmigrasi Orang Jawa ke Papua 14 Pemerintah Orde Baru dianggap secara sepihak menetapkan standar dan cara hidup orang Jawa di Papua Barat. Niccolò Machiavelli menuliskan dalam bukunya yang termasyur, The Prince, bahwa pemindahan penduduk adalah salah satu cara terbaik untuk mengontrol sebuah wilayah. Cara ini dinilai lebih efektif dan murah ketimbang mengirimkan pasukan untuk menjaga wilayah koloni. Teori Machiavelli sangat tepat menggambarkan kesulitan orang-orang Belanda menjamah tanah Papua sejak paruh kedua abad ke-19. Pemerintah kolonial tidak memiliki cukup dana untuk melakukan ekspansi ke ujung timur Nusantara, kendati mendapat tekanan agar segera memperluas wilayah jajahan. Guna mengatasi hal tersebut, maka dimulailah program kolonisasi dengan memindahkan penduduk dari Jawa, pusat pemerintahan kolonial, ke Papua. Berdasarkan catatan H.W. Bachtiar dalam “Sejah Irian Jaya” yang terangkum dalam buku Irian Jaya: Membangun Masyarakat Majemuk (1993, hlm. 56) hasil suntingan Koentjaraningrat, diketahui pada 1903, asisten residen Belanda di Merauke ditugasimempersiapkan daerahnya sebagai tujuan program kolonisasi. Dua tahun kemudian, misionaris Katolik turut serta dalam program ini dengan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan keterangan mengenai bahasa dan adat istiadat penduduk lokal. Papua bukan satu-satunya daerah tujuan program kolonisasi pemerintah Hindia Belanda. Pada bulan November 1905, Asisten Residen Sukabumi H.G. Heyting turut memberangkatkan sebanyak 155 kepala keluarga asal Jawa ke Gedong Tataan, Lampung. Mereka dikenal sebagai orang-orang Jawa pertama yang berpindah atas sponsor pemerintah. Catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dalam Transmigrasi Masa Doeloe, Kini dan Harapan Kedepan (2015) menunjukan bahwa program rintisan pemerintah kolonial kemudian dihidupkan kembali pada 12 Desember 1950. Nama transmigrasi dipilih pemerintah Indonesia karena dinilai lebih nasionalis dan bebas dari kesan penjajahan. Namun, hakikatnya, pemerintah Indonesia hanya meneruskan warisan kebijakan orang-orang Belanda mengurai kepadatan penduduk di Jawa ke pulau seberang. Adapun daerah-daerah tujuan transmigrasi pertama pemerintah RI kala itu lebih sering membidik wilayah-wilayah dengan potensi pertanian. Namun, Papua Barat bukan salah satunya. 15 Papua Barat, seperti yang dituturkan Loekman Soetrisno dalam kumpulan tulisan Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 (1985, hlm. 118), baru dijadikan tujuan transmigrasi pemerintah pada 1964. Alasannya: pemerintah merasa sudah tidak ada lagi wilayah yang lebih ideal dijadikan tujuan transmigrasi ketimbang Papua Barat. Transmigrasi Di Tengah Konflik Papua Menjadikan Papua sebagai daerah tujuan transmigrasi pada 1964 menimbulkan beragam tanya. Perlu diketahui sejak 1961, pemerintah RI sedang gencar-gencarnya melakukan perlawanan terhadap Belanda yang ingin membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia. Keinginan untuk menggagalkan kekuasaan Belanda di atas tanah Papua kemudian memaksa Sukarno mengeluarkan Trikora yang isinya dengan tegas menentang pembentukan negara boneka Papua. Pada 1963, Menteri Luar Negeri Soebandrio mengatakan bahwa orang Jawa tidak akan mengkolonisasi Papua Barat. Lebih jauh ia merinci, Papua tidak akan dijadikan tujuan program transmigrasi yang sudah digalakkn pemerintah Indonesia sejak 1950-an. Demikian ditulis John Saltford dalam The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969 (2003, hlm. 77). Meskipun begitu, masih mengutip Saltford, tidak bisa dipungkiri orang-orang Jawa sudah banyak yang mendiami Papua Barat pada saat itu. Selain berkat program kolonisasi 60 tahun silam, kedatangan mereka diakomodasi oleh kelompok-kelompok partikelir Belanda sebelum kemerdekaan. Setidaknya ada sekitar 16.000 orang dari Jawa dan Sulawesi yang sudah berdiam di beberapa kota utama Papua. Satu tahun kemudian, janji Soebandrio tinggal omong kosong. Saltford mengutip surat pernyataan perwakilan diplomatik Australia yang menyebut gelombang perpindahan penduduk dari Jawa ke Papua Barat. Laporan lain yang dikutip Saltford menyatakan mereka menemui beragam kesulitan, khususnya masalah pengadaan lahan dan rumah. Hal serupa juga dipaparkan dalam buku Pananganan Program Transmigrasi di Irian Jawa: Suatu Pendekatan Kesejahteraan dan Kemanusiaan (1984, hlm. 4). Menurut isinya, pada 1964, Kodam Cendrawasih menyaksikan kedatangan transmigran dari Jawa ke Jayapura dan Merauke. Jumlahnya sekitar 1.000 jiwa yang terbagi menjadi 267 kepala keluarga. 16 Mengindonesiakan Papua Konsensus dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 secara resmi memasukkan Papua Barat ke dalam Indonesia. Namun, kondisi yang berangsur baik ini disusul permasalahan baru. Gelombang transmigrasi terarah dalam jumlah tinggi melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) justru memicu kecemburuan sosial. Esther Heidbüchel dalam bukunya The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches (2007, hlm. 44) menyebut sebagian rakyat setempat menganggap pemerintah pusat berusaha merebut tanah mereka dengan cara mengindonesiakan tanah Papua berserta isinya melalui program transmigrasi. Pemerintah Orde Baru, lanjut Heidbüchel dianggap secara sepihak menetapkan standar hidup berdasarkan kebudayaan dan cara hidup orang Jawa. Buku-buku sekolah, tata cara menanam padi, bahkan pembangunan rumah semuanya mengikuti apa yang ada di Jawa. Belum lagi, transmigran asal Jawa yang tiba di wilayah rintisan di Papua Barat selalu mendapat posisi yang lebih unggul ketimbang masyarakat lokal. “Transmigran umumnya bermukim di kota-kota baru yang berbatasan dengan Papua Nugini, sementara mereka yang pindah ke Papua atas kesadaran sendiri lebih banyak berdiam di perkotaan. Mereka adalah tenaga-tenaga yang disukai untuk jabatan di kantor-kantor dan perusahaan,” tulis Heidbüchel. Kembali mengutip catatan Loekman Soetrisno, sejak 1969, jumlah orang Jawa yang berpartisipasi dalam program transmigrasi jumlahnya selalu naik. Melalui Repelita I sampai II, pemerintah Orde Baru tercatat berhasil menempatkan tidak kurang dari 41.701 transmigran yang terbagi menjadi 9.916 kepala keluarga (hlm. 119). Dalam Repelita IV yang dimulai pada 1984, jumlah tersebut melompat menjadi 137.800 kepala keluarga. Sebagian besar transmigran datang dari etnis Jawa, Buton, Bugis, dan Makassar. Untuk menghidupi pendatang sebanyak itu, harus membuka lahan seluas 689.000 ha. Sejak Januari 1985, sejumlah akademisi secara halus mulai mendesak pemerintah untuk mengurangi jumlah transmigran ke wilayah Papua Barat. Tim gabungan dari P3PK Universitas Gadjah Mada dan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta sempat mengadakan peninjauan lokasi dan seminar yang membahas permasalahan tersebut. Akan tetapi, Menteri Transmigrasi Martono menolak usulan tim gabungan. 17 “Pemerintah tidak akan mengurangi pengiriman transmigrasi ke Irian Jaya, bahkan akan meningkatkan namun pelaksanaannya akan dilakukan lebih hati-hati untuk menghindarkan konflik sosial antara pendatang dengan penduduk asli,” kata Martono, seperti dikutip Sabam Siagian dalam “Kita dan Papua Nugini: Masa Depan Bersama” dari Buletin Antara (25/2/1985). Tulisan Sabam Siagian dalam buku kenang-kenangan Ali Moertopo, Sekar Semerbak (1985, hlm. 157), itu juga menyinggung transmigrasi dipercaya dapat mendorong tahap kemajuan penduduk Papua Barat, sesuai dengan tujuan dari program transmigrasi itu sendiri, yakni memeratakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengukuhkan persatuan. Program transmigrasi orang Jawa ke Papua Barat kenyataannya tidak bisa jauh dari nama Soeharto. Satu tahun setelah Presiden RI ke-2 itu lengser, program transmigrasi ini efektif dihentikan. Pemerintah Provinsi Papua menyebut gelombang transmigran terakhir yang ditempatkan di wilayah itu terdiri dari 78.000 kepala keluarga. (Sumber : https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs) 5. PEMUKIMAN REAL ESTATE (PEMUKIMAN BARU) Pemukiman semacam ini direncanakan pemerintah dan bekerja sama dengan pihak swasta. Pembangunan tempat pemukiman ini biasanya di lokasi yang sesuai untuk suatu pemukiman (kawasan pemukiman). Ditempat ini biasanya keadaan kesehatan lingkunan cukup baik, ada listrik, tersedianya sumber air bersih , baik berupa sumur pompa tangan (sumur bor) atau pun air PAM/PDAM, sistem pembuangan kotoran dan iari kotornya direncanakan secara baik, begitu pula cara pembuangan samphnya di koordinir dan diatur secara baik. Selain itu ditempat ini biasanya dilengakapi dengan gedung-gedung sekolah (SD, SMP, dll) yang dibangun dekat dengan tempat tempat pelayanan masyarakat seperti poskesdes/puskesmas, pos keamanan kantor pos, pasar dan lain lain. Jenis pemukiman seperti ini biasanya dibangun dan diperuntukkan bagi penduduk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Rumah-rumah tersebut dapat dibeli dengan cara di cicil bulanan atau bahkan ada pula yang dibangun khusus untuk disewakan. contoh pemukiman spirit ini adalah perumahan IKPR-BTN yang pada saat sekarang sudah banyak dibangun sampai ke daerah-daerah. 18 Untuk di daerah–daerah (kota) yang sulit untuk mendapatkan tanah yang luas untuk perumahan, tetapi kebutuhan akan perumahan cukup banyak, maka pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta membangun rumah tipe susun atau rumah susun (rumah bertingkat) seperti terdapat di kota metropolitan DKI Jakarta. Rumah rumah seperti ini ada yang dapat dibeli secara cicilan atau disewa secara bulanan. (Sumber : https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761- AR%20Bab2001.doc) Profil Umum Perencanaan Kawasan Permukiman Kota Baru Berdasarkan amanat Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa arah kebijakan pembangunan wilayah perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019: (i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; (iii) Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana; (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; serta (v) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan. STRATEGI PEMBANGUNAN Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni pada kawasan metropolitan dan kota sedang di luar Jawa termasuk kawasan perbatasan, kepulauan, dan pesisir dengan: (a) Menyediakan sarana dan prasarana dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kotanya; (b) Meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya; (c) Mengembangkan perumahan sesuai dengan tipologinya; (d) Mengembangkan sistem transportasi publik terintegrasi dan multimoda sesuai dengan tipologi dan kondisi geografisnya; (e) Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana ekonomi sektor perdagangan dan jasa termasuk pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (f) Meningkatkan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota. 19 PENGEMBANGAN KOTA BARU Pembentukan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan khususnya di luar Pulau Jawa – Bali merupakan sesuatu yang mendesak dan harus dilaksanakan sebagai keberpihakan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi. Kawasan kota baru sebagai bagian dari kawasan permukiman perkotaan harus direncanakan, dilaksanakan serta dikelola dengan baik dengan memasukkan unsurunsur kota hijau dan kota cerdas, yang pada gilirannya dapat mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam pengaturan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan dalam hal pengelolaan kawasan permukiman terutama kawasan perkotaan perlu mengambil langkah nyata dengan kegiatan perencanaan kawasan permukiman kota baru yang mengadaptasi konsepsi kota hijau dan kota cerdas dalam mendukung terwujudnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan. (Sumber : http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/kotabaru) Kota Baru Pontianak Secara umum Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang luasnya mencapai 10.782 ha, secara administatif dibagi menjadi 6 kecamatan, 29 kelurahan, 534 Rukun Warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT). Kota Baru Pontianak terdiri dari 4 kecamatan dan 10 kelurahan dengan total luasan mencapai 740, 34 Ha. (Sumber : http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/profilkotabaru/1) 20 DAFTAR PUSTAKA https://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2DOC/2015-1-00761AR%20Bab2001.doc http://sariaerahmawati.blogspot.com/2013/06/struktur-kota-tradisional.html https://beritagar.id/artikel/infografik/infografik-darurat-air-bersih-di-ibu-kota https://www.boombastis.com/tempat-paling-kumuh/14104 https://tirto.id/sejarah-transmigrasi-orang-jawa-ke-papua-egJs http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/kotabaru http://sim.ciptakarya.pu.go.id/kotabaru/site/profilkotabaru/1 21