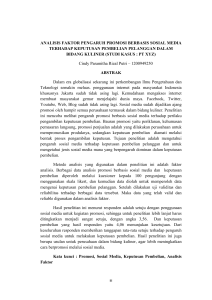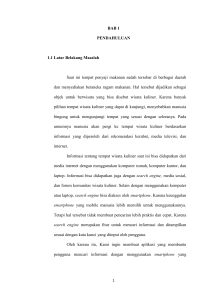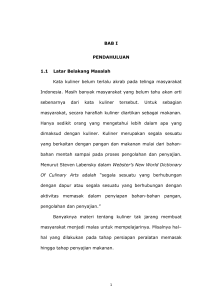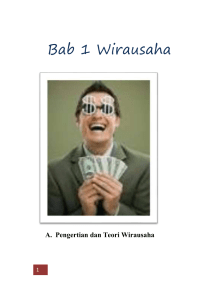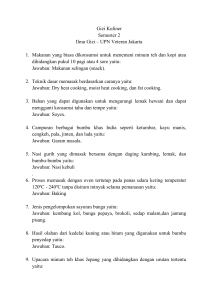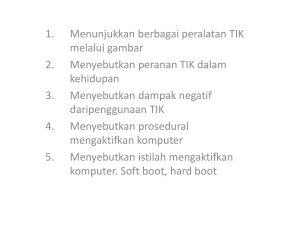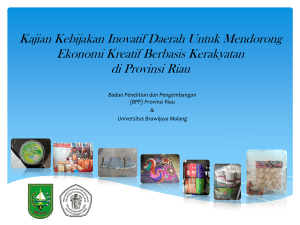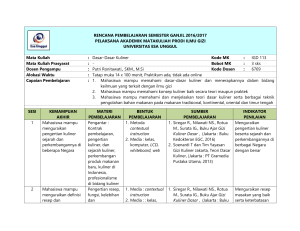BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan Pada awalnya
advertisement

BAB VI PENUTUP 6.1. Kesimpulan Pada awalnya, gudeg merupakan makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang tidak berbeda dengan makanan tradisional lainnya. Hal yang membuat gudeg menonjol adalah mudahnya gudeg ditemui dan dikonsumsi. Seiring dengan berkembangnya waktu, gudeg kini telah memiliki status sebagai ikon kuliner di Yogyakarta. Sementara itu, konsumsi gudeg oleh masyarakat Yogyakarta pun berkembang tak lagi sekedar konsumsi nilai guna dalam keseharian. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, tampak bahwa perjalanan gudeg menjadi ikon kuliner tidak terjadi begitu saja. Globalisasi memiliki peran penting dalam kemunculan gudeg sebagai ikon kuliner. Meski globalisasi mengakibatkan serbuan kuliner dari belahan dunia lain, globalisasi juga membuka ceruk pasar baru bagi kuliner-kuliner tradisional. Begitu pula yang terjadi pada gudeg sebagai materi budaya di Yogyakarta. Meningkatnya posisi gudeg juga disebabkan oleh narasi-narasi yang terbangun melalui memori para perantau yang pernah tinggal di Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta itu sendiri. Status gudeg sebagai ikon kuliner di Yogyakarta ini kemudian dilanggengkan. Gudeg kemudian dikaitkan dengan citra-citra seperti tradisional, Yogyakarta hingga sakral. Untuk mendukung citra-citra ini, estetisasi dilakukan oleh berbagai pihak. Disadari maupun tidak, estetika ini juga ikut 128 melanggengkan status gudeg sebagai ikon kuliner di Yogyakarta. Meski begitu, estetika pada gudeg pun tidak dapat melanggar “standar” gudeg yang telah dimengerti oleh masyarakat Yogyakarta. Estetika pada gudeg juga dilakukan dengan memadukannya dengan berbagai kuliner internasional sebagai usaha diferensiasi produk kuliner. Selain itu, padu-padan gudeg dengan kuliner asing ini juga untuk memperkenalkan gudeg sebagai ikon kuliner di Yogyakarta, kota di mana produk dia berada. Posisi gudeg sebagai ikon kuliner menjadikan masyarakat Yogyakarta tidak lagi mengonsumsinya hanya sebagai makanan subsisten. Masyarakat Yogyakarta kini mengonsumsi nilai-nilai tanda yang terkandung di dalam gudeg. Sesuai dengan pemikiran Baudrillard, gudeg kini telah menjadi obyek yang “dikonsumsi” karena tanda-tanda yang terkandung di dalamnya. Terkait dengan gudeg yang kerap ditampilkan sebagai suguhan, konsumsi gudeg ini berkembang menjadi suatu bentuk komunikasi. Baudrillard menjelaskan bahwa konsumsi dapat menjadi sistem komunikasi dan pertukaran, karena tanda dikirim, diterima, dan diciptakan secara berkesinambungan – sebagai bahasa (Baudrillard, 1998: 94). Untuk mendukung konsumsi sebagai ikon kuliner ini, gudeg pun berubah menjadi hiper-realitas. Dari sudut pandang Baudrillard, gudeg tidak lagi merupakan hal yang nyata, melainkan merupakan bentuk simulasi. Dalam simulakra orde ketiga ini, gudeg pun menjadi sebuah konsep yang dibangun atas tanda-tanda. Simulasi kemudian menjadi “yang nyata” untuk mengamankan yang nyata itu sendiri, namun dengan melakukan hal ini, justru menggantikan yang nyata dengan hiper-real 129 (Pawlett, 2007: 114). Gudeg pun mengalami proses menjadi hiper-real, ketika rujukan pada “yang nyata” tidak stabil dan tanda-tanda “disuntikkan” ke dalam konsep gudeg agar dapat menghadirkan “gudeg asli Yogyakarta”. Selain itu, masyarakat Yogyakarta juga mengonsumsi gudeg sebagai bentuk rekreasi. Di posisi ini, bentuk konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta pun tak jauh berbeda dengan bentuk konsumsi wisata, di mana gudeg menjadi salah satu dari banyak varian kuliner yang dapat dinikmati untuk rekreasi. Rasa penasaran dari gudeg yang didapatkan melalui aneka jalur informasi menjadikan konsumen tergerak untuk memuaskan rasa penasaran atas perbedaan tersebut. Baudrillard berargumen bahwa personalisasi ini berdasar pada tanda-tanda (Baudrillard, 1998: 91). Personalisasi pun muncul atas perbedaan-perbedaan yang ada. Terlepas hal di atas, dari studi mengenai gudeg ini didapat pula kesimpulan bahwa konsumsi gudeg juga kegiatan sosial, di mana jarang dilakukan sebagai aktivitas personal. Dalam konsumsi sebagai nilai tanda, gudeg biasanya dikonsumsi bersama tamu dari luar kota yang tidak mengenal, tidak biasa, atau jarang mengonsumsi gudeg. Sementara, dalam konsumsi rekreasional, biasanya gudeg dikonsumsi bersama kerabat atau teman yang merupakan satu “kelompok” atau “komunitas”, di mana mereka nyaman untuk bersantai bersama. Sesuai pandangan Baudrillard, nilai tanda dan perbedaan yang terkandung dalam komoditi yang dikonsumsi, terkait erat dengan kelompok sosial. Di satu sisi, dapat menyatukan namun di sisi lain juga dapat membedakan status dan kelompok. 130 Pola-pola konsumsi gudeg yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta ini turut membuat gudeg menjadi populer. Sebagai materi budaya sekaligus ikon kuliner di Yogyakarta, gudeg seakan-akan harus diperkenalkan secara terus-menerus dan dilibatkan pada berbagai acara selebrasi. Dari sini, posisi gudeg sebagai bagian dari industri pariwisata turut berkembang. Bagi masyarakat Yogyakarta pun gudeg dikonsumsi sebagai hidangan rekreasional dan menjadi bagian dari kehidupan modern. 6.2. Saran Makanan adalah bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Studi mengenai gudeg dan konsumsinya ini hanya merupakan bagian kecil dari bidang kuliner yang dapat diteliti dari sudut pandang antropologis. Terangkatnya status gudeg menjadi materi budaya sekaligus ikon kuliner di Yogyakarta memunculkan bentuk-bentuk relasi baru antara masyarakat Yogyakarta dengan gudeg itu sendiri. Ini menjadikan gudeg memiliki posisi baru dalam budaya kuliner di Yogyakarta. Terkait dengan masih sedikitnya penelitian antropologis yang berhubungan dengan kuliner Indonesia, gudeg sebagai makanan tradisional masih memiliki potensi lebih untuk diteliti. Penelitian masih dapat dilakukan dengan melihat gudeg dari perspektif-perspektif yang berbeda dengan perspektif yang telah digunakan di penelitian ini. 131