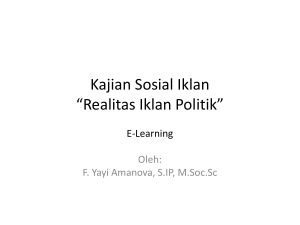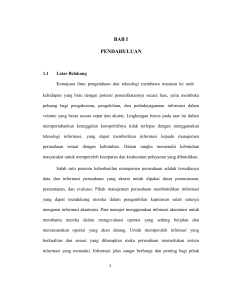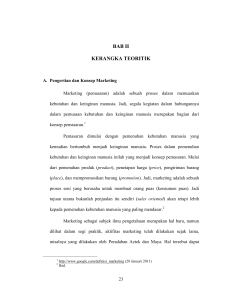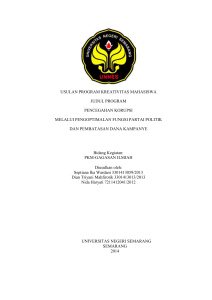(ber)politik uang - ePrints Sriwijaya University
advertisement

(BER)POLITIK UANG Alamsyah Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsri & penggiat Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Unsri FISIP Universitas Sriwijaya Pemilu legislatif 2014 dalam hitungan hari. Potret diri calon anggota DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPD, dan DPR RI bertebaran di pelosok negeri. Mereka menebar slogan dan janji agar para pemilih bersimpati. Tetapi, para caleg harus ekstra hatihati. Sebab, para pemilih sudah mencoblos berkali-kali. Para pemilih tidak belajar dari teori, tetapi belajar dari eksperimentasi. Salah satu temuan eksperimentasi para pemilih adalah opini bahwa banyak caleg tidak memenuhi janji. Begitu para caleg terpilih, mereka lari. Para pemilih merasa dibohongi. Peristiwa ini bukan sekali, tetapi berkali-kali. Maka, tak mengherankan jika banyak para pemilih dalam Pemilu legislatif 2014 merubah persepsi mereka tentang relasi politisi-pemilih. Para pemilih tetap membuka komunikasi dengan politisi, meski isinya bukan sekedar narasi yang cepat basi. Para pemilih seringkali menuntut para caleg agar menutup proses komunikasi dengan bukti sebagai tanda komitmen diri. Dari sudut pandang politisi, tidak semua tuntutan para pemilih bisa segera dipenuhi. Sebab, ada tuntutan para pemilih yang manusiawi, tetapi banyak juga yang tidak manusiawi. Semua ini muncul karena pemahaman para pemilih tentang negara, pemerintah, dan sistem politik sangat bervariasi. Sebetulnya, para politisi dari beragam parpol sangat senang jika para pemilih bisa didekati hanya dengan dialog dan diskusi. Tetapi, rakyat Indonesia belum sampai pada titik ini. Butuh beberapa generasi untuk sampai pada titik ini. Pertanyaanya, mengapa situasi negeri kita seperti ini? Saya coba berargumentasi terhadap persoalan ini. Saya ingin mengatakan bahwa menerima dan memberi adalah sesuatu yang manusiawi. Tindakan take and give yang dilandasi prinsip resiprokal hampir bisa ditemukan di seluruh peradaban manusia. Bahkan, syurga dan neraka yang dijanjikan Tuhan dalam beragam kitab suci, diatur dengan mekanisme take and give dan resiprokal. Jika patuh dengan Tuhan, maka syurga. Jika tidak patuh dengan Tuhan, maka neraka. Dalam sistem demokrasi, prinsip take and give juga menyelimuti keseluruhan proses demokrasi itu sendiri. Para pemilih yang memilih parpol/kandidat tertentu dalam pemilu berharap agar mereka dapat memproduksi beragam kebijakan yang pro-pemilih. Jika mereka tidak memenuhi hal ini, maka para pemilih akan memilih parpol/kandidat lainnya di pemilu yang akan datang. Proses take and give menjadi salah menurut hukum positif dan etika demokrasi ketika ia didefenisikan secara dangkal sebagai membeli suara (vote buying), baik dengan mata uang maupun dengan barang. Mengapa membeli suara itu salah? Karena ia mencederai demokrasi dan melanggar hak asasi manusia yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Bahkan, Tuhan sendiri pun menghormati kebebasan manusia untuk memilih. Jika tidak ada paksaan dalam agama, maka tidak ada paksaan dalam demokrasi. Meskipun transaksi jual beli dilandasi prinsip kepercayaan, suka sama suka, tetapi ia membuka peluang terjadinya unsur pemaksaan. Sebab, dalam transaksi jual beli terjadi mekanisme peralihan hak milik. Jika seorang penjual X menjual barang Y kepada pembeli Z, Dimuat di SKH Sumatera Ekspress, 25 Februari 2014 maka barang Y menjadi hak milik pembeli Z. Jika barang Y yang sudah dibeli Z tidak diserahkan penjual X, maka pembeli Z sah menurut hukum positif untuk melakukan tindakantindakan pemaksaan terhadap penjual X. Kembali ke pertanyaan “mengapa situasi negeri kita seperti ini”, maka yang salah itu bukan prinsip take and give yang sudah given. Sebaliknya, yang keliru itu adalah serangkaian tindakan memberi (give) secara sistemik yang dilakukan lembaga-lembaga politik di negeri ini, terutama eksekutif, legislatif, dan partai politik. Di antara ketiga lembaga ini, parpol menjadi pihak yang paling berdosa. Sebab, orang-orang yang duduk di jabatan eksekutif dan legislatif adalah orang-orang partai politik. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa proses menerima (take) yang salah. Rakyatlah yang salah, bukan lembaga politik yang salah. Saya kira, rakyat tidak salah. Sebab, posisi mereka diatur bukan mengatur. Idealnya, parpol adalah lembaga yang paling powerful di suatu negara. Ia menyeleksi warga negara untuk mengikuti pemilu dalam rangka memperebutkan kursi eksekutif dan legislatif. Parpol mengendalikan eksekutif dan legislatif melalui ideologi dan platform yang dimilikinya. Tetapi, situasi di Indonesia sangat jauh dari kondisi ideal ini. Di Indonesia, parpol yang memiliki ideologi yang jelas, terang benderang, dan maujud dalam kebijakankebijakan politik bisa dihitung dengan jari. Para warga negara yang berkecimpung dalam parpol juga hanya melihat parpol sebatas kendaraan rental. Hari ini partai A, besok partai B, dan lusa partai C. Bahkan, beberapa politisi menganggap parpol tak ubahnya seperti perusahaan keluarga. Orang lain boleh ikut dan menumpang, tetapi tidak boleh mengatur. Di Indonesia, parpol itu lemah secara ekonomi dan politik. Dari sisi ekonomi, sumber keuangan parpol hanya terbatas kepada iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dari ketiga sumber keuangan ini, yang terakhir adalah yang paling pasti. Sedangkan sumber pertama dan kedua sangat absurd dan membuka praktek-praktek ketidakjujuran. Dari sisi politik, parpol mampu mengantarkan sekelompok orang menduduki jabatan eksekutif dan legislatif, tetapi ia seringkali tidak pernah disiram sehingga berkembang dengan sempurna. Ideologi parpol seringkali kalah dengan kepentingan-kepentingan politik pragmatis para elit parpol yang sedang duduk di jabatan eksekutif dan legislatif. Kondisi ini yang menciptakan proses memberi (give) yang dilakukan parpol menjadi bias. Rakyat pun kecewa dan antipati dengan partai politik. Oleh karena itu, parpol harus diperkuat dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sebab, akar parpol adalah warga negara yang memiliki kesadaran politik. Hidup dan matinya parpol, baik dan buruknya parpol, kuat dan lemahnya kelembagaan parpol, akan sangat bergantung kepada dukungan warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. Kesadaran politiklah yang menjadi kata kunci untuk merubah status parpol dari sebatas shortcut menjadi operation system. Kesadaran politik inilah yang akan membentengi para pemilih dari rayuan para politisi yang berusaha membeli suara para pemilih. Meskipun kesadaran politik itu bersarang dalam kognisi orang per orang, tetapi ia bisa diekspor keluar sehingga menjadi kesadaran kolektif. Proyek penyadaran ini yang pernah dilakukan rezim Orde Baru melalui kegiatan P4. Sayangnya, kegiatan ini tidak manusiawi karena cenderung doktrinisasi, anti-kritik, dan jauh dari prinsip learning by doing. Rakyat yang memiliki kecerdasan dan kesadaran politik mampu melihat visi bahwa parpol hanyalah salah satu alat mengorganisir kepentingan-kepentingan kolektif. Di luar parpol, masih banyak saluran-saluran politik yang bisa digunakan warga negara untuk mengorganisir kepentingan-kepentingan politik mereka. Saya membayangkan parpol di Indonesia di masa mendatang merupakan sumber pengetahuan dan ide-ide kreatif untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Parpol adalah pusat pemikiran dan pusat aksi. Pengurus parpol tak perlu gemuk, tetapi ia mampu menggerakkan warga negara dengan ide-ide inspiratif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengurus parpol tidak mesti mencalonkan diri sebagai kandidat eksekutif dan Dimuat di SKH Sumatera Ekspress, 25 Februari 2014 legislatif. Ia hanyalah petugas yang menyeleksi warga negara yang sejalan dengan ideologi dan platform partainya untuk dipromosikan sebagai kandidat di lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam situasi ini, saya yakin, praktek-praktek membeli suara (vote buying) sudah terkubur bersama masa lalu. Dimuat di SKH Sumatera Ekspress, 25 Februari 2014