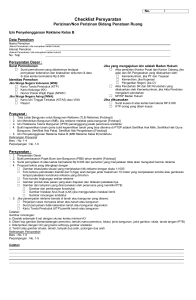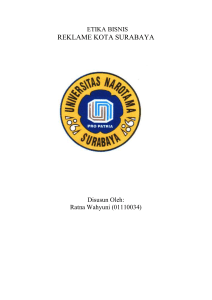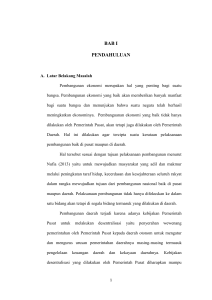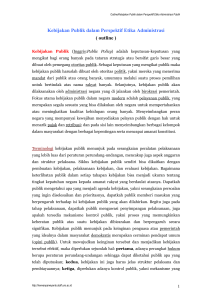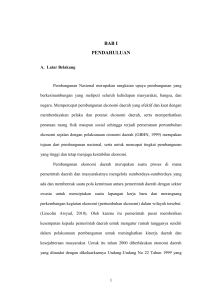BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penggalan
advertisement

BAB I PENDAHULUAN “Streets and their sidewalks, the main public places of a city, are its most vital organs. Think of a city and what comes to mind? Its streets. If a city’s streets look interesting, the city looks interesting; if they look dull, the city looks dull.” –Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities A. Latar Belakang “Kualitas ruang publik di Yogyakarta 5 tahun terakhir menapaki jalan turun. Realitas sosial menggambarkan ruang publik Yogyakarta telah diprivatisasi merk dagang tertentu. Sebentar lagi ruang publik Yogyakarta diprivatisasi dan diserahkan secara sukarela oleh penguasa Yogyakarta kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2014. Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara, saat secara visual ruang publik Yogyakarta menjadi tempat sampah yang menampung ratusan sampah visual iklan komersial maupun iklan politik. Pada titik ini, ruang publik menjadi tidak ramah lingkungan dan ramah visual bagi warga. Ekstremnya, ruang publik Yogyakarta menjadi ruang terbuka yang tidak manusiawi. Dikatakan demikian, karena ruang publik yang terdiri dari ruang terbuka hijau, taman kota dan trotoar untuk pejalan kaki dilabeli merek dagang produk barang dan jasa. Sementara itu, beberapa penggal jalan lainnya, dikuasai partai politik tertentu. Simaklah penggal jalan: Sudirman, Senopati, Urip Sumoharjo, Diponegoro, AM Sangaji, Cokroaminoto, Wirobrajan, Timoho, Badran, dan Abubakar Ali. Tidak ketinggalan Kleringan, Jembatan Kewek, seputaran Kridosono dan Mandala Krida serta tempat lainnya. Di sana dapat disaksikan betapa kumuhnya ruang publik yang diprivatisasi merek dagang atau partai politik…” (Kedaulatan Rakyat, Rabu, 6/3/2013, hlm. 12.)1 Penggalan artikel di atas menunjukkan gambaran tentang persoalan ruang publik yang dihadapi masyarakat Yogyakarta dalam beberapa tahun belakangan. Persoalan ini disebabkan oleh kehadiran iklan luar ruang. Ruang publik di Yogyakarta—tanpa disadari oleh warganya—ditengarai telah hilang. Iklan luar ruang telah menginvasi ruang publik dan keseharian warga kotanya. Ruang kota 1 Sumbo Tinarbuko dalam Rubrik Opini: Sampah Visual di Ruang Publik, Harian Kedaulatan Rakyat Edisi Rabu Wage 6/3/2013, hlm. 12 1 Yogyakarta secara halus direbut dari warga kota oleh hingar-bingar visualitas iklan luar ruang, atau biasa juga dikenal dengan reklame. Reklame yang hadir dalam berbagai bentuk (poster, spanduk, baliho, billboard, grafiti dan sejenisnya)-secara perlahan tapi pasti—mengambil alih fungsi ruang publik. Beragam bentuk reklame tersebut tidak hanya hadir memadati trotoardan perempatan jalan raya, melainkan juga berhamburan tersebar di berbagai ruang kota seanteroYogyakarta. Kondisi ini disamping membawa persoalan visualitas ruang kota, juga menciptakan masalah lingkungan, yaitu sampah visual. Wajah kota yang dikenal sebagai kota budaya ini menjadi tidak estetis lagi, estetika ruang kota tergantikan dengan visualitas reklame yang dipasang berlomba-lomba untuk merebut perhatian warga kota. Lebih kompleks lagi, fenomena menjamurnya reklame—secara langsung maupun tidak—merepresentasikan upaya logika ekonomi (kapitalisme) untuk merebut keseharian warga di ruang kota. Visualitas yang memenuhi pandangan mata didorong oleh gerak kapitalisme dengan warga kota sebagai konsumen dari iklan-iklan tersebut. Keseharian warga kota dikonstruksi untuk melakukan praktik-praktik konsumerisme. Dialektika yang dibangun di dalamnya adalah dialektika konsumsi, dan bukanlah dialektika demokratis. Ruang publik tidak lagi menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertindak sebagai warga (act of citizenship), melainkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk bertindak sebagai konsumen, serta sebagai ruang bagi penguasa untuk melakukan akumulasi kapital. Kehadiran reklame memang bukan sesuatu yang baruterjadi di wilayah urban seperti Yogyakarta. Seperti halnya di kota-kota besar lain, kehadiran 2 reklame merupakan konsekuensi logis dari peningkatan ekonomi di suatu kota. Peningkatan ekonomi akan diiringi dengan pertumbuhan media-media promosi untuk mengenalkan produk barang dan jasa yang dihasilkannya kepada masyarakat. Kondisi ini terjadi karena para pengusaha—produsen produk barang dan jasa—masihmenganggap bahwa iklan merupakan ujung tombak pemasaran yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mendorong keberhasilan pemasaran dan aktivitas konsumsi—setelah masyarakat menanggapinya dengan cara membeli—dibutuhkanmedia promosi (iklan) yang besar. Reklame kemudian menjadi opsidengan tingkat feasibilityyang tinggi untuk dijadikan media beriklan karena dianggap paling mampu mencuri perhatian konsumen (masyarakat) dalam keseharian mereka. Hal ini dikarenakan hampir setiap hari, keseharian mereka sebagai masyarakat urban dihabiskan di luar ruangruang privat mereka. Maka jika ditinjau dari sudut sasaran iklan, reklame mampu menjangkau audience yang sifatnya heterogen—berasal dari segala golongan usia, pekerjaan, bahkan kelas—secara simultan dan dalam jangka waktu lama. Dan dengan karakteristik media luar ruang seperti ini, keterlihatan reklame menjadi faktor penting bagi para produsen iklan. Dalam perspektif produsen iklan, persoalan keterlihatan berorientasi pada tersampaikannya muatan iklan kepada konsumen. Oleh karena itu, reklame tidak hanya sekedar ditempatkan di luar ruangan atau outdoor, melainkan harus ditempatkan pada lokasi yang mampu dijangkau oleh banyak mata warga (konsumen). Bisa juga berarti secara simultan reklame 3 harus dipasang dalam jumlah banyak di berbagai tempat agar sering terlihat oleh orang. Pemasangannya juga tak tanggung-tanggung kerap dijumpai dalam ukuran besar dengan tiang pancang yang menjulang tinggi-tinggi, bahkan—bila perlu— menutupi detail bangunan-bangunan kota. Berdasarkan itu semua, perburuan titiktitik strategis lokasi pemasangan reklame pun dimulai. Selain di pusat-pusat industri komersial (pertokoan), perempatan jalan juga merupakan titik strategis dalam ruang kota untuk penempatan reklame. Namun, keberadaan ruang publik di kota seperti taman kota, taman bermain, dan pedestrian (trotoar) menjadi terancam seiring dengan pertumbuhan reklame yang begitu pesat. Taman-taman kota, taman bermain dan trotoar jadi sasaran tempat pemasangan reklame karena dianggap sebagai lokasi strategis. Hingga akhirnya ruang-ruang publik di kota terlihat penuh dan sesak dipadati beragam iklan. Pertumbuhan reklame pun menjadi tidak terarah. Kondisi ini, selain berdampak pada distorsi visual, akhirnya ikut memberikan tekanan pada ruang publik di kota Yogyakarta. Keberadaan ruang-ruang publik di kota menjadi semakin tergerus oleh deru kapitalisme. Pertumbuhan reklame yang terjadi di Yogyakarta juga tidak diiringi dengan kontrol dari pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan reklame terbukti sangat minim dengan kebijakan pemerintah yang sangat rentan terhadap pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang seringkali terjadi, antara lain: banyak reklame yang terpasang ternyata belum memiliki izin, bagi reklame yang sudah mengantongi izin pun banyak yang melanggar aturan pemasangannya. Reklame dalam berbagai bentuk dipasang berjajar dengan jarak berdekatan di trotoar, tiang 4 listrik, tiang telepon, tiang lampu jalan, tiang rambu lalu lintas, tiang lampu lalu lintas (traffic light), bahkan dipakukan di pohon-pohon perindang jalan. Akibatnya, kondisi ini mengganggu aktivitas warga (publik) karena mengambil alih fungsi trotoar dan mempersempit luas jalan. Pemasangan reklame yang tidak beraturan dan berhamburan di ruang kota pada akhirnya menghasilkan persoalan lingkungan baru di perkotaan, yaitu sampah visual. Sampah visual didefinisikan sebagai iklan luar ruang yang dipasang tidak sesuai dengan peruntukkannya (Arifin dan Nisa, 2014:13).Artinya, reklame yang dipasang di ruang-ruang kota tidak pada tempatnya, seperti pada fasilitas-fasilitas publik, misal tiang listrik, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang rambu pendahulu penunjuk jalan (RPPJ), tiang rambu lalu lintas (seperti traffic light, rambu U-turn dan sejenisnya), pohon perindang, atau ruang-ruang publik, seperti trotoar, taman kota, dan taman bermain ini adalah sampah visual. Selain mencemari keindahan lingkungan, sampah visual juga mencemari kondisi visual ruang kota. Sampah visual yang tersebar di ruang kota Yogyakarta pun tak berhenti pada sampah visual yang dihasilkan oleh iklan komersial. Kehadiran iklan politik pada masa kampanye menjelang pemilihan umum lima tahunan turut menyerbu ruang-ruang publik. Invasi iklan politik bahkan masuk ke ruang-ruang publik dengan lingkup yang lebih kecil, seperti jalanan perkampungan sekitar lokasi pemukiman warga, lapangan-lapangan bola dan ruang-ruang tempat berkumpulnya warga. Kondisi ini terjadi karena praktik kampanye konvensional dengan menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK) masih secara masif 5 dilakukan oleh partai politik dan para peserta pemilu, baik calon anggota legislative (caleg), kandidat kepala daerah, maupun kandidat presiden dan wakil presiden. Hakikat iklan politik pun hampir sama dengan iklan komersial, kehadirannya tanpa mempertimbangkan visualisasi dan estetika. Dalam penyelenggaraannya, praktik iklan politik juga tercatat diwarnai banyak pelanggaran. Dari data Bawaslu DIY per akhir bulan Februari 2014 tercatat sebanyak 12.020 jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Jumlah tersebut tersebar di lima Kabupaten dan Kota, sedangkan terbanyak ditemukan di Kota Yogyakarta mencapai 6.492 APK.2 Jenis pelanggarannya juga masih sama seperti yang sebelumnya—periode pemilu sebelumnya—daripara caleg, yaitudalam bentuk baliho, spanduk dan rontek. Dan pemasangannya tidak pada zona yang ditentukan. Pada saat yang sama, di tengah kekacauan visual yang terjadi di ruang kota itu, pemerintah sebagai penentu kebijakan kota melihat peluang untuk meningkatkan pemasukan daerahnya dengan kehadiran reklame. Reklame menjadi salah satu sumber penyumbang terbesar bagi pemasukan asli daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Dalam kondisi tersebut, iklan luar ruang atau reklame hanya dipandang sebagai salah satu aspek ekonomi yang perlu diatur oleh Negara. Pengaturannya hanya berorentasi pada kontrol Negara terhadap persoalan keterlihatan yang menyangkut titik-titik (lokasi) pemasangan reklame dengan logika ekonomi. Persoalan keterlihatan dalam pengaturan tersebut tidak 2 Lihat berita Kota Yogya Terbanyak Ditemukan Pelanggaran Pemasangan APK pada situshttp://jogja.tribunnews.com/2014/03/08/kota-yogya-terbanyak-ditemukan-pelanggaranpemasangan-apk/ 6 membicarakan sama sekali apakah pemasangan reklame nyaman bagi mereka yang melihatnya (warga kota). Padahal, semestinya persoalan keterlihatan reklame di ruang kota harus dilihat lebih dari sekedar persoalan mengenai pajak— harga sewa dan besaran pemasukan—yang dihasilkan dari penyelenggaraan reklame. Persoalan keterlihatan reklame di ruang kota seharusnya dilihat sebagai persoalan perlawanan terhadap dominasi narasi kapitalisme telah merebut ruang publik dari warga kota itu sendiri. Ketika pemerintah tak mampu melakukan perlawanan itu dan juga tak mampu melindungi warga kota dari gencatan dominasi kapitalisme di ruang kota, maka warga kotalah yang harus melakukan perlawanan untuk melindungi diri mereka sendiri.Menjelang tahun 2012, muncul kampanye ‘anti sampah visual’ melalui media jejaring sosial yang diunggah oleh Sumbo Tinarbuko, seorang dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual (DKV) pada Jurusan Desain Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Kampanye ‘anti sampah visual’ ini kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan sosial berbasis masyarakat. Gerakan ini mendorong warga kota untuk lebih peka terhadap persoalan visualitas kota yang kian memprihatinkan akibat ekspansi sampah visual di ruang-ruang kota. Gerakan yang diinisiasi oleh Sumbo Tinarbuko ini kemudian diwadahi ke dalam sebuah komunitas yang dikenal dengan nama Komunitas Reresik Sampah Visual. Gerakan ini selain melakukan kampanye ‘anti sampah visual’ juga melakukan protes yang ditujukan kepada pemerintah dengan aksi mencabuti sampah visual di ruang-ruang kota Yogyakarta, yang kini dikenal dengan nama 7 gerakan reresik3 sampah visual.Hal yang menarik dari adanya gerakan ini adalah gerakan ini sebenarnya bisa dilihat sebagai respon warga kota terhadap ancaman ruang publik kota mereka dari dominasi kepentingan sektor privat yang mengkerutkan ruang publik dengan serbuan sampah visual di ruang publik kota.Berdasarkan itu semua, dengan mengambil kasus Gerakan Reresik Sampah Visual, penelitian ini bermaksud melihat upaya perlawanan oleh warga kota Yogyakarta terhadap dominasi kapitalisme untuk merebut kembali ruang publik mereka. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana GerakanReresik Sampah Visual dalam upayanya merebut kembali ruang publik di Yogyakarta dilihat dalam konsep gerakan sosial baru?” C. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui upaya-upayayang dilakukan gerakanreresik sampah visualuntuk merebut kembali ruang publik di kota Yogyakarta. b. Untuk mengetahui dinamika gerakan dalam upaya merebut kembali ruang publik di kota Yogyakarta. c. Untuk mengetahui upaya gerakan reresik sampah visual untuk merebut kembali ruang publik di kota Yogyakarta dalam konsep gerakan sosial baru. 3 Dalam bahasa Jawa, reresik memiliki arti membersihkan. Terminologi ini digunakan agar nama aksi bisa menjadi familiar di tengah masyarakat Yogyakarta, tempat lahirnya gerakan tersebut. 8 D. Kerangka Teori Penelitian ini akan dilandasi dengan beberapa landasan berpikir yang akan menjadi pembatas bagi penulis dalam mengumpulkan data dan menuangkannya ke dalam tulisan. Diawali dengan pendefinisian ruang publik yang akan mempengaruhi pendekatan konsep antara ruang publik yang akan digunakan dalam tulisan ini. Kemudian, komersialisasi ruang publik yang melatarbelakangi penelitian ini juga perlu dikerangkai dengan teorisasi mengenai minimalisme ruang publik guna menjelaskan tentang bagaimana kemunculan sampah visual dapat menyebabkan hilangnya ruang publik bagi masyarakat kota di Yogyakarta. Sedangkan, Gerakan Reresik Sampah Visualdalam penelitian ini akan dilihat dengan pendekatan gerakan sosial baru (GSB) untuk dapat mengetahui peran gerakan ini dalam ranah politik di area perkotaan terkait persoalan komersialisasi ruang publik, sekaligus untuk menjelaskan apakah strategi ini cukup efektif dalam upaya merebut kembali ruang publik yang hilang dari masyarakat kota. D.1. Ruang Publik Sejak awal kemunculannya, setiap pembicaraan tentang ruang publik selalu harus berhadapan dengan persoalan keberagaman definisi yang tidak mudah diselesaikan. Istilah “ruang publik” memiliki beragam maknatergantung dari konteks penggunaannya. Misalnya, ruang publik bagi para pemikir geografi dan arsitektur, merujuk pada Lefebvre (1996: 67), yakni “jaringan keterlibatan dan ruang sosial tertentu yang menyangga kerjasama dan koordinasi civitas, terutama dalam interaksi antara kota besar dan ekonomi global”. Bagi para ekonom mainstream, istilah ruang publik (public domain) merujuk sebagai sesuatu yang 9 muncul karena kegagalan mekanisme pasar bebas (market failure) dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan semua warga masyarakat. Pada umumnya ruang publik dilihat sebagai bidang-bidang seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pendidikan masal, keamanan dan semacamnya yang pengadaannya dianggap sebagai tugas pemerintah (B. Herry-Priyono, 2005: 153). Ruang publik bagi berbagai refleksi budaya, merujuk ke Eagleton (2003: 74-102), mengacu pada gugus-gugus keyakinan, pandangan dan praktik yang menyangkut sikap, wacana, cara berpikir dan merasa kolektif, selera, corak keberadaban (civility) yang berlangsung dalam interaksi sosial. Sedangkan bagi berbagai refleksi sosiologis, ruang publik mengacu pada jaringan trust dan resiprositas yang menentukan ada-tidaknya kohesi suatu masyarakat atau dapat dikatakan konsepsi yang bersifat Durkheimian, yakni konsepsi yang mengacu pada ciri dan kadar sosial (the social) suatu masyarakat (Durkheim, 1964). Selanjutnya, ruang publik dalam refleksi filsafat politik, konsepsi ruang publik banyak mengacu pada konsepsi Habermas, yakni “ruang publik merupakan arus keterlibatan kolektif yang selalu dinegosiasikan, bersifat tidak stabil, lentur dan terbuka” (Habermas, 1989: 37). Dari beberapa contoh keberagaman definisi ruang publik seperti yang diuraikan tersebut bisa dilihat dengan lebih jelas melalui skema berikut: 10 RUANG PUBLIK Social Capital: Public Services: Jaringan trust& resiprositas Keamanan, pendidikan, Kebutuhan umum kesehatan, jalan, (market failure) tanaman, lingkungan hidup, dsb Public Culture: Public Space: Public Goods: Bahasa, sikap, selera, cara pikir-rasa kolektif, civility Ruang/tempat bertemu untuk debat-diskusi Interelasi antara ranah pasar, keluarga, pemerintah, dan kelompok independen yang membentuk the social suatu masyarakat Skema 1. Keragaman Definisi Ruang Publik4 Berdasarkan skema keragaman definisi ruang publik tersebut, secara positif kita dapat menunjuk arti ruang publik dalam rumusan berikut: ruang publik adalah arena maupun aset, barang, jasa, ruang, dan gugus infrastruktur lain yang kinerjanya menjadi penyangga watak sosial suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut berevolusi dari sekedar ‘kerumunan’ (crowd)menjadi ‘komunitas’ (community) (B. Herry-Priyono, 2005: 158). Jika disimak dari rumusan tersebut, maka ruang publik merupakan sebuah arena dimana keseharian kita berkecimpung di dalamnya.Ruang publik baik dalam arti fisik maupun non fisik tidak hanya merupakan sebuah arena sebagai tempat bagi kita beraktivitas, tetapi juga sebuah ruang bagi berkembangnya ide, pikiran, dan artikulasi 4 Gambar dipinjam dari Daniel Drache, “The Return of the Public Domain…” dalam Sunaryo Hadi Wibowo (Ed.), Republik Tanpa Ruang Publik, Yogyakarta: IRE Press, 2005, hlm. 156 11 kepentingan kita. Dengan demikian, ruang publik bukan hanya sekedar sebuah taman kota, jalan raya, maupun tempat-tempat yang berkaitan dengan tata kota tetapi juga mencakup kehidupan kita dalam berdemokrasi melakukan praktik sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu, ruang publik bukanlah hak prerogatif pemerintah dan keberadaannya pun tidak untuk diperjual-belikan melalui mekanisme pasar-bebas. Dalam tulisan ini, istilah ‘ruang publik’ mengacu pada dua arti: pertama, istilah ruang publik dalam arti deskriptif, yakni sebagai sesuatu yang berkaitan dengan distingsi antara publik dan privat. Istilah ini mengacu pada suatu ruang yang dapat diakses semua orang, maka juga membatasi dirinya secara spasial dari adanya ruang lain, yaitu ruang privat. Dalam arti ini, ruang publik—berbeda dari ruang privat yang merupakan locus intimitas, seperti keluarga dan rumah— merupakan locus kewarganegaraan dan keadaban publik, karena ruang publik dibentuk oleh para warga yang saling respek terhadap hak mereka masing-masing. Kedua, istilah ruang publik dalam arti normatif, yakni mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Ruang publik dalam arti normatif itu—yang juga disebut “ruang publik politis”—adalah suatu ruang komunikasi para warganegara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan (Hardiman, 2010:1011). D.2. Minimalisme Ruang Publik5 Jika ruang publik dijelaskan dengan analogi sebuah wadah, maka wadah tersebut dapat dikatakan mempunyai kualitas kepublikan (publicity) sejauh ia 5 Meminjam istilah Yasraf A. Piliang, “Minimalisme Ruang Publik: Budaya Publik di dalam Abad Informasi” dalam Sunaryo Hadi Wibowo (Ed.), Republik Tanpa Ruang Publik, Yogyakarta: IRE Press, 2005. 12 dapatmenampung di dalam dirinya berbagai entitas dengan beragam kepentingan (interest). Dengan analogi yang sama pula, ruang publik juga dapat dibedakan dalam ruang publik ideal (ideal public sphere) dan ruang publik riil (real public space). Ruang publik ideal menjelaskan sebuah ruang teoritis yang didalamnya terdapat berbagai elemen publik dengan berbagai kepentingan, dimana kepentingan mereka secara maksimal dapat ditampung dan direalisasikan di dalam ruang publik. Ruang publik riil menjelaskan ruang publik ‘nyata’ dalam realitas sehari-hari, yang berdasarkan perannya, menampung kepentingan publik dibedakan di dalam semacam spektrum kepublikan (the spectrum of publicness) (Wibowo, 2005:1-3). Selanjutnya, apabila ruang publik dinilai berdasarkan ‘kapasitas’ dan ‘kualitasnya’ dalam menampung dan memberi tempat berbagai kelompok dan kepentingan, maka sebenarnya ada semacam ‘derajat kepublikan’ (a degree of publicness) sebuah ruang publik (Piliang, 2005: 12). Ruang publik dapat dibedakan dalam dua titik ekstrem berdasarkan derajat kepublikan tersebut, yakni ruang publik yang ‘minimalis’ dan ruang publik yang ‘maksimalis’. Ruang publik minimalis, yaitu ruang publik yang minimal tingkat kepublikannya, dan ruang publik maksimalis, yaitu ruang publik yang tinggi kualitas kepublikannya. Ruang publik dengan tingkat kepublikan yang minimalis rentan mengalami apa yang disebut sebagai ‘minimalisme’. Merujuk pada Piliang (2005), istilah ‘minimalisme’ ini berkaitan dengan keadaan psikis pada diri seseorang atau kelompok sosial, yang mengalami keadaan diri minimal (minimal self) (Piliang,2005:13). Dalam konteks ruang publik, minimalisme terjadi dalam 13 berbagai unsur yang membangun ruang publik itu sendiri, yang meliputi aktor, institusi, sarana, ide dan gagasan yang terlibat di dalamnya. Minimalisme ruang publik dalam konteks masyarakat Indonesia dapat dijelaskan melalui berbagai fenomena minimalisme sebagai berikut (Piliang,2005:15): a. Pendangkalan ruang publik, yaitu ketika ruang publik cenderung dibangun oleh representasi atau tindakan (action) yang dilandasi oleh berbagai strategi populer yang memanfaatkan model-model psikologi massa populer dalam rangka menguasai ruang publik melalui ‘kekuatan popularitas’ di dalamnya, meskipun popularitas ini tidak didukung oleh pengetahuan, ketrampilan dan kecakapan yang sebenarnya. b. Komodifikasi ruang publik, yaitu didominasinya ruang publik oleh kaum borjuis-kapitalis yang menanamkan pengaruhnya tidak saja pada sektor ekonomi akan tetapi pada sektor-sektor kehidupan lainnya. Minimalisme ruang publik dalam hal ini adalah ketika ruang publik dikerutkan atau diredusir ke dalam wujud komoditi. c. Banalitas ruang publik, yaitu marjinalisasi dan minimalisasi berbagai hal yang esensial dalam rangka memaksimalkan berbagai hal yang takesensial, semata dalam rangka mengikuti mekanisme hasrat kapitalisme—minimalisme yang esensial, maksimalisme yang takesensial. d. Virtualitas ruang publik, yaitu didominasinya relasi di dalam ruang publik oleh model-model relasi virtual. Minimalisme ruang publik dalam hal ini terbentuk ketika—lewat kemampuan teknologi digital dan 14 virtual dalam memanipulasi dan merekayasa citra realitas—ruang publik didominasi oleh berbagai bentuk kepalsuan, kesemuan dan distorsi realitas. e. Transparansi ruang publik, dalam pengertian runtuhnya batas-batas yang selama ini memisahkan antara ruang publik (public sphere) dengan apa yang disebut ruang pribadi (private sphere). Minimalisme ruang publik dalam hal ini terjadi ketika ruang tersebut didominasi oleh elemenelemen private space, yang sebelumnya dianggap rahasia kini dapat disebarluaskan ke dalam berbagai jaringan global sebagai pengetahuan publik. f. Imortalitas ruang publik, yaitu kecenderungan tergusurnya berbagai prinsip moral di dalam ruang publik, yang diambilalih oleh berbagai kecenderungan permutarbalikan atau permainan moral (immortality). Dengan kata lain, immortalitas ruang publik adalah proses ke arah ‘minimalisme moral’, yaitu diredusirnya makna moralitas itu sendiri ke dalam bentuk yang paling rendah. g. Mitologisasi dan mistifikasi ruang publik, yaitu didominasinya ruang publik oleh berbagai mitor dan mistik dengan meminggrikan dunia realitas yang sesungguhnya. Minimalisme ruang publik tidak akan mampu menciptakan sebuah ruang yang di dalamnya dapat dimaksimalkan debat publik secara demokratis. Maka, jika Jurgen Habermas mengajukan ruang publik ideal (ideal public sphere) sebagai syarat mutlak bagi sebuah proses demokratisasi, dengan melihat berbagai 15 kecenderungan minimalisme di atas, kemungkinan yang terbentuk justru sebaliknya, yakni ‘ruang publik minimalis’ atau dengan kata lain, ruang publik yang sangat tidak ideal bagi sebuah proses demokrasi. Dalam tulisan ini minimalisme ruang publik mengacu secara spesifik dalam konteks komodifikasi ruang publik. Pada kasus dominasi ruang publik oleh sampah visual, ruang publik di kota Yogyakarta mengalami komersialisasi. Dan bentuk komersialisasi ruang publik yang paling nyata terjadi adalah ketika pemanfaatan ruang publik di kota berorientasi pada akumulasi kapital yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sampah visual yang justru dijadikan peluang oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. D.3. Konsep Gerakan Sosial Seiring dengan perkembangan kisah–kisah gerakan sosial, tidak ada definisi tunggal mengenai konsep gerakan sosial sebagai suatu gejala sosial. Oleh Gidden (1993: 642) misalnya, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama, mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action) di luar lembaga yang mapan. Definisi yang lebih komprehensif dirumuskan oleh Van Klinken (2007: 11), gerakan sosial sebagai kolektivitas-kolektivitas yang dengan organisasi dan kontinuitas tertentu bertindak di luar saluran-saluran institusional atau organisasional dengan tujuan menggugat atau mempertahankan otoritas, baik yang didasarkan secara institusional atau kultural dan berlaku dalam kelompok, organisasi, masyarakat, kebudayaan atau tatanan dunia di mana merekamerupakan salah satu bagiannya. 16 Dari definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial merupakan suatu gerakan kolektif yang bersifat menentang dengan tujuan mencapai kepentingan atau tujuan kolektif.Definisi ini bersifat luas karena gerakan sosial memiliki ragam yang sangat variatif. Konseptualisasi ini melibatkan 5 (lima) hal untuk bisa dikatakan sebagai gerakan sosial (Haryanto, Hairini, Abu Bakar: 2013, 189), yakni: tindakan kolektif atau gabungan, bersifat ekstra-institusional atau non institusional, tujuan atau klaim-klaim yang berorientasi pada perubahan, organisasi sampai tingkat tertentu (relasi), dan keberlanjutan dalam hal waktu sampai tingkat tertentu. Gerakan sosial bisa memiliki partisipan yang sedikit, tetapi bisa juga memiliki partisipan dalam jumlah ribuan bahkan jutaan orang. Gerakan sosial bisa beroperasi dalam batas-batas legalitas suatu masyarakat, namun bisa juga bergerak secara illegal atau sebagai kelompok ‘bawah tanah’ (underground groups) (Suharko, 2006: 3). Tarrow (1998) menempatkan gerakan sosial dalam kategori yang lebih umum, yaitu tentang politik perlawanan (contentious politics). Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh untuk menggalang kekuatan melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (cyclus of contention) dan revolusi.Perlawanan seperti ini biasanya muncul ketika kesempatan dan hambatan politik tengah berubah sehingga menciptakan dorongan bagi aktor-aktor sosial yang kurang memiliki sumber daya pada dirinya sendiri. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial yang kuat dan digaungkan oleh resonansi kultural 17 dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan mengarah ke interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak lawan, sehingga menghasilkan suatu gerakan sosial. Tindakan yang mendasari politik perlawanan menurut Tarrow (1998) adalah aksi kolektif yang melawan (contentious collective action). Tindakan atau aksi kolektif ini bisa dilihat dalam banyak bentuk, yakni singkat atau berkelanjutan, terlembagakan atau cepat bubar, membosankan atau dramatis. Aksi kolektif memiliki semangat perlawanan apabila aksi dilakukan oleh orang-orang yang kurang memiliki akses ke institusi-institusi untuk mengajukan klaim baru atau klaim yang tidak diterima oleh pemegang otoritas atau pihak lain yang ditentang. Aksi kolektif yang sifatnya melawan merupakan basis dari gerakan sosial, karena aksi tersebut seringkali menjadi satu-satunya sumberdaya yang dimiliki untuk menentang pihak-pihak yang lebih kuat, seperti negara. Akan tetapi, tidak semua bentuk perlawanan politik bisa disebut sebagai gerakan sosial. Tarrow (1998: 4-7) merumuskan bahwa gerakan sosial harus memiliki empat hal yang mendasar, yakni: a. Tantangan kolektif (collective challenge) Hal yang membedakan gerakan sosial dari tindakan-tindakan kolektif lain adalah bahwa gerakan sosial selalu ditandai oleh tantangan-tantangan untuk melawan melalui aksi langsung yang mengganggu terhadap para elit, pemegang otoritas, kelompok-kelompok lain, atau aturan-aturan kultural tertentu. Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap kegiatan-kegiatan pihak lain, dan biasanya 18 disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penanaman baru objek-objek yang familiar dengan simbol yang berbeda atau baru. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (contention)mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Itulah mengapa, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi titik fokus bagi para pendukung untuk memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan. b. Tujuan bersama (common purpose) Jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihal lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Meskipun tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dan kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama (Suharko: 2006, 6) c. Solidaritas dan Identitas Kolektif Sesuatu yang menggerakan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata (Suharko: 2006, 6). Perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Akan tetapi, pemimpin gerakan hanya dapat menciptakan 19 suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas. d. Memelihara Politik Perlawanan Memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh merupakan cara yang paling efektif untuk bisa membawa suatu cerita perlawanan menjadi gerakan sosial. Politik perlawanan ini bisa dipelihara gerakan dengan bantuan tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang teridentifikasi. Namun, hal sebaliknya akan terjadi jika gerakan tidak mampu memelihara tantangan bersama. Gerakan akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individual, atau merubah menjadi sekte religious, atau bahkan mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Oleh karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat dapat menandai titik pergeseran suatu penentangan (contention) berubah menjadi suatu gerakan sosial (social movement). D.4. Gerakan Sosial Baru Wacana tentang Gerakan Sosial Baru (GSB) bermula di negara-negara maju sebagai bagian dari konteks perkembangan peradabannya. Istilah “gerakan sosial baru” digunakan secara luas untuk merujuk pada fenomena gerakan sosial yang muncul sekitar tahun 1960-an – 1970-an di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat yang pada masa itu telah memasuki era ekonomi pasca-industrial (post-industrial economy). Para ilmuwan sosial yang mengamati fenomena gerakan sosial ini sejak awal kemunculannya mendapati bahwa GSB merupakan tambahan baru untuk teori gerakan sosial yang menekankan baik pada elemen makrohistoris maupun mikrohistoris pada gerakan social (Pichardo, 1997: 20 411).Pada tingkat makro, GSB menekankan hubungan antara kemunculan gerakan sosial kontemporer dan struktur ekonomi yang lebih besar, serta peran budaya dalam gerakan tersebut. Sedangkan, pada tingkat mikro, GSB menekankan bagaimana isu-isu identitas dan perilaku pribadi terikat dalam gerakan sosial (Pichardo, 1997: 411). Seiring dengan perubahan tata sosial dan peradaban Barat, para ilmuwan sosial melihat gerakan-gerakan sosial di sana memiliki tampilan watak yang berubah dari gerakan-gerakan sosial sebelumnya (gerakan sosial ‘lama’ atau klasik atau tradisional) (Suharko, 2006:8). Gerakan sosial lama (klasik) seperti dalam teori-teori Marxis, dicirikan secara kuat dengan tujuan ekonomis-material sebagaimana tercermin dari gerakan-gerakan kelas pekerja atau kaum buruh, sedangkan GSB lebih menekankan pada tujuan-tujuan yang bersifat non-material. Kemudian dalam perkembangannya, para ilmuwan sosial memperluas kajiannya ke berbagai negara yang sedang berkembang. Hasilnya adalah temuan gerakan sosial yang memiliki tipe kurang lebih sama, meskipun latar dan konteks perkembangan masyarakat pasca-industrial belum terjadi di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Singh (2001), GSB bukan hanya terjadi di negara-negara Barat, akan tetapi juga berlangsung di negara-negara berkembang. Gerakan sosial baru sendiri bisa dipahami dalam dua hal. Pertama, GSB sebagai suatu tipe gerakan sosial yang memiliki karakter unik dan berbeda jauh dari gerakan-gerakan sosial pada era industri atau gerakan sosial lama. Kedua, akumulasi pengetahuan yang dihasilkan dari riset-riset tentang GSB telah 21 membawanya pada status sebagai suatu cara pandang terhadap suatu permasalahan (paradigma) dalam memahami kenyataan sosial itu sendiri (Pichardo, 1997; Singh, 2001). Perbedaan-perbedaan karakter gerakan yang membentuk keunikan dari gerakan sosial baru tampak dalam tujuan dan ideologi, taktik, struktur dan partisipan atau aktor gerakannya. Karakteristik utama GSB adalah pandangan ideologisnya yang berbeda (Dalton et al, 1990). Perjuangan-perjuangan GSB lebih menekankan pada permasalahan gaya hidup dan kualitas hidup daripada berfokus pada redistribusi ekonomi seperti yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan kelas pekerja. Gerakan sosial baru tidak lagi tertarik dengan isu-isu seperti kenaikan upah buruh dalam industri, perjuangan terhadap ketimpangan ekonomi dan eksploitasi kelas yang diakibatkan oleh bekerjanya sistem kapitalisme (Suharko, 2006: 9). Secara bersamaan, nilai-nilai GSB berpusat pada otonomi dan identitas (Offe, 1995; Pichardo, 1997: 414). Fokus pada identitas juga dianggap unik karena “politik identitas juga mengungkapkan keyakinan bahwa identitas itu sendiri—dengan elaborasi, ekspresi atau penegasannya—harus menjadi fokus fundamental dari kerja politik. Dengan cara ini, politik identitas telah menghasilkan sebuah politisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari medan nonpolitik” (Kauffman, 1990: 67). Hal ini diungkapkan dalam gagasan bahwa “pribadi adalah politik” (Picardo, 1997: 414). GSB pada dasarnya hadir sebagai bentuk respon terhadap menguatnya kehadiran dua institusi, yakni negara (the state) dan pasar (the market) terhadap masyarakat sipil (Singh, 2001), dimana ruang sosial warga mengalami penciutan 22 dikarenakan kontrol negara yang berlebihan dan pasar yang menerobos masuk hampir ke dalam semua aspek kehidupan warga. Oleh karena itu, GSB membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat untuk melawan ekspansi aparat negara dan pasar yang makin meningkat. Ekspresinya mewujud dalam lahirnya agen-agen yang memperjuangkan pengawasan dan kontrol sosial, seperti kaum urban marginal, aktivis lingkungan, kelompok anti otoritarian, kaum anti rasisme dan juga para feminis. GSB melawan tata sosial dan kondisi yang didominasi oleh negara dan pasar, serta menyerukan sebuah kondisi yang lebih adil dan bermartabat (Suharko,2006: 10). Taktik-taktik yang digunakan GSB mencerminkan orientasi ideologinya. Keyakinan pada karakter demokrasi modern yang tidak representatif konsisten dengan orientasi taktik yang anti-institusional. GSB lebih memilih saluran-saluran di luar politik formal. Dalam tujuannya untuk mendapatkan daya tawar politik, para aktivis GSB menerapkan taktik yang bersifat mengganggu (disruptive) dengan melakukan mobilisasi wacana atau opini publik dan menggunakan bentukbentuk demonstrasi yang sangat dramatis lengkap dengan representasirepresentasi simbolik (Tarrow, 1994). Namun, tidak berarti GSB tidak melibatkan diri dalam politik atau menghindari menjadi terlembaga sendiri. Beberapa gerakan sosial baru telah berintegrasi ke dalam sistem kepartaian dan mendapatkan akses pada pengaturan, pelaksanaan dan lembaga pengambil keputusan, sedangkan beberapa lainnya telah membentuk partai politik yang secara rutin berkompetisi dalam pemilihan perwakilan, seperti sejumlah partai Hijau (Green parties) yang 23 terkenal di Eropa dengan beberapa yang memiliki perwujudan local di Amerika Serikat. Pada umumnya, GSB membidik isu-isu yang bersumber dari masyarakat sipil (civil society) daripada perekonomian dan negara. Dalam sasaran perjuangannya, GSB membatasi pada empat hal, yakni: tidak berjuang untuk kembalinya komunitas-komunitas utopia yang tidak terjangkau di masa lalu; berjuang untuk otonomi, pluralitas dan perbedaan; melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran; mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar (Cohen: 1985). Dengan demikian, Cohen berpandangan bahwa tujuan GSB adalah menata kembali hubungan negara, masyarakat dan perekonomian, serta untuk menciptakan ruang publik yang di dalamnya wacana demokratis tentang otonomi dan kebebasan individual, kolektivitas, serta identitas dan orientasi mereka bisa didiskusikan. Sikap anti-institusional GSB juga meluas terhadap cara mereka mengatur diri. GSB mencoba untuk meniru jenis pemerintahan representatif yang mereka inginkan ke dalam struktur mereka sendiri. Artinya, mereka mengorganisir diri dalam gaya cair dan tidak kaku agar terhindar dari bahaya oligarkisasi. Mereka juga mendukung sikap anti-birokrasi untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai karakter dehumanisasi birokrasi modern (karakter birokrasi yang merendahkan martabat) (Kitschelt, 1993: 15). Jadi, mereka menuntut sekaligus menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan 24 individu-individu, yakni struktur yang terbuka, terdesentralisasi dan tidak bersifat hirarkis. Para aktor-aktor atau partisipan GSB berasal dari berbagai basis sosial. Mereka tidak bisa dibedakan berdasarkan kelas, gender, suku, umur, lokalitas, pendidikan, pekerjaan dan seterusnya. Mereka tidak terkotakkan pada penggolongan tertentu seperti kaum proletar, petani dan buruh, sebagaimana aktor-aktor gerakan sosial lama yang biasanya melibatkan kaum marjinal dan teralienasi (Suharko, 2006: 11). Meskipun ada anggapan bahwa partisipan GSB umumnya berasal dari kalangan kelas menengah baru (the new middle class): strata sosial yang baru-baru ini muncul yang bekerja di sektor-sektor ekonomi non-produktif, akan tetapi strata sosial ini justru mampu menghasilkan partisipanpartisipan utama atau pemimpin-pemimpin gerakan. Hal ini disebabkan karena mereka yang termasuk dalam kalangan ini umumnya tidak terikat oleh motifmotif keuntungan korporasi dan juga tidak bergantung pada korporasi untuk kelangsungan hidup mereka. Sebaliknya, mereka umumnya bekerja di sektorsektor yang sangat bergantung pada belanja negara seperti kaum akademia, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan, dan mereka pun umumnya merupakan kaum terdidik (Pichardo, 1997: 416-417) Para aktor GSB tidak dibedakan berdasarkan batasan-batasan kelas, melainkan ditandai berdasarkan keprihatinan bersama atas isu-isu sosial, karena ini bukanlah komunitas berbasis suku, agama ataupun kelas, melainkan berbasis ideologi dan nilai yang sama. Offe (1985) menawarkan pandangan yang sedikit berbeda terkait siapa aktor-aktor dalam GSB. Ia berpandangan bahwa aktor atau 25 partisipan GSB berasal dari tiga sektor, yakni: kelas menengah baru, unsur-unsur kelas menengah lama (petani, pemilik toko dan penghasil karya seni), dan populasi pinggiran yang terdiri dari orang-orang yang tidak terlalu terlibat dalam pasar kerja (mahasiswa, ibu rumah tangga dan para pensiunan). Berdasarkan uraian karakteristik tersebut, GSB menampakkan wajah sebagai gerakan sosial yang plural. Pluralitas itu terpantul jelas dari bentuk-bentuk aksi GSB yang menapaki banyak jalur, mencita-citakan beragam tujuan, dan menyuarakan aneka kepentingan (Suharko,2006: 12). Isu-isu yang menjadi perhatian GSB melintasi batasan-batasan bangsa dan masyarakat, bahkan melintasi dunia melintasi dunia manusia menuju dunia alami. Artinya, dalam konteks ini GSB menampakkan wajah trans-manusia dengan mendukung kelestarian alam dimana manusia merupakan salah satu bagiannya, diantaranya seperti pada gerakan-gerakan ekologi atau lingkungan, anti nuklir, perdamaian dan sejenisnya, yang menghamparkan kebersamaan warga dari beragam nasionalitas, kebudayaan dan sistem politik (Singh, 2001). Berdasarkan teorisasi GSB tersebut, tulisan tentang Gerakan Reresik Sampah Visualini akan dilihat dengan perspektif GSB. Asumsinya bahwa ide-ide dasar gerakan didasarkan pada isu seputar ruang publik dan lingkungannya, dan perhatian terhadap budaya dan gaya hidup sosial warga kota. Mobilisasi wacana publik tentang bencana sosial berupa sampah visual yang dilakukan oleh gerakan ini menciptakan berbagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan iklan luar ruang (reklame) juga merupakan alasan mendasar penggunaan konsep GSB dalam tulisan ini. 26 E. Metode Penelitian E.1. Jenis Penelitian Banyak metode penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian mengenai gerakan reresik sampah visualini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan karena dianggap mampu mendeskripsikan suatu fenomena secara lebih mendalam. Penelitian kualitatif juga memberikan jawaban atau rincian lebih kompleks yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan menggunakan metode kuantitatif (Yin,2006). Secara lebih spesifik, dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Hal ini didasarkan pada kasus yang ingin diungkapkan merupakan sebuah kasus spesifik dan cenderung tidak mampu digeneralisir dalam mencari jawabannya. Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya hanya kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus juga merupakan sebuah penelitian dimana hal yang diteliti adalah hal yang bersifat kontemporer. Dengan kata lain, kasus tersebut sedang atau telah selesai terjadi namun masih memiliki dampak yang dapat dirasakan pada saat penelitian dilaksanakan, atau yang dapat menunjukkan perbedaan fenomena yang biasa terjadi. Sebagai sebuah metode yang cukup tua dalam mahzab kualitatif, studi kasus senantiasa mengalami perkembangan dalam perjalanannya. Menurut Mooney (1998) ada empat sudut pandang dalam melihat studi kasus. Dalam penelitian ini, 27 penulis mengacu pada studi kasus tunggal dengan Single Level Analysis, yakni studi kasus yang menyoroti perilaku individu atau kelompok individu dengan satu masalah penting. Lebih dalam lagi studi kasus ini berada pada tahap explanation yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti.Penggunaan studi kasus tunggal dalam penelitian ini, dirasa penulis paling pas untuk dalam menjelaskan fenomena yang ingin diteliti, yaitu proses gerakan reresik sampah visualmerebut kembali ruang publik di wilayah perkotaan Yogyakarta. Ini masuk ke dalam kasus tunggal karena memang yang menjadi target penelitian adalah satu masalah yang bersifat kontemporer dan didalamnya terdapat keterlibatan individu atau kelompok individu dalam merespon suatu fenomena. Studi kasussebenarnya memiliki beberapa kelemahan, yakni terkait intepretasi dan objektivitas. Dalam penelitian dengan studi kasus sendiri, peneliti diharapkan dapat menjadi bagian dari kelompok individu atau komunitas tujuannya agar data yang didapatkan bisa lebih mendalam. Akan tetapi, hal inilah yang menyebabkan objektivitas akan sedikit terganggu. Kedekatan peneliti dengan respondententu akan berimplikasi pada intepretasi saat menganalisis data.Di samping itu, studi kasus sebagai sebuah metode kerap bersifat permisif terhadap bukti yang samar-samar atau pandangan bias. Padahal hal ini praktis akan sangat berkaitan dengan arah temuan-temuan dan konklusi. Studi kasus pun tidak menyarankan peneliti untuk membatasi waktu dalam berinteraksi dalam pencarian data. Padahal hal tersebut akan sangat terkait dengan fokus penggalian data. 28 E.2. Unit Analisis Data Penelitian ini memilih locus tempat di kota Yogyakarta. Secara lebih spesifik di wilayah perkotaan, yaitu wilayah yang notabene cukup mewakili fenomena maraknya reklame—baik iklan komersial maupun iklan politik— memenuhi ruang publik. Ruang publik perkotaan ini mengacu pada taman kota, trotoar, jalan protokoler, persimpangan ataupun perempatan jalan raya, jalan tempat lokasi pertokoan dst. Menjelang tahun 2012, muncul kampanye anti sampah visual melalui jejaring media sosial yang diunggah oleh Sumbo Tinarbuko, seorang dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang juga merupakan seorang pengamat ruang publik. Diawali dengan kampanye ‘anti sampah visual’ melalui media jejaring sosial, Sumbo mulai memperkenalkan Komunitas Reresik Sampah Visual lewat dunia maya. Akhirnya, pada pertengahan tahun 2012 cikal aksi komunitas ini diluncurkan dan perjuangan komunitas ini hingga kinipun terus berkembang. Kampanye ‘anti sampah visual’ dan aksi-aksi mencabuti sampah visual yang dilakukan oleh komunitas ini kini dikenal dengan nama gerakan reresiksampah visual. E.3. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian tentangGerakan Reresik Sampah Visual ini, penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitusumber data primer dan sekunder. Penggunaan data primer yang diperoleh dari interaksi langsung dengan aktor pelakuGerakan Reresik Sampah Visual mencakup hasil interview atauwawancara, dan obeservasi non partisipan. Data primer kemudian digunakan sebagai bahan 29 acuan analisis untuk mengetahui bagaimana strategi Gerakan Reresik Sampah Visual dalam upayanya merebut kembali ruang publik di Yogyakarta dan dinamika yang menyertainya, serta bagaimana peran Gerakan Reresik Sampah Visual dalam merespon komersialisasi ruang publik yang terjadi akibat fenomena sampah visual. Wawancara (interview) dilakukan guna mendapat data yang mendalam terkait individu maupun kelompok sebagai aktor gerakan itu sendiri dan juga aktor-aktor lain yang mempengaruhi gerakan. Wawancara untuk memperoleh data mendalam dalam penelitian ini dilakukan kepada penggerak Komunitas Reresik Sampah Visual sebagai aktor gerakan, dan beberapa aktor lain di luar gerakan, baik yang ikut mempengaruhi gerakan maupun terpengaruh dari gerakan tersebut, di antaranya adalah Sekretaris Jendral Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Cabang Yogyakarta dan koordinator aksi Komunitas Warga Peduli Pohon Perindang. Dalam melakukan wawancara, peneliti membekali diri dengan interview guide yang berfungsi sebagai panduan dalam kapasitasnya untuk membuka kunci potensi informasi-informasi yang diperlukan. Kemampuan untuk mengelaborasi lebih dalam dari pertanyaan awal yang sudah dirumuskan guna mengeksplorasi temuan informasi yang lebih komperhensif. Metode selanjutnya yaitu observasi non partisipan, mengharuskan peneliti untuk masuk dan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas. Dalam hal ini peneliti hanya menjadi penonton tanpa memiliki hak suara dalam kegiatan komunitas. Dari metode ini diharapkan peneliti dapat melihat secara langsung strategi gerakan yang dituangkan dalam agenda aksi 30 Gerakan Reresik Sampah Visual beserta dinamika di dalamnya yang tidak bisa dilihat ketika wawancara individu. Data sekunder diperoleh dari studi literatur mencakup buku, artikel, film dokumenter maupun dokumentasi data dari komunitas yang terkait dengan tema penelitian. Penggunakan data sekunder berperan sebagai referensi tambahan yang memperkuat data dari lapangan. Selain sebagai referensi tambahan, data sekunder juga berfungsi untuk mendukung intepretasi data dari hasil interaksi langsung dan observasi non partisipan. E.4. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis data model alir. Artinya, awalnya penulis akan membaca hasil catatan lapangan pada saat observasi, yaitu pada saat mengamati sebaran reklame di kota Yogyakarta dan pengamatan terhadap wacana yang disebarkan melalui media, seperti surat kabar, portal berita online, dan media jejaring sosial. Kemudian penulis mendengarkan kembali rekaman wawancara dan membaca transkrip wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kasus yang dikaji. Pada tahapan ini, penulis umumnya mendapat penambahan beberapa catatan yang bisa digunakan dalam mengkaji kasus. Pada tahapan selanjutnya, penulis menyusun kata-kata kunci yang muncul dan mengelaborasinya sehingga kasus yang dikaji dapat “menuturkan kisahnya”. 31 F. Sistematika Penulisan Penulisan hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan dan landasan teori yang digunakan dalam penulisan, serta metode penelitian yang mengiringi penulisan ini. Bab keduamenjelaskan kehadiran sampah visual sebagai fenomena minimalisme ruang publik di kota Yogyakarta, mulai banalitas ruang publik yang terbentuk dari praktik beriklan dan penataan iklan luar ruang (reklame) di ruang kota; kemunculan sampah visual yang mengdekonstruksi kota secara visual; dan terakhir komersialisasi ruang publik yang menyebabkan hilangnya ruang publik di kota Yogyakarta. Bab ketiga menceritakan tentang gerakan reresik sampah visualyang melakukan upaya penyelamatan ruang publik dari invasi sampah visual di kota Yogyakarta, dimulai dari profil gerakan yang mencakup sejarah kemunculan dan perkembangan gerakan; strategi gerakan dan dinamika yang mengiringinya. Bab keempat berisi tentang refleksi atas keberadaan gerakan reresik sampah visualsebagai gerakan sosial baru. Bab kelima berisi kesimpulan penelitian yang merupakan inti dari jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. 32