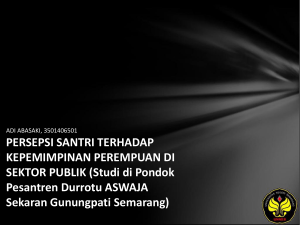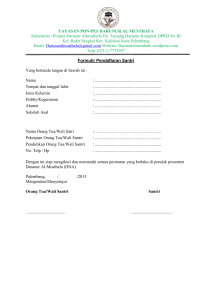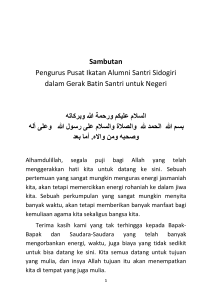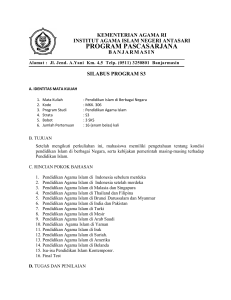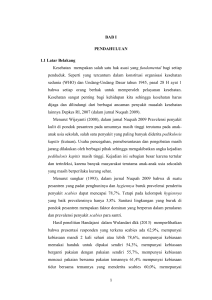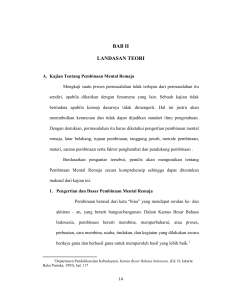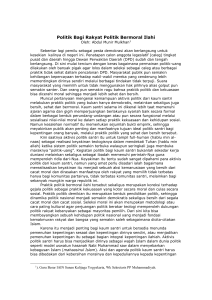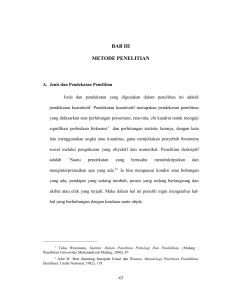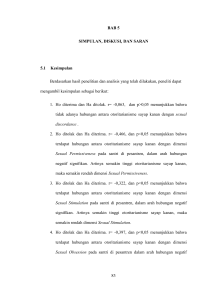(Saifullah, dalam Okezone, 2012) yang pertama
advertisement
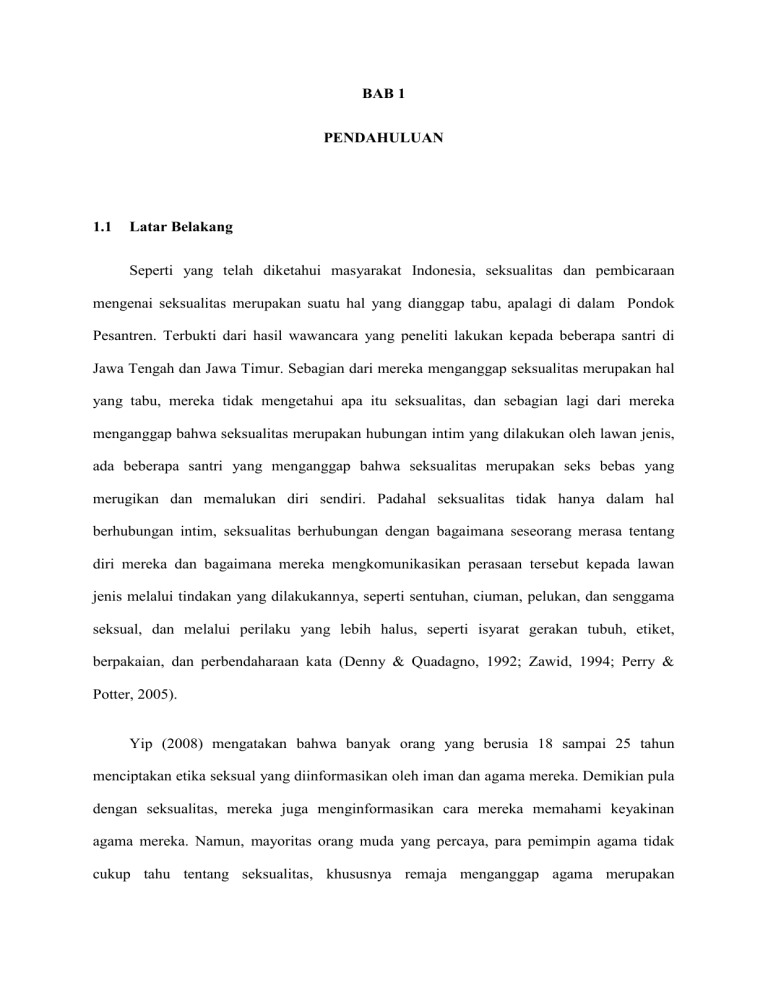
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Seperti yang telah diketahui masyarakat Indonesia, seksualitas dan pembicaraan mengenai seksualitas merupakan suatu hal yang dianggap tabu, apalagi di dalam Pondok Pesantren. Terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa santri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagian dari mereka menganggap seksualitas merupakan hal yang tabu, mereka tidak mengetahui apa itu seksualitas, dan sebagian lagi dari mereka menganggap bahwa seksualitas merupakan hubungan intim yang dilakukan oleh lawan jenis, ada beberapa santri yang menganggap bahwa seksualitas merupakan seks bebas yang merugikan dan memalukan diri sendiri. Padahal seksualitas tidak hanya dalam hal berhubungan intim, seksualitas berhubungan dengan bagaimana seseorang merasa tentang diri mereka dan bagaimana mereka mengkomunikasikan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus, seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata (Denny & Quadagno, 1992; Zawid, 1994; Perry & Potter, 2005). Yip (2008) mengatakan bahwa banyak orang yang berusia 18 sampai 25 tahun menciptakan etika seksual yang diinformasikan oleh iman dan agama mereka. Demikian pula dengan seksualitas, mereka juga menginformasikan cara mereka memahami keyakinan agama mereka. Namun, mayoritas orang muda yang percaya, para pemimpin agama tidak cukup tahu tentang seksualitas, khususnya remaja menganggap agama merupakan institusional mekanisme kontrol sosial yang berlebihan yang mengatur gender dan perilaku seksual, tanpa keterlibatan yang cukup dengan orang-orang muda sendiri. Lebih dari setengah partisipan penelitian Religion, Youth, and Sexuality (Yip dan Keenan, 2008), 65,1 persen terlibat dalam sebuah komunitas agama, dan lebih dari setengahnya (56,7 persen) menghadiri pertemuan keagamaan publik setidaknya sekali seminggu. Kebanyakan mereka berpikir bahwa ekspresi dari seksualitas seseorang yang diinginkan bervariasi: beberapa dari mereka percaya bahwa orang dewasa harus dapat mengekspresikan seksualitas yang mereka inginkan, sementara yang lain percaya bahwa ekspresi seksual harus terbatas pada pernikahan atau hubungan berkomitmen. Meskipun keragaman pendapat, yang paling menonjol adalah dukungan untuk hubungan monogami dengan 83,2 persen dari sampel. Pengalaman mereka dalam menghubungkan keyakinan agama mereka dan seksualitas yang beragam. Beberapa telah mengalami ketegangan dan konflik. Lainnya dapat menangani setiap konflik dengan iman dan seksualitas. Sementara ada juga peserta yang telah menemukan cara untuk mengakomodasi keduanya. Individu yang dijelaskan diatas memiliki otoritarianisme sayap kanan, yaitu kepatuhan psikologis kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang atau berkuasa dalam tatanan kehidupan seseorang individu yang mendukung otoritas yang kuat dalam masyarakat (Altemeyer, 1981). Demikian pula pada santri di pesantren, mereka memiliki iman dan otoritarianisme sayap kanan yang diduga tinggi. Para santri memiliki otoritas syariat yaitu AlQuran dan As-Sunnah, sedangkan didalam pesantren yaitu Kitab Kuning dan Kiai. Kitab kuning sebagai kurikulum pesantren ditempatkan pada posisi istimewa. Karena, keberadaannya menjadi unsur utama dan sekaligus ciri pembeda antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Pada pesantren di Jawa dan Madura, penyebaran keilmuan, jenis kitab dan sistem pengajaran kitab kuning memiliki kesamaan, yaitu sorogan dan bandongan. Kesamaan-kesamaan ini menghasilkan homogenitas pandangan hidup, kultur dan praktik-praktik keagamaan di kalangan santri (Zamakhsyari, 1998). Menurut Bruinessen (dalam Suprayogo, 2007), sikap hormat, takzim dan kepatuhan kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan mutlak diperluas sehingga mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya dan ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya. Bahkan sikap patuh tidak hanya diperuntukkan bagi kyai atau pengarang kitab, namun kepada keluarga kyai (anak) juga ditampakkan. Kepatuhan ini, bagi pengamat luar tampak lebih penting dari usaha menguasai ilmu, akan tetapi bagi kyai hal itu merupakan bagian integral dari ilmu yang akan dikuasainya. Dari otoritas dan norma yang ada tersebut, justru beberapa santri memiliki otoritarianisme sayap kanan yang rendah, dan mengalami gangguan seksual di pesantren seperti yang ditulis oleh Syarifuddin (2005), pesantren sering dijadikan tempat untuk menyalurkan hasrat libido santri pada santri lain. Di pesantren kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan umumnya dilakukan di tengah malam ketika “korban” sedang tertidur lelap. Praktik seperti ini dilakukan antar sesama jenis kelamin (laki-laki dengan lakilaki atau perempuan dengan perempuan). Seks antar sesama jenis kelamin inilah yang menjadi titik tekan buku Mairil Sepenggal Kisah Biru di Pesantren (Syarifudin, 2005). Gangguan seksual menurut Garos (1995, 1996) ada 4 faktor yaitu Discordance, Permissiveness, Sexual Obsession, dan Sexual Stimulation. Faktor pertama adalah Discordance, yaitu konflik, ketidakamanan, atau kegelisahan tentang perilaku seksual dan seksualitasnya. Faktor kedua adalah Permissiveness, yaitu individu yang "liberal" atau "unconventional" yang berorientasi tentang seks dan seksualitas. Faktor ketiga adalah Sexual Obsession, yaitu keasyikan dengan seks dan kesulitan dengan kontrol impuls. Faktor keempat adalah Sexual Stimulation, yaitu tingkat kenyamanan dengan seks dan gairah seksual yang tinggi. Gangguan seksual di beberapa pesantren salah satunya adalah nyempet dan mairil. Menurut Syarifuddin (2005), nyempet merupakan jenis atau aktivitas pelampiasan seksual dengan kelamin sejenis yang dilakukan seseorang ketika hasrat seksualnya sedang memuncak, sedangkan mairil merupakan perilaku kasih sayang kepada seseorang yang sejenis. Perilaku nyempet terjadi secara insidental dan sesaat, sedangkan mairil relatif stabil dan intensitasnya panjang. Namun dalam banyak hal antara nyempet dan mairil mengandung konotasi negatif, yaitu sama-sama terlibat dalam hubungan seksual satu jenis kelamin. Menurut Syarifuddin (2005), kondisi sosiologis dunia pesantren dengan pembinaan moral dan akhlak secara otomatis interaksi antara santri putra dan putri begitu ketat. Keseharian santri dalam komunitas sejenis, mulai bangun tidur, belajar, hingga tidur kembali. Santri bisa bertemu dengan orang lain jenis ketika sedang mendapat tamu. Itu pun jika masih ada hubungan keluarga. Praktis, ketika ada di pesantren –terutama pesantren salaf (tradisional)– tidak ada kesempatan untuk bertemu dan bertutur sapa dengan santri beda kelamin. Di samping tempat asrama putra dan putri berbeda, hukuman yang harus dijalankan begitu berat, bisa-bisa dikeluarkan dari pesantren, jika ada santri putra dan putri ketahuan bersama. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan perilaku nyempet di kalangan santri di pesantren begitu marak. Perilaku nyempet dan mairil biasanya dilakukan oleh santri tua (senior), tidak jarang pula para pengurus atau guru muda yang belum menikah. Menurut Syarifuddin (2005), umumnya yang menjadi korban nyempet dan mairil adalah santri yang memiliki wajah ganteng, tampan, imut, dan baby face. Hampir pasti santri (baru) yang memiliki wajah baby face selalu menjadi incaran dan rebutan santri-santri senior. Bahkan tidak jarang antara santri yang satu dan santri yang lain terlibat saling jotos, adu mulut, bertengkar (konflik) untuk mendapatkannya. Di pesantren berlaku hukum tidak tertulis yang harus dijalankan bagi orang yang memiliki mairil. Misalnya jika si A sudah menjadi mairil orang, maka si mairil tersebut akan dimanja, diperhatikan, diberi uang jajan, uang makan, dicucikan pakainnya, dan sebagainya; layaknya sepasang kekasih (pacaran). Jika si mairil dekat dengan orang lain pasti orang yang merasa memiliki si mairil tersebut akan cemburu berat. Penyebab gangguan seksual di pesantren (Saifullah, dalam Okezone, 2012) yang pertama adalah pesantren pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan lain seperti sekolah. Bedanya, di pesantren para pelajar disediakan tempat untuk menginap. Ihwal kekerasan fisik dan seksual di pesantren muncul karena para santri dalam jumlah besar tinggal di satu tempat. Dalam satu kamar berukuran 3x4 meter bisa terdapat 12 santri. Mereka beraktivitas, mandi, mencuci, makan, dan tidur bersama, mulai dari santri junior maupun senior. Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung penginapan seringkali membuat para santri harus tidur berdesakan dan mandi bersama-sama. Sehingga bisa dikatakan sama sekali tidak ada wilayah privat di pesantren. Interaksi fisik antar santri terjadi dalam interaksi tinggi. Pada waktu bersamaan, mayoritas santri sedang mengalami masa-masa pubertas. Mereka sedang asyik mencari tahu tentang fungsi dan perkembangan alat-alat reproduksinya. Dengan demikian tidak heran jika mereka saling memperhatikan atau membandingkan antara organ vital miliknya dengan teman-temannya. Bahkan ketika bergurau topik pembahasan pun mengarah pada seksualita. Jangan kaget bila di kegelapan malam tiba-tiba ada tangan yang menggerayangi. Keterbatasan sarana dan fasilitas ini juga memicu terjadinya kekerasan fisik. Perebutan wilayah kekuasaan oleh raja-raja kecil merupakan pemicunya. Kedua, peraturan di pesantren dalam hal pergaulan antara santri dengan santriwati atau antara santri dengan dunia luar dukup ketat. Pembatasan secara fisik untuk berinteraksi dengan lawan jenis berpotensi memicu santri tidak menemukan penyaluran dan membuat orientasi seksualnya sedikit menyimpang. Hal ini didukung dengan interaksi intens dengan sesama jenis. Ibarat kata pepatah, tak ada tali akar pun jadi. Ketiga, kekerasan seksual seringkali dipicu karena seorang whistle blower. Sangat mungkin dari ratusan santri, satu atau dua orang memang memiliki kelainan orientasi seksual. Terlebih untuk masuk pesantren belum ada test masuk. Sehingga semua orang bebas masuk asal membayar biaya administrasi. Para pelajar dari keluarga broken home dan anak-anak nakal pun seringkali dititipkan ke pesantren agar insaf. Alih-alih belajar, para santri dan santriwati bermasalah ini lebih sering merusak temannya. Keempat, di pesantren juga terdapat materi pelajaran seksualitas dengan merujuk pada literatur dari kitab-kitab kuning. Pelajaran ini sejatinya khusus untuk santri dan santriwati senior. Namun, santri-santri junior juga sering menyamar untuk mengikuti pengajian yang digelar tengah malam ini. Tidak menutup kemungkinan kekerasan fisik dan seksual juga dilakukan oleh para staf pengajar. Pasalnya, di pesantren dituntut adanya ketaatan penuh. Melihat dari fenomena di atas, diasumsikan jika individu memiliki ideologi otoritarianisme sayap kanan yang tinggi, seharusnya semakin rendah terjadinya gangguan seksual. Otoritarianisme sayap kanan menurut Altemeyer (1981) didefinisikan sebagai kepatuhan psikologis kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang atau berkuasa dalam tatanan kehidupan seseorang. Otoritarian awalnya dikembangkan sebagai suatu bentuk kepribadian (Adorno dkk, 1950; Altemeyer, 1981) sebelum Duckitt (2001) mengembangkan dan menyimpulkan bahwa sikap otoritarian berangkat dari suatu ideologi. Biasanya orang yang memiliki ideologi otoritarian adalah mereka yang bersifat konservatif, menolak hal yang baru, tidak menyukai perbedaan, dan menekankan pada satu pemahaman. Individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan otoritarian akan memandang yang memiliki pemahaman berbeda sebagai suatu ancaman dan keburukan. Orang yang berbeda ini dianggap akan merusak kestabilan pemahaman sehingga akan membentuk suatu dunia yang kehancuran atau tidak menentu. Orang beragama yang menganggap bahwa ajarannya yang paling benar dan agama lain sebagai suatu ancaman maka dapat dipastikan mereka akan memiliki prasangka yang negatif pada orang dari agama lain. Altemeyer (1996) menyebut bahwa individu berkepribadian otoritarian melakukan authoritarian aggression, yaitu agresi terhadap orang lain yang dirasakan sebagai sanksi dari otoritas. Agresi dapat berupa luka fisik, luka psikologis, pengambilan harta dan isolasi sosial. Individu dengan ideologi otoritarian memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap otoritas yang ada dalam masyarakat. Individu dengan kepribadian otoritarian menganggap pentingnya kepatuhan dan rasa hormat untuk dipelajari pada masa kanak-kanak. Individu dengan kepribadian otoritarian beranggapan otoritas harus diberi hak untuk memutuskan suatu hal walaupun melanggar hukum. Otoritas diartikan sebagai individu yang secara moral memiliki otoritas terhadap orang lain. Altemeyer (1996) menyebutnya sebagai authoritarian submission. Individu dengan kepribadian otoritarian memiliki aturan otoritarian. Aturan otoritarian keagamaan disebut konvensional karena didasarkan atas aturan lama, dan tidak menggambarkan bagaimana bersikap saat ini. Altemeyer (1996) menyebutnya sebagai conventionalism yang merupakan penerimaan, komitmen dan kepatuhan yang tinggi terhadap norma sosial tradisional dalam masyarakat. Norma dapat dikatakan sebagai norma kelompok, adat, agama dan rasa nasionalisme. Sedangkan individu dengan ideologi otoritarianisme sayap kanan yang rendah (kaum liberal) cenderung relatif anti-Pembentukan atau penetapan, dan lebih mendukung mereka yang melanggar tatanan sosial yang didirikan. Mereka menerima lebih dari individu atau kelompok yang dianggap tidak konvensional, dan cenderung untuk memegang keyakinan yang tidak konvensional sendiri. Mereka menempatkan nilai yang relatif tinggi pada kebebasan pribadi dan self-direction, dan tidak nasionalistik atau etnosentris. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual discordance pada santri di pesantren? 2. Apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual permissiveness pada santri di pesantren? 3. Apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual stimulation pada santri di pesantren? 4. Apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual obsession pada santri di pesantren? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual discordance pada santri di pesantren. 2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual permissiveness pada santri di pesantren. 3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual stimulation pada santri di pesantren. 4. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara otoritarianisme sayap kanan dengan sexual obsession pada santri di pesantren.