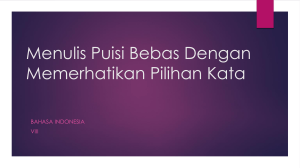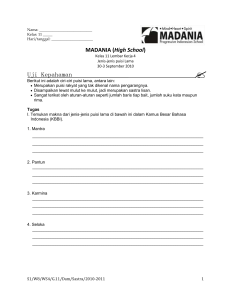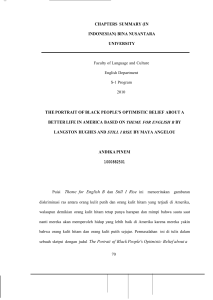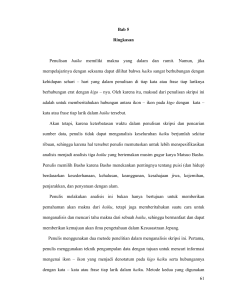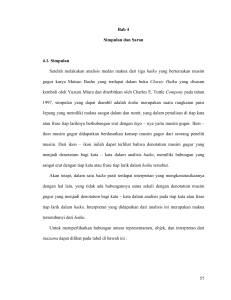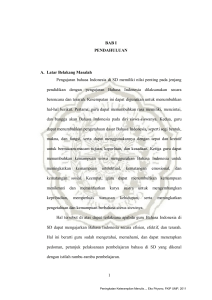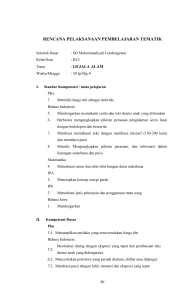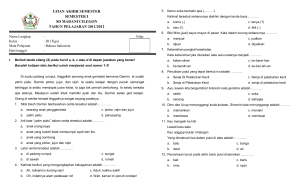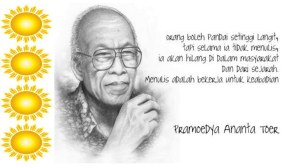Bab 2 Landasan Teori 2.1 Konsep Wabi Sabi Wabi sabi adalah
advertisement
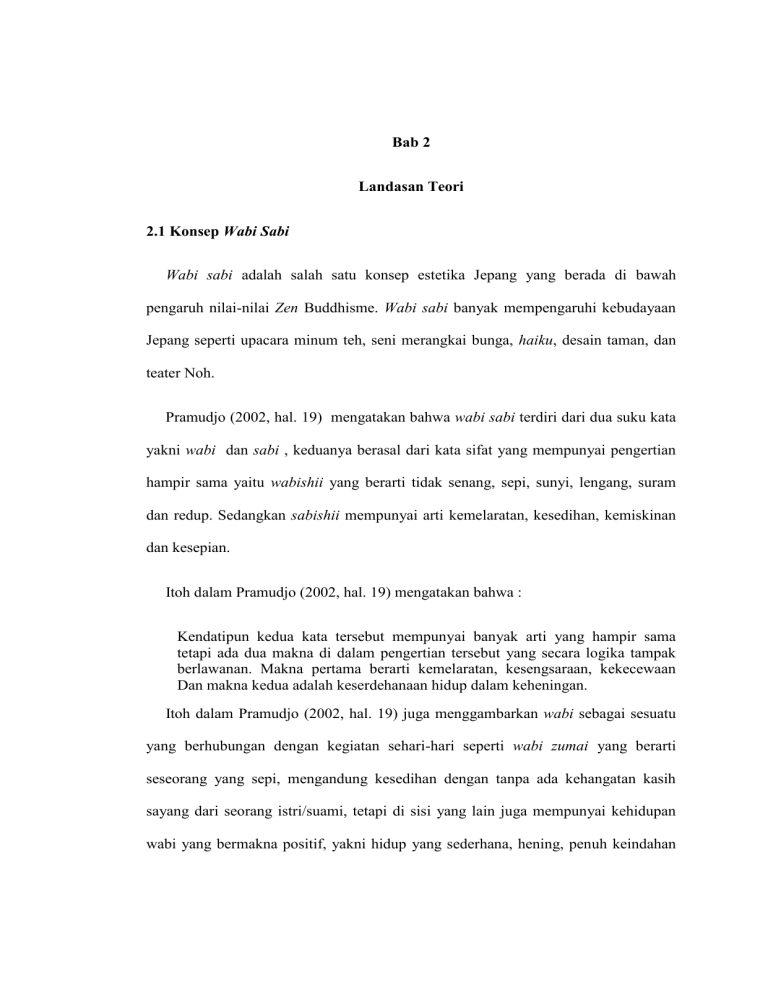
Bab 2 Landasan Teori 2.1 Konsep Wabi Sabi Wabi sabi adalah salah satu konsep estetika Jepang yang berada di bawah pengaruh nilai-nilai Zen Buddhisme. Wabi sabi banyak mempengaruhi kebudayaan Jepang seperti upacara minum teh, seni merangkai bunga, haiku, desain taman, dan teater Noh. Pramudjo (2002, hal. 19) mengatakan bahwa wabi sabi terdiri dari dua suku kata yakni wabi dan sabi , keduanya berasal dari kata sifat yang mempunyai pengertian hampir sama yaitu wabishii yang berarti tidak senang, sepi, sunyi, lengang, suram dan redup. Sedangkan sabishii mempunyai arti kemelaratan, kesedihan, kemiskinan dan kesepian. Itoh dalam Pramudjo (2002, hal. 19) mengatakan bahwa : Kendatipun kedua kata tersebut mempunyai banyak arti yang hampir sama tetapi ada dua makna di dalam pengertian tersebut yang secara logika tampak berlawanan. Makna pertama berarti kemelaratan, kesengsaraan, kekecewaan Dan makna kedua adalah keserdehanaan hidup dalam keheningan. Itoh dalam Pramudjo (2002, hal. 19) juga menggambarkan wabi sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti wabi zumai yang berarti seseorang yang sepi, mengandung kesedihan dengan tanpa ada kehangatan kasih sayang dari seorang istri/suami, tetapi di sisi yang lain juga mempunyai kehidupan wabi yang bermakna positif, yakni hidup yang sederhana, hening, penuh keindahan dan keanggunan yang mempunyai tujuan mendapatkan kepuasan spiritual dengan cara mengasingkan diri dari keramaian atau keduniawian. Sedangkan sabi, yang berasal dari kata sabishii berarti sunyi, sepi, sesuatu yang rusak akibat dari pengaruh cuaca atau udara, sehingga secara tidak langsung sabi berkaitan dengan “waktu”. Itoh dalam Pramudjo (2002, hal. 19) mengartikan keindahan sabi lebih banyak ditentukan oleh faktor waktu atau usia, karena waktu mempunyai kemampuan untuk menyiratkan esensi suatu benda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kato dalam Pramudjo (2002, hal. 21) menekankan bahwa wabi sabi identik dengan kewajaran atau alami. Dan menurutnya, kewajaran tersebut mempunyai pengertian “tidak sempurna, tidak lengkap dan tidak abadi”. Kriteria dari kewajaran itu adalah tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan hidup, sederhana, dan tidak menentang kodrat. Menurut Kato dalam Pramudjo (2002, hal. 21) : Nilai-nilai spiritual wabi sabi ini diperoleh dari hasil kontak manusia dengan alam yang dipadukan dengan pemikiran Tao, yakni mengkaitkan antara benda dan waktu, keduanya jika dipadukan berakibat tidak abadi, tidak lengkap dan tidak sempurna. Pemahaman wabi sabi dalam nuansa ketiadaan terhadap benda, merupakan efek dari bergulirnya waktu yang menimpa benda, sehingga menyebabkan benda menjadi renta, layu, retak, berlubang, mengelupas, berkerut dan perubahan wujud suatu benda itu sesuai dengan karakteristik masing masing benda. Secara keseluruhan, makna wabi sabi adalah kepasrahan dan ketulusan dalam menghadapi pergantian waktu, sehingga rasa itu dilukiskan oleh orang Jepang ke dalam karya seninya yang melukiskan keadaan yang hening, tenang, dan diam. Menurut Juniper (2003, hal. 1) : Wabi sabi embodies the Zen nihilist cosmic view and seeks beauty in the imperfections found as all things, in a constant state of flux, evolve from nothing and devolve back to nothing.” Terjemahannya : Wabi sabi mengandung pandangan ketiadaan Zen yang mencari keindahan dari ketidaksempurnaan yang ditemukan di semua benda yang terus berubah, yang berkembang dari ketiadaan menjadi ketiadaan lagi. Wabi sabi menawarkan keindahan ideal yang berfokus pada nilai keindahan yang terdapat dalam ketidakabadian yang bisa ditemukan dalam semua benda yang tidak sempurna. Ekspresi keindahan yang berada di antara kehidupan dan kematian, kebahagian dan penderitaan yang merupakan takdir kita sebagai manusia. Itoh (1993, hal. 7) menyatakan bahwa : Wabi may describe beauty in nature untouched by human hands, or it may emerge from human attempts to draw out instinctive beauty of materials. To discover wabi, one must have an eye for the beautiful, yet it is not an aesthetic understood only by the Japanese of old, but a quality that can be recognized by anyone, anywhere who is discriminating and sensitive beauty.” Terjemahannya : Wabi bisa diartikan sebagai keindahan alam yang tidak pernah disentuh oleh tangan manusia, atau bisa muncul dari manusia yang melukiskan keindahan dari material. Untuk menemukan wabi, seseorang harus mempunyai penglihatan akan keindahan, yang bukan sesuatu yang hanya dimengerti oleh orang Jepang dahulu saja, tetapi juga sesuatu yang bisa dilihat oleh siapa saja, dimana saja yang bisa membedakan dan peka terhadap keindahan.” Kemudian sabi (Itoh, 1993, hal. 7) jika sebuah hal atau benda berusia semakin tua, nilai atau keberadaannya tidak akan hilang dimakan waktu. Sebuah jam tangan baru tentu saja terlihat bagus. Namun, seiring dengan waktu, jam tangan itu bukan lagi jam tangan baru melainkan sebuah jam tangan yang tua, kusam dan kemungkinan memiliki banyak goresan. Jika dilihat dari sudut pandang konsep sabi, jam tangan tua itu terlihat semakin indah, karena jam tangan tersebut memiliki ‘sejarah’ yang dimilikinya seiring dengan perjalanan hidup pemiliknya. 2.1.1 Wabi Sabi dalam Zen Suzuki (2005, hal. 30) menyatakan bahwa, jika wabi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang merasakan kepuasan dalam hidupnya hanya dengan tinggal di sebuah gubuk kecil dengan ruangan berukuran dua tatami dan memakan sayur-mayur yang dipetik dari kebun pribadi. Karena wabi adalah bagian dari Zen, maka wabi bertujuan untuk menyadarkan manusia bahwa alam dan sekitarnya juga penting dalam kehidupan ini. Sampai saat ini, alam dan sekitarnyalah yang telah membantu kelangsungan hidup manusia. Keindahan yang tidak sempurna adalah keindahan yang antik dan primitif, yang disebut juga dengan sabi. Jika sebuah benda kesenian memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, maka di dalamnya pastilah terdapat unsur sabi. Sabi memiliki unsur ketidaksempurnaan yang kampungan dan kolot (Suzuki, 2005, hal. 32). Berikut ini menurut Hisamatsu (1997, hal. 29-37) Zen memiliki tujuh karakteristik yang secara tidak langsung berhubungan dengan konsep wabi sabi : 1. Fukinsei 「不均整」、‘asimetris’ Berarti ketidakteraturan atau asimetri. Hisamatsu mencontohkan fukinsei dalam hal seperti geometris, hal jumlah, seni ikebana dan kaligrafi, dan kedalaman atau ketinggian dari suatu permukaan. Dalam geometris, fukinsei adalah ketidaksempurnaan atau ketidakseimbangan apabila dicontohkan sebagai lingkaran penyok atau miring. Dalam hal jumlah, fukinsei dapat diartikan sebagai jumlah ganjil. Jumlah yang genap dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak, yang dapat dianalogikan sebagai simetris. Sebagai latar belakang kebudayaan Zen, asimetri fukinsei mempunyai makna membuang nafsu duniawi atau kehidupan bukan saja berorientasi pada kesempurnaan tetapi juga pada ketidaksempurnaan, karena sesuatu kesempurnaan yang sempurna adalah sesuatu yang tidak sempurna. 2. Kanso 「簡素」、‘kesederhanaan’ Karakteristik yang kedua memiliki arti kesederhanaan, tidak adanya kekacauan atau tidak adanya kecampuradukkan. Kesederhanaan yang paling tinggi adalah sesuatu yang dapat mewakili atau mencerminkan sifat dari suatu benda secara utuh yang diekspresikan melalui garis, warna, bentuk dan unsur-unsur lainnya. 3. Kokou 「枯高」、‘kekeringan yang agung’ Kokou punya arti menjadi kering dan agung, yang secara singkat berarti menjadi berpengalaman dalam hidup selama bertahun-tahun. Kasarnya dapat dianalogikan sebagai hilangnya indera pada kulit dan daging dan menjadi kering. Analogi ini menunjukkan telah dicapainya sesuatu yang terdalam, hilangnya sensualitas dari kulit luar dan menyisakan sesuatu yang paling esensial. Seringkali terdapat kalimat “menjadi kering” digunakan untuk mengungkapkan karakteristik yang penting dalam keindahan pada Zen, yaitu keistimewaan sebuah keindahan Oriental. Konsep keindahan menurut Zen, “menjadi kering” berarti puncak dari sebuah seni, penembusan sebuah intisari oleh seorang ahli dimana hal tersebut melewati batas seseorang dan ketidakdewasaan. 4. Shizen 「自然」、‘kealamian’ Karakteristik ini memiliki arti alami, natural, wajar atau bukan buatan. Karekteristik fukinsei juga harus mempunyai shizen. Meskipun asimetris, tapi juga harus terlihat wajar. Natural juga berarti tanpa berpikir. Dengan kata lain adalah menjadi diri yang sesungguhnya, tanpa adanya tujuan terhadap sesuatu hal, tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Alami dan natural bukanlah artifisial, dalam makna bukan dibuat-buat. Dalam hal ini adalah ekspresi yang tidak dibuat-buat, apa adanya, atau tanpa berpikir. Bukan artifisial adalah menjadi diri kita yang sesungguhnya. 5. Yuugen 「幽玄」、‘kedalaman esensi’ Karakteristik ini mempunyai arti kedalaman esensi atau makna yang mendalam. Dalam ekspresi, makna yuugen lebih kepada ‘esensi’ atau ‘maksud’ daripada ‘pengungkapan langsung secara keseluruhan’. Yuugen juga dapat diungkapkan sebagai sesuatu yang tidak berdasar atau tidak berakhir, yang dapat digambarkan dengan sumber yang dalam atau gaung tak berakhir. Hanya dari sesuatu yang sederhana, dapat digali sesuatu yang tak terbatas. Yuugen adalah kesederhanaan yang memungkinkan kita untuk membayangkan kedalaman isinya, seakan merasakan ‘gema’ yang tak terbatas, merasakan sesuatu yang tak mungkin didapat dari karya yang jelas dan mendetail. Yuugen juga punya makna kegelapan atau kesuraman. Kegelapan di sini bukanlah kegelapan yang berarti menakutkan, mencekam, ataupun kesuraman yang bermakna sengsara atau menyedihkan. Kegelapan di sini adalah kesuraman yang menenangkan. 6. Datsuzoku 「脱俗」、‘bebas dari ikatan’ Berarti bebas dari kebiasaan, aturan, rumusan dll. Bagi Zen, peraturan atau kebiasaaan tersebut akan menjadi penghalang atas aktivitas dan kreativitas. Kebebasan dalam Zen bukan berarti menjadi bebas secara akal sehat dan kemauan menurut peraturan-peraturan tapi merupakan perasaan untuk tidak berada di bawah peraturan. 7. Seijaku 「静寂」、‘ketenangan’ Adalah keheningan atau ketenangan. Tenang dapat diartikan sebagai tidak terganggu. Dalam konsep Zen, ketenangan itu diekspresikan dalam keadaan yang diam tapi punya bentuk bergerak. Oleh karena itu, bernyanyi, membuat suara, dan sebagainya, pada saat bersamaan juga membawa ketenangan, merupakan salah satu keistimewaan dari budaya pengungkapan Zen. 2.2 Konsep Haiku Hori (2004, hal. 10) menyatakan bahwa dahulu haiku sebelum zaman Masaoka Shiki (1867-1902) dikenal oleh banyak orang sebagai hokku . Menurut Hori (2004, hal. 10) : 発句とは、「連歌」の発端の句という意味である。五七五の長句と七七 の短句とを交互に鎖のように連ねる鎖連歌は、中世を通じて発達普及し、 社交の格好のアイテムとして愛好された。五七五の長句であること、当 座の季を重んじ、一句で意味が完結するよう言い切ると(切れ字を入れ る)、巻頭の句らしく長高く幽玄に句作りするなどが、その主たるもの である。 Terjemahannya : Hokku adalah bagian permulaan dari renga. Renga yang diselingi oleh 5-7-5 dan 7-7 silabel (kusari renga 鎖連歌) seperti rantai ini telah digemari oleh orang-orang sejak peredarannya di masa pertengahan. Dalam 5-7-5 silabelnya, hal yang paling utama adalah kata yang mengindikasikan musim pada saat haiku itu ditulis, kata yang menjadi hal yang ditekankan oleh pengarang yang diberi kireji, dan sifat misterius yang ada diawal sebuah haiku.” Hal yang sama dikemukakan oleh Beilenson (2008, hal. 1) yang menyatakan bahwa hokku (atau lebih sering disebut dengan haiku) adalah salah satu bagian dari puisi Jepang yang sudah berkembang ratusan tahun lamanya. Yang merupakan bagian awal dari tanka, puisi lima baris yang sering ditulis oleh dua orang sebagai permainan literatur. Menurut Beilenson (2008, hal. 2), biasanya haiku sangat sulit diterjemahkan secara harafiah dengan mempertahankan bentuk 17 silabelnya. Haiku berisikan banyak kutipan dan kiasan yang hanya dimengerti oleh orang Jepang. Menurut Beilenson (2008, hal. 2): The hokku – or more properly haiku – is a tiny verse-form in which Japanese poets have been working for hundreds of years. Originally it was the first part of the tanka, a five-line poem, often written by two peolple as a literary game.” Terjemahannya : Hokku, atau lebih dikenal sekarang sebagai haiku, adalah bagian kecil dari puisi Jepang yang telah dikerjakan selama ratusan tahun lamanya. Awalnya merupakan bagian pertama dari tanka, puisi lima baris yang sering ditulis oleh dua orang sebagai permainan literatur. Menurut Ueda (1995, hal 1) hokku, atau sekarang dikenal dengan haiku, terdiri dari tiga baris atau larik dalam bentuk 5-7-5 silabel. Berdasarkan sejarahnya, hokku adalah perkembangan dari renga, bentuk utama puisi Jepang yang berkembang pada abad keempat belas dan kelima belas. Biasanya mengandung suatu kata yang mengindikasikan musim pada saat haiku itu ditulis. Sedangkan menurut Katoku (2008, hal 8) : 俳句とは形式の面からいえば、俳句は五音、七音、五音の計十七から成 る最短詩型で、その中にはかならず季語一つを含んでいなければならな いものとされている。 Terjemahannya : Haiku, bila dilihat dari bentuknya, tersusun atas 5-7-5 bunyi atau 17 silabel yang didalamnya mengandung satu kigo. Menurut Reichhold (2002, hal 24) haiku Jepang terbagi menjadi tiga bagian yang tersusun atas lima on, tujuh on, dan lima on lagi pada baris terakhir. Susunan 5-7-5 on ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh para leluhur orang Jepang, yang tidak pernah lelah untuk meneliti hitungan pada on atau satuan suara dalam haiku yang mereka buat, hingga menemukan hitungan yang tepat, yaitu 5-7-5 on atau 17 silabel. Tanka atau haiku tidak hanya dibacakan seperti sedang membaca puisi, melainkan juga dinyanyikan seperti nyanyian yang dibawakan oleh penganut agama Budha kuno. Dalam puisi Jepang, selalu ada kata yang berfungsi sebagai pemberhenti, yang disebut dengan kireji, yang terletak diantara bait kedua dan ketiga. Contoh kireji yang sering digunakan oleh para penulis haiku adalah ya dan kana (Reichhold, 2002, hal. 29). Selain kireji, ada pula hal penting yang selalu ada dalam puisi Jepang. Hal penting itu adalah unsur kigo yang pasti selalu ada dalam haiku. Fungsi dari unsur kigo adalah untuk memberi informasi kepada pembaca haiku mengenai kapan puisi tersebut dibuat atau untuk menunjukkan kapan terjadinya suatu masalah yang terdapat dalam puisi tersebut (Reichhold, 2002, hal. 24-25). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ross (2002, hal. 12-13) menjelaskan : The essence of traditional haiku consists of two things. First, there is an association with nature through one of the seasons either by naming the season (kigo). The second essential part of traditional haiku is setting up a relationship between two images and separating those images with a punctuation mark (kireji). The kireji is thus an emotional and linguistic break that creats an ‘internal comparison’. This internal comparison supplied the dynamic feeling for many haiku.” Terjemahannya : Haiku tradisional terdiri atas dua esensi. Yang pertama, adanya asosiasi dengan alam melalui salah satu musim yang disebut dengan kigo. Esensi yang kedua adalah mendirikan hubungan antara dua gambaran yang dipisahkan menggunakan tanda baca yang disebut dengan kireji. Kireji merupakan jeda yang bersifat emosional dan linguistik yang menciptakan perbandingan yang ada di dalam haiku. Perbandingan tersebut memberikan perasaan yang dinamik dalam banyak haiku.” 2.3 Teori Pengkajian Puisi Mengenai macam-macam aspek yang dapat dikaji dari puisi, menurut Pradopo ( 2005, hal. 3) : Puisi sebagai salah sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan saranasarana kepuitisan. Dapat pula puisi dikaji jenis-jenis atau ragam-ragamnya, mengingat bahwa ada beragam-ragam puisi.” Menurut Pradopo (2005, hal. 13), “puisi sebagai karya seni itu puitis. Kata puitis sudah mengandung nilai keindahan yang khusus untuk puisi.” Pradopo (2005, hal. 3) berpendapat bahwa orang tidak akan dapat memahami puisi secara sepenuhnya tanpa mengetahui dan menyadari bahwa puisi itu karya estetis yang bermakna, yang mempunyai arti, bukan hanya sesuatu yang kosong tanpa makna. Selain itu, Wellek dalam Pradopo mengemukakan analisis seorang filsuf asal Polandia yang mengatakan bahwa lapis arti (units of meaning) berupa rangkaian fonem, suku kata, kata, frase, dan kalimat. Semua itu merupakan satuan-satuan arti. Rangkaian kalimat menjadi alinea, bab, dan keseluruhan cerita ataupun keseluruhan sajak. Rangkaian satuan-satuan arti ini menimbulkan lapis ketiga, yaitu berupa latar, pelaku, objekobjek yang dikemukakan, dan dunia pengarang yang berupa cerita atau lukisan. (Pradopo, 2005, hal. 15). Wellek dan Warren dalam Pradopo (2005, hal. 14) menyatakan bahwa : Puisi (sajak) merupakan sebuah struktur yang kompleks, maka untuk memahaminya perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Analisis yang bersifat dichotomis, yaitu pembagian dua bentuk dan isi belumlah dapat memberi gambaran yang nyata dan tidak memuaskan. Wellek dalam Pradopo (2005, hal. 14) juga menambahkan, puisi merupakan sebab yang memungkinkan timbulnya pengalaman. Hal ini berhubungan dengan pernyataan Altenbernd dalam Pradopo (2005, hal. 5), “puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan) dalam bahasa berirama (bermetrum)”. Selain itu, menurut Pradopo (2005, hal. 14), karya sastra bukan hanya merupakan satu sistem norma saja, melainkan juga terdiri dari beberapa lapis norma. Masingmasing dari norma tersebut akan menimbulkan lapis norma di bawahnya. Lalu, Riffaterre dalam Pradopo ( 2005, hal. 279) menyatakan bahwa : Puisi itu dari waktu ke waktu selalu berubah karena evolusi selera dan konsep estetik yang berubah. Akan tetapi, ada suatu esensi yang tetap, yaitu puisi itu menyatakan suatu hal dengan arti yang lain atau puisi itu menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Waluyo (1995, hal. 2) menyatakan bahwa dalam proses penulisan puisi, seorang penyair akan memilih kata dan memadatkan bahasa. Penyair akan memilih kata-kata yang memiliki keindahan dan arti yang paling tepat untuk mewakili maksud dari sang penulis syair. Sedangkan memadatkan bahasa berarti kata-kata yang diungkapkan haruslah memiliki banyak pengertian. Biasanya puisi diciptakan saat suasana perasaan penyair yang sedang peka, dimana suasana tersebut menuntut seorang penyair untuk membuat puisi tersebut secara spontan dan memiliki arti yang padat. Pradopo (2005, hal. 117) menambahkan analisis puisi tidak cukup hanya dengan menganalisis unsur-unsur sajak yang sengaja dipisah-pisah saja. Analisis puisi juga dapat dijelaskan secara keseluruhan dari sajak tersebut, karena sebuah sajak merupakan kesatuan yang utuh dan norma-norma yang terdapat dalam sajak itu saling berhubungan erat satu sama lainnya. Melalui analisis secara menyeluruh dan memiliki kaitan yang erat, makna sajak dapat dimengerti seutuh sajak tersebut. Untuk mendapatkan makna utuh dari sebuah sajak, diperlukan analisis secara struktural (susunan unsur-unsur bersistem), semiotik (simbol-simbol) dan intertekstual (hubungan antar teks dengan sajak-sajak yang terbit sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan antar teks dengannya).