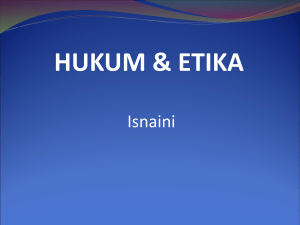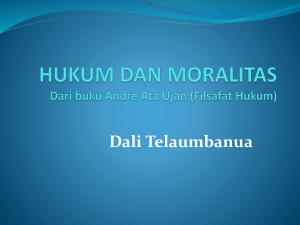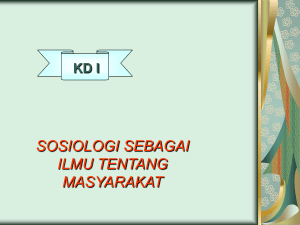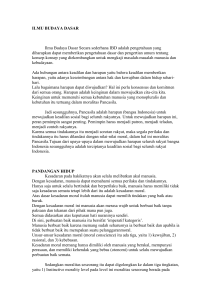Konsep Moralitas Sosial Emile Durkheim BAB I PENDAHULUAN A
advertisement

Konsep Moralitas Sosial Emile Durkheim BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah. Manusia pada eksistensinya di dunia, sebagai khalifah untuk menjaga, memelihara dan mengelola alam beserta isinya, utamanya manusia dengan manusia lainnya. Hal inilah manusia diberikan akal budi untuk berpikir mencari kepuasan dari perbuatannya atau mencari mana yang baik dan buruk dan sekaligus menunjukkan bahwa manusia sangat erat hubungannya dengan moralitas. Dari awal sampai sekarang dalam perkembangan ke-hidupan bumi, manusia telah banyak mengalami per-kembangan, evolusi pemikiran dan perubahan tatanan kehidupan, sehingga timbul berbagai pergolakan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, utamanya integrasi manusia dengan sesamanya. Hal ini perlu dicermati dan dikaji, persoalan yang satu (individu) membantai yang lainnya, atau sebaliknya sekelompok gerakan (kolektif) membantai kelompok yang lainnya, hal ini menjadi pergolakan egoistis, yang tidak melihat kebenaran, pentingnya solidaritas dalam kehidupan, keselarasan diantara keduanya termasuk keselarasan seluruh umat manusia. Pada prinsipnya, manusia dalam perbuatan dan kehendaknya mengarah pada suatu titik (tujuan) yang tinggi (esensi), Aristoteles menandaskan bahwa perbuatan manusia bagaimanapun mengejar sesuatu yang baik. Baik adalah sesuatu yang menjadi arah semua hal, sesuatu yang dikejar atau dituju, dan tujuan adalah sesuatu yang untuknya sesuatu itu dikerjakan.[1] Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain, hidup berbagai rahasia yang banyak ragam dan misteri, maka manusia perlu persatuan dan saling tolong menolong. Gabriel Marcel (1889-1973), menjelaskan dan keterikatan antara sesama manusia adalah: “Aku hanya mungkin mencapai kesempurnaan, kalau ia mengarahkan dirinya kepada orang lain, sehingga tanpa menghayati itu hidupnya mustahil memadai bagi panggilannya yang paling inti. Aku dan Engkau saling menghidupi, sehingga pada hakikatnya mereka tidak dapat dicairkan satu dari yang lain. Mereka dapat memberi wujud kongkrit kepada saling terjalinan mereka dan kesetiaan dan cinta. Menurut Marcel, kesatuan antara Aku dan Engkau dapat menghasilkan kepenuhan hidup sebagai manusia yang merupakan penyinaran intinya yang paling dalam, yang pada gilirannya memantulkan keterjalinan Aku dan Engkau yaitu Allah ”.[2] Manusia (individual) hidup berkumpul dalam lingkungan masyarakat (kolektif), yang dalam sejarah dikatakan bahwa mulai dari zaman Yunani Kuno (dimana masa ini persoalan kemasyarakatan sudah menjadi perhatian, namun belum menjadi pusat perhatian sepenuhnya),[3] sampai sekarang abad moderen, persoalan kemasyarakatan menjadi ciri khas para filusuf, utamanya persoalan moralitas yang menjadi bagian dari persoalan etika sebagai bagian yang sangat penting, mengingat kehidupan masyarakat yang serba pluralistik, membutuhkan perhatian yang serius dan perlu penyelesaian. Demikian halnya di Perancis, persoalan-persoalan sosial bergejolak. Bahkan perubahan-perubahan sosial[4] menjadi bahan pikiran. Maka persoalan–persoalan yang timbul dan solusi yang diberikannya tidak dapat mengatasinya. Revolusi Perancis dicanangkan untuk mengubah tatanan sosial yang terjadi pada abad ke-17 dan 18, mulai dari faham Feodalisme diterapkan, sehingga masyarakat buruh dan tani menjadi kaum yang tidak dapat menikmati kehidupan bebas, demikian lagi sistem pemerintahan yang menganut Absolutisme menjadi pedoman raja-raja, persoalan perbedaan kelas yaitu, atas, menengah dan bawah tidak hentihentinya menjadi pertentangan. Maka lahirlah perlawanan-perlawanan yang mengakibatkan peperangan dan saling menumpahkan darah. Tapi gerakan revolusi tidak dapat dikuasai lagi dan tidak dapat merubah tatanan sosial, sampai pada tahun 1792 di Perancis “Republik” di Proklamasikan dan tahun 1799 Napoleon melakukan gerakan perebutan kekuasaan sebagai orang yang sukses untuk Republik dan menobatkan dirinya sebagai kaisar pada tahun 1807, hingga abad ke-19 sistem Liberlisme dan sosialisme menjadi faham masyarakat Eropa menuju masyarakat yang demokratis moderen.[5] Emile Durkheim merupakan salah seorang dari tiga tokoh yang dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar sosiologi bersama Karl Marx dan Max Weber dalam berbagai penelitian aspek-aspek sosial. Namun tidak perlu disangkal, dalam konseptual pemikirannya tidak banyak persamaan, bahkan Durkheim banyak menentang sosialisme yang “Revolusioner” dari Marx Karl Marx menempatkan kerja dalam konteks keseluruhan hidup manusia, sehingga ia berpendapat bahwa pada hakikatnya manusia adalah “pekerja”, mengingat bahwa pada dasarnya segala-galanya berakar pada materi, jadi kerja tidak hanya merupakan inti dari individual, tetapi menerangkan dia dengan kolektifitas besar yaitu umat manusia beserta sejarahnya.[6] Atau dengan kata lain, Marx cenderung melihat masyarakat sebagai wahana dan sekaligus mekanisme penyangga dari berbagai konflik. Durkheim sangsi akan teori Marx di atas (revolusioner) sebagai cara pemecahan yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang bergejolak. Menurutnya masyarakat memerlukan peneguhan dasar “moralitas” yang baru,[7] Konsensus yang dimaksud adalah “persepakatan” atau kesepakatan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Demikian halnya dalam persoalan “perilaku sosial” Max Weber memandang lain dari Durkheim, bagi Weber adalah: “Prilaku sosial bukanlah struktur-struktur sosial yang pertama-tama menghubungkan orang atau menentukan isi corak kelakuan mereka, melainkan arti-arti yang dikenakan orang-orang kepada kelakuan mereka.”[8] Durkheim dengan sosialismenya dalam sosiologi moderen, menjelaskan pola-pola interaksi sosial antara seseorang dengan yang lain, melainkan berdasar pada tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dan laranganlarangan yang dikenakan oleh kolektifitas yang berlaku pada anggotanya (individu). Dari berbagai paparan singkat di atas, nampak kepada kita, akan perjuangan Durkheim dalam merintis moralitas, khususnya di Perancis sebagai bagian Eropa yang mengalami situasi transpormasi sosial yang juga dialaminya pada masa itu. Dalam konsep pemikiran Durkheim ada hal yang unik untuk dicermati, persoalan-persoalan ketimpangan sosial memerlukan moralitas, yang arah pemikirannya yaitu dengan jalan Positivisme yang murni, Ilmiah Rasionalis dan Sekuler, sehingga memandang tentang “Ilmu Moralitas” sebagai: “Ketentuan moral dan hukum, pada dasarnya me-mantulkan keperluan sosial yang hanya bisa dimasukkan oleh masyarakat itu sendiri-sesuatu yang berdasarkan pada pandangan “kolektif”, maka bukanlah tugas kita untuk mendapatkan (ketentuan) etik dari ilmu pengetahuan, melainkan membentuk suatu ilmu tentang etika”.[9] Demikian pula moralitas baginya, bukanlah saja sesuatu yang deduktif, melainkan sesuatu yang berangkat dari kenyataan empiris dan ilmiah serta bercorak pasca pengalaman. Dengan gagasan filosofisnya ini, Ia nampak sebagai seorang yang konservatif, yang ingin ketentuan sosial berdasarkan ketentuan kolektif (kesadaran), dan tidak ingin kembali pada ketentuan sosial yan lama dan juga sebagai orang yang progresif yang mencari dasar baru dari solidaritas sosial. Persoalan moral dalam Islam, yang lebih dikenal dengan istilah “akhlak”, dalam hal ini menganut suatu tata aturan (ajaran moral) tersendiri (moral keagamaan Islam), yang dengan pasti tidak akan lepas dari pedoman ajarannya yaitu Alqur’an dan Hadis, karena diyakini bahwa Alqur’an diturunkan kepada Nabi pilihan Tuhan Yang Maha Muliah, untuk memberikan petunjuk kehidupan bumi, termasuk persoalan prilaku kehidupan manusia (sosial), sebagaimana dalam sabdanya: ق ال و س لم ع ل يه هللا صل هللا ر سول إن ب ل غه إن ه ؛ مال ك عن ث نى حد: [األخ الق ح سن ألت مم ب ع ثت10] Artinya: “Telah sampai kepadaku kabar; “Bahwa sesungguhnya Rasullah saw. menyampaikan: Bahwa diutusnya beliau untuk menyempurnakan akhlak yang muliah”. Secara teoritis dan konseptual, umat Islam yakin akan eksistensinya itu, sebagai rambu, jalur yang menuju pada hakikat manusia, yang namun tidak perlu dipungkiri dalam ajaran ini, wahyu, akaliah dan kekuatannya tetap diakui eksisitensinya serta kapasitasnya dalam melihat fakta realitas yang bergejolak sebagai fenomena kehidupan yang dinamis dialam semesta. B. Rumusan dan Batasan Masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah di-kemukakan, lahirlah suatu permasalahan, yang penulis mencoba mengemukakan rumusan permasalahan yang selanjut-nya akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut: Bagaimana corak moralitas sosial yang ditawarkan Emile Durkheim? Bagaimana pandangan etika Islam tentang moralitas Durkheim? C. Hipotesis. Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan jawaban sementara, sebagai berikut: Moralitas sosial yang ditawarkan oleh Durkheim adalah suatu moral yang bersifat atau bercorak positivisme, rasionalis dan sekularis dan objektif dalam melihat sesuatu, dimana ketentuan moral lahir dari konsensus secara kolektif. Sehingga moralitas sosial bukan hanya sebagai “kewajiban” (ketentuan), melainkan kebaikan ketika manusia telah dihadapkan pada realitas sosial, serta “ketentuan-ketentuan” itu berada diluar diri “sipelaku”, sehingga misalnya sesuatu yang salah tidak harus menderita, sehingga ia sadar dan menghayati aturan-aturan moral dari sudut kemasyarakatan. Islam memiliki konsep etika yang lebih dikenal dengan istilah ahklak, dalam mengarungi berbagai fenomena dan keaneka ragaman realitas, untuk mengatur integritas sesama manusia, etika Islam yang berakar pada ketentuan ilahiah dalam Alqur’an dan Hadis Rasulullah saw., yang menjadi pedoman pokok umat Islam dalam prilaku kehidupannya. Etika Islam mengakui moralitas bukan hanya menyangkut persoalan baik dan buruk, tetapi sesuatu yang terkait dari keseluruhan komponen dalam dunia, namun berbeda karena Durkheim yang sekularis, sedangkan etika Islam mengakui dua kekuatan yang ada dalam diri manusia, demikian pula etika islam memiliki konsep moral tersendiri yang termuat dalam “wahyu” dan “hadis” yang meliputi segala zaman manusia (pra, sedang berlangsung dan pasca pengalaman) tercantum dan tersirat di dalamnya. D. Pengertiaan Judul. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai judul skripsi ini, maka perlu diberikan kata yang dianggap kurang jelas, untuk memberikan batasan pemikiran agar tidak menyulitkan dalam pembahasan. Judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk menyelidiki dan mempelajari bagaimana konsep moralitas sosial Emile Durkheim, maka penulis menganggap perlu memberikan pengertian, sebagai berikut: Moralitas; pola-pola, kaidah tingka laku, budi bahasa yang dipandang baik dan luhur dalam suatu masyarakat tertentu.[11] Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia yang dengan itu ia berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruknya perbuatan manusia.[12] Keseluruhan normanorma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat.[13] Dan kerangka yang rasional, tidak memihak, bebas dan objektif.[14] Sosial; Perkenaan dengan masyarakat, perlu adanya komunikasi, suka memperatikan kepentingan umum.[15] Studi; kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.[16] Analisis; Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau menguraikan suatu pokok atas bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan.[17] Filsafat; pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat segala yang ada, sebab, asal dan teori-teori yang mendasari alam pikiran secara mendalam.[18] Dan filsafat atau pemikiran kritis normatif tentang moralitas.[19] Akhlak; Hal-hal berkaitan dengan sikap, prilaku dan sifat-sifat manusia dalam berinteraksi dengan dirinya, sasarannya, makhluk-makhluk lain dan dengan Tuhan, atau berarti tabiat, perangai dan adat kebiasaan.[20] Emile Durkheim; sosiolog Perancis, lahir di Epinal tahun 1858-1917, beliau mengajar sosiologi di Universitas Bordeaux dan Sarbonne. Beliau menentang para ahli sosiologi tahun 1980-an yang menganggap individu sebagai dasar terbentuknya tatanan sosial.[21] Dari pengertian kata judul di atas, dapat diberikan kesimpulan adalah suatu penelitian ilmiah mengenai kerangka pemikiran Emile Durkheim tentang moralitas yang ingin memperbaiki tatanan kehidupan, kemudian akan dikaji lebih lanjut dalam sudut pandang Filsafat Akhlak. E. Tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis perlu memberikan sedikit gambaran tentang relevansi antara masalah pokok yang akan dikaji dengan sejumlah teori dalam berbagai referensi yang penulis gunakan. Setelah penulis menelitih secara saksama tentang masalah yang akan dibahas dalam judul skripsi ini, maka penulis berkesimpulan bahwa judul ini telah ada yang membahasnya dalam judul “Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas” karangan Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, namun berbeda dengan sudut tinjauan (analisis) yang penulis kaji, dan sangat menarik untuk dikaji. Adapun rujukan literatur yang penulis gunakan adalah literatur yang termuat dalam berbagai buku hasil terjemahan kedalam bahasa Indonesia, diantaranya sebagai berikut: “Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas” karangan Taufik Abdullah dan A.C. Van der Leeden yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, yang didalamnya termuat ulasan-ulasan mengenai pemikiran Durkheim dalam hal moralitas, selanjutnya buku “Realitas Sosial” Refleksi Filsafat atas Hubungan Individu – Masyarakat dalam Cakrawala Sosiologi, karangan KJ. Veeger yang diterbitkan oleh Gramedia, yang memuat pembahasan metodologi dan kasus-kasus prilaku individu dalam masyarakat, kemudian buku “Tata, Perubahas dan Ke-timpangan” Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi, karangan L. Laeyendecker diterbitkan oleh Gramedia, yang didalamnya memuat tentang moral dan bentuk-bentuknya, metodologi dan prilaku individu dalam masyarakat, selanjutnya buku “Pendidikan Moral; Suatu Study Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan” Karangan Emile Durkheim yang dialih bahasakan oleh Drs. Lukas Ginting dari judul “Moral Education” yang di dalamnya memuat masalah pemikiran Durkheim mengenai Moral yang diajarkan di Sarbonne, penerbit Erlangga pada tahun 1990, kemudian buku “Emile Durkheim Aturan-aturan Metode Sosiologis” karangan Prof. DR. Soerjono Soekanto S.H, M.A, diterbitkan oleh Rajawali Perss tahun 1985, yang memuat tentang metode sosiologinya, serta berbagai literatur yang banyak menjadi kutipan dan berkaitan dengan judul pembahasan ini, semoga kita semua memperoleh tambahan wawasan intelektual dan kritis dalam melihat realitas dengan positif dari karya tulis ilmiah ini. F. Metode Penelitian. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, diperlukan suatu metode sebagai petunjuk jalan penelitian yang sisitimatis dan dapat dipertanggung jawabkan. Maka penulis dalam penulisan ini, menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut: 1.Metode Pengumpulan Data. Dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh secara keseluruhan adalah data yang dihimpun dari data kepustakaan, baik secara pribadi maupun yang bersifat umum, maka penulis menggunakan metode penelitian pustaka atau Library Research yakni dengan jalan membaca atau mengutip berbagai buku literatur yang ada kaitanya dengan objek yang dibahas pada skripsi ini. 2.Metode Pendekatan. Pendekatan Sosiologis yaitu membahas suatu permasalahan berdasarkan pada studi mengenai hubungan kelompok manusia dengan melihat bahwa hukum kemajuan adalah tindakan kehidupannya.[22] Pendekatan Historis yaitu membahas suatu permasalahan berdasarkan data masa lalu (sejarah) atau yang berlangsung pada masa lalu yang merupakan rangkaian peristiwa masa sekarang maupun tidak. Pendekatan Filosofis yaitu membahas suatu permasalahan dengan jalan melakukan perenungan yang mendalam, rasional, terarah, untuk mencapai atau sampai pada hakikat sesuatu, baik yang menyentuh sesuatu yang ada sekarang maupun yang mungkin ada.[23] 3.Metode Pengolahan Data. Dalam metode ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut: Metode Induktif yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum. Metode Deduktif yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat umum, kemudian diterapkan kepada yang bersifat khusus atau kebalikan dari Induktif.[24] Metode Komperatif yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan menggunakan atau melihat beberapa pendapat kemudian membandingkan dan mengambil yang kuat atau dengan jalan mengkompromikan beberapa pendapat tersebut. G. Tujuan dan Kegunaan. Adapun maksud dan dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penelitian terhadap suatu masalah yang sedang dikaji adalah sebagai berikut: Menguji kebenaran suatu teori moralitas sebagai Ide yang ditawarkan oleh Durkheim di Prancis untuk mengubah tatanan yang dianggap ambruk pada masa itu. Mencoba mengangkat permasalahan moralitas, yang penulis anggap relevansi dengan kondisi Indonesia, terutama perubahan tatanan sosial yang mengalami transpormasi. Mengkaji teori moralitas Durkheim, dimana beliau dikenal sebagai peletak dasar dan pejuang untuk memperbaiki masyarakat, yang sampai sekarang dikenang oleh masyarakat Prancis. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini yang dimaksud adalah sebagai berikut; Kegunaan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya. Kegunaan praktis yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat dengan jalan memberikan tambahan wawasan dan loncatan berpikir demi terwujudnya pembangunan bangsa, negara dan agama. H. Garis-garis Besar Isi Skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima Bab, mengawali pembahasan dalam tulisan ini, dikemukakan Bab I sebagai Bab pendahuluan yang memuat; tentang latar belakang sebagai gambaran tentang permasalahan yang dibahas, dari situlah timbul beberapa permasalahan atau rumusan masalah yang menjadi kajian pokok isi skripsi, yang dilanjutkan dengan hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan pengertian judul sebagai gambaran untuk menghindari terjadinya interpretasi yang luas dalam judul skripsi ini, kemudian mengetengahkan metode penelitian dan tujuan dan kegunaan penelitian serta diakhiri dengan garis-garis besar isi skripsi. Pada Bab II, dikemukakan tentang biografi Emile Durkheim yang memuat; latar belakang kehidupannya, karya-karyanya, dan metodologi pemikiran sosiologinya. Pada Bab III, sebagai pembahasan inti skripsi ini, yang mengemukakan tentang corak moralitas sosial Emile Durkheim yang memuat; pengertian moralitas, dilanjutkan dengan unsur-unsur moralitas dan beberapa persoalan prilaku moralitas sosial yang dianggap suatu permasalahan yang banyak terjadi pada masanya (lingkungannya). Pada Bab IV, sebagai Bab pembahasan tentang tanggapan etika Islam (akhlak) mengenai pemikiran Durkheim yang meliputi; persoalan manusia dan moralitas perbuatannya, dilanjutkan dengan tanggapan etika Islam tentang unsur-unsur moralitas dan etika Islam dan prilaku moral kehidupan. Pada Bab V, sebagai Bab penutup dalam penulisan skripsi ini, dimana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan landasan berpikir dan penelitian serta saran-saran sebagai rangkaian dalam skripsi ini. [1]Lihat W. Poespoprodjo, L.HP, Filsafat Moral; Kesusialaan Dalam Teori dan Praktek (Cet. II; Bandung: Komadja Karya, 1988), h. 19 [2] P. Leenhouwers, Men Zijn Een Opgave! Op Weg Mec Zichzelf, diterjemahkan oleh K,J. Veeger dengan judul “Manusia dalam lingkungannya; Refleksi Filsafat tentang manusia (Jakarata : Gramedia,1988), h. i [3]Lihat K. Bertens, Panorama Filsafat Moderen (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 186-187 [4]Lihat L. Laeyerdecker, Tata, Perubahan dan Ketimpangan ;Suatu Pengantar Sejarah Sosiaologi (Cet. II; Jakarta: Gramedia,1991), h. 1-32 [5]Lihat Ibid., h. 38-43 [6]Lihat P. Leenhouwers, op.cit., h. 260-260 [7]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas, Edisi I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 7 [8]K.J. Veeger, Realitas Soaial; Refleksi Filsafat Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sosiologi (Cet. III; Jakarta: Gramedia, 1990), h. 175 [9]Tufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 3 disadur dari buku Durkheim, The Division in Society, h. 33 [10]Imam Malik Ibnu Anas ra., Al-Muwaththa’ (Bairut: Darul Al-Kabil, 1414 H), h. 789 [11]Ensiklopedia Indonesia, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru – Van Houve, 1983), h. 2288 [12]Lihat W. Poespoprodjo L. PH., op.cit., h. 102 [13]Franz Magnis Suseno, et.all., Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa PBI-PBVI (Cet. III; Jakarta: Gramedia, 1993),h. 9 [14]Lihat Robert C. Solomon, Ethics; a Brief Intrrudaction, dialih Bahasakan oleh R. Andre Karo-karo dengan judul “Etika; Suatu Pengantar” (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 78 [15]Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 855 [16]Ibid., h. 860 [17]Lihat ibid., h. 32 [18]Lihat ibid., h. 242. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata philo berarti “cinta” dan sophia berarti “ilmu pengetahuan”, sehingga kedua kata tersebut dirangkai menjadi philosophia yang bermakna “cinta ilmu pengetahuan”. Lihat Louis O. Kattsoff, Elements of Philosophy, dialih bahasakan oleh Soejono Soemargono dengan judul “Pengantar Filsafat” (Cet. V; Yokyakarta: Tiara Wacana Yokya, 1992), h. i lebih lanjut Filsafat bermakna berpikir secara mendalam tentang hakikat segala sesuatu sampai pada akar-akarnya. Ibid., h. 3-16 [19]Franz Magnis Suseno, et.all., loc.cit. [20]Depaetemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jilid I (Jakarta: CV. Anda Utama, 1992), h. 104 [21]Lihat Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h.430-431 [22]Lihat Ridwan Tang, Metodologi Research; Suatu Himpunan Kuliah (Ujungpandang: Fak. Ushuluddin IAIN Alauddin UP., 1993), h. 20 [23]Lihat H. Hadari Nawawi dan H. M. Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosiologi (Cet. II; Yokyakarta: Gaja Mada University, 1995), h. 66 [24]Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi Resesarch, Jilid I (Cet XXVII; Yokyakarta: Andi Offset, 1994), h. 36-49 BAB II BIOGRAFI EMILE DURKHEIM A. Latar Belakang Kehidupannya. Pergolakan revolusi Eropa membawa dampak yang sangat menyensarakan tatanan kehidupan, utamanya persoalan sosial menjadi ambruk saat itu, melihat hal ini, muncul berbagai tokoh-tokoh sosiologi yang menentang berbagai konsep, utamanya konsep yang beranggapan bahwa individu sebagai dasar terbentuknya tatanan kehidupan sosial.[1] Dari realitas pergolakan jalannya kehidupan dari hari-kehari, justru konsep yang demikian itu membawa masyarakat terpecah-pecah, persatuan dan keutuhan masyarakat terancam hancur, karena konsep individualis yang semuanya mengandalkan dirisendiri dan yang paling diutamakannya, serta sifat toleransi semakin menipis. Kondisi semacam ini, tampillah salah seorang tokoh yang bernama Emile Durkheim, dilahirkan 15 April di Epinal[2] tahun 1858, anak dari seorang Rabbi.[3] Daerah tersebut lebih dikenal dengan kota kecil Lorraine, mereka adalah keluarga besar Yahudi Perancis.[4] Pada awal perkembangannya, dalam studinya Ia mula-mula belajar teologi, karena Ia berkeinginan menjadi seorang pendeta Yahudi (rabbi), karena pengaruh seorang guru wanita Katolik, Ia cenderung kearah bentuk mistik Katolisme, tetapi akhirnya Ia menjadi penganut agnotisisme. Pada umur 18 tahun, Ia pergi ke Paris guna mempersiapkan diri untuk masuk Ecole Normale Supereriure. Tahun 1878, Ia mengikuti ujian bersama dengan Bergson, tetapi Ia ditolak, setelah setahun kemudian Ia lulus dan belajar selama 4 tahun di lembaga tersebut, tapi Ia tidak merasa bahagia di tempat itu, karena beberapa pengajar yang menurutnya dibawah standar dan bergaya literer dan kurang eksakta, tiga tahun kemudian ia lulus pada urutan ke-2 dari belakang.[5] Pada tahun 1882 setelah lulus, Ia menjadi guru sekolah menengah, kemudian Ia belajar filsafat di Jerman walaupun tidak jelas kapan Ia mulai, dan di mana, namun Ia tertarik pada karya-karya ahli-ahli filsafat seperti Auguste Comte, F. de Coulenges, C.H. Smint Simon, Ia juga belajar karya-karya psikologi Wundt dan Herbert Spencer, dalam tahun 1887, Ia menjadi Dosen ilmu sosiologi di Universitas Bordeaux[6] dan mencapai gelar Professor dalam ilmu sosial dan pedagogi.[7] Dan pada tahun 1889, Ia bersama beberapa muridnya membina kelompok stady dan menerbitkan majalah I’Annee Sociologique dan pimpinannya beliau sendiri, sampai pada tahun 1902, Ia berangkat ke Paris untuk mengganti gelar guru besar dalam ilmu pedagogi di Sarbonne dan diangkat sebagai guru besar di perguruan tinggi I’Ecole Normale Superieure.[8] Kelompok studi yang dibimbingnya tetap aktif dan sampai tahun 1912, Ia menulis karya-karya penting yang menyangkut unsur-unsur elementer dari kehidupan ke-agamaan, yang banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran para sarjana sosiologi dan sarjana antropologi pada masa itu.[9] Pada tahun berikutnya (1913), untuk pertama kalinya ke Eropa dan dalam surat tugas mengajarnya disertai dengan kata sosiologi[10] untuk memberikan keterangan bahwa beliau adalah geru besar yang menangani mata kuliah sosiologi di Universitas di Eropa, sampai pecahnya perang dunia ke-1. Ia menghentikan aktivitas kelompok studinya, dikarenakan banyak anggota kelompok studi tersebut dipanggil masuk dinas militer (tentara), dan banyak di antara mereka gugur di medan perang, termasuk anak Durkheim yang bernama Andre Durkheim, akibat peristiwa kematian putranya, Durkheim sangat shock mendengar kabar tersebut dan sangat mempengaruhi kesehatannya, kepedihan hatinya tidak dapat Ia atasi, sehingga sampai tahun 1917 Ia meninggal dunia dikarenakan serangan jantung.[11] Demikian perjalanan hidupnya, beliau dikenal sebagai tokoh sosiologi Perancis yang ke-2 setelah Auguste Comte,[12] bahkan Durkheim sendiri menyatakan bahwa Comte adalah guru sosiologinya, namun perlu diklarifikasi bahwa Comte banyak dihadapkan pada implikasi sosial revolusi Perancis yang amat luas, maka Durkheim dihadapkan pada akibat-akibat yang ditimbulkan perang tahun 1870 antara negaranya dengan Prusia, yaitu pada saat Republik ke-3 Perancis membutuhkan kembali konsilidasi sosial.[13] Dalam pemikiran Durkheim dapat kita lihat atas pengaruh Comte dalam analisis fungsional dan analisis historis yang tidak lain dari pada pembagian Auguste Comte tentang statika dan dinamika sosial, hal ini dapat disinyalir bahwa pengaruh Comte dalam konsep filsafat positivisme terhadap Durkheim, demikian juga mengenai “masyarakat” dapat kita lihat sebagai berikut: “Banyak kaitan antara pandangan Auguste Comte dengan pandangan Durkheim mengenai masyarakat, baik yang mengenai segi-segi teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang dirintis Auguste Comte, juga Durkheim memandang masyarakat itu sebagai kenyataan tersendiri. Masyarakat bukanlah sekedar perjumlahan para individu, meskipun masyarakat tadi tidak dapat dilepaskan dari para individu yang merupakan unsur-unsur dari padanya. Masyarakat bukanlah sesuatu yang transendent, juga bukan sesuatu yang metafisik, melainkan “natur” dan tempat di mana kebudayaan berkembang. Melalui mata simbol-simbol, norma-norma moral, bahasa dan lain sebagainya”.[14] Pada awal karirnya, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Herbert Spencer, misalnya: Ia memakai istilah protoplasma sosial, tetapi segera Ia sampai kepada suatu pengertian hidup bermasyarakat yang lebih seimbang, di mana ia melihat masyarakat dalam kehidupan, membutuhan suatu tatanan yang baik dari suatu tatanan masyarakat (kolektifitas) dan masyarakat dimengerti sebagai “realitas sui generis” (memiliki corak tersendiri).[15] Dalam berbagai referensi belum didapatkan informasi yang lengkap mengenai tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikirannya, namun dapat kita mengerti bahwa ketertarikan seseorang atas suatu pemikiran belum tentu konsep tersebut mempengaruhi intelektual seseorang, karena perkembangan intelektual seseorang dipengaruhi oleh perkembangan analisisnya terhadap sesuatu yang ada. Dalam berbagai karya Durkheim memonopoli di Perancis, yang setelah perang dunia ke-2, pengaruhnya di Amerika Serikat juga semakin meningkat,[16] demikian halnya di Jerman, pada masa hidupnya karyakaryanya hampir tidak perna dipelajari, pengaruhnya mulai tampak setelah Anglo Saxon karya-karyanya tersedia dalam terjemahan-terjemahan dan ini terjadi menjelang akhir tahun tiga puluhan.[17] Dan bahkan sampai sekarang di negara kita (Indonesia) kata Drijarkara S.J, juga mempunyai pengaruh, meskipun dengan tidak sengaja.[18] Karya-karya Emile Durkheim. Manusia diciptakan di permukaan bumi ini, karena manusia memiliki potensi untuk berkarya dengan bekal utama yang diberikan Tuhan adalah akal untuk mengelola dan memelihara alam di sekitarnya, dengan demikian cipta, rasa dan karya serta karsa bergejolak dalam pandangan akal yang sehat, sehingga lahirlah berbagai karya. Demikian halnya dengan Durkheim, sepanjang hidupnya selama kurang lebih 59 tahun, telah menghasilkan beberapa karya yang mampu memberikan sumbangan wawasan intelektual yang cukup besar dalam ilmu sosiologi, demikian karya-karyanya sebagai berikut: Tahun 1893 membuat karya yang berjudul “De la Division du Travail Social: Edute Des Societes uperieurs” pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1933 dengan judul The Division of Labor in Society terjemahan George Simpson, New York: The Free Press.[19] First Published as De la Division du Travail Sicial.[20] (Tentang Pembagian Kerja Sosial). Tahun 1895 Ia menulis buku tentang “Peraturan Metodologi Sosiologi” [21] dengan judul “Les Regles de la Methode Socioloqique”. Pertama kali terbit dalam bahasa Inggris tahun 1938 dengan judul “The Rulles of Sociological Method” diterjemahkan oleh Sarah A. Solovay and John M. Meuller, New York: Free Press.[22]Tahun 1958 “The Rules of Socilogical Method” 8 th. Ed. Edited by Ge George E.G. Caltin. Glencoe, III; Free Press – First Published in French.[23] Tahun 1887[24] tahun 1877[25] menghasilkan karya tentang “bunuh diri” dengan judul “Le Suicide de la Methode Sociologigue”, pertama terbit dalam bahasa Inggris tahun 1951. Suicide: A Study in Sociology, terjemahan John a. Spaulding and George Simpson, Glencoe: Free Press, sedangkan dilain buku diterbitkan pada tahun 1897.[26] Tahun 1896 menerbitkan majalah I’Annee Sociologigue di mana Ia menulis berbagai resensi buku dan artikel.[27] Tahun 1898 menghasilkan karya tentang sosiologi dan filsafat dalam salah satu buku yang berjudul Sociologigue et Philosophie yang tahun 1953 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul “Sociology and Philosophy” Glencoe, III: Free Press–Written Between 1898-191. First Published in French in 1924.[28] Tahun 1899 Ia menghasilkan buku yang diterbitkan tahun 1960 “Prefaces to L’ annee Sociologigue: Prefuce to Volume 2” Pages 347-353 M Kart H. Wolff (Editor), Emile Durkheim, 1858-1917; A Collection of Essays With Translation and a Biography. Columbus, Ohio State Univ.Perss.[29] Tahun 1902 Ia menghasilkan buku I’Education Morale (pendidikan Moral),[30] yang tahun 1961 dengan buku “moral education: A Study in The Ory and Application of The Sociology of Education. New York: Free Press – Lectures First Published in Franch.[31] Tahun 1902[32] menulis buku tentang “Bentuk-bentuk Primitif Klasifikasi” bersama muridnya M. Mauss dan tahun 1903[33] yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1963 “Durkheim and Mauss, Marcel., Primitive Classification. Translaed and Edited by Rodney Needham. Univ. of Chicago Pres – First Published as “De Guelgues Formes Primitivesde Classification” in L’Annee Sociologigue. Tahun 1906 menghasilkan karya, yang tahun 1953 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul “The Determination of MoralFacts” Glencoe, III; Fre Press – First Published in Franch.[34] Tahun 1911 menghasilkan karya yang tahun 1953 diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul “Value Judgments and Judgments of Reality”. Pages 80-97 in Emile Durkheim Sociology and Philosophy. Glancoe, III; Free Press – First Published in Franch. Tahun 1912 menghasilkan karya tentang bentuk-bentuk elementer kehidupan religius dengan judul “Les Formes Elementaires de la Vio Religieuse”,[35] yang diterbitkan tahun 1954 dalam bahasa Inggris dengan judul “ The Elementary Forms of The Religions Life”, Allen and Unwin: Macmillan - First Published as Les Formes Elementaires de La Vie Religieuse, le Systeme Totenigue en Australie. A Paperbeck Edition Was Published in 1961 by Coller.[36] Demikian pula karya-karyanya yang dihasilkan selama hidupnya yang tidak jelas data yang penulis temukan sebagai berikut: Education et Sociologigue (Pendidikan dan Sosiologi) I‘Evolution Pedagogigue en France (Evolusi Pedagogi di Prancis) La Socialisme et Saint – Simon (Sosialisme dan Saint – Simon) Lecons de Sociologie (Pelajaran Sosiologi) Monstesguieu et Roysseau Pragmatisme et Sociologie (Pragmatisme dan Sosiologi) Quia a Voulu la Guerre (Siapa menghendaki Perang) I’Allemague au Dessus de Tout (Jerman diatas Segalahnya)[37] Demikian berbagai karya-karya Durkheim yang dihasilkannya sepanjang masa hidupnya namun berbagai karyanya tidak dapat dihasilkan (diterbitkan) semasa Ia hidup, namun demikian karya-karyanya setelah beliau meninggal tidak menghalangi pengikut-pengikutnya untuk mengangkat di permukaan perdebatan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi untuk dijadikan bahan penambah wawasan para intelektual semasanya maupun sesudahnya. B. Metode Pemikiran Sosiologinya. Berbagai akibat-akibat yang ditimbulkan oleh revousi Perancis, benar-benar membawa situasi keterpurukan tatanan sosial di Perancis dan perdebetan-perdebatan dalam persoalan sosial semakin semarak, utamanya perdebatan persoalan kekacauan dan ketidakberesan masyarakat disebabkan oleh konsep individualisme, membawa Durkheim melihat kenyataan yang terjadi, sehingga Ia cenderung pada suatu filsafat sosial, di mana keseluruhan berkuasa atas bagian-bagiannya dan masyarakat atas anggota-anggota individual. Pendirian Durkheim nampak nyata dan jelas sekali dalam salah satu kutipan buku karangannya: “Kalau kita menerima kenyataan bahwa keyakinan-keyakinan dan praktek-praktek sosial disampaikan kepada kita dari luar…kita tidak boleh menarik kesimpulan bahwa kita menerima mereka dengan pasif saja dan tanpa modifikasi. Waktu kita diperkenalkan dengan pranata-pranata kolektif dan membuktikan mereka, kita mengindividualisir mereka dengan mengisi mereka dengan ciri-ciri yang kurang bersifat pribadi…Dari itu dapat dikatakan bahwa kita masing-masing menghasilkan moralitas, agama dan cara hidup kita sendiri. Tidak ada orang yang menyesuaikan diri seluruhnya kepada suatu tata sosial dengan tidak memasukkan sejumlah pariasi-pariasi individu.[38] Dengan membicarakan metodologi, maka terlebih dahulu yang harus kita lakukan adalah mengetahui objek sosiologi Durkheim yang sangat paling penting, agar kita tidak keliru dalam melihat apa yang disampaikan dalam pembahasan ini. Durkheim dalam upayahnya berusaha agar sosiologi di tempatkan pada ilmu pengetahuan yang mandiri, tidak tergantung pada ilmu biologi dan psikologi maupun filsafat. Dalam usaha tersebut, objek sosiologi yang di-maksudkan adalah “fakta sosial” ialah cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa apa yang ada di luar individu dan yang memiliki daya paksa atas dirinya,[39] (perilaku sosial), hal ini dimaksudkan agar sosiologi memiliki kapasitas sebagai ilmu yang mandiri, karena pada awalnya fakta sosial kadang diartikan dalam arti umum, sehingga sosiologi tampak tercampur adukkan dengan psikologi, biologi dan ilmu-ilmu lainnya. Durkheim menyarankan agar cara berpikir, hendaknya tidak rancu dengan gejala-gejala psikologi yang hanya ada dalam kesadaran pribadi tetapi sosiologi ada pada kesadaran sosial. Fakta sosial adalah penggambaran dan perbuatan-perbuatan, tapi fakta-fakta ini bukan fakta fsikis, karena fakta psikis hanya ada dalam individu sedangkan fakta sosial berada pada di luar individu secara terpisah, sekalipun hal itu tidak dapat dilepaskan dari individu secara bersama-sama, tetapi Durkheim merumuskannya sebagai otonom yaitu sebagai realitas yang merupakan jenis tersendiri.[40] Untuk lebih jelasnya Durkheim memberikan gambaran agar kita mudah memisahkan diantaranya sebagai berikut: “Fakta fsikis mempunyai subtratum material, ialah sel-sel otak dan proses-proses psikologis, tetapi fakta-fakta itu tidak identik dengan subtratum itu. Fakta-fakta fsikis itu tidak sama sekali otonom, sebab tanpa proses-proses di dalam subtansi otak, maka berpikir tidak mungkin sama sekali. Hal yang sama sebagai perbandingan, berlaku pada fakta sosial. Fakta sosial mempunyai subtratum, yaitu individuindividu dalam hubungannya satu sama lain. Tanpa kembali kepada subtratum itu, pikiran yang ada di belakang semua ini ialah bahwa keseluruhan adalah lebih dari pada jumlah bagian-bagiannya.[41] Kemudian persoalan metodologi, dari berbagai tokoh yang hidup dalam suatu lingkungan intelektualnya, mereka menggunakan metode dalam sistimatika pemikirannya, hal yang sama dengan Durkheim, dalam menganalisa suatu realitas dalam hubungannya dengan sosiologi (fakta sosial) memiliki metode sosiologi yang khusus, dalam hal ini dirumuskannya agar sosiologi dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan tersendiri seperti ilmu alam lainnya. Sepanjang waktu, perhatian utama yang Ia curahkan adalah bagaimana membuat suatu rumusan metode dalam sosiologi, dan sampai pada kesimpulannya Ia telah menetapkan rumusan yang akhirnya menjadi acuan bagi murid-muridnya, rumusan tersebut adalah sebagai berikut: Sosiologi harus bersifat ilmiah. Dalam metode ini, Durkheim sepenuhnya memisahkan sosiologi dari ketergantungan filsafat, dengan alasan bahwa sosiologi lahir dalam lingkungan ajaran filsafat, maka terdapat kecenderungan untuk mengandalkan beberapa sistem filsafat, sehingga larut dalam sistem tersebut. Olehnya itu, sosiologi harus bersifat ilmiah dalam arti bersifat positivisme, evolusioner, dan idealistis,[42] sehingga cukup memenuhi syarat sebagai suatu metode sosiologi. Sebagaimana yang penulis telah uraikan sedikit pada bab I, dalam pendekatan metodelogi positivisme, Durkheim mirip dengan Auguste Comte dalam hal ini, Comte dalam positivisme yang dirintisnya dapat kita ketahui dengan berdasar pada filsafat positif, di mana ia berangkat dari apa yang kita telah ketahui, faktual yang positif. Hal ini nyata bahwa apa yang ada di luar apa yang ada, sebagai fakta atau kenyataan harus dikesampingkan, olehnya persoalan metafisik ditolaknya. Demikian positivisme diuraikan untuk mendapatkan pengertian yang jelas, maka akan nampak kepada kita hal di bawah ini, suatu uraian tentang positivisme, sebagai berikut: “Apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tanpak, segala gejala. Demikianlah positivisme membatasi filsafat dan ilmu pengetahuan pada bidang gejala-gejala saja. Apa yang dapat kita lakukan adalah segala fakta, yang menyajikan diri kepada kita sebagai pemampakan atau gejala, kita terima seperti apa adanya. Sesudah itu kita berusaha mengatur fakta-fakta tadi, kita mencoba melihat kemasa depan, apa yang akan tanpak sebagai gejala dan menyesuaikan diri dengannya. Artinya segala ilmu pengetahuan ialah mengetahui untuk dapat melihat kemasa depan.[43] Jadi dapat dipahami bahwa kita hanya mengkonstatir fakta-faktanya dan menyelidiki hubunganhubungannya yang satu dengan yang lainnya, hal ini bertitik tolak pada pengalaman yang objektif, tidak seperti empirisme yang juga menerima pengalaman-pengalaman batiniah (subjektif). Demikian halnya dengan Comte memberikan kejelasan mengenai cara kerja positivisme, yang dijelaskan dalam batasan-batasan pengertian positif dalam karyanya “Discours Sur Lesprit Positif” sebagai berikut: Sebagai lawan atau kebalikan yang bersifat khayalan, sehingga postivisme dalam menyelidiki sasarannya, didasarkan pada kemampuan akal. Sebagai lawan dari sesuatu yang tidak bermafaat, sehingga segala sesuatu harus diarahkan kepada pencapaian kemajuan dan bermafaat bagi kepentingan orang banyak. Sebagai lawan sesuatu yang meragukan, artinya positif adalah pensifatan sesuatu yang sudah pasti, sehingga harus sampai pada keseimbangan yang logis dan membawa kebaikan bagi setiap individu dan masyarakat. Sebagai lawan dari sesuatu yang kabur, jadi positif adalah sesuatu yang jelas dan tepat, sehingga positif harus memberikan pengertian yang jelas mengenai gejala yang nampak dan mengenai apa yang sebenarnya. Sebagai lawan dari yang negatif, jadi positif adalah sesuatu yang pasti (positif), dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat pandangan filsafat yang selalu mengarah pada penataan atau penertiban.[44] Dari pengertian di atas, Auguste Comte ingin memperlihatkan ciri khas positivisme dan metode dalam kerangka kerjanya yang berbeda dengan filsafat lama yang bercorak teologis dan metafisis, demikian halnya dengan Durkheim yang memiliki unsur pikiran yang banyak mempengaruhi sistimatika kerangka rasionalnya dalam menjelaskan fakta yang dijumpainya atau dipecahkannya. Telah tergambar persoalan Durkheim dalam berilmiah mengenai metode sosiologinya, hal ke-2 dalam berilmiah Ia juga memakai pemikiran evolusioner, karena Ia sangat menolak teori revolusi yang dianggapnya tidak membawa mamfaat yang justru memperburuk keadaan kehidupan masyarakat, dapat dipahami bahwa evolusioner akan kembali pada pembahasan di atas, di mana manusia dalam kehidupannya berjalan secara alami, karena proses alamiah yang berlaku, sesuatu yang tidak dapat kita hindari, maka manusia akan belajar dari historis yang mereka lihat, dengarkan atau yang mereka alami, maka pengalaman sangatlah berpengaruh, olehnya dapat dijelaskan dalam positivisme yang telah kita singgung di atas dan sangat jelas tampak kepada kita hal ini seperti halnya moral terlibat dalam proses historis yang bersifat evolusi, artinya berubah sesuai dengan struktur sosial.[45] Lebih lanjut akan evolusi, kita teringat Charles Darwin yang dikenal dengan teori evolusinya dalam kanca intelektualitas, menurutnya, evolusi adalah proses peningkatan yang mengarak tercapainya keadaan yang lebih sempurna, Hobhouse menjelaskan bahwa dalam indikator objektif pada suatu masyarakat yaitu antara lain: 1) Besarnya masyarakat, 2) Efesiensi masyarakat, 3) Besarnya kebebasan yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan lain-lain. Lebih lanjut Hobhouse mengatakan, proses evolusi masyarakat berjalan sejajar dan seiring dengan proses prasionalisasi kehidupan yang makin besar. Darwin menguaraikannya sebagai berikut: Pada permulaan bumi, segala makhluk organis tidak dengan serentak dijadikan menurut jenis mereka masing-masing. Mereka adalah hasil proses adaptasi, perubahan, dan evolusi. Evolusi tidak terjadi dengan mengarah pada suatu tujuan (causa finalis) yang telah dirancang sejak semula. Melainkan adaptasi pada lingkungannya. Kondisi lingkungan faktor-faktor kebetulan material telah menentukan arah evolusi dan hasil yang dicapainya. Proses evolusi berlangsung dalam empat sistem yaitu: Struggle for life yaitu persaingan yang ketat untuk saling mengalahkan demi untuk hidup. Survival Sof the fittest yaitu organisme-organisme yang lemah akan mati sebelum mampu mempergandakan diri. Natural selection yaitu pilihan alam atau alam mengadakan seleksi. Progress yaitu peningkatan mutu semua organisme.[46] Spencer mengamalkan teori Darwin (evolusi), masyarakat disamakan dengan suatu organisme yang menurutnya: “Masyarakat adalah organisme! Semua gejala sosial diterangkan berdasarkan suatu penentuan oleh hukum alam. Hukum yang memerintah atas proses evolusi sosial. Manusia tidak bebas dalam hal ini, ia memainkan suatu peranan bebas dalam mengembangkan masyarakat.[47] Dari beberapa komparatif pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran evolusionistik (proses alam), yang terjadi dalam kehidupan tidaklah berbeda dengan apa yang ada pada Durkheim, yang menganggap salah satu bentuk evolusi adalah proses masyarakat dari suatu sistem mekanik kepada masyarakat organik. Namun perlu dicatat, pemikiran Durkheim dalam hal ini, memang banyak melihat dari tokoh-tokoh tersebut, walaupun penulis tidak mengatakan bahwa pemikiran Durkheim dipengaruhi olehnya secara seratus persen, karena pemikiran seseorang juga mengalami proses evolusi yang sangat erat kaitannya dengan lingkungan yang memberikan sumbangan terhadap diri sendiri. Metode sosiologi harus bersifat objektif. Dalam menganalisa beberapa fakta realitas, seorang sosiolog perlu kiranya tidak terpengaruh oleh berbagai pemikiran yang cendrung pada suatu kepentingan kelompok atau masyarakat tertentu, hendaknya ia dapat melihat secara murni, demikian Durkeim melihat bahwa ia memasuki alam gejala sosial, suatu wilayah yang belum dikenal, sehingga Ia harus bersifat polos, tidak berperasangka atau beranggapan dan tidak terpengaruh oleh berbagai pemikiran yang menyimpang, ia harus mempunyai “one certaine attitude mentar” yang hanya menyambung pada pengalamannya.[48] Sehingga dalam melihat gejala sosial, dicirikhaskan oleh dua hal, yaitu exteriority (sifat luaran) dan constraint (paksaan), hal ini membawa pendirian dalam menganalisa suatu fakta (objek) sama dengan mengamati objek-objek yang lain dari alam benda-benda. Hal yang dimaksudkan adalah sifat luaran dan sifat memaksa dari realitas sosial, sebagai hal yang menarik perhatian, sehingga kedua sifat tersebut dapat dipakai sebagai definisi sementara dan titik tolak metodologis untuk penelitian selanjutnya. Lebih lanjut Durkjheim dalam hal ini mengatakan: “Para sosiolog, harus mengesampingkan segala prakonsepsi mengenai fakta, sehingga dapat menghadapi fakta itu secara langsung. Juga telah ditunjukkan bagaimana para sosiolog harus dapat membedakan unsur-unsur fakta menurut klasifikasi fakta yang normal dan patologis. Para sosiolog harus memiliki prinsip yang sama dalam menjelaskan fakata yang ditelitinya dan bagaimana menguji penjelasan-penjelasan itu. mereka hendaknya tidak lagi terpengaruh oleh pemikiran yang bersifat ulitarium atau melakukan penalaran silogistis dan meyadari adanya kesenjangan antara sebab dan akibat. suatu hal merupakan suatu kekuatan yang hanya dapat di kembangkan oleh kekuatan yang lain. Dengan demikian dalam mengadakan penelitian terhadap fakta sosial, yang harus diungkapkan adalah energi yang memproduksi fakta sosial itu.oleh karena itu penjelasan yang diberikan harus bersifat khas, hal mana juga belaku bagaimana caranya mengadakan verifikasi. Kalau gejala sosiologi hanya merupakan suatu sisitim gagasan yang diobjektifkan, maka dalam mejelaskannya diperlukan pemikiran kembali mengenai tertib logisnya, dan penjelasan itu sendiri merupakan bukti, walaupun dalam hal tertentu diperlukan contoh-contoh untuk memperkuatnya.[49] Comte sependapat dalam hal ini, sebagaimana telah disinggung terdahulu dalam corak positivisme, objektifitas dalam melihat fakta yang ada, hanya kita klarifikasi apa yang tampak secara nyata dan pasti, itulah yang dapat kita ambil dan hal yang subjektif hendaklah kita kesampingkan. Jadi fakta sosial harus dilihat dari sebelah luar, dan diterangkan secara kausal. Lebih lanjut Durkheim menjelaskan, fakta sosial dirumuskannya sebagaimana yang diuraikan oleh L. Laeyendecker sebagai berikut: “Fakta sosial harus diperlakukan sebagai benda, Durkheim tidak bermaksud mengatakan bahwa faktafakta sosial itu benda, walaupun rumusan seperti itu perna ditulisnya, menurut Durkheim, fakta sosial harus dipandang dalam kwalitasnya seperti yang diberikan dalam pengamatan dan bukannya sebagai sesuatu yang dapat dikejar dengan intropeksi, selain itu fakta sosial tidak dapat diubah dengan kemauan semata-mata. Fakta sosial ini memberikan perlawanan seperti yang dilakukan oleh benda-benda, hal mana berbeda dengan gambaran-gambaran dalam batin yang dapat diubah-ubah sekehendak hati. Jadi misalnya, fakta-fakata sosial dapat dihitung dan dinyatakan dalam statistik.[50] Hal di atas dimaksudkan oleh Durkheim adalah perlakuan yang demikian, agar orang dapat mengambil jarak emosional, berbeda kita memahami manusia (masayarakat), lebih baik kita mendekatinya dengan simpati untuk mengetahui apa yang menyibukkannya. Tetapi fakta sosial harus dengan cara memberikan pengertian-pengertian yang tepat yang tidak selalu tersedia secara langsung, perlu pemikiran klasifikasi berulang-ulang kita melihatnya dari luar dan kita dapat lepas dari manifestasimanifestasi individualnya. 3. Metode sosiologi harus ekslusif bersifat sosiologis. Sosiologi dalam memperlihatkan kematangan dan kemandiriannya, maka sebagai suatu ilmu pengetahuan, hendaknya Ia terpisah dan tidak tercampur adukkan dengan ilmu pengetahun lain, seperti yang telah diterangkan terdahulu. Sosiologi hendaknya tidak bercampur dengan psikologi, filsafat atau dengan yang lainnya, agar memperlihatkan kematangannya yang menjadi ciri khasnya serta dipandang matang untuk disebut sebagai salah satu disiplin ilmu. Demikianlah yang telah dirintis oleh Comte dan lebih diperjelas (diperluas) oleh Durkheim dalam membentuk sosiologi menjadi suatu ilmu pengetahuan yang mempunyai metode tersendiri dalam mengungkapkan kasus-kasus sosial, maka dari itu ia membuat suatu batasan metode yang telah tersebut di atas, lebih lanjut Durkheim menjelaskan bahwa: “Fakta sosial hanya dapat dijelaskan oleh fakta sosial lainnya, hal mana dimungkinkan dengan cara menonjolkan fakta pokok dalam evolusi kolektif, pada lingkungan sosial internal. Dengan demikian, maka sosiologi merupakan suatu ilmu yang mandiri. Perasaan adanya kekhususan relaitas sosial, sedemikian pentingnya bagi orang sosiolog, sehingga hanya latihan-latihan keterampilan sosiologis yang akan dapat mempersiapkannya untuk dapat menelaah fakta sosial secara intelektual”.[51] Sebenarnya dapat kita cermati bahwa pada gagasan pertama dan yang kedua merupakan penampakan ciri khas sosiologi yang dirintis oleh Durkheim, maka terlihatlah apa yang dimaksud metode sosiologi yang diperjuangkan oleh Durkheim pada masa itu, dan ini sangatlah penting karena sisitimatika pemikiran Durkheim berakar pada konseptual yang dibuatnya. Itulah metode sosiologi Durkheim, yang mungkin akan nampak lebih rumit sedikit dari metode yang telah ada terdahulu dan sudah berakar dikalangan sosiolog, namun hal ini rumit karena belum berakar pada intelektual seseorang. Tidaklah menutup kemungkinan terjadi suatu perbedaan dan kritikan pada konsep Durkheim, seperti yang terjadi setelah Durkheim memperkenalkan gagasannya di dalam percaturan ilmu pengetahuan dan intelektualitas pada masanya, tetapi perlu dipikirkan bahwa suatu ilmu tidak akan mapan tanpa kritikan dari yang lainnya, dan itulah usaha Durkheim yang memang patut kita syukuri, dimana banyak memberikan tambahan wawasan intelektual pada para penganut sosiolog. BAB III CORAK MORALITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM A. Pengertian Moralitas. 1.Pengertian menurut bahasa. Moralitas berasal dari kata dasar “moral” berasal dari kata “mos” yang berarti kebiasaan, kata jumlahnya “mores” yang berarti kesusilaan, dari “mos”, “mores” adalah kesusilaan, kebiasaan.[52] Sedangkan “moral” adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain; akhlak budi pekerti; dan susila.[53] Kondisi mental yang membuat orang tetap berani; bersemangat; bergairah; berdisiplin dan sebagainya. Moral secara etimologi diartikan: a) Keseluruhan kaidah-kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu, b) Ajaran kesusilaan, dengan kata lain ajaran tentang azas dan kaidah kesusilaan yang dipelajari secara sistimatika dalam etika.[54] Dalam bahasa Yunani disebut “etos” menjadi istilah yang berarti norma, aturan-aturan yang menyangkut persoalan baik dan buruk dalam hubungannya dengan tindakan manusia itu sendiri, unsur kepribadian dan motif, maksud dan watak manusia.[55] kemudian “etika” yang berarti kesusilaan yang memantulkan bagaimana sebenarnya tindakan hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan yang buruk.[56] Moralitas yang secara leksikal dapat dipahami sebagai suatu tata aturan yang mengatur pengertian baik atau buruk perbuatan kemanusiaan, yang mana manusia dapat membedakan baik dan buruknya yang boleh dilakukan dan larangan sekalipun dapat mewujudkannya, atau suatu azas dan kaidah kesusilaan dalam hidup bermasyarakat. 2. Pengertian menurut istilah. Secara terminologi moralitas diartikan oleh berbagai tokoh dan aliran-aliran yang memiliki sudut pandang yang berbeda, namun kenyataannya dapat kita lihat di bawah ini, sebagai berikut: Franz Magnis Suseno menguraikan moralitas adalah keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat.[57] W. Poespoprodjo,[58] moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Lebih lanjut Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa moralitas adalah sikap hati yang terungkap dalam perbuatan lahiriah (mengingat bahwa tindakan merupakan ungkapan sepenuhnya dari hati), moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena Ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan ia mencari keuntungan. Moralitas sebagai sikap dan perbuatan baik yang betulbetul tanpa pamrih.[59] Immanul Kant, sebagaimana yang ditulis oleh Franz Magnis Suseno, mengatakan bahwa moralitas itu menyangkut hal baik dan buruk, yang dalam bahasa Kant, apa yang baik pada diri sendiri, yang baik pada tiap pembatasan sama sekali. Kebaikan moral adalah yang baik dari segala segi, tanpa pembatasan, jadi yang baik bukan hanya dari beberapa segi, melainkan baik begitu saja atau baik secara mutlak.[60] Emile Durkheim mengatakan moralitas adalah suatu sistem kaidah atau norma mengenai kaidah yang menentukan tingka laku kita. Kaidah-kaidah tersebut menyatakan bagaimana kita harus bertindak pada situasi tertentu. Dan bertindak secara tepat tidak lain adalah taat secara tepat terhadap kaidah yang telah ditetapkan.[61] Dari pengertian tersebut di atas, dapat kita uraikan bahwa moralitas adalah suatu ketentuan-ketentuan kesusilaan yang mengikat perilaku sosial manusia untuk terwujudnya dinamisasi kehidupan di dunia, kaidah (norma-norma) itu ditetapkan berdasarkan konsensus kolektif, yang pada dasarnya moral diterangkan berdasarkan akal sehat yang objektif. Durkheim menyangga dari pengertian moralitas yang bersifat individualitik, dan hal-hal yang darinya secara subjektif. Olehnya, Ia menyangga bahwa moralitas yang demikian berlawanan sama sekali dengan keadaan sebenarnya, maka apabila kita meninjau moralitas dengan apapun adanya, kita akan melihat moralitas mencakup kaidah-kaidah khusus, tertentu dan pasti tidak terbilang jumlahnya, kaidahkaidah tersebut, mengatur tingka laku manuisa dalam berbagai situasi yang paling sering dihadapinya. Jadi secara terminologis, dalam moralitas kita tidak mengatur perilaku kita berdasarkan pandangan teoritis dan kaidah-kaidah umum, melainkan berdasarkan pada kaidah khusus yang diterapkan secara khusus pada situasi tertentu yang mencakup di dalamnya, sekalipun pada posisi penting, kita tidak berpaling dari kaidah-kaidah umum moralitas untuk menemukan bagaimana menerapkannya dalam kasus-kasus tertentu, maka akan mengetahui apa yang kita lakukan. B.Unsur-unsur Moralitas. Dalam pembahasan moralitas, perlu diketahui bahwa penulis tidak memberikan atau mempermasalahkan bahasa antara moral dan etika, namun yang sangat perlu diklarifikasi bahwa moralitas bukan keseluruhan etika, tetapi merupakan persoalan pokok dalam etika.[62] Sekalipun banyak yang mempersoalkannya, seperti salah satu dari berbagai di antaranya adalah ulasan O. Kattsoff, bahwa etika yaitu analisa mengenai makna apakah yang dikandung oleh predikat-predikat kesusilaan.[63] Dan masih banyak yang lainnya. Tetapi Durkheim tidak banyak mempersoalkan permasalahan ini. Durkheim dalam pemikiran moralitas yang ditawarkannya, dengan konsepsi pemecahan kondisi zaman yang melanda negerinya, dalam hal ini penulis memberikan kejelasan tentang klarifikasi persoalan moralitas yang akan diuraikan, yakni persoalan mengenai “norma-norma” moral dalam kategori undangundang atau hukum aturan yang. Tetapi secara teoritis yang ditampilkan sebagai tawaran moral untuk mengubah tradisi masyarakat, untuk membawa masyarakat pada kondisi yang lebih menyenangkan dengan pandangan kolektifitas kesadaran sosial. Di sini Durkheim menjelaskan raison d’etre (alasan untuk berada), bagi teori-teori tersebut terletak pada tindakan seseorang, oleh sifat dualisme inilah yang sedang ia coba mengungkapkannya sebagai teoritis praktis. Mamfaatnya yang dapat diharapkan adalah ditentukan oleh sifat ambivalent.[64] Baginya tindakan itu bukanlah yang karenanya sendiri dapat menggantikan tindakan, tetapi dapat memberikan wawasan kedalam tindakan. Durkheim banyak melihat kebanyakan moralis beranggapan bahwa moralitas seakan-akan terdapat dalam hati nurani masing-masing orang, dan yang memahaminya cukup kita sendiri, sehingga persoalan yang demikian diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti Kantianisme berbeda dengan Utilitarisme dan memiliki kaidah-kaidah tersendiri, konsep tersebut mengungkapkan perbedaan klasik antara moralitas teoritis dengan moralitas terapan.[65] Demikian lagi perlu diperjelas sebelum kita menguraikan unsur-unsur moralitas dalam kenyataan dan prakteknya, kita tidak mengatur prilaku kita berdasarkan pandangan-pandangan teoritis atau kaidahkaidah umum, melainkan kita harus berdasar pada kaidah-kaidah khusus dan menganggap moralitas sebagai suatu totalitas dari kaidah-kaidah yang pasti dan jelas, ia dapat di umpamakan berbagai macam cara atau cetakan dengan batas-batas yang jelas, demikian yang diungkapkan oleh Durkheim dapat tergambar dalam tulisannya : “Kita melihat adanya gejala yang tidak hanya nyata, tetapi juga tregantung pada situasi yang dihadapi. Dengan demikian yang kita saksikan bukan semata-mata aspek dan prinsip umum yang satu dan yang mencakup semua makna dan realitas. Justru sebaliknya, terlepas dari apa pun hakikatnya dan pemahaman orang ter-hadapnya. Kaidah umum tidaklah membentuk realitas itu sendiri, melainkan hanya merupakan abstraksi yang berlaku. Tidak ada kaidah dan aturan sosial yang diakui atau memperoleh sanksi dari imperatif moral Kant atau hukum kegunaan seperti dikemukakan oleh Bentham Mill atau Spencer. Semua itu hanya merupakan generalisasi buatan para filsuf belaka, sekedar hipotesis buatan teoritis. Apa yang dianggap oleh kebanyak orang sebagai hukum umum moralitas…..Hukum moraitas hanya sekedar ringkasan, yang kurang lebih memuaskan, dari ciri-ciri yang biasa terdapat pada semua kaidah moral, jadi bukan kaidah yang nyata, pasti dan efektif. Bagi realitas morali ini, hipotesis para filsuf yang dimaksudkan untuk menunjukkan kesatuan dari sifat dasar, yang merupakan besar itu sendiri. Dan ini termasuk kedalam susunan ilmu pengetahuan, bukan tatanan kehidupan”.[66] Olehnya itu, kita harus memahami moralitas seperti apa adanya tanpa adanya pengaruh dari berbagai simbol dalam mencari wujud rasionalitas moral dan mengetahui kekuatan-kekuatan moral, menyelidiki bagaimana kekuatan tersebut bisa di kembangkan, tetapi hal yang pertama merupakan suatu yang terpenting dengan jalan, kita harus menemukan unsur-unsur dasar moralitas sebelum memperhitungkan perubahan-perubahan yang mungkn terjadi. Mempertanyakan unsur-unsur moralitas bukanlah berarti mencari susunan daftar lengkap mengenai semua keutamaannya, atau beberapa bagian yang terpenting, tetapi kita mencari disposisi dasar, keadaan (seseorang) secara mental.[67] Ide konsepsionalnya berhasil disimpulkan dalam berbagai ceramahnya, persoalan moralitas harus dipecahkan dengan melihat tiga hal sebagai unsur-unsur moralitas, sebagai berikut: Unsur pertama moralitas : Semangat Disiplin. Dalam tindakan manusia, hendaknya melihat sifat dasar moralitas yang sungguh-sungguh, bukan dalam kesempatan-kesempatan tertentu, melainkan secara umum dalam hubungannya antara sesama manusia. jika kita perhatikan sekilas dalam segi-seginya yang formal dan eksternal, tampak tidak begitu penting, tetapi moralitas bukan hanya yang kita peraktekkan setiap hari, melainkan juga yang kita saksikan dalam sejarah, terdiri dari seperangkat kaidah-kaidah tertentu dan khusus yang menetapkan secara tegas bagi prilaku manusia. Dari realitas di atas Durkheim menjelaskan bahwa ada dua konsekuensi logis, yaitu: “Pertama, karena moralitas menetapkan dan mengatur prilaku, maka moralitas mengandaikan sikap batin tertentu dalam diri seseorang untuk hidup secara teratur, atau sikap yang lebih menyukai keteraturan. Kewajiban selalu bersifat teratur. Oleh karena itu, orang yang lebih menyukai perubahan dan perbedaan mendesak dilakukannya perubahan terhadap segala bentuk keseragaman adalah orang yang secara moral tidak lengkap. Keteraturan adalah analogi moral dari keteraturan gerak dan organisme. Kedua, karena kaidah moral bukan hanya sekedar nama lain untuk kebiasaan pribadi, karena kaidah moral menentukan tingka laku secara imperatif dari sumber-sumber luar diri kita agar bisa memenuhi kewajiban dan agar bisa bertindak secara moral, kita harus menghormati otoritas “sui generis” yang memberikan informasi tentang moralitas.[68] Pada langka awal, kita harus mengetahui juga moralitas secara jelas yakni pertama-tama adalah menentukan tingka laku, menetapkannya, membatasi unsur yang bersifat semau-maunya, yang dimasud tentu kaidah moral yakni hakikat dari tingka laku yang diharuskan dan juga yang memiliki nilai moral, di sini kita akan melihat bahwa moralitas pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat tetap, dan sejauh kita tidak membicarakan tentang jangka waktu yang panjang, moralitas tetap akan sama, tidak berubah. Dengan demikian moralitas mengandaikan kemampuan tertentu untuk bertindak secara sama dalam keadaan yang sama, dan dengan sendirinya juga mencakup kemampuan untuk mengembangkan kebiasaan dan kebutuhan akan adanya keteraturan.[69] Dan untuk menjamin keteraturan hanya diperlukan kebiasaan[70] yang tertanam kokoh. Benar, jika kita mengatakan kita sendiri yang menentukan garis kehidupan kita sendiri, di mana tindakan kita susun sendiri yang selalu dapat kita rubah, hal ini, bagi Durkheim bukanlah kaidah, melainkan rancangan; maka kita harus membenarkan tindakan kita pada otoritas ilmiah, karena prilaku kita menyandarkan diri pada ilmu pengetahuan bukan pada dasar diri kita. Dari sini tergambar bahwa otoritas menjadi pendamping keteraturan, karena otoritas adalah pengaruh yang memaksa kepada kita semua, kekuatan moral yang kita akui sebagai sesuatu yang mengatasi kita. Untuk melakukan hal yang demikian, perlu dipahami bahwa semakin banyak campur tangan unsur-unsur lain, maka semakin sedikit sifat moralitasnya.[71] Lebih lanjut dijelaskan bahwa keteraturan dan otoritas tidak lain merupakan dua aspek dari satu kenyataan kompleks dari disiplin, kerana Durkheim menjelaskan: “Disiplin moral adalah suatu yang baik yang ada dalam diri sendiri, sebab kita harus mentaati semua perintahnya, bukan karena tindakan-tindakan itu wajib dilaksanakan atau karena penting, melainkan semata-mata karena diperintahkan”.[72] Persoalan disiplin sangat erat kaitannya masalah pembatasan dan paksaan, maka hal ini, memang banyak diperbincangkan oleh para intelektual mengenai kebebasan, di mana manusia harus hidup bebas dalam perbuatannya dan pemikirannya untuk merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia. Seperti halnya dengan konsep kebebasan Hobbes dan Locke, yang banyak dijadikan konsep baku tradisi liberal Barat di mana Ia beranggapan bahwa kebebasan ialah bebas dari campur tangan, paksaan dan hambatan dari kungkungan atau dengan kata lain bebas dari penahanan oleh pihak yang berwajib ketika kita menyatakan pendapat kita. Lain lagi dengan konsep Hegel dan idealisme kebebasan yang di bimbing oleh rasio, bukan hawa nafsu, yakni bebas melakukan apa yang perlu kita lakukan, dan kedua konsep menjadi kajian dan diperkenalkan oleh Berlin menjadi komperatif pemikiran. Gerald Mac Callum menambahkan bahwa kebebasan ialah tiada hambatan dari luar.[73] Pendapat tersebut di atas, tidak lepas dari kajian Dukheim, sehingga ia menyangga konsep yang demikian itu, dengan alasan bahwa orang sering mempermasalahkan paksaan sebagai salah satu ketidakadilan, dan kebebasanlah yang dapat memberikan keadilan, keadilan sebagai cirinya adalah ia tidak berpangkal pada hakikat sesuatu hal yang tidak berakses dari akal budi. Perspektif kebebasan menjadi pemujaan intelektual pada abad ke-19 seperti halnya dengan Bertham menganggap hukum sebagai suatu kejahatan, Saint Simon menambahkan bahwa diharapkan adanya suatu masyarakat yang tidak ada suatu peraturan sama sekali. Bagi Durkheim, hal inilah yang menyebabkan terjadinya banyak macam komplik egoistis individualis merajalela dan tidak ada aturan sosial yang menjamin, sehingga orang selalu menyombongkan dirinya melebihi kemampuan. Olehnya itu, sangat diperlukan disiplin, karena manusia hidup cenderung kepada hubungannya dengan orang lain dan menelaah fungsi disiplin memiliki kegunaan sosial dalam dan pada dirinya sendiri, terlepas dari perbuatan yang diperintahkannya.[74] Durkheim menjelaskan bahwa manusia jika ingin hidup, harus manghadapi tuntutan hidup yang sarak dengan kekonflikan dengan cadangan tenaga yang terbatas. Jadi hidup adalah suatu keseimbangan yang kompleks, di mana berbagai unsur saling membatasi satu sama lain. Olehnya, keseimbangan tidak boleh diganggu begitu saja, karena dapat mengakibatkan kekecewaan dan penderitaan bagi orang yang melakukannya berdasarkan alasan yang sama. Lebih lanjut Durkheim memaparkan: “Agar suatu tindakan dapat membawa kesenangan bagi diri kita, kita harus bisa merasakan bahwa tindakan tersebut mempunyai tujuan, dan membawa kita semakin dekat dengan sasaran yang dituju… agar dapat memahami realisasi sepenuhnya, manusia sama sekali tidak perlu melihat cakrawala tanpa batas di depannya, karena dalam kenyataan ia tidak akan mendapat sesuatu yang mengecewakan dari sasaran yang tidak mengenal batas dari keinginan seperti itu. manusia bisa bahagia bila terlibat dalam tugas-tugas yang pasti dan jelas, bukannya untuk merasakan bahwa ia sedang menghadapi tatangan karir tanpa suatu batasan yang jelas”.[75] Otoritas sangatlah penting dalam hal ini, karena kekuatan yang ada di dalamnya menjadi kekuatan yang asli mencegah keinginan dan hasrat kita, kekuatan tersebut jelas sebagai suatu material, meskipun tidak mempengaruhi tubuh secara langsung tetapi dapat menggerakkan jiwa. Moralitas adalah sebagai suatu disiplin (memerintah), kepada kita tidak sesuai dengan kecenderungan kodrat kita masing-masing. Dari pembatasan tersebut, sebagai tujuan dari pencegahan kekuatan nafsu yang hanya mementingkan pribadi dan kekuatan terkendali dengan baik. Disiplin pada dirinya merupakan faktor “sui generis”, di mana terdapat unsur hakiki tertentu dari prilaku moral sebagai ciri disiplin, karena hanya disiplin yang dapat mengendalikan keinginan. Menetapkan sasaran aktifitas kehidupan, pembatasan itu jelas berbeda-beda, sesuai dengan waktu dan tempatnya serta berbeda pula pada setiap tahap dalam kehidupan dan hal ini (kemampuan) untuk mengendalikan diri sendiri sangatlah dituntut, olehnya peranan pendidikan sangat pula diharapkan, sekalipun menurut Durkheim sangat sulit, tetapi tidak ada jalan lain,[76] kita harus berusaha. Maka jelaslah bahwa disiplin moral tidak hanya menunjang hidup moral, melainkan pengaruhnya berlangsung terus, yang secara realistis kita kihat bahwa unsur paling hakiki dari watak adalah mengendalikan diri yang memungkinkan kita mengendalikan nafsu, keinginan dan kebiasaan kita serta mengaturnya menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Unsur kedua moralitas: Ikatan pada Kelompok Sosial. Dari unsur pertama yang telah kita sebut di atas, telah menunjukkan arti yang paling formal dari kehidupan moral, sebagai suatu absrtaksi yang bisa diuji kebenarannya. Dalam kenyataan, moralitas kandungan yang memiliki makna moral, semua tingka laku termasuk dalam kategori yang sama, maka tingka laku akan menampakkan ciri umum yang merupakan unsur hakiki lain dari moralitas, karena itu terdapat dari semua tingka laku moral, dan itulah yang harus ditemukan, di mana hal tersebut, sebagai hal pendorong seseorang untuk bertindak sejauh dengan ketentuan. Untuk menemukan ciri-ciri umum tersebut, Durkheim memberikan petunjuk dalam tulisannya, sebagai berikut: “kita tidak akan mulai pertanyaan apa sebaiknya suatu moralitas itu, atau sebaiknya bentuk apriori dari suatu moralitas. Kita tidak akan bertanya apa sebaiknya tindakan moral itu supaya benar-benar dapat di sebut dengan “moral”, dengan menetapkan beberapa pengertian tentang moralitas sesuai dengan kemajuan penyelidikan atau semacamnya. Sebaliknya kita akan membahas jenis tindakan mana yang disebut tindakan moral. Bagaimana cara-cara bertindak yang diakui bersifat moral dan apa ciri-ciri khas dari cara bertindak tersebut? tugas kita untuk membentuk anak berdasarkan konsep-konsep moral yang berlaku dan sepatutnya diberlakukan.[77] Pada dasarnya unsur ke-2 ini, merupakan proposisi dasar sebagai manipestasi dari fakta empiris yang dapat diverifikasi, fakta menunjukkan bahwa tindakan moral bukanlah dihadapkan pada kepentingan pribadi, melainkan dikatakan tindakan moral, jika prilaku tersebut dihadapkan pada kesatuan sosial atau berhubungan dengan kepentingan publik (orang banyak). Untuk itu, unsur ini perlu diklasifikasi dalam tiga hal, yakni: Disiplin dalam hubungannya dengan keterikatan sosial, masyarakat pada prilaku moral dan masyarakat dengan otoritas moral, ketiga hal di atas, menjadi konsep komparatif intelektual bagi pemikiran Durkheim. Disiplin dalam Ikatan Kelompok Sosial. Sebelumnya perlu kita tegaskan, bahwa kita tidak mempermasalahkan pembatasan sebagai hal pemerkosaan atas kodrat manusia dan telah kita bahas pada pembahasan terdahulu, karena disiplin berguna bukan hanya kepentingan masyarakat dan sebagai syarat mutlak bagi kerja sama yang terakhir, melainkan juga untuk kepentingan individu sendiri, karena tanpa demikian kita tidak mencapai kebahagiaan. Dari sini, proposisi menjadi dasar pemikiran untuk pembahasan selanjutnya. Disiplin merupakan sarana manusia untuk mewujudkan kodratnya, maka disiplin harus berubah sesuai dengan zaman, berhubungan dengan perkembangan historis dari peradaban, maka diperlukan pengungkapan fakta realitas, bukan hanya itu tetapi cara menanamkan disiplin perlu juga kita rubah dan kekuatan-kekuatan yang membatasinya pun selalu kita samakan berbagai kurung waktu dalam perjalanan sejarah. Demikian kompleksnya suatu masyarakat, maka semakin sulit moralitas secara otomatis, jadi perlu pemecahan intelektual untuk memungkinkan diterapkannya kaidah-kaidah moral. Moralitas harus kita tumbuhkan secara fleksibel untuk dapat berubah jika kita perlukan. Tingka laku manusia dapat kita bedakan atas tujuan, yakni ada tiga yang menyangkut individu (personal) dan tujuan yang menyangkut lain dari individu yaitu impersonal,[78] kategori ke-2 mencakup berbagai tindakan, sesuai dengan apa yang ingin dicapai dan tujuan impersonal inilah yang memiliki makna moralitas, karena tindakan moral mengejar tujuan impersonal serta perlu dipahami bahwa tindakan yang dimaksud tidak dilakukan demi kepentingan orang lain yang bukan pelakunya, juga bukan kepentingan orang banyak, tetapi tujuan itu harus melibatkan sesuatu yang lain dari individu-individu yang bersifat adiindividual. Memang banyak yang berpendapat bahwa disiplin (tindakan moral) dalam kelompok sosial (masyarakat), mempunyai ciri-ciri dari individu yang ada di dalamnya, namun anggapan seperti itu, Durkheim menyangkal bahwa secara fakta kita lihat dari penggabungan beberapa unsur elemen seperti Timah dan Tembaga, kedua unsur tersebut sebagai unsur dasar yang lemah, yang kita gabungkan, akan menghasilkan elemen baru (ciri element yang berbeda), yakni menghasilkan perunggu yang keras,[79] jadi dapat dipahami bahwa penggabungan ciri-ciri individu dalam kelompok sosial akan melahirkan ciriciri tersendiri, lain dari dua unsur yang tergabung di dalamnya, namun perlu dibedakan kedua kepentingan di mana sebagai mahluk individu dan sekaligus sebagai mahluk sosial.[80] Tampak secara jelas dari ungkapan di atas, bahwa disiplin dalam ikatan kelompok sosial sangatlah penting fungsinya, karena dalam suatu kelompok terdapat banyak tuntutan yang masing-masing komponen berbeda dan tentunya sangat sulit bagi kita, sehingga kelompok-kelompok sosial hendaklah membuat suatu konsensus, sebagai hukum moral dan rambu bagi anggota-anggotanya dalam pencapaian tujuan kolektif, di sini perlu adanya otoritas disiplin dan keteraturan, sebagaimana yang telah kita ungkapkan. Durkheim memberikan ketegasan bahwa disiplin dan kelompok sosial saling memperkuat sebagai dua hal yang berbeda tapi kedua kebutuhan itu sangat penting dan itulah yang menyebabkan keduanya bersatu, karena tanpa masyarakat disiplin tidak ada artinya, karena masyarakatlah yang menganggap disiplin harus dipatuhi. Masyarakat sebagai sesuatu yang menarik kita yang tampak sebagai pelindung yang penuh kebaikan, karena memiliki aspek dan peranan ganda, terbentuknya ciri khas yang unik, sehingga ia melebihi individu dan masyarakat memerintah kita sebagai otoritas yang imperatif.[81] Masyarakat dengan Tindakan Moral. Durkheim dalam masa perjalanan hidupnya, mempertanyakan persoalan apa yang dapat mempersatukan masyarakat dengan kondisi pada waktu itu, manusia tak lagi memegang arti persatuan, olehnya Ia mendapatkan konsep itu dan dinamakannya “moralitas”. Masyarakat sekalipun dibentuk oleh manusia, tetapi memiliki bentuk hidup sendiri, masyarakat berada di luar perorangan yang memiliki hidup dan eksistensi tersendiri.[82] Perkembangan moral dikaitkan kerelaan para anggota sistem itu tanpa memandang kepentingan individu dan orang lain juga patuh pada pensyaratan “moral”.[83] Wewenang kehidupan moral mempunyai ruang lingkup seluas lingkup kehidupan kolektif, dan dapat dipahami, bahwa kita sebagai mahluk moral sejauh kita menjadi mahluk sosial, sehingga masyarakatlah menjadi tujuan tingka laku moral, dan kita tidak perlu menyangkal bahwa individu dan masyarakat yang pada hakikatnya berbeda, tetapi keduanya bukanlah terdapat semacan antagonistik yang sulit diungkapkan. Manusia pada dasarnya adalah produk masyarakat dan masyarakatlah asal segala sesuatu yang paling baik dalam diri kita serta segala bentuk tingka laku kita yang luhur. Masyarakat berada di luar kita dan melingkupi kita, sekaligus berada dalam diri kita dan merupakan salah satu kodrat kita, dan terdapat di dalamnya seperti halnya dengan organisme fisik yang mendapat makanan dari luar dirinya, demikian pula dengan organisme mental mendapat ide, pikiran dan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari masyarakat, antara kita dengan masyarakat terdapat ikatan yang sangat erat, karena masyarakat merupakan unsur paling baik dalam diri. Olehnya untuk hidup sebagai seorang egois murni kita harus mendekati batas-batas abstrak tersebut. Durkheim menjelaskan keterikatan masyarakat dengan tindakan moral, sangatlah penting yang sulit dipisahkan sebagaimana apa yang dikatakannya: “Untuk menjadi manusia sejati, kita harus segera mengaitkan diri kita dengan sumber utama kehidupan moral dan mental yang menjadi ciri pokok umat manusia. Sumber itu tidak berada dalam diri kita melainkan dalam masyarakat. Dan masyarakat merupakan penghasil serta penyimpang semua kekayaan peradaban. Tanpa kekayaan tersebut, manusia tidak ada bedanya dengan binatang.[84] Sebagaimana manusia hidup dalam tiga kekuatan, yakni keluarga, bangsa atau kelompok politik dan umat manusia, yang ketiganya tidak perlu kita mengabaikan salah satunya dan pertentangan di antara ketiganya macam loyalitas tersebut, seakan-akan seseorang mengasingkan diri dari keluarga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai warga negara atau umat manusia. Karena masyarakat menyatu dengan individu, ia menancapkan akarnya yang kuat dan dalam diri kita di mana terbaik dalam diri hanya emanasi dari masyarakat. Manusia hanya bisa lengkap secara moral, bila dikuasai oleh tiga kekuatan tersebut. dan ketiganya dapat berdampingan, merupakan tujuan yang layak kita kejar, tujuan keluarga berada di bawah tujuan bangsa, karena bangsa sebagai kelompok sosial yang lebih luas (tinggi), sedangkan keluarga sebagai kelompok yang lebih dekat dengan individu, yang lebih mengarah pada kepentingan pribadi. Masyarakat semakin maju dan tersentralisasinya semua anggotanya yang bermula dan berakhir dalam kelompok politik, bangsa-bangsa bertumbuh dari kelompok sampai bergabungnya organisasi sosial yang lebih besar lagi, dengan demikian tujuan moral semakin meluas. Beda dengan bangsa umat manusia sebagai ikatan kelompok sosial yang tidak memiliki unsur struktur dan sifat dan kelompok yang pasti dan jelas. Olehnya tidak mengarah kesana, hanya negara merupakan bentuk yang paling teratur organisasi manusiawi yang ada.[85] Karena suatu perbuatan moral apabila tujuannya adalah kepentingan masyarakat yang memiliki struktur dan sifat tersendiri untuk merealisasikan cita-cita umat manusia yang hanya melalui kelompok paling maju dan paling dekat dengan umat manusia secara keseluruhan, tanpa mencampur adukkan kedua tersebut. Hal ini berarti melalui usaha negara tertentu, usaha-usahanya tidak berpikir “perluasan” atau menyakiti negara-negara tetangganya, hendaklah negara tersebut merealisasikan kepentingan umat dikalangan warga negaranya, menegakkan keadilan, mencapai moralitas yang lebih tinggi, mengatur dirinya sedemikian rupa hingga tercapai hubungan yang lebih erat, hal ini dimaksudkan untuk pencegahan pertikaian antar berbagai negara. Masyarakat dengan Otoritas Moral. Masyarakat sebagai kesatuan sosial menjadi suatu kekuatan yang memiliki sifat dan ciri khas tersendiri yang memaksa individu dalam gerak tingka lakunya, kekuatan dan kesatuan nasional yang menjadi kekuatan penentu disebut “normatif” yaitu kekuatan yang isinya menjadi aturan atau norma[86] yang menjadi aturan sosial. Karena moralitas dalam salah satu fungsinya menghubungkan individu dengan beberapa kelompok, jadi tidak secara apriori bahwa moralitas di buat oleh masyarakat. Demikian masyarakat secara umum memilki kesadaran sendiri untuk mewujudkan masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya, moralitas berbeda antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, ini pertanda secara realitas bahwa moralitas merupakan suatu produk kesatuan sosial, setiap sistem moral dibangun oleh masyarakat yang strukturnya dipantulkan secara sempurna di dalamnya. Masyarakat yang membentuk dan menetukan kewajiban terhadap diri kita, dan menuntut pengembangan suatu bentuk ideal karena terdapat kepentingan yang sangat vital, oleh masyarakat tidak memiliki eksistensi jika semua anggotanya cukup serupa satu sama lainnya, yakni semuanya mencerminkan ciri-ciri hakikat cita-cita tertentu (kolektif), jadi moralitas berbeda-beda sesuai dengan bentuk masyarakat dan negaranya. Otoritas berada dalam pikiran bukan dalam realitas dan otoritas dapat terpenuhi tuntutannya hanya dengan kolektifitas, sebab hanya dengan konsekuensi dari masyarakat secara tidak terbatas mengatasi individu bukan dalam hal material, melainkan juga dalam kekuatan moral. Sangat logis kita berpikir bahwa betapa kuatnya moralitas yang dilengkapi dengan otoritas pada kesatuan sosial, itulah sebabnya otoritas mencapai pengaruhnya yang maksimun, utamanya dalam religius.[87] Kesadaran moral adalah produk masyarakat sebagai masyarakat yang nada bicaranya (tentunya) sebagai refleksi adanya otoritas yang luar biasa, masyarakat bukan hanya merupakan suatu moralitas moral melainkan sebagai sumber semua otoritas moral, hal ini berarti, kekuatan seperti ini bukanlah kekuatan fisik, karena kekuatan fisik tidak memberikan otoritas moral, otoritas tidak terletak pada fakta ekstern dan objektif, yang secara logis menyimpulkan penghasilan moralitas, otoritas terdiri dari konsep yang dimiliki oleh semua manusia yang merupakan masalah opini yang bersikap kolektif serta otoritas sebagai penilaian kelompok dan kualitas seseorang dianggap lebih tinggi (super). Namun dipahami bahwa apa yang digelarkannya tetap orang itu sebagai manusia biasa hanya perbedaannya adalah tingkat belaka, untuk itu, masyarakat melengkapi kualitas manusiawi dengan sifat “sui generis”, mereka menjadi manusia super karena mereka bagian dari superioritas, dalam transendensi masyarakat berhadapan dengan anggotaanggotanya.[88] Secara jelas dapat dipahami bahwa moralitas terdiri dari dua yaitu moralitas yang hanya terdiri dari perintah dan larangan (moralitas kaku) dan yang paling baik adalah moralitas yang tampak layak kita inginkan termasuk dan yang paling baik adalah moralitas yang tampak layak kita inginkan termasuk citacita yang kita semua dambakan dengan sepenuh hati. Dan segala bentuk kehidupan betapa akan berawang-awang, maka tidak akan dapat menyentuh hati dan budi anak-anak, serta rasionalitas melibatkan dorongan moralitas karena hal itu, penting sebagai daya penggerak tingka laku. 3.Unsur Ketiga Moralitas: Otonomi. Banyak ahli pemikir yang merasakan dua kata yang saling berbeda yaitu “kebaikan” dan “kewajiban”, hal mana kewajiban sebagai suatu moralitas yang diperintahkan sebagai suatu otoritas yang harus dipatuhi sedangkan kebaikan adalah suatu moralitas yang dianggap hal yang di inginkan, menarik perhatian secara suka rela dan memperkuat diri kita terhadapnya. Dari sini tampak jelas bahwa keduanya sebagai suatu realitas yang sama, kewajiban adalah masyarakat dalam penetapan aturan-aturan dan kebaikan juga masyarakat dalam pembentukan realitas yang lebih kaya dari pribadi kita sendiri. Secara sepihak banyak yang menyatakan hal itu berbeda, tapi unsur moralitas tersebut dalam kenyataan berkaitan, di mana kebaikan merupakan pengertian dasar dari pada kewajiban berasal, dan kewajiban merupakan persesuaian dari suatu kaidah karena perbuatan yang diperintahkan adalah suatu kebaikan. Konsepsi moral yang banyak diyakini oleh para kaum agamaisme, menganggap bahwa tujuan dari moralitas adalah Tuhan sebagai sesuatu yang mengusai kita sebagai mahluk Adikodrati, hal ini Durkheim memahami konsepsi tersebut, tetapi hanya dalam alur pemikirannya saja, namun Durkheim mengganti Tuhan dengan suatu istilah masyarakat atau dengan kata lain, masyarakat sebagai suatu kekuatan realitas dalam persoalan kehidupan individu dengan hubungannya dengan lingkungan yang mengelilinginya.[89] Banyak juga yang sangsi akan konsep ini, karena moral keagamaan dengan balasanbalasan di alam baqa’, sebagai jaminan otoritasnya, sangksi sosial yang demikian, dalam pelaksanaannya mudah keliru dan tidak pasti. Durkheim menganggap bahwa sangksi seperti itu bukan landasan moral keagamaan seperti dalam sejarah agama Yahudi. Karena kenapa banyak orang yang tidak mau membahas persoalan moralitas, hal itu disebabkan oleh adanya premis-premis dalam paradigma intelektual bahwa memasuki alam moralitas berarti kita memasuki alam misteri yang sangat abstrak, sehingga dalam usahanya (Durkheim) ingin menjelaskan moralitas sebagai suatu realitas yang rasional. Demikian lagi Kant, sebagai seorang moralis yang peka merasakan persoalan seperti itu, ia merasakan sifat imperatif dari hukum moral; ia menjadikannya sebagai kaidah sejati yang harus ditaati dengan pasif. Hubungan antara kehendak manusia dengan hukum adalah hubungan ketergantungan, sekaligus menolak kehendak sepenuhnya akan bersifat moral jika tidak otonomi. Jadi rasionalitas (nalar murni) hanya tergantung pada dirinya sendiri (otonomi), sebagai produk kehendak yang dituntut oleh nalar sedangkan heteronomi merupakan produk perasaan.[90] Durkheim menyangkal bahwa, kita tidak perlu membahas persoalan metafisika, karena itu akan menyesatkan pikiran kita, hendaknya kita beralih pada konsep kenyataan sebagai fakta kenyataan yang ada dalam dihadapan kita. Kadang kita lihat terjadi kontradiksi diantara unsur-unsur moralitas yaitu: kebaikan dan kewajiban, individi dengan masyarakat, moral merupakan hal yang kompleks dan sekaligus kesatuan yang utuh. Kesatuan ini berasal dari mahkluk yang kongkrit dan kodratnya yaitu masyarakat. Di sini Kant, memperlihatkan otonomi merupakan prinsip moralitas yang dalam kenyataan mewujudkan impian impersonal dan umum, Durkheim menyatakan bahwa seluruh kodrat kita mempunyai kebutuhan untuk dipaksa dan diikat serta dibatasi baik kodrat intelektualnya maupun kodrat emosionalnya, karena dalam kenyataan nalar bukan kekuatan transendent, melainkan bagian dari alam dan tunduk pada hukum alam.[91] Karena alam itu terbatas, dan semua pembatasan mengisyaratkan kekuatan yang membatasi, sehingga tampak bahwa otonomi kehendak harus kita tolak dan buang jauh-jauh dari pikiran. Manusia memilki ilmu pengetahuan sebagai alat dalam fisik dan segala yang dapat diamati, akan tersimpan dalam otak sebagai ide-ide yang bersifat ilmiah, sehingga dunia tidak lagi berada di luar diri kita dalam mempelajari hubungan kita dengan dunia, kita hanya menyadari apa yang ada dalam diri kita yaitu otonomi tingkat pertama, kemudian kita mengetahui hukum dari segala sesuatu dan mengetahui alasan sehingga kita mengetahui tatanan universal tadi. Dan kita menyesuaikan diri dengannya, bukan karena paksaan, tidak dapat berbuat lain, tetapi kita berbuat karena menganggap baik dan tidak tidak ada pilihan yang lebih baik. Faitac Compli merupakan suatu balasan ideal yang kita dekati, dan dalam hubungan kita dengan dunia fisik, kita cenderung bertumpu pada diri sendiri dan membebaskan diri dari paksaan dengan ilmu pengetahuan sebagai sumber otonomi kita, yang dalam moralitas terdapat tempat semacam itu.[92] Bukan hal-hal (otonomi dalam arti lain), karena moralitas merupakan pengungkapan kodrat masyarakat yang pemahaman kita tidak dapat lebih dari pengetahuan dunia fisik. Ilmu moralitas sebagai fakta realitas yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menyesuaikan diri dengannya secara suka rela. Komfromitas semacam ini bagi Durkheim, tidak mempunyai unsur pemaksaan dan inilah yang akan menjadi aspirasi umum untuk otonomi moral yang lebih besar. Olehnya, pada saat kita mengetahui “raison d’etre” dan kaidak-kaidah moral, yang kita secara suka rela menyesuaikan diri dengannya, maka kaidah-kaiadah tersebut tidak akan kehilangan sifat imperatifnya yang merupakan ciri khas yang menonjol, karena dalam kenyataan bahwa sesuatu tidak berhenti menjadi dirinya sendiri, hanya karena kita mengetahui sebabnya, ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa sebab-sebab sifat imperatif yang inheren pada kaidah moral, ini tidak memberatkan eksistensi dan kehilangan sifat impertifnya, bahkan kita taat secara suka rela. Dengan demikian kita tetap mahkluk yang pasif bila kita melihat kaidah-kaidah perintah, dan sekaligus aktif dan bebas menghendaki serta mengetahui alasannya. Moralitas bukanlah karya pribadi, tetapi sesuatu yang kita inginkan bersama, yang olehnya kita memiliki kesadaran yang memberi otonomi pada tingka laku. Ketiga unsur moralitas di atas, merupakan ciri khas moralitas sekuler yang semuanya dianggap sebagai Human science berdasarkan ilmu pengetahuan yang mengarah pada sesuatu yang dapat diverifikasi. Kita telah melihat akan disiplin sebagai aspek moralitas dan moralitas kebaikan karena ia memberikan tujuan yang baik, serta juga moralitas rasional sebagai unsur “sui generis” demikian juga pentingnya mengikatkan diri pada kelompok sosial sebagai suatu kodrat alam, yang bila kita melanggarnya (mengasingka diri) darinya sama halnya dengan memperkosa kodratnya sendiri, serta dari kesemuanya lahirlah suatu kesepakatan kesadaran sosial akan suatu aturan yang merupakan tuntutan kita juga di dalamnya, sehingga tidak hanya tanpak paksaan dalam perintah tersebut, melainkan dalam kewajiban itu kita mengetahui alasan-alasan kebaikan yang dikandungnya, sehingga kita mengikuti dengan suka rela. C.Beberapa Persoalan Prilaku Moralitas Sosial. Agama. Kekuatan-kekuatan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat adalah agama yang memiliki konseptualitas moral yang banyak dianut oleh anggota masyarakat, bahkan memasuki segala sendi kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini pertanda bahwa agama merupakan kekuatan moral yang sangat berpengaruh dalam menginterpensi penganutnya. Manusia terkontrol oleh tekanan-tekanan moral yang mengikatnya, segala gerak gerik prilaku sosialnya, terkait dalam aturan yang dipakai, dapat mengantarkan kepada kebahagian bersama. Durkheim memandang agama sebagai fakta sosial,[93] dan agama harus memiliki fungsi, sebab agama bukan ilusi tetapi merupakan fakta yang dapat di indifikasi dan mempunyai kepentingan sosial, segala konsep dasar yang dihubungkan dengan agama, seperti Dewa, Jiwa dan Totem berasal dari pengalaman manusia terhadap golongan sosial.[94] Olehnya, masyarakat membentuk individu sesuai dengan wajah serta gambaran masyarakat sebagaimana ditunjukkan dalam injil bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan wajah dan gambaran dirinya. Masyarakat memiliki sifat keagamaan dan pantas memperoleh penghormatan melampaui individu secara terpisah, dan merupakan objek sesungguhnya dari semua ritual keagamaan. Dalam penelitiannya (mencari ciri-ciri umum agama), ia tidak mendapatkan pada “supra alami” sebab kategori ini bukan ciri universal semua agama dan Tuhan tidak dijadikan “kriterium”, jadi semua agama dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Keyakinan keagamaan, yakni keyakinan yang mengasumsikan penggolongan semua hal, baik yang nyata maupun yang bersifat gagasan, suci maupun duniawi, karena yang suci berada tersendiri dan terlarang, 2) Upacara-upacara keagamaan yaitu aturan-aturan yang mengenai terhadap objek yang suci. Semua agama memiliki komonitas yang mengikuti upacara-upacara yang sama. Dari itu, benda-benda suci tidak disebabkan oleh sifat intrinsiknya, melainkan oleh kenyataan bahwa benda-benda itu melambangkan sesuatu. Durkheim mempertegas bahwa sumber kekuatan keagamaan adalah masyarakat dan tidak dapat diragukan bahwa masyarakat memiliki segalanya untuk membangkitkan pengalaman ketuhanan dalam diri manusia.[95] Hal ini terjadi dalam perayaan-perayaan kolektifitas seperti: kelahiran, pemburuan dan kematian, perasaan kolektif dieratkan, di mana individu terjerat olehnya, di sini terungkap kekuasaan kolektifitas yang merupakan kekuasaan keagamaan dan lebih lagi dijelaskan dalam kutipan di bawah ini: “Mengingat bahwa kekuatan keagamaan tidak lain dari pada kekuatan kolektif dan anomi dari warga, dan mengingat bahwa warga ini hanya diwakili jiwanya dalam bentuk Totem, maka lambang Totem itu ialah tubuh Dewa yang tanpak, dan Dewa sesungguhnya tidak lain dari pada kolektifitas”.[96] Dalam acara seperti itu, dimaksudkan untuk meningkatkan kesatuan kolektif dan mempertajam ide-ide kolektif untuk dapat menghadapi krisis. Masyarakat harus dapat mengukur kelakuan dan membentuknya melainkan sebagai sumber dan objek semua kegiatan keagamaan. Durkheim menganggap semua itu sebagai kategori yang merupakan produk kehidupan sosial, karena kekuatan keagamaan di alami dalam perayaan kolektif dan masyarakat memberikan sarana yang digunakan manusia untuk mengatur dan mengenal kenyataan yang mengelilinginya. Jadi masyarakat sebagai tujuan semua tindakan moral dan salah satu ikatan memilki kekuatan moral adalah agama. Demikian pula agama merupakan suatu “hal sosial” yang utama (pur exellence), agama memberikan penganutnya “kesan-kesan” nyaman,[97] dan semua ini kata “person” konsepsi Durkheim mengenai agama dengan masyarakat, dibuatlah pola-pola yang diberikan sangksi moral sebagai milik bersama anggota masyarakat.[98] Pembagian Kerja. Masyarakat merupakan kekuatan moral yang memiliki kekuatan otoritas yang dalam fungsionalnya menyatakan individu dalam suatu kebersamaan yang utuh, tanpa melihat perbedaan sekalipun, tetapi memandang sesuatu dengan jalan kepentingan orang banyak (publik). Masyarakat dalam hal ini dibagi dua, yaitu: 1) Masyarakat modern dengan ciri pluralistik, dan 2) Masyarakat kuno dengan ciri khasnya “solidaritas mekanis”, mempunyai sumber kesadaran kolektif yang satu dan sama di sebut “alami” yang dihayati sebagai Dewa, Totem dan Masyarakat sendiri. Masyarakat mengatur keberagamaan yang memukul rata fungsi-fungsi anggotanya dengan meniadakan pembagian kerja para anggotanya, karena dianggap sebagai hal yang dapat mengurangi solidaritas dan integritas. Lain lagi dengan masyarakat pluralistik dimana penghargaan terhadap kebebasan, bakat dan prestasi serta karier individu sebagai dasarnya. Penghargaan itu berasal masyarakat, hal ini terlihat suatu pergeseran nilai-nilai, dari kepentingan individu mendahului kesadaran individu, yang pada akhirnya menyebabkan disperensiasi sosial.[99] Durkheim menggunakan istilah “organis” karena menurutnya, beraneka ragamnya dalam anggota masyarakat itulah yang saling membutuhkan dan ketergantungan, tindakan sosial yang berlainan menyangga masyarakat pada tingkat perkembangannya rendah, hampir seluruh hukum bersifat pidana dan tidak berubah, hukum agama mengekang dan tampak konserpatif (hakikatnya).[100] Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu perlu kiranya bahwa keterikatan antara individu dengan masyarakat adalah suatu hubungan yang saling melengkapi dan erat kaitannya yang tak dapat dipisah-pisahkan, olehnya itu, kita tidak boleh terjebak berbagai uraian yang dapat mengelirukan. Dalam masyarakat kolektifitas, kedudukan dan pekerjaan semua anggota ditentukan oleh kolektifitas, sehingga mendefinisikan hidup sebagai kategori sosial, pembagian kerja menurut klasifikasinya dan sebagai ciri masyarakat pluralistik membahayakan kolektif. karena kebebasan individu merupakan alat dan penghormatan baginya, sehingga kolektifitas tidak lagi dapat membatasinya. Kepadatan moral menjadi hal yang sangat terancam,[101] dan meningkat. Olehnya dalam masyarakat mekanis, hukuman yang ditetapkan mengarah pada hukum pidana sebagai suatu solusi yang dapat menyangga otoritas suatu hukum yang dilahirkan berdasarkan konsensus publik. Keadaan yang demikian itu bagi Durkheim, dimaksudkan agar kesadaran moral masyarakat dapat dijaga keutuhannya dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam ruang dan waktu perputarannya. Dengan demikian pembagian kerja bukanlah solusi yang tepat dalam pemikiran kekuatan-kekuatan moral pada masa seperti itu. Solidaritas. Secara spesifikasi kita akan membicarakan tentang hubungan (integritas) antara individu dengan masyarakat atau selebihnya, persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lain sangatlah penting adanya. Berbagai kontradiktif yang sering terjadi di tengah masyarakat yaitu persoalan moralitas yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik untuk kebahagiaan bersama. Olehnya, untuk mencapai maksud tersebut, perlu kiranya dilihat subtansi dari hubungan itu, yang bagi Durkheim dikatakan dalam permasalahan atau hukum sebagai pelengkap dari tindakan “depersonalisasi” dari individu, yang harus konsisten agar stabilitas dari sistem sosial tetap terjaga (solidaritas antara satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan kuat).[102] Pembahasan ini erat kaitannya dengan pembagian kerja, Durkheim pernah berpendapat bahwa kelihatannya untuk meningkatkan solidaritas,[103] di sini nampak kontradiksi antara pemikiran Durkheim, tapi hal ini dipahami bahwa solidaritas dan pembagian kerja yang dimaksud adalah pembagian kerja seperti yang ada dalam keluarga sangatlah penting, karena dalam suatu keluarga perlu manajemen dan pembagian kerja yang merata, seperti Ayah mencari nafkah, Ibu mengurus dapur atau yang lainnya, dalam individu (kelompok keluarga) ini terjadi konflik yang dapat merusak solidaritas atau terjadi diskomunikasi di dalamnya.[104] Dari kenyataan yang ada, baik yang dilukiskan oleh maupun tidak, bahwa disintegritas dari suatu kelompok atau lainnya, banyak menimbulkan dampak negatif seperti: peperangan, permusuhan yang kesemuanya itu salah satu bagian moral yang rusak akibat putusnya rasa solidaritas dalam suatu masyarakat, olehnya dalam unsur moralitas dijelaskan bahwa kesadaran kolektif harus ditumbuhkan dan hal ini dilandasi rasa solidaritas terhadap kolektifitas, karena jika tidak demikian, mustahil kolektifitas yang dimaksud akan tercapai, yang sampai pada disiplin dengan otoritasnya itu sebagai responsibility pemecahan tidak dapat diterapkan dan kontradiksi terus dan semakin meluas yang pada akhirnya hanya menghasilkan kesengsaraan umat. Durkheim mengakui bahwa masyarakat mengalami evolusi solidaritas, yakni solidaritas mekanis menjadi solidaritas organis sebagai ciri khas masyarakat modern yang ciri-cirinya telah kita bahas terdahulu (pembagian kerja).[105] Hal ini disadari akan pentingnya moral dan solidaritas untuk mengantisipasi halhal yang dapat merusak sendi-sendi persatuan kehidupan, yang justru akan membawa masyarakat pada kesengsaraan. Hukum membawa masyarakat pada peradaban untuk lebih baik. Pergeseran ini diakibatkan oleh kesadaran kolektifitas, egoistis indivdidu mengikat dan kepadatan moral tidak terpecahkan. Bunuh Diri. Durkheim melihat bahwa, pluralisme dan pembagian kerja mengakibatkan melemahnya kesadaran kolektif, kekangan atau paksaan masyarakat atas individu berkurang, dan individualisme meningkat. Hal inilah yang dapat membahayakan solidaritas organis yang merupakan syarat utama bagi kehidupan masyarakat modern, olehnya, masyarakat harus dapat mengambil tindakan periventif supaya tidak menjadi kacau balau.[106] Dalam hal ini Dukheim menguji sejauhmana ketergantungan individu dari masyarakat, apakah tindakan ditentukannya sendiri atau pengaruh masyarakat (sosial). Kemudian perbuatannya yang nampak paling individualistik, yaitu bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri sebagai individu, yang akhirnya di simpulkan bahwa bunuh diri adalah “gejala sosial” sebagai fenomenannya.[107] Dari sinilah dapat dilihat dalam tiga bentuk bunuh diri, yaitu: bunuh diri egoistis, bunuh diri altruistis dan bunuh diri anomis (kehilangan pegangan hidup). Bunuh diri egoistis. Sikap seseorang yang tidak berintegrasi dengan orang lain (egoisme), yang tidak memilki tujuan hidup bagi lingkungan sekitarnya. Keadaan yang demikian itu disebabkan oleh egoisme yang berlebihan yang dapat mengakibatkan seseorang bunuh diri. Bunuh diri altruistis. Bunuh diri semacam ini, sebagai lawan bunuh diri egoistis yang merupakan akibat ikatan pada kelompok sosial (masyarakat) yang kuat.[108] Adanya suatu tuntutan ikatan yang demikian kuat, maka ia harus menyesuaikan diri dengannya untuk kepentingan bersama, hal ini sering terjadi dikalangan militer (contoh Durkheim) karena prajurit lebih berintegrasi dengan kesatuan militer, Durkheim menunjukkan dalam statistik, bahwa semakin lama seseorang menjadi militer (profesional), maka semakin besar kemungkinan untuk bunuh diri, seperti halnya jika ia lebih merelakan nyawanya melayang demi masalah bangsa dan negara. c. Bunuh diri alkibat anomi. Bunuh diri keadaan moral, di manusia seseorang kehilangan cita-cita, tujuan dan norma kehidupan. Segala bentuk optimisme dan kreativitasnya musnah dan tak berbadaya, bunuh diri yang demikian bagi Durkheim bahwa manusia tidak dapat bertahan dengan tidak adanya apa yang disebut “summer” sebagai folkways.[109] Dari kesemuanya itu, Durkheim sampai pada kesimpulan bahwa setiap kelompok sosial mempunyai kecenderungan untuk bunuh diri sebagai sumbernya (kecenderungan kolektif yang mengadakan paksaan terhadap prilaku manusia). Dari sinilah tampak kepada kita bahwa bunuh diri merupakan suatu tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan moral sosial, yang jika seseorang menyimpang darinya akan seperti itulah akibatnya. Maka bunu diri tindakan yang menyalahi ketentuan-ketentuan moral. [1]Lihat Ensiklopedia Nasional Indonesia, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 430 [2]Ensiklopedia Indonesia, Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1980), h. 872 [3]Lihat J. Van Baal, Sejarah Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya; Hingga Dekade 1970, diterjemahkan oleh J. Piry, Pengantar Selo Soemardjan, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 201 [4]Lihat Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi (Cet. II; Jakarta: UI-Press. 1982), h. 85 [5]Lihat L. Laeyendecker, Orde, Verandering, Ongelijkheid Een Inleiding in de Geschiedenis Van de Sociologie, dialih bahasakan oleh Samekto, dengan judul: “Tata, Perubahan dan ketimpangan; Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi” (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 280-281 [6]Lihat Koentjaraningrat, loc.cit. [7]Lihat L. Laeyendecker, loc.cit. [8]Lihat Koentjaraningrat, op.cit., h. 87 [9]Lihat Ibid. [10]Lihat L. Laeyendecker, loc.cit. [11]Lihat Koentjaraningrat, loc.cit. [12]Lihat Ensiklopedia Indonesia, Jilid II, loc.cit. [13]Lihat Koento Wibisono, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste Comte, (Cet. II; Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 74 disadur dari buku Emile Durkheim, Over Moraliteit terjemahan berbagai teks dari “Determination du Fait Moral” oleh K. L. Van Der Leeuw, (Boom Mappel, 1977), h. 7-9 [14]Ibid., h. 75 [15]Lihat K. J. Veeger, Realitas sosial; Refleksi Filsafat Sosial Ats Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Cet. III; Jakarta: Gramedia, 1990), h. 166 [16]Lihat Ensiklopedia Indonesia, Jilid II loc.cit. [17]Lihat Prof. DR. L. Laeyendecker, op.cit., h. 306 [18]Lihat Prof DR. N. Drijarkara S.J., Percikan Filsafat; Filsafat Kesusilaan, (Cet. III; Jakarta: PT. Pembangunan, 1978), h. 24 [19]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas, Edisi I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), ck., h. 2 dan 5 [20]David L. Sills, Internasional Encyclopedia of the Social Sciences, Volume III (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1968), h. 319 [21]J. Van Baal, op.cit., h. 202 [22]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, ck., loc.cit. [23]David L. Sills, loc.cit. [24]J. Van Baal, loc.cit. [25]Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, ck., loc.cit. [26]David L. Sills, loc.cit. [27]L. Laeyendecker, loc.cit. [28]David L. Sills, loc.cit. [29]Ibid. [30]L. Laeyendecker, loc.cit. [31]David L. Sills, loc.cit.. [32]J. Van Baal, loc.cit. [33]David L. Sills, loc.cit. [34]Ibid. [35]J. Van Baal, loc.cit. [36]David L. Sills, loc.cit. [37]L. Laeyendecker, loc.cit. [38]K. J. Veeger, Realitas Sosial; Refleksi Filsafat atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Ssejarah Sosiologi, op.cit., h. 140 disadur dari buku Emile Durkheim “Les Regles De la Methode Sociologigue” (1950), h. 56-57 [39]L. Laeyendecker, op.cit., h. 282 [40]Lihat Ibid., h. 283 [41]Ibid. [42]Lihat Soerjono Soekanto, Emile Durkheim; Aturan-aturan Metode Sosiologi (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 137 [43]Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, (Cet. IX; Yokyakarta: Kanisius, 1993), h. 109-110 [44]Lihat Koento Wibisono, op.cit., h. 37-38 [45]Lihat Taufik Abdullah dan A. C. Van Der Leeden, op.cit., h. 11 [46]Lihat K.J. Veeger, op.cit., h. 47-48 [47]Ibid., h. 39 [48]Lihat Ibid., h. 143 [49]Soerjono Soekanto, Emile Durkheim, op.cit., h. 140 [50]L. Laeyendecker, op.cit., h. 284 [51]Soerjono Soekanto, op.cit., h. 141 [52]Lihat Ensiklopedia Indonesia, Jilid IV (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Houve, 1989), h. 2288 [53]Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 592 [54]Lihat Ensiklopedia Indonesia, Jilid IV, loc.cit. [55]Lihat Juhana S. Praja, Aliran-aliran Filsafat dan Etika; Suatu Pengantar (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 42 [56]Lihat Ensiklopedia Indonesia, op.cit., h. 973 [57]Franz Magnis Suseno, dkk., Etika Sosial; Buku Panduan Mahasiswa PBI-PBVI (Cet. III; Jakarta: Gramedia, 1993), h. 9 [58]W. Poespoprdjo, Filsafat Moral; Kesusilaan dalam Teori dan Praktek (Cet. II; Bandung: Remadja Karya, 1988), h. 102 [59]Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika; Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19 (Yokyakarta: Kanisius, 1997), h. 143 [60]Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas, Edisi I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), h. 157 [61]Robert C. Solomon, Ethics, A Brief Introduction, diterjemahkan oleh R. Anre Karo-Karo, ”Etika; Suatu Pengantar” (jakarta: Erlangga, 1987), h. 7 [62]Baca Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, diterjemahkan oleh Soejono Margono dari judul “Elements of Philosophy (Cet. V; Yokyakarta: Tiara Wacana Yokya, 1992), h. 353 [63]Ibid. [64]Sikap atau peranan seseorang yang bertentangan dalam waktu yang bersamaan terhadap orang lain, misalnya: rasa benci dan cinta; kelakuan-kelakuan yang tidak tepat, karena perubahan-perubahan disebabkan oleh suatu pembatasan, lihat, Sudarsono, Kamus Filsafat dan Psikologi (cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 10 [65]Tujuan moralitas teoritis adalah menyusun hukum umum moralitas, sedangkan moralitas terapan bertujuan menyelidiki bagaimana hukum tersebut diterapkan pada situasi umum yang bermacam ragam, dan ditemukan dalam hidup. Durkheim menyatakan bahwa kaidah khusus yang disimpulkan dengan cara seperti itu bukan merupakan realitas yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan perluasan atau akibat wajar dari prinsip umum sebagaimana yang tercermin dalam rangkaian pengalaman hidup, Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 157-158 [66]Emile Durkheim, Pendidikan Moral; Suatu studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan, dialih bahasakan oleh Lukas Ginting, dari judul “Moral Education” (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 19 [67]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 154 [68] Emile Durkheim, Pendidikan Moral, op.cit., h. 24-25 [69]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 161 [70]Kebiasaan adalah daya-daya yang di internalisasikan dalam pribadi seseorang, semacam kumpulan pengalaman dalam diri kita yang mekar dari dirinya sendiri yang diaktifkan secara spontan, Lihat Ibid. [71]Lihat Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 22 [72]Lihat Ibid., h. 25 [73]Vurgina Held, Rights and Goods, Instifying Social Action, dialih bahasakan oleh Y. Andry Handoko dengan judul “Etika Moral; Pembenaran Tindakan Sosial” (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 125-128 [74]Lihat Taufik Abdullah dan Van Der Leeden, op.cit., h. 153-169 [75]Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 28-29 [76]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 177-178 [77]Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 40-41 [78]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 188 [79]Ibid., h. 193-194 [80]Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 67 [81]Lihat J.Van Baal, Syarat dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya, Jilid I (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 201-203 [82]Lihat Doyle Paul Johnson, Sociological Theory; Classical Faunders and Contemporery Perpectives, dialih bahasakan oleh Robert M.Z. Lawang denha judul “Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1986), h.58 [83]Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 52-53 [84]Taufik Abdullahdan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 206 [85]A. Lysen, Individu En Gemeenschap, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Individu dan Masyarakat” (Cet. IX; Bandung: Sumur Bandung, 1981), h. 21 [86]Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 218-219 [87]Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 218-219 [88]Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 65-66 [89]Lihat Ibid., h. 75 [90]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 239 [91]Lihat, Emile Durkheim, Pendidikan Moral…, op.cit., h. 81 [92]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 245 [93]K.J. Veeger, Realitas Sosial; Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi (Cet. III; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 157 [94]Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat; Pendekatan Sosiologi Agama (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 31 [95]L. Laeyendecker, Orde, Verandering, Ongeljkheid; Een Inleiding In de Geschendenis um de Socilkogie, dialih bahasakan oleh Samekto dengan judul “Tata, Perubahan dan ketimpangan ; Suatu Pengantar Sosiologi” (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.298 [96]Totem adalah benda suci, sejenis hewan atau tanaman sebagai komponen struktur sosial dan marga adalah kelompok orang-orang suci yang memakai simbol Totem, Lihat Ibid., h. 297 [97]Lihat Thomas F. O’dea, Sosiologi agama; Suatu Pengantar Awal (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindi Persada, 1994), h. 21-23, disadur dari Dukheim, The Elemtary Froms of The Religions Life, h. 387 [98]Ibid., h. 25, disadur dari Parsons, “Essays in Sociological Theory” (Glencoe, III; The Free Press, 1958), h. 208-209 [99]Lihat K.J. Veeger, op.cit., h. 146-148 [100]Lihat Taufik Abdullah dan A.C. Van Der Leeden, op.cit., h. 146-157 [101]Lihat K.J. Veeger, op.cit., h. 149-150 [102]Lihat Adam Podgorecki dan Chriestopher J. Whelan (ed.), Sociological Approaches to law, yang diterjemahkan oleh Rac. Widyaningsih dan G. Kartasa Poetra dengan Judul “Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum” (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 104-105 [103]L. Laeyendecker, op.cit., h. 290 [104]Lihat Ibid. [105]Lihat Ibid., h. 292 [106]lihat K.J. Veeger, op.cit., h. 150 [107]Lihat Ibid., h. 151 [108]Lihat L/ Laeyendecker, op.cit., h. 288 [109]Lihat K.J. Veeger, op.cit., h. 154-157