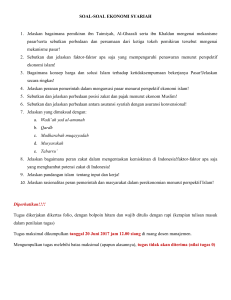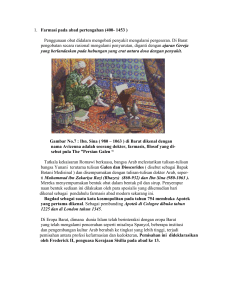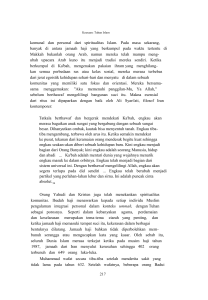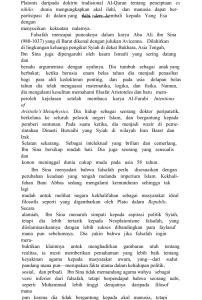Akhirnya, Ahlussunnah wal-Jama`ah (Aswaja) yang dianut
advertisement

Prelude Yang tersayang, Peserta MAPABA 22. Puji Syukur kami sampaikan pada Allah SWT, Tuhan yang dituhankan sebagian umat manusia, Tuhan mutlak bagi umat Islam. Dalam modul kali ini kami sertakan beberapa tulisan yang kami rasa cukup merefleksikan semangat kePMII-an. Semoga susunan modul ini dapat memberikan manfaat, walaupun hanya sedikit. Syukur-syukur kalau dibaca, kalau tidak, setidaknya disimpan saja kami sudah bahagia. Toh kalau tidak kuat membacanya, setidaknya modul ini dapat dijadikan bantal sandaran tidur, sehingga berkah dapat diperoleh dengan variasi yang berbeda, yaitu relaksasi urat leher mahasiswa yang menuntut ilmu. Salam hangat, Tim penyusun 10 November 2016 AHLUSSUNNAH WAL-JAMA’AH (Oleh : Ahmad Afif Hidayatulloh) Pendahuluan Islam adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia, demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat. Sebagai risalah yang diperuntukkan kepada umat manusia, Islam merupakan agama yang sempurna. Islam yang sudah sempurna tersebut identik dengan al-Qur’an dan al-Hadits sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Aku tinggalkan (wariskan) bagimu dua hal yang kalau kalian selalu berpegang teguh padanya, maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kalamullah (al-Qur’an) dan Sunnah Rasul (al-Hadits)”. Islam demikianlah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika Beliau menerangkan “Ahlussunnah walJama’ah”, yaitu: ma ana alaihi wa ash-habi, yang artinya “Apa yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku (ajaran yang aku sampaikan dan aku teladankan serta diamalkan dan ditiru oleh para sahabatku)”. Menurut K.H. Abdul Muchith Muzadi, kesempurnaan Islam sebagaimana diterangkan di atas tentunya bukan berarti bahwa segala hal diterangkan secara terinci dan ketat (baku), tetapi justru kesempurnaan Islam itu tercermin dari dua cara pemberian pedoman, ada yang terperinci dan ada yang hanya diajarkan prinsip-prinsipnya saja yang dapat/harus dikembangkan. Dengan demikian Islam akan selalu dapat memberikan pedoman bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman, “shalihun li kulli zamanin wa makan”. 1 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Islam yang dinyatakan sempurna oleh Allah SWT, Islam yang Ma Ana Alaihi wa Ash-habi, Islam pada zaman Rasulluah SAW yang dilanjutkan oleh generasi para sahabat, ialah Islam yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlussunnah walJama’ah (biasa disingkat Aswaja), Islam yang murni atau otentik, dan Islam yang harus dipegang teguh sepanjang zaman, tidak boleh disempalkan. Selain itu, Islam yang sempurna dan yang paling terjaga kemurnian atau keotentikannya tersebut harus dikembangkan secara terkendali agar tetap pada keaslian dan kelurusannya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dapat menjawab masalah-masalah baru yang selalu muncul sepanjang zaman.2 Sebagai organisasi dengan corak ke-Islaman, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sejak awal berdirinya hingga sekarang menegaskan dirinya sebagai penganut, pengemban, dan pengembang Islam ala Ahlussunah wal-Jama’ah di atas. Dengan sekuat tenaga, PMII berusaha menempatkan diri sebagai penebar dan pengamal setia ajaran Aswaja ini. Bagi PMII sendiri, Aswaja menjadi pemandu gerakannya agar selaras dengan cita-cita perjuangan Islam sebagaimana yang telah diajarkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW 1 K.H. Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Surabaya: Penerbit Khalista, 2007), hlm.151. 2 Ibid, hlm. 152. 1 beserta para sahabat. Karena penting dan mendasarnya Islam yang tidak menyimpang, tidak menyeleweng, dan tidak pula menyempal ini, maka tentunya diperlukan upaya untuk memahami ajaran Islam yang murni, Islam yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai Ahlussunnah wal-Jama’ah, yang akan diterangkan lebih lanjut pada pembahasan berikut ini. Sketsa Sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah: Timbulnya Firqah dalam Islam Risalah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan kesatuan utuh yang sempurna dan paling lengkap dibandingkan risalah yang dibawa oleh para Rasul sebelum beliau. Adapun risalah tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yaitu, Iman, Islam dan Ihsan. 3 Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Iman berarti akidah/keyakinan, Islam berarti syari’ah/amalan-amalan, sedangkan Ihsan berarti akhlak dalam beribadah. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, ketiga ajaran tersebut diterapkan/diamalkan oleh para sahabat secara terpadu dan seimbang berdasarkan petunjuk dan keteladanan beliau. Sehingga di antara ketiga unsur tersebut, tidak ada yang lebih ditonjolkan atau bahkan dipertentangkan dengan yang lain. Keutamaan risalah Nabi SAW yang seperti ini menjadikannya sebagai agama (din) yang paling sempurna, paling lengkap, dan diridhai oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya, “…..Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-penuhi nikmat-Ku padamu, dan telah Ku-ridhai Islam jadi agama bagimu” (Q.S. al-Maidah: 4). Selama itu, segala hal yang tidak dimengerti penjelasannya dan tidak diketahui praktik amalannya, maka seluruh persoalan itu dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah yang akan mengajarkan dan membimbing umatnya sesuai petunjuk Allah SWT. Oleh karenanya, risalah Nabi SAW tentu terpelihara kemurnian dan keasliaannya. Di masa Rasulullah SAW sedang sakit, bibit-bibit keretakan/konflik di antara umat Islam mulai tampak. Konflik tersebut semakin mencuat pada saat Allah SWT memanggil Nabi SAW kembali ke haribaan-Nya. Adapun keretakan/konflik pendapat yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika beliau 3 Dalam Kitab Tajrid al-Sharih, keterangan mengenai Iman, Islam, dan Ihsan ini tercantum dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari: “Abu Hurairah R.A. menceritakan: suatu hari Rasulullah SAW tampil di hadapan umum, lalu seorang laki-laki menghampirinya dan laki-laki itu bertanya, apa Iman itu? Rasulullah SAW menjawab, bahwa engkau beriman kepada Allah SWT, malaikat-Nya, beriman akan berjumpa dengan-Nya, beriman pada para rasul-Nya, dan pada hari kebangkitan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apa Islam itu? Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu bahwa engkau menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat wajib, dan berpuasa ramadhan. Laki-laki itu bertanya lagi, apa Ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, bahwa engkau menyembah Allah SWT seakan-akan engkau melihat-Nya, namun jika engkau tidak dapat demikian maka sesungguhnya Ia melihatmu……(setelah semua pertanyaan dijawab Rasul SAW), kemudian beliau bersabda, inilah malaikat Jibril yang datang untuk mengajar tentang urusan agama kalian” (Abu al-Abbas Zain al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Lathif, Tajrid al-Sharih li Ahadits al-Jami’ ma’a al-Shahih, [Surabaya: Penerbit al-Hidayah], hlm. 13). 2 sedang sakit dan sesudah wafat tersebut sebenarnya merupakan perbedaan (ikhtilaf) masalah ijtihad semata, sedangkan perbedaan pendapat tersebut justru akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum baru dan akan memperkokoh agama4. Hanya saja, dari sekian banyak perbedaan itu, kemudian Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm.14. Menurut al-Syahrastani, jumlah ikhtilafiyah (perbedaan) tersebut berjumlah sepuluh. Berikut uraikan kesepuluh macam jenis perbedaan tersebut: 1) Perbedaan di kalangan para sahabat dalam menafsirkan sabda Nabi SAW pada saat beliau sedang sakit keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda: “Ambillah tinta dan kertas, kutulis untuk kamu satu kitab yang kamu tidak akan tersesat sesudahku….,” Salah satu sahabat, Umar ibn Khattab menafsirkan ‘kitab’ yang dimaksud Nabi ialah kitab Allah SWT, sedangkan sahabat yang lain berbeda pandangan dengan sahabat Umar. 2) Perbedaan pendapat yang terjadi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit , yaitu pada hadis beliau yang berbunyi: “Bergabunglah kalian dengan pasukan Usamah, Allah SWT mengutuk orang yang tidak menggabungkan diri dengannya.” Sebagian sahabat berpendapat wajib mengikuti perintah Rasulullah SAW meskipun pasukan Usamah sudah berada di luar kota. Sebagian sahabat lain berpendapat bahwa dalam keadaan Rasul SAW sakit keras begini, mereka tidak tega meninggalkannya dan sebaiknya memilih bersabar sampai jelas bagi mereka keadaan Rasulullah SAW. 3) Perbedaan pendapat ketiga terjadi sesudah Rasul SAW wafat di mana sahabat Umar ibn Khattab berkata, “Siapa yang mengatakan Muhammad telah tiada akan kupenggal lehernya dengan pedangku ini. Ia naik ke langit sebagaimana Isa AS diangkat naik ke langit”. Sahabat Abu Bakar ibn Quhafah menandaskan dan berusaha menyadarkan Umar dengan membacakan surat Ali Imran ayat 144. Dengan kejujuran dan ketulusan Abu Bakar, seketika Umar tersadar dari kekalutannya. 4) Perbedaan keempat mengenai tempat pemakaman Rasulullah SAW. Kaum Muhajirin menghendaki agar dimakamkan di Makkah dengan alasan bahwa beliau lahir dan dibesarkan di kota itu, dan merupakan tempat permulaan hijrahnya. Kaum Anshar menghendaki dimakamkan di Madinah dengan alasan tempat itu menjadi tujuan hijrah Nabi SAW, permulaan kemenangan dalam menyebarkan Islam. Sedangkan yang lain menginginkan dimakamkan di Bait al-Maqdis karena kebanyakan para Nabi dimakamkan di sana. Namun pada akhirnya semua sepakat untuk memakamkan jasad Nabi SAW di Madinah setelah menyimak hadis yang dibacakan Abu Bakar, “Para Nabi dikuburkan di mana mereka wafat.” 5) Perbedaan kelima yaitu tentang kepemimpinan (imamah). Tidak ada perselisihan yang tersebar selain dari perselisihan mengenai imamah ini. Sebuah perbedaan pandangan yang bahkan menjurus pada pertikaian dengan mengangkat senjata. Namun, Allah SWT telah menyelamatkan umat Islam pertama dari bencana ini, ketika terjadi perbedaan pendapat antara kelompok Muhajirin dan Anshar di pertemuan Saqifah Bani Sa’adah dalam memilih kepemimpinan sesudah Rasulullah SAW wafat. Hingga akhirnya seluruh kaum muslimin sepakat membai’at sahabat Abu Bakar ibn Quhafah sebagai khalifah pertama penerus perjuangan Nabi SAW. 4 3 6) 7) 8) 9) Perbedaan keenam menyangkut masalah tanah yang terletak di perkampungan Fadak yang merupakan peninggalan Rasulullah SAW. Fatimah selaku puteri Nabi SAW mengatakan tanah itu adalah tanah warisannya dari Rasulullah SAW sehingga ia berpandangan bahwa tanah itu menjadi haknya. Sebaliknya, Abu Bakar sebagai Khalifah terpilih menolak permintaan Fatimah dengan mengacu pada hadis Nabi SAW, “Kami para nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.” Lalu, para sahabat ingat akan hal itu. Perbedaan ketujuh mengenai sikap terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dalam hal ini, Ibn Katsir menceritakan, mereka yang menolak membayar zakat berhujjah dengan firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 103, bahwasanya zakat tidak wajib ditunaikan kecuali kepada orang (Nabi SAW) yang do’anya membuat mereka tenang. Umar beserta sebagian sahabat lain berbicara kepada Abu Bakar agar beliau membiarkan mereka yang tidak mau membayar zakat, dan terus mengasihi mereka sehingga iman menancap kokoh dalam hati mereka, sampai saatnya nanti mereka mau membayar zakat. Akan tetapi, Abu Bakar menolak. Sekelompok ulama ahl al-hadits meriwayatkan dalam kitab-kitab mereka – selain Ibn Majah – dari Abu Hurairah RA. bahwasanya Umar ibn Khattab berkata pada Abu Bakar, “Atas dasar apa engkau perangi orang-orang itu, padahal Rasulullah SAW bersabda, Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Kalau mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, niscaya jiwa dan hartanya terjamin, kecuali dengan haknya.” Lalu Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan seekor anak unta – dan dalam sebuah riwayat: seutas tali – yang dahulu pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena itu, sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat.” Kemudian Umar berkata, “Demi Allah, telah tampak padaku bahwa Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang, lalu aku mengetahui bahwa itulah yang benar.” Perbedaan kedelapan yaitu tentang penunjukan sahabat Umar ibn Khattab sebagai Khalifah kedua oleh Abu Bakar sebelum wafatnya. Sebagian sahabat berkata Abu Bakar telah menunjuk orang yang keras dan kasar. Namun, Abu Bakar berkata kalaulah aku ditanya pada hari kiamat nanti akan kujawab aku telah menunjuk orang yang menjadi pemimpin adalah orang yang terbaik di antara mereka. Perbedaan kesembilan yaitu tentang musyawarah dan perbedaan perndapat. Tatkala Khalifah Umar menderita sakit keras akibat tikaman belati seorang Majusi bernama Abu Lu’luah, beliau berkata – setelah mengetahui siapa pembunuhnya -, “Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang muslim yang akan menghujatku di sisi Allah dengan sujud yang dia lakukan.” Kemudian Khalifah Umar dalam sebuah musyawarah menetapkan tim suksesi yang beranggotakan enam sahabat, yaitu Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa’ad ibn Abi Waqqash. Lalu, Abdurrahman bertanya, “Siapa yang akan mundur dari pencalonan ini?” Dan ia sendiri mengundurkan diri, kemudian diikuti oleh tiga orang lainnya sehingga tinggal Ali dan Utsman saja – keduanya menantu Nabi SAW. Tiga orang yang memilih mundur tersebut beserta dua calon sepakat menyerahkan panitia pemilihan kepada Abdurrahman ibn Auf. Sebagai ketua panitia, Abdurrahman kemudian 4 melakukan hubungan dengan siapa saja terutama penduduk Madinah, siapa yang pantas kiranya menjadi khalifah. Ammar ibn Yasir berkata padanya, “Kalau ingin umat Islam bersatu, tidak pecah belah, hendaknya memilih Ali.” Miqdad ibn al-Aswad menyetujui pendapat ini. Akan tetapi, Abdullah ibn Abi Sarrah berpendapat, “Jika ingin suku besar Quraisy utuh, hendaknya memilih Utsman saja.” Pendapat ini disepakati oleh Abdullah ibn Rabi’ah. Pendapat ini lantas diprotes oleh Ammar dan ia bertanya, “Sejak kapan engkau menjadi penasihat Islam?” Ibn Abi Sarrah disindir keras karena dulunya memeluk Islam, tapi kemudian hari ia berpaling kepada pembesar Quraisy dan mengolok-olok Nabi SAW. Hingga tiba saatnya Nabi mendapatkan kemenangan (peristiwa fath al-makkah) dan mengumumkan perdamaian kepada penduduk Makkah, kecuali delapan orang yang harus menjalani hukuman mati, termasuk di antaranya ialah Abdullah ibn Abi Sarrah. Setelah mengetahui keputusan Nabi SAW tersebut, Ibn Abi Sarrah segera meminta perlindungan kepada Utsman ibn Affan dimana keduanya masih saudara sesusuan. Berkat Utsman, akhirnya ia memperoleh ampunan Nabi SAW. Hal inilah yang menjadikan Ammar ibn Yassir beranggapan bahwa Ibn Abi Sarrah hanya mementingkan suku Quraisy saja, meskipun setelah pertobatannya itu Ibn Abi Sarrah menjadi komandan pasukan pimpinan panglima Amr ibn Ash dan ia berjasa dalam penakhlukan Palestina, Syiria, dan Mesir. Akhirnya, setelah melakukan “lobi” yang lebih luas dengan kaum muslimin, Abdurrahman ibn Auf menetapkan Utsman ibn Affan sebagai khalifah. Awalnya, Ali mengkritik keputusan itu, apalagi Abdurrahman adalah ipar Utsman ibn Affan – keduanya termasuk Bani Umayyah, sedang Ali adalah Bani Hasyim. Akan tetapi, Abdurrahman menjelaskan bahwa pilihannya itu bukan kepentingan pribadinya, melainkan kepentingan mayoritas kaum muslimin. Setelah menerima penjelasan tersebut, Ali pun ikut membai’at Utsman bersama-sama dengan para sahabat lainnya. Pada saat kekhalifahan dijabat Utsman, keadaan negara di masanya tenteram, dakwah Islamiah tambah meluas dan banyak daerah baru yang dikuasai umat Islam, keuangan Negara melimpah ruah, semua orang merasa diperlakukan dengan adil dan masyarakat merasa diayomi dengan baik. Hanya saja, pemerintahan Utsman berakhir dengan berbagai macam kekacauan dan pemberontakan yang dipicu oleh tuduhan dan fitnah oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya mengakibatkan ia sendiri mati terbunuh. 10) Perbedaan kesepuluh terjadi di masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Peristiwa pertama yaitu terjadinya pemberontakan terhadap pemerintahan Ali ibn Abi Thalib oleh Thalhah dan Zubair di Makkah yang mengajak Aisyah bergabung dengan mereka dan berangkat ke Bashrah untuk mencari dukungan masyarakat. Munculnya pemberontakan di atas pada dasarnya berawal dari situasi pembai’atan Ali yang masih dipenuhi kekacauan dan merebaknya tuntutan atas pelaku pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Kelompok yang dipimpin Aisyah, Zubair, dan Thalhah beralasan bahwa sikap mereka tersebut didasari sebuah tuntutan keadilan hukum atas pelaku yang membunuh Utsman. Mereka berpandangan bahwa tindakan qishash (tuntutan balas membunuh) harus segera dilakukan dan mendesak Khalifah Ali agar tidak membiarkan para pembunuh Utsman berkeliaran menghirup udara bebas tanpa hukuman qishash atas mereka. Khalifah Ali sependapat dengan kelompok yang dipimpin Aisyah, bahkan ia mengutuk keras para pembunuh Utsman. Hanya saja Khalifah Ali meminta mereka bertiga untuk bersabar dulu dan memberikan dukungan padanya untuk menciptakan kondisi Negara yang solid dan 5 berkembang menjadi perselisihan yang menyebabkan timbulnya firqah-firqah (sempalan-sempalan) di kalangan umat Islam. Perselisihan tersebut tidak lain ialah perdebatan mengenai siapa yang tepat menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Sahabat Anshar (kaum muslim Madinah) memandang bahwa jabatan Khalifah harus dari kalangan mereka, karena merekalah yang telah menyambut, menolong dan melindungi dakwah Nabi SAW, sehingga Islam bisa berkembang pesat. Pada saat itu, mereka (sahabat Anshar) berkumpul di sebuah rumah kondusif, sehingga hukuman had (tuntutan balas) itu memungkinkan diberlakukan dalam iklim yang tertib dan aman terkendali, jauh dari perpecahan. Akhirnya upaya Khalifah Ali pun menuai hasil berkat seorang sahabat genius, al-Qa’qa’ ibn Amr al-Tamimi yang berhasil melobi Aisyah dan kelompoknya untuk berdamai dan membuat kesepakatan atas rencana Sang Khalifah. Demikianlah, upaya rekonsiliasi di atas berhasil mendamaikan kedua kelompok dan Aisyah beserta Thalhah dan Zubair menyadari kekeliruannya. Kirakira dua hari semenjak perdamaian tersebut, para pembunuh Utsman yang merasa terancam dengan perdamaian kelompok Ali dan Aisyah berupaya menyulut kembali api peperangan, terutama ditujukan pada sejumlah pendukung Aisyah yang tidak senang atas perdamaian tersebut. Hingga akhirnya muncullah kekacauan antara kedua kelompok tersebut di mana masing-masing pihak menuduh telah mengkhianati janji yang telah mereka sepakati. Perang pun tak dapat dielakkan (sejarah menyebutnya sebagai perang jamal) dengan sepuluh ribu korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk Thalhah dan Zubair gugur sebagai syuhada’ di tangan para pengendali kekacauan dari kedua belah pihak. Aisyah sendiri beruntung masih selamat, sehingga ketika ditawan pasukan Ali, ia menyadari kesalahannya dan Khalifah Ali membebaskannya. Perbedaan pendapat juga terjadi antara Khalifah Ali dengan Muawiyah (Gubernur Damaskus, Syam). Sikap Muawiyah yang tidak berkenan dengan permintaan Sang Khalifah akhirnya menyebabkan terjadinya peperangan yang dalam sejarah dikenal dengan nama perang Shiffin. Pada saat pasukan Ali hampir menuai kemenangan, pasukan Muawiyah yang dipimpin Amr ibn Ash mengangkat mushaf pada ujung tombak sebagai isyarat meminta perundingan sebagaimana ajaran menurut al-Qur’an. Dengan adanya perundingan ini, sejumlah kalangan yang awalnya mendukung Khalifah Ali akhirnya memilih keluar dari kelompok Khalifah. Mereka berpandangan kelompok Muawiyah yang diwakili Amr ibn Ash sebenarnya memiliki niat jahat di balik maksud ajakan tahkim (gencatan senjata) tersebut. Sehingga Khalifah Ali yang menerima perundingan tersebut dianggap tidak memenuhi perintah Allah SWT untuk menumpas para pembangkang (kelompok Muawiyah) yang mereka anggap telah kafir, keluar dari ajaran islam. Mereka ini yang keluar dari kelompok Ali kemudian dinamai sebagai kelompok Khawarij. Pada perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij semakin kuat dan solid ketika proses perundingan menuai kegagalan dan berakhir tanpa membawa kesuksesan. Khalifah Ali memutuskan untuk menumpas kelompok Khawarij ini, meskipun beliau masih membuka pintu bagi orang-orang Khawarij yang mau bertobat. Pada episode akhir peperangan dengan kaum Khawarij ini, dengan dalih untuk membebaskan umat Islam dari tiga orang yang mereka tuduh kafir (Ali, Muawiyyah, dan Amr ibn Ash), mereka (kelompok Khawarij) melakukan konspirasi untuk membunuh ketiga orang di atas. Akan tetapi rencana mereka hanya berhasil membunuh Khalifah Ali melalui tangan Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. 6 ‘Saqifah Bani Sa’adah’ (suatu keluarga terhormat dan terkemuka dari Suku Khajraj) untuk bermusyawarah. Mereka mengajukan seorang sahabat Anshar bernama Sa’ad ibn Ubadah untuk menggantikan Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam. 5 Sementara di pihak lain, kaum Muhajirin (kaum muslimin suku Quraisy) – setelah mendengar kabar berkumpulnya kaum Anshar di atas – berpandangan bahwa khalifah harus dari kalangan mereka dengan alasan bahwa mereka lebih dahulu memeluk Islam, lebih dekat dengan Nabi (paling banyak merasakan susah-duka berjuang bersama Nabi SAW), di samping Nabi SAW pada kenyataannya berasal dari suku mereka. Kemudian, kaum Muhajirin memutuskan untuk menemui kaum Anshar yang berkumpul di Saqifah Bani Sa’adah melalui perwakilan mereka yang terdiri dari tiga orang, yaitu Abu Bakar ibn Quhafah, Umar ibn Khattab, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kemudian, terjadilah dialog yang diiringi perdebatan antara kedua pihak (kelompok Anshar dan Muhajirin), hingga akhirnya perdebatan tentang masalah khilafah ini dapat diatasi dengan tampilnya Abu Bakar, yaitu pada saat beliau berpidato6 untuk mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun keputusan mengenai khilafah sudah disepakati menjadi hak kaum Quraisy, mulanya Abu Bakar mengajukan Umar ibn Khattab sebagai Khalifah. Namun, Umar merasa keberatan dengan permintaan beliau. Malahan, Umar meminta Abu Bakar sendiri yang menjadi khalifah. Selanjutnya, Umar segera membai’at Abu Bakar dan perbuatannya ini diikuti oleh sahabat yang lain, seperti Abu Ubaidah (Muhajirin), Basyir ibn Sa’ad (Anshar). Pada akhirnya, semuanya membai’at Abu Bakar. Al-Thabari menceritakan dalam Tarikh-nya: Seorang Anshar yang mendukung Sa’ad ibn Ubadah berkata, “Orang-orang Arab telah tunduk pada beliau (Nabi SAW) adalah karena pedang-pedang kalian. Allah telah mewafatkan beliau dan beliau ridha terhadap kalian, dan beliau merasa senang terhadap kalian. Maka raihlah kekuasaan ini. Sesungguhnya kekuasaan ini untuk kalian, bukan orang lain. Lalu serentak yang lain berkata, “Kamu tepat dengan pendapat ini dan kamu benar” (Ibn al-Arabi, Gejolak Api Permusuhan Syi’ah-Khawarij dan Orientalist terhadap Nabi SAW: al-Awashim min al-Qawashim fi Tahqiqi Muwatifi al-Shahabah ba’da Wafati al-Nabiy, [Penerbit Akbarmedia, 2010], hlm. 8). 6 Ibn al-Arabi menceritakan: Abu Bakar membacakan hadis Nabi SAW (riwayat Imam Ahmad), “Para pemimpin itu dari Quraisy, sesungguhnya mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan.” Kemudian, beliau melanjutkan pidatonya, “Aku wasiatkan pada kalian agar berbuat baik pada kaum Anshar. Yaitu agar kalian menerima dengan baik orang yang baik dari kalangan mereka dan memaafkan orang yang bersalah dari mereka”. Setelah itu beliau menuturkan, “Sesungguhnya Allah menamai kami gelar al-shadiqin (orang-orang yang benar) dan menamai kalian orang-orang al-muflihin (orang-orang yang beruntung). Allah memerintahkan kalian agar selalu bersama kami di manapun kami berada.” Kemudian beliau membaca surat at-Taubah ayat 119, “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah SWT, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” Dan perkataan-perkataan lain yang benar dan argumen yang kuat. Semua itu membuat kaum Anshar tersadar dan patuh kepada Abu Bakar dan mereka pun bersedia membai’atnya (Ibid, hlm. 9). 5 7 Ketika Abu Bakar sedang sakit7, beliau merasa ajalnya telah dekat. Dalam kondisi demikian, beliau merenung-renung lama tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Meskipun dalam hatinya Abu Bakar cenderung kepada Umar, tapi ia ingin tahu bagaimana pendirian para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya setelah melibatkan perundingan dengan banyak sahabat, diputuskanlah Umar ibn Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Khalifah Umar menjabat selama kurang lebih 10 tahun. Pada akhir masa kekhalifahannya dalam kondisi sakit payah, ia menetapkan penggantinya berdasarkan musyawarah8. Akhirnya, musyawarah yang dipimpin oleh Abdurrahman ibn Auf tersebut menghasilkan kesepakatan Utsman ibn Affan sebagai khalifah pengganti Umar ibn Khattab. Akan tetapi, pada masa kekhalifahan Utsman ibn Affan, khususnya pada masa-masa akhir pemerintahannya, perselisihan masalah khilafah ini muncul kembali (salah satunya dipelopori oleh Abdullah ibn Saba’ dari Yaman), sehingga memicu timbulnya perpecahan dan firqah di kalangan umat Islam secara lebih serius. Kira-kira setelah 6 tahun pertama dari masa kepemimpinan Khalifah Utsman 7 8 Ketika Abu Bakar sedang sakit, merasa ajalnya telah dekat, ia pun merenung-renung lama tentang siapa yang akan jadi penggantinya. Akhirnya, ia pun memilih Umar. Itu di dalam hatinya. Akan tetapi, Abu Bakar pun ingin tahu bagaimana pendirian sahabat-sahabatnya. Dipanggilnya Abdurrahman ibn Auf. Sahabat ini menjawab, “Memang Umar lebih utama dari siapa pun. Tetapi ia keras.” Kata Abu Bakar, “Itulah yang tepat. Sebab, saya lemah terhadap seseorang, dan apabila saya keras kepada seseorang, ia malah membela.” Abu Bakar juga memberi alasan bahwa nanti kalau Umar memimpin, ia akan berubah karakternya. Kemudian Utsman ibn Affan dihubungi, dan ia menjawab, “Umar adalah orang yang baik meski ia keras, dan yang pasti tak seorang pun serupa dia.” Abu Bakar lalu meminta Abdurrahman ibn Auf dan juga Utsman untuk merahasiakan semua pembicaraan itu. Lalu dihubungilah Tolhah bin Ubaidillah. Kata Tolhah, “Sebaiknya tanyakan kepada orang-orang.” Pada hari berikutnya, setelah dibantu didudukkan oleh istrinya, Asma’ binti Umais, dan berada di pelukannya, Abu Bakar bertanya kepada orangorang, “Bagaimana pendapat kalian apabila aku menunjuk Umar sebagai Khalifah penggantiku? Ia bukan keluargaku dan aku telah berpikir sungguh-sungguh.” Para hadirin menjawab, “Sami’na wa atha’na”. Dalam al-Maghazy, Abu Abdillah Muhammad alWakidi mengatakan bahwa ia (Abu Bakar) mengundang Umar dan menyampaikan amanatnya, antara lain: “Jangan engkau mengangkat keluargamu demi memperbudak umat. Aku sendiri tidak mengangkat keluargaku” (Samsul Munir Amin, Percik Pemikiran Para Kyai: Pustaka Pesantren, 2009, hlm. 135). Ibn al-Arabi menjelaskan bahwasanya yang dimaksud yaitu dalam urusan kekhalifahan. Menjelang Khalifah Umar mati syahid di tangan Abu Lu’luah (seorang majusi), yang telah menusuknya tatkala Umar beliau sedang menunaikan ibadah shalat subuh bersama kaum muslimin. Khalifah berkata – setelah mengetahui siapa pembunuhnya, “Segala puji bagi Allah SWT yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang muslim yang akan menghujatku di sisi Allah SWT dengan sujud yang ia lakukan.” Dalam musyawarah itu, Khalifah menetapkan enam orang anggota, yaitu Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Thalhah ibn Ubaidillah, Zubair ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa’ad ibn Abi Waqqash (Ibn al-Arabi, Gejolak Api Permusuhan Syi’ah-Khawarij dan Orientalist terhadap Nabi SAW: al-Awashim min al-Qawashim fi Tahqiqi Muwatifi al-Shahabah ba’da Wafati al-Nabiy, [Penerbit Akbarmedia, 2010], hlm. 20). 8 ini, badai fitnah9 semakin mengguncang dengan hebat dan kuat, yang pada akhirnya mengantarkan pada terbunuhnya Khalifah Utsman oleh Sudan bin Hamran setelah dirobohkan terlebih dahulu oleh al-Ghafiki. 10 Kemudian jabatan khilafah berpindah ke tangan Ali ibn Abi Thalib. Namun, beragam kekacauan yang terjadi pada masa Khalifah Utsman sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Khalifah Ali. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, terjadi perang besar-besaran antara kelompok Khalifah Ali dengan kelompok Thalhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah. Perang ini dalam sejarah Islam selanjutnya dikenal dengan sebutan perang Jamal. Kemudian terjadi perang Shiffin dengan kelompok Muawiyah ibn Abi Sufyan (Gubernur Syam pada masa khalifah Umar dan Utsman). Ketika pasukan Muawiyah semakin terdesak sedangkan di pihak lain pasukan Khalifah Ali hampir mendapatkan kemenangannya, Amr ibn ‘Ash yang ditunjuk Muawiyah menawarkan gencatan senjata dan perundingan (tahkim). Abu Musa al-Asy’ari ditunjuk Khalifah Ali untuk menyelesaikan masalah ini melalui perundingan tersebut. Namun, sebagian kelompok Khalifah Ali tidak dapat menerima keputusan tersebut dan akhirnya memutuskan keluar dari kelompok sang Ibnul ‘Arabi (Ibid, hlm. 31) menceritakan terjadinya fitnah atas Khalifah Utsman dan keluarganya, di antaranya: (a) Dia memukul Ammar hingga robek ususnya, (b) Memukul Ibnu Mas’ud hingga tulang rusuknya patah, dan bahwa Utsman tidak mau memberi haknya (dalam penulisan mushaf al-Qur’an), (c) Melakukan bid’ah dengan menghimpun al-Qur’an dan menulisnya serta membakar mushaf-mushaf yang lain, (d), menentukan batas wilayah terlarang , (e) Mengusir Abu Dzar ke Rabdzah, (f) Mengusir Abu Darda’ dari Syam, (g) Mengembalikan Al-Hakam setelah Rasulullah SAW mendeportasinya, (h) Menggugurkan shalat qashar ketika safar (dalam perjalanan), (i) Mengangkat Mu’awiyah sebagai penguasa, (j) Mengangkat Abdullah ibn Amir ibn Kuraiz sebagai penguasa, (k) Mengangkat Marwan sebagai penguasa, (l) Mengangkat Walid al-Uqbah sebagai penguasa. Padahal ia orang fasik dan tidak kompeten menjadi seorang pemimpin, (m) Memberi Marwan seperlima dari hasil rampasan perang Afrika, (n) Dahulu Umar memukul dengan tongkat kecil yang dibawa seorang raja. Sedangkan Utsman memukul dengan tongkat besar, (o) Melampui derajat Rasulullah SAW, padahal Abu Bakar dan Umar tidak berani melangkahinya, (p) Tidak ikut dalam perang Badar, kalah dalam perang Uhud, dan tidak dating ke Bai’atur Ridhwan, (q) Tidak menghukum mati Ubaidillah ibn Umar sebagai balasan atas Hurmuzan (orang yang memberikan pisau kepada Abu Lu’luah dan mendorongnya untuk memusuhi Umar hingga membunuhnya), (r) Mengirimkan surat bersama budaknya di atas untanya kepada Ibnu Sarh untuk membunuh orang-orang tersebut dalam surat itu. Dalam semua tuduhan/fitnah atas Utsman ini, Ibnul ‘Arabi mengatakan bahwa semua tuduhan itu batil (bohong), baik dari segi sanad (riwayat) atau matan (teks). Keterangan selengkapnya mengenai bantahan Ibnul ‘Arabi tersebut, bisa dibaca lebih lanjut pada buku berjudul “Gejolak Api Permusuhan Syi’ah-Khawarij dan Orientalist terhadap Nabi SAW” yang merupakan terjemahan dari kitabnya “al-Awashim min al-Qawashim fi Tahqiqi Muwatifi ash-Shahabah ba’da Wafati an-Nabiy”. Adapun bantahan lain mengenai fitnah atas Khalifah Utsman ini dijelaskan oleh Muhammad Idrus Ramli dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Sejarah Ahlussunah wal-Jama’ah” (Surabaya: Penerbit Khalista, 2011, hlm. 26-47). 10 Samsul Munir Amin, Percik Pemikiran Para Kyai, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 138. 9 9 Khalifah. Mereka inilah yang kemudian dinamakan kelompok Khawarij11. Kelompok Khawarij (seperti Asy’ari ibn Qais, Mas’ud ibn Fudali al-Tamimi, Zaid ibn Hushain al-Thai) dengan tegas menolak tunduk di bawah kepemimpinan Khalifah Ali, sehingga timbullah perselisihan yang diikuti pertempuran antara kedua belah pihak. Sebagai reaksi dari kelompok Khawarij di atas, maka pada masa Khalifah Ali muncul juga kelompok pimpinan Abdullah ibn Saba’. Kelompok ini sangat fanatik terhadap Khalifah Ali dan bahkan berani mengkultuskan Ali sebagai Tuhan. Mereka yang fanatik dan berlebihan terhadap Khalifah Ali ini dinamakan kelompok Rafidhah (Syi’ah)12. Setelah Khalifah Ali ibn Thalib terbunuh, perpecahan di atas berkembang menjadi dua bentuk, yaitu perpecahan dalam masalah kepemimpinan (imamah) dan kedua perpecahan dalam akidah. Perpecahan dalam masalah kepemimpinan yang paling menonjol dimulai dari pertikaian antara kelompok Khawarij dengan Syi’ah yang masingmasing saling mengklaim diri mereka paling benar. Kemudian di tengah-tengah konflik yang tidak berkesudahan ini, muncul satu kelompok lagi yang merasakan kejenuhan sehingga mereka enggan mempersoalkan konflik yang sedang terjadi. Kelompok baru ini memutuskan untuk tidak memihak kelompok yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Kelompok ini berpandangan bahwasanya ketika kita tidak dapat menentukan mana pihak yang salah dan mana yang benar, maka kita harus mengembalikan persoalan itu kepada Allah 11 12 Dalam kitabnya Tabsith al-Aqaid al-Islamiyah, Hasan Ayyub menyatakan bahwa aliran Khawarij pada awalnya memerankan politik yang radikal. Hanya saja, persoalan politik ini mengalami dinamika dan berubah menjadi persoalan ideologis. Kelompok Khawarij berpandangan bahwa seorang khalifah harus dipilih secara bebas oleh kaum muslimin. Seorang khalifah tidak harus seorang yang berasal dari kalangan suku Quraisy saja. Khalifah tidak boleh mengundurkan diri atau melakukan atau melakukan tahkim. Mereka mendefinisikan iman dengan keyakinan yang disertai pengamalan, sehingga keyakinan tidaklah berguna ketika tidak disertai pengamalan. Oleh karena itu, kelompok Khawarij mengkafirkan perilaku dosa. Berangkat dari pandangan politik mereka yang radikal ini, mereka berpandangan bahwa Utsman, Ali, Aisyah, Thalhah, Zubair, Muawiyah dan pengikut mereka di perang Jamal dan Shiffin adalah kafir. Mereka hanya mengakui Khalifah Abu Bakar dan Umar (Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah, [Surabaya: Penerbit Khalista, 2011], hlm. 65). Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari menyatakan ciri-ciri kelompok Rafidhah ialah menghujat Khalifah Abu Bakar dan Umar, termasuk para sahabat yang membela mereka. Sebaliknya, mereka sangat berlebihan mengagung-agungkan Khalifah Ali dan para kerabatnya dari Bani Hasyim. Beliau mengutip pandangan Sayid Muhammad bahwa kelompok Rafidhah yang berlebihan di atas pada hakikatnya sudah kufur dan zindiq (mengingkari Allah dan Rasulullah). Beliau menyebutkan sebuah hadits riwayat Abdullah ibn Mighfal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Takutlah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah untuk mencaci-maki para sahabatku. Janganlah engkau menimpakan kesalahan pada mereka…..Barang siapa menyakiti mereka, maka sungguh ia juga menyakitiku. Barang siapa menyakitiku maka sungguh ia menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah maka Allah akan mendatangkan siksa padanya” (K.H. Hasyim Asy’ari, Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah: fi Hadits al Mawta wa Asyrath al-Sa’ah wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid’ah, [Jombang: Maktabah Turats al-Islami Tebuireng, 1418 H], hlm.10-11). 10 SWT. Dengan pandangan ini, kelompok tersebut akhirnya dinamakan kelompok Murji’ah (kelompok yang mengembalikan persoalan kepada Allah SWT). Seiring berjalannya waktu, kelompok Murji’ah kemudian mengembangkan pandangan mereka hingga memasuki soal-soal keagamaan, seperti mendefinisikan iman dengan mengetahui Allah SWT dan rasul-Nya. Kajian mereka kemudian semakin ekstrem dengan berpandangan bahwa iman itu hanyalah keyakinan saja, sedangkan amaliah tidak memiliki peran sama sekali dalam iman. Mereka mengeluarkan pernyataan yang sangat populer “la tadhurru ma’a al-iman ma’shiyatun kama la tanfa’u ma’a al-kufri tha’atun” (kemaksiatan tidak akan membahayakan seseorang selama ia masih beriman sebagaimana amal baik tidak akan bermanfaat selama dia masih kafir). Aliran Murji’ah ini dalam perjalanannya mendapatkan perlindungan dari para penguasa Bani Umayyah dan Abbasiyah karena sikap pengikutnya yang netral (tidak anti dan tidak pro penguasa) dianggap menguntungkan pihak penguasa. Dengan munculnya kelompok Murji’ah di atas, maka semakin nyatalah perpecahan dalam masalah akidah. Terbukti setelah itu banyak aliran-aliran baru mulai bermunculan. Aliran-aliran tersebut antara lain seperti: Jahmiyah13 yang dipelopori oleh Jahm ibn Shafwan dan Dhirariyah14 yang dipimpin oleh 13 14 Jahmiyah merupakan nama madzhab teologi (kalam) Islam yang dinisbatkan kepada nama pendirinya, Jahm ibn Shafwan (124 H). Al-Syahrastani memasukkan aliran ini ke dalam aliran Jabariyah (Jabariah: secara bahasa berarti paksaan/terpaksa). Aliran ini (Jahmiyah) tersebar di daerah Tirmiz, dan pendirinya (Jahm) mati dibunuh Muslim ibn Ahwas alMazini di akhir masa Khalifah Malik ibn Marwan (Bani Umayyah). Beberapa inti ajaran Jahmiyah antara lain sebagai berikut: a) Makhluk tidak boleh memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah. Apabila makhluk bersifat sama dengan Khalik (Allah), maka akan terjadi tasybih (penyerupaan hamba kepada Khalik) dan ini adalah mustahil. Secara khusus, aliran ini menolak keadaan Allah Maha Hidup dan Maha Mengetahui, namun mengakui keadaan Allah Maha Kuasa. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Kuasa itulah yang berbuat dan menciptakan, sehingga semua perbuatan makhluk itu hanya majbur (terpaksa/di luar kemauan dan kemampuannya). Semuanya sudah digariskan secara rinci oleh Allah SWT sejak zaman azali. Makhluk tinggal menerima apa adanya di dalam pengendalian Allah; b) Manusia akan kekal, baik dalam surga maupun neraka berdasarkan takwil mereka pada Q.S. Hud: 108; c) Siapa yang sudah memiliki pengetahuan dan ma’rifah (pengenalan) kepada Allah kemudian ia mengingkariNya dengan lisannya, maka ia tidak dapat dikatakan kafir. Untuk mendukung pendapat di atas, aliran ini mengungkapkan bahwa iman tidak terdiri dari tashdiq (pembenaran atas keesaan Allah) dan perbuatan. Selain itu, dikatakan juga bahwa iman bentuknya sama, baik iman para nabi maupun iman umatnya (iman tidak ada tingkatan-tingkatannya) (Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal: Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, [Surabaya: PT. Bina Ilmu], hlm. 71). Dhirariyah merupakan nama madzhab teologi Islam yang dinisbatkan kepada nama pendirinya, Dhirar ibn ‘Amr dan Hafshul al-Fard. al-Syahrastani memasukkan aliran ini ke dalam aliran Jabariyah karena aliran ini juga memandang bahwasanya perbuatan manusia sudah ditentukan Allah (manusia tidak berkuasa apa-apa atas perbuatan yang ia lakukan). Beberapa ajaran aliran ini antara lain sebagai berikut: a) Allah memiliki sifat, di antaranya yaitu Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Adapun Zat Allah tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah sendiri yang mengetahui; b) Manusia memiliki indera keenam 11 Dhirar ibn Amr al-Kufi (keduanya termasuk aliran Jabariyah), Qadariyah15 di bawah pimpinan Ma’bad al-Juhani, Ghailan al-Dimasyqi, dan Ja’ad ibn Dirham, Mu’tazilah16 yang dipelopori oleh Washil ibn Atha’ al-Ghazzal, Najjariyah17 di yang akan digunakannya untuk melihat Allah pada hari pembalasan segala amal kebajikan di dalam surga; c) Perbuatan manusia adalah ciptaan Allah pada hakikatnya, namun manusia yang mempergunakannya, sehingga memungkinkan satu perbuatan dari dua pelaku (perbuatan Allah = hakiki, perbuatan manusia = majazi); d) Sumber ajaran Islam sesudah masa Rasulullah SAW hanya ijma’ dan bahwasanya qiraat Ibn Mas’ud dan Ubay ibn Ka’ab harus ditolak karena tidak pernah diturunkan Allah; e) Sebelum wahyu diturunkan Allah melalui rasulNya, akal manusia tidak wajib dalam ketentuan syara’ (agama); f) Dalam masalah imamah (kepemimpinan), boleh mengangkat seorang pemimpin dari suku selain Quraisy, namun apabila ada keturunan Rasulullah yang lebih pantas, maka diutamakan keturunan Rasulullah dengan alasan bahwa jumlah keturunan itu sedikit (Ibid, hlm. 74-76). 15 Secara harfiah, Qadariyah berarti kuasa. Ibn al-Ibri sebagaimana dikutip Hitti menyatakan bahwa Qadariyah merupakan madzhab filsafat Islam paling awal, dan besarnya pengaruh pemikiran mereka bisa disimpulkan dari kenyataan bahwa dua Khalifah Umayyah (Muawiyah II dan Yazid III) merupakan pengikut Qadariyah (History of The Arabs: Penerbit PT Serambi Ilmu Semesta, 2006, hlm. 306). Ajaran Qadariyah mengenai perbuatan bebas manusia di atas bermula dari penafsiran firman Allah SWT (Q.S. al-Ra’du: 11) yang artinya, “Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan apa saja (yang ada) pada suatu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka tatkala Allah SWT menghendaki pada kaum itu bencana/petaka, maka tak ada (siapapun) yang dapat menolaknya. Dan tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” Dengan ayat ini, aliran Qadariyah mengajarkan bahwa Allah tidak merubah keadaan suatu kaum (seseorang) dari yang buruk (miskin, bodoh, lemah) hingga kaum itu mau berusaha (merubah). Dengan demikian, aliran ini sebenarnya mencoba menawarkan sebuah pemikiran bahwasanya masalah miskin, bodoh, lemah secara teknis diserahkan kepada manusia itu sendiri (tidak ada campur tangan Allah). Lebih jauh aliran ini berpendapat bahwa semua perbuatan manusia adalah karena kehendaknya sendiri, bebas dari kehendak Allah. Manusia dengan kemampuan dan kemauannya dapat berbuat baik dan buruk tanpa ada kekuatan dan kekuasaan lain yang memaksanya. 16 Mu’tazilah adalah sebuah aliran teologi Islam yang muncul di Bashrah pada abad ke2Hijriyah/ ke-8 Masehi. Nama Mu’tazilah berasal dari kata i’tazala yang secara harfiah berarti memisahkan diri, yaitu keluarnya seorang bernama Washil ibn Atha’ dari majlis pengajian gurunya Hasan al-Bashri. Adapun nama lain yang disebutkan untuk aliran ini adalah Mu’tathilah (berasal dari kata atthala = mengosongkan) karena golongan ini tidak mengakui sifat-sifat Allah. Aliran Mu’tazilah mengalami masa kejayaannya pada masa Dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah al-Ma’mun (813-833 M) (Hitti, 2006: 307). Aliran ini mengajarkan tentang kebebasan berfikir dan kebebasan berkehendak. Selain itu, aliran ini juga menolak terhadap kesatuan antara Allah dan sifat-sifatNya (seperti Berkuasa, Bijaksana, dan Maha Hidup) dengan argumen bahwa konsep semacam itu akan merusak keesaan Allah. Oleh karena itu, julukan yang sangat disukai kaum Mu’tazilah adalah Ahl al-Adl wa at-Tauhid (pendukung keadilan dan kekuasaan) (Hitti, 2006: 307). Beberapa ajaran Mu’tazilah ini antara lain, yaitu: a) Menolak sifat-sifat Allah seperti Ilmu, Qudrat, Iradat, dan Hayat. Hal ini dikarenakan apabila Allah bersifat, dan sifat itu baru (huduts), maka Allah bukan Dzat yang Qadim (tidak berpermulaan), sedangkan apabila sifat itu Qadim, maka ada sesuatu yang menyamai Allah. Begitu juga al-Qur’an itu apabila bukan makhluk tapi qadim, maka ada sesuatu yang menyamai Allah. Prinsip yang demikian oleh kaum Mu’tazilah dinamakan prinsip al-Tauhid (Allah Maha 12 17 Esa dan tidak bersifat). Menurut al-Syahrastani (hlm. 40), pendapat seperti ini merupakan hasil pengaruh dari pemikiran-pemikiran filsafat (Madzhab Elea, Permeneides: catatan penulis). Agaknya, kaum Mu’tazilah menjumpai dua kesimpulan tentang sifat yang samasama rancu/absurd, sehingga mereka memilih pertimbangan akal (rasio), yaitu sifat-sifat yang telah disebutkan itu tidak lain adalah Dzat Allah sendiri. Penyebutan sifat hanyalah ungkapan bahasa (‘itibariah) semata yang tidak berimplikasi pada dualitas sifat-dzat; b) Dalam hal takdir, kaum Mu’tazilah sependapat dengan Ma’bad al-Juhani, Ghailan alDimasyqi. Menurut Mu’tazilah, Allah adalah Hakim yang adil. Karena keadilan-Nya, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menentukan baik dan buruk, sehingga manusia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila tidak demikian – sedangkan Allah memberikan taklif (beban aturan syari’ah) kepada manusia, maka Allah tidak adil. Bagi mereka, siapa yang menolak pendapat ini sama artinya menolak sesuatu yang diterima menurut akal yang definitif (prinsip al-adl/keadilan); c) al-Manzilah baina al-Manzilatain, artinya adanya tempat di antara dua tempat surga dan neraka. Tempat ini diperuntukkan bagi seorang Mukmin yang berbuat dosa besar dan belum bertaubat sebelum mati, serta anak-anak kecil yang belum pernah berbuat kebaikan. Kaitannya dengan masalah ini, kaum Mu’tazilah berpendapat bahwa Iman terdiri dari unsur-unsur kebaikan. Apabila semuanya lengkap dinamakan seorang Mukmin yang terpuji, sedangkan orang munafik yang unsur imannya kurang, maka ia bukanlah mukmin yang terpuji tapi juga tidak dapat dikatakan orang yang celaka dan kafir; d) Tentang orang yang terlibat dalam peperangan Jamal dan Shiffin, kaum Mu’tazilah berpendapat salah satu kelompok memang bersalah. Misalnya, kasus saling mengutuk (li’an) antara Khalifah Ali, Zubair, dan Thalhah maka salah satu kelompok – entah kelompok siapa – jelas berbuat fasik. Karena tidak diketahui dengan jelas siapa yang bersalah, maka minimal hukuman dikenakan kepada kedua kelompok. Sebenarnya, pendiri aliran ini al Husain ibn Muhammad an-Najjar (230 H) termasuk tokoh Mu’tazilah yang banyak menggunakan rasio. Hanya saja al-Syahrastani memasukkan kelompok ini ke dalam aliran Jabariyah karena ajarannya mengenai tawallud (perbuatan tidak langsung/tidak mempunyai pelaku) pada perbuatan makhluk. Beberapa ajaran Najariyah yaitu: a) Allah Maha Berkehendak dengan dzat-Nya, juga Allah mengetahui dengan dzat-Nya. Karena itu dapat disimpulkan berlaku taalluq (keterkaitan) secara menyeluruh. Sehingga dikatakan Allah Maha Berkehendak berarti Allah tidak dipaksa dan tidak terpaksa dan Allah menciptakan semua perbuatan makhluk, yang baik dan yang buruk. Dalam hal kasab dan istitha’ah (usaha dan kemampuan manusia) Najariyah sependapat dengan al-Asy’ari, yaitu bahwasanya manusia sebatas merencanakan; b) Mengenai ru’yah (melihat Allah di akhirat), Najariyah menolak kemungkinan ru’yah ini kecuali jika Allah memindahkan pengenalan (makrifat) hati ke kepala; c) Kalam Allah adalah makhluk apabila ditulis menjadi huruf, dan lebih aneh lagi Kalam Allah tersebut bukan dzat dan bukan pula sifat sehingga setiap yang bukan dzat dan bukan sifat Allah adalah makhluk. Meskipun Najariyah mengatakan Kalam Allah sebagai makhluk, tapi yang mengatakan al-Qur’an makhluk adalah kafir; d) Sebelum diturunkan wahyu, maka wajib mengenal Allah dengan akal sehingga bagi yang tidak menggunakan akalnya maka akan dikenai siksaNya; e) Iman hanya terdiri dari tashdiq (pembenaran dengan hati), karena itu seorang mukmin yang meninggal setelah meninggal tanpa sempat bertobat, maka ia dihukum dalam neraka. Namun, setelah hukuman tersebut dituntaskan secara adil, ia akan dikeluarkan juga (tidak seperti orang kafir yang kekal dalam neraka). Pada intinya, aliran ini termasuk ke dalam Jabariyah karena pendapatnya yang menyatakan bahwa Allah berkehendak terhadap segala yang diketahui seperti baik dan buruk, iman dan kafir, taat dan maksiyat. Berbeda dengan Mu’tazilah yang dengan tegas menolak pandangan demikian (Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal: Aliran- 13 bawah pimpinan Husain ibn Muhammad al-Najjar, Karramiyah18 di bawah pimpinan Muhammad ibn Karram al-Sijistani, Bayaniyah19 di bawah pimpinan Bayyan ibn Sam’an al-Tamimi, Mughiriyah20 di bawah pimpinan Mughirah ibn aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, [Surabaya: PT. Bina Ilmu], hlm. 71). Al-Syahrastani (hlm. 97) menyebutkan bahwa aliran Karamiyah ini pada dasarnya termasuk ke dalam kelompok Shifatiyah karena mereka mengakui bahwa Allah memiliki sifat, namun mereka terlalu berlebihan yang akhirnya menyamakan Allah dengan makhluk (tasybih) dan mengakui Allah mempunyai anggota tubuh seperti manusia (tajsim). Berikut ajaran-ajaran Karamiyah sebagaimana dikemukakan oleh pendirinya Abu Abdullah Muhammad ibn Karam, yaitu: a) Allah bersemayam di atas Arasy, Dia berada di atas semua benda (jauhar). Allah bersentuhan dengan Arasy dari arah atas, Dia dapat berpindah-pindah, bergerak, turun; b) Allah memiliki tangan, muka, dan sifat-sifat lain yang ada pada dzat-Nya, namun menurut aliran ini tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia, muka Allah tidak sama dengan makhluk-Nya. Dalam hal ini, Ibn Haitsam sebagaimana dikutip al-Syahrastani (hlm. 100) menyatakan bahwa tindakan tasybih mereka kepada Allah seperti mempunyai bentuk rupa (wajah), rongga, lari, dapat dijabat dengan tangan, dapat dipeluk dan sebagainya tidak sama dengan apa yang diyakini kelompok Qaramithah. Karamiyah tidak membenarkan penyerupaan semua itu karena tidak sesuai dengan arti dan makna anggota tubuh seperti Arasy sebagai tempat duduk dan Allah dating ke suatu tempat. Karamiyah hanya berpendapat sesuai dengan yang disebutkan al-Qur’an tanpa menentukan cara dan kesamaannya dengan makhluk. Mereka dengan tegas menyatakan apa yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadits tidak diakuinya sebagaimana tindakan mempersamakan dan personifikasi; c) Kebaikan dan keburukan dari Allah. Allah pula yang menimpakan kebaikan dan keburukan kepada makhluk-Nya, selain itu Allah pula yang menciptakan kekuatan yang terbatas pada makhluk (kasab). Terbatas maksudnya ialah hanya untuk mencapai hikmah ciptaan-Nya. Dengan adanya kasab ini, makhluk dibebani (taklif) yang akan mendatangkan pahala dan dosa; d) Akal dapat menentukan baik dan buruk, hanya saja Karamiyah menolak pendapat Mu’tazilah bahwa wajib bagi Allah mewujudkan kebaikan dan yang lebih baik; e) Sahnya iman hanya dengan tuturan lisan, sementara tashdiq hati dan perbuatan bukanlah rukun iman. Seorang mukmin yang benar ialah yang melaksanakan hukum lahiriah dan taklif serta hukum-hukum akhirat dan ketentuannya; f) Imamah ditentukan berdasarkan kesepakatan umat, bukan ditunjuk dan bukan pula ditetapkan nash. Lebih jauh lagi Karamiyah memperbolehkan tindakan membaiat dua orang imam pada dua daerah yang berbeda, seperti mengakui Muawiyah sebagai pemimpin yang sah di Syam dengan adanya kesepakatan sahabat di sana, dan pengakuan terhadap Khalifah Ali di Madinah dan Irak dengan adanya kesepakatan para sahabatnya (Ibid). 19 Kelompok Bayaniyah termasuk kelompok Syi’ah ekstrem yang mengakui Ali ibn Abi Thalib adalah Tuhan (al-Syahrastani: 129). Menurut aliran ini, Tuhan telah masuk ke dalam tubuh Ali dan bersatu dengan Ali, karenanya Ali mengetahui hal-hal yang ghaib. Pendirinya, Bayan ibn Sam’an al-Tamimi mengaku bahwa dirinya adalah bagian dari roh Tuhan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui inkarnasi (tanasukh), sehingga ia berhak menjadi imam dan khalifah. Selanjutnya, ia (Bayan) mengatakan bahwa tubuh Adam mengandung ruh Tuhan, maka Allah memerintahkan agar para malaikat bersujud kepada Adam. Selain itu, ia juga mengatakan Tuhan yang disembah itu berbentuk manusia yang mempunyai anggota tubuh, semua bagian tubuh Tuhan akan binasa kecuali wajah-Nya. Hal ini didasarkan atas takwil mereka pada firman Allah (Q.S. al-Qashash: 88) yang artinya, “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah-Nya” (Ibid). 20 Kelompok Mughiriyah termasuk aliran syi’ah al-Ghaliyah (ekstrem). Pendirinya, Mughirah ibn Sa’id al-Jilli mengatakan imamah sesudah Muhammad ibn Ali ibn Husain adalah 18 14 Sa’id al-Jilli, Manshuriyah21 di bawah pimpinan Abu Manshur al-Ijli, aliran-aliran lain seperti Ibahiyun22, Tanasukhiyah23, Hululiyah24 dan Ittihadiyah25, dan masih Muhammad ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan dan dia berada di luar kota Madinah dan haidup sampai sekarang. Selanjutnya, ia (Mughirah) mengaku dirinya menjadi Nabi yang menghalalkan yang haram, melebihkan Ali dariyang lain, dan menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Beberapa ajaran yang disampaikan Mughirah antara lain sebagai berikut: a) Menurutnya, Allah mempunyai bentuk, terdiri dari tubuh dan mempunyai anggota tubuh seperti huruf alphabet. Bentuknya seperti seorang lelaki yang terdiri dari cahaya, di atas kepalanya mahkota yang terdiri dari cahaya, mempunyai hati yang keluar darinya hikmah; b) Ketika Allah berkehendak menciptakan alam ini, Ia menyebut Asmau al-A’dham (nama-nama yang luhur), maka beterbangan dan berjatuhanlah ke atas kepalanya mahkota. Mughirah menafsirkan firman Allah (Q.S. al-A’la: 1-2) yang artinya, “Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Paling Tinggi. Yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya).”; c) Allah menciptakan makhluknya dari air keringat-Nya. Air keringat itu berkumpul menjadi dua lautan, yang airnya keruh asin dan yang airnya tawar jernih. Orang mukmin diciptakan dari air laut yang tawar jernih, sedangkan orang kafir diciptakan dari air laut yang keruh asin; d) Bayang-bayang yang diciptakan Allah pertama kali ialah bayang-bayang Muhammad kemudian bayang-bayang Ali, baru setelah itu diciptakanlah bayang-bayang seluruh makhluk. Karenanya, setelah Muhammad wafat, Ali yang paling pantas dan berhak untuk menggantikannya. Mughirah tidak menaruh respek pada Khalifah Abu Bakar dan Umar karena dianggapnya sebagai orang dzalim yang merebut khilafah dari tangan Ali. Untuk mendukung pendapatnya demikian, ia menafsirkan firman Allah (Q.S. al-Ahzab: 72) yang artinya, “…dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim lagi amat bodoh.” Menurutnya lagi, firman Allah (Q.S. al-Hasyr: 16) diturunkan berkaitan dengan perbuatan Umar, di mana ayat itu berbunyi, “(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) setan, ketika ia berkata kepada manusia, ‘kafirlah kamu’. Maka tatkala manusia telah kafir ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu….”; e) Mengakui imamah Abu Ja’far ibn Ali, dan bahkan memujimujinya sampai-sampai mengatakannya sebagai Tuhan. Setelah mati, Abu Ja’far akan hidup kembali. Jibril dan Mikail akan membaiatnya di Multazam. Menurutnya juga, Abu Ja’far dapat menghidupkan orang mati (Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa alNihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, [Surabaya: PT. Bina Ilmu]). 21 Awalnya, Manshuriyah yang berasal dari ajaran Abu Manshur al-Ajali menyatakan kesetiaannya pada Abu Ja’far Muhammad ibn Ali al-Baqir, tapi hal itu ditolak oleh alBaqir. Ketika al-Baqir meninggal, imamah berpindah kepada Abu Manshur dengan dukungan dari Bani Kindah di Kufah. Ajaran ini bertahan hingga pada akhirnya Abu Manshur ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam ibn Abd al-Malik. Beberapa ajaran Manshuriyah antara lain sebagai berikut: a) Pendapatnya bahwa Ali ibn Abi Thalib adalah al-Kusuf (gerhana) yang jatuh dari langit. Dikatakan ‘gerhana’ karena pada saat menjadi imam, Ali dimi’rajkan ke langit dan melihat Tuhan. Tuhan mengusap kepalanya dengan tangan-Nya seraya berfirman, “Anakku, turunlah dan sampaikanlah dari-Ku. Kemudian, diturunkanlah ke bumi karena itu dinamakan gerhana jatuh dari langit; b) Kerasulan tidak pernah terputus. Surga adalah nama orang (imam) yang memerintahkan untuk menaatinya, sedangkan neraka adalah nama bagi orang yang memerintahkan untuk memusuhi imam; c) Pertama kali yang diciptakan Allah adalah Isa ibn Maryam dan sesudah itu diciptakanlah Ali ibn Abi Thalib (Ibid). 22 Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari menjelaskan Ibahiyun sebagai kelompok yang berpendapat bahwa ketika seorang hamba mencapai puncak kecintaan, sementara hatinya suci dari unsur kelalaian dan dipenuhi keimanan, maka telah gugur darinya segala perintah dan larangan agama. Karenanya Allah tidak memasukkannya ke dalam neraka. Sebagian dari 15 banyak aliran-aliran lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akar persoalan yang melatarbelakangi timbulnya firqah-firqah di kalangan umat Islam adalah 23 24 kelompok ini mengatakan, “telah gugur segala kewajiban ibadah lahiriah dan sebagai gantinya yaitu ibadah berupa tafakkur dan memperbaiki akhlak batin”. Sayid Muhammad dalam Syarah Kitab Ihya’ menjelaskan ajaran Ibahiyun ini sesat dan dipenuhi unsur-unsur zindiq (kekufuran) karena mengabaikan ilmu syari’ah (K.H. Hasyim Asy’ari, Risalah Ahl al-sunnah wa al-Jama’ah: fi hadits al Mawta wa asyrath al-Sa’ah wa Bayan Mafhum alSunnah wa al-Bid’ah, [Jombang: Maktabah Turats al-Islami Tebuireng, 1418 H], hlm.1011), hlm. 11). Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari (ibid, hlm. 12) menyatakan ciri utama aliran Tanasukhiyah yaitu pendapatnya mengenai reinkarnasi ruh dan perpindahannya dari satu badan ke badan lain (tanasukh). Al-Syahrastani dalam al-Milal wa al-Nihal (hlm. 234) menyebutkan pendapat aliran ini, yaitu bahwasanya apa yang dialami semasa hidup ini seperti rasa tenang, capek, penat adalah berasal dari tubuh sebelumnya, karena tubuh yang baru menjadi bagian dari tubuh dahulu. Apa yang terjadi dalam diri manusia mungkin merupakan balasan atas perbuatannya sendiri atau perbuatan orang lain, surga dan neraka berada di tubuh ini. Dengan demikian dapat disimpulkan, yang dimaksud tanasukh adalah kelahiran berulang kali atau periodisasi dan proses yang terus-menerus. Apa yang ada pada suatu periode akan lahir kembali pada periode berikutnya. Siksa (ta’dzib) dan ganjaran (tan’im) terjadi di dunia ini menurut kadar kebersihan dan kekeruhan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Pendapat tanasukh ini oleh Syihab al-Khafaji sebagaimana dikutip Hasyim Asy’ari (hlm. 12) dikatakan telah menyimpang dari syari’ah karena telah mendustakan sendi-sendi keimanan pada Allah, rasul, dan kitab-kitab-Nya. Dalam masalah Hululiyah dan Ittihadiyah ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari (hlm. 12) menunjuk secara khusus pada kelompok tasawuf yang diliputi kebodohan dari pengetahuan syari’ah. Kelompok ini mengatakan bahwa Allah adalah wujud al-muthlaq, sedangkan makhluk sama sekali tidak memiliki sifat wujud ini. Selanjutnya, apabila dikatakan ‘manusia maujud (ada)’ maka yang dimaksud ialah sifat wujud itu berta’alluq (berkaitan) dengan wujud al-muthlaq (Allah SWT). Dalam hal ini, Syekh al-‘Allamah Amir sebagaimana dikutip Hasyim Asy’ari menghukuminya sebagai perbuatan kufur sharih/nyata (karena ungkapan ini mengandung makna penuhanan pada diri manusia: catatan penulis). Selain kedua aliran di atas, Hadratus Syekh menyebutkan aliran lain yang membahayakan akidah seorang mukmin, yaitu aliran wahdatul wujud dengan pernyataan populernya “Ma fi al-Jubbah illa Allah” (Di balik jubah ini tiada maujud apapun melainkan wujud Allah). Pada dasarnya, masalah yang terdapat pada ajaran hulul, ittihad maupun wahdatul wujud ialah pandanganya tentang kesatuan manusia dengan Allah yang dianggap melampaui batas syara’. Dalam hal ini, Hadratus Syekh mengutip pandangan kitab Lawaqih al-Anwar bahwa irfan (makrifat) yang sempurna terjadi manakala terjadi syuhud (persaksian hati) seorang hamba bersama Rabb-nya, sehingga apa yang dikatakan hulul, ittihad, dan wahdah di atas berlaku dalam batasan kesatuan antara syuhud (kesaksian mata hati) hamba bersama Rabb-nya, bukan wujudnya. Jika dalam suatu kesempatan dijumpai seorang arif (ahli makrifat) mengingkari adanya syuhud sebagaimana dijelaskan di atas, maka menurut kaidah yang benar ialah ia tidak bisa dikatakan sebagai seorang arif. Sebenarnya, orang yang menafikan syuhud itu berada dalam kondisi kasuistik (shahibu al-hal), yang berarti dalam kondisi mabuk ilahi/jadzab (keluar dari batas kesadaran manusiawi), dan menurut kaidahnya orang yang jadzab tidak dapat disebut ahlu tahqiq, yaitu segala ucapan dan perilakunya tidak dapat dijadikan sebagai dalil/pijakan syara’ (ibid, hlm. 12). 25 16 masalah Khilafah atau masalah politik. Dari akar permasalahan ini, kemudian timbul usaha membentengi ajaran dengan rumusan-rumusan hujjah (argumentasi). Maka lahirlah firqah-firqah yang selanjutnya ditopang madzhabmadzhab, baik di bidang akidah, fikih, maupun akhlak/tasawuf. Adapun salah satu firqah yang belakangan muncul ialah aliran Wahabi26 yang dirintis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi (1115-1206 H/1703-1791 M). Aliran Wahabi ini mengadopsi ajaran-ajaran Ibn Taimiyah al-Harrani (661-728 H/1263-1328 M) yang banyak di antaranya keluar dari mainstream, seperti larangan ziarah ke makam Nabi SAW, larangan tawassul dengan para nabi dan wali, dan lain-lain. Di samping itu, aliran ini juga mengadopsi radikalisme aliran Khawarij pada masa awal Islam. Hakikat dan Pengertian Ahlussunah wal-Jama’ah Pada hakikatnya, Ahlussunnah wal-Jama’ah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: “Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, yang selamat dari padanya hanya satu dan yang lainnya binasa. Nabi SAW ditanya: siapa yang selamat? Nabi SAW menjawab: Ahlussunnah wal-Jama’ah. Nabi SAW ditanya (lagi): apa itu Ahlussunnah walJama’ah? Nabi SAW menjawab: apa yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku”.27 Hadis inilah yang kemudian dijadikan pegangan banyak kalangan 26 Ajaran-ajaran Wahhabi dapat disimpulkan ke dalam dua bidang, bidang tauhid dan bidang ibadah. Dalam bidang tauhid, Wahhabiyah berpendirian sebagai berikut: a) Penyembahan dan permohonan kepada selain Allah adalah salah dan barang siapa yang berbuat demikian wajib dibunuh; b) Orang yang mencari ampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan orang-orang saleh termasuk golongan musyrikin; c) Termasuk kufur adalah memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas al-Qur’an dan as-Sunnah, yaitu ilmu yang bersumber kepada akal pikiran semata; d) Termasuk kufur adalah mengingkari qadar dalam semua perbuatan dan penafsiran al-Qur’an dengan jalan takwil; e) Memberikan tambahan kata ‘sayidina’ kepada nabi pada waktu salat dihukumi syirik; f) Larangan memakai tasbih sebagai alat penghitung pada saat melakukan dzikir; g) Sumber syari’ah Islam dalam hal halal-haram hanyalah al-Qur’an dan as-Sunnah, sehingga perkataan para ulama tentang halal-haram selama tidak didasarkan atas kedua sumber itu tidak dapat dijadikan pegangan; h) pintu ijtihad tetap terbuka dan siapapun dapat melakukannya. Adapun masalah ibadah yang dipandang bid’ah dan harus diberantas oleh aliran Wahhabi antara lain sebagai berikut: a) wanita ikut serta mengiringi ziarah; b) Mengadakan perkumpulan dan pertemuan untuk berdzikir; c) Berdo’a dengan tawassul; d) Membangun kubah di atas kuburan; e) Berziarah ke kubur/makam; f) Kebiasaan sehari-hari, seperti merokok, berfoto, minum kopi, memakai cincin, dan lain-lain (Tim Penyusun Ma’arif, Pendidikan Aswaja & Ke-NU-an, [Surabaya: PW. LP. Ma’arif NU Jatim, 2003], hlm. 910). 27 K.H. Husein Muhammad mengutip pandangan Abd al-Qahir al-Baghdadi yang menyebutkan bahwasanya paling tidak terdapat tiga versi mengenai hadits di atas, yaitu: a) Versi pertama menyebutkan redaksi “Ma ana alaihi wa ash-habi” (apa yang aku berada di atasnya bersama para sahabatku); b) Versi kedua menyebutkan redaksi “Hiya al-Jama’ah” (ia adalah Jama’ah); c) Versi ketiga tidak menyebutkan sebuah redaksi mengenai golongan yang selamat. Abd al-Qahir mengatakan bahwa hadis ini mempunyai banyak sanad 17 untuk menapaki golongan Islam yang benar “Ahlussunnah wal-Jama’ah”, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Ahlussunnah wal-Jama’ah bukanlah suatu hal yang baru timbul sebagai reaksi dari timbulnya beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran yang murni, seperti Khawarij, Syi’ah, Mu’tazilah, dsb. Oleh karena itulah, pendapat yang mengatakan bahwa nama Ahlussunnah wal-Jama’ah muncul pada masa imam madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) adalah pendapat yang keliru dan tidak memiliki landasan ilmiah maupun historis yang kuat. Begitu juga tidak dapat dibenarkan, yaitu pendapat lain yang mengatakan munculnya nama ini pada masa Imam al-Asy’ari dan al-Maturidi dan pendapat lain yang menyatakan muncul pada sekitar abad ke-7 Hijiriyah. Dengan demikian, dapat disimpulkan Ahlussunnah wal-Jama’ah sudah ada sebelum semuanya itu muncul. Aliran-aliran sempalan itulah yang merupakan gangguan terhadap kemurnian Ahlussunnnah wal-Jama’ah. Pada saat gangguan ini muncul secara bertubi-tubi, segera dirasakan perlunya istilah Ahlussunnah wal-Jama’ah ini dipopulerkan kembali oleh kaum muslimin yang tetap teguh pada ajaran-ajaran (sunnah) sebagaimana yang diajarkan, dipraktekkan, dan dicontohkan oleh Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabatnya. Pentingnya untuk mempopulerkan ajaran Ahlussunnah wal-Jama’ah (aswaja) ini tentunya membutuhkan penjelasan secara distingtif, karena kalau tidak demikian maka akan semakin membingungkan kita untuk menentukan mana yang Aswaja dan mana yang bukan. Sehubungan dengan hal ini, alSyahrastani28 menyatakan dua proposisi yang kontradiktif tidak mungkin benar keduanya. Demikian pula dalam ajaran agama, yakni dua ajaran yang bertentangan tentu yang satunya benar dan yang satunya lagi salah. Tidak mungkin ajaran dua golongan yang bertentangan dapat dikatakan bahwa keduanya benar karena kebenaran itu satu. Maka, kesimpulannya kebenaran hanya pada satu golongan dari sekian golongan, yaitu golongan Ahlussunnah wal-Jama’ah. Di sini mungkin ada yang bertanya, lantas apakah yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal-Jama’ah tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka diperlukan penjelasan yang distingtif seputar Ahlussunnah wal-Jama’ah sehingga pertanyaan di atas dapat dijawab dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian Ahlussunnah wal-Jama’ah dapat dijelaskan dengan terlebih dahulu memilahnya menjadi tiga kata. Pertama, kata Ahl yang berarti keluarga, pengikut, golongan29. Kedua, kata al-Sunnah secara etimologis memiliki arti al(transmisi/jalur periwayatan). Oleh karena itu, beberapa ulama menilai hadis ini sahih atas dasar bahwa ia diriwayatkan dari banyak jalan. Banyak sahabat Nabi SAW yang menyampaikan hadits ini (K.H. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme, [Bandung: Penerbit al-Mizan, 2011], hlm. 186). 28 Muhammad ibn ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 2-3. 29 Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah, (Surabaya: Penerbit Khalista, 2011), hlm. 53. 18 Thariqah (jalan dan perilaku), baik jalan dan perilaku tersebut benar atau keliru. Sedangkan secara terminologis (syara’) al-Sunnah adalah nama bagi jalan dan perilaku yang diridhai dan menjadi praktik agama yang sah, yang ditempuh oleh Rasulullah SAW atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama, seperti para sahabat, berdasarkan hadis Nabi SAW: “Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa’ al-Rasyidin sesudahku.” Adapun pengertian sunnah secara kebiasaan (‘Urf) yaitu segala macam perbuatan yang ditradisikan oleh orang-orang yang menjadi teladan, baik itu nabi ataupun wali30. Ketiga, kata al-Jama’ah secara etimologis berarti orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektifitas dalam mencapai satu tujuan, sebagai kebalikan dari firqah, yaitu orang-orang yang bercerai-berai dan memisahkan diri dari golongannya. Sedangkan secara terminologis, kata al-Jama’ah ialah mayoritas kaum muslimin (al-sawad al-a’dham) sebagaimana sabda Nabi SAW: “Sesungguhnya umatku tidak bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan maka ikutilah kelompok mayoritas (alsawad al-a’dham).”31 Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal-Jama’ah ialah golongan yang menerapkan ajaran agama yang sah sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki wewenang tasyri’ (membentuk dan mengadakan hukum) dan para sahabat yang hanya memiliki wewenang tathbiq (menerapkan prinsip-prinsip pada perumusan sikap dan perbuatan konkret). Adapun ciri golongan tersebut adalah upayanya untuk senantiasa menjaga kolektifitas dan menjauhi segala bentuk perpecahan (iftiraq) yang dilakukan para kelompok sempalan (firqah) Islam. Maka, dalam hal ini istilah Ahlussunnah wal Jama’ah diartikan sebagai nama bagi setiap Muslim yang bukan pengikut aliran Khawarij, Rafidhah (Syi’ah), Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu’tazilah, Karamiyah, Wahabiah, dan kelompok (firqah) lain yang menyimpang dari ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Dalam konteks ini, al-Imam al-Hafidh al-Zabidi mengatakan: “Apabila dikatakan Ahlussunnah wal-Jama’ah, maka yang dimaksud adalah pengikut madzhab al-Asy’ari dan al-Maturidi.”32 30 31 32 Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, Risalah Ahl al-sunnah wa al-Jama’ah: fi hadits al Mawta wa asyrath al-Sa’ah wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid’ah, (Jombang: Maktabah Turats al-Islami Tebuireng, 1418 H), hlm. 5. Muhammad Idrus Ramli, Madzhab al-Asy’ari: Benarkah Ahlussunnah wal-Jama’ah (Surabaya: Penerbit Khalista, 2009), hlm. 176-177. Ibid, hlm. 233. Adapun pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal-Jama’ah yang disarikan dari pemikiran al-Asy’ari dan al-Maturidi antara lain: a) Iman adalah mengikrarkan lisan, dan membenarkan hati. Bila ditambah dengan perbuatan, maka iman menjadi sempurna; b) Allah SWT memiliki sifat Jalal (Kebesaran), Jamal (Keindahan), dan Kamal (Kesempurnaan). Sifat Allah SWT yang wajib diketahui setiap mukmin berjumlah 41, yaitu 20 sifat wajib Allah SWT, 20 sifat mustahil Allah SWT, dan 1 sifat jaiz Allah SWT; c) Allah SWT dapat dilihat dengan mata kepala di surga; d) al-Qur’an sebagai perwujudan Kalamullah yang bersifat qadim ialah qadim. Sedangkan al-Qur’an yang 19 Ahlussunnah wal-Jama’ah: Upaya Memelihara Kemurnian Islam Ketika Rasulullah SAW masih hidup, segala macam urusan agama yang belum dimengerti dapat ditanyakan langsung kepada beliau, sehingga segala persoalan agama dapat dipecahkan dengan jelas dan tidak dijumpai perbedaan. Hal ini mengingat kedudukan beliau sebagai utusan Allah SWT yang diberikan wewenang tasyri’. Akan tetapi berbeda halnya ketika Rasulullah SAW telah wafat. Sebagaimana dijelaskan di atas, persoalan yang pertama kali merebak di kalangan para sahabat ialah tentang pengganti beliau sebagai pemimpin umat. Pada perjalanan selanjutnya, timbullah firqah-firqah (Khawarij, Saba’iyah/Syi’ah, dsb) yang saling memperebutkan pengaruh untuk menarik simpati umat dalam rangka mengejar kepentingan politik kekuasaan masingmasing. Dari akar permasalahan ini kemudian timbul berbagai macam ajaran dengan rumusan-rumusan hujjah/argumentasi tertentu, sehingga seringkali bahkan ajaran-ajaran tersebut digunakan untuk melegitimasi kebenaran firqahnya dan juga untuk menyerang kelompok yang lain. Oleh karena itulah, Ahlussunnah wal-Jama’ah meskipun sebenarnya sudah ada semenjak zaman Nabi SAW, tapi istilah ini mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream. Sehubungan dengan hal ini, menarik kiranya kita cermati firman Allah SWT, “Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan yang haq (benar) dan dengan yang haq itu mereka menjalankan keadilan” (Q.S. al-A’raf: 181). Di ayat yang lain, Allah SWT juga berfirman, “Hendaknya orang-orang yang dianugerahi ilmu mengerti bahwasanya al-Qur’an itulah yang haq (benar) di sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman karenanya (kebenaran al-Qur’an) hingga kemudian hati mereka tenteram. Sesungguhnya Allah pasti memberi orang-orang yang beriman hidayah menuju jalan yang lurus” (Q.S. al-Hajj: 53). Dari kutipan ayat di atas, kita jumpai Allah SWT menekankan pentingnya sebuah “ilmu” yang akan memandu jalan kaum muslim untuk mencapai kebenaran (haq), yaitu kebenaran berupa tegaknya Islam yang lurus dan murni dari segala penyimpangan yang merusak sendi-sendi pokok ajaran agama. Kaitannya dengan Ahlussunnah wal-Jama’ah, ilmu memiliki kedudukan yang tidak dapat diabaikan. Begitu eratnya hubungan Ahlussunnah wal-Jama’ah dengan ilmu ini, Ibnu Abbas sahabat Nabi SAW yang terkenal alim dan pakar dalam tafsir Al-Qur’an menjelaskan maksud firman Allah SWT pada surat Ali- berupa huruf dan suara adalah baru; e) Allah tidak berkewajiban membuat yang baik dan yang terbaik, memberi pahala pada yang ta’at, dan menjatuhkan siksa pada yang durhaka; f) Kebaikan dan keburukan tidak dapat diketahui melalui akal semata; g) Allah SWT menciptakan perbuatan manusia; h) Pertanyaan malaikat Munkar & Nakir, siksa kubur, rahmat kubur, kebangkitan di akhirat, hari mahsyar, timbangan amal (al-mizan), shirat (jembatan akhirat) adalah benar semuanya; i) Surga dan neraka adalah ciptaan Allah SWT dan tidak ada tempat di antara keduanya (manzilah baina al-manzilatain), dsb. 20 Imran ayat 106 sebagai berikut: “Adapun yang dimaksud firman Allah SWT mengenai orang-orang yang wajahnya putih berseri adalah pengikut Ahlussunnah wal Jama’ah dan orang-orang yang berilmu, sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram, adalah pengikut bid’ah dan sesat.”33 Ahlussunnah wal-Jama’ah yang dipopulerkan oleh orang-orang yang berilmu (para sahabat, tabi’in, tabi’ al-tabi’in, dan ulama saleh) sebagai gerakan untuk memurnikan ajaran Islam tentunya sama sekali berbeda dengan para pengikut bid’ah. Hal ini mengingat tindakan bid’ah menjerumuskan pada kesesatan dan pasti bertentangan dengan ajaran Islam yang benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan (agama) kita, sedangkan perkara tersebut sama sekali bukan dari (ketentuan agama), maka perkara tersebut ditolak (keabsahannya).” Begitu pula hadis Nabi SAW yang berbunyi, “Semua tindakan membuat perkara baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan semua bid’ah adalah sesat”. Dengan memperhatikan pernyataan Nabi SAW mengenai bid’ah yang memiliki konsekuensi menyangkut identitas sesat-tidaknya seorang muslim, maka diperlukan pemahaman yang lebih gamblang mengenai konsepsi bid’ah ini. Dengan upaya ini, diharapkan kita dapat mengetahui kebenaran ajaran Ahlussunnah wal-Jama’ah yang terbebas dari unsur-unsur bid’ah yang menyesatkan. Menurut Syaikh Marzuq sebagaimana dikutip oleh Kiai Hasyim Asy’ari, bid’ah yaitu upaya membuat perkara baru dalam urusan agama sehingga perkara baru tersebut seolah-olah merupakan bagian dari ketentuan agama, namun pada dasarnya perkara tersebut bukanlah bagian agama, baik dalam bentuk maupun substansinya34. Bid’ah pada prinsipnya sangat berbeda dari ajaran Islam yang benar, sehingga dapat dipastikan Islam bukanlah bid’ah atau sebaliknya bid’ah bukanlah Islam. Hal ini dikarenakan dua hal yang saling bertentangan tidak mungkin keduanya benar atau keduanya salah, bahwa kebenaran pasti salah satu di antara keduanya sedangkan kebenaran itu tidak lain adalah al-sunnah (Islam yang diajarkan Nabi SAW). Kendatipun sudah diketahui bid’ah pasti sesat, namun kondisi sekarang telah mengalami perubahan dari pada kondisi di saat Nabi SAW masih hidup, sedangkan Nabi SAW sendiri telah mengatakan semua perkara baru (bid’ah) adalah sesat. Dalam konteks demikian, para ulama menjelaskan mengenai maksud hadits Nabi di atas. Menurut jumhur ulama’ (mayoritas ulama’), bid’ah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tersebut sebenarnya mengacu pada ada tidaknya perubahan status hukum pada hal-hal yang profan (non-agama), yaitu ketika hal yang profan itu dirubah menjadi suatu hal yang memiliki ketentuan agama. Jadi, hadis tersebut bukan untuk mem-bid’ah-kan 33 34 Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah, (Surabaya: Penerbit Khalista, 2011), hlm. 69-70. Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, Risalah Ahl al-sunnah wa al-Jama’ah: fi hadits al Mawta wa asyrath al-Sa’ah wa Bayan Mafhum al-Sunnah wa al-Bid’ah, (Jombang: Maktabah Turats al-Islami Tebuireng, 1418 H), hlm. 6. 21 semua perkara baru. Aturan yang dipakai adalah: jika perkara yang dipersoalkan itu ditemukan ketentuan jelas syari’ahnya (Al-Qur’an & Al-Hadits) maka harus dihukumi sesuai aturan syari’ah, namun jika perkara tersebut tidak ditemukan secara jelas rujukan syari’ahnya tapi secara prinsip ada kesamaannya maka harus disimpulkan status hukumnya berdasarkan qiyas/analogi. 35 Adapun parameter yang digunakan dalam rangka mengukur bid’ah tidaknya sebuah perkara ada tiga macam.36 Pertama, apabila tindakan membuat perkara baru (inovasi) tersebut lebih dominan dimensi syari’ahnya, maka hal itu tidak bisa dikatakan bid’ah. Adapun jika terjadi sebaliknya, yaitu dimensi tindakan membuat perkara baru tersebut lebih dominan dibandingkan dimensi syari’ahnya, maka hal itu merupakan suatu kebatilan. Kedua, yaitu menggunakan acuan kaidah para imam yang tidak diragukan kesunnahannya. Apabila tindakan membuat perkara baru tersebut mengacu pada kaidah-kaidah tersebut, maka hal itu bukanlah bid’ah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka hal itu berarti bid’ah. Misalnya, ijtihad para ulama NU yang menerima keabsahan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi para ulama NU, eksistensi Negara ini sudah tidak terbantahkan lagi sebagaimana realitas historis perjuangan bangsa ini hingga mencapai kemerdekaannya. Oleh karena itulah, tidak diperlukan lagi sebuah keberadaan Negara Islam yang ditawarkan sebagai alternatif untuk sistem yang sudah ada. Mengingat Negara ini telah ada terlebih dahulu, maka harus ada seorang pemimpin yang memiliki wewenang penuh dalam rangka mengatur pelaksanaan sebuah pemerintahan. Para Ulama NU akhirnya merujuk pada kaidah fiqih “al-dharuratu tubihu al-mahdhurat” (keadaan yang terpaksa memperbolehkan sesuatu yang dilarang). Dengan demikian, akhirnya para Ulama NU menyepakati keabsahan Presiden Soekarno sebagai pemimpin Negara dengan sebutan Wali al-Amri al-Dharuri bi al-Syaukah (pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh). Meskipun Presiden Soekarno tidak dipilih dengan mekanisme ahl al-halli wa al-aqdi (mekanisme pemilihan imamah sebagaimana yang dilakukan para sahabat Nabi SAW) di mana itu berarti tidak sepenuhnya memiliki keabsahan di mata hukum fiqih, tapi kekuasaannya harus efektif karena eksistensi Negara yang terlanjur ada ini membutuhkan kuasa penuh pemimpinnya. Ketiga, yaitu menggunakan parameter hukum syari’ah yang berjumlah 5, yaitu wajib (al-wujub), sunah (al-nadb), haram (al-tahrim), makruh (alkarahah), dan mubah (al-ibahah). Maksudnya yaitu sejauh mana perkara baru tersebut diputuskan berdasarkan parameter lima di atas. Dengan mengacu pada lima parameter ini, maka bid’ah dapat dibagi dalam lima hal, yaitu: 1) Bid’ah yang bersifat wajib, yaitu bid’ah yang tidak dilaksanakan di zaman Rasul SAW, tapi hukumnya wajib dilakukan. Misalnya, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur’an dan al-Hadits, seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, 35 36 Ibid, hlm. 6. Ibid. hlm. 6-7. 22 dsb. Bid’ah jenis ini tidak bisa dikatakan sebagai bid’ah dhalalah (bid’ah sesat); 2) Bid’ah yang bersifat mandub, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. Misalnya, membangun sekolah, mengamalkan tahlil, istighotsah dan berbagai kebajikan lain yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Bid’ah jenis kedua ini juga sama dengan bid’ah jenis pertama; 3) Bid’ah yang bersifat haram. Misalnya, bid’ah yang dilakukan kelompok beberapa kelompok dalam Islam (Qadariyah, Jabariyah, Tanasukhiah, Ibahiyun, dsb). Inilah yang dimaksud bid’ah dhalalah; 4) Bid’ah yang bersifat makruh, yaitu apabila dikerjakan tidak apa-apa namun bila ditinggalkan mendapat pahala. Misalnya, menghiasi masjid, memperindah mushaf, merokok, dsb. Bid’ah jenis keempat ini mendekati bid’ah jenis ketiga, meskipun secara hukum masih diperbolehkan untuk dikerjakan; 5) Bid’ah yang bersifat mubah, yaitu boleh dilakukan dan tidak. Misalnya, berjabat tangan sehabis salat, memakai kopyah, dsb. Berdasarkan tiga parameter ini, maka Kiai Hasyim Asy’ari membagi bid’ah tiga macam.37 Pertama, bid’ah sharih yaitu bid’ah yang jelas kebatilan/keharamannya. Misalnya, mengikuti ajaran jabariah, qadariah, dan kelompok sempalan Islam yang lain. Kedua, bid’ah idhafiyah, yaitu bid’ah yang disandarkan pada sebuah perkara agama. Apabila bid’ah tersebut menunjang perkara agama tersebut, maka tidak bisa dihukumi bid’ah. Misalnya, mempelajari ilmu mantiq (ilmu logika) untuk mendalami pengetahuan Islam. Ketiga, bid’ah khilafiyah, yaitu bid’ah yang sama-sama memiliki rujukan pokok agama yang jelas dan kuat sehingga menimbulkan perbedaan (ikhtilaf) di antara para ulama’. Misalnya, para ulama’ berbeda pendapat dalam menyikapi hukum bunga bank, sebagian ada yang mengatakan haram dan yang lain mengatakan mubah dan syubhat (samar). Meskipun terlihat masih belum lengkap, konsepsi bid’ah yang dipaparkan di atas dirasa cukup untuk menunjukkan pemahaman keagamaan ala Ahlussunnah wal-Jama’ah yang terbukti mampu mempertahankan kemurniannya tanpa harus kehilangan nuansa kekinian. Dengan demikian Islam tidak akan lekang oleh perubahan zaman. Di tangan paham Ahlussunnah walJama’ah, Islam tetap menjadi agama yang rahmatan li al-alamin, sesuai di setiap situasi dan kondisi (shalihun li kulli zaman wa makan), tidak seperti pahampaham lain yang telah mengalami kepunahan, seperti Khawarij, Mu’tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Ahlussunnah wal-Jamaa’ah: Metode Bermadzhab Sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat tidaklah sulit mendapatkan kemurnian ajaran Islam karena jarak waktu dan jarak fisik yang sangat dekat dengan beliau. Segala persoalan yang tidak diketahui para sahabat, maka satu-satunya cara ialah menanyakan langsung kepada beliau. Dalam menghadapi pertanyaan para sahabat itu, Rasulullah SAW menjawab berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepadanya, dan itulah yang dinamakan Al-Qur’an. Terhadap keterangan Al37 Ibid, hlm. 7-8. 23 Qur’an yang tidak sepenuhnya menjelaskan persoalan secara detail, Rasulullah SAW menjelaskan persoalan tersebut tentunya dengan petunjuk Allah SWT secara lebih terperinci lagi, dan itulah yang dinamakan al-Hadits. Oleh karena itulah, para sahabat merupakan generasi Islam paling awal dan paling memahami dan menghayati ajaran Islam. Sesudah generasi sahabat, selanjutnya datanglah generasi baru secara silih berganti, berkesinambungan mewarisi ajaran Nabi SAW, yakni para tabi’in (pengikut sahabat Nabi SAW), tabi’ al-tabi’in (pengikut tabi’in), hingga tiba pada masa generasi sekarang. Dengan mengetahui posisi spasio-temporal kita yang terpaut amat jauh dari zaman Nabi SAW, maka itu artinya makin sulit pula mendapatkan kemurnian ajaran tentang Islam. Apalagi, dalam sejarahnya Islam tidak hanya mengalami perbedaan (ikhtilaf) saja, tapi lebih parah lagi yaitu mengalami perpecahan (iftiraq) yang melahirkan banyak firqah-firqah. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kemurnian Islam yang jauh dari pengaruh firqah-firqah di atas, maka jalan satu-satunya adalah kembali pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sehubungan dengan ini, Nabi SAW bersabda: “Aku wariskan kepadamu dua perkara yang mana jika engkau berpegang teguh padanya maka engkau tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah (AlQur’an) dan sunnah rasulNya.” Secara prinsipnya, memang al-Qur’an dan al-Hadist adalah sumber utama dalam memecahkan segala persoalan agama. Namun, yang harus disadari adalah Al-Qur’an itu sendiri nyatanya tidaklah sesederhana yang kita bayangkan, tapi justru al-Qur’an tersebut terdiri dari berbagai macam unsur yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat ayat muhkamat, mutasyabihat, nasikh, mansukh, al-‘am, khas, takhsis, dan berbagai macam ketentuan yang lain. Kenyataannya, al-Qur’an tidaklah sekedar dipahami arti tekstualnya saja, tapi banyak ilmu yang harus dikuasai untuk memahami isi kandungan al-Qur’an, seperti: nahwu & sharaf (ilmu tata bahasa arab), balaghah (sastra), mantiq (logika), ushul al-fiqih, qawaid al-fiqhiyah, asbab al-nuzul, tafsir, ‘ulum al-qur’an, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan al-Hadits, meskipun lebih terperinci isinya, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW secara sebagian sehingga untuk menganalisa satu masalah saja (umpamanya salat) mungkin membutuhkan beratus-ratus hadis yang berhubungan dengan masalah tersebut. Sebagaimana al-Qur’an, memahami al-Hadits tidaklah cukup dengan mengetahui maknanya saja, tapi harus memiliki pengetahuan juga apakah hadis tersebut shahih (benar), hasan (baik), dha’if (lemah), maudhu’ (palsu), apakah hadist itu mutawatir, masyhur, aziz, mudallas, mu’an’an, dsb. Selain itu, kita juga dituntut mengetahui latar belakang sejarah (asbab al-wurud) disampaikannya hadis oleh Nabi SAW. Demikian mengingat rumitnya memahami al-Qur’an dan al-Hadits, maka dapat dipastikan tidak banyak orang yang mampu memahami sendiri dan menggali sebuah persoalan secara langsung pada al-Qur’an dan al-Hadits. Dari kenyataan ini, maka terdapat dua kemungkinan bagi seorang muslim yang perlu memiliki pendapat atau perlu melakukan suatu hal mengenai Islam: 1) Bagi yang memenuhi syarat dan sarana untuk mengambil kesimpulan pendapat 24 (istinbath) sendiri, maka dapat menggunakan metode ijtihad. Untuk kemungkinan yang pertama ini, kita bisa melihat tokoh-tokoh Islam yang dapat disebut sebagai mujtahid, seperti: Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit (80-150 H/699-767 M), Malik ibn Anas al-Anshari (93-179 H/712-795 M), Muhammad ibn Idris al-Syafi’i (150-204 H/ 767-820 M), Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani (164-241 H/780-855 M), Abu al-Hasan al-Asy’ari (260-330 H/873-947 M), Abu Manshur al-Maturidi, dsb; 2) Bagi yang tidak memenuhi syarat atau yang kemampuannya diragukan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti hasil ijtihad atau istinbath para ulama’ yang sudah tidak diragukan lagi kapasitas keilmuannya. Metode demikian dinamakan metode taqlid (bermadzhab). Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka pemahaman dan pengamalan Islam yang murni yang dikatakan Alussunnah wal-Jama’ah itu tidaklah mudah ditempuh dengan melakukan ijtihad dan istinbat langsung kepada sumber pokoknya (al-Qur’an dan al-Hadits). Dengan mempertimbangkan bahwasanya jarak yang begitu jauh dengan Rasul, begitu pula ijtihad dan istinbath yang tidak boleh dilakukan sembarang orang, maka Ahlussunnah wal-Jama’ah harus dimaknai sebagai upaya bermadzhab. Dengan kata lain, jika dengan jujur kita mengakui bahwa perkara ijtihad dan istinbath bukanlah hal yang mudah dilakukan, maka konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah keharusan bermadzhab. Hal ini dikarenakan hanya dengan upaya bermadzhablah, sehingga Ahlussunnah wal-Jama’ah itu sendiri menjadi mungkin. Ahlussunnah wal-Jama’ah dengan metode bermadzhab berarti menggunakan produk-produk hukum para ulama yang sudah mempunyai kapasitas pemahaman yang bersifat otoritatif (mujtahid). Inilah pengertian Ahlussunnah wal-Jama’ah sebagaimana yang dirumuskan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari dalam Qanun Asasi (konstitusi dasar) yang dijadikan pedoman Nahdhadul Ulama (NU), salah satu organisasi social keagamaan yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia. Dalam Qanun Asasi tersebut, dinyatakan bahwa Ahlussunnah wal-Jama’ah merupakan sebuah paham keagamaan di mana dalam bidang aqidah menganut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur alMaturidi, dalam bidang fikih mengikuti pendapat dari salah satu madzhab empat (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hanbali) dan dalam bidang tasawuf/akhlak menganut Imam Abu Qasim Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Upaya memahami dan mengamalkan Ahlussunnah wal-Jama’ah dengan pendekatan bermadzhab merupakan keniscayaan intelektual38 yang tidak dapat dibantah. Hal ini sebagaimana dijelaskan Kiai Hasyim Asy’ari, khususnya ketika beliau memberikan alasan tentang pentingnya berpegang teguh pada empat imam madzhab dalam fikih. Pertama: mengacu para ulama salaf merupakan konsensus (ijma’) para ulama. Paham keagamaan, khususnya hukum Islam merupakan mata rantai yang tidak terputus. Para tabi’in mendasari 38 Hal ini mengacu Firman Allah SWT, “Maka bertanyalah kepada orang-orang cerdik-cendekia (ahl al-dzikr) jika kalian tidak mengetahui” (Q.S. al-Nahl: 43). 25 pandangannya pada para sahabat Nabi SAW. Begitu pula para tabi’ al-tabi’in juga mengikuti para generasi tabi’in, dan seterusnya. Hal itu semakin meneguhkan bahwa seseorang tidak bisa langsung memahami al-Qur’an dan al-Hadits. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kearifan dan keseriusan untuk mempelajari pandangan para ulama terdahulu. Kedua: hadis Nabi SAW39 yang menegaskan pentingnya mengikuti pandangan orang-orang yang mulia dan cerdas, mereka adalah kelompok alternatif (al-sawad al-a’dham), di mana pemahaman mereka terhadap syari’at tidak diragukan lagi. Mereka adalah para ulama yang dikenal sepanjang masa sebagai ahli waris para nabi karena kedalaman ilmu dan kemuliaan hati mereka. Ketiga: menghindari adanya klaim-klaim kebenaran yang dilakukan beberapa orang yang mengaku-ngaku ahli agama. Dalam hal ini Kiai Hasyim Asy’ari sangat mewanti-wanti adanya fatwa yang dikeluarkan oleh ulama buruk moral, yang kerap kali mengeluarkan fatwa berdasarkan hawa nafsu. Sebab itu, mengikuti para imam madzhab fikih yang sangat diakui integritas keilmuannya, kejujurannya, dan keadilannya akan memberikan manfaat yang lebih besar dari pada mengambil dari fatwa yang tidak otoritatif. Sehubungan dengan ini, sahabat Umar ibn Khattab berkata, “Islam akan hancur karena perdebatan orang-orang yang munafik terhadap Al-Qur’an.” Ungkapan ini dapat dipahami jika dalam memahami teks keagamaan tidak digunakan rujukan yang jelas dari para ulama otoritatif40. Revitalisasi Ahlussunnah wal-Jama’ah Pemahaman Ahlussunnah wal-Jama’ah dalam bingkai madzhab sebagaimana digambarkan Kiai Hasyim Asy’ari mendapat respons luar biasa dari para kalangan, terutama warga NU dan sebagian besar masyarakat muslim senusantara bahkan penjuru dunia. Sebagaimana dilaporkan Zuhairi Misrawi yang pernah belajar di Perguruan Tinggi Islam al-Azhar (Mesir), rumusan Ahlussunnah wal-Jama’ah Kiai Hasyim tersebut ternyata menjadi bahasan utama di perguruan tinggi tertua di dunia tersebut. Ia merasakan betul betapa pandangan teologis Abu al-Hasan al-Asy’ari menjadi rujukan primer. Begitu pula dalam bidang fikih, yaitu mengacu pada madzhab empat. Adapun tasawuf di antaranya mengacu pada Imam al-Ghazali. 41 Meskipun demikian, oleh karena zaman terus berkembang, maka dapat dipastikan terjadi perubahan juga pada segala sendi kehidupan, baik ranah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Dalam konteks demikian, maka muncullah gagasan mengenai revitalisasi42 terhadap paham Ahlussunnah 39 Dari Anas ibn Malik R.A. berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ‘Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas (al-sawad ala’dzham)” (H.R. Ibn Majah) (Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah, [Surabaya: Penerbit Khalista, 2011], hlm. 56). Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta, Penerbit: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 111-113. 41 Ibid, hlm. 133. 42 Dalam hal ini, revitalisasi tersebut harus dibingkai dalam tiga fundamen sebagaimana yang 40 26 wal Jama’ah ini. Menurut Zuhairi Misrawi, revitalisasi yang dimaksud ialah upaya untuk memaksimalkan fungsionalisasi paham Ahlussunnah wal-Jama’ah rintisan Kiai Hasyim di atas. Di samping itu, ia menambahkan ada alasan yang lebih penting, yaitu dalam rangka melakukan distingsi dengan pihak-pihak lain yang selama ini mengklaim dirinya berpaham Ahlussunnah wal-Jama’ah. Padahal, dalam praktiknya, mereka tidak konsisten dengan parameter sebagaimana yang dijelaskan para ulama Ahlussunnah wal-Jama’ah seperti Kiai Hasyim. Bahkan, kerapkali terjadi klaim bahwa model pemahaman bermadzhab demikian menyebabkan Ahlussunnah wal-Jama’ah mengalami pereduksian makna.43 Sosok yang menonjol dalam melakukan revitalisasi terhadap paham Ahlussunnah wal-Jama’ah antara lain K.H. Said Aqil Siradj44. Dunia Islam terutama kalangan Muslim Ahlussunnah sedang dihadapkan pada krisis yang melanda hampir seluruh sektor kehidupan umat. Keadaan demikian tercermin pada realita menjamurnya tindakan ekstrimisme (fanatik) dan radikalisme diungkapkan Gus Dur. Pertama, pandangan bahwa keseluruhan hidup adalah ibadah (al-hayatu ‘ibadatun kulluha). Prinsip ini berarti bahwa apa yang dilakukan setiap muslim pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk kemuliaan dan memaksimalkan peran manusia sebagai khalifah, yaitu makhluk yang bertanggung-jawab untuk memakmurkan alam beserta isinya yang diciptakan Allah SWT. Prinsip setiap tindak tanduk seorang Muslim adalah ibadah merupakan manifestasi dari paham Ahlussunnah wal-Jama’ah, di mana dalam setiap ikhtiar manusia di dalamnya terdapat kuasa Allah SWT yang akan menjadikan amalnya bermakna. Kuasa Allah SWT meniscayakan seorang Muslim harus meyakini bahwa setiap hal yang dilakukan merupakan manifestasi dari peribadatan yang akan mempunyai nilai plus sebagai tanda ketundukan dan penyerahan diri secara total kepada-Nya. Kedua, perlunya kejujuran dalam hidup bermasyarakat. Kejujuran dimulai dari kelapangdadaan untuk menerima pendapat ulama yang sudah mempunyai kapasitas pemahaman yang bersifat otoritatif. Dalam sikap seperti itu akan muncul sebuah sikap toleransi dalam menerima perbedaan pendapat. Dengan demikian, pandangan ulama yang beragam menunjukkan bahwa yang paling penting adalah kejujuran untuk menerima perbedaan dan keragaman pendapat, di mana kejujuran dilandasi sebuah pemahaman yang komprehensif dan argumentatif. Sikap ini harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kalangan Muslim dapat memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif. Ketiga, perlunya moralitas yang utuh dan kuat. Dalam rangka membangun kehidupan yang bersih dan transparan, selain diperlukan sistem yang baik, juga diperlukan pola hidup yang asketis, sederhana, dan mengedepankan kepentingan umum. Moralitas yang seperti ini merupakan sebuah cerminan dari penghayatan nilai-nilai Ahlussunnah wal-Jama’ah karena pada hakikatnya para ulama di masa lalu adalah teladan moralitas yang paling paripurna. Sehubungan dengan hal ini, para ulama memandang keteladanan merupakan moralitas yang mencerminkan sebuah pemahaman yang paripurna terhadap agama, yang diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Mereka membangun umat melalui pembangunan mental dan penajaman hati nurani untuk kemaslahatan umat. Ketiga hal inilah yang sejatinya dapat melandasi pemikiran Islam, khususnya Ahlussunnah wal-Jama’ah. Sebab, jika tidak tercermin dengan baik, akan membuat semua pemikiran yang cemerlang itu hanya menjadi dokumen yang normatif yang tidak mempunyai makna fungsional (Ibid, hlm.133-137). 43 Ibid, hlm. 133. 44 Said Aqil Siradj, Ahlussunnah wal-Jama’ah: Sebuah Kritis Historis, (Jakarta: Pustaka Cendekiamuda, 2008) 27 (tindak kekerasan), kemiskinan, keterbelakangan (anti kemajuan), kebodohan (irasionalitas), dan berbagai macam ketidakmampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras untuk menjadikan paham ini menjadi lebih kompatibel dengan realitas kekinian. Hal ini mengingat Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian45, keadilan46, dan kemajuan47. Sehingga harus diupayakan agar Islam bersifat fungsional, inovatif, dan solutif dalam ikhtiar menjawab segala persoalan dan tantangan zaman. Jadi, penting untuk diketahui bahwa langkah ini bukanlah untuk menegasikan makna paham Ahlussunnah wal-Jama’ah sebagaimana dilontarkan Kiai Hasyim. Dalam hal ini, Kiai Said Aqil mengacu pada definisi yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrazaq al-Husaini al-Zabadi Abul Faridl, seorang ulama asal India. Ahlussunnah wal-Jama’ah, menurutnya ialah orang-orang yang mempunyai paham keagamaan dalam seluruh sektor kehidupan yang dibangun di atas prinsip al-tawassuth (moderasi), al-tawazzun (keseimbangan), al-i’tidal (keadilan), al-tasamuh (toleransi). 48 Melalui pandangan demikian, maka Ahlussunnah wal-Jama’ah bukan dimaknai lagi sebagai metode bermadzhab seperti dijelaskan sebelumnya, tapi dimaknai sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr) yang berpegang pada prinsip empat tersebut (al-tawassuth, al-tawazzun, al-il’tidal, al-tasamuh). Berikut penjelasan Ahlussunnah wal-Jama’ah sebagai manhaj al-fikr. Prinsip al-Tawassuth Kata al-tawasuth yang secara bahasa berarti pertengahan diambil dari kata wasathan berdasarkan firman Allah SWT: “Dan demikian, Kami telah jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat wasathan (pertengahan/pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Rasulullah SAW menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian…” (Q.S. Al-Baqarah: 143). Ukuran penilaian pada ayat di atas dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW sebagai pengukur umat Islam, sedang umat Islam menjadi pengukur manusia pada Firman Allah SWT: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.S. Ali ‘Imran: 133-134). 46 Firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. AlMaidah: 8). 47 Firman Allah SWT: “….Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan derajat (yang berlipat-lipat)” (Q.S. AlMujadilah: 11). 48 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 140. 45 28 umumnya.49 Sebagai tolak ukur atas umat manusia pada umumnya, maka kaum Muslim dituntut berpandangan objektif. Dengan pikiran yang objektif ini, maka setiap penilaian tersebut dilandasi hujjah/argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dilandasi sikap sentimen dan apriori. Tentunya pandangan yang objektif ini disertai pula dengan kadar integritas pada diri seseorang. Sehingga, segala perbedaan akan disikapi dengan jujur dan lapang dada. Adapun implementasi prinsip al-tawasuth ini oleh Kiai Said Aqil dijelaskan sebagai penerapan metode pengambilan hukum yang menghubungkan nash (dalil naqli) dan akal (dalil aqli). Sedangkan dalam metode berpikir secara umum mampu untuk merekonsiliasikan50 antara wahyu dan rasio. Sikap al-tawasuth yang seperti ini mampu meredam dua ekstrimisme sekaligus, yaitu ekstrimisme tekstual dan ekstrimisme akal. Rekonsiliasi antara teks dan rasio telah menyebabkan diskursus hukum Islam mengalami pengayaan yang amat luar biasa.51 Prinsip al-Tawazzun Pengertian al-tawazzun secara bahasa berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak berlebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain. Kata ini diambil dari al-waznu atau al-mizan yang berarti timbangan/penimbang. Hal ini seperti pada firman Allah SWT, “Supaya kamu jangan melampui batas tentang neraca (al-mizan) itu. Dan tegakkanlah timbangan itu (al-waznu) itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca (al-mizan) itu” (Q.S. Al-Rahman: 8-9). Menurut Kiai Said Aqil, prinsip al-tawazzun diekspresikan dalam sikap politik, yaitu sikap tidak membenarkan berbagai tindakan ekstrem yang sering kali menggunakan kekerasan dalam tindakannya dan mengembangkan kontrol 49 K.H. Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Surabaya: Penerbit Khalista, 2007), hlm. 69. 50 Rekonsiliasi antara wahyu (teks) dan akal ini dijelaskan oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi (w. 606H/1210 M), ulama ahli tafsir, teolog, dan ahli fikih madzhab Syafi’i dalam kitabnya “Al-Mathalib al-Aliyah fi al-Ilm al-Ilahiy”. Beliau menjelaskan: “Manakala terjadi kontradiksi (al-ta’arudh) antara makna tekstual dan akal yang definitif, maka keduanya tidak bisa dinyatakan benar secara bersama-sama. Karena kalau begitu, sama artinya dengan pembenaran dua hal yang bertentangan. Tetapi, tidak bisa juga dikatakan keliru semua. Karena kalau begitu, sama artinya dengan meniadakan pertentangan dua hal tersebut. Makna tekstual tidak dapat mengungguli temuan akal yang definitif, sebab kebenaran makna teks tidak bisa lepas dari dalil (argumen) akal. Berdasarkan ketentuan ini, maka mengunggulkan teks atas akal sama halnya dengan menyangkal teks. Mengingat akal adalah dasar memahami teks, maka penyangkalan atas akal membawa konsekuensi penyangkalan terhadap akal dan teks sekaligus. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Yang tersisa adalah kemungkinan yang keempat, yakni keharusan memenuhi dalil (argumen) akal dan makna harfiah teks harus ditakwil. Kesimpulannya adalah bahwa dalil (argumen) teks tergantung pada argumen yang tidak bertentangan dengan akal” (K.H. Hussein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, [Bandung: Penerbit al-Mizan, 2011], hlm. 33-34). 51 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 140. 29 terhadap kekuasaan yang lalim. Keseimbangan ini mengacu pada upaya untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat. 52 Adapun cara yang bisa ditempuh untuk mengimplementasikan prinsip ini di tengah-tengah kehidupan bangsa adalah dengan menjunjung konstitusi Negara dan menegakkan supremasi hukum untuk menyelesaikan segala persoalan. Jadi, bukan dengan cara-cara kekerasan, karena cara ini tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu, cara yang dipilih ialah memperkuat sistem hukum yang dapat melindungi segenap warga dan konsisten dalam menegakkannya. Semua ini dilakukan sebagai upaya untuk memainkan peran kontrol/penyeimbang53 yang kuat sehingga tidak ada penyelewengan terhadap hak-hak warga Negara. Sebuah perjuangan demi menegakkan keseimbangan tata politik sebuah Negara berdasarkan prinsip musyawarah (al-syura)54, keadilan (al-adl)55, kebebasan (al-hurriyah)56, dan persamaan (al-musawah)57. Jika prinsip-prinsip ini 52 Ibid, hlm. 141. Sehubungan dengan implementasi prinsip al-tawazzun sebagai penyeimbang dalam konteks kenegaraan ini menarik kiranya untuk menyimak pemikiran Gus Dur. Dalam sebuah subbab tulisannya yang diberi judul “Fikih dan keabsahan Negara”, beliau mengutarakan sebagai berikut: “Upaya menampilkan Islam sebagai ‘jalan hidup alternatif’ yang membentuk sistem kemasyarakatan baru (Negara Islam) di luar yang telah ada (NKRI), jelas sulit diterima oleh para ulama NU, kecuali jika ia telah menjadi bentuk kenegaraan yang memiliki wujud penuh dan mampu mempertahankan diri, seperti Libya, Iran, Saudi Arabia dewasa ini. Landasan penolakan sistem alternatif ‘Islam’ itu adalah keabsahan bentuk Negara yang telah ada. Akan tetapi, itu tidak berarti jalannya pemerintahan juga lalu terlepas sama sekali dari kendala keagamaan. Bahkan, oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan pada ketetntuan-ketentuan fikih, sehingga sikap itu sendiri sering diterima oleh kalangan pemerintah sebagai ‘hambatan’ di kala melaksanakan wewenang mereka. Untuk kepentingan penilaian apakah jalannya pemerintahan tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan fikih, digunakan tolok ukur berupa sejumlah kaidah fikih, seperti ‘Kebijaksanaan kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat’ (tasharruf al-imam ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah). Bentuk formal pemerintahan, dengan demikian, tidaklah menjadi permasalahan bagi NU selama masih diikuti pola perilaku formal Negara yang tidak bertentangan dengan hokum fikih. Kasus-kasus penyimpangan dari “pola umum” perilaku formal Negara ini tidaklah sampai pada penolakan bentuk kenegaraan dan proses pemerintahan yang sudah ada…..Kasus-kasus penyimpangan haruslah ditangani secara kasuistik, bukannya dengan menolak kehadiran Negara dan mengubah bentuk pemerintahan” (Samsul Munir Amin, Percikan Pemikiran Para Kiai, [Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009], hlm. 209-210). 54 Firman Allah SWT, “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirian salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. al-Syura: 38). 55 Firman Allah SWT, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. al-Nisai’: 58). 56 Prinsip kebebasan manusia dalam syari’ah termaktub dalam al-maqashid al-syari’ah 53 30 ditegakkan dengan baik, maka Negara akan mampu menjalankan amanat dan mandatnya untuk melayani rakyat. Prinsip al-tawazzun di atas, selain diekspresikan di bidang politik juga dapat diekspresikan sebagai bentuk apresiasi yang seimbang di bidang keilmuan. Ahlussunnah wal-Jama’ah harus senantiasa dikembangkan supaya tidak sempit. Sikap mayoritas kaum Muslimin yang hanya mencukupkan pada apa yang telah diketahui dan dipelajari serta tidak mau berdialog dengan para ilmuwan yang lain, jelas akan merugikan pengembangan wawasannya. Karena itulah, paham Ahlussunnah wal-Jama’ah ini harus dikembangkan secara mendalam dari sudut pandang berbagai ilmu, baik ilmu pengetahuan alam (sains) ataupun ilmu pengetahuan sosial. Hal ini bertujuan agar paham Ahlussunnah wal Jama’ah ini bisa diintrodusasi secara rasional, sistematis, dan kontekstual sesuai dengan transformasi kultural yang berlandaskan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Harus diakui, upaya mengapresiasi di bidang keilmuan ini (terutama ilmu non-agama) pernah menjadi kontroversi hebat di kalangan ulama masa lalu. Sebagian ulama Islam mengharamkan kaum Muslimin mempelajari ilmu tersebut, seperti ilmu filsafat dan logika58. Sementara sebagian yang lain membolehkannya bahkan menganjurkannya59. Sebagian yang lain lagi sebagaimana dicetuskan al-Syatibi. Prinsip tersebut berjumlah lima, yaitu: 1) Hifdhu alNafs (menjaga jiwa), kebebasan untuk hidup; 2) Hifdhu al-Din (menjaga agama), kebebasan untuk memeluk, meyakini, dan menjalankan agama dan kepercayaan; 3) Hifdhu al-Mal (menjaga harta benda), hak untuk mendapat jaminan keamanan harta benda; 4) Hifdhu al-Nasl (menjaga keturunan), jaminan terhadap asal-usul, identitas, garis keturunan, etnis setiap warga negara; 5) Hifdhu al-Irdh (menjaga kehormatan), jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan, atau pun kedudukan setiap warga negara. 57 Firman Allah SWT, “…..sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa…” (Q.S. al-Hujurat: 13). 58 Salah satu ulama yang mengharamkan ilmu filsafat dan logika adalah Ibn Shalah, ahli hadis klasik terkemuka. Beliau berfatwa, “Belajar dan mengajarkan logika Aristotelian adalah haram. Ia sumber segala keburukan. Belajar dan mengajarkan ilmu mantiq bukan hal yang dibolehkan oleh agama dan tidak pula oleh seorang pun dari kalangan sahabat Nabi, tabi’in, dan para imam mujtahid serta ulama yang saleh” (K.H. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, [Bandung: Penerbit alMizan, 2011], hlm. 92). 59 Bertolak belakang dengan ulama golongan pertama yang mengharamkan ilmu filsafat dan logika, golongan kedua ini merupakan para ulama yang menganjurkan filsafat, salah satunya adalah Ibn Rusyd. Ibn Rusyd sangat mengagumi logika Aristoteles dengan mengatakan, “Tanpanya, orang tidak bisa bahagia dan sungguh kasihan bahwa Plato dan Socrates telah menyia-nyiakannya.” Karena penghormatannya yang sangat tinggi terhadap Aristoteles ini, Ibn Rusyd harus membayarnya mahal. Dia diserang oleh kaum ortodoks karena usahanya untuk menyejajarkan ajaran Aristoteles dengan Islam. Para Teolog merasa bahwa Ibn Rusyd, dalam rangka untuk merekonsiliasi dogma Islam dengan filsafat Aristoteles telah menodai ajaran Islam. Mereka sangat murka terhadap Ibn Rusyd dan menuduhnya telah murtad (Ahmad Zainul Hamdi, Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern, [Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004], hlm. 195-196). 31 membolehkannya, namun dengan syarat hanya dibolehkan bagi orang-orang yang sudah memahami ilmu-ilmu agama secara mendalam60. Terlepas dari kontroversi tersebut, sejarah peradaban Islam abad pertengahan memperlihatkan kepada kita bagaimana para khalifah Islam memberikan respons dan penghargaan tinggi terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemajuan dunia keilmuan dalam sejarah peradaban Islam tersebut di antaranya terjadi pada masa Khalifah al-Ma’mun dari Dinasti Abasiyah. Bahkan pada masa khalifah inilah, dunia keilmuan Islam mencapai puncak kejayaannya. Hal ini terbukti dalam catatan sejarah yaitu pada tahun 830 M, al-Ma’mun membangun Bayt al-Hikmah (rumah kebijaksanaan), sebuah perpustakaan, akademi, sekaligus biro penerjemahan yang dalam berbagai hal merupakan lembaga pendidikan paling penting sejak berdirinya museum Iskandariyah pada paruh pertama abad ke-3 S.M. Dimulai pada masa al-Ma’mun, dan berlanjut pada masa penerusnya, aktivitas intelektual berpusat di akademi yang baru didirikan tersebut (Bayt al-Hikmah).61 Dari upaya penerjemahan yang dilakukan pada zaman peradaban Islam tersebut, kemudian lahir para sarjana, ilmuwan, dan filsuf Muslim dengan reputasi fenomenal dan dikenal sepanjang masa, seperti Abu Abdillah Muhammad ibn Musa al Khawarizmi seorang ahli matematika, falak, geografi, dan sejarah (w. 846 M); Abu Bakar al-Razi seorang ahli filsafat metafisika & logika, teologi, psikologi, fisika, geografi, optik, kimia, kedokteran, geometri, musik, dan politik (864/925 M); Abu Nashr al-Farabi seorang ahli filsafat, fisika, geometri, musik, dan kedokteran (874 /950M); Abu Ali Muhammad ibn Haitsam seorang ahli filsafat, geometri, ahli falak, sastra (965/1039 M); Abu Ali al Husayn ibn Abdullah ibn Sina ahli filsafat, kedokteran, geometri, aritmatika, bahasa, teologi, dan musik (980-1037 M). Abu Bakar ibn Thufail al-Qaisi 60 Ulama golongan ketiga ini yang lebih moderat dibanding kedua jenis ulama sebelumnya, salah satunya yaitu Abu Hamid al-Ghazali. Meskipun status moderat yang dialamatkan pada sosok al-Ghazali ini masih menimbulkan perdebatan yang alot, tapi hal ini bisa dilihat dari pandangan beberapa tokoh mengenai pemikirannya yang terkenal kontroversial tersebut. Menurut Zainul Hamdi (2004: 126), tuduhan antirasio yang dialamatkan pada al-Ghazali terkait kecamannya terhadap para filsuf (tertuang dalam kitab Tahafuth al-Falasifah) pada dasarnya tidak memiliki alasan yang kuat dan merupakan simplifikasi masalah yang tidak proposional. Yang dilakukan al-Ghazali hanyalah mendudukkan rasio manusia dalam batas-batas wilayahnya(limits of human mind). Senada dengan Zainul Hamdi, K.H. Husein Muhammad (2011: 95) dalam memahami pikiranpikiran al-Ghazali yang dianggap inkonsisten/ambigu tersebut, ia membayangkan kapasitas intelektual al-Ghazali yang beragam dan hampir menyeluruh itu tentunya menyebabkan al-Ghazali memilih pendekatan yang beragam dalam membahas persoalan umat. Sebagaimana al-Ghazali membagi tiga kelompok manusia (awam/orang umum, khawash/terpelajar, khawas al-khawas/para sufi), maka sudah barang tentu al-Ghazali akan menyampaikannya dengan cara berbeda, sesuai dengan kadar pikiran masingmasing. Misalnya, al-Ghazali akan menyampaikan kepada orang awam sebatas apa yang dapat mereka pahami, karena jika disampaikan terlalu rumit/filosofis maka dikhawatirkan akan menggoyahkan akidah mereka. 61 Philip K. Hitti, History of The Arabs, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 386. 32 seorang ahli filsafat, kedokteran, dan sastra (1106M/1185M), Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd seorang ahli filsafat, kedokteran, teologi, falak, fikih, dan nahwu (1126/1198 M), Waliyuddin Abdurrahman ibn Muhammad atau dikenal sebagai Ibn Khaldun seorang ahli filsafat, sosiologi, sejarah, al-hisab, politik, ekonomi, dan sastra (1332/1406 M), dan ribuan sarjana yang lain. Tidak disangsikan lagi, berkat merekalah ilmu pengetahuan dan peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya (al ‘ashr al-dzahabiy). Dengan begitu, jelaslah bahwa Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu agama saja (al-ulum al-diniyyah), tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan umum (al-ulum al-awa’il). Para ulama Islam generasi terdahulu tidak pernah membeda-bedakan kedua jenis ilmu tersebut. Sepanjang ilmu tersebut berguna bagi kemanusiaan, maka Islam akan memberikan apresiasinya, dari manapun sumbernya, Islam maupun non Islam. Jadi tak ada dikotomisasi, malahan Islam sangat menekankan keseimbangan (al-tawazzun) terhadap penguasaan dua jenis ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan dan filsafat dalam banyak pandangan ditafsirkan juga sebagai al-hikmah (kebijaksanaan). Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda: “Hikmah adalah barang hilang orang mukmin, di mana saja dia menemukannya hendaklah dia mengumpulkannya kembali (al-hikmah dhallah al mu’min haitsuma wajada al mu’min dhallah falyajma’ha ilaihi)”. Selain itu Allah SWT juga berfirman, “Allah menganugerahi hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka sesungguhnya dia dianugerahi kebaikan yang berlimpah” (Q.S. alBaqarah: 269).62 Prinsip al-I’tidal Secara bahasa, kata al-I’tidal berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Kata ini diambil dari kata al-adlu yang berarti keadilan atau í’dilu yang artinya bersikap adillah, sebagaimana firman Allah SWT: “Hai orangorang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang yang tegak membela kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Melihat terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Maidah: 8).63 Menurut Kiai Said Aqil, prinsip al-i’tidal mengacu pada kehidupan masyarakat yang berkeadilan, antara kelompok yang kaya (the have) dan kelompok miskin (the have not). Begitu pula keadilan dalam konteks kebudayaan dan politik, yang di dalamnya mencerminkan dimensi kesetaraan bagi segala kelompok, baik mayoritas maupun minoritas.64 62 63 64 K.H. Husein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, (Bandung: Penerbit al-Mizan, 2011), hlm. 50-51. K.H. Abdul Muchith Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran (Surabaya: Penerbit Khalista, 2007), hlm. 70. Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 141. 33 Tak perlu diragukan lagi, keadilan merupakan inti dari ajaran Islam, sebagaimana firman Allah SWT, “Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan yang haq (benar) dan dengan yang haq itu mereka menjalankan keadilan” (Q.S. al-A’raf: 181). Kiranya ayat tersebut menegaskan perintah berlaku adil dalam kehidupan umat manusia, sebab dengan cara yang demikian solidaritas di antara sesama muslim akan terbangun. Sehubungan dengan prinsip al-i’tidal ini, menarik kiranya untuk melihat upaya rekonstruksi yang dilakukan K.H. Sahal Mahfudh melalui paradigma fikih sosialnya65. Dalam upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, beliau melakukan terobosan mengenai konsep dakwah dan zakat. Dakwah yang selama ini lebih diartikan sebagai pengajaran masalah-masalah rohani diperluas maknanya menjadi suatu upaya mengubah keadaan menjadi lebih baik; dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju keterdidikan, dari kemiskinan menuju kecukupan, dari keterbelakangan menuju kemajuan, dan semua itu ditujukan untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sesuai ajaran agama Islam (din al-islam)66. 65 Kiai Sahal selalu menjelaskan secara detail definisi fikih untuk dijadikan titik acuan gagasan fikih sosialnya. Definisi fikih adalah ilmu hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Pada dasarnya definisi tersebut mengandung tiga substansi dasar yang sangat krusial. Pertama, ilmu fikih adalah ilmu yang paling dinamis karena ia menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial (af’al al-mukallifin) yang selalu mengalami perubahan. Kedua, ilmu fikih sangat rasional, mengingat ia adalah ilmu iktisab (ilmu hasil kajian, analisis, penelitian, generalisasi, konklusi). Di sini terjadi kontak sinergis antara sumber transedental (nash) dan akal (ijtihad). Ketiga, fikih adalah ilmu yang menekankan pada aktualisasi (amaliah). Di sini kelihatan paradigm berpikir Kiai Sahal yang rasional, analitis, dan filosofis. Beliau mampu menangkap spirit/ruh transformatif dalam fikih. Karena itulah, kajian fikih harus menggunakan optimalisasi rasio dan kemampuan analisis, sehingga fikih tidak menjadi ajaran yang bersifat dogmatik, rigit, dan eksklusif. Fikih harus berhubungan secara erat dan sinergis dengan problematika manusia, karena fungsi fikih adalah mengarahkan, mendorong, dan meningkatkan perilaku manusia agar sesuai dengan tuntutan agama. Perilaku manusia tentu tidak terbatas pada ibadah mahdhah (ritual-formal) yang sangat terbatas, namun juga mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kependudukan, dan kebudayaan. Dengan itulah fikih menjadi actual dan relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman (Jamal Ma’mur Asmani, Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi, [Surabaya: Penerbit Khalista, 2007], hlm. 55-56). 66 Kiai Sahal selalu menekankan kajian mendalam tentang pengertian din (agama), yaitu: “Ketentuan Ketuhanan yang mendorong orang berakal sehat untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat”. Dari definisi ini Kiai Sahal menyimpulkan bahwa syari’at/agama tidak hanya berkutat dalam masalah hubungan vertical-transedental (hablun min allah) ansich, seperti salat, zakat, puasa, haji, dsb, tapi juga mengembang dalam wilayah profan-transedental (hablun min al-nas), seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, SDM, dsb. Bergulat dalam wilayah itu tidak ada yang lebih diutamakan. Keduanya sama-sama penting, saling melengkapi, sinergis, dan kombinatif. Sehingga tidak ada yang namanya dikotomi, demarkasi, polarisasi, segmentasi 34 Dalam mengatasi kemiskinan, dakwah Islam bisa ditempuh dengan dua cara. Pertama, memberi motivasi kepada kaum muslimin yang mampu untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Sebab akhir-akhir ini, di kalangan umat Islam ada kecenderungan menurunnya solidaritas sosial itu. Tentu saja hal itu jangan dilihat sebatas hal yang verbalis67 saja karena ia akan sangat tergantung kepada pendekatan yang dipergunakan. Kedua, yang paling mendesak adalah dakwah dalam bentuk aksi-aksi nyata dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan. Ini disebut dakwah bi al-hal. Menurut Kiai Sahal, dakwah dalam bentuk kedua ini sebenarnya sudah banyak dilaksanakan kelompok-kelompok Islam, namun mereka masih melaksanakannya secara sporadis dan tidak dilembagakan sehingga menimbulkan efek kurang baik, misalnya dalam membagikan zakat68. Akibatnya, menjadikan kaum fakir miskin dalam menerima zakat tersebut berkecenderungan menjadi orang yang tamak. Hal itu dikarenakan teknis pembagian zakat yang tidak dikelola dengan baik. 69 Prinsip al-Tasamuh Prinsip-prinsip al-tawassuth, al-tawazzun, al-i’tidal sebagaimana diuraikan di atas, pada gilirannya meniscayaan sebuah keterbukaan pikiran antara wilayah agama dan non-agama. Semua masuk wilayah agama secara komprehensif (kaffah) (ibid, hlm. 53-54). 67 Sehubungan dengan hal ini, terdapat kaidah fikih yang berbunyi, “memfungsikan perkataan lebih utama dari pada membiarkannya (I’mal al-kalam aula min ihmalihi).” Kalau orang yang berilmu diam terus, khawatir pada hal-hal yang membawa dosa, lantas bagaimana dengan misi memberantas kebodohan, mengentaskan kemiskinan, tentu tidak bisa hanya dengan berucap saja tanpa tindakan nyata. Ucapan harus diiringi dengan tindakan kongkret untuk hal-hal yang positif-konstruktif, dan berhati-hati agar terhindar dari hal-hal negative-destruktif. 68 Menurut Kiai Sahal, zakat harus dijadikan senjata ampuh bagi pengentasan kemiskinan. Caranya adalah dengan mengelola harta zakat secara produktif melalui sebuah lembaga yang tentunya harus handal, professional, dan beorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harus ada monitoring dan evaluasi agar tujuan zakat terealisir secara maksimal. Dalam praktiknya, Kiai Sahal telah menerapkan model zakat di atas pada tiga desa di lingkungan tempat beliau tinggal. Memang, ketentuan zakat secara formal (fikih klasik) mengharuskan agar diberikan langsung kepada mustahiq (penerima zakat) dan tidak boleh ditukar dengan bentuk yang lain. Untuk menyiasatinya – di samping juga harus hati-hati pula agar tidak bertentangan dengan ketentuan agama, beliau tetap memberikan harta zakat kepada mustahiq. Langkah ini dilakukan agar akad zakat tetap terpenuhi. Kemudian beliau menariknya kembali sebagai modal yang akan dikelola lembaga koperasi rintisannya. Setelah modal tersebut dirasa cukup bertambah, kemudian dirupakan sesuatu yang lebih produktif. Kalau si mustahiq membutuhkan becak, maka diberilah becak; kalau mustahiq mempunyai keterampilan menjahit maka diberilah mesin jahit. Dengan demikian, meskipun masalah kemiskinan tidak dapat dihapuskan atau dilenyapkan sama sekali, paling tidak ada upaya untuk menguranginya. Rupanya, ikhtiar Kiai Sahal dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat tersebut diilhami oleh sebuah kaidah fikih yang berbunyi, “Sesuatu yang tidak dapat dicapai/diupayakan semuanya, bukan berarti semuanya itu harus ditinggalkan (ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu). 69 Samsul Munir Amin, Percikan Pemikiran Para Kiai, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 151. 35 (broadmindedness). Dengan demikian, pernyataan tersebut tentunya membawa implikasi logis bahwa manusia, siapapun dia dan apa latar belakangnya, selalu dituntut untuk saling menghargai sesamanya, bekerja bersama-sama, dan berkontestasi untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, keadilan bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara lebih luas. Sayangnya, dewasa ini terdapat banyak kasus intoleransi antara umat beragama dan kekerasan terhadap yang lain, yaitu terkait dengan kehendak untuk memaksakan pikiran, ideologi, agama, tindakan, dan sebagainya. Ini sering kali muncul karena masing-masing individu/kelompok menganggap bahwa pikiran dirinyalah sebagai satu-satunya kebenaran. Sementara pikiran, ideologi, agama, keyakinan, budaya, persepsi, pandangan, dan perasaan liyan (the other) tidak masuk dalam kesadarannya sebagai subjek yang juga berpikir dan memiliki hak atas kebenaran yang diperolehnya. Cara pandang seperti ini telah menafikan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang merdeka dan harus dihargai atau dihormati.70 Dengan demikian, kebenaran hanya dimonopoli oleh kelompok tertentu, dan akibatnya kelompok lain menjadi tereksklusi dari kebenaran. Cara pandang seperti ini sungguh bertentangan dengan pesan dan visi Islam sendiri, sebagaimana firman Allah SWT, “Tidak (boleh) ada paksaan dalam agama” (Q.S. al-Baqarah: 256). Di ayat lain Allah SWT juga berfirman, “Dan sekiranya Allah SWT tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah (sinagog) kaum Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (Q.S. al-Hajj: 40). Islam sebagai agama rahmatan li al-alamin mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap toleran (al-tasamuh) demi terciptanya kehidupan yang damai dan rukun di tengah-tengah realitas kehidupan yang plural. Meskipun kehidupan ini dipenuhi keragaman suku, ras, budaya, agama, namun semua adalah ciptaan Allah SWT. Prinsip Tauhid ini pada gilirannya meniscayakan pandangan dunia (weltanschauung) seorang Muslim bahwasanya manusia adalah sederajat dan setara, hanya bentuk ketakwaanlah yang membedakan satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu” (Q.S. al-Hujurat: 13). Dengan menyimak uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi paham Ahlussunnah wal-jama’ah yang menghasilkan rumusan manhaj al-fikr tersebut merupakan sebuah fase lompatan yang sangat luar biasa, terutama dalam menegaskan Islam sebagai sumber segala inspirasi, spirit, pengetahuan, dan 70 K.H. Hussein Muhammad, Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, (Bandung: Penerbit al-Mizan, 2011), hlm. 17. 36 praksis yang mendorong umatnya semakin kreatif, inovatif, dan progresif dalam menghadapi segala tantangan perubahan zaman. Definisi Ahlussunnah walJama’ah yang paling mutakhir ini (sebagai manhaj al-fikr) akan memberikan corak pemahaman baru yang tidak hanya dapat mengapresiasi khazanah klasik ke dalam dengan sangat baik, tapi juga ke luar, misalnya hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan urusan sosial-kemasyarakatan. Penutup Demikianlah, pokok-pokok pikiran mengenai Ahlussunnah wal-Jama’ah yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, maupun diskursus untuk mengembangkan wacana keagamaan. Pembahasan pertama diawali dengan uraian sejarah Ahlussunnah wal-Jama’ah. Topik ini dirasa penting mengingat setiap pemikiran apapun bentuknya tidak pernah lepas dari kondisi sosial-budaya yang melingkupinya. Karena ia adalah respons terhadap kondisi ri’il yang terjadi. Demikian pula, paham Ahlussunnah wal-Jama’ah merupakan hasil dari pada akumulasi respon atas berbagai macam kasus sesuai lika-liku gerak sejarah, yaitu dimulai dari masa awal kemunculannya (risalah Nabi SAW) hingga tiba masa generasi sekarang. Dalam menyikapi hal ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali mempelajari paham Ahlussunnah wal-Jama’ah tersebut dengan disertai pijakan yang kuat pada akar historis. Pemahaman yang tidak berpijak pada akar sejarah bisa dipastikan akan mengakibatkan pada keterputusan historis yang pada akhirnya akan membentuk suatu generasi yang latah, pongah, dan sok islami. Inilah kenyataan yang sedang menjangkiti generasi kita sekarang di mana kebanyakan orang lebih mementingkan simbolsimbol agama, namun kering dari substansinya yang jauh lebih penting. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai hakikat dan pengertian Ahlussunnah wal-Jama’ah. Hakikat Ahlussunnah wal-Jama’ah ialah Islam sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Dengan demikian, maka dapat dihindari kesalahpahaman dari praduga untuk mengalamatkan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas pada para sahabat Rasulullah SAW yang terlibat konflik. Karena perbuatan ini jelas menyalahi hadis Nabi SAW. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah untuk menghindari klaim “paling benar sendiri” yang dilontarkan sejumlah pihak hanya karena merasa sudah Ahlussunnah walJama’ah. Dengan mempertimbangkan posisi spasio-temporal kita yang terpaut jauh dari Rasulullah SAW, maka konsekuensi logisnya ialah bahwa kondisi keaswajaan kita ini tidak mesti seratus persen. Karena itu, segala penyikapan atas perbedaan harus bertumpu pada landasan etika deskriptif. Artinya, kita menyikapi perbedaan itu demikianlah adanya, apa adanya. Mengingat sesat tidaknya seseorang bukanlah urusan kita, tapi hal itu seluruhnya bergantung pada keputusan Allah SWT. Adapun uraian mengenai pengertian Ahlussunnah wal-Jama’ah (Aswaja) dimaksudkan untuk memberikan sebuah kerangka pemahaman tentang terminologi Aswaja dalam rumusan dan batasan yang jelas. Dengan cara ini, maka tindakan serba kompromistis dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisme) dapat dihindari. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan 37 tindakan yang serba kompromistis itu akan semakin mengaburkan Islam yang direpresentasikan oleh Ahlussunnah wal-Jama’ah. Memang, upaya untuk merumuskan pengertian Aswaja itu tidak dapat dilepaskan dari hakikat Aswaja itu sendiri. Adapun yang menghubungkan dua hal tersebut adalah laku mengetahui (mengerti). Dalam hal ini, terdapat dua macam penyikapan, secara positif atau negatif. Penyikapan secara negatif harus dihilangkan. Kalau ini dibenarkan, maka segala upaya untuk membangun pengertian Aswaja ini akan terus-menerus dicurigai sebagai reduksi Aswaja dalam arti hakikatnya. Akan tetapi, bukankah satu-satunya cara untuk mencapai (baca: mendekati) hakikat Aswaja itu adalah dengan memberikan rumusan pengertian yang baku atasnya? Bukankah Socrates telah mengajarkan kepada kita bahwa ucapan yang dimengerti berbeda dari ucapan biasa, bahwa budi ialah mengerti? Karena yakin akan perbedaan itu, maka harus ada ikhtiar tiada henti untuk memperjuangkan kebenaran melalui laku mengerti tersebut. Kalaupun memang kebenaran yang kita upayakan melalui laku mengerti itu tidak sepenuhnya dapat kita capai, maka kita anggap saja ia hanya berperan dalam proses penemuan, bukan dalam proses pembenaran. Adapun bagian ketiga merupakan upaya penajaman paham Ahlussunnah wal-Jama’ah yang sudah dibakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi segala unsur-unsur yang menyalahi aturan pokok yang sudah ditetapkan. Proses identifikasi tersebut menghasilkan konsepsi mengenai bid’ah. Konsep ini perlu dielaborasi sedetail mungkin agar semakin mudah dilakukan pemetaan antara perkara yang benar dan yang telah menyimpang. Jika hal ini diabaikan, maka akan berakibat fatal mengingat konsep ini menyangkut identitas (sesat tidaknya) seorang Muslim. Hal ini dikarenakan term bid’ah merupakan lawan dari term sunnah. Keduanya memiliki perbedaan yang jelas, sehingga makna keduanya tidak bisa saling bertumpang tindih. Pada bagian selanjutnya, pembahasan diarahkan pada pendekatan Ahlussunnah wal-Jama’ah melalui metode bermadzhab. Seringkali, pandangan bermadzhab ini dianggap sebagai cara yang sudah usang dan tidak akomodatif terhadap tuntutan dan perubahan zaman. Agaknya anggapan demikian merupakan sebuah simplifikasi masalah yang tidak proposional dan tidak berdasar. Upaya bermadzhab merupakan keniscayaan intelektual karena realita sekarang sangat sulit untuk menemukan para ulama yang memiliki kapasitas pemahaman yang otoritatif. Bahkan, ketentuan ulama tersebut tidak cukup hanya mumpuni secara intelektual saja, tapi juga harus memiliki integritas, kepribadian yang paripurna, sikap hidup yang bersahaja, kepeduliaan sosial yang tinggi, di mana semua itu termanifestasikan dalam kehidupan nyata. Sepertinya sulit – untuk tidak mengatakan mustahil – menjumpai ulama yang memiliki kriteria komplet di atas. Jika dengan jujur kita mau mengakui segala keterbatasan ini, maka kita mau tidak mau harus ber-taqlid (bermadzhab) mengikuti ajaran para imam madzhab. Selain metode bermadzhab, Ahlussunnah wal-Jama’ah juga diperlakukan sebagai metode berfikir (manhaj al-fikr). Ini merupakan buah dari revitalisasi paham Ahlussunnah wal-Jama’ah dalam menghadapi segala 38 perubahan dan tantangan zaman. Dengan demikian, diharapkan paham ini senantiasa kompatibel terhadap persoalan kekinian. Melalui pendekatan manhaj al-fikr ini, Ahlussunnah wal-Jama’ah menjadi sesuatu yang fleksibel, inovatif, solutif, sehingga jauh dari kesan kejumudan/kemandegan dalam beragama. Penting untuk diketahui, pendekatan ini (manhaj al-fikr) bukanlah untuk menegasikan makna paham Ahlussunnah wal-Jama’ah dengan metode bermadzhab. Justru keduanya bersifat sinergis dan saling melengkapi, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi “al-Muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik). Seringkali penggunaan istilah ‘metode’ pada Aswaja ini dianggap sebagai kerancuan yang berdampak fatal. Dinamakan metode (al-manhaj), berarti Aswaja itu hanya sebatas alat/cara (tools/instruments). Konsekuensinya, apakah ia bisa diganti dengan yang lain? Bukankah ia merupakan agama (Islam) itu sendiri yang tidak boleh diganti? Sebagai metode bermahdzab dan metode berpikir, tentu saja ia memungkinkan dirubah/diganti dengan yang lain. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa perubahan itu bukanlah mengarah pada Ahlussunnah walJama’ah dalam arti hakikatnya, yaitu Islam yang diajarkan dan dipraktikkan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Jadi, perlu ditegaskan kembali bahwasanya perubahan hanya mungkin terjadi pada konsepsi Ahlussunnah walJama’ah sejauh yang dipahami, baik melalui metode bermadzhab maupun metode berpikir (manhaj al-fikr). Apalagi, segala bentuk pemahaman mengenai Ahlussunnah wal-Jama’ah – baik melalui upaya bermadzhab ataupun manhaj alfikr – senantiasa mengandaikan keterbatasan pada laku mengetahui manusia. Hal ini mengingat posisi spasio-temporal kita yang terpaut jauh dari masa kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, berbicara mengenai Ahlussunnah wal-Jama’ah dalam konteks kemurniannya senantiasa mensyaratkan upaya pendekatan yang paling mungkin diterapkan kepadanya. Sehubungan dengan hal ini, para ulama Islam sepakat bahwa pendekatan apapun yang digunakan, sungguh tidak menjadi masalah sepanjang makna yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip, norma-norma, atau nilai-nilai universal Islam. Ada ungkapan yang berbunyi “Fa ma wafaq al-syar’a fa huwa shahih”, artinya apa yang sejalan dengan agama adalah benar (shahih). Ringkasnya, pemahaman Ahlussunnah wal-Jama’ah yang dirumuskan melalui pendekatan bermadzhab dan manhaj al-fikr di atas merupakan model pendekatan yang dilakukan secara tepat dan cermat. Dikatakan tepat, karena mengacu pada hasil ijtihad para ulama yang sudah cukup teruji melalui mekanisme ijma’ (kesepatakan para ulama’), dan dikatakan cermat karena mengacu pada sejumlah parameter penting (al-tawassuth, al-tawazzun, ali’tidal, dan al-tasamuh) dalam mendeduksikan persoalan partikular kekinian yang tidak cukup memadai bila hanya mengacu pada produk-produk pemikiran ulama madzhab. Terakhir, penting untuk ditekankan bahwa Aswaja bukanlah sebuah ideologi sebagaimana anggapan beberapa kalangan. Ideologi merupakan hasil 39 serangkaian penyikapan terhadap berbagai macam pengalaman hingga akhirnya membentuk suatu sistem nilai dan keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran. Dengan mengacu pada pengertian ini, maka ia mengandung tiga karakteristik fundamen. Pertama, ideologi bersifat subyektif karena ia berupa akumulasi pengalaman. Kedua, ideologi dihasilkan dari simplifikasi untuk mengatasi kompleksitas sesuatu yang sulit dipahami. Ketiga, ideologi berkonotasi ketidak-berubahan hingga pada taraf tertentu mensugestikan sebuah kecenderungan ke arah ‘pemberhalaan’ dan propaganda. Dengan demikian, ideologi hanyalah sesuatu yang dipenuhi ilusi (kesemuan), bersifat kaku, dan manipulatif. Ia yang sepenuhnya dilahirkan dari kehidupan duniawiah, sehingga wujudnya pasti bersifat fana’ (lekang zaman). Sedangkan Ahlussunnah wal-Jama’ah hakikatnya ialah Islam, berupa wahyu Ilahi, kalamullah yang qadim (tidak terbingkai ruang-waktu). Kebenarannya pasti mutlak (haq) sebagaimana cerminan dari Sang Pemilik Kebenaran (Allah SWT). Maka, bagaimana mungkin dua hal yang berbeda ini bisa disatukan, antara yang haqiqi dan yang berupa bayang-bayang semu? Apalagi watak ‘penyeragaman’ yang intrinsik dalam ideologi itu akan berdampak pada pemberhalaan dirinya. Islam sebagai agama tauhid tentunya menolak penuhanan terhadap semua ciptaan yang disamakan dengan Penciptanya. Akhirnya, Ahlussunnah wal-Jama’ah (Aswaja) yang dianut PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) adalah model Aswaja yang memadukan dua pendekatan, yaitu metode bermahdzab dan metode berpikir (manhaj al-fikr). Aswaja yang dianut PMII tidak bisa dikatakan sebagai ideologi. Selain bertentangan dengan prinsip ketauhidan, ideologisasi Aswaja juga tidak sesuai diterapkan dalam konteks ke-Indonesia-an yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, etnik, dan budaya. Sejak awal berdirinya negara ini, Pancasila telah diterima semua kalangan sebagai asas bernegara yang mempersatukan segala perbedaan tersebut. Dengan demikian, semua elemen masyarakat yang tergabung dalam Negara Republik Indonesia harus menerima Pancasila ini sebagai satu-satunya asas/ideologi. Apakah PMII akan menolak ketentuan pemerintah tentang asas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi? Di sinilah, kemampuan Aswaja sebagai metode bermadzhab dan metode berpikir (manhaj al-fikr) terlihat keluwesannya dalam menghadapi tuntutan akan penerimaan asas Pancasila tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan fikih (mahdzab) yang disertai penerapan prinsip-prinsip ke-Aswaja-an (manhaj al-fikr), asas Pancasila itu diterima PMII sebagai asas organisasinya. Hal ini dikarenakan asas Pancasila adalah salah satu persyaratan bagi keabsahan Negara Republik Indonesia. Karena eksistensi Negara ini sudah diterima keabsahannya sejak awal ia berdiri, maka secara fikih hukum untuk menerima asas Pancasila itu adalah wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah, “Apabila sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu juga hukumnya wajib (ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib).” Dasar inilah yang menjadikan PMII tidak memiliki alasan apapun untuk menolak Pancasila 40 sebagai asas organisasinya. Apalagi, asas Pancasila tersebut tidak berfungsi untuk menggantikan kedudukan agama (Aswaja) dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam konteks demikian, Islam (Aswaja) dapat saja diletakkan dalam kedudukan dan waktu yang berlainan dalam kehidupan organisasi PMII ini. Sehingga pada perkembanganya nanti akan terlihat, Islam dijadikan asas keorganisasian (AD/ART dan NDP), pada saat lain dijadikan landasan keimanan (akidah). 41 HISTORISITAS PMII DAN GENEOLOGI GERAKAN MAHASISWA Nur Sayyid Santoso Kristeva., M.A. SEKILAS HISTORISITAS PMII Secara historis PMII berdiri pada tahun 1960. Kondisi sosial politik waktu itu sedang terjadi rebutan kekuasaan antara kaum Islam modernis dengan kalangan NASAKOM (NasionaIis, Agarna dan Komunis). Pada waktu itu kekuasaan yang dekat adalah PKI dengan orang-orang tradisionalis dan nasionalis. Karena ketiga kelompok ini meiliki titik temu dalam garis perjuangan maupun pandangan politiknya. Pada pemilu tahun 1955 PKI dan NU memiliki suara yang sangat signifikan dibangding dengan partai yang lainnya. Semua partai politik mempunyai sayap poIitik ditingkat mahasiswa, antara lain; Masyumi-HMI, PKI-CGMNI, PMI-GMNI. Saat itu terjadi konflik ditingkat HMI yang saat itu merupakan satu-satunya organisasi mahasiswa Islam. Kebetulan dalam organisasi ini banyak pula kader-kader NU, yang merasa tidak cocok dengan strategi dan kebijakan organisasi. Sehingga akhimya Mahbub Junaidi, dkk, keluar dari HMI dan membentuk PMII untuk mewadahi mahasiwa tradisionalis di Surabaya pada tanggal16 April 1960. Pada awalnya PMII juga merupakan Under-Bow NU, yang kemudian melepaskan diri dari cengkeraman partai pada tahun 1972 dengan deklarasi Munarjati. Pasca kudeta militer tahun 1966 kondisi sosial politik berubah total. Semua pos-pos penting diisi oleh tentara. Kekuatan Islam akomodatif dan konfrontatif dengan negara pada masa ORLA ditimbulkan karena keduanya tidak bisa diajak untuk menciptakan stabilitas keamanan. Dengan ideologi developmentaIisme negara korporasi ORBA menrapkan kebijakan pembangunan sebagai pangIima untuk mengontrol kesejahteraan kelas menengah, hutang besar-besaran dan WorId Bank digunakan untuk membangun berbagai proyek yang menguntungkan pemilik modal dan orang kota. Pada dataran inilah PMII dengan semangat kerakyatan dan kebangsaan berada di garis perjuangan membela rakyat tertindas. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu elemen mahasiswa yang terus bercita-cita mewujudkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. PMII berdiri tanggal 17 April 1960 dengan latar belakang situasi politik tahun 1960-an yang mengharuskan mahasiswa turut andil dalam mewarnai kehidupan sosial politik di Indonesia. Pendirian PMII dimotori oleh kalangan muda NU (meskipun di kemudian hari dengan dicetuskannya Deklarasi Murnajati 14 Juli 1972, PMII menyatakan sikap independen dari lembaga NU). Di antara pendirinya adalah Mahbub Djunaidi dan Subhan ZE (seorang jurnalis sekaligus politikus legendaris). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) lahir karena menjadi suatu kebutuhan dalam menjawab tantangan zaman. Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bermula dengan adanya hasrat kuat para mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlusssunnah wal Jama'ah. Dibawah ini adalah beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai penyebab berdirinya PMII: 1. Carut marutnya situasi politik bangsa indonesia dalam kurun waktu 19501959. 42 2. Tidak menentunya sistem pemerintahan dan perundang-undangan yang ada. 3. Pisahnya NU dari Masyumi. Hal-hal tersebut diatas menimbulkan kegelisahan dan keinginan yang kuat di kalangan intelektual-intelektual muda NU untuk mendirikan organisasi sendiri sebagai wahana penyaluran aspirasi dan pengembangan potensi mahasiswa-mahasiswa yang berkultur NU. Disamping itu juga ada hasrat yang kuat dari kalangan mahsiswa NU untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang berideologi Ahlussunnah Wal Jama’ah. Organisasi-organisasi Pendahulu Di Jakarta pada bulan Desember 1955, berdirilah Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) yang dipelopori oleh Wa'il Harits Sugianto.Sedangkan di Surakarta berdiri KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama) yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Namun keberadaan kedua organisasi mahasiswa tersebut tidak direstui bahkan ditentang oleh Pimpinan Pusat IPNU dan PBNU dengan alasan IPNU baru saja berdiri dua tahun sebelumnya yakni tanggal 24 Februari 1954 di Semarang. IPNU punya kekhawatiran jika IMANU dan KMNU akan memperlemah eksistensi IPNU. Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU muncul kembali pada Muktamar II IPNU di Pekalongan (1-5 Januari 1957). Gagasan ini pun kembali ditentang karena dianggap akan menjadi pesaing bagi IPNU. Sebagai langkah kompromis atas pertentangan tersebut, maka pada muktamar III IPNU di Cirebon (27-31 Desember 1958) dibentuk Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang diketuai oleh Isma'il Makki (Yogyakarta). Namun dalam perjalanannya antara IPNU dan Departemen PT-nya selalu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program organisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang yang diterapkan oleh mahasiswa dan dengan pelajar yang menjadi pimpinan pusat IPNU. Disamping itu para mahasiswa pun tidak bebas dalam melakukan sikap politik karena selalu diawasi oleh PP IPNU. Konferensi Besar IPNU Oleh karena itu gagasan legalisasi organisasi mahasiswa NU senantisa muncul dan mencapai puncaknya pada konferensi besar (KONBES) IPNU I di Kaliurang pada tanggal 14-17 Maret 1960. Dari forum ini kemudian kemudian muncul keputusan perlunya mendirikan organisasi mahasiswa NU secara khusus di perguruan tinggi. Selain merumuskan pendirian organ mahasiswa, KONBES Kaliurang juga menghasilkan keputusan penunjukan tim perumus pendirian organisasi yang terdiri dari 13 tokoh mahasiswa NU. Mereka adalah: 1. Khalid Mawardi (Jakarta) 2. M. Said Budairy (Jakarta) 3. M. Sobich Ubaid (Jakarta) 4. Makmun Syukri (Bandung) 5. Hilman (Bandung) 6. Ismail Makki (Yogyakarta) 7. Munsif Nakhrowi (Yogyakarta) 8. Nuril Huda Suaidi (Surakarta) 9. Laily Mansyur (Surakarta) 43 10. Abd. Wahhab Jaelani (Semarang) 11. Hizbulloh Huda (Surabaya) 12. M. Kholid Narbuko (Malang) 13. Ahmad Hussein (Makassar) Keputusan lainnya adalah tiga mahasiswa yaitu Hizbulloh Huda, M. Said Budairy, dan Makmun Syukri untuk sowan ke Ketua Umum PBNU kala itu, KH. Idham Kholid. Deklarasi Pada tanggal 14-16 April 1960 diadakan musyawarah mahasiswa NU yang bertempat di Sekolah Mu’amalat NU Wonokromo, Surabaya. Peserta musyawarah adalah perwakilan mahasiswa NU dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar, serta perwakilan senat Perguruan Tinggi yang bernaung dibawah NU. Pada saat tu diperdebatkan nama organisasi yang akan didirikan. Dari Yogyakarta mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunny. Dari Bandung dan Surakarta mengusulkan nama PMII. Selanjutnya nama PMII yang menjadi kesepakatan. Namun kemudian kembali dipersoalkan kepanjangan dari ‘P’ apakah perhimpunan atau persatuan. Akhirnya disepakati huruf "P" merupakan singkatan dari Pergerakan sehingga PMII menjadi “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”. Musyawarah juga menghasilkan susunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi serta memilih dan menetapkan sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum. Ketiga orang tersebut diberi amanat dan wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan PB PMII. Adapun PMII dideklarasikan secara resmi pada tanggal 17 April 1960 masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1379 Hijriyah. SEMUA itu berkat IPNU. Independensi PMII Pada awal berdirinya PMII sepenuhnya berada di bawah naungan NU. PMII terikat dengan segala garis kebijaksanaan organisasi induknya, NU. PMII merupakan perpanjangan tangan NU, baik secara struktural maupun fungsional. Selanjuttnya sejak dasawarsa 70-an, ketika rezim neo-fasis Orde Baru mulai mengkerdilkan fungsi partai politik, sekaligus juga penyederhanaan partai politik secara kuantitas, dan issue back to campus serta organisasi- organisasi profesi kepemudaan mulai diperkenalkan melalui kebijakan NKK/BKK, maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. 14 Juli 1971 melalui Mubes di Murnajati, PMII mencanangkan independensi, terlepas dari organisasi manapun (terkenal dengan Deklarasi Murnajati). Kemudian pada kongres tahun 1973 di Ciloto, Jawa Barat, diwujudkanlah Manifest Independensi PMII. Namun, betapapun PMII mandiri, ideologi PMII tidak lepas dari faham Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan ciri khas NU. Ini berarti secara kultural- ideologis, PMII dengan NU tidak bisa dilepaskan. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan benang merah antara PMII dengan NU. Dengan Aswaja PMII membedakan diri dengan organisasi lain. Keterpisahan PMII dari NU pada perkembangan terakhir ini lebih 44 tampak hanya secara organisatoris formal saja. Sebab kenyataannya, keterpautan moral, kesamaan background, pada hakekat keduanya susah untuk direnggangkan. Dari namanya PMII disusun dari empat kata yaitu “Pergerakan”, “Mahasiswa”, “Islam”, dan “Indonesia”. Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan kontribusi positif pada alam sekitarnya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalifahannya. Pengertian “Mahasiswa” adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dimnamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan negara. “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma ahlussunah wal jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, islam, dan ikhsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan transformatif demikian platform PMII, yaitu Islam yang terbuka, menerima dan menghargai segala bentuk perbedaan. Keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized). Sedangkan pengertian “Indonesia” adalah masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 45. Pelacakan Gerakan Mahasiswa Level Makro Kecenderungan menguatnya neo-Iiberalisme terjadi dimana-mana, terutama di negara berkembang atau negara dunia ketiga. Kecenderungan itu ditunjukkan oleh peran membesar yang dipermainkan oleh berbagai intitusi perekonomian dunia, seperti; International Monetary fund (IMF), International Bank for Recontruction of Development (IBRD), World Trade Organization (WTO). Institusi yang didukung penuh oleh negara-negara maju begitu ganas mempromosikan struktur perekonomian dunia yang leizes-fair (membiarkan sesuai mekanisme pasar) dan meminimalisir campur tangan negara yang dihegemoni. Neo-liberalisme temyata menjadi gurita panas yang mengecam kekuatan ekonomi di negara berkembang. Pandangan bebasa ini menjadi paradoks dengan sedemikian rupa mengatur mekanisme perekonomian dunia. Dengan melihat struktur perekomian negara-negara pheriphery bisa disimpu1kan bahwa kecenderungan neoliberalisme ini sangat mempengaruhi 45 perekonomian di tingkat akar rumput. Mainstream kapitalisme global dengan wajah baru telah merasuk dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kebijakan di masing-masing negara berkembang. Menghadapi konsekuensi buruk kapitalisme global dan neoIiberalisme itu menjadi tesis runtuhnya negara berkembang. Perkembangan global kontemporer dipicu oleh perkembangan teknologi produksi, informasi, telekomunikasi, dan globalisasi. Kekuatan negara menjadi sernakin rapuh untuk mengontrol fluktuasi ekonomi politik. Keterpurukan negara berkembang setelah tidak bisa mengembalikan tatanan ekonomi ditambah lagi dengan pengabaian Human Right (HAM), komflik etnis, pelecehan seksual, eksploitasi buruh, konflik atas nama agama, inkonsistensi para birokrat, dan sekian rnasalah yang menjadi entitas problem. Dalam hal perekonomian ciri-ciri struktur keterbelakangan negara indonesia diindikasikan dalam bemagai faktor kehidupan. Salah satu yang menjadi momok besar atau kesulitan menjadi negara maju adalah bahwa Indonesia tidak sanggup untuk bergabung dengan kapitalisme global, teritama sejak ORBA berkuasa tahun 60-an. Indonesia temyata msuk dalam kungkungan anak kandung kapitalisme yaitu developmentalisme (pembangunanisme). Ideologi developmentalisme temyata memaksa Indonesia untuk larut dalam gaya pembangunan kapitalis yang direpresentasikan melauli kebijakan negara yaitu REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), kebijakan ini berdampak pada jaminan kesestabilan politik untuk menarik investor asing. Kestabilan politik ORBA ini dicapai dengan melakukan tindakan yang sangat dominatif dan bersifat Otoritarian-Birokratik terhadap kedaulatan rakyat. Indikasi dari gaya pemerintahan Otoritarian-Birokratik adalah berkuasanya militer secara institusional, penyingkaran dari partisipasi, kooptasi terhadap organisasi massa. Gaya pemerintahan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan filsafat trickle down effek mengisaratkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang Iebih tinggi harus dicapai terlebih dahulu sebelum dibagikan secara m.erata kepada seluruh masyaraka - harus dibayar dengan diberangusnya hak-hak politik rakyat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tinggi ini hanya dinikmati oleh minoritas-hal ini berdampak terjadinya kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Strategi Gerakan Sosial Empat landasan dalam menyusun strategi gerakan sosial, yaitu: Pertama, Ideologi, dasar filosofi gerakan merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan pergerakan mahasiswa. Sebuah institusi kemahasiswaan yang mengemban idealisme yang tinggi harus memakai filsafat gerakan pembebasan (liberasi) dan kemandirian (interdependensi). Liberasi adalah sebuah metode alternatif untuk mencapai kebebasan individu, sehingga individu tersebut mempunyai kualitas dan mental yang kuat untuk mendobrak dan menggeser kekuasaan negara yang represif dan totaliter dan melakukan perlawaman atas ekspansi hegemoni negara, untuk mengembalikan kekuasaan tersebut kepada otoritas dan kedaulatan rakyat. Liberasi ini juga memberikan kebebasan berekspresi dan kebebasan berfikir tanpa dipasung oleh sebuah rezim. lnterdependensi adalah kemandirian dalam mengembangkan kreatifitas, 46 keterbukaan, rasa tanggungjawab dalam dinamika pergerakan untuk membangun moralitas dan intelektualitas sebagai senjata dan tameng dalam setiap aksi. Aksi yang diiringi dengan interdependensi akan mewujudkan kesadaran mahasiswa dalam menjaga jarak dan hubungan dengan kekuasaan, sehingga aksi mahasiwa merupakan kekuatan murni untuk membela kepentingan rakyat dan melakukan transformasi sosial tanpa terkooptasi oleh kepentingan politik kelompok manapun. Kedua, Falsafah Gerakan, strategi ini lebih kepada falsafah bertindak dengan model pendekatan (appoach methode). Dalam pendekatan ini gerakan mahasiswa berupaya mengambil jarak dengan negara tanpa menafikan keberadaan dan legitirnasinya, sehingga kekuatan negara dapat diimbangi oleh kekuatan masyarakat. Model pendekatan ini adalah proses; (a) transformasi dari orientasi massa ke individu, (b) transformasi dari struktur ke kultur, (c) transfornzasi dari elitisme ke populisme, (d) transformasi dari negara ke masyarakat. Ketiga, Segmenting, strategi ini merupakan pilihan wilayah gerak. Yang harus dipahami bahwa terbentuknya Student Government adalah sebagai upaya taktis untuk melakukan proses transformasi sosial, berangkat dari student movement menuju ke social movement. Transformasi sosial merupakan wahana yang paling kondusif untuk membebaskan kaum tertindas menuju masyarakat mandiri (civil society). Gerakan mahasiswa juga harus mengarah pada advokasi akan hak-hak kaum bawah, sehingga posisi mahasiswa merupakan penyambung lidah dan jerit kaum yang termarginalkan oleh penguasa. Kebijakan pemerintah yang sentralistik tanpa melibatkan rakyat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik, serta konstalasi politik yang carut marut merupakan lahan garapan mahasiswa baik yang ada di intra parlemen yaitu BEM atau organisasi ektra perlementer atau luar kampus seperti PMII, HMI MPO, HMI DIPO, IMM, KAMMI, FPPI, LMND dan organisasi ekstra palementer lainnya. Keempat, Positioning, artinya adalah bahwa lembaga eksekutif tersebut harus meletakkan dasar organisasi sebagai institusi profit atau nonprofit. Idealnya menurut hemat penulis bahwa lembaga eksekutif ini yang berada pada jalur intra parlementer lembaga kemahasiswaan ini menggeser paradigrna yang tadinya dari gerakan student movement menjadi social movement. Sehingga aras gerak yang dilakukan lebuih kepada pemberdayaan rakyat keeil yang tertindas dan terhegemoni oleh kekuasaan yang represif. 47