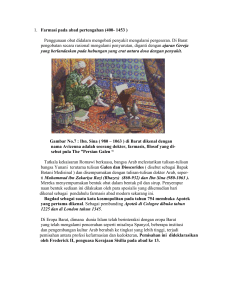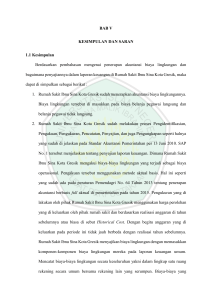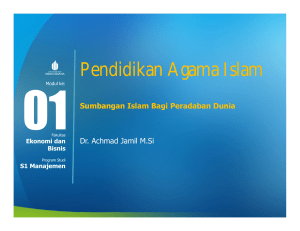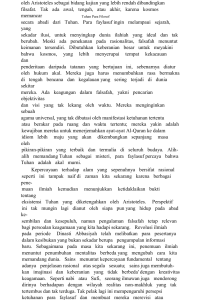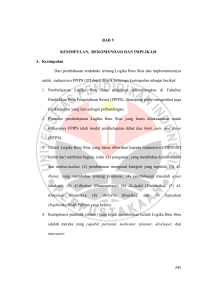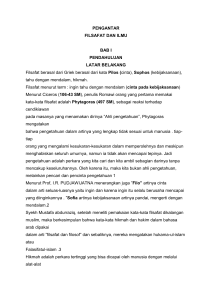7-PDF247-252_karen-amstrong-sejarah
advertisement
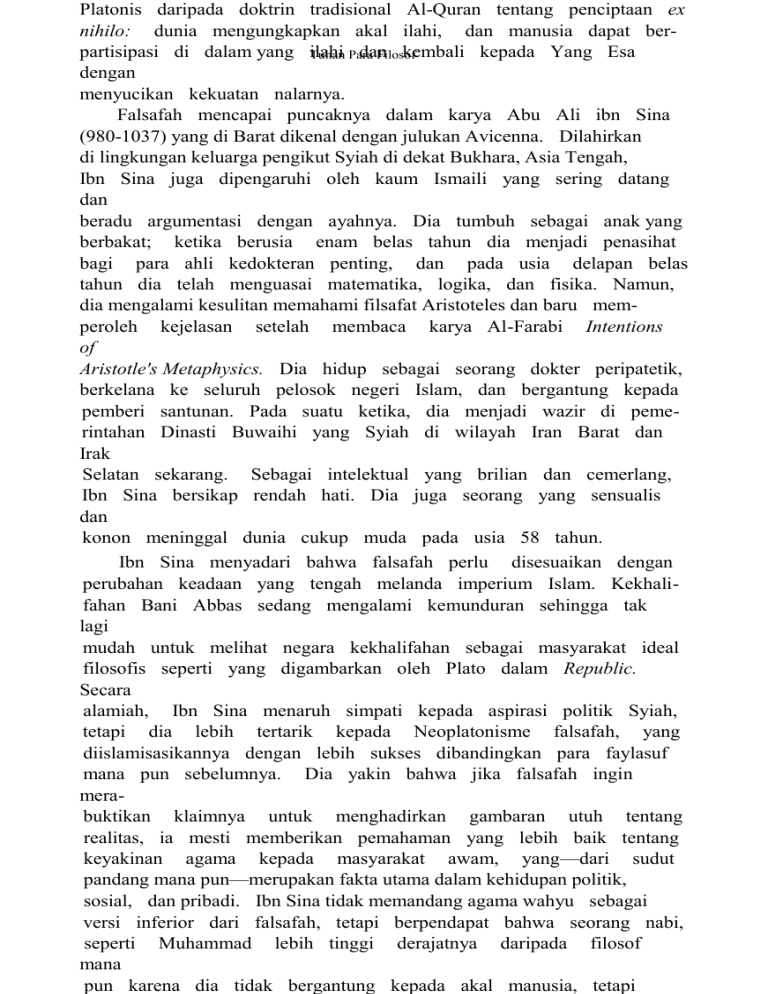
Platonis daripada doktrin tradisional Al-Quran tentang penciptaan ex nihilo: dunia mengungkapkan akal ilahi, dan manusia dapat berpartisipasi di dalam yang ilahi dan kembali kepada Yang Esa Tuhan Para Filosof dengan menyucikan kekuatan nalarnya. Falsafah mencapai puncaknya dalam karya Abu Ali ibn Sina (980-1037) yang di Barat dikenal dengan julukan Avicenna. Dilahirkan di lingkungan keluarga pengikut Syiah di dekat Bukhara, Asia Tengah, Ibn Sina juga dipengaruhi oleh kaum Ismaili yang sering datang dan beradu argumentasi dengan ayahnya. Dia tumbuh sebagai anak yang berbakat; ketika berusia enam belas tahun dia menjadi penasihat bagi para ahli kedokteran penting, dan pada usia delapan belas tahun dia telah menguasai matematika, logika, dan fisika. Namun, dia mengalami kesulitan memahami filsafat Aristoteles dan baru memperoleh kejelasan setelah membaca karya Al-Farabi Intentions of Aristotle's Metaphysics. Dia hidup sebagai seorang dokter peripatetik, berkelana ke seluruh pelosok negeri Islam, dan bergantung kepada pemberi santunan. Pada suatu ketika, dia menjadi wazir di pemerintahan Dinasti Buwaihi yang Syiah di wilayah Iran Barat dan Irak Selatan sekarang. Sebagai intelektual yang brilian dan cemerlang, Ibn Sina bersikap rendah hati. Dia juga seorang yang sensualis dan konon meninggal dunia cukup muda pada usia 58 tahun. Ibn Sina menyadari bahwa falsafah perlu disesuaikan dengan perubahan keadaan yang tengah melanda imperium Islam. Kekhalifahan Bani Abbas sedang mengalami kemunduran sehingga tak lagi mudah untuk melihat negara kekhalifahan sebagai masyarakat ideal filosofis seperti yang digambarkan oleh Plato dalam Republic. Secara alamiah, Ibn Sina menaruh simpati kepada aspirasi politik Syiah, tetapi dia lebih tertarik kepada Neoplatonisme falsafah, yang diislamisasikannya dengan lebih sukses dibandingkan para faylasuf mana pun sebelumnya. Dia yakin bahwa jika falsafah ingin merabuktikan klaimnya untuk menghadirkan gambaran utuh tentang realitas, ia mesti memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan agama kepada masyarakat awam, yang—dari sudut pandang mana pun—merupakan fakta utama dalam kehidupan politik, sosial, dan pribadi. Ibn Sina tidak memandang agama wahyu sebagai versi inferior dari falsafah, tetapi berpendapat bahwa seorang nabi, seperti Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada filosof mana pun karena dia tidak bergantung kepada akal manusia, tetapi dengan pengalaman mistik kaum Sufi dan pernah disebut Plotinus sebagai bentuk kearifan tertinggi. Namun, tidak berarti bahwa akal sama sekali tidak memiliki penalaran tentang Tuhan. Ibn Sina membeSejarah Tuhan rikan demonstrasi rasional tentang eksistensi Tuhan berdasarkan buktibukti Aristoteles yang kemudian menjadi standar di kalangan filosof Yudaisme maupun Islam pada akhir abad pertengahan. Ibn Sina maupun para faylasuf sama sekali tidak menaruh keraguan tentang keberadaan Tuhan. Mereka tak pernah ragu bahwa akal manusia tanpa bantuan wahyu dapat tiba pada pengetahuan tentang eksistensi Wujud Tertinggi. Akal adalah aktivitas manusia yang paling mulia: ia adalah bagian dari akal ilahi dan jelas memiliki peran penting dalam menjawab persoalan keagamaan. Ibn Sina berpendapat bahwa orangorang yang memiliki kemampuan intelektual mengemban tugas untuk menemukan Tuhan melalui akal, karena akal dapat memperhalus konsepsi tentang Tuhan serta membebaskannya dari takhayul dan antropomorfisme. Ibn Sina dan para pengikutnya yang memikirkan demonstrasi rasional tentang eksistensi Tuhan tidak bertentangan dengan kaum teis dalam pengertian kita atas kata itu. Mereka ingin menggunakan akal untuk menemukan sebanyak yang mereka bisa tentang hakikat Tuhan. "Bukti-bukti" Ibn Sina dimulai dengan pertimbangan tentang cara pikiran kita bekerja. Ke mana pun kita mengarahkan pandangan di dunia ini, kita melihat wujud-wujud senyawa yang terdiri dari sejumlah unsur berbeda. Sebuah pohon, misalnya, terdiri atas kayu, kulit kayu, getah, dan daun. Ketika kita mencoba untuk mengerti sesuatu, kita "menganalisis"-nya, memecahnya ke dalam bagian-bagian komponennya hingga tak ada lagi pembagian yang mungkin. Unsur-unsur sederhana menjadi primer bagi kita dan wujud senyawa yang dibentuk oleh unsur-unsur itu menjadi sekunder. Oleh karena itu, kita terusmenerus mencari penyederhanaan bahkan untuk wujud-wujud yang tidak bisa direduksi lagi. Adalah aksioma falsafah bahwa realitas membentuk satu kesatuan yang koheren secara logis; itu berarti bahwa pencarian tanpa akhir kita akan kesederhanaan pastilah mencerminkan keadaan pada skala besarnya. Seperti seluruh penganut Platonis, Ibn Sina merasakan bahwa kemajemukan yang kita lihat di sekeliling kita pasti bergantung pada kesatuan primal. Karena pikiran kita memang memandang benda-benda senyawa sebagai sekunder benda senyawa tidak berdiri sendiri, dan wujud yang tidak berdiri sendiri itu lebih rendah daripada realitas tempat mereka bergantung; Tuhan Para Filosof seperti dalam sebuah keluarga, anak berada pada status lebih rendah daripada ayah yang darinya mereka diturunkan. Sesuatu yang merupakan Kesederhanaan itu sendiri adalah apa yang disebut para filosof sebagai "Wujud Wajib", yakni yang tidak tergantung pada sesuatu yang lain bagi keberadaannya. Adakah wujud yang seperti itu? Seorang faylasuf, seperti Ibn Sina menerima begitu saja bahwa kosmos bersifat rasional dan dalam sebuah semesta yang rasional pastilah ada Wujud yang Tak Disebabkan, Penggerak yang Tak Digerakkan, di puncak hierarki eksistensi. Sesuatu pasti telah memulai rantai sebab akibat. Ketiadaan wujud tertinggi seperti itu akan berarti bahwa pikiran kita tidak selaras dengan realitas secara keseluruhan. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa alam semesta tidaklah koheren dan rasional. Wujud sangat sederhana yang kepadanya seluruh realitas majemuk bergantung adalah apa yang disebut agama sebagai "Tuhan". Karena merupakan yang tertinggi di atas segalanya, ia pasti sempurna secara mutlak dan pantas dihormati dan disembah. Namun karena eksistensinya begitu berbeda dari semua yang lain, ia bukanlah salah satu simpul dalam rangkaian mata rantai wujud. Para filosof berpandangan sama dengan Al-Quran bahwa Tuhan adalah kesederhanaan itu sendiri: Tuhan itu Satu. Oleh karena itu, Tuhan tidak bisa dianalisis atau dipecah-pecah ke dalam komponen atau sifat-sifat. Karena wujud ini secara mutlak sederhana, tidak memiliki sebab, tidak berdimensi temporal, dan tak ada sama sekali sesuatu yang bisa dikatakan mengenainya. Tuhan tidak bisa menjadi objek pemikiran diskursif, karena otak kita tidak bisa mencakup Tuhan seperti caranya mencakup hal-hal lain. Karena Tuhan itu secara esensial unik, dia tidak dapat diperbandingkan dengan apa pun yang ada dalam pengertian yang normal. Akibatnya, tatkala kita berbicara tentang Tuhan, lebih baik kita menggunakan pernyataan Murni—pada saat yang sama merupakan tindak penalaran serta objek Sejarahmungkin Tuhan dan subjeknya sekaligus—dia hanya berpikir tentang dirinya dan tidak memikirkan realitas yang bersifat sementara dan lebih rendah. Ini tidak sesuai dengan gambaran tentang Tuhan di dalam wahyu yang menyebutkan bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, hadir dan aktif dalam tatanan makhluk. Ibn Sina mengupayakan sebuah kompromi: Tuhan terlalu agung untuk turun ke taraf mengetahui makhluk-makhluk yang hina dan partikular seperti manusia dan segala perbuatannya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, "Ada hal-hal yang lebih baik tidak dilihat daripada dilihat." 8 Tuhan tidak mungkin mencemari dirinya dengan detail-detail kehidupan di bumi yang remeh dan sangat rendah. Namun di dalam aktivitas pengenalan dirinya yang abadi, Tuhan mengetahui segala sesuatu yang beremanasi darinya dan yang telah diberinya wujud. Tuhan mengetahui bahwa dia adalah sebab bagi makhluk-makhluk fana. Pemikirannya sangat sempurna sehingga berpikir dan bertindak merupakan satu aksi yang sama. Kontemplasi abadinya tentang dirinya sendiri menimbulkan proses emanasi seperti yang telah dijelaskan oleh para faylasuf. Akan tetapi, Tuhan mengetahui kita dan dunia kita hanya secara umum dan universal; dia tidak berurusan dengan yang partikular. Sungguhpun demikian, Ibn Sina tidak puas dengan penjelasan abstrak tentang kodrat Tuhan ini: dia ingin menghubungkannya dengan pengalaman keagamaan kaum beriman, para Sufi, dan kaum batini. Karena tertarik pada psikologi agama, dia menggunakan skema emanasi Plotinian untuk menjelaskan pengalaman kenabian. Pada setiap sepuluh fase emanasi wujud dari Yang Esa, Ibn Sina berspekulasi bahwa sepuluh Akal Murni itu, bersama dengan jiwa-jiwa atau malaikat-malaikat yang menggerakkan kesepuluh bidang Ptolemik, membentuk sebuah alam penengah antara manusia dan Tuhan, yang bersesuaian dengan dunia realitas arketipe yang diimajinasikan oleh kaum batini. Akal-akal ini juga memiliki imajinasi; bahkan mereka adalah Imajinasi dalam keadaan murninya. Melalui alam penengah inilah—bukan melalui akal diskursif—manusia dapat mencapai pengenalan paling lengkap tentang Tuhan. Akal paling akhir dari cakrawala kita—yakni akal kesepuluh—adalah malaikat pembawa wahyu, yang dikenal sebagai Jibril, sumber cahaya dan pengetahuan. Jiwa manusia tersusun dari akal praktis yang berhubungan dengan dunia ini, dan akal kontemplatif250 yang mampu hidup berdampingan dengan Malaikat Jibril. Dengan demikian, menjadi mungkin bagi Tuhan Para Filosof nabi-nabi untuk mendapatkan pengetahuan intuitif dan imajinatif tentang Tuhan, serupa dengan pengetahuan yang dimiliki Akal yang mentransendensi akal praktis dan diskursif. Pengalaman kaum Sufi memperlihatkan bahwa manusia dimungkinkan untuk mencapai visi tentang Tuhan secara filosofis tanpa menggunakan logika dan rasionalitas. Sebagai pengganti silogisme, mereka menggunakan alat-alat imajinatif berupa simbol dan kiasan. Nabi Muhammad Saw. telah menyempurnakan penyatuan langsung dengan alam suci ini. Tafsiran psikologis tentang visi dan wahyu ini akan memampukan para Sufi yang berkecenderungan filosofis untuk mendiskusikan pengalaman keagamaan mereka sendiri, seperti yang akan kita saksikan pada bab mendatang. Pada akhir hayatnya Ibn Sina tampaknya telah menjadi seorang mistikus pula. Dalam risalahnya Kitab Al-Isyarat (Kitab Peringatan), dia dengan jelas menjadi sangat kritis pada pendekatan rasional terhadap Tuhan, yang menurutnya melelahkan. Dia beralih kepada apa yang disebutnya "Filsafat Timur" (al-hikmah al-masyriqiyyah). Ini tidak mengacu pada arah timur secara geografis, melainkan kepada sumber cahaya. Dia bermaksud menulis sebuah risalah esoterik menggunakan metode yang didasarkan pada disiplin iluminasi (isyraq) serta rasiosinasi. Kita tak yakin apakah dia memang pernah menulis risalah itu: sekiranya pun pernah, tentu risalah itu telah hilang. Namun, sebagaimana juga akan kita saksikan pada bab mendatang, filosof besar Iran, Yahya Suhrawardi mendirikan aliran Isyraqi yang memang menggabungkan filsafat dengan spiritualitas dalam cara yang pernah direncanakan oleh Ibn Sina. Ilmu kalam dan falsafah telah mengilhami sebuah gerakan intelektual yang sama di kalangan orang-orang Yahudi yang berdomisili di kerajaan Islam. Mereka mulai menulis filsafat mereka sendiri dalam bahasa Arab dan untuk pertama kali memperkenalkan unsur metafisika dan spekulasi ke dalam Yudaisme. Berbeda dengan para faylasuf Muslim, para filosof Yahudi tidak melibatkan diri ke dalam seluruh rentang ilmu filsafat tetapi memusatkan perhatian terutama pada masalah-masalah keagamaan. Mereka merasa harus menjawab tantangan Islam dengan cara mereka sendiri, dan itu melibatkan pencocokan Tuhan Alkitab yang personalistik dengan Tuhan para faylasuf. Seperti kaum Muslim, mereka tidak nyaman dengan penggambaran Tuhan secara antropomorfis di dalam kitab suci dan Talmud. Mereka bertanya kepada diri sendiri bagaimana Tuhan yang seperti 251 itu bisa sama dengan Tuhan para filosof. Mereka memikirkan masalah penciptaan alam dan hubungan antara wahyu dengan akal. Meski Sejarah Tuhan yang berbeda, secara ilmiah tiba pada kesimpulan mereka sangat tergantung pada para pemikir Muslim. Saadia bin Yoseph (882-942), orang pertama yang melakukan interpretasi filosofis terhadap Yudaisme, adalah seorang Talmudis sekaligus Mu'tazilah. Dia percaya bahwa akal bisa mencapai pengetahuan tentang Tuhan melalui kekuatannya sendiri. Seperti seorang faylasuf, dia memandang pencapaian konsepsi rasional tentang Tuhan sebagai suatu mitzvah, kewajiban agama. Akan tetapi, seperti rasionalis Muslim, Saadia tidak memiliki keraguan sama sekali tentang eksistensi Tuhan. Realitas Tuhan Pencipta tampak begitu jelas bagi Saadia sehingga, dalam karyanya Books of Beliefs and Opinions, dia merasa yang lebih perlu dibuktikan adalah soal kemungkinan keraguan di dalam agama daripada soal iman. Seorang Yahudi tidak dituntut untuk memaksa akalnya menerima wahyu, demikian Saadia berpendapat. Namun itu tidak berarti bahwa Tuhan dapat sepenuhnya dijangkau oleh akal manusia. Saadia mengakui bahwa ide tentang penciptaan dari ketiadaan mengandung banyak kesulitan filosofis dan tak mungkin dijelaskan dalam terma rasional, karena Tuhan yang dikonsepsikan oleh falsafah tidak dapat membuat keputusan mendadak dan memicu perubahan. Bagaimana mungkin alam material bisa berasal dari Tuhan yang sepenuhnya bersifat spiritual? Di sini kita telah mencapai batas akal dan harus menerima saja bahwa alam ini tidak abadi, seperti yang diyakini oleh kaum Platonis, tetapi memiliki permulaan dalam waktu. Ini satu-satunya penjelasan yang mungkin dan bersesuaian dengan kitab suci dan akal sehat. Setelah menerima ini, kita dapat mendeduksikan faktafakta lain tentang Tuhan. Tatanan makhluk telah direncanakan dengan cerdas; ia memiliki hidup dan energi; oleh karena itu, Tuhan yang telah menciptakannya pasti juga memiliki Hikmat, Hidup, dan Kekuatan. Atribut-atribut ini bukanlah hypostases yang terpisah, seperti disiratkan doktrin Trinitas Kristen, tetapi semata-mata merupakan aspek dari Tuhan. Hanya karena bahasa manusia tidak mampu mengungkapkan realitas Tuhan secara memadai maka kita terpaksa menganalisisnya lewat cara ini dan seolah merusak simplisitas mutlak Tuhan. Jika kita ingin bicara sangat eksak tentang Tuhan, kita hanya bisa menyatakan bahwa dia ada. Saadia tidak membuang semua