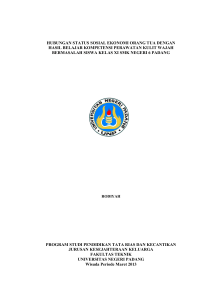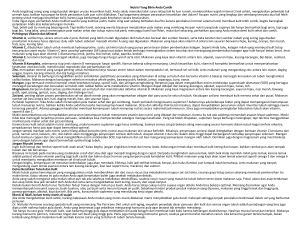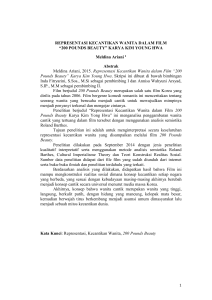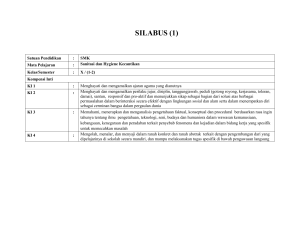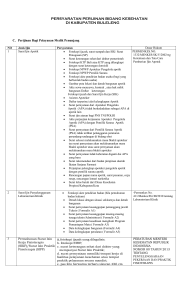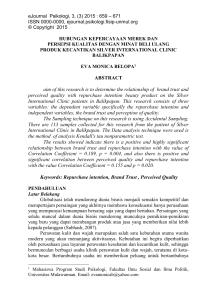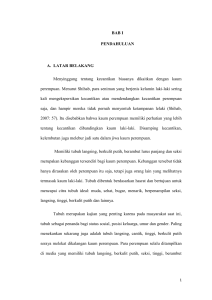Genealogi Kecantikan
advertisement

Genealogi Kecantikan Elya Munfarida *) *) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen Jurusan Dakwah (Komunikasi) STAIN Purwokerto. Abstracts: From social construct, beauty always embedded with feminine aspect. Therefore, its embedded on woman’s self. Beauty has unusual attractiveness that can destroy man’s world. It is so priceless, until woman would do anything to be beautiful. Genealogical perspective sees beauty as a discourse that has power relation inside. In beauty discourse, social construct has made women as subjugated object. Woman-meaning determinated by social meaning. Capitalism power also plays a role behind beauty discourses. With the power of his media, capitalism creates unlimited psychological desire that would stimulate beauty commodity demand. This is brought great advantage to capitalist because beauty commodity or product will continue to be produced. Keywords: genealogy, discourses, beauty, objectification, and capitalism. Pendahuluan Konon kecantikan adalah anugerah terindah bagi wanita. Kecantikan memiliki kemampuan magnetik luar biasa yang mampu meruntuhkan dunia laki-laki. Dalam berbagai sejarah kemanusiaan dan mitologi kuno dilukiskan betapa dahsyatnya pengaruh kecantikan seorang perempuan terhadap jiwa laki-laki sehingga ia mau berkorban dan melakukan apa saja demi sang perempuan. Keagungan dan kekuasaan laki-laki dapat jatuh dan bertekuk lutut di bawah kakinya. Beberapa contoh ilustrasi misalnya, kisah Adam dan Hawa, Julius Cesar dan Cleopatra, Rama dan Shinta, dsb. Perebutan wanita cantik antara Qabil dan Habil, perselisihan antara Epimetheus dan Prometheus demi memperebutkan Pandora yang cantik, juga turut mewarnai sejarah tragedi kemanusiaan atas nama kecantikan perempuan. Begitu berharganya kecantikan sehingga tidak jarang kaum perempuan sangat terobsesi untuk mendapatkannya. Mereka bersedia melakukan apapun untuk mendapatkannya meskipun harus merogoh kocek yang tidak sedikit. Tempat-tempat kebugaran, spa, salon kecantikan, dan berbagai institusi kecantikan yang lain menjadi tempat-tempat yang diminati perempuan untuk mengubah dirinya menjadi cantik. Uang tidak sedikit yang harus mereka keluarkan untuk mengkonsumsi berbagai produk kecantikan, tidak menyurutkan hasrat untuk tampil cantik dan menarik. Bagi para perempuan terutama kelas menengah ke atas, masalah biaya yang besar tentu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bagi kelas bawah, mengejar kecantikan tentu bukan persoalan yang sederhana dan P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 1 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 mudah. Kendala dana tidak memungkinkan mereka untuk mengakses institusi-institusi kecantikan, meskipun bukan berarti mereka tidak memiliki keinginan untuk menjadi cantik. Obsesi yang berlebihan untuk menjadi cantik terkadang justru membutakan rasionalitas perempuan. Perilaku konsumtif terhadap berbagai produk dan program kecantikan, yang menurut Yasraf Amir Piliang merupakan salah satu manifestasi hiperealitas budaya,1 menjadi gaya hidup para perempuan modern saat ini. Berbagai produk kecantikan dikonsumsi tidak lagi didasari semata-mata oleh nilai utilitasnya, tetapi lebih-lebih untuk menandai kelas, status, atau simbol sosial tertentu. Komoditi-komoditi kecantikan yang tampil dalam berbagai media massa diburu, meskipun terkadang harus mempertaruhkan harta dan jiwa. Alih-alih untuk mendapatkan kecantikan, perempuan terkadang memperoleh yang sebaliknya, yakni penderitaan. Di beberapa media massa, diberitakan berapa banyak perempuan yang sakit atau bahkan meninggal akibat suntik silikon. Berbagai penelitian juga menunjukkan meningkatnya jumlah penderita penyakit anoreksia dan bulimia yang banyak diderita perempuan karena terobsesi dengan tubuh kurus atau langsing dengan melakukan diet ketat, atau dalam bahasa Naomi Wolf “memelihara rasa lapar”.2 Belum lagi berbagai dampak psikologis atau penyakit mental yang ditimbulkan oleh berbagai mitos kecantikan seperti penolakan terhadap tubuh, rasa malu, self esteem (penghargaan diri) yang rendah, depresi sampai disfungsi seksual, banyak diderita oleh kaum perempuan yang terobsesi dengan kecantikan. Realitas di atas memunculkan pertanyaan apakah kecantikan merupakan sesuatu yang objektif dan universal? Apakah kecantikan adalah sebuah wujud yang otonom ataukah sebuah konstruksi sosial yang menyimpan adanya relasi kuasa? Mengapa perempuan sangat terobsesi mengejar kecantikan? Jawaban atas beberapa pertanyaan di atas akan menjadi inti pembahasan dari kajian ini. Dengan menggunakan perspektif genealogis,3 kajian ini berupaya mengungkap anatomi kekuasaan yang berada di balik diskursus4 kecantikan. What is Beauty? Sejak zaman dahulu, wanita sudah dikonstruksikan sebagai makhluk yang cantik, identik dengan keindahan. Bila cantik dilabelkan pada laki-laki maka akan timbul persoalan karena pelabelan itu akan mengesankan sifat banci (waria/she-she). Oleh karenanya kecantikan selalu melekat pada unsur feminitas bukan maskulinitas. Konstruksi ini telah berlaku sepanjang sejarah perempuan sehingga kecantikan dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan universal yang inheren dalam diri perempuan. Naomi Wolf mengungkapkan kecantikan bukanlah sesuatu yang obyektif universal yang tidak dapat berubah, meskipun orang Barat percaya bahwa kecantikan yang ideal berawal dari sosok yang Platonis. Namun demikian, orang-orang suku Maori mengagumi tubuh yang gemuk. Sementara orangorang Padung mengagumi buah dada yang montok. Kecantikan juga tidak selalu melekat pada perempuan. Dalam kehidupan suku Woodabe di Nigeria, sistem matriarkhal yang dianut oleh mereka membalikkan relasi perempuan dan laki-laki. Unsur feminin justru melekat pada kaum laki-laki. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 2 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Mereka berhias dan mempercantik diri untuk mempertontonkan kecantikannya guna mendapatkan perhatian kaum perempuan.5 Menurutnya, kecantikan merupakan salah satu kontrol sosial terhadap perempuan. Berbagai mitos kecantikan diciptakan oleh kekuasaan patriarkhi untuk meneguhkan dominasinya terhadap perempuan. Kebebasan perempuan dari mistik feminin (Feminine Mystique) tentang domestisitas perempuan abad pertengahan,6 di satu sisi memberikan angin segar bagi eksistensi perempuan. Ruang gerak perempuan tidak hanya terbatas pada wilayah domestik saja, tetapi juga menjangkau wilayah publik. Namun demikian, di sisi lain, kebebasan ekspresi ini oleh sistem patriarkhi yang sudah mapan dipandang sebagai ancaman serius. Oleh karenanya kebebasan perempuan akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kontrol atas mereka. Definisi kecantikan bersifat politis karena hakikatnya merupakan representasi relasi-relasi kekuasaan. Kritik Wolf terhadap mitos kecantikan, menyiratkan bahwa kecantikan itu pada realitasnya “ada dan objektif” dalam masyarakat. Beragam persepsi akan muncul terkait dengan makna kecantikan. Tanpa berpretensi menggeneralisir persoalan, secara garis besar, berbagai pendapat tentang definisi kecantikan dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok: pertama, kecantikan hanya bersifat fisik saja (outer beauty). Wajah yang ayu, tubuh yang langsing, kulit putih, tinggi semapai, hidung mancung merupakan manifestasi kecantikan fisik. Kedua, hakikat kecantikan itu ada dalam Diri ( D besar) bukan pada diri (d kecil) atau fisik, yang diistilahkan dengan inner beauty. Kepribadian, intelektualitas, kecakapan emosional, dan kualitas-kualitas nonfisik merupakan gambaran kecantikan model kedua ini. Ketiga, kecantikan itu bersifat fisik dan nonfiisik. Kecantikan tidak hanya berada pada tataran penampilan fisik saja, tetapi juga pada tataran nonfisik. Artinya, perempuan yang memiliki inner beauty juga harus memiliki outer beauty. Bagi perempuan yang dianugerahi Tuhan penampilan fisik yang menarik, mungkin akan menempatkan dirinya pada kelompok pertama atau ketiga. Bahwa kecantikan itu adalah penampilan fisik yang menarik saja atau penampilan fisik dan non-fisik sekaligus. Akan tetapi, bagi perempuan yang kebetulan memiliki ukuran tubuh yang secara sosial tidak proporsional atau kurang menarik, mungkin akan lebih condong pada pendapat kelompok kedua, meskipun tidak menutup kemungkinan alam bawah sadarnya juga menginginkan kecantikan fisik. Akan tetapi di manapun anda menempatkan posisi anda dalam ketiga kelompok klasifikasi di atas, kalau anda dimintai komentar tentang gambar seorang wanita yang bertubuh langsing, berkulit putih, memiliki rambut lurus yang tergerai indah dan wajah yang agak indo, barangkali secara spontan, anda akan menjawab: “gadis ini cantik sekali”. Ini artinya kecantikan itu objektif dalam struktur kesadaran masyarakat yang seringkali direpresentasikan dengan keindahan fisik. Dalam interaksi sosial bentuk fisik seseorang adalah hal pertama yang dinilai dari perempuan. Masyarakat tidak akan menilai dari kecerdasan intelektualnya atau kelebihan lain di balik bentuk fisiknya terlebih dahulu. Budaya kesan pertama (first impression culture) di masyarakat kita P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 3 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 menunjukkan bahwa lingkungan sering kali menilai seseorang berdasarkan kriteria luar, seperti tampilan fisik.7 Penampilan fisik yang menarik kemudian diasosiasikan dengan kesempatan kerja lebih luas, kehidupan asmara yang lebih baik, dll. Pada saat ini, penekanan penilaian penampilan fisik perempuan terletak pada proporsionalitas fisik, yaitu pada ukuran dan bentuk tubuh. Tubuh yang langsing dan proporsional akan mendapatkan respek yang positif dari masyarakat, sementara yang kurang proporsional akan mendapatkan respek negatif. Oleh karena itu, dalam masyarakat kita sering mendengar ungkapan: “cantik tapi gemuk” atau “cantik tapi kurus”. Sebuah studi menyatakan bahwa analisis dari gambar-gambar yang disodorkan media massa memperkuat bukti bahwa tipe bentuk tubuh langsing sangat mendominasi, dan bahwa anggapan sosial yang positif selalu dihubungkan dengan kelangsingan, sebaliknya anggapan sosial yang negatif dihubungkan pada kegemukan.8 Perempuan diberi tahu bahwa mereka dapat dicintai hanya jika mereka langsing karena kelangsingan disetarakan dengan kecantikan dan diinginkan secara seksual. Sebaliknya, kegemukan disetarakan dengan jelek dan ketidak-erotisan. Pertanyaaan yang kemudian muncul adalah apakah memang secara historis langsing itu identik dengan cantik dan sebaliknya, gemuk identik dengan jelek? Jawaban atas pertanyaan ini akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya, yakni sejarah tubuh perempuan. Sejarah Tubuh Perempuan Dalam sejarah kemanusiaan, ukuran dan bentuk tubuh perempuan kerap kali diidentikkan dengan kecantikan. Beberapa mitologi, patung, dan lukisan kuno melukiskan bahwa bentuk tubuh perempuan merupakan representasi kecantikannya. Ukuran kecantikan terkait dengan idealitas bentuk tubuh perempuan sangat relatif, serta berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan satu masyarakat pada masa tertentu dengan masa yang lain, di samping perbedaan-perbedaan antarsetiap individu. Dahulu, banyak masyarakat menilai perempuan yang gemuk adalah perempuan yang cantik. Gemuk juga dijadikan pertanda kesejahteraan hidup, karena itu perempuan di masa lalu selalu ingin tampil gemuk. Badan yang “penuh lemak” adalah ukuran utama, sedang yang lainnya tidak terlalu penting. Secara jenaka, Anis Manshur dalam bukunya Min Awwal Nazdrah melukiskan perempuan cantik dalam pandangan mayoritas suku-suku di Afrika, sebagai perempuan yang tidak bisa berjalan. Kalau berjalan dia dapat terjatuh, dan kalau nyaris terjatuh dia bersandar di pohon atau di pundak pembantunya. Sementara itu, perempuan yang kurus oleh suku Masai dianggap sebagai kutukan sehingga perempuan yang kurus harus dibakar agar kutukannya tidak merambat ke perempuan lain. Masyarakat Romawi menyenangi perempuan yang tidak gemuk, tetapi yang berisi/gempal, sedangkan masyarakat Andalusia (Spanyol) sangat senang perempuan yang ikat pinggangnya seluas lengan lakilaki, yakni ramping, dan laki-laki yang ingin mempersunting perempuan, arah pandangannya banyak sekali tertuju kepada mata perempuan itu.9 P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 4 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Di Jepang kuno, sebagaimana di Cina pertengahan, para perempuan sering dilukiskan sebagai sosok yang kokoh, dengan wajah gemuk, dada besar, pinggang ramping, tetapi pinggul besar, yang mengesankan pelahir anak. Akan tetapi, pada abad XVII ideal-ideal Cina mengenai keindahan perempuan berubah ke sisi lain. Orang Jepang juga mengikuti gaya ini. Dalam cetakan-cetakan ukiyo- e belakangan menggambarkannya dengan para perempuan yang tampak lembut, yang wajah ovalnya disepakati sebagai puncak kecantikan.10 Dalam lukisan-lukisan klasik abad pertengahan di Barat, perempuan juga dilukiskan dengan tubuh yang subur, dengan perut, lengan, dan wajah yang berdaging dan berisi. Bentuk tubuh yang ideal adalah yang gemuk dan berlekuk-lekuk layaknya perempuan rumahan. Ini mengesankan bahwa bentuk ideal pada masa itu adalah yang mewakili citra kesuburan. Tidak diketahui, sejak kapan bentuk tubuh perempuan yang gemuk ini menjadi sosok ideal. Yang jelas, banyak ahli purbakala banyak menemukan figur patung atau relief yang menggambarkan sosok perempuan yang bertubuh gemuk dan subur. Bahkan, sebuah patung yang cukup terkenal bernama Venus of Willendorf seolah-seolah mencitrakan bahwa Dewi Venus yang banyak dipuja sebagai simbol kecantikan pun bertubuh sangat gemuk.11 Berakhirnya perang dunia II pada 1950-an, selain membawa hawa baru dalam kehidupan politik juga berpengaruh pada perubahan kehidupan kaum perempuan. Para lelaki yang sebelumnya sibuk mengangkat senjata, kini kembali ke kampung halaman dan banyak beralih profesi sebagai buruh atau pegawai kantoran. Keadaan ini mendorong para perempuan untuk “kembali” ke rumah. Dalam masa regresif ini, para perempuan lebih disibukkan dengan urusan domestik seputar rumah tangga. Pikiran mereka terasing di dalam rumah. Oleh karena itu, pada 1950-an para perempuan cenderung kelebihan berat badan (overweight). Pada saat itu, kaum hawa tidak perlu tersiksa oleh diet ketat dan korset, serta bebas memamerkan “daging” mereka tanpa khawatir komentar orang.12 Berbeda 180 derajat dengan zaman 1950-an yang memuja perempuan bertubuh subur, pada era 1960-an, mendadak tubuh kurus justru menjadi simbol kecantikan. Banyak pemerhati masalah tubuh ini sepakat bahwa citra ideal perempuan bertubuh subur mulai tergusur seiring dengan munculnya industri media dan periklanan. Media massa, terutama pada 1960-an banyak memunculkan figur langsing, selain dijadikan simbol kecantikan, tubuh langsing juga dianggap sebagai simbol pemberontakan perempuan. Kalau di era sebelumnya, perempuan bertubuh gemuk dikatakan subur secara seksual, maka tren tubuh langsing menjadi pendobrak bahwa perempuan tidak hanya sekedar sebagai alat reproduksi semata.13 Tren tubuh tipis yang mulai booming pada 1960-an mengalami momentumnya di 1970-an. Pada masa ini, hampir semua model yang muncul di media massa memiliki tubuh tanpa daging. Bentuk tubuh kurus mencapai puncaknya pada 1980-an. Di era ini, tubuh langsing tetapi atletis, tidak berlemak, dan berpayudara kecil menjadi tren. Para gadis mati-matian berdiet untuk memiliki tubuh kurus. Berbagai artikel dan buku yang membahas tentang berbagai cara diet laris manis di pasaran. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 5 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Kemudian pada masa 1990-an, para perempuan bebas “merenovasi” fisiknya akibat adanya berbagai penemuan baru di bidang teknologi kosmetika yang mulai bermunculan dan memberikan angin segar bagi mereka yang merasa tubuhnya kurang sempurna. Pengelupasan kulit (acid peels), sedot lemak (liposuction), injeksi kolagen, dan penanaman payudara (breast implant) adalah bebarapa contoh keberhasilan teknologi kosmetika yang membuat tubuh perempuan berubah dari alamiah menjadi buatan. Di era 2000-an, pribadi yang penuh percaya diri, aktif dan bugar menjadi gambaran ideal sosok perempuan masa kini. Badan yang langsing dan kencang, bahu dan lengan sedikit berotot menjadi tren.14 Akhirnya, ke mana pun tren tersebut menuju, selalu saja sangat sulit bagi perempuan untuk menghindarinya. Selama isu-isu seputar kecantikan atau keindahan fisik (beauty myth) masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, pemujaan terhadap bentuk tubuh ideal semakin subur. Padahal dengan begitu, perempuan justru mengingkari hak untuk dilihat dan dikagumi apa adanya. Proses Objektivikasi Diri Kecenderungan perempuan untuk mengedepankan penampilan fisik dan obsesinya untuk menjadi cantik dan tampil menarik, seringkali dilekatkan dengan unsur feminitas yang dimiliki perempuan. Oleh karenanya, ia merupakan bagian dari kodrat yang harus disandang oleh kaum perempuan. Meskipun dalam uraian di atas, diungkapkan bahwa ternyata kecantikan tidak hanya dimonopoli oleh perempuan saja. Kaum laki-laki dari suku Woodabe di Nigeria justru meluangkan waktu berjam-jam untuk berhias dan mempertontonkan kecantikannya di hadapan juri perempuan dalam suatu kontes kecantikan. Namun demikian, realitas ini tetap tidak akan dapat menghilangkan anggapan sosial bahwa kecantikan adalah bagian integral dari diri perempuan. Obsesi perempuan terhadap penampilan fisik dapat dijelaskan dengan teori objektivikasi Fredrickson dan Roberts yang dikembangkan pada 1997. Kerangka teori ini dibangun dari proses analisis atas tubuh perempuan yang diletakkkan dalam konteks sosiokultural. Tubuh dikaji bukan sebagai struktur biologis, melainkan dari struktur pengalaman. Sebagai struktur pengalaman, makna, fungsi, dan idealisasi seseorang atas tubuhnya menjadi rumusan konsep yang sifatnya tidak tetap, dapat berubah-ubah antar-ruang dan waktu, ditentukan bukan saja secara individual melainkan juga secara sosial. Kriteria yang secara sosial dikondisikan sebagai tolak ukur idealisasi atas tubuh, misalnya, akan turut mempengaruhi bagaimana individu di dalamnya melakukan penilaian dan pemaknaan terhadap tubuhnya, di mana perempuan dikondisikan untuk berada pada posisi pasif. Pihak di luar perempuanlah yang justru akan menentukan bagaimana seharusnya memaknai dan memperlakukan tubuhnya. Perempuan dikondisikan untuk menggantungkan diri pada penilaian orang lain ketika hendak mengukur atau menilai pengalamannya seputar persoalan tubuh.15 Teori objektivikasi memandang tren pementingan aspek penampilan fisik di kalangan kaum perempuan sebagai konsekuensi maraknya praktik objektivikasi seksual terhadap tubuh perempuan. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 6 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Praktik objektivikasi seksual terjadi ketika tubuh seseorang atau bagian-bagian tubuhnya atau fungsi seksualnya dipisahkan dari totalitas kediriannya. Tubuh dilihat semata-mata sebagai objek seksual, untuk diamati, dievaluasi dan ditentukan nilai dan maknanya oleh pihak lain di luar si pemilik tubuh. Praktik objektivikasi seksual atas tubuh perempuan merupakan perpanjangan peran pasif perempuan. Perempuan -–dalam hal ini tubuhnya— diposisikan dan dimaknai sebagai objek keindahan atau kepuasan untuk dilihat, diamati, dinilai, bahkan digunakan oleh pihak lain di luar dirinya.16 Menurut Fredrickson dan Roberts, akumulasi dari berbagai bentuk praktik objektivikasi seksual dapat membentuk suatu sistem kultural yang disebut kultur objektivikasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kultur objektivikasi mensosialisasikan pada kaum perempuan agar memperlakukan tubuhnya lebih sebagai objek untuk diamati dan dievaluasi daripada sebagai bagian dari keutuhan subjek yang otonom. Efek terdalam dari objektivikasi seksual adalah diadopsinya cara pandang atau sudut penilaian yang biasa digunakan pelaku objektivikasi oleh mereka yang justru mengalami objektivikasi seksual. Proses adopsi cara pandang ini dimungkinkan karena praktik objektivikasi seksual telah berlangsung secara massal dan terus-menerus sehingga diterima sebagai kebiasaan sehari-hari. Dalam praktik objektivikasi seksual, tubuh perempuan lebih sering diamati dan dievaluasi kualitas serta nilainya, pertama-tama berdasarkan aspek penampilan fisiknya seperti warna kulit atau sensualitasnya daripada berdasarkan kompetensi fisiknya seperti stamina atau kebugarannya. Perempuan yang terus-menerus mengalami sudut penilaian semacam ini lama kelamaan akan terdorong untuk menginternalisasikan cara pandang tersebut.17 Selanjutnya, diprediksikan bahwa objektivikasi diri akan menstimulasi kemunculan sejumlah konsekuensi psikologis bahkan resiko kesehatan mental. Konsekuensi psikologis tersebut adalah rasa malu, kecemasan, menurunnya self esteem (penghargaan diri), dan kepekaan atas gejala internal tubuh. Akumulasi berbagai konsekuensi psikologis tersebut pada gilirannya memunculkan sejumlah resiko kesehatan mental seperti depresi, disfungsi seksual, dan gangguan perilaku makan.18 Objektivikasi ini bisa dilakukan siapa saja, baik oleh orang tak dikenal yang hanya sekadar mengomentari tubuh perempuan maupun oleh orang terdekat, bahkan pasangan sendiri. Perempuan mengalami objektivikasi seksual ketika bagian-bagian tubuhnya dipisahkan dari identitas mereka dan direduksi menjadi instrumen yang dapat digunakan dan menyenangkan orang lain atau dapat memberikan keindahan visual.19 Dengan demikian, konsep diri perempuan sangat dipengaruhi oleh konsep sosial atasnya. Masyarakat memiliki kekuasaan besar atas pemaknaan perempuan terhadap dirinya. Dalam relasi pemaknaan ini, perempuan berposisi sebagai subjugated (objek yang tertindas) karena makna dirinya sangat ditentukan oleh makna sosial. Konstruksi sosial atas makna perempuan ini akan diinternalisasikan dalam kesadaran perempuan dan dijadikan sebagai standar dalam mereproduksi makna dirinya sendiri. Akibatnya, penilaian kualitas perempuan yang secara sosial ditekankan pada penampilan fisik akan berimplikasi terhadap penilaian perempuan sendiri terhadap kualitas dirinya. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 7 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Kehidupan perempuan, pada gilirannya cenderung berkutat pada persoalan fisik atau tubuh. Makna Dirinya ditentukan oleh seberapa banyak dia mampu memenuhi kemestian-kemestian atau standarstandar sosial tentang kecantikan. Totalitas dirinya menjadi terfragmentasi dalam diri-diri fisik semata. Peran Kapitalisme dalam Diskursus Kecantikan Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang dibentuk oleh kesadaran modern yang berpijak pada rasionalitas. Sebagai sistem ekonomi rasional, kapitalisme mengharuskan adanya akumulasi modal yang berlaku terus-menerus. Berbagai komoditi diciptakan demi menjaga stabilitas kemapanannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan dengan maksimal sehingga dapat mendukung kepentingannya. Media massa dikuasai dan dijadikan alat untuk mengkomunikasikan kepentingannya kepada masyarakat selaku konsumennya.20 Sistem kapitalisme global telah merasuk dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya. Hampir tidak ada satu wilayah pun yang tidak terjamah oleh pengaruh kapitalisme bahkan dalam wilayah privat sekalipun. Kapitalisme melakukan penetrasi ke dalam semua lini kehidupan manusia agar dapat semakin mengokohkan kekuasaannya sekaligus demi mencapai satu tujuan, yakni meningkatkan akumulasi kapital sebanyak-banyaknya. Atas nama kepentingan ini, komoditi diproduksi secara terus-menerus agar menghasilkan keuntungan ekonomis. Sebagai salah satu aspek kemanusiaan yang penting, kecantikan yang dianggap sebagai bagian integral dari diri perempuan menjadi salah satu wilayah strategis yang dapat dijadikan objek komoditas. Berbagai komoditi atau produk kecantikan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perempuan untuk menjadi cantik dan menarik. Kapitalisme juga menciptakan keinginan-keinginan psikologis perempuan agar produk-produk kecantikan dapat selalu diproduksi dan menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya, pengetahuan dan mitos-mitos kecantikan diciptakan untuk menumbuhkan keinginan-keinginan psikologis dalam diri perempuan. Berbagai iklan kecantikan di media massa yang menampilkan gadis yang langsing, kulit yang putih menyiratkan pesan bahwa cantik itu identik dengan tubuh langsing dan kulit putih. Sementara itu, badan yang berlemak, kulit hitam, dan lain-lain, itu jelek dan tidak menarik. Objektivikasi ini akan terinternalisasi dalam diri perempuan dan kemudian memunculkan keinginan-keinginan psikologis sesuai dengan pesan dalam iklan tersebut. Citra-citra kecantikan yang dimunculkan oleh media massa akan mempengaruhi kesadaran perempuan sehingga pemenuhan terhadap citra-citra tersebut merupakan sebuah kebutuhan. Kalau mau cantik harus langsing dan kalau mau langsing harus mengkonsumsi produk pelangsing. Kondisi ini akan mendorong perempuan pada perilaku konsumtif. Berbagai produk dan institusi kecantikan dikonsumsi untuk mengubah diri menjadi cantik, meskipun terkadang harus membayar dengan mahal. Menurut Yasraf Amir Pilliang, ada tiga kekuasaan yang beroperasi dibalik produksi dan konsumsi komoditi, yakni kekuasaan kapital, kekuasaan produser, serta kekuasaan media massa.21 Ketiga P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 8 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 kekuasaan ini saling berjalin berkelindan untuk menciptakan permintaan (demand) secara terusmenerus. Melalui media massa keinginan-keinginan psikologis diciptakan sehingga komoditi bisa terus-menerus diproduksi. Pada akhirnya, pola konsumsi ternyata lebih menguntungkan bagi para pemilik modal daripada benar-benar mengubah perempuan menjadi cantik. Perilaku konsumtif juga menampilkan realitas lain yang disebut Yasraf Amir Pilliang sebagai hypercommodity. Komoditi tidak lagi berfungsi sebagai objek utilitas, tetapi sebagai simbol prestise, status dan kelas sosial.22 Fungsi komoditi melampaui alam komoditi itu sendiri (hiperkomoditi). Penggunaan produk dan institusi kecantikan tidak lagi semata-mata berdasarkan aspek kegunaannya, tetapi lebih sebagai ajang untuk memperoleh status dan kelas sosial. Konstruksi sosial dalam kapitalisme memandang perempuan hanya semata-mata dilihat sebagai komoditas. Akibatnya, berbagai mitos kecantikan yang diciptakan, memberikan penekanan yang lebih pada kualitas fisik. Dunia perempuan selalu ditampilkan dalam ruang yang serba fisikal. Konstruksi ini menjadikan perempuan teralienasi dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri semakin jauh dari totalitas kediriannya karena terfragmentasi dalam diri fisik semata. Kondisi seperti ini akan sangat menguntungkan bagi industri kapitalis. Tidak adanya konsep diri yang utuh, akan menjadikan kaum perempuan mudah terpedaya oleh persuasi iklan-iklan kecantikan dalam media massa yang lebih banyak menampilkan aspek kecantikan fisik saja. Kesimpulan Diskursus kecantikan, dalam kenyataannya telah menindas perempuan sendiri. Berbagai kekuasaan yang bermain di balik diskursus ini, mengkonstruksikan perempuan hanya sebagai objek semata. Makna dirinya dideterminasi oleh kekuasaan eksternal di luar dirinya sendiri. Akibatnya, perempuan tidak memiliki konsep diri yang otonom karena selalu tergantung oleh pemaknaan sosial. Konstruksi sosial telah mengalienasikan perempuan dari totalitas kediriannya. Penekanan sosial atas kualitas perempuan hanya pada penampilan fisiknya, menjadikan diri perempuan terfragmentasi dalam diri fisik semata. Objektivikasi ini akan terinternalisasi dalam kesadaran perempuan bahwa kualitas dirinya ditentukan seberapa besar ia memberi perhatian pada penampilan fisiknya. Kehidupan perempuan, pada gilirannya hanya berkutat pada pemenuhan-pemenuhan kebutuhan fisik. Perilaku konsumtif terhadap berbagai komoditi kecantikan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan dari konstruksi ini. Idealnya, perempuan harus mendapatkan kembali kepemilikan tubuhnya dengan mendefinisi ulang makna kecantikannya. Tampil cantik dan menarik tentu menjadi keinginan semua perempuan. Sepanjang hal itu didasari oleh sebuah konsep diri yang utuh dan otonom, maka pembebasan perempuan dari hegemoni kekuasaan eksternal akan terbentang lebar. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 9 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Endnote Hiperealitas (Hyper-Reality) adalah keadaan runtuhnya realitas, yang diambil alih oleh rekayasa modelmodel (citraan, halusinasi, dan simulasi), yang dianggap lebih nyata dari realitas sendiri sehingga perbedaan antara keduanya menjadi kabur. Lihat Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang Dilipat (Bandung: Mizan, 1999), hal. 161. 1 Di Inggris, kini ada 3.5 juta penderita anorexia dan bulimia (95% di antaranya adalah perempuan), dengan 6.000 kasus baru setiap tahunnya. Penderita penyakit ini juga banyak ditemukan di Rusia, Australia, Swedia, Italia, Amerika Serikat, dan Jepang. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Naomi Wolf, Mitos Kecantikan (Yogyakarta: Niagara, 2004), hal. 357-361. 2 Arkeologi dan genealogi merupakan istilah yang digunakan Michael Foucoult untuk mendeskripsikan dan menguraikan anatomi suatu kekuasaan yang ada dalam diskursus. Lihat Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press, 2002), hal.172. 3 Wacana atau diskursus adalah cara tertentu untuk membicarakan atau memahami dunia (atau aspek dunia ini). Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillips, Analisis Wacana: Teori & Metode (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). Menurut Yasraf Amir Piliang, Diskursus adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut saling berkaitan di antara semua aspek ini. Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia, hal. 14. 4 5 Naomi Wolf, Mitos, hal. 28-31. 6 Ibid., hal. 25-26. Annastasia Melliana S., Menjelajah Tubuh: Perempuan dan Mitos Kecantikan (Yogyakarta: LKiS, 2006), hal. 45. 7 8 Ibid., hal. 47. M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 59-60. 9 10 Geoffrey Parrinder, Teologi Seksual (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 214-215. 11 Annastasia Melliana S., Menjelajah, hal. 63-64. Ibid., hal. 64. 13 Ibid., hal. 67. 12 Ibid., hal. 68-73. 15 Ibid., hal. 50-51 16 Ibid., hal. 52-53. 17 Ibid., hal. 54. 18 Ibid., hal. 55. 19 Ibid., hal. 57. 14 20 Fachrizal A. Halim, Beragama dalam Belenggu Kapitalisme (Magelang: Indonesia Tera, 2002), hal. 60-63. 21 Yasraf Amir Pilliang, Sebuah Dunia, hal. 246. 22 Ibid., hal. 216. Daftar Pustaka P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 10 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256 Fakih, Mansour. 2002. Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press. Halim, Fachrizal A. 2002. Beragama dalam Belenggu Kapitalisme. Magelang: Indonesia Tera. Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips. 2007. Analisis Wacana: Teori & Metode. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Melliana S., Annastasia. 2006. Menjelajah Tubuh: Perempuan dan Mitos Kecantikan. Yogyakarta: LKIS. Parrinder, Geoffrey. 2004. Teologi Seksual. Yogyakarta: LKiS. Piliang, Yasraf Amir. 1999. Sebuah Dunia yang Dilipat. Bandung: Mizan. Shihab, M. Quraish. 2005. Perempuan: dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru. Jakarta: Lentera Hati. Wolf, Naomi. 2004. Mitos Kecantikan. Yogyakarta: Niagara. P3M STAIN Purwokerto | Elya Munfarida 11 Ibda` | Vol. 5 | No. 2 | Jul-Des 2007 | 241-256