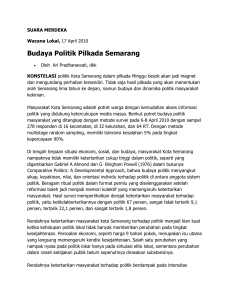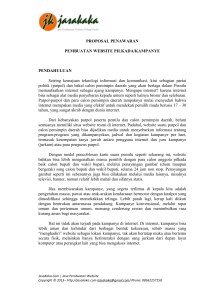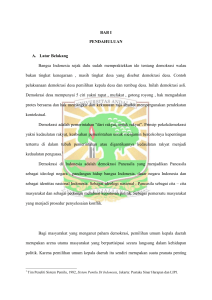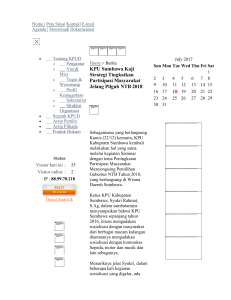MENAKAR DAMPAK PILKADA LANGSUNG: Studi Pilkada
advertisement

MENAKAR DAMPAK PILKADA LANGSUNG: Studi Pilkada Langsung Gubernur Jawa Timur 2008 Surwandono dan Witri Elvianti [email protected] dan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Abstrak Artikel ini menjelaskan tentang relasi biaya sosial, ekonomi, politik dan budaya yang harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat lokal terkait dengan proses demokratisasi local. Diskursus ini sedemikian mengemuka untuk menakar produktivitas demokrasi langsung di dalam arena politik local. Studi ini menunjukan bahwa biaya politik yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat local masih sebanding dengan berkembangnya demokratisasi local. Pilkada langsung mampu mentransformasi maupun mendekonstruksi nilai-nilai local menjadi lebih demokratis. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap dokumen-dokumen, wawancara terhadap narasumber yang relevan. Key Words: Biaya Politik, Dampak Pilkada Langsung, Demokrasi Lokal Pengantar Sejak runtuhnya rezim otoriter orde baru, secercah harapan untuk demokrasi yang tidak semu mulai hadir di benak masyarakat Indonesia. Segera setelah otonomi daerah digelar, pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) seolah menjadi menu utama pemerintah pusat dengan tujuan masyarakat Indonesia telah siap masuk ke dalam babak baru era demokrasi. Ironisnya, sekali lagi, tidak hanya kabar baik yang mengiringnya, sederet kabar buruk akan terjadinya disintegrasi, konflik etnik dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi terus membayangi demokratisasi di Indonesia terlebih lagi pada saat Pilkada tersebut diselenggarakan. Sejak tahun 2005 hingga Agustus 2008, Indonesia telah mencatat prestasi yang terang benderang. Tercatat bahwa sebanyak 360 kali Pilkada tingkat kabupaten dan 20 tingkat provinsi telah dilaksanakan di Indonesia, sebagai bukti betapa kuatnya komitmen rezim SBY terhadap pengejawantahan nuansa demokrasi. Dari total provinsi dan kabupaten yang melaksanakan Pilkada ini, secara umum, ada dua partai politik besar yang masih mendominasi arena perpolitikan nasional dan lokal, yaitu PDI Perjuangan dan Golkar. PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pilkada di 15 Provinsi dan 166 kabupaten/kota sementara Partai Golkar berhasil menorehkan tinta emasnya di hanya 7 provinsi dan 154 kabupaten/kota.1 Barangkali Indonesia perlu berbangga hati dengan keberhasilan tersebut karena besarnya kuantitas pemilihan kepala daerah langsung yang telah dilaksanakan. Namun, rezim pemerintah tidak perlu melulu menjualnya sebagai bukti keberhasilan pemerintah mengingat realita politik yang ada. Pelaksanaan Pilkada tidak semuanya berjalan dengan mulus dan bebas hambatan. Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga saat ini menunjukkan kecenderungan akan terjadinya demokrasi transaksional dan terjebak dalam nuansa elektoralisme. Seharusnya, Pilkada menjalankan perannya dalam bingkai dictum penguatan demokrasi kerakyatan sebagai bentuk dukungan atas pelembagaan demokrasi di tingkat lokal. Namun, yang terjadi adalah Pilkada kerap berubah menjadi media transaksi politk dengan motif ekonomi segelintir elit politik lokal. Pilkada tidak disertakan dengan kedewasaan berpolitik dan profesionalitas penyelenggaraan sehingga seringkali menuai konflik horizontal antar elemen masyarakat setempat. Perlu diketahui pula, hampir 40% dari total daerah penyelenggara Pilkada menghadapi konflik dan sejumlah kasus hukum.2 Tak jarang, ajang penguatan pelembagaan demokrasi lokal itu diwarnai dengan tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum bahkan bentrokan fisik antar pendukung yang mengusung masing-masing calon kepala daerah. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri mencatat sedikitnya 23 daerah mengalami konflik Pilkada. Pada 23 Juli 2008, Jawa Timur melaksanakan perhelatan akbar. Pemilihan kepala daerah langsung digelar. Sebagai catatan, banyak pengamat politik yang menggarisbawahi signifikansi pengawalan ekstra ketat terhadap persiapan dan penyelenggaraan Nur Iman Subono dalam Dari “Civil Society” ke “Blok Demokratik”: Masalah dan Tantangannya di Indonesia, Jakarta, Oktober 2008. 2 Dilaporkan oleh seorang wartawan surat kabar harian SuaraKarya, Yudhiarma MK, dalam Menyoal Legitimasi dan Potensi “Kudeta” Pasca Pilkada. Dapat diakses di http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=114440 yang diakses pada 15 September 2009 1 Pilkada Jawa Timur tersebut. Hal ini dikarenakan keberagaman etnik, adanya pengaruh tokoh agama yang kuat dengan masyarakat sehingga ada kekhawatiran gerakan memobilisasi grass root oleh elit lokal, dan latar belakang sejarah yang pernah melibatkan etnis tertentu dalam konflik sosial yang masif dan destruktif beberapa waktu yang silam. Hasil akhir dari pemilihan putaran pertama menghasilkan dua pasang kandidat dengan suara mayoritas yaitu Syaifullah Yusuf dengan Sukarwo (KarSa) dan Kofifah dengan Mudjiyono (KaJi). Hingga pelaksanaan pemilihan putaran kedua, Pilkada Jawa Timur didominasi oleh konflik horizontal yang cenderung mengarah pada disintegrasi atau pembelahan sosial. Konflik diawali dengan penemuan kecurangan yang dilakukan baik selama persiapan Pilkada hingga tahap penyelenggaraan. Kecurangan itu berkisar pada data fiktif DPT, proses penyusunan DPT yang tidak transparan. Alhasil, konflik horizontal yang melanda Pilkada Jawa Timur tersebut berdampak pada dimensi masyarakat Jawa Timur secara ekonomi dan politik, hukum dan keamanan serta sosial dan budaya. Ibarat dua mata koin yang saling bersebelahan, dampak tersebut bisa menjadi sesuatu yang konstruktif namun juga boomerang. Kerangka Dasar Teoretik Lembaga Informasi Nasional (LIN) selama 5 tahun terakhir melakukan penelitian terhadap konflik-konflik etnis di Indonesia, baik di Papua, Poso, Ambon, Aceh, SampitDayak, maupun di Jawa Timur. Terdapat temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh LIN bahwa konflik etnis di daerah konflik sangat berhubungan erat dengan proses pemilihan kepala daerah.3 Issue etnik sengaja dipilih oleh para kandidat kepala daerah untuk meningkatkan derajat representasi di depan publik, sehingga jika suatu kandidat dari etnik tertentu kalah dalam Pilkada, maka kemudian dimaknai sebagai kekalahan etnik. Makna seperti inilah yang kemudian dikelola oleh para elit politik yang kalah dalam politik untuk melakukan bargaining politik melalui penciptaan konflikkonflik horisontal. Temuan yang juga menarik adalah adanya kecenderungan besar bahwa adanya kekurangsiapan kelembagaan dan instrumen politik untuk menghadapi ledakan konflik 3 Lihat lebih jauh dalam Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional, 2004 seputar pilkada. Pengelola pilkada seperti KPUD dan pemerintah daerah seringkali terlambat melakukan respon yang memadai sehingga ekskalasi konflik pilkada menjadi meluas, dan akhirnya menjadi konflik horisontal yang bernuansakan etnik. Dari beberapa konflik pilkada di Maluku Utara maupun Poso, ada kecenderungan proses penyelesaian konflik cenderung menggunakan pendekatan security approach dibandingkan dengan political approach. Penyelesaian konflik horisontal melalui pendekatan keamanan sesungguhnya mengambarkan bahwa kapasitas politik dari pemerintah daerah dan KPUD yang didukung oleh Panwaslu maupun aparat keamanan tidak mampu mengelola Pilkada secara komprehensif. Pada sisi yang lain, penyelesain dengan menggunakan security approach hanya menciptakan perdamaian secara sementara, atau sering dikenal dengan konsep negative peace. Bukan tidak mungkin, penyelesaian menggunakan pendekatan keamanan justru membuat konflik horisontal menjadi sangat akut dan sulit terselesaikan. Dalam studi yang dilakukan oleh Surwandono terlihat bahwa konflik Pilkada di Ambon maupun Poso, setelah mengalami ekskalasi yang sangat serius menjadi konflik yang bersifat primordial, telah menggubah peta konflik dari konflik lokal menjadi nasional bahkan internasional. Kelompok Islam maupun Kristen dari luar Poso maupun Ambon kemudian saling berkonflik secara intensif. Bahkan juga ditemukan fakta konflik Pilkada tersebut menjadi konflik yang kemudian berhubungan erat dengan aktivitas terorisme.4 Studi yang dilakukan oleh majalah Tempo dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia juga menggambarkan bahwa ; Di banyak tempat, pilkada diwarnai oleh konflik horizontal, yang justru lebih sarat dengan muatan politis, daripada konflik sosial-kultural. Di beberapa tempat KPUD menjadi langganan demo massa pendukung calon yang tidak lulus verifikasi. Di Indragiri Hulu, demo massa mendorong KPUD untuk melakukan koordinasi dengan desk pilkada, berkaitan dengan pencalonan salah satu kandidat. Di Jayapura, Papua, KPUD terpaksa mengundurkan pengumuman nama calon. Di Jember, ketidakpuasan terhadap KPUD "diekspresikan" dengan membakar kantor tersebut. Selain dengan KPUD, kelompok pendukung calon juga bentrok dengan panitia pengawas daerah, atau kelompok pendukung dari calon lainnya.5 4 5 Lihat lebih jauh analisis Surwandono dalam “Poso dan Fogging DPO”, Republika, Juli 2007 Majalah Mingguan TEMPO Edisi 24 Juli 2005 Studi yang dilakukan oleh Suwandi Sumartias6 menunjukkan beberapa fakta kekerasan dan konflik horizontal. Di Padang Pariaman (Sumatra Barat) misalnya, pilkada berbuntut perusakan kantor KPUD setempat. Aksi pendudukan, pengepungan kantor KPUD, bentrokan dengan petugas keamanan, dan sejenisnya terjadi di tempattempat seperti Depok (Jawa Barat), Semarang dan Sukoharjo (Jawa Tengah), Mataram (NTB), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gowa (Sulsel), Gorontalo, Cilegon (Jawa Barat), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), dan Kaur (Bengkulu). Laporan yang mendalam yang dilakukan oleh Jawa Pos tentang beragam konflik dalam Pilkada di beberapa propinsi di Jawa7 menunjukkan bahwa konflik dalam pelaksanaan pilkada terbagi dalam 4 kelompok besar; pertama, konflik sebelum pelaksanaan pilkada, biasanya terkait dengan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang seringkali tidak up-date ataupun banyak nama-nama ganda. Kedua, pelaksanaan kampanye pilkada, di mana ditandai dengan konflik antar kandidat, baik dengan menggunakan black campaign maupun negative campaign, melalui politik pencitraan secara sefihak. Ketiga, pelaksanaan pemungutan suara, yang ditandai dengan tidak netralnya PPS maupun tidak adanya Tim Pemantau Independen, maupun mobilisasi pemilih melalui money politics dari kandidat. Dan keempat, penghitungan suara dan penetapan pemenang Pilkada oleh KPUD, yang ditandai dengan konflik seputar keabsahan penghitungan, penggelembungan suara Metode Penelitian A. Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang factor-faktor yang menyebabkan konflik horizontal maupun pola-pola ekskalasi dalam pelaksanaan pilkada secara langsung. Langkah untuk mengetahui penyebab dan pola konflik horizontal dalam pelaksanaan Pilkada langsung sebagai berikut 1) bagaimana stakeholders dari Pilkada langsung, baik partai politik, 6 Lihat lebih jauh dalam http://www.ijrsh.wordpress.com Jawa Pos, “Catatan Kritis Atas Pilkada di Beberapa Daerah: Depdagri Akar Konflik Pilkada, 3 Oktober 2005 dalam Kajung Maridjan, “Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal”, makalah yang disampaikan pada , “In-House Discussion Komunikasi Dialog Partai Politik”, yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID) Jakarta, 16 November 2007 7 kandidat kepala daerah, media massa, organisasi social dan kemasyarakat, dalam memandang konflik horizontal dalam pilkada langsung 2) bagaimana kesiapan sistemik dari pemerintah dan pengelola pilkada langsung baik KPUD, Panwaslu, KPU dan Bawaslu terhadap kemungkinan terjadinya konflik horizontal dalam pilkada langsung. B. Tekhnik pengumpulan data Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dari para stakeholders dan pengelola pilkada langsung, baik melalui pengumpulan dokumen-dokumen kebijakan politik terkait dengan pilkada langsung, maupun dokumen dari media massa yang melakukan proses peliputan maupun framing terhadap konflik yang muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung. Untuk memperoleh data primer terkait dengan upaya mengetahui penyebab kritikal dan pola ekskalasi konflik dilakukan melalui deep interview dengan para narasumber yang kompeten. Ada sekitar 15 orang narasumber yang menjadi rujukan dalam deep interview ini, baik di tingkat nasional maupun propinsi. 1. Bawaslu, merupakan lembaga yang memiliki fungsi secara langsung dalam proses pengawasan pelaksanaan Pemilu. Salah seorang personel Bawaslu yang telah dilakukan wawancara adalah dengan Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP, M.Si tentang tata aturan Bawaslu dalam proses pengawasan dan laporan hasil pengawasan terhadap sejumlah pelaksanaan Pemilu. Terkait dengan Pilkada di Jatim, diperoleh dari wawancara dengan Panwas Propinsi Jawa Timur 2. DPR, dalam hal ini terkait dengan proses pembuatan UU Partai Politik, maupun Pilkada Langsung. Yang dipetakan dari anggota DPR adalah bagaimana produk UU tentang Partai Politik dan Pilkada Langsung memiliki instrument yang memungkinkan bisa merespon secara cepat terhadap kemungkinan konflik yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada, baik konflik karena aturan penyelenggaraan, penyelenggaran, maupun proses penetapan. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan Agus Purnomo,S.IP, anggota fraksi PKS di DPR. Untuk memperkuat pandangan para politisi dalam memandang UU tentang Pilkada Langsung juga dilakukan wawancara dengan Takdir Ali Mukti, yang selama dua periode telah menjadi anggota DPRD di Yogyakarta. 3. Kepolisian, dalam hal ini dilakukan deep interview dengan dua orang, yakni mantan Kapolda Jatim (yang mengundurkan diri) dalam proses pelaksanaan Pilkada Jatim, maupun dengan Kapolda Jatim definitif, tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam proses mengantisipasi konflik pilkada Jatim Timur. Yang ditelusur adalah kebijakan pelembagaan mengantisipasi konflik, baik melalui pendekatan keamanan, politik, maupun social budaya. 4. KPUD Jatim, dalam hal ini dilakukan interview kepada mantan pengurus KPUD Jatim, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Jatim yang berlangsung di tahun 20082009, di mana sekarang ini sudah ada pergantian pengurus KPUD Jawa Timur per Maret 2009. Data yang diperoleh dari mantan anggota KPUD Jatim adalah terkait seputar konflik dalam pilkada Jatim, baik dalam persoalan DPT fiktif, maupun masalah penghitungan suara ulang, dan pencobolosan ulang di beberapa kabupaten baik Sampang, Bangkalan dan Pamekasaan. Wawancara dilakukan terhadap 2 anggota KPUD Jawa Timur yakni Arief Budiman dan Didik . 5. Panwas Jatim, dalam hal ini dilakukan terhadap laporan dan analisis pelaksanaan Pilkada Jatim, sebab-sebab konflik terjadi, dan factor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dalam proses Pilkada Langsung tidak memicu lahirnya konflik horizontal. Wawancara dilakukan terhadap Sugeng Pudjiatmoko, yang selama ini aktif menjadi pengawas Pemilu yang berasal dari unsure birokrasi. Wawancara juga dilakukan terhadap ketua JPPR wilayah Jatim, Sukardjo, untuk memperdalam persoalan pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada Jatim yang berlangsung sampai 3 putaran. 6. Organisasi Sipil. Ada dua organisasi sipil yang dipilih, yakni Muhammadiyah dan NU. Sedari awal memang tidak terdapat kandidat dari cagub maupun cawagub yang berasal dari anggota Muhammadiyah, namun posisi Muhammadiyah tetap penting karena sedari awal pula PW Muhammadiyah melakukan sosialisasi secar massif untuk mendorong pelaksanaan Pilkada langsung secara damai. Yang akan ditelusur adalah mengapa Muhammadiyah terlibat dalam konteks kampanye politik damai meskipun tidak ada anggota Muhammadiyah yang menjadi bakal calon. Untuk menggali informasi ini maka dilakukan wawancara dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya dengan Ketua Majlis Hikmah, Ustadz Munthalib Sukandar. Sedangkan NU, merupakan satu-satunya organisasi yang menyumbangkan semua kandidat, bahkan ada seorang kandidat yang kebetulan menjadi pengurus di PWNU Jatim, kemudian memilih mengundurkan diri guna memuluskan jalan dalam pencalonannya. Yang ditelusur adalah bagaimana NU, yang menjadi payung organisasi para kandidat kepala daerah, melakukan politik managemen konflik untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang terjadi sesama warga NU. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan wakil sekretaris Pimpinan Wiayah NU, Nur Hidayat, yang menjelaskan seputar kebijakan dasar NU terkait dengan Pilkada, maupun pembentukan Halaqah Maslahah ‘Ammah menjelang Pilkada. Wawancara juga dilakukan terhadap sekretaris Lakspedam NU, Ahmad Faisal, seputar kebijakan NU dalam mengantisipasi mobilisasi konflik dengan menggunakan instrumentintrumen keorganisasian NU. 7. Tim Sukses, terutama dari Karsa dan Kaji. Tim sukses merupakan mesin politik dari pasangan calon untuk mendapatkan suara melalui proses mobilisasi massa, bahkan terkadang melakukan politisasi issue, dari proses soft campaign, negative campaign sampai dengan black campaign. Data yang ditelusur adalah 1) bagaimana tim sukses suatu calon memandang dan mempersepsi calon lain, 2) bagaimana tim sukses memandang proses kompetisi sebagai bagian dari konflik, 3) bagaimana tim sukses merespon issue yang memojokkan ataupun memprovokasi calon yang didukung. 4) Bagaimana tim sukses memaknai proses kalah dan menang dalam Pilkada, dan 5) bagaimana tim sukses menaati aturan main pelaksanaan Pilkada. Wawancara dilakukan terhadap anggota tim sukses Khofifah-Mujiono, Muh. Mirdasy, yang juga memberikan jawaban tertulis terhadap pendalaman pertanyaan yang disampaikan tim peneliti. Informasi tentang strategi dan pilihan politik Kaji, juga diperoleh dari beberapa anggota pimpinan wilayah NU Jawa Timur yang menjadi simpatisan dan pendudung pasangan ini. Sedangkan untuk wawancara terhadap tim sukses Sukarwo-Syaifullah Yusuf, dilakukan terhadap Martono maupun Ana Luthfie. Namun karena kesibukan yang sangat padat, keduanya tidak bisa diwawancara secara langsung dan hanya memberikan gambaran secara umum. Sehingga dalam upaya membangun obyektivikasi lebih mengandalkan kepada release yang disampaikan tim sukses Karsa dalam media massa. 8. Tokoh masyarakat di Madura, baik di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Wawancara ini untuk mengeksplorasi beberapa issue krusial seperti tradisi kekerasan dalam menyelesaikan konflik (Carok), maupun issue mobilisasi dukungan melalui organisasi social keagamaan dan praktek politik uang dalam Pilkada serta persoalan pandangan masyarakat Madura terhadap pelaksanaan Pilkada yang berlangsung sampai 3 kali putaran. Untuk mengetahui informasi ini dilakukan wawancara terhadap KH. Junaidi dan H. Abdul Manan, merupakan tokoh masyarakat Madura di daerah Pamekasan. C. Teknis analisis data Untuk mendapatkan obyektivikasi yang tinggi dalam penelitian ini, dilakukan analisis secara bertahap. Pertama, melakukan analisis isi terhadap dokumen-dokumen kebijakan politik dan perundangan-undangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pilkada langsung, untuk mengetahui pengaruh kebijakan, instrument maupun sumber daya yang dipergunakan untuk mengelola konflik selama pilkada langsung. Kedua, melakukan analisis framing terhadap ekspos media massa terhadap pemilu maupun konflik horizontal yang terjadi selama pelaksanaan pilkada langsung, untuk mengetahui posisi media dalam konflik, apakah menjalankan peran sebagai media massa damai, atau justru menjadi media massa provocator. Hal ini terkait dengan saran dari beberapa stakeholders pilkada Jatim yang menempatkan media massa sebagai salah satu unsur penting dalam pemberitaan konflik Pilkada. Ketiga, melakukan interpretasi dari berbagai temuan dokumen, , wawancara mendalam untuk membuat benang merah hubungan antar variable yang menyebabkan konflik sekaligus memetakan pola ekskalasi konflik. Hasil interprestasi ini digunakan sebagai bahan dasar bagi penyusunan kebijakan early warning system dalam mengantisipasi konflik pilkada secara langsung. Dampak Politik: Bipolarisasi Masyarakat Sipil Pemilihan putaran kedua telah meloloskan dua pasang kandidat yaitu KarSa dan KaJi. Meskipun saling berkompetisi demi memenangkan kontestasi politik, Syaifullah Yusuf (calon wakil gubernur dari pasangan KarSa) dan Khafifah Indar Parawansa (calon gubernur dari pasangan KaJi) sejatinya memiliki afiliasi ideologi yang sama. Keduanya adalah kader utama NU. Pada saat Pilkada, keduanya masih menjabat posisi strategis di dua lembaga otonom NU, Syaifullah sebagai ketua Gerakan Pemuda Anshor sementara Khafifah sebagai ketua Muslimat, organisasi perempuan terbesar milik NU. Sejak kedua tokoh muda NU tersebut memutuskan untuk bersaing dalam kancah Pilkada, isu pecahnya suara ulama NU telah mulai terdengar. Bukan suatu hal yang biasa, bagi warga NU mendapatkan izin politis dari para ulama adalah hal yang istimewa. Hal ini diakibatkan karena budaya NU yang dipandang masih tradisionil. Warga NU memiliki keterikatan dan kepatuhan yang sangat besar dengan para agamawan. Inilah, ketaatan dan kepatuhan para santri dan warga Nahdlyin seringkali disalah-gunakan oleh segelintir oknum yang ingin meloloskan kepentingan politisnya. Kondisi kultural seperti ini sangat rawan dengan bias kepentingan. Bila berkaca pada pengalaman silam, NU dan kancah politik bukan hal yang terpisah. Secara singkat, kader NU diperbolehkan terjun dalam arena politik demi menyebarluaskan misi dakwah NU untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang menyejukkan semesta alam. Aktivitas politik NU telah lama terlibat dalam dunia politik. Pada era 1950an, dengan jelas dan lantang, NU mendukung suara politiknya dari masa ke masa, mulai dari terbentuknya partai Masyumi untuk beberapa dekade hingga akhirnya suara NU terakomodasikan oleh PPP. Namun, bergulirnya era reformasi di Indonesia paska runtuhnya rezim Soeharto, kesatuan suara pun terancam dengan kehadiran banyak partai politik yang mengaku berafiliasi dengan NU. Jadilah, kader politik NU terpecah. Seharusnya warga NU terlebih lagi para pemimpin dan ulamanya bisa mengambil arti pelajaran dan pengalaman yang penting dari sejarah. Alih-alih mencerahkan, perpecahan politik hanya akan memperburuk kondisi umat. Banyak pengamat konflik sosial berharap penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur tidak akan memecah belah suara NU karena ini akan berkomplikasi pada efek detrimental yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ekspektasi ini tidak terjadi selama Pilkada Jawa Timur, setahun yang lalu. Masing- masing kandidat sibuk mencari restu para ulama. Bipolarisasi politik melanda warga NU. NU terbelah menjadi dua kubu utama yakni antara pemilih pasangan SoekarwoSyaifullah Yusuf (KarSa) dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi). Dengan mulusnya, KarSa dengan basis dukungan Partai Demokrat, PKS dan PAN mendapatkan restu dari kiai sepuh, karena mayoritas kiai sepuh masih memandang kepemimipinan perempuan dalam wilayah publik dan politik adalah hal yang tabu dan tidak sesuai dengan prinsip Islami. Sementara itu, KaJi yang didukung penuh oleh PPP dan aliansi 12 partai gurem tanpa ada embel-embel PKB, juga mengantongi dukungan politik penuh dari organisasi yang dipimpinnya,Muslimat, dan beberapa kiai langitan penting seperti Hasyim Muzadi. Tentu saja, banyak pihak yang mengkhawatirkan pecahnya kekuatan NU selama Pilkada Jawa Timur diselenggarakan. Hal ini akan mengancam peranan NU yang sebenarnya. Sejatinya, para ulama bisa memaksimalkan peran nya sebagai social control dan moral forces hingga bisa memantau kecurangankecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh kader NU sendiri. Kondisi miris ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang baru sekitar lima tahun ini menerpa perpolitikan lokal di Indonesia. Kekuatan civil society sangat mempengaruhi perjalanan pelembagaan dan perwujudan substansial demokratisasi. Menurut Larry Diamond dan Brian C Smith, esensi dari demokratisasi pemerintah lokal adalah untuk memperluas kesempatan check and balances antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat.8 Karenanya, pemerintah daerah sangat membutuhkan kemandirian dan kedewasaan politik para elit politik lokal dan civil society organization seperti NU9, untuk melakukan kontrol sosial politik dan pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini, secara jelas, sesuai dengan khitah politik warga NU. Tidak ada yang salah jika perbedaan pandangan politik mekar di tubuh NU. Justru hal ini menandakan awal dari kedewasaan berpolitik itu sendiri. Namun, secara ideal, para kaum intelektual NU harus bisa memposisikan diri kapan dan dimana mereka harus mengenakan seragam jami’yyah (institusi) atau kendaraan politik pribadi. 8 Kacung Maridjan, dalam Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal, Jakarta, November 2007. 9 Beberapa akademisi beranggapan bahwa kehadiran NU dan Muhammadiyah merupakan titik sejarah awal lahirnya gerakan civil society di Indonesia. Apa yang terjadi di Pilkada Jawa Timur sangat berbeda dengan harapan idealita tersebut. Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Kajian Nusantara (Laksnu) Gugus Joko Waskito, kisruh pilkada Jawa Timur menjadi bukti bahwa kyai NU lebih memilih terlena menikmati “berkah” dari komparador politik daripada mengurus warga NU. NU secara institusi terbuai oleh pragmatisme politik sempit yang dimotori oleh kader dan petinggi organisasi.10 Bipolarisasi konfigurasi politik NU telah memunculkan stigma baru yaitu kyai vs santri. Kyai dipandang sebagai kekuatan penuh para “orang tua” yang tertuju pada KarSa sementara terminologi “santri” diarahkan pada “anak muda” yang melakukan perlawanan ideologi, yang merepresentasikan dukungan terhadap KaJi. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi psiko-sosial kader grass root NU yang barangkali apolitis dan acuh dengan sikap politik para kyai nya. Stigmatisasi dan fragmentasi ini berimplikasi pada degradasi kepercayaan public atau warga NU terhadap peran ulama dalam dimensi kehidupan yang lebih luas. Intervensi politik Hasyim Muzadi dengan segala maneuver politik nya dianggap sudah melampaui batas sehingga berpotensi memicu terjadinya keretakan sosial dan melemahnya ukhuwwah islamiyah di kalangan NU. Sebagai catatan penting, di Bojonegoro, telah ditemukan adanya indikasi melemahnya kepercayaan public terhadap peran ulama di Bojonegoro (baik selama Pilkada Bojonegoro maupun Pilkada Jawa Timur kemarin). Hal ini terjadi karena masyarakat sudah jenuh dengan drama politk yang dipertontonkan oleh beberapa kyai. Masyarakat memandang, kadang-kadang, tidak ada kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan apa yang diperlakukan oleh banyak kiai NU.11 Lagipula, Kacung Maridjan membenarkan hal itu. Menurutnya, penurunan secara drastis atas dukungan atau bahkan kepatuhan santri dan warga NU terhadap keputusan 10 R Ferdian Andi R, Jatim Terbentur, NU Babak Belur, inilah.com Jakarta, dapat diakses di http://www.inilah.com/berita/pemilu-2009/2008/12/02/65748/jatim-terbentur-nu-babak-belur/ yang diakses pada 10 Oktober 2009 11 Pada Juni-Juli 2007, sebuah penelitan Komunitas Tabayun oleh Prof Dr Nur Syam dilakukan di beberapa pesantren besar di Jawa Timur. Salah satu hasil pentingnya, para santri mengatakan bahwa mereka masih menjadikan kiai sebagai rujukan dalam masalah agama tapi tidak untuk masalah politik. Bagi para santri, kiai tidak lagi merepresentasikan suara politik ideal sehingga bukanlah sebuah dosa jika santri tidak patuh dengan pilihan politik kiai. Dirujuk oleh Akhmad Zaini dalam Nu dan Pilkada Bojonegoro, Dipublikasikan di Jawa pos, 12 Desember 2007. politik para kiai dalam Pilkada dikarenakan polarisasi dukungan politik sejumlah kiai ke beberapa partai politik yang diawali pada Pemilu 2004 lalu.12 Jika kemudian di Jawa Timur telah terjadi bipolarisasi konfigurasi politik NU maka setidaknya realita ini juga memiliki tendensi atas pelemahan politik secara nasional. Jawa Timur seringkali dijadikan barometer politik nasional. Temperatur politik yang kian memanas di Jawa Timur selama penyelenggaraan Pilkada menjadi ancaman tersendiri bagi kader NU secara nasional mengingat Jawa Timur adalah basis utama dan terbesar massa NU di Indonesia. Delegitimasi Pilkada Sebagai Pelembagaan Demokratisasi Selain berimplikasi pada bipolarisasi konfigurasi politik lokal seperti yang terjadi di Jawa Timur, konflik horizontal juga berpotensi atas delegitimasi Pilkada sebagai sarana pelembagaan demokrasi lokal. Merujuk pada bangunan teori kelembagaan baru (new institutionalism) bahwa pilihan disain kelembagaan yang dianut oleh suatu Negara memiliki pengaruh terhadap wajah demokrasi yang dimiliki. Oleh Kacung Maridjan, dituliskan bahwa pada awalnya, disain kelembagaan yang ditempuh untuk menumbuhkan demokrasi adalah melalui pembukaan system multi partai dan adanya pemilu yang bebas dan adil. Hal ini juga menurun pada level daerah. Menurut Brian C Smith, ada korelasi positif antara penguatan demokrasi lokal dengan perbaikan demokrasi pada tingkat nasional. Oleh karena itu, demi terwujudnya perbaikan kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah memberlakukan pemilihan kepala daerah sebagai media alternatif yang efektif untuk penguatan pelembagaan demokratisasi di tingkat daerah. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Pemerintah lupa, atau mungkin belum siap, melakukan langkah antisipatif atas kecurangan-kecurangan, penyalahgunaan wewenang dan fenomena raja kecil daerah yang meracuni kesaktian Pilkada itu sendiri. Data kecurangan pilkada yang kemudian memicu konflik antar masa dan tim sukses calon kepala daerah banyak ditemukan di lapangan. Pelanggaran dan ketidak-jelasan data daftar pemilih tetap oleh KPU disinyalir sebagai akibat tingginya angka golput pada pelaksanaan pemilihan gubernur di daerah. Di Sumatra Utara angka golput mencapai 41,83% dan di Jawa 12 Ibid,. Tengah melebihi angka tersebut dan mencapai hampir 50% masyarakat Jawa Tengah tidak menyuarakan pilihan politik mereka. Tidak berbeda dengan kasus konflik Pilkada di daerah yang lain, Pilkada Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. Pelanggaran dan ketidakjelasan data DPT adalah hal utama yang menyebabkan gesekan politik kerap terjadi di antara tim sukses khususnya antara KaJi dan KarSa. Berulang kali, tim sukses dan masa pendukung KaJi melakukan unjuk rasa dan aksi masa, walau cenderung damai, menentang keputusan KPU provinsi yang dipandang memihak ke salah satu calon. Pernah, pada saat KPU Provinsi sedang mengumumkan hasil rekapitulasi suara pada pemilihan putaran ke dua, masa tim KaJi mengepung kantor KPU guna menekan KPU agar tidak mengumumkan KarSa sebagai kandidat terpilih dikarenakan kecurangan yang terjadi secara masif. Eksekutif Indo Barometer, Mohamad Qodari menyatakan bahwa perlu adanya kedawasaan berpolitik dari pasangan calon jika tidak maka konflik horizontal Pilkada Jawa Timur bisa berubah menjadi malapetaka yang lebih destruktif dari apa yang terjadi di Maluku Utara. Sesuai dengan perhitungan KPUD Jawa Timur, pasangan KarSa berhasil memenangkan perolehan akhir suara dengan jumlah suara 7.729.944 suara atau sekitar 50,20% sementara itu KaJi meraih 7.669.721 suara atau 49.80%. Angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Jawa Timur putaran kedua yang berlangsung 4 November 2008 lalu ternyata masih sangat rendah. Angka golput pada Pilkada Jawa Timur putaran ke dua mencapai 13.880.805 suara atau 47%. 13 Konflik memanas dan memuncak pada saat pasangan calon KaJi memaksa KPU pusat untuk segera membentuk dewan kehormatan KPU untuk menghakimi anggota KPUD Jawa Timur yang diduga melakukan kecurangan data fiktif. Praktik curang pada Pilkada Jawa Timur merupakan kecurangan yang tersistematis. Beberapa pihak menduga adanya pemanfaatan pola intervensi dan manipulasi data pemilih hingga ratusan ribu suara pemilih yang digandakan. Modus yang digunakan adalah “Nomor Induk Kependudukan” (NIK) digandakan untuk beberapa pemilih serta pemilik dengan NIK dan nama yang sama tetapi alamat tinggal berbeda. 13 Chusnun Hadi, Sikapi Pilkada Jatim Secara Dewasa, www.sinarharapan.co.id/berita/0811/12/sh01.html yang diakses pada 5 September 2009 Praktik manipulasi daftar suara pemilih merupakan pelanggaran serius dalam proses pemilu dan akhirnya mengancam demokrasi di tingkat lokal hingga nasional. Pemenang sebuah Pilkada yang curang tidak akan memiliki wibawa dan legitimasi yang kuat untuk memimpin sebuah daerah.14 Apalagi pada level daerah, masyarakat memiliki kedekatan hubungan emosional dan personal dengan calon kepala daerah mereka. Situasi ini membuat derajat ketampakan konflik horizontal semakin dekat dengan masyarakat. Dengan kenyataan ini, maka legitimasi rendah pemenang Pilkada Jawa Timur dan banyaknya kecurangan yang ditemukan di lapangan pada saat pelaksanaan Pilkada akan menjadi sumber delegitimasi dan instabilitas kepala daerah dan pemerintah daerah terpilih selama lima tahun masa jabatan.15 Di Jawa Timur, konflik Pilkada telah meluas hingga menyentuh tatanan relasi sosial antar agamawan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh the Wahid Institute, Pilkada di Kabupaten Sampang yang diperparah dengan pemilihan ulang telah merusak hubungan kultural antara kiai dengan santri. Juga, terjadi pengotakan pesantren yang ada di Madura. Para ulama dan pesantren kini telah mengarah pada golongan-golongan. Akibatnya, hubungan antar ulama dan pesantre menjadi renggan dan rapuh.16 Lebih berbahaya lagi, situasi ini akan menjadikan suasana semakin keruh. Tuntutan dari sejumlah pihak untuk mempertanyakan efektifitas Pilkada sebagai jembatan menuju demokratisasi lokal muncul kembali. Dalam masalah ini, NU yang “terkorbankan” dalam Pilkada Jawa Timur setahun lalu, menyatakan hal demikian. Bagi NU, selama ini Pilkada tidak banyak memberikan bukti akan perbaikan politik dan bidang kehidupan lainnya. Justru, konflik semakin meluas. PB NU menarik konklusi bahwa penyelenggaraan Pilkada telah memancing berbagai kenaifan dan ironi yang berseberangan dengan tujuan awal dari Pilkada. Pilkada hanya memperluas friksi sosial politik.17 Konflik horizontal Pilkada akan memperkeruh suasana politik dan berimbas pada delegitimasi pemerintahan yang terpilih. Jika demikian, maka potensi “kudeta” 14 Syamsuddin Haris, peneliti utama Pusat Penelitian Politik LIPI, dalam Mengelola Potensi Konflik Pilkada, dimuat di surat kabar harian Kompas, Jumat 26 September 2008. 15 Ryas Raasyid dalam Suara Karya ,06 Juli 2005. 16 www.thewahidinstiture.org yang diakses pada 27 September 2009 17 Berita online, Pilkada Langsung Harus Segera Dihentikan., dapat diakses di http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_vie&news_id=14797 yang diakses pada 10 November 2009 politik lokal yang ditandai dengan aksi boikot politik oleh masa akan merajalela dan mencederai proses demokratisasi. Dampak Sosial Budaya: Rekonstruksi Diskursus Sosial Budaya Seringkali, beredar sebuah hipotesa bahwa keragaman suku di Jawa Timur menjadi polemic tersendiri bagi terlaksananya pemilihan kepala daerah langsung guna mewujudkan akselerasi demokratisasi di daerah tersebut. Dalam banyak literatur antropologi Indonesia, masyarakat Jawa Timur dikenal dengan keragaman suku dan kekentalan nuansa etnisitas (ethnicity). Nuansa etnisitas ditandai dengan kedekatan emosional antar kerabat dan rasa eksklusif satu kelompok suku dengan kelompok suku yang lain. Keragaman suku Jawa Timur dibalut dengan kebanggaan atas symbol-simbol kebudayaan yang dieratkan dengan garis keturunan (keturunan ulama atau tidak). Meskipun masyarakat Jawa Timur masuk dalam kategori suku Jawa, tapi ada beberapa pengecualian dan excuses di sini. Misalnya, suku Madura tidak ingin dikatakan sama secara budaya dengan suku Jawa. Orang Jember tentu berbeda secara kultural dengan orang Surabaya. Sehingga, orang Jember tidak ingin disebut sebagai orang Surabaya, demikian pula sebaliknya. Belum lagi dengan orang Madura yang lebih menonjolkan kepemilikan sebagai orang Madura daripada orang Jawa Timur. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan kultural ini keduanya disebut sebagai sebuah kelompok etnik yang berbeda walaupun keduanya sama-sama suku Jawa di Jawa Timur.18 Situasi kemajemukan sosial dan budaya seperti ini sering menyeret Jawa Timur dalam kasus konflik etnik yang dituding sebagai aksi politisasi. Semisal; konflik Banyuwangi karna kasus pocong yang dipelintir sebagai politisasi dari kelompok elit politik tertentu di Jakarta. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur, isu primordialisme sudah menjadi senjata lama bagi para kandidat untuk saling menjatuhkan kompetitor politiknya. Pada saat pelaksanaan Pilkada di Tuban misalnya. Sebelum Pilkada, Tuban dikenal 18 Kusnadi dalam Dinamika Kelompok Etnik, Etnisitas & Pembangunan Daerah (Konflik Sosial dalam Perebutan Sumberdaya), makalah yang dipresentasikan dalam seminar rutin CERIC Universitas Jember, Lemlit UNEJ, Sabtu 02 Juli 2005. Dapat diakses di http://share.ciputra.ac.id/Student/GSB/IAD/Dinamika%20Kelompok%20Etnik,%20Etni...rah%20%28Konf lik%20Sosial%20dalam.pdf yang diakses pada 15 November 2009 sebagai kota yang tenang dan aman dari ancaman konflik etnik. Namun, Sabtu 29 April 2006, kerusuhan melanda Tuban. Sekitar 5000 orang mengamuk dan membakar kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat, pendapa kabupaten, hotel, rumah pribadi, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Meskipun konflik etnik tidak pernah melanda Tuban, namun konflik Pilkada telah mengubah situasi tenang tersebut. Walaupun banyak pihak menyatakan konflik hanya bersifat sementara, tapi konflik pilkada yang terjadi di Tuban tetap telah melukai perjalanan demokratisasi di Indonesia. Jika dilihat dari sisi pembangunan dan transformasi ekonomi, Tuban mengalami percepatan yang cukup pesat. Namun di saat Pilkada Tuban berlangsung, bupati incumbent, Haeny, diduga melakukan banyak kecurangan dan rekayasa sehingga memantik aksi anarkis masa. Isu SARA juga merebak di Tuban, yaitu ‘anti China’ atau orang ‘China tidak boleh jadi bupati’. Isu ini sengaja dihembuskan untuk mencekal salah satu calon wakil bupati yang berasal dari etnis China, Go Tjong Ping. Terlepas dari kondisi sosial ekonomi yang tidak terlalu terbelakang, ternyata masyarakat Tuban masih terlalu mudah disulut api provokasi. Dari fakta kasus Tuban tersebut kita bisa menarik hipotesis sementara bahwa beberapa lapisan masyarakat Jawa Timur memiliki kerentanan yang relative tinggi terhadap potensi konflik Pilkada. sehingga diskursus ini menimbulkan kekhawatiran oleh beberapa pihak jika pasangan kandidat membawa isu primordialisme dalam Pilkada Jawa Timur seperti yang terjadi di Pilkada beberapa Kabupaten di Jawa Timur sebelumnya. Harus diakui bahwa selama masa kampanye pemilihan gubernur Jawa Timur, kelima pasang calon sering membawa isu etnik sebagai bumbu politiknya. Di banyak baliho, pamflet dan atribut kampanye lainnya mengandung kalimat yang mengandung sentiment agama yang cukup kuat. Tentu, ini bisa memancing sensitivitas masyarakat Jawa Timur. Selain itu, sebelum penyelenggaraan pemunguan suara putaran pertama, beberapa pengasuh pondok pesantren di Jember mengakui bahwa masyarakat Jawa Timur masih mengedepankan garis keturunan dan latar belakang agama dibandingkan dengan target pembangunan dan program politik lainnya. Hal ini dimanfaatkan oleh pasangan KarSa yang menjual jargon ‘masyarakat santri’ dalam strategi kampanyenya. Akan tetapi, situasi yang terjadi di Tuban, Banyuwangi, dan Madura serta pernyataan dan anggapan miring tentang pilihan politik masyarakat Jawa Timur tidak semuanya terjadi selama pemilihan gubernur Jawa Timur. Hal ini terlihat dari imunitas politik masyarakat Jawa Timur paska Pilkada putaran pertama, putaran kedua dan penghitungan ulang di tiga kabupaten di Madura. Meskipun banyak pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pilkada Jawa Timur, secara umum dapat dikatakan tidak ada social disorder yang masif. Pengerahan masa oleh tim sukses yang dianggap belum siap kalah tidak mampu memaksa publik melakukan tindakan anarkis. Kondisi ini adalah antithesis dari apa yang pernah diduga sebelumnya. Masyarakat Jawa Timur memang kental dengan nilai agama. Tapi tidak berarti agama selamanya bisa dipelintir oleh kepentingan politik. Beberapa kasus konflik etnis dan konflik Pilkada kabupaten memang pernah menerpa Jawa Timur tetapi tidak untuk pemilihan gubernur. Masyarakat Jawa Timur sekarang cenderung memilih untuk bersikap secara rasional. Bagi mereka, ketampakan figure yang maju dalam Pilkada tidak terlalu besar seperti kedekatan emosional dalam Pilkada kabupaten. Tipekal masyarakat Surabaya yang metropolitan dan cosmopolitan menjadikan masyarakat lebih pragmatis dalam berpolitik. Paska konflik Pilkada Jawa Timur ini, sekarang kita bisa melihat bahwa Jawa Timur berhasil membuktikan bahwa kisruh sengketa pilkada hanya terjadi antara tim sukses saja. Peliknya DPT, KPU yang tidak jelas atau bahkan sikap pragmatis para kiai tidak serta merta menyeret masyarakat Jawa Timur masuk ke dalam ring of fire. Mereka justru bisa diantisipasi lebih cepat dan cenderung kooperatif. Kondisi ini adalah cikal bakal rekonstruksi sosial budaya Jawa Timur. Konflik pilkada tidak selamanya berujung pada konflik yang anarkis. Tapi juga bisa mengerucut pada proses pendewasaan manusia yang sebenarnya. Ini adalah intangible positive impact (dampak positive yang tak terlihat) dari konflik pilkada Jawa Timur. Dampak yang kedua adalah mulai diakuinya keberadaan perempuan dalam dunia perpolitikan oleh masyarakat Jawa Timur. Masyarakat Jawa Timur nota bene nya adalah masyarakat dengan tingkat homegenitas ideologi yang cukup tinggi. Di tengah arus modernisasi yang melanda masyarakat di wilayah periperi di Jawa Timur, masih ada pemikiran konservatif yang mendiskreditkan peran perempuan dalam wilayah kemajemukan sosial. Para ulama tradisionil memandang tabu bila perempuan menjadi pemimpin skala kewilayahan provinsi. Bagi mereka, membiarkan perempuan memimpin sebuah negeri adalah sebuah penghianatan agama. Khafifah Indar Parawansa telah akan menjadi gubernur perempuan pertama di Indonesia jika ia berhasil melaju dan menyingkirkan rival politiknya pada Pilkada Jawa Timur yang lalu. Khafifah merepresentasikan perempuan NU yang cakap dalam berpolitik dan kepemimpinan nasional. Khafifah dinilai oleh banyak pengamat politik lokal sebagai figure calon pemimpin yang mengetahui akar permasalahan di Jawa Timur. Meskipun masifnya usaha beberapa oknum yang meminimalisir pengaruhnya dalam Pilkada, namun masyarakat Jawa Timur dengan kekentalan ketaatan pada pemuka agama telah membukakan hati bagi sosok perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam wilayah sosial dan politik masyarakat Jawa Timur. Hal ini menandakan adanya perubahan paradigmatik masyarakat Jawa Timur dalam memandang dan memposisikan perempuan pada tempat dan dengan kesempatan yang sama dengan kaum adam dalam kontes politik. Konflik Pilkada Jawa Timur telah memaksa tim KaJi untuk berjuang dengan maksimal. Perilaku politik para tim sukses KaJi seolah menguatkan proses pencitraan peran perempuan dalam pelembagaan demokratisasi di Jawa Timur. Meskipun Khafifah awalnya hanya dianggap calon yang underdog, tapi Khafifah justru berhasil melenggang ke putaran kedua pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Dampak Ekonomi Demokrasi itu memang mahal. Barangkali ini adalah kalimat pertama yang seringkali masyarakat lontarkan jika mereka harus berbicara tentang demokrasi. Robert A Dahl mungkin akan membenarkan hal itu karena memang demokrasi menimbulkan efek detrimental yang tidak hanya populis bagi kaum elit. Menurut pandangannya, selain untuk menghindari tirani politik, demokrasi juga dimaksudkan untuk menciptakan tujuang-tujuan yang lain. Di antaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapatnya kesamaan politik, munculnya moral otonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi diri individu, dan adanya kesejahteraan.19 Paling tidak, selama ini 19 Kacung Maridjan dalam Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik, dan Demokrasi Lokal, Jakarta 16 November 2007, hal 13. terdapat pandangan bahwa demokrasi hanya akan berjalan dengan baik di Negara yang telah memiliki tingkat kesejahteraan tinggi. Sejalan dengan teorisasi demokrasi oleh Dahl, pemerintah Indonesia berniat untuk memasifkan arus demokrasi melalui pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah akhirnya menjadi rutinitas pemerintah SBY sejak lima tahun silam. Ditambah dengan pelaksanaan Pilkada, pemekaran memakan biaya pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat tidak minimalis. Pemekaran daerah telah menjebak pemerintah pada pengeluaran yang sangat tinggi. Berdasarkan catatan empiris, anggaran biaya penyelenggaraan satu putaran Pilkada provinsi rata-rata mencapai sekitar Rp 500 miliar. Sementara untuk satu putaran Pilkada kabupaten/kota menghabiskan dana sebesar Rp 25 miliar. Dengan demikian, jumlah kebutuhan anggaran biaya yang harus disediakan pemerintah untuk kepentingan Pilkada adalah sebesar Rp 28 triliun. Bayangkan juga, pemerintah paling tidak harus membiayai terselenggaranya Pilkada di sebanyak 33 provinsi dan 465 kabupaten/kota. 20 Pilkada Jawa Timur dan sengketa politik yang mewarnainya telah memecah rekor nasional sebagai Pilkada termahal. Putaran pertama Pilkada Jawa Timur mampu mencapai biaya sebesar Rp 500 miliar. Disusul dengan putaran kedua yang berhasil menelan APBD sebesar Rp 200 miliar. Dana ini belum termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dan penghitungan ulang di tiga kabupaten di Madura. Total biaya yang hampir mencapai Rp 800 miliar ini tidak disertakan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang memuaskan dengan angka golput hampir mencapai 50%. Kondisi ini tampak berbanding terbalik dengan situasi yang sedang dihadapi oleh korban lumpur lapindo. Ironis memang, biaya ekonomi yang tinggi tidak disertai dengan empati sosial politik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dampak Hukum dan Keamanan 20 Sudaryadi dalam Mengendalikan Pemekaran Wilayah, http://www.isei.or.id/page.php?id=5jan094 yang diakses pada 15 AGustus 2009 dapat dilihat di Secara umum Pilkada Jawa Timur (pemilihan gubernur) tidak berdampak pada terancamnya system keamanan. Tetapi, jika kita melihat pada pelaksanaan Pilkada di 16 kabupaten, maka terdapat konsekuensi kerawanan keamanan yang cukup tinggi. Kerawanan itu berupa keamana yang menjadi lahan bisnis oleh aparat penegak keamanan. Jika kemudian, pilkada tidak dapat dikelola dengan baik maka penyalahgunaan wewenang berupa bisnis keamanan oleh oknum tertentu dalam mengatasi konflik pilkada akan semakin sering terjadi. Jika penyalahgunaan ini terus terjadi maka pihak yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh seorang pengamat politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Haryadi; “Eksploitasi kerawanan Pilkada yang berlebihan bisa melahirkan praktik bisnis keamana. Dan, yang dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah daerah setempat, karena alokasi anggaran untuk keamanan menjadi berlipat ganda”21 Haryadi juga menambahkan, berdasarkan informasi yang dia dapat dari penemuannya diketahui bahwa ada pematokan anggaran biaya yang dilakukan oleh oknum tertentu. Pihak polres tertentu (setingkat kabupaten/kota) mematok biaya sekitar Rp 3 miliar untuk pengamanan pilkada di salahsatu kabupaten di Jawa Timur. Baginya, anggaran biaya ini dianggap terlalu besar dan mengalami eksploitasi besar-besaran. Sementara itu, dampak hukum dari konflik Pilkada Jawa Timur menuntut profesionalitas dan independensi dari para penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan Agung. Dalam kasus pelanggaran Pilkada Jawa Timur telah mengakibatkan mantan pejabat polda Jawa Timur mengundurkan diri karena kecewa dengan proses penyidikan kasus data DPT fiktif. Selain itu, dengan melebarnya penyelesaian kasus sengketa Pilkada Jawa Timur berdampak pada system perundang-udangan yang masih belum akomodatif atas terselenggaranya Pilkada yang lebih professional. Diduga, konflik ini juga dipicu oleh intervensi patronase politik para tim sukses yang sejatinya duduk di lembaga legislative. Kekecewaan tim sukses atau bahkan rekan separtai atas kekalahan kandidat yang diusung oleh partai politiknya menghasilkan lobi politik yang curang dan tidak mewakili semangat demokratis itu sendiri. 21 Pilkada Rawan Timbulkan Bisnis Keamanan, www.suaramerdeka.com/harian/0502/26/nas09.htm yang diakses pada 10 Oktober 2009 Tambahan pula, dengan konflik horizontal Pilkada Jawa Timur, maka ada kecenderungan ketidakpercayaan pada independensi para penegak hukum dalam menindaklanjuti pihak-pihak yang diduga melakukan penyelewengan wewenang. Masih berkaitan dengan DPT, Kafifah menduga ada keterlibatan anggota KPU, Wahyudi Purnomo dan Arif Budiman. Meskipun calon gubernur terpilih telah dilantik, namun kasus pelanggaran hukum tetap harus diusut tuntas jika tidak maka konflik horizontal Pilkada Jawa Timur akan meluas dan melebar hingga paska konflik pilkada. Daftar Pustaka Agustino, Leo, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009 Anam, Chairul, Pilkada Jawa Timur paling kotor: Ada Kecurangan dibiarkan.artikel. Amirudin dan A. Zainal Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalanan Pilkada 2005, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2006 Cahyono, Heru, 2005, Konflik dan Pelanggaran pada Pilkada Langsung 2005: Elite Politik Hendak Kemana, dalam Year Book 2005 Politik BBM, Jakarta, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Chang, William, Dimensi etnis konflik sosial, Kompas 2 Februari 2001 Chester A. Crocker, and Fen Osler Hampson. 1996. Managing global chaos: Sources of and responses to international conflict. Washington, DC: U.S. Institute for Peace Dinamika Konflik dalam Transisi Demokrasi: Informasi Potensi Konflik dan Potensi Integrasi Bangsa (Nation and Character Building), Jakarta, Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Informasi Nasional, 2004 Doug, J. Craig Bond, Jenkins, Charles Taylor, and Kurt Schock. 1997. “Mapping mass political conflict and civil society”. Journal of Conflict Resolution 4:553-79. Faishal, Nur, Berpegang pada pedoman politik NU, artikel tertanggal 2 Juni 2008 Gurr, Ted Robert, and Barbara Harff. 1996. Early warning of communal conflict and genocide. Tokyo: United Nations University Press Gurr, Ted Robert, and Mark Lichbach. 1986. Forecasting internal conflict: A competitive evaluation of empirical theories. Comparative Political Studies -------------, 1998, Early warning of ethnopolitical rebellion: In Preventive measures, Lanham, MD: Rowman & Littlefield -------------, 1998, Minorities at risk. Washington, DC: U.S. Institute for Peace Harris,Peter, dan Reilly, Ben, (ed.), 2000, Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, Jakarta, International IDEA. James A. Thurber, Campaigns and Elections American Style. NY Westview Press; 2nd edition, 2004. J. Craig Jenkins, 2001, “Conflict-Carrying Capacity, Political Crisis, and Reconstruction: A Framework for the Early Warning of Political System Vulnerability, Journal of Conflict Resolution Vol. 45 No. 1 John Davis, and Ted Robert Gurr. 1998. Preventive measures: Building risk assessment and crisis early warning systems. Lanham, MD: Rowman & Littlefield. Karim Elha H, Sofwan, Muhammadiyah dalam Pilkada, Artikel. Koran Tempo, 21 Oktober 2008. Kompas, Polda Jatim antisipasi kecurangan, KPU jangan sampai diintervensi. 16 November 2008 Mau, Yoyarib, Kisruh DPT Pilkada Jatim. www. kannutuan.com Malik, Ichsan, Manual Pelatihan Pembangunan Perdamaian dan Pencegahan Konflik, Jakarta, SERAP, 2006 Maliki, Zainuddin, 2006, Peta dan Ancaman Konflik di Jawa Timur, ...Makalah disampaikan dalam Diskusi ...Pengelolaan dan Antisipasi Ancaman Konflik di Jawa Timur, yang diselenggarakan Dewan Pakar Propinsi Jawa Timur, tanggal 14 Juni 2006 di Balitbang Propinsi Jawa Timur. Majalah Matan: Pilkada Jawa Timur, edisi 11 Mei 2008. Marijan, Kacung, Pilkada langsung: resiko politik, beaya ekonomi, akuntabilitas politik dan demokrtasi lokal. Artikel disampaikan dalam "in house disscusion" komunikasi partai politik yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk demokrasi ( KID ) 17 November 2007. Maya, Ridha, Orientasi politik warga Muhammadiyah ( Studi deskriptif tentang orientasi politik warga Muhammadiyah Surabaya menjelang Pilgub Jatim 2008, Universitas Airlangga, Skripsi tidak diterbitkan Muchith Muzadi, Abdul, Mengenal Nahdlatul Ulama, Khalista Surabaya 2006 Mujiran, Paulus, 2006, Konflik Pilkada Ujian Demokrasi Lokal, http://www..suarakaryaonline.com Najib, Mohammad, 2005, Agama dan Resolusi Konflik dalam Pilkada, dalam Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Unisia No. 58/XXVIII/IV/2005, Yogyakarta, UII.