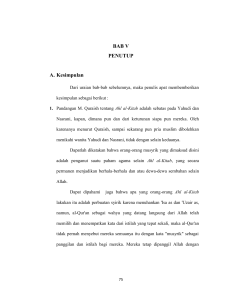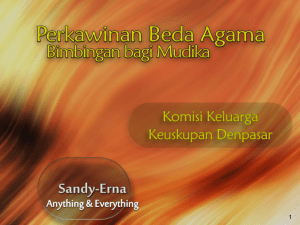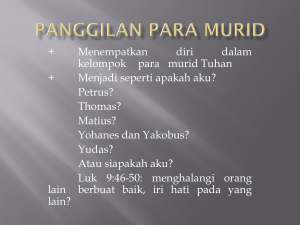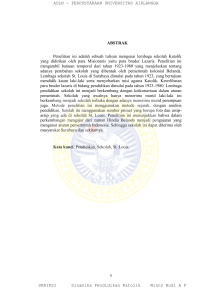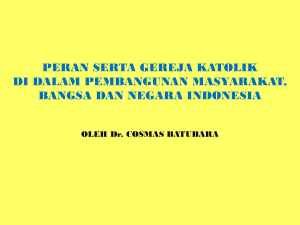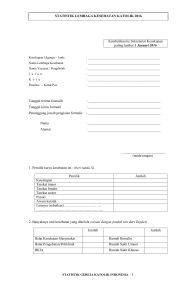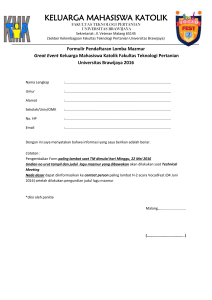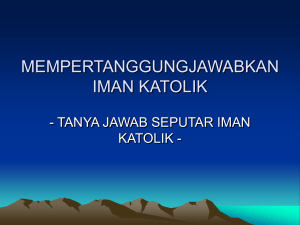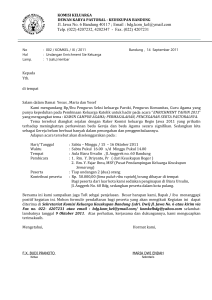pernikahan beda agama menurut islam dan katolik
advertisement
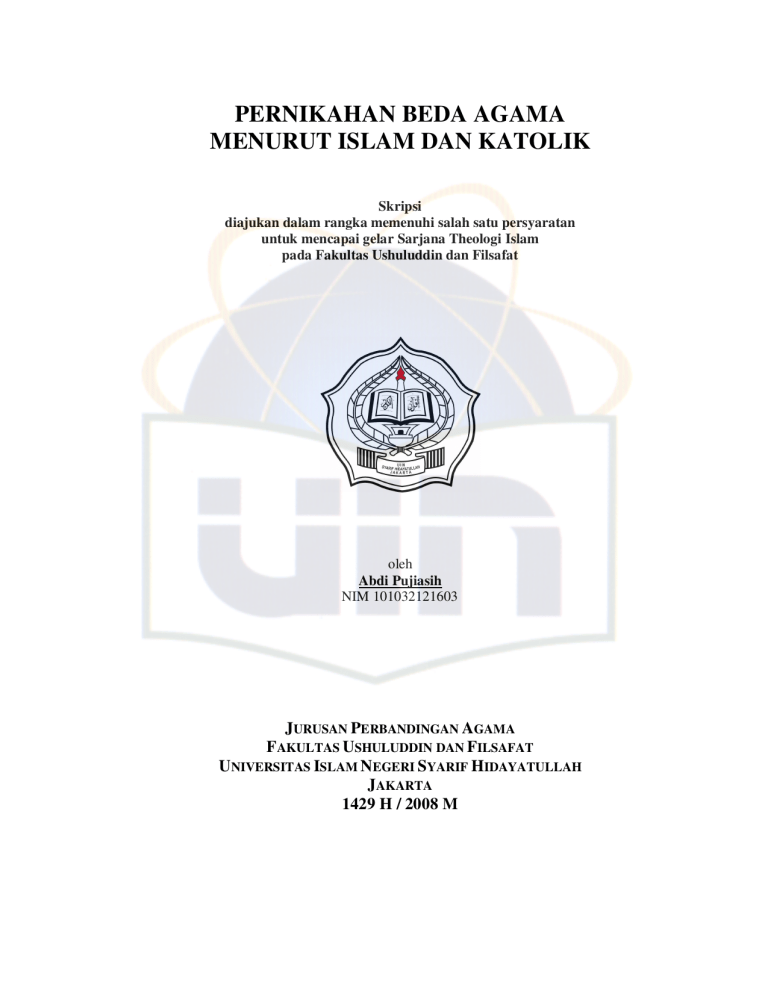
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
MENURUT ISLAM DAN KATOLIK
Skripsi
diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk mencapai gelar Sarjana Theologi Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
oleh
Abdi Pujiasih
NIM 101032121603
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
F AKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
U NIVERSITAS ISLAM N EGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H / 2008 M
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
MENURUT ISLAM DAN KATOLIK
Skripsi
diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
untuk mencapai gelar Sarjana Theologi Islam
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
oleh
Abdi Pujiasih
NIM 101032121603
Di bawah bimbingan
Prof. Dr. Zainun Kamal MA
NIP 150228520
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
F AKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
U NIVERSITAS ISLAM N EGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429 H / 2009 M
Pengesahan Panitia Ujian
Skripsi yang berjudul Pernikahan Beda Agama Menurut Islam dan Katolik telah
diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 21 Februari 2008. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Program
Srata 1 (S1) pada Jurusan Perbandingan Agama.
Jakarta, 18 Maret 2008
Sidang Munaqasyah
Ketua merangkap Anggota
Sekretaris merangkap Anggota
Drs. Agus Darmaji. M.Fils
NIP: 150262447
Maulana. M.A.
NIP: 150293221
Anggota,
Dra. Ida Rosyidah. M.A,
NIP: 150242267
Dr. Hamid Nasuhi. M.A.
NIP: 150241817
Dr. Zainun Kamal. M.A.
NIP: 150228520
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, berkat petunjuk-Nya penulis
dapat menyelesaikan karya ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam selalu
tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan semua manusia
di dunia. Selanjutnya, adalah suatu keharusan bagi setiap mahasiswa yang ingin
menyelesaikan perkuliahan dan mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk menyusun
sebuah skripsi. Terkait hal tersebut, penulis telah menyelesaikan penulisan sebuah
skripsi dengan judul: ”PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT ISLAM
DAN KATOLIK.”
Dalam hemat penulis, tema pernikahan beda agama ini perlu diangkat
mengingat ia telah menjadi permasalahan yang menghinggapi hampir seluruh
agama dan keyakinan yang ada dan berkembang di dunia. Persoalan ini tak jarang
menimbulkan konflik antara pemeluk agama bahkan meluas menjadi persoalan
antar-agama, meski tak jarang, dari sini, kemudian lahir sebuah hubungan yang
toleran, saling menghormati, dan harmonis antar-agama. Karena fakta yang terjadi
kini tidak lagi memungkinkan seseorang atau institusi, termasuk juga agama,
untuk abai terhadap kehadiran dan karenanya berinteraksi dengan yang lain, maka
pernikahan beda agama pun sudah selayaknya menjadi persoalan yang harus
secara bijak ditanggapi. Eksklusif dengan keberadaan agama dan umat lain dan
ahistoris terhadap perkembangan sejarah manusia dan hubungan yang harus
dibangun di antara sesamanya, adalah sebentuk kekerdilan sikap dan kepicikan
dalam menjalani hidup, tidak hanya dalam beragama.
Dari pemikiran dasar itulah, skripsi ini dihadirkan dan memperoleh
momentumnya. Namun, penyelesaian skripsi hingga sampai pada bentuknya yang
sekarang sungguh bukan sesuatu yang mudah, melainkan banyak menemui
kesulitan dan hambatan yang kadang tidak begitu saja mudah diselesaikan.
Kendati demikian, berkat segenap dukungan dan motivasi dari berbagai pihak
skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tulus penulis
ucapkan kepada: Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Dr. M. Amin
Nurdin, MA, Dra. Hj. Ida Rosyidah, MA dan Bapak Maulana, M.A, sebagai ketua
dan sekretaris Jurusan Perbandingan Agama yang begitu tulus dan ikhlas untuk
selalu membantu penulis dalam berbagai hal.
Terimakasih pula untuk Bapak Prof. Zainun Kamal, M.A selaku
pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan tidak
hanya dalam aspek substansi keilmuan, melainkan juga memfasilitasi waktu
dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga ditujukan
kepada seluruh dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, khususnya dosen
Jurusan Perbandingan Agama yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama
menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kepada yang terkasih dan tersayang suamiku Muhamad Arif Hadiwinata
yang selalu memberi sentuhan kasih sayang dalam perjalanan hidup dan semangat
yang membara dalam menyelesaikan tugas ini. Kepada Alvan Razky Hadiwinata,
the little container driver, aku persembahkan segenap cinta dan kasih sayang yang
tulus sebagai kesediaanmu mewarnai hidupku dengan penuh canda tawa.
Juga yang saya cintai kedua orang tua, H. Kasdullah dan Hj. Sukarsih, dan
kedua mertua, H. Hadiat Subawinata dan Hj. Dwi Sulasmimbar, karena kesabaran,
doa, kasih sayang dan motivasi yang begitu besar membuat saya mampu
menuntaskan tugas ini. Tak lupa anggota keluarga yang lain, Mami dan Hani,
adik-adikku, ka Abas, mbak Ratna, abang Maulvi dan Chika terima kasih atas
pinjaman rumah dan tamannya. Ka Syidqi dan mbak Lina terima kasih atas
pinjaman buku-bukunya. Terima kasih kepada Ayesha, Nayla, Azril dan Tante
Wini yang selalu setia menjadi teman anak kami. Secara khusus, penulis
menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar pa’de Legimin di
Legoso, Ciputat. Tanpa bantuan mereka, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan
skripsi ini dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
Teruntuk teman-teman di pondok mawar, khususnya Indri, terimakasih
atas kosannya. Didi yang selalu siap sedia untuk bantuan skripsinya, dan untuk
teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Agama angkatan 2001,
khususnya Olies dan Awad yang masih setia menemani penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
Penulis mengakhiri dengan mengutip karya seorang novelis terkenal Paulo
Coelho, ”jika engkau ingin mewujudkan legenda pribadimu, niscaya segenap
alam semesta akan membantumu” . Dalam hal ini penulis percaya bahwa karya
penulis yang ada saat ini merupakan satu lompatan besar dalam rangka
mewujudkan legenda pribadi penulis.
Jakarta, Januari 2008
ABDI PUJIASIH
DAFTAR IS I
LEMBAR PENGESAHAN
i
KATA PENGANTAR
iii
DAFTAR IS I
vi
BAB I. PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang Masalah
1
B. Batasan dan Rumusan Masalah
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
7
D. Metodologi Penelitian
8
E. Sistematika Penulisan
8
BAB II. PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM ISTILAH
10
A. Pengertian Pernikahan Beda Agama
10
B. Kebijakan Negara tentang Pernikahan Beda Agama
15
BAB III. PERNIKAHAN BEDA AGAMA
MENURUT PANDANGAN ISLAM DAN KATOLIK
24
A. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Islam
24
1. Pernikahan Beda Agama Menurut al Quran
24
2. Pernikahan Beda Agama dan Perdebatan
tentang Ahl al-Kitab
B. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Katolik
29
39
1. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Lama
40
2. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Baru
41
3. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik
43
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP
FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA
A. Fakta Pluralitas di Indonesia
B. Perdebatan Kontemporer Pernikahan Beda Agama
47
47
di Indonesia
54
C. Analisis Komparatif terhadap Fenomena Pernikahan
Beda Agama di Indonesia
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Landasan Pernikahan Beda Agama dalam Islam dan Katolik
65
73
73
73
2. Keterkaitan Pemahaman Keagamaan terhadap Fenomena
Pernikahan Beda Agama dan Hubungan Antaragama
di Indonesia
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
75
77
78
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang identitas penduduknya terdiri beragam
agama, etnis, dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara
yang dikenal dengan kekayaan budayanya di antara negara lain di dunia ini.
Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan negara yang berpenduduk
Muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Muslim ini kemudian menjadikan
Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dikaji. Sejumlah penelitian
menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam,
Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup merepresentasikan
nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari.
Asumsi tersebut memang sah, namun justru terbantahkan dengan realitas
sosial yang menunjukkan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan dari multi
kebudayaan.1 Dengan kata lain, identitas masyarakat indonesia tidak hanya
bersandar kepada homogenitas agama Islam melainkan juga mengacu kepada
heterogenitas budaya yang melingkupinya. Implikasi luas dari heterogenitas
kebudayaan adalah timbulnya beragam perbedaan dalam realitas sosial. Sebagai
contoh seringkali ditemukan perbedaan baik di tingkat sikap, persepsi, bahkan
tindakan (yang sangat mungkin berujung konflik) di antara sesama Muslim
1
Dalam prakata buku Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama, Perspektif Perempuan dan
Pluralisme, (Jakarta, Kapal Perempuan, 2004) hlm ii. Yanti Muchtar mengatakan bahwa
masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural; dilihat dari sisi agama, suku, ras, dan
kelas, dan lain-lain. Ruang interaksi lintas golongan sangat terbuka lebar.
Indonesia tentang sebuah fenomena sosial keagamaan. Untuk mencontohkan
betapa perbedaan seperti itu kerap terjadi di Indonesia ambil contoh peristiwa
pengusiran jamaah Ahmadiyah, jamaah Salamullah pimpinan Lia Eden, hingga
peristiwa pernikahan beda agama di kalangan umat Muslim.
Isu pernikahan beda agama juga merupakan isu yang sensitif jika kita
tempatkan kepada pemeluk agama selain Islam di Indonesia. Dalam konteks
agama Katolik di Indoenesia, pernikahan beda agama merupakan sebuah hal yang
sama sensitifnya dengan agama Islam. Setidaknya dua agama besar ini melihat
bahwa pernikahan beda agama justru merupakan hal yang tidak mungkin
dilakukan jika pasangan yang melakukan pernikahan tetap berpegang kepada
prinsip agamanya masing-masing dalam melangsungkan pernikahan. Namun
demikian, dalam agama Katolik pernikahan yang dilakukan tetaplah sah jika
pasangan yang berbeda agama tersebut menerima prinsip-prinsip, sifat dan tujuan
pernikahan menurut agama Katolik.
Peristiwa pernikahan beda agama menjadi salah satu masalah perbedaan
yang cukup kompleks dalam isu pernikahan. Dalam sejarah pernikahan beda
agama, pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tunduk pada hukum yang
berbeda berdasarkan hukum agama, adat, maupun kewarganegaraan telah diatur
secara khusus sejak zaman kolonial, hingga pasca kemerdekaan.2 Namun sejak
diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974, definisi pernikahan beda agama mengarah
kepada orang yang menikah dengan perbedaan kewarganegaraan.
Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 tentang pernikahan
memuat asas penting bahwa, “pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan
2
Maria Ulfa dan Martin Lukito Sinaga (ed.), Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama,
Perspektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 92
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Asas ini
berlaku untuk semua pernikahan yang dilaksanakan di Indonesia termasuk
pernikahan antar agama.3
Di sini jelas bahwa pernikahan yang dilaksanakan di luar hukum agama
maka akan dianggap oleh negara sebagai pernikahan yang tidak sah. Selama ini
pernikahan beda agama sudah banyak terjadi di Indonesia, tetapi dalam hal ini
pemerintah kurang tegas dalam menanggapi pernikahan beda agama karena
sampai detik ini pernikahan beda agama masih terus berlangsung. Dan dari sekian
banyak pelaku pernikahan beda agama pun masih belum jelas tercatat dalam arsip
pemerintah.
Sedangkan permasalahan pernikahan beda agama dalam hukum agama
Islam, senantiasa dimaknai dan dipahami secara berbeda oleh para penganutnya.
Hal itu merupakan konsekuensi logis dari kandungan kitab suci Al-Quran yang
lebih banyak memuat gambaran umum dari satu persoalan, dan oleh karenanya
selalu ada peluang untuk ditafsirkan, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kondisi
dan situasi saat ini yang jelas berbeda dengan kondisi masa lalu. Beragam
penafsiran disamping mencerminkan bahwa ada pluralitas dalam agama itu
sendiri, juga mencerminkan kekayaan khasanah al-Quran yang senantiasa bisa
digali untuk kemudian mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ditemukan
oleh generasi sebelumnya.
Oleh karena itu, pernikahan beda agama dalam Islam menjadi sesuatu
yang tak pernah selesai diperdebatkan. Sebagian sumber (nash al-Qur’an)
dimaknai sebagai bentuk pelarangan terhadap pernikahan beda agama, sementara
3
H. Ichtiyanto, SA, SH, APU, Pernikahan Campuran dalam Negara Republk Indonesia,
(Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,2003), h.81
sebagian lagi ditafsirkan oleh banyak kalangan sebagai ayat yang membolehkan
pernikahan beda agama. Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam upaya
memahami teks al-Qur’an sebagai sumber hokum, termasuk untuk pernikahan
beda agama, adalah konteks pada saat ayat itu diturunkan. Dengan melihat
konteks tersebut, penafsiran ayat yang membicarakan tentang pernikahan beda
agama akan lebih jelas dipahami.
Maka, dalam hemat penulis, ayat yang melarang pernikahan beda agama
merupakan bentuk larangan untuk umat pada saat itu. Terbukti ketika konteksnya
berubah, nada ayat al-Qur’an juga mengalami perubahan. Al-Qur’an kemudian
secara tegas memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama meski, pada saat
itu, terbatas hanya pernikahan antara kaum Muslim dengan Ahl al-Kitab.
Konteks yang terjadi dan dapat dilihat pada masa kini, berbeda hampir 180
derajat dengan konteks baik ketika al-Qur’an melarang pernikahan beda agama
maupun ketika memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Konteks kini,
manusia begitu plural, tidak mungkin hidup menyendiri tanpa bergaul dan
berinteraksi dengan yang lain. Hubungan dan, bahkan, pernikahan dengan umat
dari agama lain pun, kini, tak terelakkan lagi. Pendapat seperti ini sudah
diutarakan oleh banyak ulama dan pemikir Islam kontemporer sebagaimana akan
dijelaskan pada bab III.
Sedangkan bagi umat Katolik sendiri pernikahan beda agama adalah salah
satu halangan yang membuat tujuan pernikahan tidak dapat diwujudkan. Apabila
pernikahan beda agama ini masih tetap dilaksanakan harus terlebih dahulu
meminta izin atau dispensasi kepada uskup setempat.4 Walaupun di dalam
4
Lihat Kanon 1086 pasal 2
pernikahan ini tidak ada keharusan bagi pihak yang bukan Katolik untuk ikut
menjadi Katolik, tetapi ia harus menerima prinsip-prinsip, sifat dan tujuan
pernikahan menurut agama Katolik.
Di dalam agama Katolik terdapat ayat-ayat yang dipakai sebagai acuan
pernikahan beda agama. Sebagian besar kitab Katolik melarang terjadinya
pernikahan beda agama. Hal itu sebagaimana terlihat pada beberapa ayat di dalam
kitab Perjanjian Lama seperti Kejadian 6:5-6 dan Ulangan 7:3-4. Pelarangan
pernikahan beda agama juga terrekam dalam kitab Perjanjian Baru seperti pada
Korintus 6:14 Korintus 7:1 dan 7: 12-16.5 Sementara tanda-tanda pembolehan
pernikahan beda agama baru muncul pada Hukum Kanonik, hukum turunan dari
Kitab Suci yang berbasis pada realitas. Meski pasangan yang akan menikah beda
agama terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan tertentu, dua ayat dalam
Hukum Kanonik patut disebut sebagai ayat-ayat yang memungkinkan terjadinya
pernikahan beda agama dalam Katolik. Dua ayat tersebut adalah Hukum Kanon
1125 dan 1126.
Perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan, dan itu tidak akan menjadi
suatu masalah selama kita bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana, salah
satunya
yaitu senantiasa menumbuhkan sikap saling menghormati dan
menghargai kepada sesama pemeluk agama. Dan kita tidak sepatutnya untuk
memaksakan suatu agama kepada orang lain karena pada dasarnya semua agama
itu mengajarkan tentang kebaikan.
Demi kepentingan kajian ini, penulis akan membahas lebih jauh mengenai
pernikahan beda agama dari perspektif agama Islam dan dari agama Kristen
5
Yonathan A. Trisna, Berpacaran dan Memilih Teman Hidup, (Bandung:Penerbit Kalam
Hidup Pusat, 1987), h.53
Katolik. Kedua agama ini merupakan agama yang cukup menarik karena kedua
agama ini cukup banyak membahas tentang pernikahan beda agama, baik itu dari
perspektif yang melarang pernikahan beda agama sampai dengan perspektif yang
membolehkan bersyarat dengan alasan kemajemukan agama merupakan suatu
yang tak terbantahkan, sehingga pernikahan seperti ini merupakan hal yang wajar
terjadi di Negara Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku
dan agama .
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis kemudian merasa perlu untuk
melakukan studi secara mendalam mengenai pernikahan beda agama. Tentunya
studi mendalam terhadap pandangan agama Islam dan Kristen Katolik dalam
melihat pernikahan beda agama. Studi ini akan ditulis dengan judul:
“PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT ISLAM DAN KATOLIK”.
Diharapkan dengan adanya studi mengenai pernikahan beda agama ini penulis
bisa memberikan kontribusi penting baik bagi studi agama yang telah dilakukan
maupun yang akan dilakukan.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Pernikahan beda agama adalah peristiwa sosial. Ia sangat mungkin terjadi
dan dialami oleh setiap umat dari semua agama dalam konteks kehidupan kini
yang plural, multietnis, multi bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Maka,
pernikahan beda agama merupakan sebuah tema yang sungguh memiliki cakupan
sangat luas. Karena keluasan wilayah itu, tanpa ada kepentingan lain, kecuali
kebutuhan pemokusan masalah, penulis akan membatasi persoalan yang akan
diangkat dalam tulisan ini pada pernikahan beda agama dalam pandangan Islam
dan Katolik.
Dalam rangka memperoleh dan coba masuk pada pembahasan yang lebih
sistematis dan logis, penulis perlu membuat beberapa rumusan masalah sebagai
patokan dan focus bahasan pada bab-bab dan paparan-paparan selanjutnya. Untuk
itu, rumusan masalah pada tulisan ini adalah:
1. Apa sesungguhnya yang menjadi landasan utama dalam agama Islam dan
Katolik dalam memandang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana pula penafsiran teks-teks keagamaan berimplikasi bagi para
pelaku pernikahan beda agama dan kehidupan atau hubungan antar-umat
beragama di Indonesia secara lebih luas?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah dalam rangka pemenuhan syaratsyarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1). Adapun
yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan analisis
tentang bagaimana sesungguhnya pernikahan beda agama yang terjadi di dalam
agama Islam dan Kristen Katolik. Adapun manfaat penelitian ini adalah
diharapkan dapat memberikan pengayaan terhadap literatur penelitian di
Indonesia khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
D. Metodologi Penelitian
Sebagai sebuah karya ilmiah, ulasan dan isi karya ini merujuk pada dan
menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penulis berusaha
mensistematisasi berbagai penemuan dari bermacam literatur menjadi sebuah
kumpulan kalimat atau paparan yang bermakna. Karena akan menganalisis
kumpulan temuan literatur, maka data yang akan digunakan sekaligus penelitian
ini juga bisa disebut dengan penelitian pustaka. Secara lebih tegas, penelitian
pustaka dilakukan dengan membaca dan menginterpretasikan buku-buku dan
dokumen yang memiliki kaitan erat, baik secara substansial maupun sekadar
pelengkap data, dengan pembahasan yang tentunya disesuaikan berdasarkan
pilihan tema yang menjadi konsentrasi perbabnya.
Informasi yang didapatkan dari penelitian pustaka tersebut akan dianalisis
dengan pendekatan komparatif antara satu informasi dengan informasi lainnya dan
diskematisasikan melalui perangkat tabel. Dengan model analisis demikian
diharapkan dapat tercipta proposisi kalimat yang kuat dan bertanggung jawab
tidak hanya secara teks, tetapi juga konteks. Sehingga penarikan kesimpulan dan
tesis yang dibuat oleh penulis memiliki kesesuaian dan ketepatan yang memadai.
E. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini sendiri akan terbagi ke dalam lima bab. Secara
sistematis, kelimanya akan tersusun dan secara deskriptif menjelaskan:
Bab I mencakup Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan
dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II mencakup pengertian dari pernikahan beda agama. Bagaimana
masing-masing (Islam dan Katolik) mendefinisikan pernikahan beda agama
adalah uraian pada sub bab pertama. Selanjutnya bab ini juga akan membahas
undang-undang dan kebijakan pemerintah yang telah ada dalam memandang
pernikahan beda agama.
Bab III membahas pernikahan beda agama dalam pandangan agama Islam
dan Katolik berdasarkan sumber hukum yang ada pada masing-masing agama.
Apa saja yang menjadi hambatan dan memungkinkan terjadinya atau bahkan
sahnya pernikahan beda agama adalah poin penting yang juga dibahas pada bab
ini.
Bab IV berisi tentang analisis komparatif penulis setelah melihat dan
mendeskripsikan pandangan kedua agama tersebut pada bab sebelumnya.
Perdebatan kontemporer
para tokoh agama dan celah hukum, argumentasi
pelarangan dan persetujuan akan pernikahan beda agama menjadi suguhan
utamanya.
Adapun Bab V merupakan kesimpulan dan sikap subyektif penulis setelah
melihat pandangan kedua agama (Islam dan Katolik) tentang pernikahan beda
agama. Tak lupa penulis juga mengajukan saran yang secara khusus berkaitan
dengan fenomena dan penafsiran teks keagamaan tentang pernikahan beda agama.
BAB II
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM ISTILAH
A. Pengertian Pernikahan Beda Agama
Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian pernikahan beda
agama, ada baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari pernikahan itu
sendiri. Undang-Undang (UU) perkawinan pasal 1 menyebutkan secara jelas apa
yang dimaksud dengan pernikahan. Penulis menjadikan definisi itu juga untuk
memaksudkan kata perkawinan atau pernikahan pada pembahasan selanjutnya. Di
Undang-undang itu pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang
maha Esa.6
Tampak bahwa UU di atas menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang
mulia. Dari situ, idealitas kehidupan sepasang laki-laki dan perempuan guna
memperoleh kesejahteraan dan keutuhan hidup berada pada tempat yang utama.
Undang-Undang tersebut tidak hanya melihat pernikahan dari sisi lahir, tetapi
sekaligus ikatan kebatinan antara suami istri dalam membina keluarga yang
bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan yang maha Esa.
Dalam Islam, salah satu tanda dari kekuasaan Allah adalah penyatuan
sepasang laki-laki dan perempuan. Penyatuan tersebut didasari oleh rasa kasih
sayang (mawaddah wa rahmah) yang terjalin di antara mereka. Artinya, dalam
6
Muhammad Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang
No. I Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (Medan: CV. Zahir Trading Co
Medan, ), h. 237
Islam, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sosial yang murni manusiawi,
melainkan masih menyimpan unsur-unsur ketuhanan. Pernikahan bahkan
dianggap sebagai manifestasi dari tanda kebesaran Tuhan.
Lebih dari itu, pernikahan adalah sebuah perbuatan yang diperintahkan
oleh Allah. Allah menganjurkan seorang laki-laki dan perempuan yang telah
dewasa dan mapan serta siap menjalin hubungan dengan manusia yang nota bene
lain, baik dari jenis kelamin maupun keturunan darah, untuk melakukan
pernikahan. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan Malik bin Anas
menyatakan bahwa untuk pribadi-pribadi tertentu, yang telah memenuhi
kualivikasi sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya, menikah menjadi
suatu perbuatan dan pengambilan sikap yang dihukumi wajib.
Kewajiban, atau lebih tepatnya perintah, kemudian bahkan tidak hanya
dikenakan pada perbuatan menikah dalam skala besar, tetapi juga pada praktek
yang lebih spesifik di dalamnya, yakni dalam rangka menambah dan melanjutkan
keturunan. Pada kasus ini Islam memerintahkan untuk senantiasa mengingat dan
bertaqwa kepada-Nya. Karena itulah, pernikahan memiliki filosofi yang sangat
mendalam. Dalam Islam, menikah kemudian bukan hanya dianggap sebagai
sebuah perbuatan yang bermaksud untuk sekedar bersenang-senang dan
melampiaskan nafsu (rekreasi) tetapi juga mengemban tugas mulia untuk
melangsungkan keberlangsungan spesies manusia di muka bumi ini (prokreasi).
Tugas suci tersebut hanya bisa diemban jika manusia memiliki cinta kasih
(mawaddah wa rahmah) dalam melaksanakan pernikahan. Tanpa itu, cita-cita
mulia yang sebenarnya hendak dicapai akan sulit untuk diwujudkan.
Karena pernikahan adalah institusi yang dianggap sakral, maka pernikahan
biasanya diatur oleh aturan-aturan agama. Mulai dari persyaratan, tata cara, dan
segala tetek bengek-nya. Karena itulah, pada lazimnya, pernikahan dilakukan oleh
pasangan yang memeluk agama yang sama.
Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pasangan yang menikah berasal
dari agama yang berbeda. Pernikahan seperti inilah yang disebut dengan
pernikahan beda agama. Bisa jadi, orang Islam, baik pria maupun wanita, akan
menikah dengan orang yang non-Islam seperti Katolik, Protestan, Budha, Hindu,
Khonghucu, dan lain-lain.
Pernikahan beda agama ini mengundang titik perdebatan yang panjang.
Karena, semua agama tampak ingin melindungi para penganutnya dari pengaruh
yang ditebarkan oleh agama lain. Di samping itu, pernikahan beda agama
seringkali “dicurigai” sebagai upaya-upaya yang tersistematisir untuk membawa
pemeluk salah satu agama menjadi pemeluk agama lain.
Titik perdebatan tersebut juga merambah hingga hal yang paling mendasar
yaitu persoalan penafsiran terhadap teks-teks suci, baik al-Quran dari pihak Islam
maupun Injil dari pihak Katolik.
Ada banyak pro dan kontra mengenai persoalan penafsiran teks suci ini.
Pihak yang tidak menyetujui pernikahan beda agama biasanya menggunakan pola
penafsiran tekstual dalam memahami ayat-ayat suci. Mereka menganggap bahwa
teks suci diturunkan tanpa memandang realitas sosial yang terjadi di masa itu.
Bagi kalangan penafsir tekstualis, kitab suci diangap sebagaimana layaknya
Tuhan itu sendiri, yang berkuasa mengatur segala persoalan kehidupan.
Sebaliknya, kalangan yang menerima keberadaan pernikahan beda agama
cenderung menafsirkan teks suci atau teks keagamaan dengan pendekatan yang
lebih bersifat kontekstual. Mereka memandang bahwa teks adalah produk budaya,
yang tak lepas dari interaksi dengan kondisi sosial pada masa ayat tersebut
diturunkan. Artinya, teks suci selalu berdialektika dengan kondisi sosial pada saat
teks tersebut diturunkan, tak pernah tercabut dari kontekstualitas.
Oleh karena itu, dalam menyarikan maksud dari teks suci, para penafsir
haruslah mempertimbangkan konteks “ruang” dan “waktu” ketika ayat tersebut
diturunkan. Artinya, harus ditelaah pula kondisi sosial budaya yang berlangsung
pada saat ayat tersebut diturunkan, untuk diterjemahkan dalam konteks kekinian.
Perlu juga untuk menerjemahkan konteks tersebut dalam bingkai “ruang”, artinya
bahwa teks tersebut diturunkan di suatu tempat tertentu yang notabene memiliki
kultur budaya berbeda dengan kultur budaya Indonesia.
Pembahasan lain yang berkenaan dengan penikahan beda agama adalah
yang berkait dengan statusnya dalam wilayah hukum Indonesia. Hingga saat ini,
belum ada hukum yang mengatur mengenai pernikahan beda agama. Dalam UU
Nomor 1 tahun 1974 pasal 57 memang disebutkan istilah perkawinan campur.
Akan tetapi, yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam undang-undang ini
adalah perkawinan (pernikahan) antara dua orang yang tinggal di Indonesia dan
tetap tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan,
salah
satu
pihak
berkewarganegaraan
asing
dan
pihak
lainnya
berkewarganegaraan Indonesia.7 Jadi, pernikahan yang dimaksud bukan
7
Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di
Indonesia, ( Serang: Percetakan Saudara, 1995), h. 35
merupakan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama, melainkan
pernikahan antara dua orang yang berbeda status kewarganegaraan.
Undang-undang perkawinan pada dasarnya telah menjelaskan pernikahan
yang secara substansial dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang memiliki
perbedaan spesifik seperti kewarganegaraan. Kendati perbedaan agama tidak
disebutkan secara spesifik dalam undang-undang perkawinan, namun para pakar
hukum perkawinan di Indonesia telah mendefinisikan pernikahan beda agama
sebagai “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing
berbeda agamanya dan mempertahankan agamanya itu sebagai suami istri
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.8 Pengertian pernikahan antar agama
yang lebih ringkas dapat ditemukan dalam pedoman pegawai pencatat nikah.
Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa pernikahan antar agama adalah
pernikahan yang terjadi di Indonesia antara dua orang yang menganut agama yang
berbeda.9
Sedangkan pernikahan beda agama menurut Romo Antunius Dwi Joko, Pr
yaitu pernikahan antara seorang baptis Katolik dengan pasangan yang bukan
Katolik (bisa dibaptis oleh gereja lain, atau sama sekali tidak dibaptis). Dan,
menurutnya, gereja memberi kemungkinan untuk pernikahan beda agama tersebut
8
Eoh O.S., Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996) cet 1, h 35
9
A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk),
(Bandung: Al-Bayan, 1994) cet 1, h
karena membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih
pegangan hidup (agama) sesuai dengan hati nuraninya.10
Dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama yaitu suatu pernikahan
yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda keyakinan atau agama, mereka
bertekad untuk membangun keluarga bahagia tanpa harus meninggalkan
keyakinan mereka masing-masing dan mereka tetap taat kepada agama yang
mereka anut.
B. Kebijakan Negara tentang Pernikahan Beda Agama
Sebelum berlakunya UU tahun 1974, di Indonesia kita jumpai peraturan
perkawinan campuran (Regeling of De Gemende Huwelykue; Staatsblad 1898 No.
158). Akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 66 UU, peraturan Staatsblad
1898 No. 158 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Di luar fakta sejarah di atas, UU Staatsblad 1898 No. 158 sendiri
menyatakan bahwa pernikahan campuran adalah pernikahan antara orang-orang
yang tinggal di Indonesia namun tunduk pada hukum yang berlainan.11 Menurut
UU di atas setiap pernikahan di antara orang-orang yang berada dan tunduk pada
hukum yang berlainan disebut pernikahan campuran, baik disebabkan perbedaan
golongan penduduk, perbedaan hukum adat, maupun perbedaan agama. Artinya,
UU Staatsblad tahun 1898 No. 158 ingin mengatakan bahwa perbedaan golongan
penduduk baik warga asing atau bukan warga asing, perbedaan hukum adat dan
perbedaan agama bukanlah suatu penghalang bagi pasangan yang ingin
10
Romo Antunius Dwi Joko, “Kawin Campur,” artikel diakses pada 10 september 2007 dari
WWW.Yesaya. Indocell. Net.
11
M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan nasional, h. 238
melangsungkan pernikahan campuran. Ini jelas sangat bertolak belakang dengan
UU tahun 1974 yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini.
UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 disusun berdasarkan Pancasila yang
berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam UU ini tidak dibahas secara
eksplisit mengenai pernikahan beda agama. Walaupun secara implisit dapat
ditemukan landasannya pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan
adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”. Pasal inilah yang selalu menjadi rujukan soal pernikahan
beda agama di Indonesia. Pasal 2 ayat 1 menyerahkan sepenuhnya soal pernikahan
beda agama kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan
mengenai diperbolehkan atau dilarangnya pernikahan tersebut.12
Sedikit ke belakang, menengok proses sejarah yang sebelumnya terjadi,
pemberlakuan pasal itu sendiri sebelumnya melalui pro-kontra yang tidak pendek.
Pengesahan UU perkawinan ini sendiri sempat mengalami penolakan baik dari
internal DPR, sebagai pemutus UU, maupun dari masyarakat. Sebagai bentuk
kompromi, akhirnya UU perkawinan tidak membahas secara eksplisit tentang
pernikahan beda agama. Pernikahan yang diatur di dalam UU perkawinan sebatas
pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan, bukan
berbeda agama.
Dalam buku terbitan Balitbang Depag RI yang ditulis oleh Ichtiyanto
disebutkan bahwa kata “masing-masing” dalam UU perkawinan tertuju pada
agama-agama yang dipeluk di Indonesia, bukan mengacu kepada masing-masing
pengantin. Yang dimaksud di sini bahwa pernikahan itu akan sah apabila
12
Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di
Indonesia, h. 36
pengantin dapat memeluk agama dan kepercayaan yang sama, jika yang terjadi
sebaliknya, yaitu pengantin menganut agama yang berbeda, maka pernikahan
tersebut tetap dianggap tidak sah. 13
Di Indonesia, pernikahan beda agama bisa dilakukan bila salah satu
pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama terlebih dahulu
melakukan perpindahan agama sehingga kedua pasangan memiliki kesamaan
agama. Di sisi lain, pernyataan seperti itu sama sekali tidak sesuai dengan prinsip
yang terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sebagai konstitusi dasar,
pasal 29 ayat 2 yang secara tegas menyatakan adanya kebebasan beragama bagi
setiap warga negara, tanpa terkecuali. Inilah contoh penyimpangan UU turunan
dari UUD di antara sekian banyak contoh lainnya.
Dari sejarahnya, rancangan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
diajukan oleh pemerintah kepada DPR, semula memuat pasal 11 ayat 2 yang
menyebutkan bahwa perbedaan kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat
asal, agama atau kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang
pernikahan. Tetapi, karena satu dan lain hal yang tidak penulis ketahui, akhirnya
ketentuan dalam rancangan UU itu tidak dimasukkan sebagai salah satu pasalnya.
Alih-alih memberi keleluasaan semua pemeluk agama untuk melangsungkan
pernikahan, UU perkawinan sekarang malah memperlihatkan bahwa perbedaan
agama dapat menjadi penghalang dalam melangsungkan pernikahan.14
Kesan bahwa UU no 1 tahun 1974 menentang pernikahan beda agama
terlihat pada pasal 2 ayat (1) UU no 1 tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan
13
Ichtiyanto, SA, SH, APU, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia,
(Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003) h. 85
14
Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di
Indonesia, (Serang:Penerbit Saudara, 1995), h. 37
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu”.15 Karena setiap agama dalam pemikiran mainstream
cenderung menolak pernikahan beda agama, maka dengan demikian pasal ini
secara implisit juga melarang pernikahan beda agama.
Pelarangan beda agama di Indonesia pada ujungnya menimbulkan dampak
sosial yang tidak ringan. Karena Undang-Undang tidak melindungi pasangan
berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan, maka yang sering terjadi
adalah salah satu pasangan berpindah agama ke agama pasangannya. Walhasil,
keberadaan Undang-Undang ini seakan memaksa seseorang untuk berpindah
keyakinan. Padahal, undang-undang dasar sudah menjamin bahwa setiap warga
negara berhak menjalankan keyakinan masing-masing tanpa ada paksaan. Atau,
bisa juga dikatakan bahwa, pelarangan atas pernikahan beda agama sama juga
dengan perngangkangan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Pelarangan pernikahan beda agama, yang berakibat perpindahan agama
yang terpaksa dilakukan oleh pasangan yang hendak melakukannya, juga bisa
dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Karena,
memeluk agama dan kepercayaan merupakan hak manusia yang paling asasi.
Setiap orang berhak memeluk agama yang dianutnya tanpa ada paksaan. Hal ini
termaktub dalam piagam HAM yang sudah diratifiaksi dalam TAP MPR no XVII
/MPR/1998 pasal 13 yang berbunyi : “Setiap orang bebas memeluk agamanya
15
Undang-Undang No : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara 1974/1; TLN
NO. 3019
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu”16
Perpindahan agama yang dilakukan oleh pasangan beda agama seringkali
dilakukan dengan kepura-puraan. Maskudnya, salah satu pasangan pura-pura
berpindah agama dengan memeluk agama yang dianut oleh pasangannya, hanya
untuk “mengelabui” hukum dan aturan tertulis. Hal ini merupakan konsekuensi
lebih parah dari adanya pelarangan atas pernikahan beda agama. Tindakan
demikian sama dengan mempermainkan hukum dan kepercayaan. Sesuatu yang
sejatinya bertentangan dengan semangat penegakan hukum itu sendiri.
Upaya lain yang sering dilakukan oleh pasangan yang hendak melakukan
pernikahan beda agama adalah melakukan pernikahan di luar negeri. Hal ini
menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang juga sama beratnya. Selain
membebani ongkos yang tidak sedikit, pernikahan di luar negeri juga menyisakan
sedikit “pekerjaan rumah” bagi pasangan tersebut, yaitu mengenai status
kewarganegaraan anak mereka. Karena, pernikahan mereka dilakukan tidak
dengan
hukum
yang
berlaku
di
Indonesia,
maka
mengurus
status
kewarganegaraan anak mereka akan lebih rumit.
Bila pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama ini merasa
repot dengan segala aturan yang ada, sementara mereka tidak ingin berpindah
agama masing-masing, terkadang mereka mengambil jalan pintas untuk “kumpul
kebo” atau hidup bersama tanpa menikah.
Dari segala paparan diatas, maka akan tampak bahwa setiap upaya untuk
menghalangi pernikahan beda agama akan menimbulkan konsekuensi yang
16
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII
/MPR/1998.
sebenarnya bertentangan dengan tujuan pernikahan yang diatur dalam UU itu
sendiri. Karena itu, sebaiknya pemerintah patut mempertimbangkan kembali
segala macam aturan yang melarang, atau setidaknya menghalangi dan
mendiskriminasi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama selayaknya
diberikan jalan yang lebih mudah, demi terciptanya tatanan sosial yang lebih baik.
Pemerintah harus lebih tegas karena pernikahan beda agama akan terus
terjadi di Indonesia yang masyarakatnya sangat plural ini. Untuk keselamatan
masyarakat Indonesia, pemerintah sudah sepatutnya menetapkan hukum yang
berlaku untuk masyarakatnya tentang pernikahan orang-orang yang berlainan
agama, dengan tidak melebihkan satu agama atas agama lainnya. Pemerintah
harus betul-betul kembali mempertimbangkan dan memperhatikan asas kesamaan
di muka hukum untuk semua warga negara dari semua agama. Sekali lagi,
terutama dalam kasus pernikahan, pemerintah harus menetapkan aturan yang
egaliter dan memfasilitasi mereka yang kemungkinan menikah dengan pasangan
yang memiliki perberbedaan keyakinan beragama. Hal ini penting mengingat
modernitas dan perkembangan interaksi yang terjadi di Indonesia sudah tidak bisa
dibatasi dengan faktor agama atau apapun.
Lebih dari itu, pelaranganan terhadap pernikahan beda agama hanya akan
memperbanyak anak-anak yang tidak mempunyai orang tua sah menurut hukum.
Yang dari sini kemudian menimbulkan masalah baru seperti tidak terjaminnya hak
atas pemeliharan dan warisan. Lebih parah lagi, anak hasil pernikahan beda agama
kerap memperoleh penghinaan dalam pergaulannya dengan anak-anak lain yang
kebetulan orang tuanya menikah dengan pasangan yang seagama. Hampir dapat
disimpulkan kalau anak hasil pernikahan beda agama adalah anak yang tidak jelas
identitas dan statusnya dalam hukum negara.
Ada sejumlah tempat di mana Kantor Catatan Sipil (KCS) bisa
mencatatkan pernikahan beda agama. Dari sumber-sumber tulisan yang menjadi
rujukan, terlihat bahwa di kantor-kantor tersebut terdapat beberapa putusan yang
memberi izin pernikahan beda agama yaitu:
1. Penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pdt/P/1990, 3 april 1990
antara Bambang Djatmiko Setiabudi, pria Indonesia Islam dan
Maliangkay Sharon dari perempuan Kristen, mendasarkan antara lain
atas Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986
2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 151/Pdt/P/1988 antara
laki-laki Indonesia beragama Budha Cornelis Hendrik dan Siti Nuraini
Isa seorang perempuan Indonesia beragama Islam. Berdasarkan pasal 66
UU tahun 1974 No. 1. Hakim telah menggunakan materi aturan dari
Regeling op de Gemengde Huweijken (GHR), aturan tentang perkawinan
campur zaman pendudukan Belanda, 1898 No. 158 mengingat dalam
UU 1974 No. 1 tidak mengatur pernikahan beda agama secara devinitif.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pdt/P/1989/P.N. Jkt.
Sel. tertanggal 23 Februari 1989, tentang pengabulan pernikahan antara
Togar Siborutorop, laki-laki Indonesia Kristen dan Yavinsa Merlgita
seorang perempun Islam. Pernikahan beda agama tersebut tetap
dilangsungkan berdasar pada materi putusan GHR (sebagaimana juga
disebut pada Pasal 60 undang-undang tahun 1974 No. 1 ayat 3 dan 4):
perbedaan agama bukan penghalang untuk menikah.
4. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 456/Pdt/P/1988/PN Jkt.
Bar., tanggal 29 juni 1988, antara Geri Lumempow seorang laki-laki
Indonesia Kristen, dengan Gina Lasiari seorang wanita dari Islam,
dengan alasan bahwa sesuai pasal 29 UUD 1945. sesungguhnya tidak
ada aksaan dari warga Indonesia untuk memeluk suatu agama tertentu.
Demikian pula undang-undang perkawinan tidak mengadakan paksaan
atau desakan agama yang satu terhadap yang lain. Dan sama sekali tidak
menganjurkan seseorang untuk berpindah agama. Sesuai dengan
Rakernas M.A. dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun
1986 No. 102, menurut pasal 2 ayat 2 PP No. 9/1975, pencatatan mereka
yang melangsungkan pernikahan menurut agama dan kepercayaan selain
Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Kantor Catatan Sipil. Kalau
pegawai Kantor Catatan Sipil menolak,
pengadilan berwenang
memerintahkan mereka untuk mencatat pernikahan tersebut.17
Keputusan-keputusan yang membolehkan pernikahan beda agama seperti
yang tertera diatas tidak banyak kita dapati di Indonesia mungkin hanya sebagian
kecil saja. Hanya beberapa lembaga yang memberi kemudahan bagi pasangan
beda agama untuk melaksanakan pernikahan seperti Paramadina dan Wahid
Institut. Yang dipertanyakan disini mengapa Departemen Agama yang merupakan
alat Negara untuk memberi solusi semacam pernikahan beda agama malah tidak
memberi jalan bagi pasangan beda agama.
Dari situ, tak aneh kalau kemudian orang-orang yang ingin melaksanakan
pernikahan beda agama malah lari ke negara-negara lain hanya untuk
17
Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, (Bandung:Citra
Aditya Bakti,1996), h. 289
mendapatkan keabsahan pernikahan mereka. Di sini jelas bahwa negara kita tidak
mampu untuk melindungi warga negaranya sendiri, malah negara lain yang
sanggup memberi perlindungan bagi warga negara Indonesia, seperti Singapura
dan Australia. Maraknya pernikahan di luar negeri memberi kesan bahwa
Indonesia belum dapat menjamin sepenuhnya hak-hak warga negaranya. Pada titik
inilah dapat diambil kesimpulan bahwa diskriminasi masih menghantui pasangan
yang melakukan pernikahan beda agama di Indonesia. Cara-cara seperti menikah
di negara lain seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah lebih mempunyai
kepekaan dan tanggung jawab untuk menjamin kebebasan warga negaranya
sebagaimana diamanatkan oleh UUD.
BAB III
PERNIKAHAN BEDA AGAMA
MENURUT ISLAM DAN KATOLIK
A. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Islam
Islam terlahir tidak pada ruang yang kosong. Ia terlahir pada sebuah
konteks sosial, sekaligus merespon segala keadaan yang terjadi di seputarnya.
Islam merespon dari masalah ketuhanan, politik, hukum, hubungan antar makhluk
hidup, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Islam tentunya merespon hubungan
pernikahan antar sesama manusia, lebih khusus lagi pernikahan antar-manusia
yang kebetulan berbeda keyakinan, berbeda agama. Paparan selanjutnya akan
memfokuskan diri pada pembahasan tentang pernikahan beda agama ini.
1. Pernikahan Beda Agama menurut al Quran
Respon Islam atas konteks sosial yang terjadi pada saat itu terrangkum
dalam kitab suci al Quran. Al-Qur’an, meski menjadi pembeda antara Islam
dengan agama-agama lainnya, memiliki pesan universal yang sama dengan
agama-agama yang terlebih dahulu diturunkan ke dunia. Salah satu kesamaan
yang paling kentara misalnya pesan yang mengatakan bahwa semua agama
menyerukan umatnya untuk menyembah Allah yang Esa dan selalu melakukan
perbuatan yang bermoral dan konstruktif.
Namun demikian, pengejawantahan nilai-nilai dasar agama senantiasa
bervariasi ketika sudah berhadapan dengan realitas sosial. Selalu terdapat dua
dimensi das sein dan das solen, dimensi historisitas dan normativitas. Kedua
dimensi tersebut tak ubahnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa
dipisahkan satu sama lain. Maka wilayah das solen ajaran agama Islam menyatu
dengan praktek keseharian wilayah das sein sejarah kemanusiaan. 18
Pergumulan das sein dan das solen sudah dimulai sejak permulaan sejarah
kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sangatlah naif kalau hanya memokuskan
diri pada wilayah das solen seraya abai terhadap wilayah das sein. Karena, sekali
lagi, teks-teks al-Quran sebagai wahyu Allah sendiri tidak berbicara pada ruang
hampa. Artinya jelas bahwa al Quran akan kehilangan maknanya ketika
ditanggalkan dari konteksnya. Penafsiran yang dilakukan secara parsial hanya
akan menghilangkan keutuhan makna al Quran dan cenderung terjebak pada aspek
yang sejatinya hanya simbolis.
Khusus tentang permasalahan pernikahan beda agama, ayat-ayat al-Quran
yang umumnya dijadikan pegangan oleh para ulama adalah surat al-Baqarah: 221
⌧☺
!"$%
&'(")*
+',-"." &/01 !2" 3'⌧."
/
/45
6(78$9
:
;
(<=☺
$"$% >/3;
!"."
&/01
!2"
3@."
/ /45
(78$9 3BCDE9
(F$$>(%
GHIJ
KL
MN
O$$>(%
GHIJ
'L-8
,(0P☺
RSTUV
<2=(3$%
R6(%5 LL-X /4YCX;
(F$0Z⌧[(6(% \]]^_
18
M. Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”, Ulumul Qur’an,
No. 4, IV, (1993), h. 17
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang
musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya
budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan
dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya)
kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (al-Baqarah: 221)
atau surat al-Mumtahanah:10:
'`a>DC(%
(<bcZN
O$("5
TJ
$4de5Nc!
d,-"☺
f4(0h8Y$"
!;i$(6"j MN $4HXk9
!`_l☺%UV
FUj
!;i☺n☺X($ f"$" :⌧j
!;i$;o/0 GHIJ KpP5
:
!;i qq /4rsf : /4;i
(FtX(u
!rf 4;i;5
NL" dJ⌧PS9 : ,-$o
/45
[HX(k F9
!;i
NTJ
!;i☺6v5
!;iK$oE9 :
5
w☺;
4xy;V
z0j
;X({| N("
5}J⌧PS9
;X({w~
N(" dJ⌧PS9 /45
T $4
$
{N $45
(u /45
,-v(V MN
+X(k ~
\^h_
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah
mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu
kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka
tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah
mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar
kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta
mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu.
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (al-Mumtahanah/60:10)
Ayat-ayat di atas diturunkan di Madinah serta membawa pesan agar orangorang muslim tidak menikahi perempuan musyrik, begitu juga sebaliknya. Istilah
al-Musyrikun dan al-Musyrikah dalam ayat diatas merujuk pada masyarakat
politeis, penyembah berhala, yang dibedakan oleh al-Qur’an dengan masyarakat
keagamaan lainnya.19 Sedangkan Muhammad Abduh, sebagaimana dinyatakan
oleh muridnya, Muhammad Rasyid Ridha, dengan tegas berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan Musyrik adalah Musyrik Arab pada konteks saat itu yang sangat
agitatif terhadap umat Islam.20
Ayat itu selain berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau
perempuan musyrik juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan
menikahinya, maka si budak dan anak-anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi
lain, surat al-Baqarah: 221 di atas turun dengan kondisi masyarakat Madinah yang
cukup homogen. Umat Islam pada saat itu masih sangat sedikit, ditambah kondisi
kebencian dan peperangan antara kaum Musyrik dengan umat Islam yang
menyebabkan terusirnya Nabi Muhammad dan kaum Muslimin pengikutnya. Oleh
karena itu, melakukan pernikahan dengan kaum Musyrik yang senantiasa
memusuhi dan memerangi Islam, selain dianggap bertentangan dengan tujuan
Islam juga dikhawatirkan malah hanya akan menimbulkan masalah lain.
19
Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Qur’an:
Sebuah kerangka konseptual, (Bandung: Mizan, 1992), h. 73.
20
Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha pada Tafsir al-Manar,
Jilid VI, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t), Nurchalish Madjid dkk. menguatkannya dengan
kontekstualisasi aspek keindonesiaan di sana-sini, sebagaimana terrekam pada tulisan mereka
dalam Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis, (Jakarta: Paramadina dan
The Asia Foundation, 2004), h. 160.
Selain Surat al-Baqarah sebagaimana disebutkan di atas, ayat lain yang
seringkali dijadikan dasar pelarangan nikah beda agama adalah surat alMumtahanah: 10. Ayat ini turun beriringan dengan peristiwa perjanjian
Hudaibiyah yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Quraisy
pada tahun 628 M. Salah satu butir kesepakatan yang dilahirkan pada perjanjian
ini berisi bahwa apabila ada orang dari pihak Quraisy datang kepada Muhammad
atau melarikan diri dari mereka tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan
kepada pihak Quraisy. Sebaliknya, jika ada pengikut Muhammad yang datang
kepada pihak Quraisy, melarikan diri dari dia, maka tidak akan dikembalikan pada
Muhammad.
Sejarah kemudian mencatat bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani,
Abu Jandal, anak dari Suhail bin Amr datang kepada Nabi dan mengutarakan
keinginannya untuk bergabung dengan kaum Muslim. Suhail ternyata mengetahui
hal ini, dia marah besar kemudian memukuli anaknya, direnggut kerah bajunya
untuk dikembalikan kepada kaum Musyrik Quraisy. Saat itu, Abu Jandal berteriak
dengan keras, “wahai kaum Muslim, apakah aku dikembalikan kepada orangorang Musyrik yang akan menyiksaku karena agamaku?” lantas Rasulullah
berkata: “wahai Abu Jandal, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan memberikan
jalan keluar kepadamu dan kepada orang-orang yang lemah yang bersamaan.
Kami telah mengikat perjanjian dengan kaum Musyrik Quraisy, dan kita tidak
boleh menghianati mereka.”
Setelah peristiwa itu ada beberapa orang perempuan Mukminin datang
berhijrah ke Madinah, Ummu Khultsum binti ‘Uqba bin Mu’ait keluar dari
Mekkah. Saudaranya, Umara bin Walid, kemudian menuntut kepada Nabi supaya
wanita itu dikembalikan kepada mereka sesuai dengan isi perjanjian. Tetapi Nabi
menolak permintaannya, karena isi yang termaktub dalam perjanjian tidak
mencakup kaum perempuan. Disamping itu, perempuan yang sudah masuk Islam
tidak sah lagi bagi suaminya yang masih kafir Musyrik, oleh karena itu mereka
harus berpisah. Maka dalam konteks inilah surat al-Mumtahanah turun.21
Dari latar belakang turunnya ayat yang telah dipaparkan di atas, jelaslah
bahwa ayat tersebut hanya menegaskan keharaman perempuan-perempuan
Muslim untuk menikah dengan lelaki kafir Musyrik. Sebagian penafsir
mengemukakan bahwa “kafir” yang dimaksud dalam ayat ini adalah kafir
Musyrik Quraisy. Artinya yang haram untuk dinikahi oleh kaum muslim (laki-laki
dan perempuan) adalah kaum Musyrik Quraisy.
Dari pemaparan kedua ayat beserta konteks sosial historisnya di atas, dapat
disimpulkan bahwa umat Islam dilarang menikah dengan orang Musyrik. Karena
berdasarkan konteksnya bagaimana mungkin akan tercipta keluarga yang
mawaddah wa rahmah jika ternyata kaum Musyrik sangat membenci dan
memerangi Islam. Ayat inilah yang dipahami dan disimpulkan sebagian besar
umat Islam sebagai ayat yang melarang pernikahan antara orang Muslim dengan
non-Muslim.
2. Pernikahan Beda Agama dan Perdebatan tentang Ahl al-Kitab
Membicarakan pernikahan beda agama dalam Islam tak bisa dilepaskan
dari perdebatan tentang Ahl al-Kitab. Perdebatan perihal ini sendiri berpangkal
pada perbedaan penafsiran ayat al-Quran yang berisi tentang kebolehan kaum
21
Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Beda
Agama, Oktober 2003, h.14
Muslim laki-laki untuk menikahi perempuan Ahl al-Kitab dan tidak sebaliknya
sebagaimana terdapat dalam Surat al-Maidah: 5. Ayat tersebut berbunyi:
$45
LqE9
(/[
$;
d(7[Z
xX(6
;E9 (<bcZN
qq /45
$"; /V5
Z qq
1!" d,-xySj /4rsf
,-"☺
1!"
d,-xySj
xX(6
;E9 (<bcZN
NTJ
/45
X/7c
!"
!;iK$oE9
!;i☺nv5
: (<=Pxw$" /0⌧+ (<=-y(;
!("
F>*9
=h[6$"
>Jj
\!%V
/0dP
(%
G<
;i
$9E☺($
⌧7
1!% % 1!" ,(01n
\_
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orangorang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi
mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu
telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan
maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa
yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah
amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (al-Maidah/5:5)
Sebagian kelompok menafsirkan ayat tersebut sebagai penghalalan Islam
atas pernikahan beda agama. Sementara sebagian lagi beranggapan bahwa
kehalalan pernikahan beda agama pada ayat tersebut telah dihapus oleh ayat-ayat
lain yang menyatakan tentang pengharamannya. Kelompok ini tetap beranggapan
bahwa pernikahan antara Muslim dan non-Muslim adalah terlarang, adalah haram.
Namun, sebelum ke penyimpulan itu, ada baiknya ditelusuri terlebih dahulu
perdebatan lebih rinci tentang konsep Ahl al-Kitab yang berkembang di dalam
dunia Islam.
Para ulama salaf (ulama-ulama terdahulu) seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i
dan Hambali sepakat untuk mengharamkan pernikahan antara kaum Muslim dan
kaum Musyrik. Perbedaan pendapat baru terjadi untuk pernikahan antara laki-laki
Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Kelompok pertama menyatakan bahwa
pernikahan yang melibatkan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahl al-Kitab
adalah haram. Mereka yang menyatakan demikian berargumen bahwa Ahl alKitab termasuk ke dalam kategori Musyrik. Keduanya adalah sama karena
kenyataannya memang sama saja.
Selain itu, kelompok pertama ini juga berargumen bahwa surat al Maidah:
5 yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab
telah dinasakh (dihapus) oleh surat al-Baqarah: 221.22 Yang termasuk ke dalam
kelompok ini antara lain Abdullah ibn Umar dan al-Thabarsi. Abdullah ibn Umar
menegaskan bahwa: ”Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari
kemusyrikan orang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu
dari hamba Tuhan.”23 Yang dimaksud dengan “seseorang yang mengaku
Tuhannya adalah Isa atau salah satu dari hamba Tuhan” adalah umat Nashrani dan
Yahudi.
Menurut
Ibn
Umar,
kelompok
ini
pada
prakteknya
telah
mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Umat Kristen dianggap menuhankan
Isa sedangkan umat Yahudi dianggap menuhankan Uzair.
22
Quraisy Shihab, Wawasan al Quran, h. 196.
23
Lihat M. Quraisy Shihab, Wawasan al Quran, (Bandung: Mizan, 1996), h. 15.
Dilihat dari konteksnya, pada saat itu memang terdapat beberapa tokoh
Islam yang menikahi perempuan Yahudi dan Kristen, seperti yang dilakukan oleh
Thalhah dan Hudzayfah. Sikap Umar sendiri sebenarnya lebih mencerminkan
kekhawatiran jika pada suatu saat para sahabat tersebut membelot dan masuk
komunitas non-Muslim. Perasaan demikian mudah dipahami mengingat Islam
pada saat itu sedang membutuhkan jumlah pengikut yang banyak dan loyal.
Dengan demikian, terlihat bahwa Umar sebenarnya hanya ingin memperingatkan
kaum Muslim untuk berhati-hati dalam memperjuangkan Islam, tak terkecuali
untuk memilih pasangan hidup.
Al-Thabarsi memperkuat argumen Ibn Umar dengan mengatakan bahwa
yang dimaksud perempuan Ahl al-Kitab yang halal dinikahi oleh laki-laki Muslim
dalam surat al-Maidah: 5 adalah perempuan Ahl al-Kitab yang sudah masuk Islam
terlebih dahulu sebelum menikah dengan laki-laki Muslim.24 Artinya, ia tetap
mengharamkan terjadinya pernikahan laki-laki Muslim dan Perempuan Ahl alKitab sebelum perempuan tersebut berpindah agama menjadi Islam.
Pandangan kelompok pertama inilah yang dijadikan landasan para ulama
saat ini dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama. Pandangan ini pula
yang menjadi mainstream umat Islam di Indonesia, bahkan kemudian dilegalkan
melalui UU Perkawinan No. I Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)
yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sebagai konsekuensinya,
pernikahan beda agama di Indonesia sama sekali tidak mendapat tempat karena
negara memang tidak memfasilitasinya, tidak memberikan ruang yang
memungkinkan untuk pelaksanaannya.
24
Muhammad Galib. M, Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina,
1998), h. 167.
Kelompok kedua adalah yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki
Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab. Kelompok ini berpendapat bahwa surat
al-Maidah: 5 telah secara tegas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah
dengan perempuan Ahl al-Kitab. Ayat madaniyah itu sekaligus merupakan ayat
terakhir di antara ayat-ayat pernikahan dengan orang kafir, sebagaimana
dinyatakan Nabi: “Surat al-Maidah adalah surat dari al-Qur’an yang terakhir
turunnya. Maka halalkanlah apa yang dihalalkan dan haramkanlah apa yang
diharamkan.”25
Berdasarkan pernyataan Nabi tersebut, kelompok kedua ini beranggapan
bahwa tidaklah benar jika surat al-Baqarah: 221 dan surat al-Mumtahanah: 60
telah me-nasakh surat al Maidah: 5, karena dua ayat yang melarang pernikahan
antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab sebenarnya diturunkan
terlebih dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqih bahwa jika terdapat
dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah
ayat yang lebih akhir diturunkan. Selain itu, kelompok ini membedakan secara
tegas antara non-Muslim dengan Musyrik berdasarkan alasan bahwa dalam alQuran sendiri terdapat sejumlah ayat yang membedakan antara Ahl al-Kitab
(termasuk Kristen dan Yahudi) dengan orang-orang Musyrik. Di antaranya adalah
surat al-Baqarah:105 yang berbunyi:
$0⌧P⌧ abcZN ~(% L"
:
hX(6
_qi9
!"
(L($%
F9
(<=Sj
!2"
/01
!2"
4d7[HX(k
(6%u
MN
/4d7HVK
5N(,
!("
R6☺(0V
25
Budi Handrianto, Perkawinan Beda Agama Dalam Syari’at Islam (Jakarta: Khoerul
Bayan, 2003), h. 65
_q⌧P
;T
MN
\^h_ h~d;
“Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang Musyrik tiada
menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan
Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya
(kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (al-Baqarah/2:105)
dan surat al-Bayyinah:1:
$0⌧P⌧ (<bcZN \!5
(%
hX(6
_qi9
!"
(<=
⌧P$"
(<=☺
$4`jD
\^_ ;'h2v(3
“Orang-orang kafir yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang Musyrik (mengatakan
bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada
mereka bukti yang nyata,” (al-Bayyinah/98:1)
Pada kedua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya, al-Quran memakai kata
penghubung “dan” (waw) di tengah kata kafir Ahl al-Kitab dan kafir Musyrik. Ini
menandakan bahwa kedua kata tersebut (Ahl al-Kitab dan Musyrik), mempunyai
arti dan makna yang berbeda.26 Abu Ja’far ibn Jarir al-Thabari dalam Jami’ alBayan ‘an Ta’wil al-Qur’an menafsirkan Musyrik sebagai orang-orang yang
bukan Ahl al-Kitab. Musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 bukanlah Kristen dan
Yahudi melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci.
Ketiga kelompok di atas yakni Musyrik, Yahudi dan Kristen merupakan
kelompok yang terdapat dalam masyarakat Arab dan sering disebut sebagai
kelompok lain (al-Akhar).27
26
Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan
AntarAgama, Oktober 2003, h. 3.
27
Dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok yang sering disebut sebagai kelompok
lain (al-Akhar) yakni Musyrik, Yahudi dan Kristen. Musyrik adalah mereka yang menempati
Namun demikian, Para ulama yang memperbolehkan pernikahan laki-laki
Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab pun masih berselisih paham tentang siapa
sebetulnya yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab dalam ayat tersebut. Apakah
terbatas hanya untuk umat Yahudi dan Nashrani atau bisa dilekatkan juga untuk
umat-umat dari agama lain? Maliki, Syafi’i dan Hambali hanya memasukkan
umat Kristen dan Yahudi ke dalam kategori Ahl al-Kitab. Sementara Hanafi tidak
hanya Kristen dan Yahudi melainkan juga kaum Majusi dan Shabi’in. Mahmud
Syaltut mengatakan bahwa pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan
perempuan Ahl al-Kitab diperbolehkan sebagai strategi dakwah. Laki-laki dalam
posisinya sebagai suami memiliki hak untuk mendidik keluarganya: istri dan
anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan tersebut diharapkan bisa
mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non-Muslim terhadap Islam
terutama di hati istri. Namun jika hal itu tidak bisa diwujudkan maka perkawinan
itu pun terlarang.28 Dengan demikian, Mahmud Syaltut membolehkan pernikahan
beda agama dengan syarat suami bisa menarik istri dan anak-anaknya untuk
masuk dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.
Adapun mengenai pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki Ahl alKitab, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam al-Quran, para ulama
posisi penting dalam masyarakat yang berpusat di Mekkah. Mereka mempunyai patung yang
paling besar, “Hibal” yang menghadap ke Ka’bah dan dikelilingi oleh 360 patung-patung kecil.
Sedangkan Kristen merupakan kekuatan yang sangat besar di kawasan Arab. Mereka adalah
sekelompok Kristen Syam yang lari dari kezaliman Romawi dan kemudian menempati puncak
gunung serta bukit melalui para pedagang Afrika. Kedatangan orang-orang Kristen tersebut
menyebabkan banyak diantara kabilah Arab yang memeluk Kristen, antara lain: kabilah Ghassan,
Taghallub, Tanukh, Lakhm, Kharam dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan Yahudi adalah
mereka yang juga lari dari kediktatoran Romawi dan Persia yang berpusat di Madinah. Jumlah
mereka hampir dari separuh penduduk Madinah, antara lain: keturunan Qainaqa, Nadhir dan
Quraidzah. Komposisi masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa ada distingsi yang jelas antara
kaum musyrik, Kristen dan Yahudi. Uraian selengkapnya lihat, Nurcholis Madjid, dkk., Fiqih
Lintas Agama, h. 163.
28
Linda Hindasyah, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Pelaku, (Jakarta: PPIM
UIN Jakarta, 2003), h. 27.
melarangnya dengan alasan bahwa perempuan dikhawatirkan akan terpengaruh
oleh agama suaminya. Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa meskipun hal
itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran, dalam prakteknya mayoritas
umat Islam tidak memberikan persetujuan sejak dahulu.
Ketidaksetujuan itu semata-mata didasarkan pada ijtihad bahwa seorang
perempuan Muslimah yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan merasa
susah jika tinggal dalam keluarga non-Muslim, karena akan kehilangan hak yang
seharusnya mereka nikmati sebagaimana jika berada dalam lingkungan keluarga
Muslim. Seorang istri akan mengikuti tradisi suaminya dan suami akan
mempengaruhi statusnya sebagai perempuan Muslim.29 Meski kritik dapat
diajukan karena pandangan seperti ini sangat bias jender, selalu menganggap
perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki, menempatkan perempuan sebagai
manusia yang sama sekali tidak mempunyai daya dan kekuatan menentukan,
dalam Islam, itu diperparah lewat hadits Nabi yang kerap dijadikan dasar
pelarangan nikah beda agama yang berbunyi: Rasulullah SAW bersabda: “Kami
menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitab dan laki-laki Ahl al-Kitab tidak boleh
menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)”.30
Senada dengan itu, Khalifah Umar ibn al-Khattab dalam sebuah pesannya
berkata: “Seorang Muslim boleh menikahi wanita Nashrani, akan tetapi laki-laki
Nashrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah”. Pesan Umar tersebut
29
Maulana Muhammad Ali, Qur’an Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir (Jakarta: Darul
Kutub al-Islamiyah, 1993), h. 2.
30
Hadits di atas menurut Shudqi Jamil al-‘Aththar tidak shahih karena mawquf, sanadnya
terputus hingga Jabir, sebagaimana dijelaskan al-Imam al-Syafi’i dalam, al-Um. Lihat, Hindasyah,
Pernikahan Beda Agama, h. 28.
seringkali dipegang oleh kelompok ini sebagai penguat alasan dilarangnya
perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim.
Dari
paparan
di
atas
terlihat
bahwa
pandangan
yang
tidak
memperbolehkan pernikahan beda agama pada umumnya beranjak dari suatu
keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang,
menurutnya, hanya bisa tercipta jika terdapat kesamaan diantara suami dan istri,
termasuk kesamaan agama. Perbedaan agama merupakan hal fundamental yang
diduga kuat akan mempengaruhi keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga.
Alasan lainnya adalah bahwa dengan pernikahan beda agama dikhawatirkan akan
terjadi konversi (perpindahan) agama atau “pemurtadan”, terlebih jika yang dalam
kubu Islam kebetulan adalah pihak perempuan. Perempuan cenderung lebih lemah
dibandingkan laki-laki.
Kesimpulannya, karena diasumsikan bahwa perempuan memiliki iman
yang lemah, mudah goyah sehingga mudah tergoda untuk pindah memeluk agama
suaminya, seorang perempuan muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan
laki-laki non-muslim sekalipun Ahl al-Kitab.
Berbeda dengan para ulama yang telah disebutkan di atas, Muhammad
Abduh, sebagaimana diungkap oleh Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat
bahwa yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab tidak terbatas pada penganut agama
Yahudi, Nashrani, Majusi dan Shabiin, melainkan para penganut semua agama.
Dengan demikian, menurutnya, Budha, Hindu, Konghucu, dan lain-lainnya pun
termasuk ahl al-kitab. Ahl al-Kitab dalam pengertian Rasyid Ridha adalah setiap
kaum yang memiliki kitab suci dan pernah didatangi seorang Nabi.31 Lebih jelas
lagi, Ahl al-Kitab merupakan gambaran dari orang-orang yang tercerahkan.
Orang-orang yang ketika bertindak mempunyai pemandu, berupa ajaran yang
diyakini, tidak seperti orang musyrik yang jelas tidak mempunyai acuan, sehingga
bermusuhan dengan siapapun.32
Selain itu, kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki
muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab ini juga berargumen bahwa pernikahan
beda agama sudah dilakukan sejak sejarah permulaan Islam. Nabi Muhammad
sendiri bahkan pernah menikah dengan Sofia yang beragama Yahudi dan Maria
Qibtiyyah yang beragama Nashrani. Sementara di kalangan shahabat, Utsman bin
Affan menikah dengan Nailah binti Quraqashah al-Kalbiyah, Huzaifah menikah
dengan perempuan Yahudi di Madinah dan Thalhah bin Ubaidillah menikah
dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Pada saat itu, tidak pernah dipersoalkan
apakah kemudian pasangan mereka itu masuk Islam atau tidak, artinya bebas.33
Lebih jauh dari itu, kelompok kedua ini juga berpendapat bahwa konteks
masyarakat yang sangat plural seperti sekarang ini, perbedaan agama tidak bisa
lagi menjadi suatu penghalang untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Di
samping itu, Islam datang dengan membawa semangat pembebasan, bukan
belenggu. Tahapan-tahapan di dalam al-Qur’an dari mulai pelarangan menikah
dengan musyrik, kemudian membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahl al-Kitab,
merupakan tahapan pembebasan yang evolutif. Penganut agama lain tidak lagi
31
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir al Manar, h. 193.
32
Nuryamin Aini, “Fakta Empiris Nikah Beda Agama,” wawancara diakses tanggal 22 Juni
2003, dari http://www.islamlib.com.
33
Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Penafsiran Baru, h. 7.
dianggap sebagai kelas dua (second class), bukan pula Ahl al-Dzimmah,
melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.34
Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pernikahan
beda agama merupakan konsekuensi logis dari realitas keberagaman agama
sebagaimana diakui sendiri oleh al-Qur’an. Untuk menjembatani ketegangan yang
selama ini terjadi diantara umat beragama, khususnya Islam dan Kristen, maka
pernikahan beda agama bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam upaya
membangun sikap toleransi antarumat beragama, sesuai dengan tujuan
pernikahan, yakni bukan hanya untuk membangun tali kasih sayang yang terdapat
dalam ikatan keluarga, melainkan juga relasi yang seimbang antara dua keyakinan
berbeda yang dilandasi oleh semangat toleransi dan saling menghargai.
Oleh karena itu, di tengah rentannya hubungan antar agama dalam
masyarakat modern dan plural sebagaimana terlihat dalam konteks keindonesiaan,
pernikahan beda agama justru bisa dijadikan wahana tidak hanya untuk merajut
kebahagiaan dua insan yang saling berbeda keyakinan, namun juga untuk
membangun kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama sekaligus dapat
merajut dan memperkuat kerukunan dan kedamaian.
B. Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Katolik
Dalam Katolik pernikahan merupakan suatu hal yang kudus. Kitab
kejadian menyatakan bahwa “tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja”.
Namun demikian, masalah kemudian muncul ketika pernikahan itu tidak
dilakukan oleh umat yang seagama, melainkan berbeda agama. Dalam pernikahan
34
Nurcholis Madjid, dkk., Fiqih Lintas Agama, h. 165.
model demikian, gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seseorang
yang beragama Katolik dengan yang bukan Katolik bukanlah bentuk pernikahan
yang ideal. Pasalnya, sekali lagi, pernikahan, dalam pandangan Katolik, dianggap
sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).35
Dua kitab suci yang dijadikan pegangan hukum umat Katolik, Kitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tak pelak membahas permasalahan seputar
pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang berbeda agama. Di samping
kedua sumber pokok ini, sebagai pelengkap dari kedua sumber hukum utama,
Katolik juga mempunyai sumber lain yakni Hukum Kanonik yang lebih
mendasarkan putusan hukumnya pada realitas kehidupan kemasyarakatan dan
lebih bersifat praktis. Berikutnya akan disajikan secara lebih lengkap mengenai
ulasan atau pandangan tentang pernikahan beda agama, menurut agama Katolik,
dari sumber-sumber yang telah disebutkan di atas.
1. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Lama
Pada Kitab kejadian, kitab yang menyoroti kehidupan bapak leluhur Israel,
dapat ditemukan beberapa kasus perkawinan beda agama. Beberapa bagian dalam
kitab tersebut yang memberi informasi berkenaan dengan kasus pernikahan beda
agama adalah:
i.
Kejadian 6: ayat 5-6
Perkawinan beda agama seperti yang diinformasikan oleh al-Kitab dalam
kejadian 6: ayat 5-6 tersebut merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki
35
Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Ed.), Pernikahan Beda Agama,; Kesaksian,
Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan, (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), h. 207.
Allah. Hal ini nyata direspon oleh Tuhan ketika melihat perkembangan yang
terjadi antara anak-anak manusia pada waktu itu. Tidak dikehendaki artinya
pernikahan yang melibatkan kaum Katolik dengan kaum non-Katolik adalah
terlarang, atau haram dalam bahasa Islam. Terlarangnya pernikahan seperti ini
karena bisa mengakibatkan bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia dan
akan mendatangkan penyesalan dalam hati Tuhan.36
Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia paling besar di bumi dan
bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, maka
menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu
sangat memilukan hatinya.
Di sini dapat dikatakan bahwa betapa besar kejahatan yang dilakukan oleh
manusia, kejahatan manusia itu tidak pernah berubah sampai saat ini. Salah satu
bentuk kejahatan yang dimaksud yaitu pernikahan beda agama. Istilah “menyesal”
dalam ayat ini menunjukkan bahwa akibat dosa umat manusia yang menyedihkan
itu, sikap allah terhadap manusia berubah yaitu sikap kemurahan hati dan sabar
berubah menjadi hukuman.37
ii.
Ulangan 7: 3-4.
Bangsa Israel dilarang kawin dengan bangsa-bangsa diluar Israel.
Pelarangan pernikahan beda agama di sini berlaku untuk agama selain agamanya
bangsa Israel tanpa terkecuali. Hubungan pernikahan beda agama pada akhirnya
hanya akan menghancurkan hubungan manusia dan kekudusan Allah. Yang
dimaksud ayat ini yaitu bahwa permasalahan seperti pernikahan beda agama dari
umat Allah dengan orang yang tidak percaya hanya akan mengakibatkan umat
36
Lihat dalam kitab Kejadian 24
37
Al-Kitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Percetakan Lembaga Al-Kitab Indonesia, h.6
Allah akan berpaling dari agama, sehingga mereka akan beribadah selain kepada
Allah. Allah kecewa dan menghukum orang-orang yang kawin dengan bangsa
diluar Israel.
2. Pernikahan Beda Agama dalam Perjanjian Baru
i.
Korentus 6: 14 dan 7: 1
Ayat ini menjadi salah satu ayat yang berisi penolakan terhadap
pernikahan beda agama. Ayat ini berbunyi “janganlah kamu merupakan pasangan
yang tidak seimbang dan orang-orang yang tidak percaya”. Terlihat jelas bahwa
penolakan atau larangan melakukan pernikahan beda agama dalam Katolik, dari
ayat ini, dikarenakan perbedaan kepercayaan. Tegasnya, maksud dari perkataan
tidak seimbang pada ayat di atas adalah suami istri yang tidak sama-sama
Kristiani, tidak sama-sama beragama Katolik.38 Yang beragana Katolik dianggap
kudus karena kelahirannya sudah melalui pembaptisan, sementara yang nonKatolik tidak kudus karena tidak terlebih dahulu dibaptis, maka bisa disebut
sebagai pasangan yang tidak seimbang.
ii.
Korentus 7: 12-16
Suami istri (pernikahan) yang tidak seiman sudah menjadi fakta yang telah
terjadi sejak gereja awal. Pernikahan beda agama sudah terjadi dan dihadapi oleh
Paulus. Katolik tidak lahir sebagai agama tunggal di muka bumi. Maka sejak
agama ini ada, kehidupan para penganutnya sudah senantiasa bersinggungan
dengan penganut dari agama dan keyakinan yang berbeda-beda (majemuk). Dari
sini, dalam hal membangun sebuah kekuarga, membangun pernikahan
kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama menjadi tak bisa dihindari lagi.
38
Yonathan A. Trisna, Berpacaran dan Memilih Teman Hidup, (Bandung:Kalam Hidup
Pusat,1987) h. 53
Menyadari bahwa melarang seseorang untuk memilih pasangan hidup yang
berbeda agama adalah suatu hal yang tidak bijaksana, Paulus kemudian menulis:
“Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan
perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah seorang itu
menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak
beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia
menceraikan laki-laki itu. (Kor 7: 12b-13).
Pernikahan beda agama dapat terus dilangsungkan atau diperbolehkan
dengan syarat pasangan tersebut dapat memenuhi beberapa persyaratan yakni mau
hidup bersama. Artinya, pasangan yang bukan beragama Katolik harus menerima
prinsip-prinsip moral kehidupan Kristiani tanpa menyebut syarat untuk berganti
agama menjadi Kristiani. Pernyataan ini sendiri sebenarnya bukan datang dari
Tuhan melainkan dari Paulus sendiri. Namun demikian Paulus meyakini bahwa
jika ikatan perkawinan antara pasangan yang berbeda agama (Katolik dan nonKatolik) semacam ini tetap suci sebagaimana diungkapkan dalam kitab I Korentus
7:14 yang berbunyi: “karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh
istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya”.
Pernikahan beda agama (melibatkan pasangan Katolik dan non-Katolik)
jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dituliskan oleh Paulus tetap sah
dan kudus karena salah satu pasangan yang beragama Katolik akan secara
otomatis mengkuduskan pasangannya yang tidak Katolik, yang tidak pernah
diberkati melalui sakramen pembaptisan. Pernikahan beda agama tetap sah
asalkan memenuhi syarat tertentu.
3. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik
Dalam melengkapi hukum ilahi, sebagaimana termaktub pada kitab suci,
Gereja Katolik juga mempunyai hukum kanonik yang landasan hukum dan
penarikan kesimpulan hukumnya lebih berdasar kepada realitas kehidupan
kemasyarakatan. Karena sifatnya yang demikian, hukum kanonik secara umum
lebih detail membahas kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di
masyarakat, tak terkecuali fenomena pernikahan beda agama.
Hukum kanonik mengatakan bahwa ada sejumlah halangan yang membuat
tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Sejumlah halangan tersebut antara
lain: adanya ikatan nikah, dan kaul kebiaraan, tahbisan imam, hubungan
kekeluargaan baik secara biologis maupun hukum, usia yang belum mencukupi,
adanya tekanan atau paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial, adanya
indikasi kejahatan, ketidakmampuan secara fisik maupun secara psikis untuk
melakukan hubungan suami-istri, kesepakatan pranikah untuk tidak mempunyai
anak, perbedaan Gereja, dan juga perbedaan agama. Jika salah satu dari beberapa
pasal di atas terdapat pada pasangan yang hendak menikah maka pernikahannya
akan menjadi tidak sah.
Tentang perkawinan beda agama sendiri hukum kanon mengatakan:
“Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu sudah dibaptis dalam
Gereja Katolik atau diterima didalamnya dan tidak meninggalkannya secara
resmi, sedang yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah”. (Kanon 1086 par. 1)39
Tegasnya, jika terjadi pernikahan beda agama dan di dalamnya terdapat atau
melibatkan umat Katolik kecil kemungkinan dapat dilaksanakan.40
Hukum Kanon Katolik, sebagaimana juga hukum-hukum yang terdapat
pada kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menyatakan dengan tegas
bahwa perkawinan orang yang beragama Katolik dengan orang yang beragama
39
Maria Ulfa Anshor dan Martin Lukito Sinaga, Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama
Pespektif Perempuan dan Pluralisme, (Jakarta:Kapal Perempuan, 2004), h. 53.
40
David Sriyanto, Perkawinan Orang yang Berbeda Agama, (Jakarta: Sekolah Tinggi
Teologi Jakarta, Thesis, 1992), h. 58.
non-Katolik adalah tidak sah. Gereja, lebih jauh, melihat perkawinan beda agama
merupakan perkawinan yang tidak diharapkan dan dilihat sebagai perkawinan
yang tidak seharusnya.
Namun demikian, tidak seperti dua kitab suci Katolik yang utama, hukum
Kanonik Katolik dapat merestui pernikahan beda agama yang melibatkan umat
Katolik di dalamnya dengan catatan pasangan tersebut dapat memenuhi
persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam hukum Kanon. Artinya, Gereja
akan memberikan dispensasi bagi pasangan beda agama yang hendak
melangsungkan pernikahan dengan syarat sebagaimana terdapat pada Hukum
Kanon: 1125 dan 1126 yang berbunyi:
Kanon: 1125: “ijin semacam itu (untuk pernikahan beda agama yang di dalamnya
melibatkan umat Katolik) dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat
alasan yang wajar dan masuk akal, ijin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi
syarat-syarat sebagai berikut: 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan
bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan
berbuat sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dalam gereja
Katolik; 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak
yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa
ia sungguh sadar akan janji dari kewajiban pihak Katolik; 3) Kedua pihak
hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan secara sifat-sifat hakiki
perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya”.41
Kanon: 1126: “menjadi kewenangan Majelis Wali gereja untuk menentukan baik
cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu, harus dibuat, maupun cara
bagaimana hal-hal itu jelas dalam tata lahir.42
Dispensasi di atas dapat terlaksana jika adanya ijin dari uskup setempat
dengan mengikuti pesyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Dispensasi dari
uskup ini juga baru dapat diberikan jika diantara kedua pasangan perkawinan beda
agama ini mempunyai kesadaran untuk membina keluarga yang baik dan utuh
41
Ichtiyanto, Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia, ( Jakarta: Badan
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 130. Lihat juga Sriyanto,
Perkawinan Orang yang Berbeda Agama, h. 58-59.
42
Ichtiyanto, Perkawinan Campuran, h. 130
setelah perkawinan, juga untuk kepentingan pemeriksaan untuk memastikan tidak
adanya halangan perkawinan. Jika syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak
dipenuhi maka uskup belum dapat mengijinkan pelaksanaan pernikahan beda
agama.
Di sini Wali Gereja harus membuat perjanjian baik lisan maupun tulisan
terhadap calon pasangan perkawinan beda agama di depan saksi mengenai janjijanji yang sudah dinyatakan oleh pasangan perkawinan beda agama. Syarat-syarat
di atas harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan perkawinan beda agama,
karena jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi perkawinan yang dilaksanakan
menjadi tidak sah.
Dengan adanya syarat-syarat yang terdapat pada kanon 1125 ini, jelaslah
bahwa agama Katolik secara ekplisit sebenarnya sudah membuka ruang
kemungkinan untuk terlaksananya pernikahan beda agama yang melibatkan
umatnya. Kendati demikian, persyaratan yang sebagaimana termaktub dalam
Kanon 1125 dan 1126 masih mengindikasikan kecemasan akan terjadinya
konversi agama. Sehingga mencegah penganutnya untuk beralih agama atau
minimal mencegah akan kemungkinan terjadinya penurunan kualitas keimanan
penganutnya setelah melakukan pernikahan dengan penganut agama lain.
BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF
TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN BEDA AGAMA
A. Fakta Pluralitas di Indonesia
Pernikahan beda agama dalam konteks Indonesia yang terdiri dari
manusia-manusia, etnis, suku bangsa, bahasa, budaya dan agama beragam
menjadi fenomena yang sangat mungkin terjadi, bahkan tak terelakkan. Suatu hal
yang tentunya sangat alamiah jika pemeluk dari satu agama dengan pemeluk
agama lain saling berinteraksi, membangun relasi, pertemanan, bahkan
persaudaraan, termasuk dalam ikatan pernikahan.
Fenomena yang sangat alamiah itu semestinya tidak berimplikasi terhadap
apapun. Sayangnya, di Indonesia hal itu muncul lebih sebagai masalah ketimbang
berkah. Maka tak bisa disangkal kalau sebenarnya ada sejenis kepentingan yang
dimainkan di balik pelarangan atau minimal sulitnya melangsungkan pernikahan
beda agama di negeri ini. Siapakah mereka yang berkepentingan ini? Kamala
Chandrakirana, dalam pengantar buku Perkawinan Lintas Agama Perspektif
Perempuan dan Pluralisme yang diterbitkan oleh Kapal Perempuan, memberi
jawaban cukup tegas. Baginya, pihak yang paling tergantung terhadap pernikahan
beda agama adalah pihak yang mempunyai kepentingan tertentu dengan institusi
perkawinan itu sendiri.43
43
Kamala Chandrakirana, “Kata Pengantar”, dalam Maria Ulfah Anshor (ed), Tafsir Ulang
Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempuan dan Pluralisme (Jakarta : KAPAL Perempuan,
2004)
Dari situ dapat dikatakan bahwa pelarangan atau resistensi beberapa
kelompok terhadap pernikahan beda agama, bukan sesuatu yang berjalan secara
alamiah. Respon demikian hadir karena memang ada pihak-pihak tertentu yang
mempunyai kepentingan di belakangnya. Untuk kembali mempertegas ungkapan
Chandrakirana, “orang dalam” institusi perkawinan itulah yang justru punya
permainan. Tentunya, ini tidak murni kepentingan agama. Kesimpulan ini bisa
ditarik karena faktanya tak ada satu agama pun yang hadir dengan eksklusifitas
spesial ketimbang agama-agama lainnya. Maka semua agama sejatinya
menempatkan posisi umat dari setiap agama sebagai umat yang setara. Semua
agama mengakui pluralitas umat manusia, tak ada satu pun yang menganggap
bahwa hanya umat dari agamanyalah yang berhak hidup dan melangsungkan
keturunan di dunia.
Dalam konteks itu, Indonesia sebagai negara besar, berpenduduk lebih dari
dua ratus juta jiwa dan plural dari segala aspeknya, hendaknya mengerti sekaligus
memperhatikan betul kemungkinan terjadinya hubungan lintas agama di antara
warga negaranya. Indonesia harus sangat sadar bahwa kemajemukan yang
embodied pada tubuhnya tak selamanya berjalan dan terawat dengan rapih. Hal itu
mesti ditekankan betul karena kemajemukan selain bisa menjadi sebuah kekayaan,
pada dirinya sendiri, ia menyimpan benih disintegrasi dan perpecahan. Perbedaan
yang dimiliki bangsa tak ubah seperti sekam dalam tumpukan jerami. Ia tidak
terlihat berbahaya, tetapi sekali mengemuka bisa membakar semuanya,
menghilangkan semua harmoni yang sebelumnya mendominasi permukaan.
Mungkin masih lekat dalam ingatan bagaimana kasus Ambon dan Poso, di mana
masyarakat saling bergolak karena tidak memahami esensi kemajemukan.
Dalam meretas gagasan di tengah-tengah kemajemukan inilah, esensi
pluraslisme dan dialog antaragama patut dibangun. Banyak titik awal untuk
memulai dialog dan kerjasama lintas agama. Di masa Orde Baru, istilah dialog
dan kerjasama tidak begitu populer. Namun demikian, berbagai upaya untuk
mempererat hubungan antaragama telah dilakukan baik oleh pemerintah, melalui
Departemen Agama (Depag), maupun oleh individu-individu tokoh dan lembagalembaga swadaya masyarakat (LSM).
Istilah toleransi dan kerukunan umat beragama awalnya diprakarsai oleh
pemerintahan Orde Baru, tepatnya oleh Depag, walaupun secara praktis masih
belum banyak dilakukan. Dalam konteks ini, perlu disebut nama Prof. Dr. Mukti
Ali. Ketika menjadi Menteri Agama periode 1971-1978, ia membentuk proyek
kerukunan hidup antarumat beragama yang menyelenggarakan dialog antar-tokohtokoh agama. Depag juga membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama
yang rutin menyelenggarakan pertemuan bersama. Wadah-wadah ini dibentuk
bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja di
Indonesia (PGI), Konferensi Wali-Wali Gereja di Indonesia (KWI), Parisada
Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia
(Walubi).44
Proyek kerukunan antarumat beragama atau toleransi dilakukan oleh
pemerintah dalam konteks integrasi nasional, atau secara spesifik untuk
menciptakan stabilitas dalam menunjang pembangunan nasional.
Kendati pemerintah merupakan pihak pemrakarsa, secara resmi sering
dinyatakan bahwa esensi kerukunan merupakan tanggung jawab agama. Karena
44
Nurcholis Madjid, dkk, Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,
(Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), h. 198.
itu, apabila terjadi perselisihan baik intern suatu agama maupun antarumat
beragama, seyogyanya harus diselesaikan oleh umat beragama itu sendiri.
Dengan kata lain, ungakapan di atas mengandung pesan bahwa di Indonesia
agama tidak berada di bawah bayang-bayang kekuasaan dan pengaruh
pemerintah. Hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang konsultatif
dan partnership (kemitraan), bukan hubungan dominatif. Sebab, Indonesia
memang tidak di desain sebagai negara agama.
Persentuhan agama dengan ide-ide demokrasi yang telah ramai disuarakan
sejak awal 1990-an, yakni pasca runtuhnya Komunisme yang diklaim sebagai
kemenangan demokrasi liberal, membuat forum-forum keagamaan menjadi lebih
terbuka terhadap segala ide yang berkembang. Dalam konteks Indonesia,
misalnya, sudah cukup sering dilakukan seminar-seminar ilmiah berskala lokal,
nasional, bahkan internasional yang mengambil tema-tema dialog antaragama,
peradaban dan globalisasi, Islam dan Barat, dan sebagainya. Semua itu tak lain
merupakan bukti bahwa agama kini tidak bisa mengisolasi diri, apalagi
menghindar, dari pergaulan global dan globalisasi. Ide keterbukaan (glasnot) yang
digulirkan oleh Mikhail Gorbachev semasa menjadi presiden Uni Soviet yang
kemudian memacu gelombang demokratisasi di seluruh Eropa Timur, bukan
hanya menjadi gejala yang khas berkembang di negeri-negeri bekas Komunis. Hal
tersebut merupakan fenomena global, termasuk gejala agama-agama.
Dialog antaragama adalah sebentuk aktivitas yang coba menyerap ide
keterbukaan itu. Dialog tidak mungkin dilakukan tanpa adanya sikap terbuka
antara dua belah pihak. Karenanya, dialog antaragama memiliki arti yang amat
penting untuk menyingkap ketertutupan dalam hubungan antaragama yang selama
ini membeku. Hubungan antar agama yang selama ini terjadi, tanpa bermaksud
membuang fakta harmoni antaragama dalam forum dan organisasi-organisasi
tertentu, masih cenderung diliputi rasa saling curiga, menganggapnya sebagai
indoktrinasi, kristenisasi dalam anggapan umat Islam dan Islamisasi dalam
anggapan umat Kristiani, dan lain sebagainya. Sebuah hubungan yang tidak
dilandasi rasa saling percaya dan saling menghormati.
Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, dialog yang dikembangkan
masih kerap dilakukan sebatas dalam forum-forum seminar di kampus-kampus
dan di tempat-tempat yang eksklusif, tidak dapat diakses oleh semua umat
beragama. Parahnya lagi, aplikasi dari dialog masih hanya mengejawantah dalam
bentuk jargon. Belum beranjak ke arah tindakan yang praksis. Itupun hanya
dilakukan oleh segelintir orang dari masing-masing agama. Beberapa kemajuan
sebagai implikasi dari forum dialog antaragama memang cukup membanggakan,
mulai terbangun rasa saling percaya dan menghormati pada kelompok atau
komunitas agama tertentu. Sayangnya ini, lagi-lagi, tidak menjadi mainstream,
bahkan cenderung dicurigai dan dinilai negatif oleh internal masing-masing
agama komunitas tersebut. Di atas segalanya, dialog antaragama sejatinya perlu
terus dikembangkan, selain mengingat kondisi pluralitas bangsa Indonesia, juga
karena persoalan globalisasi. Dua faktor besar tersebut menjadikan hubungan
antarmanusia, kini, tidak bisa disekat oleh norma budaya dan agama tertentu,
melainkan menerobos batas-batas itu dan mengatasi segalanya.
Di luar faktor agama, dalam konteks budaya bangsa, keragaman yang
dimiliki bangsa ini, sekali lagi, dapat menjadi kekayaan dan penambah keindahan,
tetapi juga sekaligus dapat menjadi bahaya dan seumber kerusakan. Masih belum
kering dalam ingatan beberapa kasus di tanah air yang terjadi atas dasar
perselisihan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA). Kasus Ambon,
Poso, Luwu, dan lain sebagainya seakan semakin menahbiskan betapa
berbahayanya keragaman bangsa ini jika tidak didialogkan. Selain itu, muncul
juga sedikit pertanyaan, jika dialog agama telah lama dilakukan dan hingga kini
masih terjadi berbagai kasus berdarah yang berlatar perbedaan agama, bukankah
berarti bahwa pola dialog antaragama yang selama ini dilakukan kurang
memberikan manfaat.
Berangkat dari pertanyaan ini, sudah saatnya pula digagas pola dialog
antaragama dalam bentuk lain. Pola dialog antaragama yang tidak hanya selesai di
seminar-seminar atau buku-buku saja. Bukan sekedar dialog dan toleransi yang
melangit dan mewacana, tidak membumi dalam tindakan praktis. Sudah saatnya
sekarang merekontruksi pola hubungan antaragama yang secara kongkrit bisa
dipraktekkan untuk mengikat pluralitas bangsa Indonesia. Salah satu cara yang
mungkin bisa dilakukan adalah dengan tidak melarang atau menghalang-halangi
pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama. Sudah tidak dapat
ditolerir lagi sikap curiga buta atau ketakutan atas agama lain, karena pluralitas
sendiri memang tidak bisa dibatasi termasuk oleh pernikahan.
Di samping itu, pelarangan pernikahan beda agama jelas merupakan
bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pernikahan adalah hak
yang asasi bagi setiap manusia. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja
yang dia anggap bisa membahagiakan dirinya dan melangsungkan keturunannya.
Lagipula, segala konseksuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan akan di
tanggung oleh orang yang menjalaninya. Baik atau buruk, duka atau bahagia
hanya akan ditanggung oleh para pelaku yang menjalaninya. Karena itulah,
seharusnya tidak boleh ada larangan untuk melakukan pernikahan campur. Setiap
orang boleh saja menikah dengan pasangan yang berbeda agama asalkan ia
meyakini bahwa pasangannya tersebut bisa membahagiakan dirinya. Sama sekali
tidak ada urusannya dengan intitusi agama atau bahkan negara.
Dilihat dari pertimbangan agama sendiri, pelarangan terhadap pernikahan
beda agama merupakan tindakan yang sama sekali tidak bijak, baik berdasarkan
ajaran agama Islam mupun Katolik (pembahasan utama tulisan ini). Setiap ajaran
agama mengajarkan tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan dan cinta kasih.
Tentunya, prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita pihak yang ingin melakukan
pernikahan beda agama, yang memang mendasarkan hubungan atas dasar cinta
kasih sesama manusia, tanpa memandang “baju” dan keyakinan apa yang mereka
kenakan dan miliki. Dalam Islam, dikenal konsep bahwa Islam adalah agama
rahmatan li al-‘alamiin, agama yang memberi rahmat, cinta kasih bagi seluruh
alam semesta. Konsep demikian membawa implikasi bahwa setiap mahluk di
seluruh dunia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam, selayaknya
mendapatkan atsar yang baik dari keberadaan agama Islam.
Konsep serupa juga dimiliki oleh Katolik. Katolik mendefinisikan dirinya
juga sebagai agama penebar cinta kasih. Yesus sebagai pembawa ajaran Kristiani
hadir dengan membawa pesan utama cinta kasih terhadap semua manusia. Pesan
utama Yesus tersebut tentunya relevan untuk diterapkan dalam pernikahan beda
agama. Karena cinta kasih tidak memandang kaya miskin, suku-bangsa, bahasa,
budaya, negara dan agama.
B. Perdebatan Kontemporer Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Hampir semua fenomena, pada dirinya sendiri, menyimpan pro dan kontra.
Tanpa terkecuali fenomena pernikahan beda agama. Pro-kontra yang meliputi
pernikahan beda agama itu sendiri mungkin sudah setua kehadiran berbagai
agama, bahkan sejak adanya perbedaan dalam umat manusia.
Dalam konteks Islam dan Katolik, kontroversi perihal pernikahan beda
agama lebih diwarnai oleh pendapat yang dimiliki oleh kelompok konservatif dan
kelompok moderat dalam memahami teks dan penafsiran agama. Pihak pertama
adalah golongan yang cenderung menolak terjadinya pernikahan beda agama,
sementara pihak kedua menjadi golongan yang menerima. Golongan pertama
memandang agama sebagai sesuatu yang “saklek” dan paten, tidak bisa diubah
lagi. Beragama adalah menjalani aturan-aturan yang telah tertulis tanpa banyak
pertanyaan, dan menganggap bahwa segala ijtihad untuk menyarikan kebenaran
secara lebih mendalam dianggap sebagai bid’ah dan menyesatkan.
Dalam konteks Islam, perdebatan tentang pernikahan beda agama hingga
kini tetap diwarnai dengan penafsiran atas kata Musyriq dan Ahl al-Kitab yang
terdapat dalam teks al-Quran. Pihak yang menolak pernikahan beda agama dari
kalangan Islam, misalnya, beranggapan bahwa Islam adalah agama yang
sempurna, dengan mengutip beberapa ayat al-Quran, seperti an-Nahl: 89.45 Bagi
kalangan ini, aturan-aturan pernikahan yang ada dalam al-Quran sudah merupakan
aturan yang final dan tidak dapat diubah lagi. Golongan ini berkeyakinan bahwa
al-Quran, sebagai kitab suci, sudah mengatur segala aspek pernikahan secara
45
Budi Handrianto, Pernikahan Beda Agama Dalam Syari’at Islam (Jakarta: PT. Kairul
Bayan, 2003), h. 14.
komprehensif.46 Pemahaman yang dikemukakan cenderung tekstualis tanpa
mempertimbangkan konteks perkembangan sejarah.
Sebaliknya, pihak yang menerima pernikahan beda agama memiliki
pemahaman agama lebih kontekstual. Pihak ini cenderung menganggap bahwa
teks agama tidaklah berdiri sendiri tanpa intervensi ruang dan waktu. Sebuah teks
agama merupakan hasil kerjasama yang sinergis antara “maksud Tuhan” dengan
setting sosial pada waktu teks tersebut diturunkan. Karena itu, untuk bisa
menyarikan kebenaran yang sejati dari sebuah teks agama, perlu dilakukan
pemaknaan atas konteks saat teks tersebut diturunkan, lalu dihubungkan dengan
konteks kekinian. Memaknai kata Musyriq dan Ahl al-Kitab harus juga
memperhatikan setting sosial saat teks tersebut diturunkan. Tidak bisa hanya
sekedar dimaknai sesuai dengan arti dari kamus atau kitab terjemahan saja.
Dari situ, sangat bisa dimaklumi kalau pihak yang menolak pernikahan
beda agama memaksudkan Ahl al-Kitab terbatas pada agama-agama Ibrahim
(Abrahamic Religions), yaitu Kristen dan Yahudi. Mereka menganggap bahwa
hanya agama-agama tersebutlah yang memiliki kitab suci asli dari “langit”.
Mereka menganggap bahwa agama-agama selain yang disebutkan di atas bukan
berasal dari wahyu Tuhan, melainkan ciptaan manusia. Bahkan, bagi mereka,
kaum Kristen dan Yahudi sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai Ahl al-Kitab
lagi karena terlalu banyak penyimpangan yang dilakukan atas kitab sucinya.
Walhasil, kemungkinan untuk melakukan pernikahan beda agama menurut
golongan ini sudah benar-benar tidak mungkin.
46
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 14.
Pihak yang menolak pernikahan beda agama juga melakukan generalisasi
bahwa orang yang menikah beda agama tidak akan berbahagia. Pernikahan
tersebut tidak akan bertahan lama. Selain itu, mereka juga mempertanyakan
tentang nasib anak-anak yang lahir dari keluarga yang melakukan pernikahan
beda agama tersebut47. Di luar perdebatan pemaknaan teks-teks agama, pihak
yang menolak pernikahan beda agama kerap menyela pemikiran pihak yang
menerima. Mereka beranggapan bahwa pendapat kalangan yang menerima
pernikahan beda agama adalah nyleneh dan tidak berdasar.48 Bahkan tak jarang
“mengkafirkan” para tokoh yang memperbolehkan pernikahan beda agama.
Sedangkan pihak yang menerima pernikahan beda agama menganggap
bahwa yang disebut Ahl al-Kitab bukan hanya agama Kristen dan Yahudi saja,
tetapi semua agama yang mengakui adanya Tuhan yang Esa, yang memiliki kitab
suci sebagai panduan hidup mereka. Dalam kategori ini, maka agama Budha dan
Konghucu masuk dalam hitungan. 49 Selain itu, mereka memiliki tafsir tersendiri
atas pemaknaan Kafir (atau Musyriq) dan Ahl al-Kitab. Sebutan untuk golongan
Kafir selalu merujuk kepada kaum Kafir Quraiys di Mekkah yang selalu menindas
kaum Muslim. Juga adakalanya merujuk kepada bangsa yang melakukan invasi
kepada Islam seperti bangsa Persia dan Romawi. Perlu dicatat, bahwa bangsa
Romawi dan Persia juga beragama Kristen dan Yahudi. Sedangkan istilah Ahl alKitab merujuk kepada kaum non-Muslim yang tidak melakukan invasi atau
upaya-upaya yang mengancam keberlangsungan Islam, baik yang beragama
Kristen, Yahudi (Abrahamic Religion) maupun lainnya. Bahkan, tercatat
47
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 26-27.
48
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 114.
49
Nurcholis Madjid, dkk, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis
(Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Fondation, 2003), h. 48.
Rasulullah SAW sendiri pernah menikahi wanita non-Muslim yang bernama
Mariatul Qibtiyah. Wanita ini beragama Kristen Koptik, atau Kristen dari Syiria.
Tipikal kalangan penolak pernikahan beda agama dapat dilihat
sebagaimana dicontohkan oleh pandangan-pandangan Budi Handrianto. Budi
menyebutkan bahwa pernikahan beda agama adalah haram. Kebahagiaan hakiki
berada dalam institusi rumah tangga50. Karena itu, dalam rumah tangga harus
dibangun sinergitas antara suami dan isteri. Hal tersebut belum terlaksana bila
pasangan suami isteri berbeda agama. Budi juga mempertanyakan pendidikan
anak hasil pernikahan campur.51 Budi mengkhawatirkan anak-anak dari
masyarakat Muslim akan beralih agama ke non-Muslim karena pernikahan
campur. Budi juga mengritik perilaku dari artis-artis yang gemar melakukan
pernikahan campur52.
Pendapat yang melarang pernikahan beda agama juga diperkuat oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah menerbitkan fatwa mengenai
keharaman melakukan pernikahan beda agama. Dalam fatwa Majelis Ulama
Indonesia nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang pernikahan beda agama,
MUI memutuskan bahwa :
1. Pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah
haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan
Muslim.
50
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 20.
51
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 26.
52
Handrianto, Pernikahan Beda Agama, h. 30.
Tentang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab sendiri
masih terdapat perbedaan pendapat. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa
mafsadah-nya akan lebih besar daripada maslahatnya, MUI kemudian
memfatwakan pernikahan tersebut juga hukumnya haram.53
Fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik oleh MUI maupun para ulama
Nahdlatul Ulama (NU) dari 1960-an hingga 1990-an tentang pernikahan beda
agama ternyata tidak mengalami perubahan dan fleksibilitas yang signifikan.
Hampir semua fatwanya berisi penolakan terhadap pernikahan beda agama.
Ulama-ulama NU, pada tahun 1962, mengeluarkan larangan pernikahan beda
agama, disusul kemudian oleh fatwa yang sama pada 1968 dan 1969. MUI Jakarta
mengeluarkan fatwa senada pada 1975, diikuti fatwa MUI pusat pada 1980.
Kemudian MUI Jakarta kembali mengeluarkan surat publik yang menegaskan
larangan pernikahan beda agama dalam situasi apapun pada tahun 1986.54
Pertanyaan yang muncul adalah mengapa fatwa-fatwa tersebut tidak
berubah? Komentar Mohammad Atho Mudzhar menanggapi hal ini menarik untuk
disimak:
“Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang kaum Muslimin pria dan wanita
untuk kawin dengan orang yang bukan Islam bahkan juga dengan orang-orang
ahl al-kitab, rupanya didorong oleh keinsyafan akan adanya persaingan
keagamaan kendatipun ada kenyataan khusus al-Qur’an yang memberi izin
kepada kaum pria Islam untuk mengawini wanita Ahl al-Kitab. Hal ini boleh jadi
berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik
rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat Muslim, sehingga pintu
bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan antaragama harus ditutup sama
sekali.”55
53
Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Inddonesia Mesjid Istiqlal, 1995), h. 91.
54
Muhammad Ali, “Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia,” Studia Islamika:
Indonesian Journal for Islamic Studies 9, no. 3 ( 2002): h. 1.
55
Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1979-1988) (Jakarta: INIS, 1993), h. 103.
Lebih lanjut dia menilai bahwa fatwa-fatwa tersebut sangat radikal karena selain
berlawanan dengan apa yang secara jelas dinyatakan oleh al-Quran juga
bertentangan dengan kitab-kitab fiqh klasik yang biasanya dirujuk oleh MUI
sendiri untuk membuat fatwa-fatwa.
Paparan di atas menerbitkan suatu pemahaman bahwa ternyata fatwafatwa pelarangan pernikahan beda agama muncul dalam konteks ketegangan
antara umat Islam dengan umat Kristen yang sudah terjadi berabad-abad. Hal lain
dapat juga diutarakan bahwa kemunculan fatwa semacam itu tidak hanya
menggambarkan wacana mengenai hukum Islam tapi lebih mencerminkan sikap
dan persepsi para pemuka Islam terhadap penganut agama lain. Ini tercermin dari
komentar beberapa tokoh Islam ketika mengomentari maraknya pernikahan beda
agama dewasa ini.
Amidhan, Ketua MUI, berpendapat bahwa pernikahan beda agama harus
dihindari karena selain bertentangan dengan Undang-undang Pernikahan Nomor I
Tahun 1974, juga dikhawatirkan menimbulkan pergeseran makna pernikahan
menurut Islam. Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki makna sakral. Dengan
menikah diharapkan terwujud sebuah keluarga yang sakinah. Berdasarkan tujuan
pernikahan tersebut maka pada prakteknya akan sulit membangun kelurga sakinah
melalui fondasi perbedaan agama dalam satu atap. Al-Quran memang
memperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab,
meski para ulama masih bersilang pendapat. Terlepas dari silang pendapat
tersebut yang perlu digarisbawahi adalah motif dari pernikahan beda agama itu
sendiri. Kalau motifnya untuk mengagamakan salah satu pasangan ke agama yang
lain, maka hal itu jelas bertentangan dengan tujuan suci pernikahan oleh agama.56
Husein Umar, Sekjen Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
berpendapat senada dengan Amidhan. Menurutnya pernikahan beda agama tidak
dapat diterima karena bertentangan dengan aqidah Islam dan undang-undang yang
ada (UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan). Islam tidak boleh menganggap
sepele masalah pernikahan beda agama. Ada sinyalemen bahwa maraknya
pernikahan beda agama di beberapa daerah merupakan bagian dari strategi
pemurtadan. Baginya, pernikahan beda agama tidak ada kaitannya dengan
toleransi antarumat beragama. Senada dengan itu, Muslimat NU mengemukakan
bahwa sebaiknya pernikahan beda agama dilarang secara tegas, tujuannya untuk
mencegah pemurtadan dan kehancuran pernikahan.57
Dari komentar tokoh-tokoh Islam yang telah dipaparkan di atas, tak heran
apabila orang-orang yang melakukan pernikahan beda agama dianggap telah
melanggar cita-cita agama dalam hal memelihara aqidah dan menjaga identitas
serta integritas komunitas (dalam hal ini Islam).
Quraisy Syihab termasuk salah seorang ulama tafsir yang memaknai Ahl
al-Kitab terbatas pada umat Yahudi dan Kristen, baik yang ada sebelum Islam
maupun setelah datangnya Islam. Menurutnya, laki-laki Muslim diperbolehkan
menikah dengan perempuan Ahl al-Kitab, yakni Yahudi dan Kristen, kalau
mereka memang senantiasa menjaga kesucian dan kehormatannya sebagaimana
56
“Ada Motif di Balik Pelaminan,” Tabloid Republika Dialog Jum’at, 15 Agustus 2003, h.
4.
57
“Galeri Pendapat: Pro-Kontra Nikah Beda Agama di Kalangan Ulama,” Tabloid Jum’at,
12 September 2003, h. 5.
diungkapkan dalam surat al Maidah di atas, (wal muhshshanatu minal ladzina utul
kitab).
Nada yang berbeda dikemukakan oleh Musdah Mulia. Menurutnya,
kekhawatiran sebagian umat Islam akan terjadinya konversi agama dari pihak
Muslim jika menikah dengan non-Muslim, berangkat dari sindrom psikologis,
yakni umat Islam seringkali dihinggapi rasa tidak percaya diri dan rasa takut yang
berlebihan, yang tidak beralasan. Meskipun mayoritas, umat Islam Indonesia
cenderung bersikap atau bermental minoritas. Lebih dari itu, kalaupun pernikahan
beda agama diperbolehkan, maka umat Islam selalu menginginkan pihak Muslim
mampu mempengaruhi pasangannya agar melakukan konversi agama, dan jika
terjadi sebaliknya, umat Islam pun menjadi murka dan mengutuknya. Hal ini
disebabkan yang pertama identik dengan kemenangan dan yang kedua identik
dengan kekalahan, dan umat Islam hanya ingin menang. Lebih parah lagi, sikap
dan pikiran yang sangat tidak sehat ini ternyata tidak hanya didapati di kalangan
Muslim, tetapi juga di kelompok agama yang lain.58
Budhy Munawar-Rahman menilai bahwa kondisi masyarakat kini yang
sangat plural mengakibatkan terjadinya interaksi yang tidak mungkin lagi
dikendalikan, ia menjadi tidak terbatas. Maka, menurutnya, negara telah berlaku
ekslusif saat menetapkan Undang-undang Pernikahan yang tidak memberi ruang
bagi pernikahan beda agama.59 Senada dengan itu, Ulil Abshar Abdala,
Koordinator Jaringan Islam Liberal, mengungkapkan bahwa dalam Islam
pernikahan beda agama itu tidak ada masalah. Islam, menurutnya, adalah agama
58
Zainun Kamal dan Musdah Mulia, Makalah: Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan
AntarAgama, Oktober 2003, h. 11.
59
“Pernikahan Campuran: Ibu Dominan, Anak Bingung,” Tabloid Republika Dialog
Jum’at, 15 Agustus 2003, h. 3.
revolusioner. Hal itu terbukti dengan diperbolehkannya pernikahan antaragama
meski pada saat itu masih sebatas untuk laki-laki Muslim yang menikahi Ahl alKitab. Revolusi seperti itu harus diteruskan sehingga pernikahan beda agama tidak
dilarang. Kesulitan pernikahan beda agama sebetulnya lebih kepada kesulitan
birokrasi, bukan kesulitan secara agama. Islam sendiri justru percaya bahwa
semua agama itu benar.60
Sedangkan menurut Zainun Kamal, secara eksplisit al-Quran sebenarnya
mengizinkan seorang laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita nonMuslim. Hal tersebut disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5. Zainun
mengatakan bahwa dalam ayat tersebut dinyatakan alladzîna ûtu al-kitab, orangorang-orang yang mempunyai kitab suci.61
Zainun berpendapat bahwa al-Quran mengkategorisasikan kaum nonMuslim menjadi golongan Musyriq, Mukmin dan Ahl al-Kitab. Orang Musyriq
bisa didefinisikan sebagai mereka yang percaya pada adanya Tuhan tetapi juga
mempersekutukan dengan lainnya, serta tidak percaya pada kitab suci dan atau
tidak percaya pada salah seorang nabi. Kaum musyrik yang disebut disini adalah
kaum musyrik Mekkah dan secara hukum Islam tidak boleh sama sekali dinikahi.
Sedangkan Ahl al-Kitab adalah mereka yang percaya pada salah seorang Nabi dan
salah satu kitab suci.
Teks yang tertera dalam al-Quran surat al-Mâ’idah adalah orang-orang
yang diberikan kitab atau Ahl al-Kitab. Golongan ini mempercayai kebenaran
kitab suci mereka dan yang diutus kepada mereka adalah seorang Nabi. Maka,
60
61
“Pernikahan Mei Menuai Kontroversi,” Gatra, 21 Juni 2003, h. 19.
Petikan wawancara dengan Zainun Kamal, dalam www.islamlib.com. Tanggal akses 29
desember 2007.
menurut Zainun, menikahi golongan ini diperbolehkan. Misalnya, orang Budha
menganggap mereka punya kitab suci dan Budha Gautama adalah seorang Nabi.
Konghuchu, dianggap Nabi dan mempunyai kitab suci. Demikian juga dengan
Sintho. Jadi, pemeluk agama-agama tersebut dianggap sebagai Ahl al-Kitab.
Begitu juga dengan pemeluk agama Yahudi, yang memiliki kitab taurat dan
percaya kepada rasul yang diutus kepada mereka, yakni Nabi Musa. Juga umat
Nasrani yang memiliki kitab suci yang rasul.
Mengenai persoalan hanya Muslim laki-laki yang boleh menikahi wanita
non-Muslim, Zainun mengatakan bahwa hal tersebut perlu untuk ditinjau ulang.
Karena pada akhirnya, tanggungjawab untuk mendidik anak ada pada kaum
perempuan. Sehingga, dalam pernikahan beda agama, posisi seorang perempuan
justru lebih potensial untuk mempengaruhi anak-anak mereka agar masuk agama
tertentu. Lebih lanjut, Zainun juga berpendapat bahwa semua agama sebenarnya
membawa pesan moral yang sama.
Selain Zainun Kamal, tokoh lain yang menerima pernikahan beda agama
adalah Drs. Nuryamin Aini., M.A. Ia adalah pengajar pada Fakultas Syariah UIN
Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
(PPSDM) UIN Jakarta pada Kamis. Nuryamin menulis tesis untuk meraih gelar
MA di Flinders university dengan mengambil tema pernikahan beda agama.
Nuryamin melakukan penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
sebagai sasaran penelitian. Alasannya, karena DIY merupakan melting pot atau
wadah peleburan identitas budaya. Dari data tersebut ditemukan bahwa di DIY
terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus yang menikah
beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik
menjadi 18 kasus dan justru trend-nya menurun menjadi 12 kasus saja pada tahun
2000. Trend penurunan ini dalam bahasa statistiknya disebut U terbalik. Tahun
1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi
tahun 2000.
Dari kalangan Katolik, tokoh yang menerima keberadaan pernikahan beda
agama adalah Antonius Dwi Joko. Antonius berpendapat memang sebaiknya
masyarakat pemeluk agama Katolik tidak melakukan kawin campur. Akan tetapi,
mengingat kompleksitas dan pluralitas situasi masyarakat, di mana orang-orang
Katolik hidup berdampingan dengan non-Katolik. Selain itu, semangat ekumenis
Gereja Katolik untuk merangkul dan bekerjasama dengan pihak-pihak Kristen
lainnya, serta kesadaran akan kebebasan beragama, telah mendorong pada
pemahaman akan realitas terjadinya pernikahan campur.62
Namun, satu hal yang menjadi amatan penulis dari perdebatan soal
pernikahan beda agama, meski tidak akan dijabarkan lebih jauh, adalah kurangnya
perhatian terhadap perspektif jender. Ini tak aneh, mengingat pembahasan
pernikahan memang kerap bias jender. Dari paparan di atas, tampak bahwa
pernikahan beda agama atau pernikahan secara umum cenderung lelaki sentris.
Makanya penghalalan pernikahan beda agama oleh beberapa kalangan pun belum
dapat melepaskan diri dari pengarus-utamaan laki-laki. Faktanya, kehalalan
pernikahan antara lelaki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab lebih dilatari
oleh alasan bahwa lelaki lebih bisa mendidik dan mengarahkan istri dan anakanaknya, tidak sebaliknya. Di dunia sekarang, hal sebaliknya justru banyak
terlihat. Kini, tidak sedikit perempuan (istri) yang lebih mempengaruhi keluarga
62
Antonius Dwi Joko, Pr, “Kawin Campur”, http://yesaya.indocell.net/id1066.htm, diakses
pada tanggal 29 Desember 2007.
ketimbang suami. Kalau sudah demikian, maka tidak hanya suami tetapi
pendidikan anak pun sebenarnya dapat ditentukan atau lebih didominasi oleh
peran istri (perempuan).
C. Analisis Komparatif terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia
Pernikahan beda agama, sedari awal sudah dinyatakan, menjadi fenomena
yang kontroversial baik dalam Islam maupun Katolik. Meski dalam banyak hal,
keduanya memiliki perbedaan yang amat jelas, persamaan juga muncul tak kalah
banyak. Persamaan ini, secara umum, terlihat minimal pada adanya sumber teks
kitab suci yang secara eksplisit melarang pernikahan beda agama dan kemudian
ada pula teks kitab suci yang memperbolehkannya dengan spesifikasi persyaratan
yang berbeda-beda. Dari sini, persamaan antara Islam dan Katolik, pada saat yang
sama juga menyimpan perbedaan. Dua hal ini pada paragraf-paragraf berikutnya
akan dieksplorasi lebih detil.
Untuk
lebih
mensistematisasi
perbandingan
pandangan mengenai
pernikahan beda agama antara Islam dan Katolik, berikut disajikan tabel
persamaan dan perbedaan sumber dan pandangan kedua belah pihak:
Tabel Perbandingan pandangan Pernikahan Beda Agama (PBA)
Menurut Islam dan Katolik
Aspek
Perbandingan
Larangan
terhadap PBA
(Teks
Primer
Kitab Suci)
Pembolehan PBA
(Teks
Primer
Kitab Suci)
Islam
al-Baqarah
ayat 221 dan
al-Mumtahanah
ayat 10
al-Maidah
ayat 5
Katolik
Keterangan
Perjanjian
Lama:
Kejadian 6: 5-6 dan
Ulangan 7: 3-4
Perjanjian
Baru:
Korentus 6: 14, 7:1, dan
7: 12-16
Baik
Islam
maupun
Katolik
mempunyai
sumber primer Kitab Suci
yang menyatakan tidak
bolehnya melakukan PBA
Islam membolehkan PBA
antara laki-laki Muslim
dan Perempuan Ahl alKitab
dan
tidak
sebaliknya.
Sementara
Teks Sekunder
Penafsiran
Kontemporer
tidak ada teks primer
Kitab Suci Katolik yang
menyatakan
bolehnya
melakukan PBA
Katolik baru menyatakan
boleh melakukan PBA
Hukum Kanon 1125
pada hukum pendukung
Hadits Nabi
dan 1126
Kitab
Suci
dengan
persyaratan yang sangat
ketat
Pandangan kontemporer yang berkembang dalam Islam maupun Katolik
tentang PBA bervariasi. Tidak sedikit yang tetap menyatakan tidak boleh,
sementara juga bermunculan penafsiran dan pendapat yang menyatakan
bolehnya melakukan PBA, bahkan tidak dibatasi oleh jenis kelamin dan
syarat-syarat yang memberatkan bagi pasangan pelaku PBA
Dari tabel di atas, tampak bahwa baik Islam maupun Katolik sama-sama
memiliki teks primer kitab suci yang menyatakan tidak diperbolehkannya
melakukan pernikahan beda agama. Namun demikian, Islam secara eksplisit
memiliki satu sumber teks pada kitab suci yang memperbolehkan pernikahan beda
agama, meski hanya untuk pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahl
al-Kitab.
Di atas segala perdebatan yang muncul tentang pemaknaan kata Ahl alKitab itu, satu hal yang menjadi nilai lebih pada Islam adalah adanya teks kitab
suci yang memperbolehkan pernikahan beda agama bagi umatnya. Lebih dari itu
terdapat juga salah satu hadits Nabi yang memperbolehkan pernikahan beda
agama. Pada titik ini, baik sumber hukum primer (al-Quran) maupun sumber
hukum sekunder, pendukung (hadits Nabi) menyatakan bolehnya melakukan
pernikahan beda agama.
Persoalan tentang pernikahan beda agama dalam Islam ternyata tidak
berhenti sampai di situ. Dalam penafsiran baik pada jaman ulama salaf (ulama
jaman dahulu) maupun jaman sekarang masih terdapat kekhawatiran akan
pernikahan beda agama. Lebih dari itu, kekhawatiran itu kini menjadi lebih tegas
dengan munculnya pelarangan pernikahan beda agama. Larangan tersebut datang
dengan latar argumen bahwa sudah tidak ada lagi umat yang bisa dikatakan Ahl
al-Kitab dan kekhawatiran terjadinya mutasi keimanan dan agama bagi umat
Islam yang melakukan pernikahan beda agama. Parahnya, hal itu diperkuat oleh
Undang-Undang (UU) perkawinan yang dimiliki oleh Indonesia. UU perkawinan
Indonesia terlihat masih membatasi, tidak memfasilitasi, bahkan dapat dikatakan
melarang terjadinya pernikahan beda agama. Kalaupun boleh, persyaratan yang
musti
dipenuhinya
begitu
berat,
hampir-hampir
tidak
memungkinkan
melangsungkan pernikahan beda agama. Untuk yang terakhir ini, tentunya, tidak
hanya dialami oleh umat Islam, melainkan juga umat Katolik dan umat agamaagama lain yang ada di Indonesia.
Sedangkan dari pemikiran agama Katolik, gereja Katolik menganggap
bahwa pernikahan beda agama bukanlah pernikahan yang ideal. Pasalnya,
pernikahan dalam agama Katolik dianggap sebagai sebuah sakramen (kudus).
Karena itu, Katolik tampak lebih memberikan persyratan yang terlampau ketat
bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama.
Persoalan Pernikahan beda agama seperti yang diinformasikan kitab
Kejadian 6: 5-6 dianggap sebagai pernikahan yang tidak dikehendaki Allah. Ada
semacam keyakinan bahwa pernikahan beda agama hanya akan mengakibatkan
pada makin bertambahnya dosa dalam kehidupan manusia, bahkan mendatangkan
penyesalan dalam hati Tuhan.63
Kitab Ulangan 7: 3-4. menyebutkan bahwa bangsa Israel dilarang kawin
dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Israel dalam konteks itu artinya umat Kristen
63
Lihat dalam kitab Kejadian: 24.
(Katolik) juga tidak boileh menikah dengan bangsa atau umat lain. Namun dalam
Hukum Kanonik, sikap gereja Katolik tampak lebih melunak. Meski
kemungkinan melakukan pernikahan beda agama disertai dengan berbagai
persyaratan yang sama sekali tidak mudah.
64
Kendati begitu, tampak bahwa
gereja lebih memiliki keasadaran untuk tidak melarang pernikahan beda agama.
Melarang seseorang untuk memilih pasangan hidup merupakan hal yang tidak
bijaksana. Dengan kejadian ini Paulus kemudian menulis, “Kalau ada seorang
saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup
bersama-sama dengan dia, janganlah seorang itu menceraikan dia. Dan kalau ada
seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup
bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.”
Kembali membincangkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi pasangan
yang hendak melakukan pernikahan beda agama dalam Katolik, hal itu tetap
memberatkan. Contohnya, pasangan yang bukan beragama Kristen harus
menerima prinsip-prinsip moralitas hidup Kristen yang dijalankan oleh
pasangannya, meski tanpa menyebut syarat untuk berganti agama menjadi
Kristen. Pernyataan ini sendiri sebenarnya bukan datang dari Tuhan tetapi dari
Paulus. Paulus meyakini bahwa ikatan pernikahan semacam ini tetap suci
sebagaimana dikatakan Korentus 7:14, “karena suami yang tidak beriman itu
dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh
suaminya.”
Dispensasi seperti yang disebutkan di atas pun baru bisa dilakukan jika
ada izin dari uskup setempat dengan mengikuti pesyaratan-persyaratan yang sudah
64
Ichtiyanto, Pernikahan Campuran dalam Negara Republik Indonesia (Jakarta: Badan
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), h. 130.
ditetapkan. Dispensasi dari uskup ini juga baru dapat diberikan jika di antara
kedua pasangan pernikahan beda agama ini mempunyai kesadaran untuk membina
keluarga yang baik dan utuh setelah pernikahan, juga untuk kepentingan
pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan pernikahan. Tanpa adanya
syarat-syarat tersebut, maka uskup belum bisa memberi izin untuk melakukan
pernikahan beda agama.
Pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama harus membuat
perjanjian lisan maupun tulisan di depan saksi mengenai janji-janji yang sudah
dinyatakan. Perjanjian tersebut kewenangannya di pegang oleh wali Gereja.
Syarat-syarat diatas harus benar-benar diperhatikan oleh pasangan pernikahan
beda agama, karena jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka pernikahan itu
tidak sah. Di atas segalanya, syarat-syarat yang sedemikian rumit sebenarnya
dilakukan sebagai upaya untuk mencegah perpindahan agama dari Katolik ke
agama lain. Atau minimal mencegah menurunnya keimanan penganutnya setelah
kawin dengan penganut agama lain.
Akan tetapi, dikalangan pendeta Katolik, kini, sudah cukup banyak yang
berpikiran moderat yang beranggapan bahwa pernikahan beda agama merupakan
suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Perbuatan menghalangi cinta kasih
dua insan atas nama agama sungguh tidak benar dan bertentangan dengan Hak
Asasi Manusia (HAM). Karena Yesus sendiri datang dengan membawa ajaran
mengenai cinta kasih dan perdamaian. Bukan malah membawa umatnya ke dalam
kejumudan dalam pergaulannya. Umat Katolik, seyogyanya menyebarkan
gagasan-gagasan cinta kasih Yesus kepada pemeluk lain dengan berbagai cara,
termasuk jika terjadi hubungan pernikahan dengan umat agama lain.
Sedangkan perbedaan antara pandangan Islam dan Katolik pada sumber
yang memperbolehkan pernikahan beda agama pada kedua agama tersebut adalah
dalam hal jenis kelamin. Dalam Islam, teks al-Quran menyebutkan bahwa
kebolehan tersebut hanya berlaku bagi laki-laki. Sedangkan perempuan tidak
diperkenankan melakukannya. Asumsi dari aturan ini adalah, bahwa laki-laki
adalah kepala keluarga yang otoritasnya dianut oleh keluarga. Sehingga, upaya
untuk membawa anak-anak mereka ke dalam agama Islam akan lebih mudah
dilakukan oleh seorang laki-laki daripada perempuan.
Meski demikian Islam kemudian menunjukkan perkembangan bahwa
pendapat dan tafsir atas hal ini perlu dikaji ulang dengan melihat pada konteks
ayat tersebut. Ayat tersebut mungkin relevan jika dikorelasikan dengan konteks
turunnya ayat di jaziran Arab pada abad ke enam (6) Masehi. Pada masa itu,
dominasi jenis kelamin laki-laki sangatlah kuat. Sedangkan kaum perempuan
tidak memiliki daya apapun jika berhadapan dengan laki-laki. Akan tetapi,
sekarang ini, asumsi tersebut tidak lagi bisa dijadikan patokan. Seorang ibu, kini,
justru lebih dekat dengan anak-anak mereka. Maka peluang untuk menanamkan
pengaruh dalam keagamaan menjadi lebih potensial dimilikinya ketimbang sang
ayah. Karena itulah kemudian muncul sebuah wacana untuk membebaskan jenis
kelamin pihak yang melakukan pernikahan beda agama tersebut.
Sementara Katolik tidak mengenal pembedaan jenis kelamin dalam
melakukan pernikahan beda agama. Setiap jenis kelamin, baik laki-laki maupun
perempuan, boleh melakukan pernikahan beda agama, asal memenuhi segala
persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Hukum Kanon. Dalam hal ini, Katolik
terlihat lebih egaliter ketimbang Islam yang masih kental patriarkhis.
Perbedaan kedua adalah mengenai syarat-syarat untuk melakukan
pernikahan beda agama. Dalam pandangan Islam, pernikahan beda agama tidak
menuntut persyaratan yang rumit, semua berlaku seperti pernikahan biasa. Akan
tetapi, dalam pandangan Katolik, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan
yang hendak melakukan pernikahan beda agama cukup rumit. Harus ada
perjanjian lisan maupun tertulis dari pihak yang beragama Katolik untuk tidak
berpindah agama. Begitu pula dengan pengasuhan anak-anak mereka. Pandangan
Katolik menuntut otoritas mendidik agama anak-anak hasil pernikahan beda
agama dalam didikan gereja.
Namun kedua agama ini juga memiliki titik kesamaan bahwa pernikahan
akan lebih baik dilakukan dengan pasangan yang seiman. Dalam pandangan
Islam, disebutkan (al-Baqarah: 221) bahwa wanita budak yang beriman lebih baik
dibandingkan dengan wanita Kafir yang merdeka. Disebutkan pula dalam hadis
bahwa dalam memilih pasangan ada empat hal yang harus dipertimbangkan; dari
aspek, kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama. Dan aspek agama inilah yang
paling penting untuk dipertimbangkan. Senada dengan pandangan Islam,
pandangan Katolik pun menganggap bahwa pernikahan akan lebih sempurna bila
penganut Katolik menikah dengan orang yang seiman.
Lebih jauh lagi, dalam menyikapi fenomena keberagaman Indonesia,
terutama konteks agama, baik dari kalangan Islam maupun Katolik sama-sama
sudah memunculkan pihak yang cukup bijak dengan menganggap pernikahan
beda agama sebagai sebuah konsekuensi yang tidak bisa dihindari lagi. Dimensi
pluralitas bangsa ini menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa jika
tidak disikapi dengan bijak. Melarang pernikahan antaragama, sama dengan
menghilangkan kemungkinan terjadinya akulturasi dan peleburan simpul-simpul
sosial bangsa. Tampak bahwa penafsiran paling kontemporer pada kedua agama
memiliki kesamaan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang tidak
terlarang, bahkan tanpa pembedaan jenis kelamin dan ketatnya persyaratan yang
terlebih dahulu harus dipenuhi oleh para pelaku pernikahan beda agama. Sebuah
kondisi yang menggembirakan.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, sebagaimana rumusan masalah
yang penulis ajukan di awal tulisan, penulis akan menyimpulkan seluruh isi
tulisan ini ke dalam dua pokok permasalahan.
1. Landasan Pernikahan Beda Agama dalam Islam dan Katolik
Landasan hukum untuk memutuskan persoalan pernikahan beda agama
baik dalam Islam maupun Katolik bersumber pada kitab suci masing-masing.
Meski terdapat perbedaan pendapat dalam penafsiran dan sebagainya, baik kitab
suci Islam maupun Katolik memiliki kesamaan sikap dalam menjawab persoalan
pernikahan beda agama. Islam maupun Katolik beranggapan bahwa pernikahan
beda agama adalah sesuatu yang terlarang secara agama.
Namun demikian masing-masing menyisakan celah untuk kemungkinan
dilangsungkannya pernikahan beda agama. Dalam hal ini, kitab suci Islam, alQuran, menurut penulis, sebagaimana juga diakui Ulil Abshar Abdalla, lebih
revolusioner menyikapi fenomena pernikahan beda agama. Meski berjalan secara
evolutif, al-Quran kemudian secara eksplisit menyatakan bahwa pernikahan beda
agama dalam Islam diperbolehkan. Dalam teksnya, al-Quran menyatakan dengan
tegas bahwa lelaki muslim boleh menikahi perempuan Ahl al-Kitab (nonMuslim).
Meski masih menyisakan perdebatan hingga sekarang, mengenai siapa saja
yang bisa disebut Ahl al-Kitab, banyak pendapat dalam Islam yang menyatakan
bahwa Ahl al-Kitab dapat dilekatkan kepada setiap agama, yang mempunyai kitab
suci, yang mempunyai tuntunan jelas untuk kehidupan umatnya, tidak hanya
untuk Yahudi dan Nashrani, atau lebih sempit lagi hanya untuk Ahl al-Kitab pada
jaman Nabi.
Teks kitab suci Katolik tidak ada yang menyatakan secara eksplisit
mengenai bolehnya pernikahan beda agama yang melibatkan umat katolik.
Kemungkinan untuk itu baru ada ketika membaca hukum kanon gereja, itupun
pasangan yang hendak melakukan pernikahan beda agama terlebih dahulu
diharuskan memenuhi persyaratan yang tidak ringan sebagaimana tercantum
dalam kanon 1125 dan 1126.
Persyaratan-persyaratan tersebut, menurut penulis, pertanda bahwa Katolik
masih memperlihatkan keengganan untuk mengabsahkan pernikahan beda agama.
Dengan persyaratan tersebut, Katolik sebenarnya secara tidak langsung mencegah
terjadinya pernikahan beda agama atau minimal mencegah menurunnya tingkat
keimanan generasi penerusnya. Lebih jauh, dengan disyaratkannya pernikahan
beda agama, Katolik mengharapkan agar tidak kehilangan penganut. Hal itu
terbukti dengan adanya persyaratan bagi pasangan Katolik untuk menjamin
pendidikan anaknya berjalan sesuai dengan iman Kristiani. Untuk kasus ini, Islam
sebenarnya memiliki ketakutan yang tidak jauh berbeda.
Karena pada faktanya pernikahan beda agama masih sangat sulit untuk
dilangsungkan, ditambah sikap gereja dan Kantor Urusan Agama (dalam Islam)
yang masih berbeda-beda dalam menyikapi pernikahan beda agama, maka
pernikahan beda agama bisa dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Dalam Katolik,
pemberkatan dapat dilangsungkan oleh gereja sesuai dengan peraturan yang
berlaku dalam gereja yang bersangkutan. Dalam Islam upacara akad nikah, tidak
harus terlebih dahulu dibacakan dua kalimat syahadat, sebagaimana umumnya
pada pernikahan sesama muslim. Sayangnya, masih banyak pejabat gereja
maupun pejabat KUA yang masih awam dengan penafsiran tokoh-tokoh agama
yang secara substantif tidak mensyaratkan kesamaan agama sepasang laki-laki dan
perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Maka pernikahan beda
agama, di Indonesia hingga sekarang, masih menjadi sesuatu yang amat sulit
untuk dilakukan. Tak heran kalau kemudian banyak pasangan beda agama yang
hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan menjadi gagal, dan kalaupun tetap
kukuh dengan keinginannya untuk menikah melakukan pernikahannya di luar
negeri.
2. Keterkaitan
Pemahaman
Keagamaan
terhadap
Fenomena
Pernikahan Beda Agama dan Hubungan Anta-agama di Indonesia
Penafsiran belakangan yang banyak bermunculan, baik di Islam maupun
Katolik, menerbitkan secercah harapan untuk pasangan berbeda agama agar dapat
membangun hubungan keluarga dalam ikatan pernikahan. Penafsiran demikian tak
lain merupakan refleksi berkepanjangan atas fakta pluralitas kehidupan
masyarakat Indonesia yang multi agama, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya.
Fakta inilah yang menjadikan pernikahan beda agama tak mungkin lagi untuk
dihindari.
Lebih dari itu, kini, banyak kasus pasangan yang menikah meski masingmasing pasangan memiliki atau menganut agama yang berbeda dapat membangun
sebuah keluarga yang sejahtera, atau dalam bahasa Islam sakinah, mawaddah,
warahmah. Keluarga dari pasangan pernikahan beda agama menjadi keluarga
yang memiliki kadar toleransi sangat besar. Sikap demikian yang sebenarnya
sangat konstrukstif untuk memelihara fakta pluralitas yang ada di Indonesia.
Pluralitas tidak bisa disikapi dengan eksklusifitas, melainkan saling menghormati
dan toleransi. Akan sia-sia upaya memajukan dialog antar agama kalau umat
masing-masing agama tetap merasa eksklusif dengan umat dari agama lainnya.
Dari fakta-fakta di atas, ditambah dengan keyakinan penulis bahwa
perbedaan agama, bangsa dan keturunan tidak bisa menjadi penghalang terhadap
perkawinan, maka, menurut penulis, pernikahan beda agama sudah tidak bisa lagi
dilarang. Pernikahan beda agama seharusnya disikapi secara lebih bijak oleh
masing-masing tokoh agama. Agama adalah keyakinan dalam hati dan tidak
mungkin dapat digoyahkan begitu saja, seperti oleh cinta atau ikatan pernikahan.
Tidak boleh ada lagi ketakutan konversi agama dan sebagainya yang semakin
mengarah pada sikap eksklusif dalam menyikapi dan memahami agama.
Pemahaman agama yang demikian akan berkontribusi positif tidak hanya
untuk pernikahan beda agama melainkan untuk hubungan antar-agama secara
lebih luas. Agama adalah jalan masing-masing individu untuk memperoleh
keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pernikahan adalah usaha
pasangan laki-laki dan perempuan untuk membina sebuah rumah tangga yang
bahagia dan sejahtera. Kebahagian rumah tangga, tidak ditentukan secara absolut
oleh kesamaan iman atau agama, melainkan komitmen masing-masing pasangan
untuk membangun keberlangsungan, keutuhan, dan keharmonisan rumah tangga.
B. Saran
Dalam tulisan ini penulis menyarankan:
1. Tulisan ini tidak begitu sempurna sebagai kajian pernikahan beda
agama, karenanya, bagi yang mau mendalami fenomena ini,
disarankan untuk mengakses sumber-sumber lain yang qualified baik
dari Islam maupun Katolik, bahkan dari agama-agama lain, terlebih
karena tulisan ini hanya berpretensi untuk membahas pendapat Islam
dan Katolik.
2. Pembacaan teks-teks keagamaan harus dilakukan secara berimbang,
agar tidak terjadi sikap apriori terhadap salah satu agama.
3. Perlunya diciptakan budaya penafsiran teks-teks keagamaan yang
konstruktif, berbudaya pluralis dan kontekstual, sehingga tidak sempit
dalam memahami agama, tidak ada lagi eksklusivitas suatu agama
terhadap agama lain..
4. Perlu adanya payung hukum yang definitif tentang pernikahan beda
agama. Sehingga yang hendak melakukannya tetap bisa merasa tenang
dan tidak terkucilkan sebagai warga Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Muhammad, dan Rasyid Ridha. Tafsir al-Manar. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Tt.
Abdullah, M. Amin. “Etika dan Dialog Antar Agama: Perspektif Islam”. Ulumul
Qur’an. No. 4. IV. 1993.
Aini, Nuryamin. “Fakta Empiris Nikah Beda Agama.” wawancara diakses tanggal
22 Juni 2003, dari http://www.islamlib.com.
Ali, Maulana Muhammad. Qur’an Suci: Teks Arab Terjemah dan Tafsir. Jakarta:
Darul Kutub al-Islamiyah. 1993.
Ali, Muhammad Daud, Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda
Agama Ditinjau dari Sudut Agama dan Perundang-undangan Perkawinan
Indonesia, Jakarta: Mimbar Hukum, 1993.
Ali, Muhammad. “Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia.” Studia Islamika:
vol 9. no. 3. 2002.
Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama Republik Imdomesia
(Depag RI), 2004.
Amal, Taufik Adnan. Tafsir Kontekstual al-Qur’an: Sebuah kerangka konseptual.
Bandung: Mizan. 1992.
Antonius Dwi Joko, Pr, “Kawin Campur” http://yesaya.indocell.net/id1066.htm
tanggal akses 29 Desember 2007.
Baso, Ahmad, dan Ahmad Nurchaliolish (Ed.). Pernikahan Beda Agama,;
Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan. Jakarta:
Komnas HAM dan ICRP. 2005.
Eoh, Sh, MS., O.S. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktik. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
Galib, Muhammad. M. Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya. Jakarta:
Paramadina. 1998.
Gatra. “Pernikahan Mei Menuai Kontroversi”. 21 Juni 2003.
Gautama, Sudargo. Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran.
Bandung:Citra Aditya Bakti. 1996.
Handrianto, Budi. Perkawinan Beda Agama Dalam Syari’at Islam. Jakarta:
Khairul Bayan. 2003.
Harahap, Muhammad Yahya. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan
Undang-Undang No. I Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975, (Medan: CV. Zahir Trading Co Medan).
Hindasyah, Linda. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Pelaku. Jakarta:
PPIM UIN Jakarta, 2003.
Ichtiyanto. Perkawinan Campuran dalam Negara Republk Indonesia, Jakarta:
Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI,
2003.
Jabari, Al, Abdul Mutaal M. Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam.
Jakarta: Bulan Bintang. 1988.
Kamal, Zainun, dan Musdah Mulia. Makalah: Penafsiran Baru Islam Atas
Pernikahan Beda Agama. Oktober 2003.
Kamal, Zainun. “Fakta Empiris Nikah Beda Agama”. www.islamlib.com. Tanggal
akses 29 desember 2007.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII
/MPR/1998.
Kitab Kejadian.
Kitab Kanon
Madjid, Nurcholis, dkk. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat InklusifPluralis. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The
Asia Fondation. 2003.
Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia. Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia. 1995.
Mudzhar, Mohammad Atho. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi
tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1979-1988. Jakarta: INIS.
1993.
Muhdlor, A. Zuhdi. Memahami Hukum perkawinan, Nikah, Talak, Cerai, Rujuk.
Bandung: Al-Bayan. 1994.
Sriyanto, David. Perkawinan Orang yang Berbeda Agama. Jakarta: Sekolah
Tinggi Teologi Jakarta. Thesis. 1992.
Suryabroto, Sumardi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998.
Shihab, M. Quraisy. Wawasan al Quran. Bandung: Mizan. 1996.
Tabloid Dialog Jum’at Republika. “Ada Motif di Balik Pelaminan”. 15 Agustus
2003.
Tabloid Dialog Jum’at Republika. “Galeri Pendapat: Pro-Kontra Nikah Beda
Agama di Kalangan Ulama”. 12 September 2003.
Tafsir Kitab Kejadian 5: 1 – 12-3. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1987.
Thabari, al, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil alQur’an. Beirut: Dar al-Fikr. 2001.
Trisna, Yonathan A. Berpacaran dan Memilih Teman Hidup. Bandung: Kalam
Hidup Pusat. 1987.
Ulfa, Maria, dan Martin Lukito Sinaga (ed.) Tafsir Ulang Perkawinan Lintas
Agama, Perspektif Perempuan dan Pluralisme, Jakarta: Kapal Perempuan,
2004.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara
1974/1. TLN NO. 3019.
Usman, Suparman. Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum
Perkawinan di Indonesia, Serang: Percetakan Saudara, 1995.