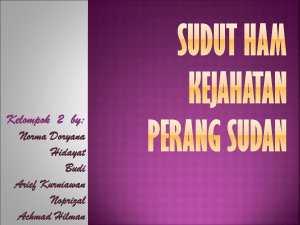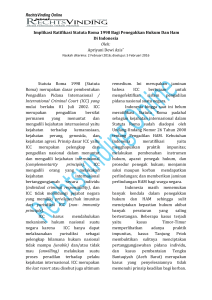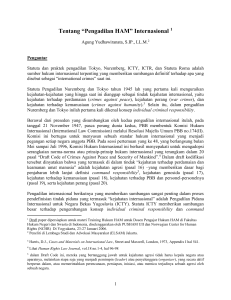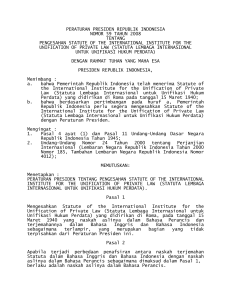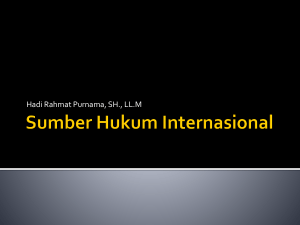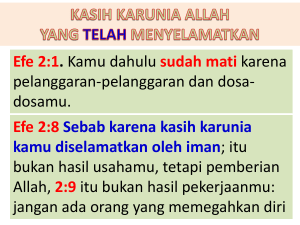pelanggaran ham berat dan hukumanny a menurut statuta roma
advertisement
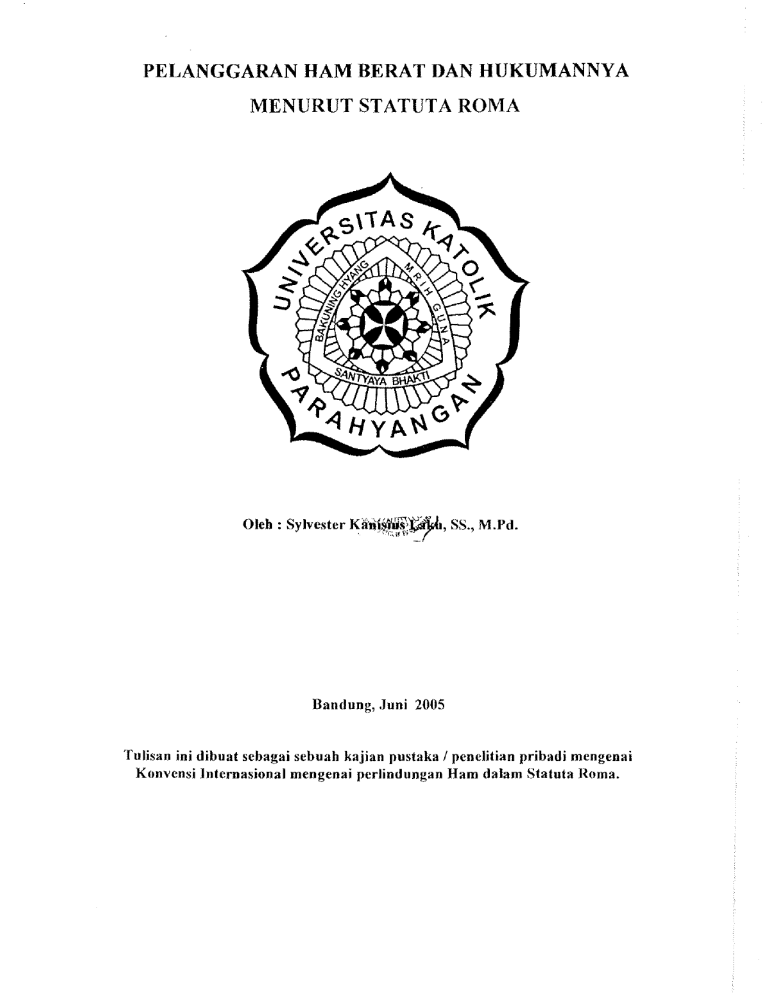
PELANGGARAN HAM BERAT DAN HUKUMANNY A
MENURUT STATUTA ROMA
Oleh : Sylvester K:tn~~~, SS., M.Pd.
Bandnng, .Juni 2005
Tulisan ini dibuat sebagai scbuah kajian pustaka / penclitian pribadi mengenai
Konvensi Internasional mengenai pcrlindungan Ham dalam Statuta Roma.
PELANGGARAN HAM BERAT DAN
MENURUT STATUTA
HUKUMANNI..¥~
.....
, \~A$JI~
ROMA<I'~\.\
Oleh : Sylvester Kanisius Laku, SS., M.Pd.
"f
i
.. >'1'
_:,!;-.'i$
1. PENDAHULlJAN
1.1. Latar Belakang
Sudah tidak asing Jagi bagi kita mendengar berita tentang kasus pelanggaran Hak
Asasi Manusia (HAM), entah ringan entah beraL Perhatian manusia terhadap realitas
penegakan kemanusiaan secara gJobal semakin gencar justru ketika hak-hak kemanusiaan
secara sengaja diabaikan atall
bahkan disisihkan dengan aJasan politik, sosial, mallplln
ekonomi. Bahkan di negara-negara, seperti Asia pada umumnya, yang menoJak konsep Hak
Asasi Munusiu kurcnu diunggup scbugui produk Bamt dan bahwa konscp HAM hanya
rasional berlaku secara reJatif sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan lokal mulai menaruh
perhatiannya yang amat besar terhadap realitas hak asasi manusia ini (Geom·ey Robertson
QC, 2000 • xvi)
Harus kita akui bahwa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia tidak dapat
dibenarkan dengan alasan apa pun. Hal ini terutama karena hak-hak asasi tersebut
merupakan hak dasar manusia yang dibawanya sejak lahir dan bahkan secara teologis
ditafsirkan bahwa hak-hak asasi tersebut secara kodrati merupakan anugcrah Tlihan (F.
Magnis Suseno, 2000 14-21). Maka dapat dikatakan bahwa, hormat terhadap bak-hak asasi
manusla, yang menentukan martabat seseorang sebagai manusia, berarti juga hormat
terbadap Allah sang pencipta-Nya.
Dengan dell1ikian dari
sudut pandang teoJogi,
pelanggaran terhadap kemanllsiaan berarti juga peJanggaran terhadap niJai hormat dan taat
pada TlIhan sebagai sang Pencipta hidllp manusia.
Dewasa ini telah banyak refleksi tentang kell1anusaian dituangkan secara konseptual
dalam beragam teori, baik t1losotls maupun teologis, dan dirumuskan dalam bcrbagai
kesepakatan dan kovcnan internasional Il1cngcnai perlindungan tcrhadap hak azasi ll1anllsia
sebagai sesuatu yang sangat pcrll! dan ll1endesak. Tapi sayangnya, sebagaimana terekam
daJall1 tulisan Geoffrcy Robertson (2000
xix), bahwa ll1asih banyak ncgara yang belull1
melakllkan ratifikasi terhadap konvensi internasional tentang kemanusiaan tersebllt dan
bahkan ada yang ll1enoJak untuk ikllt Il1cndandatanganinya seperti Amerika serikat, Cina,
maupun Lybia
Pelanggaran HAM berat tentu akan dikategorikan sebagai kejahatan dan sebuah
tindakan yang biadab bagi mereka yang punya hati nurani karena tindakan-tindakan tersebut
meniadakan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam diri manusia sehingga ia layak
disebut manusia dan mengabaikan harkat dan martabat manusia yang ada secara kodrati
dalam diri manusai sejak ia lahir. Pelanggaran HAM bera! tentu tidak dapat ditoleransi olch
siapapunjuga dan bangsa manapun juga. Konsep HAM tidak dapat lagi dilihat secara relatif
partikular, tetapi mempakan sebuah horizon yang diperluas yang dapat mencakup aspekaspek kemanusaian secara fundamental dan universal. Kefundamentalannya itulah yang
menjadikan manusia sebagai menusia perlu dilindungi secara legal-formal, baik melalui
hukum maupun Undang-Undang, nasional maupun Internasional.
Kejahatan terhadap kemanusiaan selalu mengundang kutuk dan amarah bagi mcreka
yang merasa bahwa nilai-nilai kemanusaiaan hams dihormati dan dilindungi, tetapi tidak
sedikit mereka yang mengutuk dan marah itu justm menjadi biang dari segala perlakuan keji
terhadap kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa secara teoretis-konseptual semua manusia
mengakui bahwa hak-hak dasar kemanusiaan hams dilindungi dan dijaga, tetapi secara
praksis-kontekstual kerap kali rnanusia lebih dibimbing oleh ego dan keserakahannya
sehingga membutakan tidak saja mata lahir, tetapi juga mat a hati, yang sehumsnya menjadi
penuntun dan panduan segal a tindakan dan prilaku manusia. Sejak pengadilan Nuremberg'
pelanggaran terhadap HAM disebut kejahatan terhadap Kemanusiaan
Tulisan ini hendak mengangkat dan mengkaji persoalan pelanggaran HAM berat
yang dilakukan temtama oleh para pejabat, baik sipil maupun militer, terhadap warga sipil
dalam sebuah negara atau terhadap sebuah ncgara oleh negara lain sebagaimana yang
dimaksudkan dalam Statuta Roma sebagai sebuah konvensi internasional mcngenai
pembentukan Mahkamah Pidana internasional yang berwcnang mengadili para pclaku
kejahatan
pelanggaran HAM,
sebagai
sebuah upaya global perlindungan terhadap
kemanusiaan dalam segala aspek hidupnya yang paling dasariah. ini menunjukkan sliatu
I
JcJTrey Robertson QC dalmn bukunya Kcjahatan Tcrhadap Kcmanllsiaaan, 2000, him. Xiv menjeiaskan
bahwll Pcngadilan Nuremberg adalah scbuah pcngadilan intcmasional y<l1lg dibcntuk sccara kondisional untuk
mcngadili dan mcnjatuhkan hukuman bagi para tokok Nazi atas kebiadaban mcrcka tcrhadap bangsa Yahudi.
Untuk pcrt<lm<l kalinya cia lam pcngadilan Nuremberg terscbut pelanggaran tcrhadap kcmanusiaan dikatcgorikan
scbagai bcntnk kcjahalan tcrhadap kcmanusiaan (crims against humani~"Y'). Tuduhan kejahatan tcrhadap
kcmanusian eli sini bcrbcda dcng<)fl kcjahatan pcrang yang di1akukan olch ncgara-ncgara poros non-sckutu dan
para tawanan pen-mg. Logjka dan k~jahatan tcrhadap kcmanusian yang clidcfinisikan dalam pasal 6 (c) Piagam
Nuremberg adalah alat negara yang mengesahkan siksaan atau pembuI1uhan massal (genocide) alas rak~:al
mereka sendiri, yang hams dipcrt~lI1ggungjawabkan secara krimjnal dalam hukum intcrnasional dan clapa{
clikcnakan hukuman olch pcngadilan manapun y:mg clapat menangkap mercka.
2
kemajuan yang sangat pesat di bidang perlindungan terhadap HAM di saat dimana harapan
akan masa depan manusia yang baik dan terhormat semakin diragukan.
Deflnisi tentang pelanggaran berat HAM mengikuti definisi yang dikemukakan
dalam Statuta Roma ini dapat dipahami bahwa kategori sebuah kejahatan dipandang sebagai
kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran berat HAM bila tindakan
kejahatan itu melibatkan sekelompok orang tertentu, yang atas perintah atasan, pimpinan,
komandan, atau orang tertentu berupaya secara sistematis untuk melenyapkan sekelompok
manusia lainnya terutama karena alasan politik.
Karenanya, dalam tulisan ini fokus permasalahan yang akan kami kemukakan dan
menjadi dasar pijakan pembahasan dan anal isis kami berkisar di seputar permasalahan
pelanggaran terhadap HAM sebagaimana yang dimaksud dalam Stauta Roma, yaitu keempat
masalah serius yang menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan di atas.
1.2. Statuta Roma; Mahkamah Pidana Intemasional.
Tanggal 17 Juli 1998, dalam konfrensi Diplomatik Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
telah menghasilkan satu langkah penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu
disetujuinya Statuta Roma (Jerry Fowler dalam £Isam, 2000:viii) Statuta Roma, sebuah
perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal COllrt)
untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum
(impunity) Dari 148 negara peserta konfi'ensi; 120 mendukung, 7 menentang dan 21
Abstain.
Statuta Roma sebenarnya adalah sebuah dokumen yang panjang dan rinci yang terdiri
dari 128 pasa!. Statuta tersebut tidak akan berlaku efekif sampai diratifikasi oleh 60 negara
(£Isam, 2000ix). Ini jelas merupakan suatu prosedur yang panjang dan mustahil dapat
tercapai dalam beberapa tahun saja. Menurut catatan GefTrey Robertson (2000 : 399) hingga
Maret 2000, telah terkumpul 93 tanda tangan dan baru 7 negara yang meratifikasinya. Tetapi
mcnurut informasi dari sumber £Isam, hingga September 2002 telah ada negara yang
meratifikasi Statuta ROll1a dan itu tidak terll1asuk Indonesia. Amerika Serikat yang dikenal
sebagai salah 5atu negara yang menjllnjung nilai kemanllsiaan merupakan salah satu negara bersama dengan China dan Irak- yang mcnolak disahkannya statuta roma
Statuta ROll1a telah menjadi momentum penting di akhir milenium II clan mcnjadi
sebuah titik pergerakan baru terhadap upaya penegakkan Hak Aasi Manusai di awal
"
.l
milenium III yang membangkitkan kembali harapan masyarakat dunia akan pengakuan
terhadap hak-hak dasar individu sebagai manusia.
Menurut Get1fey RobcI1son (2000
400), sebetulnya gagasan untuk membentuk
sebuah Pengadilan Pidana Intemasional sudah dimulai pada tahun 1937 oleh Liga BangsaBangsa (LBB). Ketika itu dibuat konsep rancangan statuta untuk mengadili para teroris
internasionaL Setelah Konvensi Genosida tahun 1948 rancangan statuta mulai dipersiapkan
oleh Komisi Hukum Intemasional, namun proyek tersebut dibekukan ketika tetjadi perang
dingin dan banI digulirkan lagi ketika Gorbachev mengusulkan agar rancangan statuta
tersebut dijadikan sebagai Undang-Undang anti terorisme.
Pada tahun 1993 majclis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Intemasional
untuk meneruskan proyek tersebut dan mcnyelesaikan rancangan mengenai stat uta. Baru
pad a tahun 1998 kesepakatan komunitas internasionaL yang diwakilkan oleh 148 negara
yang hadir, meskipun 7 menolak dan 2 I abstain, untuk membentuk scbuah pengadilan
pidana internasional telwujud dan membuka lagi keran penghormatan, pengakuan, dan
penegakkan terhadap nlai-nilai kcmanusiaan secara universal dan mendasar.
Dalam stat uta ini juga menjelaskan beberapa hal tentang struktur mahkamah, jenis
pelanggaran, penyelidikan dan penuntutan, persidangan dan hukuman serta beberapa hal
penting lainnya. Beberapa mahkamah yang telah dibentuk untuk berbagai kasus pelanggaran
berat HAM:
I. International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY), dibentuk pada tahun 1993
2. International Criminal Tribunal for Rwanda (lCTR), dibentuk oleh Dewan Keamanan
1994.
1.3 Daftar Negara Pe-I'atifikasi Statuta Roma (sid 05 Mei 2003)
Memang sengaja kami menampilkan daftar peserta atau negara yang sudah
meratifikasi Statuta Roma sebagai suatu bentuk partisipasi internasional untuk ikut terlibat
secara aktif dengan mengikatkan diri dalam ketentuan yang berlaku dalam statuta. Indonesia
sebagai salah satu negara penandatangan statuta, yang pada waktu itu dclegasi Indonesia
dipimpin oleh Prof Muladi, S11, yang pad a waktu itu menjabat mentcri Kehakiman tidak
termasuk dalam danar terscbut. Bahkan rencana Indonesia untuk meratilikasi Statuta Roma
sampai akhir 2007 ini belum terlaksana. Itu berarti Indonesia belum menjadi negara pihak
yang secara hukum wajib mcnaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam statuta.
4
Dalam tabel di bawah ini kami sertakan negara-negara peratifikasi Statuta Roma dan
didalamnya tidak termasuk Indonesia. Tampilan ini sekedar sebagai sebuah informasi dan
sekaligus gambaran bahwa dari banyak negara peserta penandatangan Statuta masih sangat
scdikit yang mau mcngikatkan diri secara penuh dnegan ketentuan-ketentuan yang ada
dalam
statuta
tersebut
Ini
menunjukkan
bahwa
negara-negara
lainnya
masih
rnernpertirnbangkan seeal-a hati-hati segala aspek yang memungkinkan mereka menjadi
negara pihak.
Tabel I
No.
I
2
3
4
5
6
7
8
<)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nama Negara
Senegal
Trinidad and Tobago
San Marino
Italia
Fiji
Ghana
Norwcgia
Belize
Tajikistan
Iceland
Venezuela
Perancis
Belgia
Kanada
Mali
Lesotho
New Zealand
Botswana
Luxembourg
Sierra Leone
Gabon
Spanyol
Afrika Selatan
Kepulauan Marshall
erman
Austria
Finlandia
Argentina
Dominica
Andorra
'ranggal Tanda-tangan
2 Februari 1999
6 April 1999
13 Mei 1999
26 Juli 1999
29 November 1999
20 Desember 1999
16 Fcbruari 2000
5 April 2000
5 Mei 2000
25 Mei 2000
7 Juni 2000
9 Juni 2000
28 Juni 2000
7 Juli 2000
16 Agustus 2000
6 September 2000
7 September 2000
8 September 2000
8 September 2000
15 September 2000
20 September 2000
24 October 2000
27 November 2000
7 Desember 2000
11 Desember 2000
28 Desember 2000
29 Desember 2000
8 Februari 2001
12 Februari 2001
30 April 2001
5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
fcI0
41
42
43
44
45
46
47
f:\8
f:\9
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Paraguay
Kroasia
Costa Rica
Antigua & Barbuda
Denmark
Swedia
Belanda
Yugoslavia
Nigeria
I jechtenstein
Republik Afrika Tengah
Inggris
Swiss
Peru
Nauru
Polandia
Hungary
Slovenia
Benin
Estonia
POItugal
Ekuador
Mauritius
Macedonia, FYR
Cyprus
Panama
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Kamboja
Republik Demokratik Kongo
Irlandia
Yordania
Mongolia
Niger
Romania
Slovakia
Yunani
Ugall(Ja
Brazil
Namibia
Bolivia
Uruguay
Gambia
14 Mei 2001
21 Mei 2001
7 Juni 2001
18 Juni 2001
21 JlIni 200 I
28 Juni 200 I
J7 Juli 200]
6 September 200 I
27 September 2001
2 October 2001
3 October 2001
f4 October 200 I
12 October 200 I
10 November 200 I
12 November 200 I
12 November 200 I
30 November 2001
31 Desember 200 I
22 Januari 2002
30 Janllari 2002
5 Februari 2002
5 Februari 2002
5 Maret 2002
6 Maret 2002
7 Maret 2002
2 I Maret 2002
II April 2002
II April 2002
II April 2002
I I April 2002
I I April 2002
11 April 2002
II April 2002
I I April 2002
I I April 2002
] I April 2002
15 Mei 2002
14 JUlli 2002
20 Juni 2002
?5 Juni 2002
27 Juni 2002
28 Juni 2002
28 Juni 2002
6
74
75
76
77
78
79
80
81
128 Juni 2002
1 Juli 2002
1 Juli 2002
5 Agustus 2002
120 Agustus 2002
ki September 2002
16 September 2002
19 September 2002
Latvia
Australia
Honduras
Colombia
fianzania
Timor Leste
Samoa
Malawi
Sumber, Eisam, 2003.
III. Pelanggaran ham berat berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang RI No
26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
3.1 Pelanggaran HAM Berat Mellurut Statuta Roma
Ada empat jenis tindak pelallggaran serius yang menjadi perhatian internasional,
dengan indikasi dan ciri-cirinya masing-masing. Keempat jenis kejahatan tersebut adaJah
I. Kejahatan Genosida (Genocide)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)
3. Kejahatan Perang (War crimes)
4. Kejahatan Agresi (Aggression)
Kami akan membahasnya satu-persatu di bawah i ni
3.1.1 Gellosida (Genocide).
Genosida adaJah
kejahatan
yang
paling
pertama
menarik
pcrhatian
dunia
internasional, yaitu dengan dibentuknya Konvensi Genosida pada tahun 1948 sebagai
implikasi dari pengadilan Nuremberg yang mengadili para pemimpin Nazi yang menyerang
secara sistematis kelompok masyarakat Yahudi (Geoftfey Robertson, 2000281). Pasal I
konvensi tersebut menyatakan bahwa genosida yang di lakukan pada masa damai alau perang
adaJah kejahatan yang dilakukan dibawah hukum internasionaL
Definisi genosida menuru( konvensi ini , lanju( Geoffrey (2000 : 281-282), adalah
suall! tindakan dengan kehendak menghancurkan sebagian atau keseluruhan kelompok
nasional, etnis, ras, at au agama, atas salah satu clari lima tindakan berikut ini, yaitu:
(a) membunuh anggota kclompok;
(b) menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius lerhadap anggota kelompok;
7
(e) Seeara sengaja dan tereneana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehaneuran
fisik seeara kesclurllhan atall sebagian;
(d) Memaksakan langkah-langkah yang ditujllkan untuk mcncegah kelahiran di dalam
kelompok tersebut
(e) Dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain
Definisi ini menccrminkan pemikiran kontemporer dengan kebijakan genosida Nazi
terhadap kaum Yahlldi sebagaimana terungkap dalam pengadilan Nuremberg Definisi ini
menu rut Geot1i'cy (2000
282) cllkup luas untuk melingkupi pcmbersihan ctnis dan
pcmbersihan massal agama,
Pada pasal 6 Statuta Roma genosida didefinisikan dengan istilah yang sama yang
dipakai pada Konvensi Gcnosida tahun 1948, Unsur penting yang harus dibuktikan adalah
adanya 'tujuan untuk menghancurkan baik sebagian meupun seluruhnya dari suatu negara,
kelompok etnis, kelompok ras atau agama, atau kelompok semacamnya (Elsam, 2000 • 5)
Selain melalui pembunuhan alau penyiksaan, aksi penghancuran yang dilakukan
yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM adalah upaya untuk membuat
penderitaan hidup yang berakhir dcngan kematian dan 'secm'a paksa' mcmindahkan anakanak dari datu kelompom ke kelompok lainnya. Kelompok yang dimaksudkan menurut
Geoffrey (2000 A I 0) tidak termasllk dalam pengelompokan sosial at au politik. Karenanya,
ia mencontohkan dalam kasus lendral Videla, yang secar keji mcmerintahkan untuk
menculik bayi-bayi dari ibu-ibu anggota sayap kiri di Argentinadan menyerahkan mcreka
kepada anggota tcntara yang setia, tidak dapat didakwa atas genosida. Pcnckanannya
terutama pada tujuan dari pcnghancuran tersebut adalah untuk meusnahkan umat manusia
berdasarkan ras mereka alau perbedaan mendasar yang terdapat dalam kelompok tersebllt.
3.1.2 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Againts Humanity)
Istilah kejahatan terhadap kemanusian (Crime Againls HIJmaniZv) peJ1ama kali
digunakan dalam Piagam Nuremberg. Piagam ini merllpakan pCljanjian multilateral antara
Amerika Serikat dan sekutunya setelah Perang Dlinia II berakhir. Mereka (Amcrika Serikat
dan sekutunya) menilai bahwa para pelaku (NAZI) dianggap bCJ1anggung jawab terhadap
kejahatan terhadap kemanllsiaan pada rnasa tersebut.
Detinisi Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 7 ayat I statuta roma berisi
definisi tentang kejahatan tcrhadap kemanusiaan, Aksinya scndiri sebagaian besar adalah
8
kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar dan tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan,
penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan,
dan pengasingan lndikasi ataupun ciri-ciri dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini adalab
bahwa kejahatan itu dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan
sistematis, yang melibatkan banyak pihak, dan ditujukan kepada setiap penduduk dengan
mengikuti dorongan kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan semacam
itu.
Penekanannya adalah pad a kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan
mengikuti kebijakan yang disusun, baik oleh aparat negara (seperti kepolisian atau tentara)
maupun oleh suatu entitas organisasi, dan bukan pada kejahatan yang terjadi secara spontan
yang merupakan sebuah kriminal biasa.
Pasal 7 ayat I Statuta Roma dan pasal 9 UlJ No. 26 Pengadilan HAM th. 2000
terdapat sedikit perbedaan tetapi secara umum memuat prinsip bahwa kejahatan terhadap
kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas at au sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara
langsung terhadap penduduk sipil, berupa
a.
Pembunuhan;
b.
Pemusnahan;
c.
Perbudakan;
d.
Pengusiran at au pemindahan penduduk secara paksa;
e.
Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f
g.
Penyiksaan;
Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain
yang
h.
r
setara;
Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu at au perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut
hukum internasional;
J.
Penghilangan orang secant paksa; atau
9
k.
Kejahatan apartheid.
Pelaku kejahatan terhadap kcmanusiaan bisa jadi aparat / instansi ncgara, atau pclaku non
negara.
Detinisi kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia masih menimbulkan beberapa
perbedaaan. Salah satunya adalah kata serangan yang meluas atau sistematik. Sampai saat ini
istilah tersebut masih mcnimbulkan banyak perbedaan pandangan bahkan kekaburan.
Pengertian sistematik (systematic) dan meluas (wide.lf)read) menurut M. Cherif Bassiouni
dalam bukunya yang berjudul Crime AgainlS Humanity
Oil
International Crimillal loCTW;
sistematik mensyaratkan adanya kebijakan atau tindakan negara untuk aparat negara dan
kebijakan organisasi untuk pelaku diluar negara. Sedangkan istilah meluas juga merujuk
pad a sistematik, hal ini untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tetapi korban atau
targetnya acak. Karban dimana memiliki kateristik tertentu misalnya agama, ideologi,
politik, ras, etnis, atau gender.
Yang memisahkan kejahatan terhadap kemanusiaan, batik dalam kelicikannya atau
dalam kebutuhannya akan peraturan-peraturan khusus tentang penolakan terhadapnya adalah
suatu fakta yang sederhana, yaitu bahwa kcjahatn itu merupakan suatu aksi brutal yang
nyata-nyata dilakukan oleh pemerintah atau setidak-tidaknya oleh orgamsasI
yang
melaksanakan atau mcmaksakan kekuasaan politiknya. Yang menjadikan kejahatan itu
sangat mengerikan dan menempatkan kejahatan ini dalam dimensi yang berbeda dari
kejaghatan biasa adalah bukan apa yang ada dalam pikiran si pelaku penyiksaan, meJainkan
kenyataan bahwa individu yang melakukan tindakan kejahatan tersebut merupakan 'bagian
dari aparat ncgara' (Geot1i-ey Roberson, 2000 • 416).
3.1.3 Apartheid
Apartheid adalah sebuah sistem pemisahan berdasarkan ras, agama dan kepercayaan,
diskriminasi etnis dan pemisahan kelas sosial, dimana kelompok mayoritas mcndominasi
kelompok minoritas. Karakteristik yang muncul ada lab pemisahan secara fisik serta wilayah
setiap ras, kemudian diskriminasi terhadap distribusi servis dan jasa publik. Apartheid
mcmaksakan sebuah praktek yang mirip dcngan pcrbudakan dalarn bcrbagai bagian
kebidupan berdasarkan karakteristik berbeda, seperti ras. Apartbeid adalab pelanggaran
terbadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan lnternasional.
10
3.1.4 Kejahatan Perang
Pasal 8 Statuta Roma mcmiliki dcfinisi yang panjang tcntang kejahatan perang, yaitu
bahwa scbuah kejahatan dikatcgorikan sebagai kcjahatan perang apabila 'dilakukan sebagai
bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut.
Geoffrey Robertson (2000 • 416) membagi pasal 8 Statuta Roma ini menjadi empat
kategori, yaitu
1). Kategori pertama rasal 8 (2)(a) yang melipllti semua pelanggaran berat terhadap
Konvensi Gcnewa 2 1949
2). Kategori kedlla, yaitu pasal 8 (2) (b) yang meliputi pelanggaran yang berat terhadap
hllkulll dalam kerangka hukum internasional. Kategori ini saat ini Illeliputi juga serangfan
at as pasukan perdamaian atau mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan di bawah
naungan PBB (sub-paragraf ii), serangan yang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui
bahwa serangan itu Illenimbulkan kematian atau cidera terhadap penduduk sipil, atau
mengakibatkan kerusakan sangat berat dan berjangka waktu lama terhadap lingkungan
nasional yang secara tegas melampaui batas dan kaitan dengan tujuan militer manapun (subparagraf iv), serangan secara sengaja terhadap target non-mil iter seperti, tClllpat ibadah,
sekolah, museum, rUlllah sakit, dan tempat-tempat bersejarah, atau yang memiliki nilai
keblldayaan (sub-paragraf ix), dan penggunaan gas-gas beracun untuk memllsnahkan
sekelolllpok orang (sub-paragrafxviii)
Kejahatan baru yang masllk dalam kategori kejahatan perang adalah menggunakan warga
sipil at au orang-orang yang dilindungi untuk Illcmbuat sualu wilayah militer at au atau
pasukan Illiliter kebal dari operasi mililer (sub-paragraf xxiii) dan pelibatan anak-anak di
bawah umur 15 tahun ke dalalll angkatan bersenjata atau menggunakan Illcreka untuk ikut
secara aktif dalalll pertelllpuran (sub-paragraf xxvi)
3). Kategori ketiga adalah pasal 8 (2)(c) berkaitan dengan seluuh pelanggaran serius
Konvcnsi Gellewa, 1949, pasal 3, yaitu yang mcliputi serangan tidak manusiawi tcrhadap
Konvcnsi Gcncwa, sebagaimana dicatat olch Geoffrey Robertson, 2000, hIm. 218, diadakan pada tahun 1949
scbngai suatu llpaya UI1tuk JllcnlInusk~l11 hukulll humanitcr yang dapat bcrlaku sccara intcrnasiomll. Ada cmpat
asas pCIlting yang ditctapkan dalam konvcnsi ini mcngcnai hubungan dan pcrlakulln tcrhadap individu, yaitu (1)
Pcrlakuan tcrhadar orang sakit dan tcrluka akibat pcrtempuran darat (II) Pcri<lkuan Icrhadap orang sakit dan
tcrluka akibat pcrtcmpuran laut, (III) PcrIakuan tcrhadap tawanan pcrang, dan (IV) Pcrlaku;m tcrhadap warga
sipil yang mcnjadi tawanan perang. Konvcnsi ini mc\vajibkan scmua ncgara pcnancia tangan untuk patuh,
I11cskipun Jl1usuhnya tidak atau bchlln mcnandatangi kanvensi. Jadi tidak ;:lda ncgara yang balch mclanggar
konvensi karcna aJasan pcrtahanan nasjonal, misalnya.
I1
warga sipil atau orang yang sedang sakit atau prajurit yang sudah menyerah (termasuk
mengadili mereka secara tidak adil).
4). Kategori kecmpat adalah pasal 8 (2)(e) yang menambahkan sejumlah 12 kejahatan
perang yang terdapat dalam pasal
8(2)(b) sebagai
pendorong munculnya kontlik
internasional. Keduabelas kejahatan tersebut mencerminkan hukum kebiasaan internasional
yang telah berkembang dari konflik internal, yang secat'a spesifik didetinisikan sebagai .
konflik bersenjata yang berlangsung dalam wilayah sebuah negara dimana konflik bersenjala
tersebut terjadi secara berkepanjangan antara otoritas pcmerintah dengan kelompok
bersenjata yang terorganisir, atau antara kelompok tersebut.
Kejahatan agresi belum dimmuskan secara eksplisit dalam statuta karena bclum ada
kcscpakatan soal definisi mengenai kejahatan agresi tersebut. Kejahatn agresi bam akan
dibicarakan lagi pada saat dilakukan peninjauan kembali terhadap statuta setelah tujuh tahun
masa berlakunya (pasal 123 (l )), yaitu menjelang akhir tahun 2010. Pada saat itu l1lahkamah
akan melakukan upaya amandemen terhadaop statuta, termasuk di dalal1lnya l1lendefinisikan
kejahatan agresi dan menetapkan kondisi-kondisi dimana mahkamah menjalankan jurisdiksi
berkenaan dengan kejahatan agresi tesebut (pasal 5 ayat 2).
3.2 I'elanggaran HAM berat menurul UU RI No. 26 tahun 2000 ten tang Pengadilan
HAM.
Dalam UU RI No. 26 tahun 2000 tcntang pcmbentukan pengadilan HAM di
Indonesiia, yaitu pad a pasal 7, menyebutkan bahwa kejahatan terhadap HAM yang bera! ada
dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Memang definisi tentang
kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusian ini mengikuti definsi yang
dikemukakan dalam Statuta Roma pasal 6 dan 7. Pembentukan UlJ ini menunjukkan slIatu
keserillsan pemerintah untuk melakukan ratifikasi Statuta ke dalam berbagai produk, baik
Undang-Undang maupun Peraturan
Pcmcrintah, scbagai suatu bentuk partisipasi global
dalam perlindungan dan penegakkan HAM.
3.2.1 Kejahatan Gcnosida
j"j!
12
; . '..' ; .
,
,
{Pill., \ I i
.I
, ,
I: Ii
~;
.: ) i ,
t i ::
'·,:iL'
J3
IV. Penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konseptnal
Ada tiga dokumen penting yang harus dipertimbangkan dalam menyelesaikan kasus
pelanggaran berat Ham, yaitu tentang pengadilan pidana internasional (International
Criminal Court), pembuktian (Rules of Evidence), dan unsur-unsur kejahatan (Elements of
Crime) agar tidak terdapat kekeliruan dalam penyelesaian kasus pelnggara barat HAM
tersebut.
4.1 Penyelesaian Berdasarkan Statuta Roma
Berdasarkan Statuta Roma dalam peradilan kasus pelanggaran HAM berlaku asas
non-retroaktif. Tetapi banyak kalangan berpendapat bahwa bila tidak diberlakukan asas
retroaktif, banyak pelaku kejahatan berat dimasa lalu yang tidak tersentuh oleh hukum.
Untuk
penyelesaian
kasus
pelanggaran
berat
HAM
jaksa
penuntut
harus
membuktikan bahwa aksi kejahatan dilakukan dengan mens rea, yaitu dilakukan secara
sengaja dan telah diketahui konsekuensinya (Geotlrey Robertson, 2000
420) Terdakwa
akan belianggung jawab atas kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau dengan
tujuan yang sam a , untuk tindakan membantu atau memerintahkan kejahatan, melakukan
kejahatan, dan berusaha melakukan kejahatan dengan mengambil langkah-Iangkah penting
untuk menyelesaikannya Statuta ini diberlakukan bagi kepala negara, wakil-wakil yang
terpilih, dan mereka yang telah melakukan aksi dalam kapasitas resmi, sebagai orang
memegang jabatan dalam sebuah organisasi resmi ataqu pemerintahan Prinsip ini sekaligus
meruntuhkan atau menghapus implll1itas yang kerap melekat pada mereka yang punya
kekuasaan.
Pad a pasal 64 (2) Statuta memberikan mandat kepada pengadilan untuk agar berjalan
dengan adil dan penuh penghargaan terhadap hak-hak terdakwa. Salah satunya menurut
pasal 67(c) harusnya diadili 'tanpa penundaan'. Apabila penundaan itu tidak sab dan
merugikan, selia disebabkan oleh ketudakmampuan jaksa penuntllt atau faktor-faktor lain
diluar kekuasaan terdakwa, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh pengadilan
untllk mel11enuhi prinsip tersebllt adalab membatalkan tuntutan dan membebaskan terdakwa.
Pasal 66 Statuta mengabadikan prinsip praduga tak bersalah dan menempatkan
bebannya pada jaksa penuntut untuk membuktikan kesalahan dengan alasan-alasan yang
meyakinkan. Pasal 67(i) menyarankan bahwa bukti-bukti dan bantahan tidak dapa!
dibebankan kepada terdakwa. Masalah beban dan standar bukti akan menjadi faktor yang
14
sangat penting dlam persidangan di pengadilan. Pada prakteknya pada saat tuntutan telah
membuktikan tanpa keraguan adanya tindakan kejahatan pelanggaran terhadap HAM yang
berat, tugas yang berat yang membuat pcmbuktian yang tidak bersalah, seperti adanya
paksaan atau kieadaan tidak sadar at au kesalahan, akan berpindah pada terdakwa.
4,2 Hukumall
Pasal 70 Statuta memberikan kekuatan khusus kepada pengadilan untuk menghukum,
dengan hukuman penjara sampai 5 tahun, para saksi dan tertuduh yang dengan sengaja
bersumpah palsu at au memasukkan dokumen-dokumen dalam presentasi pembuktian.
Kejahatan yang paling berat akan mendapatkan hukuman yang paling berat. Pasal 77
statuta menyatakan bahwa hllkllman bagi pelanggaran terburuk adalah hukuman penjara
seumur hid up. Dalam kasus lain mampunyai masa hukuman sampai 30 tahun, dan hukuman
yang dibebankan secara berturut-turut lIntuk sejllmlah kejahatan tidak boleh melebihi batas
maksimllm tersebut.
Dalam pasal 77(2)(b) disebutkan bahwa selain huklll1lan penjara, terdakwa yang
terbukti melakllkan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan bi lamana perlu sesuai dengan
keputllsan pengadilan, harus melakukan penebllsan hasil, kekayaan dan aset yang berasal
lagsung atau tidak langsung dari kejahatan itu. Hal ini lebih dijeaskan lagi dalam pasal 109
dengan menegaskan bahwa negara-negara pihak harus bekerja sama dalam pembekuan dan
penyitaan aset yang berada dalam Yllridiksi mereka
Perkembangan paling pesat adalah bahwa dalam statuta ini sunggllh sangat dihindari
dijatllhkannya hllkllman mati. Pasal-pasal dalam Statuta Roma menyediakan bllkti lebih jauh
akan upaya hukum internasional untuk menghapuskan hukuman mati (Geffrey, 2000 : 440).
Tetapi meskipun demikian, dalam penyelesaian
kasus pelanggaran HAM berat masih
banyak negara yang menerapkan hllkuman mati bagi para pelaku kejahatan Ini tenlu saja
tidak bertentangan secara hukum karena statuta menginjinkan setiap negara untuk
memberlakukan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dalam wilayah negara
tersebllt.
Dalam statuta terdapat juga pasal-pasal yang mengatur reparasi terhadap korban
kejahatan. Pasal 75 mcnyebutkan secara tegas mengenai sliatu upaya untuk memberikan
ganli rugi kepada korban, tennasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Karenanya
pengadilan harus menentukan Illasnya keruasakan atau luka yang diderita dan besarnya
15
kerugian yang dialami oleh korban dan menyatakan hal apa saja yang harus dilakukan untuk
rnengatasi semuanya itu. Perincian terhadap segala kerusakan dan kerugian korban bisa juga
dilakukan oleh seseorang yang dihukum dan apabila sesuai maka pengadilan dapat
memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dapat dilakukan melalui trust fil/ui. Hal ini
dimungkinkan apabila dana perwalian tersebut menarik minat dan perhatian para dermawan
yang kaya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban maupun keluarga korban.
4.3 Penyelesaian berdasal'kan UU RI No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa perangkat hukum sebagai
ratifikasi terhadap Statuta Roma. Ini dimulai dengan dibentuknya UU No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM, PP No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap
korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, dan PP No. 3 tahun 2002 tentang
Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Hal
ini menunjukkan ada upaya serius dari pemerintah untuk menegakkan dan menjamin HAM
di Indonesia secara khusus dan dunia secara global.
Pada pasal 36 UU No 26 Tahun 2004 tcntang Pengadilan HAM discbutkan bahwa
Pasal-pasal selanjutnya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan kepada
pelanggaran khusus seperti pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan
perbuatan kejahatan perbudakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, akan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5
(lima) lahun .
., Trust fund adalah dana pcnvalian yang dibuat olch ncganl-llcgara pih;:lk ulltuk tujuan I1lcmbcrikan ganti mgi
atau kompcnsasi kcpada korban apabila si kriminal tidak sanggup mcmbcrikan gallti mgi dalam jumlah yang
cukup bcsar. Jni scsnai dcngan isi pasal 79 Statut:l Roma.
16
Pasal 39 menvebutkan bahlVa Setiap orang yang me1akukan perbuatan pCl1lii<s;"ll1
sebagailllana dilllaksud dalam Pasal 9(f), dipidana dengan pi dana penjara paling lama 15
(lima belas) tabun dan paling singkat 5 (lima) tahun ..
Pasal 40 mengatuf bahwa setiap orang yang melakllkan perbuatan sebagaimana
dimakslId dalam Pasal 9(g, 11, at au i), yaitu
,"«li1. pt.'rh\!~!;-d";'il1
st'ksu;d
!'leLkUr;il! ~~,'(·:H:'
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 41 meneg{lsknn bahw{l Percobaal1, permufakatan jahat, atnu pemhantU(l1l untuk
lllelakukan
pelanggaran
terhadap
kejahatan
genosida
maupun
kejahatan
terhadap
kemanusiaanm akan dihukum dengan pi dana penjara minimal 5 tahun atau maksimum 30
'tahun dan bisa dikenai pi dana penjara seumur hidup sesuai dengan kejahatan yang
dilakukan.
Pasal 42 mengatur proses peradilan yang harus dilakukan kepafda komandan militer
yang terlibat atau yang menjadi pelakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanuisaan.
Ketentuan-ketentuannya
adalah
sebagai
beriku1:
(I) Komandan militer atau scseorang yang secara efektifbertindak sebagai komandan militer
dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi
Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah
komando dan pengendaliannya yang cfcktif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pi dana tersebut merupakan akibat dari tidak
dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaltu •
a), komandan militcr atau scscorang tcrscbut lllcngctahui atau at as dasar keadaan saat itu
seharusnya mcngetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kckuasaannya untuk mencegah atau menghcntikan
perbuatan tersebut alau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan pcnuntutan.
17
(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pi dana
terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang
berada eli bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang cfcktif, karena atasan tersebut tidak
melakukan
pengendalian
terhadap
bawahannya
secara
patut
dan
benar,
yakni
a). atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas
menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat; dan
b). atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup
kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan
pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan.
(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dan ayat (2) diancam dengan pidana
yang sam a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal
40.
Dalam UU No. 26 ini mengatur juga tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan
rehabilitasi terhaclap korban pelanggran HAM berat terseilut Pasal y; menyeblltKan 11,1111\<1
Ii
I ('! I;) i·'"
.
18
4.4 Pellyelesaiall Mellllrnt UU No 27 tahull 2004 telltang Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi
UU No 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disetujui
DPR untuk menjadi undang-undang, walaupun terdapat beberapa kekurangan, namun ada
hal positifnya. Di dalamnya masib terkandung rnaksud untuk mengungkapkan kebenaran di
masa lalu. Hal ini akan menerangkan hal-hal yang kabur dan bahkan gelap dalam
pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.
Beberapa kasus yang dapat ditangani dengan pembentukan Komisi Kebenaran di
antaranya kasus 1965, termasuk pulau Buru, kasus Papua sejak 1967, kasus Aceh mulai
daerah operasi militer (DOM), Talangsari, Haur Koneng Bandung, Kedung Ombo, dan kasus
27 Juli. Pengungkapan kebenaran dalam peristiwa tersebut belum pernah dilakukan oleh
pernerintah.
Pembentukan komisi ini mernberikan titik tekan yang berbeda dengan kinerja
mekanisme hukum yang terbatas. Titik tekannya ada pada korban. Penjelasan korban akan
menjadi dasar penyusunan laporan pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini berbeda dengan
mekanisme yang dijalankan Pengadilan ad hoc HAM yang beljalan selama ini.
Komisi Kebenaran yang akan terbentuk ilu terbagi menjadi tiga sub komisi, yaitu
Komisi Penyelidikan dan Klarifikasi, Komisi Rehabilitasi dan Komisi Amnesti. Kornisi ini
mempunyai kewenangan penyelidikan dari tahun 1945 sampai 2000. Panjangnya batas
waktu akan membuat kerumitan penelusuran dokumen, saksi serta korban.
Pengaturan mcngenai amnesti juga banyak rnenirnbulkan perdebatan. Dalarn UU
tersebut secara eksplisit mengatakan bahwa kompensasi dan rehabilitasi dapat diberikan
setelah dikabulkannya amnesti. Ada tidaknya arnnesti, masyarakat yang menjadi korban
tetap menderita. Oleh karen a itu, seharusnya mereka tetap mendapat kompensasi dan
rehabilitasi. Namun, sebaliknya korban yang telah mendapat kornpensasi dari pengadilan,
mereka tidak boleh mendapat kompensasi lagi.
Ada tiga kcmungkinan yang terjadi sekaitan kata "saling memaatkan": Pertama,
dalam hal pelaku dan korban saling memaafkan, rekomendasi pemberian amnesti wajib
diberikan sub Komisi (amnesti), yaitu Pasal 29 ayat I.
Kedua, dalam hal pelaku mengakui kesalahan, mengakui kebenaran fakta-fakta,
menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan bersedia meminta maar kepada korban atau
keluarga korban yang merupakan ahli warisnya, tetapi korban at au keluarga korban yang
19
mernpakan ahli wansnya tidak bersedia memaafkan maka komisi me mutus pemberian
rekomendasi amnesti harns mandiri dan objektif (Pasal 29 ayat 2)
Ketiga, dalam hal pelaku tidak bersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya sena
tidak bersedia menyesali perbuatannya maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang
berat tersebut kehilangan hak mengajukan amnesti dan diajukan kepengadilan HAM ad hoc.
Pasal 29 ayat 1 dan 2 terang-terangan "memaksakan" rekonsiliasi yang berujung
pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku dan bukannya mengungkapkan
kebenaran. Dalam konteks ini terjadi tubrnkan logika yang sara!. Atas nama persatuan
nasional dan masa depan bangsa, rckonsiliasi dijadikan kata kunei. Sebagaimana termaktub
dalam Pasal 3 hurnf b, "Tujuan pembentukan Komisi adalah meneiptakan persatuan dan
rekonsiliasi nasional dalam jiwa saling pengertian".
Padahal, sine qua /lone dari proses rekonsiliasi suatu bangsa bermula dari meneari,
menemukan, dan menyingkap kebenaran. Dari sana keadilan akan menyingsing di tengah
kabut misteri peristiwa yang melibatkan pelaku dan korban. Adanya keadilan akan
l11enghasilkan kOl11pensasi, rehabilitasi, restitusi pada korban. Pelaku juga akan dianugerahi
amncsti berdasarkan fakta-fakta objektif; perlimbangan yang proporsional (tidak memihak)
sena selektif
Kita tidak ingin amnesti membuka kotak pandora bagi para pelaku untuk lari dari
tanggungjawab. Dalam Undang-Undang ini al11nesti berarti pengal11punan yang dibcrikan
oleh presiden kepada pelaku peianggaran hak
asasi
manusia yang berat dengan
memperhatikan penimbangan Dewan Pcrwakilan Rakyat
Celakanya, rekonsiliasi dalam skenario Undang-Undang ini dinisbahkan untuk
"mengganti" proses peradilan atas sebuah kasus pelanggaran HAM bera!. Seluruh kasus
pelanggaran HAM berat bisa dimajukan kc komisi tanpa menel11puh jalur peradilan. Kasuskasus seperti pembantaian Teungku Bantaqiah di Beutong Atcuh, Aceh atau kasus Tanjung
Priok yang sudah diputus, tidak dapat diajukan ke komisi.
Demikian pula, kasus yang diajukan ke kOl11isi tidak dapat dibawa kc Pcngadilan
I-lAM ad hoc jika sudah tereapai kesepakatan antara peJaku dan korban. Katanya, ini sebagai
penegasan berlakunya asas Ne Bis 117 Idem--·sebuah cara berkclit untuk l11cnutup pcluang
adanya upaya pcnuntutan. Kalau presiden menolak l11cmberikan amnesti, tentu saja tidak
terjadi rekonsiliasi dan kasllsnya telap bisa dibawa kc pengadilan HAM.
20
Bagaimana jika seorang pelaku langsung mengakui perbuatannya, tapi "kebenaran"
peristiwa yang membuat dia dituding sebagai pelaku tidak diungkap? Bukankah ini
menyederhanakan persoalan, sementara duduk perkara kasus tersebut tidak disingkap? Alihalih bangsa ini belajar dari kesalahan yang terjadi di masa lalu, kita tak akan memiliki
rujukan untuk memulai langkah baru tanpa meniru masa lalu yang gelap-gulita itu.
Adalah fakta objektit; kalau kata kebenaran tetap melekat dalam Undang-Undang ini.
Akan tetapi waktu tempuh UU KKR membuat hasil jerih payah OPR dan pemerintah ini jadi
kurang greget. KKR akan dibentuk ketika negeri ini berada di persimpangan sejarahnya;
kekuatan demokratis mendapatkan tentangan kuat dari kubu konservatif yang ingin
mengembalikan negeri ini ke fase otoritarianisme kembali. KKR jadinya diragukan bisa
mengambil peran besar untuk mengantar negeri ini keluar dari transisi demokrasi.
Oua kemungkinan yang bakal terjadi menyaksikan penolakan beberapa pihak
Pertama, Komisi Kebenaran Rekonsiliasi yang bakal dilahirkan Undang-Undang ini diboikot
publik. Eksistensi KKR barangkali akan disahkan oleh presiden, tapi
publik~khususnya
korban--mengacuhkannya. Benih-benih sikap boikot ini mulai terlihat dari serangkaian
statement korban di berbagai media massa. Bila tidak mcmboikot pihak-pihak illi akall
menempuhjudicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Kedua, publik akan menerima keberadaan KKR, dcngan syarat ada semacam lampu
hijau dari anggota OPR yang baru untuk menyegerakan revisi terhadap UU KKR. Sejauh
mana peluang yang terakhir ini tergantung besamya lobi politik dari kelompok-kelompok
kepentingan (ornop, pers, organisasi korban HAM, dJl) serta masyarakat warga (civil
society).
Misalkan kondisi kedua mengedepan, KKR tetap menghadapi soal yang problematis
terkait kasus pelanggaran HAM berat yang mesti diprioritaskan. Undang-Undang ini tidak
memberi mandat jelas mengenai batasan waktu sebuah kasus pelanggaran HAM dapat diusut
KKR. Yang ada, itu pun implisit, KKR diminta mengurus kasus pelanggaran HAM sejak
1945 sampai lllasa sebeilim terbilnya UU No 26 Tahun 2000 Tcntang Pengadilan HAM.
Lalu, alas dasar apa KKR mcndahulukan sebuah kasus dan "mengemudiankan" kasus
pelanggaran HAM yang lain? Apakah sebab korbannya yang bersifat massal seperti
peristiwa 1965 dan DOM Aceh (1989-1998) at au kasus-kasus terdekat yang 1l1asih dalam
jangkauan ingatan publik se1l1acam kasus Trisakti, Semanggi Ill!, kasus 27 Juli 1966,
peristiwa Talangsari Lampung alau serangkaian pe1l1bantaian di Aceh pasca DOM?
21
V. Kesimpulan dan rekomendasi
5.1 Kesimpulan ; Ratifikasi Statuta Roma
Stat uta Roma adalah sebuah statuta badan internasional untuk membentuk sebuah
Mahkamah Pidana Internasional (lCC/international Criminal Court). Mahkamah ini bersifat
permanen dan berwenang mengadili para pclaku pclanggaran berat hak asasi manusia,
seperti pemusnahan ctnik (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against
humanity), dan kejahatan perang (war crime).
Dcngan memperhatikan prinsip yang terkandung dalam Statuta Roma, sistem
pengadilan di Indonesia akan lebih mampu menangani kasus pelanggaran HAM. Dengan
demikian, berbagai tindak kejahatan pelanggaran I-lAM juga dapat dilakukan di Indonesia
dan tidak peflu diambil alih oleh Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, Statuta Roma,
akan semakin memperkaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia, apalagi setelah
pemerintah sendiri telah melakukan ratifiksai Statuta Roma dalam bentuk Undang-Undang
dan beberapa Peraturan Pemerintah. Memang rumusan tentang kejahatan masih sangat
global, sehingga menyulitkan jaksa untuk membuktikan suatu perkara. Scmentara, di Statuta
Roma, rumusan kejahatan sudah didefinisikan dengan ukuran-ukuran yang jclas dan tidak
tcrlalu bcrsifat kualitatifsebagaimana dalam Undang-Undang HAM.
Saat ini tclah ada lebih dari 70 negara meratifikasi Statuta Roma itu berarti mulai
diberlakukannya Statuta tersebut dinegara-negara pihak dan ratifikasi tersebut harus diikurti
dengan pcmbentukan Undang-Undang HAM atau Peraturan Pemerintah di setiap negara
penanda tangan. Mcngingat pcntingnya Statuta Roma ini dalam pcncgakan hukum di
Indoncsia, kita berharap statuta ini dapat berlaku secara efektif di Indonesia.
5.2 Rekomendasi; Posisi UU No 26/2000 ten tang Pcngadilan HAM.
Bergesernya komunitas internasional tampaknya sejalan dengan pcmikiran bahwa
scbuah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, merupakan permasalahan dunia sccara
global. Pelanggaran khusus ini membuat tidak saja semua ncgara mcmpunyai hak untuk
menuntut dan menghukum pelaku kejahatan ini, tetapi sekaligus diwajibkan un/uk menuntu/
dan menghukum mcrcka-mcrcka yang tclah melakukan kejahatan scrius tadi. Lantas
bagaimana posisi Indonesia dalam menanggapi trcnd intcrnasionalisasi konflik internal ini?
Indonesia, pad a dasarnya, meletakkan pelanggaran serius dalam konflik internal ini,
pada kebijaksanaan serta aturan yang terdapat dalam hukum domestik. Niat Indonesia untuk
22
"mengatur" sendiri permasalahan konflik bersenjata internal ini, dapat dilihat dari tidak
dimasukkannya "war crimes" dalam Undang-Undang No. 26 talmn 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia. 1'adahal UU ini dilihat dari bentuk tekstual legalnya dapat dikatakan
sebagai bentuk "ratifikasi" dari Statuta Roma. Bedanya 00 domestik kita ini hanya
mcngadopsi 2 dari 4 kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma. Kedua
kejahatan tersebut adalah Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Genosida serta minus war
crimes dan aggression Meskipun UU ini secara eksplisit menghormati kaidah hukum
internasional dalam pengklasifikasian tindak pidananya atas kemcrdekaan alau kebebasan
fisik seseorang (1'asal 9 (e)), peniadaan klausul war crimes menjadi problem tersendiri bagi
UU ini. Terutama, dalam hubungannya dengan kejahatan serius yang mungkin ditemukan
dalam sebuah konflik internal bersenjata. Padahal "roh" internasionalisasi kejahalan serius
terhadap kemanusiaan dalam bentuk kriminalisasi konflik internal bersenjata melalui Statuta
Roma hanya bisa diwujudkan dengan instrumen klausul yang terdapat dalam provisi war
crimesnya. Untuk itu, penerapan operasi militer di Aceh yang sedikit banyak bersinggungan
dengan korban-korban sipil ataupun combatant yang telah menyerah, jelas tidak masuk
dalam kategori pelanggaran serius menurut undang-undang domestik kita.
Kekhawatiran aktivis pro HAM dalam negeri ten tang tidak diadopsinya war crimes
dalam UU domestik kita sebelum penerapan operasi militer di Aceh tampaknya mulai
teljawab kini. Mayoritas, untuk tidak mengatakan semua, kejahatan dalam konflik di Aceh
pasca-operasi militer tidak dikatagorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kemanllsiaan.
Yang konsekuensinya "bebas" dari jerat UU No. 26 tahun 2000.
Sebenarnya, berbicara dalam tataran semangat terhadap penanganan kejahatan
terhadap kcmanusiaan, 011 terhadap kejahatan kcmanusiaan yang dimiliki repuhlik ini boleh
dikatakan maju selangkah, minimal bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga.
Australia, misalnya, sampai saat ini masih belum memiliki special Bill ()f RighI. Bahkan Uni
Eropa,
sebagai
ncgara
yang dikenal
cukup
gigih dalam
memperjllangkan
HAM,
membutuhkan waktu 38 tahun sebelum akhirnya berhasil membentuk pcngadilan HAM
secara kolektif pad a tahun 19981. Bahkan, at as nama penghormatan terhadap kemanusiaan,
Undang-undang domestik kita secara tegas mengabaikan asas NU//lIm lJelicllIm dalam
kOllscp penuntlltan tindak pidananya
Artinya, UU No. 26/2000 dapat dipakai dalam
penuntutan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang teljadi sebclum UU tersebllt
dikeluarkan.
?~
--)
Sayangnya, semangat pro HAM dalam ULJ No. 26/2000 kurang mewarisi spirit asal
penghormatan terhadap kaum sipil noncombatant, scbagaimana yang tercantum dalam
Statuta Roma. Untuk itu, pcmberlakuan asas retroaktif atas UU No. 26/2000 tampak lebih
pada euphoria politis akan hak asasi manusia daripada aplikasi legalnya
Akhirnya, beranjak dari trend global serta kondisi disefisiensi hukum domcstik kita
terhadap kejahatan serius pad a kemanusiaan khususnya pada kontlik bersenjata internal ada
baiknya keinginan mengamandemen instrumen hukum domestik dapat menjadi euphoria
yang lain bagi para legislator. Adapun mengenai trend internasionalisasi serta kriminalisasi
konflik internal bersenjata, sebenarnya clap at kita sikapi dengan tetap menjaga kedaulatan
negara. Untuk itu, pengusungan ide meratifikasi Konvensi Geneva dan Statuta Roma disertai
reservasi pad a beberapa ketentuannya, bisa menjadi salah satu alternatifuntuk dilakukan
24
DAFTAR REFERENSI
Kasim, lfdhal, 2000, Sialuia Roma; Mahkamah Pidana JnlerbnClsional, Jakarta, Lembaga
Studi clan Aclvokasi Masyarakat (Eisam)
Robertson, Geffrey, 2000, Kejahalan Terhadap Kemanllsiaan, jakarta, Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia.
Magnis Suseno, Frans, 2000, Kliasa dan Moral, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Bertens, K, 200 I, Per,lpekl!( Etika; Emi-esai lentang Masalah Aklllal. Yogyakarta,
Kanisius.
Hup://www.google.co!T!, 2004, PP No 2 lahun 2002 lenlang Perlindllngan lerhadap saksi
dan korban da/am pelanggaran HAM berel/,
J:ittpl,iyvww.googlecQt1J, 2004, PI' No.3 lahlll1 2003 len lang Kompensasi, Reslilllsi, dan
Rehabililasi lerhadap Korban Pelanggaran HAM bera!.
25