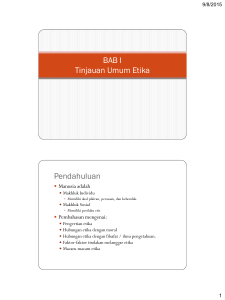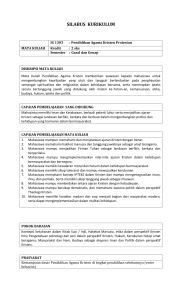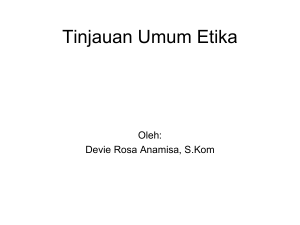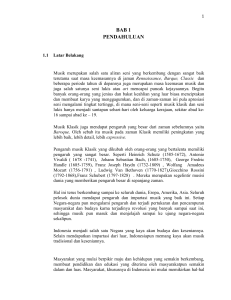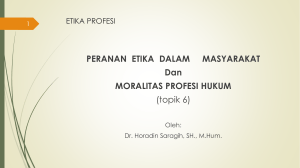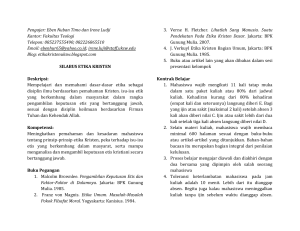(Filsafat dan Etika ) Materi Kuliah 5
advertisement

Materi 5 : Filsafat dan Etika Komunikasi Model-Model Pendekatan Etika Oleh : Tri Guntur Narwaya, M.Si “Setiap kebijaksanaan harus bersedia dipertanyakan dan dikritik oleh ‘kebijaksanaan-kebijaksanaan’ lain... Keberlakuan universal harus dapat membuktikan diri dalam konfrontasi dengan mereka yang berpikir lain” (Benezet Bujo) Secara prinsip ‘etika’ tidaklah sama dengan sebuah ajaran atau norma. Etika mempunyai tugas untuk memahami dan menjelaskan mengapa norma dan nilai nilai tertentu bisa diberlakukan. Etika juga menjelaskan mengapa pilihan moral tertentu harus diambil. Berbagai eksplorasi tentang penjelasan mengapa sebuah ‘moralitas’ tertentu tidak harus diterapkan secara imperatif adalah tugas dari etika. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja melainkan menuntut agar pendapatpendapat moral yang dikemukakan bisa dipertanggungjawabkan.1 Dalam penjelasan lain, etika merupakan usaha untuk menjernihkan permasalahan moral.2 Cara untuk mendekatai permasalahanpermasalahan moral itu tentu saja dalam perkembangan etika hadir beragam. Maka kita akan banyak disuguhkan dengan berbagai model pendekatan etika yang ada. Masing-masing mempunyai rujukan pertimbangan dan juga pendasarannya. Sebuah ‘model’ dan ‘tipe pendekatan’ bisa berarti merupakan tolok ukur. Ketika etika bertugas untuk membuat pendapat moral bisa ‘dipertanggungjawabkan”, maka kita akan ditarik pada sebentuk pertanyaan mendasar: Tolak ukur apa yang kita pakai sebagai sebuah pertanggungjawaban? Sebuah pertanggungjawaban tentu mempunyai isi dan tidak hadir dalam ungkapan kosong. Ia akan merujuk pada norma yang kemudian kita pilih untuk diterapkan. Setiap model mempunyai dasar-dasar pertimbangan ini. Tentu tugas etika lebih jauh untuk mencari dasar objektif sebuah pertanggungjawaban moral. Dasar objektif di sini bisa berarti prinsip-prinsip yang mendasari semua norma moral yang lebih kongkrit. Mengapa Penting Memahami Model? Ketika kita menghadapi satu masalah tentang ‘pilihan moral ‘yang harus kita ambil kebanyakan dari kita akan merujuk pada dua pendekatan yang umum. Ketika ada sebuah pertanyaan apa yang mendasari tindakan kita untuk berjalan seperti: Tindakan apa yang seharusnya kita ambil biar kita bisa bertanggungjawabn secara moral ? Kebanyakan kita akan menghadirkan jawaban yakni dari ‘norma yang diberikan masyarakat’ atau ‘dari suara hati’. Kedua jawaban ini tentu saja masih bisa bermasalah dan keliru. Bagaimana kita kemudian bisa menemukan jawaban-jawaban itu secara objektif dan benar? Apakah ada peertimbangan moralitas yang memang benar-benar bisa tidak 1 Lihat, Franz Magnis Suseno, Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1985, hal. 18. 2 Seperti yang juga dimengerti bahwa “norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya ‘sebagai manusia’ dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 19. 1 keliru? Mungkin di titik inilah tugas membangun prinsip etika secara universal dan objektif menjadi penting. Pada titik tertentu dalam membaca dan berpengalaman langsung dengan problem etika ini, kita sering banyak akan menemukan ketegangan-ketegangan mengenai bagaimana membangun pendasaran moral atas tindakan-tindakan yang dipilih manusia. Kita memahami bahwa masyarakat juga terbangun tidak hanya dalam plihan-pilihan tindakan yang begitu saja dianggap semua rasional. Banyak hal dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak rasional juga dipakai sebagai pilihan rujukan itu. Misalnya kita bisa bicara pada fenomena ‘etika wahyu’ yang berkembang pada keyakinan-keyakinan primodial yang dimiliki oleh agama dan keyakinan-keyakinan tertentu. Banyak unsur unsur tindakan manusia yang didasarkan atas etika ini. Asal dalam teks wahyu tertentu mengatakan demikian maka manusia harus mengatakan demikian. Pemakaian secara ‘fundamental’ dan literer’ semacam ini seringkali menciptakan nalar pikir yang ‘tertutup’ dan ‘beku’ jika tidak juga dikembangkan dengan nalar akal budi manusia yang barangkali lebih membuka cakrawala lebih luas. Tidak berarti pada kesadaran etika wahyu tidak penting, tetapi menempatkannya sebagai satu-satunya rujukan moralitas sering kali mengalami ironi dan dilema pada kenyataan hidup manusia yang sifatnya kongkrit. Maka pentingnya pemahaman ajaran wahyu dengan keterbukaan akal budi kritis kita menjadi penting untuk memahami semua realitas hidup manusia. Kesadaran literer fundamental ini juga kadang kita temukan dalam kesadaran-kesadaran ideologis yang beku. Di luar dari kesadaran ideologi itu adalah kekeliruan. Sikap ini tentu merupakan pemahaman kesadaran ideologi yang tertutup dan totaliter. Pentingnya membentangkan berbagai model pendekatan etika ini adalah bermaksud untuk membuka cakrawala kesadaran bahwa dalam setiap konteks sosial budaya dan lingkungan tertentu memiliki berbagai kondisi dan dinamika pilihan moral yang beragam. Tidak berarti bawa apa yang menjadi cita-cita kebenaran universal itu kemudian dianggap ‘nisbi’ dan ‘naif’ dan juga ‘utopis’. Barangkali justru keterbukaan menyadari berbagai pertemuan dan dinamika antara ‘yang universal’ dan ‘yang partikular’ akan menjadikan sikap berpikir akan makin terbuka dan berkembang. ‘Universalisasi’ ataupun ‘partikulasisasi’ jika dipakai sebagai kesadaran dogma dan absolut juga akan bermasalah bagi kehidupan peradaban manusia. Menjadi relefan apa yang menjadi catatan etika dari Benezet Bujo bahwa “keberlakukan universal harus dapat membuktikan diri dalam konfrontasi dengan mereka yang berpikir lain” dan juga catatannya yang memberi garis merah bahwa “konteks adalah tempat di mana apa yang universal hadir secara potensial”.3 Apa yang dipikirkan oleh Bujo mungkin juga senada dengan apa yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas dalam ‘etika diskursusnya’ yang meletakkan kunci keterbukaan dialog dan kesediaan diri untuk terbuka pada kritik validasi merupakan unsur penting dalam membangun etika komunikasi.4 Tentu saja premis dari Habermas ini juga mengandaikan bahwa sebuah dialog (komunikasi) dalam ruang publik yang demokratis harus melepaskan diri dengan segala unsur yang ‘dominatif’ dan ‘manipulatif’. 3 Catatan Benezet Bujo ini dikutip dalam bukunya Franz Magnis Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Penerbit kanisius, Yogyakarta, 1992, hal. 52 4 Dalam tulisannya tentang ‘etika diskursus Habermas’, Frank Budi Hardiman mencatat bahwa “Dalam sebuah masyarakat yang demokratis, praksis diskursus itu akan membangun sikap yang menghargai kekuatan argumentasi yang lebih baik sehingga berbagai manipulasi “ideologis” itu sendiri pada gilirannnya akan diperiksa secara publik dalam arena diskurus rasional yang bersifat publik”. Lihat, Frank Budi Hardiman, Filsafat Fragmentaris, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hal. 117. 2 Berbagai Model Pendekatan Etika Etika Peraturan Dalam ranah pembacaan tentang etika, kita minimal menemukan tiga model pendekatan yang secara umum sering dipakai dalam kehidupan masyarakat. Penting unhtuk memeriksa faham beberapa catatan etika ini terutama tentang hakikat kewajiban moral. Pertama, “etika peraturan”. Etika peraturan bukan merupakan definisi tentang pendekatan khusus tertentu tetapi hanya gambaran dari berbagai kecenderungan dalam konteks tertentu. Yang dimaksud dengan ‘etika peraturan’ adalah etika-etika yang melihat hakikat moralitas dalam ketaatan terhadap sejumlah peraturan.5 Dalam etika semcam ini ‘apa yang dimaksud baik adalah sikap yang menuruti perintahperintah yang termuat dalam peraturan-peraturan tersebut’. Bentuk etika peraturan ini bisa berbentu peraturan-peraturan dalam keluarga, sebuah lingkungan tertentu, adat istiadat atau juga peraturan yang ada dalam agama. Dalam ‘etika peraturan’ manusia tidak lebih daripada mengetahui peraturan-peraturan moral itu dan hidup sesuai dengannnya.6 Misal kita bisa ambil contoh peraturan dalam keluarga seperti ‘hormat kepada orang tua’, peraturan dalam masyarakat seperti hubungan sesama jenis dilarang, atau peraturan agama mengenai menikah dianggap resmi, sah dan baik jika melalui lembaga perkawinan. Problem dan kesulitan yang seringkali muncul pada praktik penerapan ‘etika peraturan’ adalah bahwa ‘etika peraturan’ tidak bisa menyediakan bahan jawabanmemadahi dan memusakan ketika diberikan pertanyaan tentang “apa yang menjadi dasar dari keberlakukan pilihan moral tertentu yang ada dalam peraturan tersebut”. Kebanyakan akan kembali lagi pada bahwa itu memang sudah demikian adanya ada dalam kewajiban moral yang harus dianut. Etika peraturan kiebanyakan gagal untuk menjawab segala pertanyaan tersebut. Kebanyakan dari prinsip ‘etika peraturan’ adalah bahwa yang dituntut bukan agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai tertentu, melainkan agar peraturan-peraturan itu ditaati.7 Apa yang menjadi landasan dan rujukan pertimbangan mengapa sebuah nilai tertentu harus ditaati memang tidak ada. Hal yang kedua yang sering ada dalam penerapan ‘etika peraturan’ ini adalah bahwa ia tidak menyediakan rujukan arti penting sebuah ‘tanggung jawab’. Akibat yang bisa menjadi konsekuensi tindakan manusia tidak mendapatkan tempat. Padahal secara mendasar ‘etika tanggung jawab’ menuntut pada semua orang bahwa dalam perilaku dan tindak tanduk harus dilandasi pada sikap ‘bertanggungjawab’ terhadap akibat perbuatan yang dilakukan. Apa yang dimaknai sebagai ‘moralitas’ hanya berhenti menjadi ‘hukum’. Etika Situasi Pendekatan kedua, kita akan mengenal dengan ‘etika situasi’. Etika situasi ini pada pendasaran pemikiran banyak dipengaruhi oleh cara pandang dan filsafat ‘eksistensialisme’8 dan ‘personalisme’. Eksistensialisme selalu menekankan keunikan dan tanggungjawab tiap-tiap orang, bahwa tiap-tiap orang itu khas dan tidak dapat dimasukan di dalam ‘kerangka-kerangka’, ‘skema-skema’ dan ‘normanorma umum’, melainkan harus menentukan diri sendiri berdasarkan penghayatan yang otentik.9 5 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 102. Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 103. 7 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 103 8 Eksistensialisme adalah ‘filsafat yang memandang bahwa segala gejala dengan berpangkal pada eksistensi. Ia bisa dimengerti sebagai faham yang menentang ‘esensialisme’. Dalam pandangan eksistensialisme, ‘eksistensi’ selalu mendahulu ‘esensi.’ Motif pokok dari eksistensialisme adalah keyakinan bahwa hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Lihat, Lorens bagus, Kamus Filsafat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 185. Sedang filsafat pandangan ‘personalisme’ adalah cara pandang yang menekankan bahwa manusia adalah ‘person’, bukan sekedar nomor dalam kolektif, melainkan bernilai pada dirinya sendiri. Sebagai persoan ia mempunyai kehendak sendiri dan sekaligus juga kebebasan untuk bertindak dan bertanggungjawab. 9 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 104. 6 3 Dalam praktiknya ‘etika situasi’ selalu menolak hadirnya keberadaan norma-norma dan peraturanperaturan moral yang berlaku umum. Norma dalam pandangan ini tidak berlaku universal. Semua kondisi lingkungan adalah unik, demikian juga dengan manusia. Antara ‘etika situasi’ dan ‘etika peraturan’ memang pada prinsipnya betolak belakang dan bertentangan. Etika peraturan menuntut loyalitas tindakan pada hukum peraturan dan menghilangkan kebebasan otentik dan unik dari setiap manusia, sedang 'etika situasi’ justru berjalan sebaliknya. Ia justru menolah determinasi hukum peraturan tersebut. Marilah kita mencoba membaca lebih kritis nalar ‘etika situasi’ ini. Prinsip keunikan bahwa setiap situasi adalah unik barangkali memang bisajadi benar, tetapi apakah semua kemudian kita anggap unik dan tidak membuka diri dengan apa yang dimaksud dengan sesuatu yang universal? Apakah tidak ada garis-garis kesamaan pada setiap situasi? Jika tidak ada kesamaan, kenapa manusia dan masyarakat bisa menyepakati dalam beberapa hal tentang etika hidup bersama? Apa yang kemudian disebut sebagai ‘yang universal’ tidaklah mungkin bisa tercapai? Beberapa keresahan pertanyaan ini menarik untuk kita diskusikan. Apa yang sebenarnya membuat kesamaan dalam setiap relasi sosial sehingga kita mulai dan bisa faham dalam kesapakatan? Tentu sangat sadar harus dipahami bahwa kesamaan pandangan itu karena manusia sejatinya adalah bukan sekedar mahluk personal melainkan juga mahluk sosial yang selalu membangun interaksi sosialnya dengan orang lain dalam struktur sosial. Situasi yang ada barangkali bisa dinterpretasi dan difahami secara berbeda, tetapi ia juga membuka dialog pemahaman karena pada fakta kenyataannya situasi yang ditempoati adalah sama. Bumi yang dihuni manuisa ini adalah sama. Yang lebih penting lagi bahwa manusia harus menyadari bahwa manusia tidak bisa melepaskan dengan kenyataan objektif atas dinamika relasi-relasi tersebut. Pada titik inilah, ‘etika situasi’ gagal dan cenderung melupakan kenyataan objektif itu. Satu kelemaham dari ‘etika situasi’ adalah bahwa ia jatuh pada nalar ‘individualisme ekstrem’ yang hanya melihat keunikan tanggungjawab individual, tetapi melupakan bahwa tanggungjawab itu baru menjadi nyata berhubungan dengan denhgan kedudukan kita dalam ‘kesatuan’ kehidupan masyarakat.10 Pada banyak hal melahirkan sikap ‘anarkisme’ yang mendorong sikap penolakan secara ekstrem segala bentuk peraturan dan hukum yang diberlakukan secara umum.11 Apakah memang ‘anarkisme’ ini kenyataannya bisa dipraktikan? Apakah sejatinya sikap ini juga akan membentur problem yang sama bahwa ia sendiri diam-diam justru juga menjadi aturan dan norma dalam dirinya sendiri? Dalam bukunya tentang ‘Radikal itu Menjual’ yang memberi peran penting dan optimisme pada berfungsinya peraturan, Joseph Heath & Andrew Potter bahkan memberi catatan yang bernada metaforis bahwa “Kebanyakan orang tidak siap untuk dicabut. Dan banyak diantara mereka yang begitu betah, begitu mati-matian bergantung pada sistem , sampai mereka akan berjuang untuk melindunginya”12 Etika Utilitarisme Model pembagian lain dari cara pendekatan etika yang masih mainstream diperdebatkan hari-hari ini adalah apa yang kerap dikenal sebagai ‘Utilitarisme’ yang merupakan contoh khas dari tipe ‘etika 10 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 106. Riset yang lebih populer tentang bagaimana kecenderungan ‘anarkisme’ ini hadir pada model dan strategi wacana tanding yang beberapa tahun dan hingga akhir ini dipakai. Dalam beberapa hal gerakan perlawanan wacana tandig memakai prinsip penolakjn terhadap apa yang disebut sebagai ‘universalisasi’ atau kebijakan penerapan norma secara umum. Namun dalam praktiknya ‘wacana tanding’ selalu gagal ketika berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat hidup dalam relasi-relasi hubungan yang akan melahirkan atiran-aturan hidup bersama. Lihat, Joseph Heath & Andrew Potter, Radikal itu Menjual: Budaya Perlawanan atau Budaya Pemasaran, Penerbit Antipasti, Jakarta, 2009. 12 Lihat, Joseph Heath & Andrew Potter, Ibid, hal. 10. 11 4 teleologis’, yang menentukan baik buruknya tindakan dari baik buruknya akibat yang menjadi tujuannya.13 Aliran ini lebih bersifat ‘libera’l karena yang terpenting bukan prinsip nilai yang hadir dalam nalar moralitas itu sendiri tetapi dampak yang ditimbulkan dari pilihan-pilihan moral yang diambil. Sebagai pendasaran etika, ‘utilitarisme’ berangkat dari asumsi yang persis diandaikan oleh ‘etika situasi’ yakni yang melihat bahwa konteks tindakan dan situasi lingkungan serba unik dan tidak bisa diasumsikan dalam prinsip-prinsip umum yang baku. Berbeda dengan , ‘etika deontologis’ yang berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan melekat pada tindakan itu sendiri. Prinsip pengandaian kedua dari etika jenis ini adalah apa yang dimaksud manfaat bukanlah sembarang manfaat tetapi ‘kegunaan’ dalam menunjang apa yang bernilai pada dirinya sendiri, yang baik pada dirinya sendiri. Dalam nalar pertama ‘utilitarisme’, apa yang disebut baik ‘adalah yang berguna’. Dan yang baik pada dirinya sendiri adalah ‘kebahagiaan’. Faham eudemonisme lebih sering dianggap ‘hedonis’ dan ‘egois’. Maka banyak orang juga menyebutkannya sebagai pandangan ‘etika egois’. Menurut salah satu penggagas ‘etika utilitarisme’, John Stuart Mill, apa yang disebut ‘membahagiakan’ adalah ‘nikmat’ dan ‘kebebasan’ dari perasaan tidak enak karena itulah yang selalu diinginkan manusia. Kecenderungan hedonistik ini yang berakar dalam asumsi bahwa apa yang dianggap untuk mengusahakan kebahagiaan dianggap sama dengan mengusahakan pengalaman nikmat dan menghindari pengalaman yang menyakiti. Pertanyaan lanjut: bagi siapa nikmat itu? Kehendak untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan itu bukan untuk segelintir person (pribadi) tetapi bagi semua orang. Maka di titik ini utilitariisme lebih bersifat universal etis. Maka secara umum pandangan ‘utilitarisme’ bisa dijelaskan sebagai pandangan etika yang bisa dirumuskan sebagai berikut : “tindakan atau peraturan tindakan yang secara moral betul adalah yang paling menunjang kebahagiaan semua yang bersangkutan”.14 Prinsip kegunaan ini yang akhirnya menyebutkan bahwa filsafat utilitarisme sebagai pendekatan etika yang lebih pragmatis (etika pragmatis). Lawan dari prinsip ‘utilitarisme’ ini adalah pendekatan etika deontologis yang meyakini bahwa untuk mengukur baik buruknya tindakan bukan dari tujuannya, melainkan dari sifat tindakan itu sendiri. Jika pada sebuah kasus ada dua pilihan moral yang harus diambil tetapi secara manfaat berbeda, maka bagi etika utilitarisme, pilihan moral yang kemungkinan akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan lebih tinggi harus diambil. Etika Deontologis Berbeda dengan ‘utilitarisme’ yang menekankan aspek kegunaan dan dampak manfaatnya bagi manusia, Imanuel Kant mengembangkan sebuah pembahasan etika yang lebih normatif. Apa yang dimengerti tentang moralitas yang baik bukan terletak pada kegunaannya, tetapi ada dalam prinsip nilai tujuan itu sendiri. Kebaikan moral bagi Kant adalah kebaikan dari segala segi, tanpa pembatasan. Baik adalah baik secara mutlak. Ia menggambarkan apa yang menjadi baik secara mutlak adalah kehendak baik. Kehendak baik itu selalu baik dan dalam kebaikannnya tidak tergantung pada sesuatu di luarnya. Kita melakukan pilihan moral karena memang itu baik adanya tidak ada embel-embel prasyarat apapun. Kewajiban melakukan tindakan baik karena didorong oleh kewajiban untuk bertindak baik adalah unsur atau karakteristik tindakan moral baik yang dimaksud Kant. Apa yang secara moral bisa diterapkan bila ia sudah diuniversalisasikan dan tidak terjebak pada subjektifitas masing-amsing person. Sebuah norma hanya berlaku secara moral apabila dapat diuniversalisasikan dan berlaku umum sebagai sebuah aturan main.15 13 Lihat, Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1997. hal. 178-179. 14 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 179. 15 Lihat, Franz Magnis Suseno, 12 Tokoh Etika Abad Ke-20, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 225. 5 Etika Diskursus Jurgen Habermas, salah satu pemikir Jerman lebih memberikan alternatif baru bagi pengembangan etika manusia dengan penekanannya pada diskursus (dialog). Dalam etika diskursus yang terpenting adalah ‘tindakan bahasa’. Pemusatan pentingnya bukan pada ‘subjek’ tetapi kepada ‘bahasa’. Maka bagi Habermas unsur yang terpenting dalam etika adalah dalam dimensi bahasa dan komunikasi ini. Bagi Habermas “Sebuah norma moral hanya boleh dianggap sah kalau ‘akibat-akibat dan efek-efek sampingan yang diperkirakan akan mempengaruhi pemuasan kepentingan siapa saja andaikata norma itu ditaati secara umum, dapat disetujui tanpa paksaan oleh semua”.16 Jadi sebagai cara untuk menentukan dan memastikan bagaimana norma moral bisa sah berlaku adalah harus diadakan sebuah diskursus yang bebas dari tekanan dan paksaan. Artinya jenis etika diskursus yang ingin dikembangkan oleh Habermas bisa diarikan begini : “Hanya norma-norma yang disetujui (atau dapat disetujui) oleh semua orang yang bersangkutan sebagai peserta sebuah diskursus praktis boleh dianggap sah” Selamat Belajar !!! 16 Lihat, Franz Magnis Suseno, Ibid, hal. 226. 6