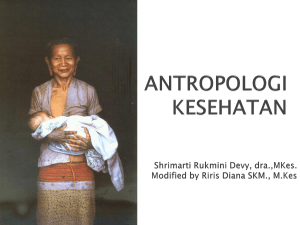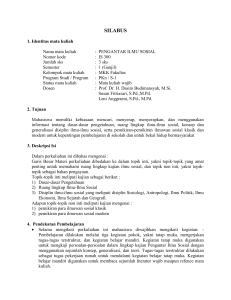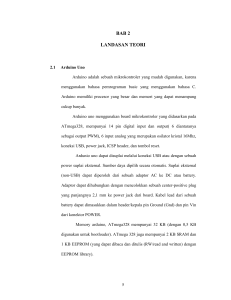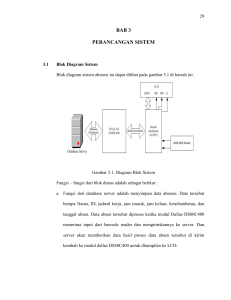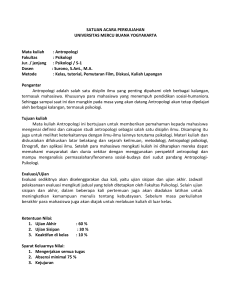Minggu V BAB V IDENTITAS INDONESIA PENDAHULUAN Pada
advertisement

Minggu V BAB V IDENTITAS INDONESIA1 A. PENDAHULUAN Pada pertemuan kelima ini mahasiswa sudah harus mulai membawa isu nasional ke dalam pembahasan mengenai ilmu antropologi di Indoenesia. Sejarah mengenai pencarian identitas Indonesia antara 1900 dan 1930 mengikuti suatu periode yang cepat dan bebas dari dan agak berlawanan dengan program reformasi pemerintah kolonial, meskipun inspirasi idelogisnya datang dari Barat. W.F. Wertheim (1964:211-237) percaya bahwa Program Politik Etik yang setengah hati untuk transformasi total masyarakat Indonesia telah menjadi daya dorong gerakan pencarian identitas itu. Namun demikian ketidak-pastian mengenai bahasa justeru memicu pencarian identitas baru dengan cara menutup-nutupi identitasnya sendiri dengan meminjam dari tempat lain (untuk memperkaya miliknya). Konstruksi “Indonesia” kemudian merupakan apropriasi sesuatu yang anonim/aneh (Siegel 1986), dan tentu saja tidak semestinya mengubah struktur yang lama. Oleh karena itu sifatnya dinamik dan diskursif. Kira-kira sejajar dengan Siegel, Benedict Anderson (2004:29-45) berargumentasi bahwa pembentukan suatu identitas kolektif, antara seseorang dan jamak/unversalitas/ kolektivitas/komunitas-nya tidaklah mengikuti suatu logika serial yang tunggal. Mengenai nasionalisme, misalnya, Anderson mengungkapkan bahwa subjektivitas kolektif (universal) melibatkan dua logika serial yang sangat berbeda. Pertama adalah logika serial yang terikat, yang diturunkan dari sensus (kategorisasi), diterapkan dan dihitung oleh aparat Negara. Mengikuti logika ini, identitas nasional seseorang tertentu (misalnya untuk memilih dan dipilih) tergantung pada imposisi kategori-kategori sensus (buatan Negara), misalnya kelamin, umur, tempat lahir, kesukubangsaan, warna kulit dll. Mengacu pada James C Scott (1998), saya menyebut serial ini sebagai identitas yang terregimentasi, karena itu diatur oleh angka dan diletakkan dalam sel baris dan kolom seperti halnya regimen tetara. Logika serial yang kedua itu tidak terikat dan tidak tercacah. Mengikuti serial ini imajinasi nasionalistik seseorang tergantung pada akumulasi pengetahuan yang dikumpulkannya dari media. Siapa pun dapat mengimajinasikan dirinya hampir sesuka hati menggunakan serialitas (klasifikasi) universal yang ada seperti sebagai revolusioner, nasionalis, aktivis, sosialis, yuppie, punk, metal, hard rocker, bahkan intelektual dll. Oleh karena itu banyak varian nasionalisme. Dalam praktek sehari-hari, orang dipaksa oleh ketegangan hubungan antara kedua serialitas itu untuk menampilkan ekspresi politik identitasnya secara taktis dan diskursif. Siegel (1997) mengklaim bahwa sejarah bangsa Indonesia berasal dari efekefek yang terjadi akibat hubungan-hubungan yang dimungkinkan oleh kehadiran lingua franca. Kita tahu kehadiran bangsa Indonesia ditopang kuat oleh keberadaan bahasa Indonesia yang asal mulanya adalah dari bahasa melayu pasar. Sebagai lingua franca bahasa Indonesia beroperasi di antara orang-orang yang berbeda-beda bahasa dan 1 Topik bahasan minggu ke V dalam mata kuliah pengantar antropologi ini merujuk pada referensi tulisan PM.Laksono (2011). “Memahami Kebudayaan (Indonesia) Dari Perspektif Antropologi”. Bahan Untuk pembahasan RUU Kebudayaan dari Pendamping Ahli Komisi X DPR untuk Pembahasan RUU Kebudayaan. budayanya tanpa menjadi milik seseorangpun. Bagi hampir semua penduduk Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa kedua, malah masih banyak warga Indonesia yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Untuk menggunakan bahasa Indonesia banyak orang harus menterjemahkan maksud hatinya. Seperti halnya teknologi yang tersedia bagi seseorang untuk menggunakannya atau, lebih penting lagi bagi kita, bagi siapa yang mulai berfantasi untuk menggunakannya, lingua franca adalah suatu alat, suatu titik antara. Jadi pemahaman kekhususan sejarah Indonesia tergantung pada pemahaman tentang suatu titik tengah yang memproduksi efek-efek kultural (Siegel 1997: 8-9),. Sejarah revolusi Indonesia dapat dianggap sebagai suatu kekecualian. Ini terjadi karena pembebasan hasrat, misalnya hasrat untuk merdeka tidak terjadi pada hubunganhubungan antara orang-orang terjajah dengan tuannya, tetapi pada hubungannya dengan dunia. Banyak contoh yang menunjukkan betapa para jenderal dan elite Indonesia yang ketika berbicara dengan rekan-rekannya selalu dengan bahasa Belanda daripada dengan bahasa Indonensia. Perjuangan Kartini juga dikenal tidak memusuhi Belanda, tetapi perjuangan menterjemahkan nilai emansipasi yang universal untuk menentang ketertindasan perempuan jawa oleh kaumnya sendiri. Jadi revolusi Indonesia menghasilkan suatu yang tidak sepenuhnya asing tetapi juga tidak sepenuhnya domestik, yaitu semacam budaya yang seolah-olah berasal dari negeri antah berantah tanpa alamat, tidak barat tidak timur. Itulah kira-kira posisi masyarakat-masyarakat dan tentu saja bahasa-bahasa lama Indonesia di dalam Negara Indonesia paska kemerdekaan.2 Melalui penterjemahan dalam lingua franca dan simbol-simbol global itu, budaya-budaya lokal kemudian mencari pengakuan atas keberadaannya. Orangorang pribumi mengadopsi pakaian Barat bukan untuk menjadi Belanda tetapi untuk mengglobalkan diri, yaitu menggunakan simbol-simbol, yang walau bukan milik siapa pun, agar dapat merasa memiliki jimat atau sumber kekuatan. Suatu saat pernah seorang anak laki-laki penutur asli bahasa jawa tamatan SD yang ingin unjuk kemampuan bahasa Indonesianya dengan susah payah berkata kepada isteri saya: “Bu ini saya mau mengembalikan anda.” Isteri saya sempat bengong: “Hei apa?” Dengan gugup ia mencoba memperbaiki budi bahasanya kini dalam bahasa jawa: “Niki kulo ajeng mangsulke anda.” Maksudnya ia mau mengembalikan tangga yang baru saja dipinjamnya untuk memperbaiki genteng rumahnya yang melorot. Proses alih bahasa semacam ini terus berlangsung dengan cepat dan penuh ketegangan di berbagai sektor hidup, termasuk yang sering dilakukan para ilmuwan gagap berbahasa (Indonesia/Inggeris). Di sini orang mendomestikkan jagad baru mereka. Dalam kasus di Solo yang diamati oleh Siegel (1986: 87-116), misalnya pentas ludruk Srimulat mendomestikkan Dracula (hantu asing) yang justeru populer karena keasingannya. Judul-judul pentas mereka ada dalam bahasa asing, Indonesia dan campuran seperti: Killer of Play Papa; Violent Papa; Bulan Madu dengan Mayat Hidup; Yang Binal yang Berontak; Kunci Nafsu Dracula; Gadis Metropolitan; Hot Love Kuntilanak. Di sini budaya lama (soal hantu dan demit) tidak lantas mati oleh kedatangan unsur budaya baru tetapi bertahan secara kreatif (melawan hirarki bahasa baru). 2 Di Indonesia terdapat kira-kira 742 bahasa di antara 237 juta penduduk. Hanya 13 bahasa dipergunakan oleh lebih dari sejuta orang. Jadi 729 bahasa lainnya dipergunakan oleh kurang dari sejuta orang, bahkan 169 bahasa di antaranya dipergunakan oleh kurang dari 500 orang. (http://didikbudiarto.wordpress.com/2008/08/13/indonesiarepublik-dengan-742-bahasa/ ) Dari maestro antropologi struktural Claude Levi-Strauss (1995) kita bisa belajar betapa posisi para penutur bahasa Indonesia sebagai lingua franca itu jadi seperti posisi pasien dalam kompleks syamanisme, yang tidak jelas juntrung sakitnya dan tidak mampu membahasakannya, kecuali dengan jalan menerima pembahasaan seorang syaman yang diterima oleh masyarakatnya. Pengalaman patologis si pasien itu tak terperikan, seperti tidak ada kata yang tepat untuk mengartikulasikanya, sementara bahasa ‘kolektif’ (omong kosong) yang keluar dari mulut syaman mungkin itu-itu saja, biasa-biasa normal. Pasien dalam situasi penuh arti yang tak terungkapkan, sementara kata-kata dalam tindak tanduk syaman menderas kurang arti. Pasien tidak dapat menyembuhkan diri sendiri karena tidak mampu menstrukturkan kegalauan yang menyakitkan ke dalam bahasa. Padahal syaman pun hanya dapat samara-samar saja memahami si pasien. Bahasa syaman menjadi sumber simbolisme sosial bagi pasien untuk menemukan koherensi-koherensi bagi sakit yang dialaminya, sehingga ia mampu mengintegrasikan pengalamannya yang menyimpang dan unik pada suatu sintesis yang normal (“kesembuhan”).3 B. PENYAJIAN Setelah mendapatkan penjelasan dari diskusi/dialog yang telah dilakukan bersama-sama, mahasiswa diharapkan dapat memahami pencarian identitas Indonesia yang ternyata bukan berasal dari asli milik dirinya, tetapi lebih pada merupakan hasil kreatif dari mengolah akulturasi yang terjadi antar etnis lokal di Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kebudayaan yang dinamis ini terus mengalami perkembangan sesuai dengan akulturasi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian mahasiswa diharapkan menemukan kunci mengenai bagaimana mengolah kreativitas dalam rangka mengembangkan kebudayaan untuk identitas Indonesia. Aktivitas: Diskusi Tugas: Mahasiswa diminta untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya dan membuat pertanyaan kritis atas pembacaannya serta terlibat aktif dalam diskusi di kelas. C. PENUTUP Tes formatif dan kunci tes formatif: mahasiswa diminta untuk membaca setiap materi sesuai topik bahasan setiap minggunya dan membuat pertanyaan kritis dari hasil membaca materi tersebut dan memberikan contoh yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Petunjuk penilaian dan umpan balik: Kriteria pertanyaan bernilai A: pertanyaan kritis yang merupakan hasil dari review materi serta memiliki bobot untuk berpikir secara reflektif terkait dengan isu sosial. Kriteria pertanyaan bernilai B: pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan di dalam materi. Kriteria pertanyaan bernilai C: hanya menyuguhkan review tanpa membuat pertanyaan kritis. Tindak lanjut: akumulasi nilai 3 Levi-Strauss meminjam istilah abreaksi dari kalangan psikologi untuk menjelaskan proses kesembuhan si pasien.