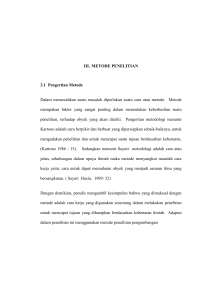Kesejarahan Agama REPUBLIKA, Kamis, 10 Juni 2010 pukul 10:51
advertisement
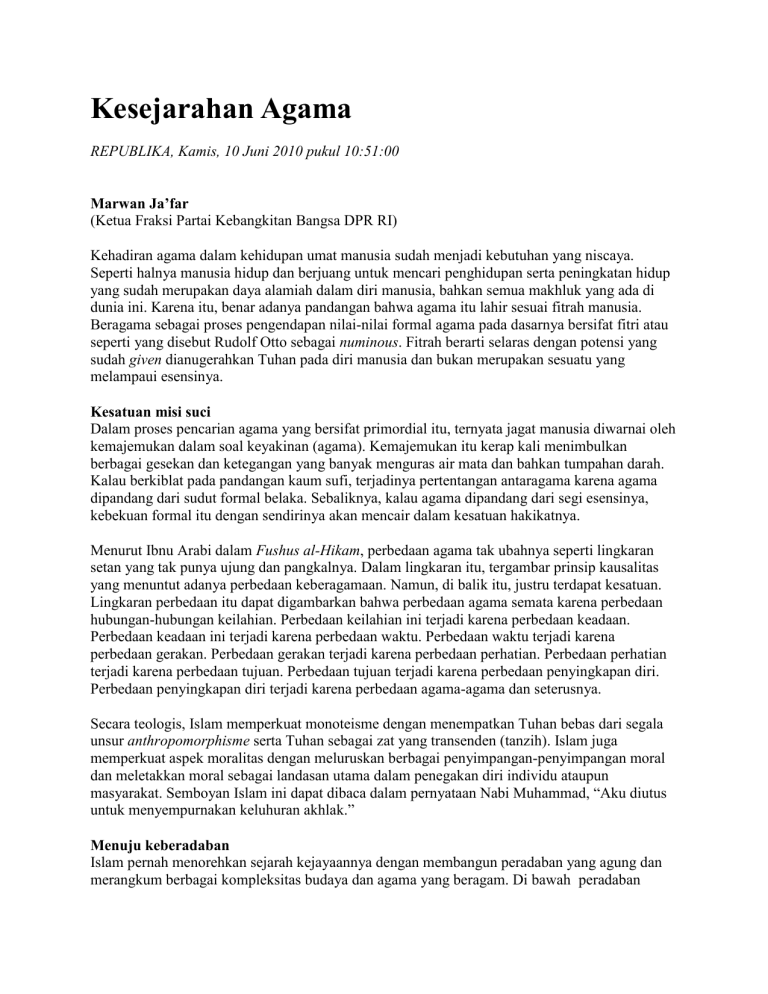
Kesejarahan Agama REPUBLIKA, Kamis, 10 Juni 2010 pukul 10:51:00 Marwan Ja’far (Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI) Kehadiran agama dalam kehidupan umat manusia sudah menjadi kebutuhan yang niscaya. Seperti halnya manusia hidup dan berjuang untuk mencari penghidupan serta peningkatan hidup yang sudah merupakan daya alamiah dalam diri manusia, bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini. Karena itu, benar adanya pandangan bahwa agama itu lahir sesuai fitrah manusia. Beragama sebagai proses pengendapan nilai-nilai formal agama pada dasarnya bersifat fitri atau seperti yang disebut Rudolf Otto sebagai numinous. Fitrah berarti selaras dengan potensi yang sudah given dianugerahkan Tuhan pada diri manusia dan bukan merupakan sesuatu yang melampaui esensinya. Kesatuan misi suci Dalam proses pencarian agama yang bersifat primordial itu, ternyata jagat manusia diwarnai oleh kemajemukan dalam soal keyakinan (agama). Kemajemukan itu kerap kali menimbulkan berbagai gesekan dan ketegangan yang banyak menguras air mata dan bahkan tumpahan darah. Kalau berkiblat pada pandangan kaum sufi, terjadinya pertentangan antaragama karena agama dipandang dari sudut formal belaka. Sebaliknya, kalau agama dipandang dari segi esensinya, kebekuan formal itu dengan sendirinya akan mencair dalam kesatuan hakikatnya. Menurut Ibnu Arabi dalam Fushus al-Hikam, perbedaan agama tak ubahnya seperti lingkaran setan yang tak punya ujung dan pangkalnya. Dalam lingkaran itu, tergambar prinsip kausalitas yang menuntut adanya perbedaan keberagamaan. Namun, di balik itu, justru terdapat kesatuan. Lingkaran perbedaan itu dapat digambarkan bahwa perbedaan agama semata karena perbedaan hubungan-hubungan keilahian. Perbedaan keilahian ini terjadi karena perbedaan keadaan. Perbedaan keadaan ini terjadi karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan gerakan. Perbedaan gerakan terjadi karena perbedaan perhatian. Perbedaan perhatian terjadi karena perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan terjadi karena perbedaan penyingkapan diri. Perbedaan penyingkapan diri terjadi karena perbedaan agama-agama dan seterusnya. Secara teologis, Islam memperkuat monoteisme dengan menempatkan Tuhan bebas dari segala unsur anthropomorphisme serta Tuhan sebagai zat yang transenden (tanzih). Islam juga memperkuat aspek moralitas dengan meluruskan berbagai penyimpangan-penyimpangan moral dan meletakkan moral sebagai landasan utama dalam penegakan diri individu ataupun masyarakat. Semboyan Islam ini dapat dibaca dalam pernyataan Nabi Muhammad, “Aku diutus untuk menyempurnakan keluhuran akhlak.” Menuju keberadaban Islam pernah menorehkan sejarah kejayaannya dengan membangun peradaban yang agung dan merangkum berbagai kompleksitas budaya dan agama yang beragam. Di bawah peradaban Islam, semuanya—termasuk agama—diberi ruang kebebasan ekspresi dan lebih mengedepankan kebersamaan yang kosmopolit dan universal dalam kendali nilai-nilai keilahian dan kemanusiaan. Kenyataan ini terwujud sebagai konsekuensi logis dari pengejawantahan dalam internalisasi nilai-nilai substansial ajaran Islam yang dilakukan oleh para pemimpin umat Islam terdahulu, terutama pada masa-masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Namun, dalam perkembangan berikutnya, lambat laun umat Islam mengalami kemunduran yang drastis. Kenyataan tragis ini disebabkan oleh umat Islam yang telah meninggalkan keteladanan dan pedoman yang diajarkan Nabi Muhammad dan yang diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin sebagai sebuah ideal type. Maka, yang menampak adalah adanya suatu “krisis legitimasi“ (azmah al-ta’sis) sebagai landasan substansial bagi pengembangan peradaban yang sempurna. Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, diakui kemajuan ilmu pengetahuan dalam masyarakat Muslim berkembang cukup tinggi dengan memberikan kebebasan pikir dan kreativitas yang besar. Di sisi lain, turut pula memunculkan krisis baru dengan menguatnya pergolakan politik dan perebutan kekuasaan. Pada masa-masa pemerintahan ini, bisa diungkapkan sebagai bentuk dari “pelegitimasian krisis” (ta’sis al-azmah). Krisis yang sudah terjadi setelah Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin menjadi membesar. Krisis yang ada ini berkelanjutan dalam estafet kenyataan umat Islam dewasa ini. Timbulnya penyempitan pemikiran dengan tersingkirnya sikap toleransi, hilangnya kreativitas, pembatasan pikir, dan taklid yang menguat justru mempertajam adanya “pelegitimasian krisis” tersebut. Lebih-lebih, hegemoni dunia Barat yang mengambil alih supremasi umat Islam ternyata malah tidak memberikan inspirasi baru terhadap umat Islam untuk memenggal ketertinggalannya. Bukannya tidak diakui, sekarang ini kesadaran umat Islam untuk maju sudah tampak kendati terlihat masih sporadis karena memang belum adanya kesatuan umat yang solid dan saling ukhuwah. Dalam kerangka turut membangun peradaban yang lebih baik pada masa kini, umat Islam seyogianya melakukan langkah-langkah yang lebih civilized. Pertama, perlunya penguatan terhadap aspek-aspek yang lebih mendalam melalui pemahaman keislaman yang berkait dengan religiositas, pluralis, dan humanis. Aspek-aspek tersebut sesungguhnya sudah termaktub secara inheren dalam ajaran Islam. Menjadi Muslim berarti menerapkan sisi-sisi ajaran keagamaan yang lebih menukik pada aspek tersebut. Bukan sebaliknya, justru menempatkan pemahaman keagamaan pada lingkup formalisasi yang rigid dan hanya bisa menimbulkan perilaku keagamaan yang kontraproduktif. Kedua, kebebasan pikir dan pembesaran sikap keterbukaan serta mau menerima kebinekaan. Bagi umat Islam, sudah seharusnya menggenggam semangat kembali pada keautentikan keteladanan sejarah yang menunjukkan keterbukaan dan kebebasan sebagaimana telah diteladankan para pendahulu. Nah, dengan demikian, keberanekaan termasuk masalah keyakinan tidaklah menjadi kendala dalam membangun suatu peradaban universal (tsaqafah wa al-hadharah) yang mampu mengayomi dan memberi arti hakiki kepada umat manusia. SUMBER: http://koran.republika.co.id/koran/24


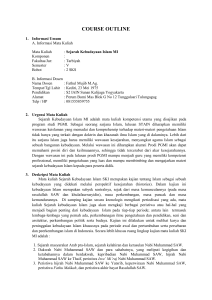

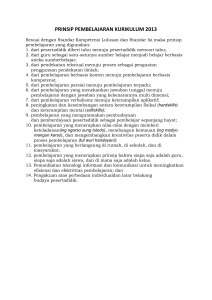




![[PDF] Contoh Draft Modul](http://s1.studylibid.com/store/data/004323240_1-df9e55ec9dabe7196b64ecb0cc16640c-300x300.png)