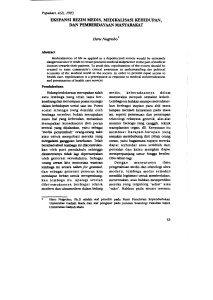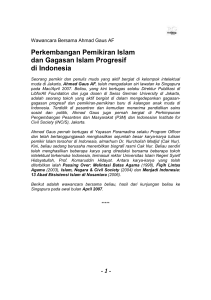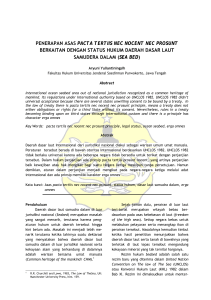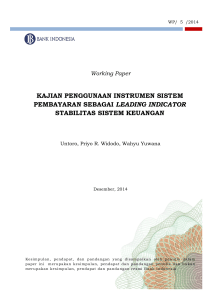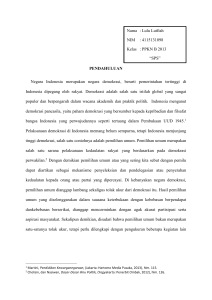Negara, Masyarakat Sipil dan Demokrasi: Sketsa Hibriditas Oleh
advertisement
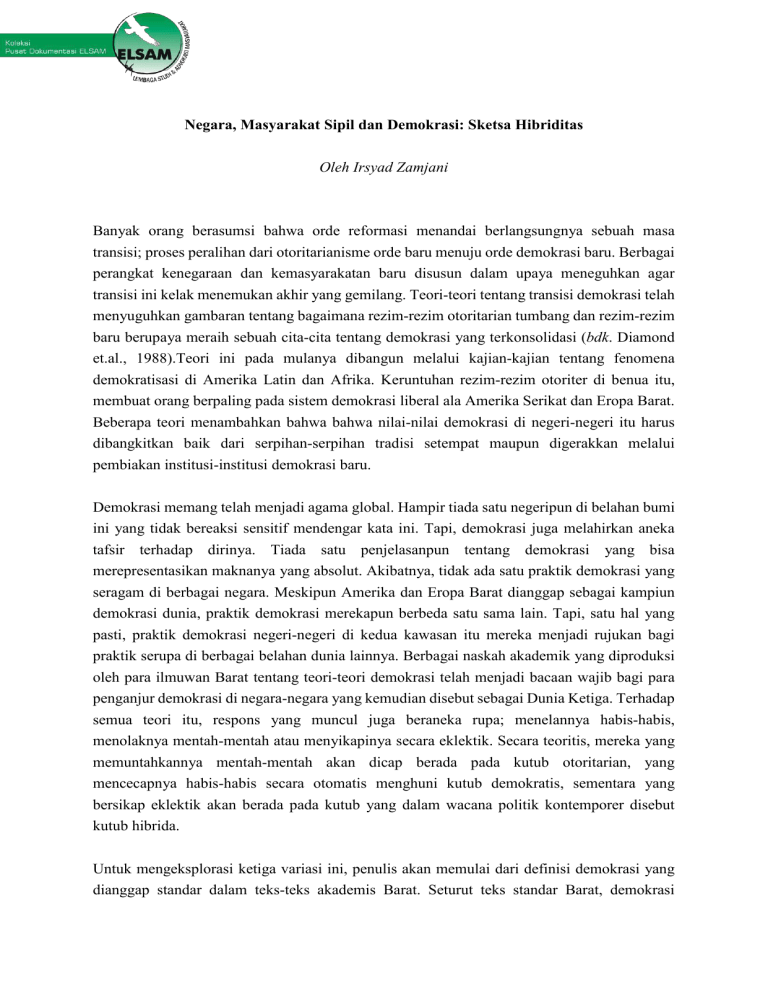
Negara, Masyarakat Sipil dan Demokrasi: Sketsa Hibriditas Oleh Irsyad Zamjani Banyak orang berasumsi bahwa orde reformasi menandai berlangsungnya sebuah masa transisi; proses peralihan dari otoritarianisme orde baru menuju orde demokrasi baru. Berbagai perangkat kenegaraan dan kemasyarakatan baru disusun dalam upaya meneguhkan agar transisi ini kelak menemukan akhir yang gemilang. Teori-teori tentang transisi demokrasi telah menyuguhkan gambaran tentang bagaimana rezim-rezim otoritarian tumbang dan rezim-rezim baru berupaya meraih sebuah cita-cita tentang demokrasi yang terkonsolidasi (bdk. Diamond et.al., 1988).Teori ini pada mulanya dibangun melalui kajian-kajian tentang fenomena demokratisasi di Amerika Latin dan Afrika. Keruntuhan rezim-rezim otoriter di benua itu, membuat orang berpaling pada sistem demokrasi liberal ala Amerika Serikat dan Eropa Barat. Beberapa teori menambahkan bahwa bahwa nilai-nilai demokrasi di negeri-negeri itu harus dibangkitkan baik dari serpihan-serpihan tradisi setempat maupun digerakkan melalui pembiakan institusi-institusi demokrasi baru. Demokrasi memang telah menjadi agama global. Hampir tiada satu negeripun di belahan bumi ini yang tidak bereaksi sensitif mendengar kata ini. Tapi, demokrasi juga melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Tiada satu penjelasanpun tentang demokrasi yang bisa merepresentasikan maknanya yang absolut. Akibatnya, tidak ada satu praktik demokrasi yang seragam di berbagai negara. Meskipun Amerika dan Eropa Barat dianggap sebagai kampiun demokrasi dunia, praktik demokrasi merekapun berbeda satu sama lain. Tapi, satu hal yang pasti, praktik demokrasi negeri-negeri di kedua kawasan itu mereka menjadi rujukan bagi praktik serupa di berbagai belahan dunia lainnya. Berbagai naskah akademik yang diproduksi oleh para ilmuwan Barat tentang teori-teori demokrasi telah menjadi bacaan wajib bagi para penganjur demokrasi di negara-negara yang kemudian disebut sebagai Dunia Ketiga. Terhadap semua teori itu, respons yang muncul juga beraneka rupa; menelannya habis-habis, menolaknya mentah-mentah atau menyikapinya secara eklektik. Secara teoritis, mereka yang memuntahkannya mentah-mentah akan dicap berada pada kutub otoritarian, yang mencecapnya habis-habis secara otomatis menghuni kutub demokratis, sementara yang bersikap eklektik akan berada pada kutub yang dalam wacana politik kontemporer disebut kutub hibrida. Untuk mengeksplorasi ketiga variasi ini, penulis akan memulai dari definisi demokrasi yang dianggap standar dalam teks-teks akademis Barat. Seturut teks standar Barat, demokrasi diartikan sebagai cara mengelola pemerintahan dan partisipasi warganegara di dalamnya. Salah satu teori dominan tentang demokrasi yang jamak diterima dalam wacana demokrasi Barat adalah teori yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Menurut Dahl, karakteristik inti dari demokrasi memuat tiga hal. Pertama, adanya persaingan yang sehat untuk meraih posisi-posisi dalam pemerintahan; kedua, partisipasi warganegara dalam memilih para pemimpin politik dan; ketiga, terselenggaranya kebebasan sipil dan politik, termasuk terjaminnya hak-hak asasi manusia (Martinussen, 1997: 195). Rezim-rezim politik yang tidak memenuhi ketiga persyaratan ini dapat dikategorikan sebagai rezim otoritarian, sementara mereka yang telah dengan sempurna memenuhinya dapat dianggap telah demokratis. Selanjutnya muncul pertanyaan tentang bagaimanakah “hukumnya” rezim-rezim yang menerapkan hanya sebagian (entah kecil ataupun besar) dari ketiganya; atau mengakomodasi semua persyaratan namun tidak sepenuhnya menerapkannya? Rezim Hibrida Para ilmuwan politik seperti Terry Lynn Karl, Friedbert W Rüb dan Heidrun Zinecker (2007) mengajukan tesis baru tentang rezim hibrida. Mereka berupaya mencari titik terang dalam ruang abu-abu antara demokrasi dan otoritarianisme. Menurut Karl, rezim hibrida muncul sebagai persoalan transisi. Dia mengamati fenomena transisi demokrasi di Amerika Tengah di mana perubahan rezim belum diiringi perubahan pemerintahan yang oligarkis. Kondisi ini yang ia sebut sebagai hibriditas. Hibriditas akan berakhir manakala konsolidasi demokrasi telah tercapai. Rub mengajukan pandangan yang berbeda. Menurutnya, rezim hibrida adalah tipe yang bersifat unik dan tidak terkait sama sekali dengan masalah transisi demokrasi. Rezim hibrida adalah buah dari kombinasi dikotomik antara dua karakteristik: di satu sisi adalah demokrasi (dengan pemilu yang bebas beserta aturan hukum yang mengikat) dan, di sisi lain, otoritarianisme (dengan struktur pemerintahan formal yang tidak pasti dan akses pada pemerintahan yang tidak dibatasi oleh hukum). Rezim model ini bisa berlangsung di manapun dan kapanpun. Sementara itu, Zinecker menyebut pendapat kedua pendahulunya tersebut bersifat teleologis. Rub, menurutnya, secara implisit menyatakan bahwa jalan menuju demokrasi yang ditempuh oleh bekas rezim otoritarian diinterupsi oleh rezim hibrida. Ia pun hanya menggabungkan kedua segmen lama (otoritarianisme) dan baru (demokrasi) sebagai satu tipe baru, tanpa menelaah kompleksitas rezim hibrida itu sendiri yang, menurut Zinecker, bisa saja terdiri dari segmen-segmen non-demokratis dan non-otoritarian sekaligus. Atas dasar itu, Zinecker kemudian mengajukan tesisnya sendiri tentang rezim hibrida. Ia memberikan lima kriteriauntuk membangun apa yang disebutnya model demokrasi/otoritarian dan non-demokrasi/non-otoritarian. Agar sebuah rezim disebut (tidak) demokratis, ia harus memiliki lima hal: Pertama, pemerintahan (non-) sipil. Hal ini untuk menggusur pemerintahan militer dan menegakkan supremasi sipil atas militer. Kedua, (non-) poliarki. Ia berfungsi untuk meluruhkan kemungkinan otoritarian dari rezim berpemerintahan sipil dengan menegakkan suatu rezim demokratis-representatif. Versi non-demokratis dari dua segmen pertama ini, pemerintahan non-sipil dan non-poliarki, bisa menggiring pada tampilnya rezim otoritarian. Tapi, tiga segmen sisanya berikut ini dalam versi non-demokratisnya tidak serta merta merefleksikan otoritarianisme, namun mungkin menjadi basis bagi suatu bentuk nonotoritarian dari sebuah rezim non-demokratis. Ketiga, (tidak) adanya aturan hukum (rule of law). Ini membedakan rezim liberal dan non-liberal. Keempat, ke(bi)adaban ([non-] civility). Penghapusan kekerasan yang dilakukan segmen non-negara dari sebuah rezim dengan menegakkan legitimasi monopoli negara atas penggunaan kekuatan dan kekerasan. Kelima, eksklusi/inklusi politik. Penghapusan segmen rezim yang memiliki watak politik eksklusif agar terbuka partisipasi yang tak terbatas dan tanpa kekerasan dari semua kekuatan politik. Singkatnya, adanya sebuah rezim demokratis-parsipatoris dan masyarakat sipil yang otonom. Yang menarik dari kajian Zinecker adalah analisisnya tentang civil society sebagai satu bagian dari pembentuk rezim hibrida. Rezim politik menyangkut gaya pemerintahan. Ia tidak identik dengan negara; ia bahkan melampaui negara. Maka, kajian tentang rezim tidak hanya menyangkut kajian tentang relasi antar-institusi negara, namun juga menelaah hubungan antara negara dan masyarakat sipil dan, di sisi lain, hubungan di antara warganegara aktif secara politik namun hidup tanpa bergantung pada negara. Agar pemerintahan berjalan efektif, sebuah rezim harus memiliki jangkauan pada masyarakat sipil. Bagi Zinecker, tidak ada pemerintahan yang efektif jika dalam masyarakat sipilnya masih terdapat aktor-aktor yang bisa memveto kekerasan. Dalam rezim non-otoritarian, tindak kekerasan terbesar muncul dari aktor-aktor non-negara yang berada di dalam masyarakat sipil. Keadaban sebuah rezim politik dengan demikian bertumpu pada keadaban masyarakat sipil. Demokrasi yang berlangsung pada level negara tidak selalu berjalan seiring dengan demokrasi pada tingkat masyarakat sipil. Zinecker ingin meluruhkan teori-teori yang selalu melihat masyarakat sipil secara normatif dan mengabaikan telaah yang lebih analitis. Ia ingin melihat masyarakat sipil dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Selama ini terdapat pemisahan antara negara yang politis dan masyarakat sipil yang non-politis. Negara yang politis cenderung “buruk” atau tidak beradab (uncivilized) dan masyarakat sipil terkesan “baik” atau beradab (civilized). Bagi Zinecker, masyarakat sipil adalah semua struktur dan asosiasi yang dibentuk oleh aktoraktor yang mengisi ruang societal antara keluarga, ekonomi dan negara. Masyarakat sipil bersifat politis dan merupakan bagian dari rezim politik. Ia bisa mencakup segmen demokratis dan non-demokratis, beradab dan biadab sekaligus. Masyarakat sipil yang demokratis adalah pula yang beradab (civilized), namun masyarakat sipil yang beradab tidak mesti demokratis. Wacana tentang rezim hibrida menarik diperbincangkan dalam konteks Indonesia; apakah ia relevan? Akan tetapi, soal pokok yang terlebih dahulu harus dijawab adalah bagian manakah dari rezim-rezim di Indonesia yang hendak disangkutkan dengan perdebatan ini? Jawaban dari pertanyaan itu terkait dengan posisi terhadap konsep hibriditas itu sendiri. Menurut penulis, hibriditas yang ditawarkan oleh Zinecker tak ubahnya bersifat teleologis, seperti halnya yang ditawarkan oleh dua orang pendahulunya. Zinecker hanya lebih banyak mengakomodasi kompleksitas, namun tetap mempertahankan konsep-konsep yang lebih merupakan klaimklaim tentang esensi seperti demokrasi dan otoritarianisme. Zinecker memang tidak menyebut secara spesifik di tanah mana demokrasi sejati telah berhasil disemai. Namun, dalam paparannya ia selalu mengulang-ulang dikotomi antara negara-negara maju dan berkembang dengan mengisyaratkan yang pertama sebagai demokratis dan yang terakhir sebagai otoritarian atau hybrid. Akan tetapi, di sisi yang lain, jawaban dari pertanyaan ini juga harus diletakkan pada konteks spasial dan temporal yang paling relevan dan paling disorot dari Indonesia terkait dengan pengalaman demokratisasinya. Posisi hibriditas yang menjadi afinitas penulis adalah versi yang banyak dikemukakan oleh teoritisi pascakolonial. Hibriditas dalam model ini muncul sebagai strategi dan praktik kebudayaan. Ia senantiasa berada pada ambang liminal yang menghindarkan diri dari setiap kategorisasi yang bersifat biner; demokratis versus otoritarian, maju versus berkembang dan sebagainya. Ia menghuni apa yang oleh Homi Bhaba disebut ruang ketiga dari setiap oposisi biner. Hibriditas mengatakan bahwa semua kategori budaya senantiasa bersifat transnasional dan translasional. Bersifat transnasional karena wacana-wacana pascakolonial kontemporer berakar pada sejarah khusus tentang perpindahan budaya, baik lewat perbudakan, ‘pelancongan’ dengan misi pemeradaban, migrasi penduduk Dunia Ketiga ke Barat setelah Perang Dunia II, atau lalu lintas para pengungsi politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri-negeri Dunia Ketiga. Bersifat translasional karena sejarah-sejarah spasial tentang perpindahan tersebut – sekarang diikuti dengan ambisi-ambisi territorial dari teknologi media global – menjadikan persoalan tentang bagaimana budaya menandai, atau apa yang ditandai oleh budaya, sebagai sebuah isu yang kompleks (Bhaba… ). Demokrasi-pun bersifat transnasional dan translasional. Apa yang oleh Amerika disebut sebagai kampanye demokrasi, misalnya, bagi bangsa-bangsa lain tak lebih sebagai model baru otoritarianisme. Penulis berpendapat bahwa tidak ada sebuah rezim yang selamanya demokratis atau otoritarian, entah di bangsa-bangsa Barat maupun Timur. Karena merupakan sebuah praktik kebudayaan, analisis tentang hibriditas sejatinya tidak terletak pada analisis normatif-institusional, namun dalam praktik yang dilakukan oleh aktor-aktornya. Meskipun bersikap kritis terhadap pendekatan Zinecker, penulis melihat bahwa ia telah menunjukkan adanya ruang ketiga hibriditas dengan kemungkinan hadirnya suatu rezim non-demokratis yang berkarakter nonotoritarian. Dalam sejarah Indonesia kontemporer, isu ini akan lebih relevan jika dikaitkan dengan perkembangan Indonesia pasca-Reformasi. Pasca keruntuhan rezim orde baru yang oleh banyak pengamat disebut sebagai rezim pembangunan represif-otoritarian (lihat Herbert Feith, 1980), Indonesia memang segera menentukan langkahnya menempuh jalan demokratisasi. Dalam standar teks demokrasi, Indonesia relatif telah terbebas dari otoritarianisme. Persyaratan pertama dan kedua yang diajukan Zinecker telah dipenuhi oleh Indonesia. Supremasi sipil atas militer dan kekuasaan yang representatif relatif telah terpenuhi, meskipun tidak sepenuhnya. Tidak ada lagi kekuatan mayoritas. Dua kali pemilu yang digelar pada tahun 1999 dan 2004 menunjukkan puspa ragam kekuatan politik baru, meski tidak benar-benar baru. Pada pemilu pertama, PDI-P, yang merupakan metamorforsa dari PNI orde lama dan PDI orde baru, menjadi partai pemenang pemilu. Meski demikian, kadernya kalah dalam permainan politik di MPR memperebutkan kursi presiden. Pemenangnya justru kader dari partai pemenang keempat, PKB. Namun, presiden terpilih inipun kemudian terjungkal dalam permainan politik yang sama. Elitisme memang tidak bisa terkontrol pada tahap awal demokrasi baru ini. Demokrasi dirayakan penuh euforia. Partai-partai bekerja sama secara radikal dan beroposisi secara fundamental pula. Abdurrahman Wahid dipilih dan dijatuhkan oleh orang-orang yang persis sama. Pada tahap selanjutnya, aturan main pun diubah. Konstitusi, kitab suci yang diagungkan sebelumnya, bahkan sudah empat kali diamandemen. Sistem pemilu diubah dari proporsional menjadi semacam perpaduan antara distrik- proporsional. Hal ini untuk memperagam rekrutmen elite bukan hanya atas basis keparpolan, namun juga representasi kedaerahan. Apalagi selanjutnya diatur pembentukan lembaga semacam senat, DPD, demi hanya menyiasati status MPR yang keberadaannya terancam setelah beberapa kewenangannya terpangkas. Presiden memang tidak lagi dipilih MPR, namun dipilih oleh langsung oleh rakyat. DPD-pun tidak memiliki tugas yang jelas layaknya senat dalam sistem demokrasi modern. Pada pemilu 2004, bekas kekuatan politik rezim otoritarian terguling, Partai Golkar, berhasil memenangkan pemilu, meskipun bukan (lagi) sebagai mayoritas tunggal. Namun, yang mengejutkan, presiden pilihan langsung rakyat bukan berasal dari partai pemenang, melainkan dari partai yang sama sekali baru, Partai Demokrat. Namun, drama politik belum berhenti. Elitisme belum pula pudar. Partai-partai besar di DPR, disponsori PDI-P, Partai Golkar dan PPP, segera membangun aliansi oposisi yang menamakan diri Koalisi Kebangsaan. Partai penguasa yang bersikap panik dan reaktif membangun tandingannya; koalisi kerakyatan. Peta koalisipun rontok setelah penguasa berhasil merebut kepemimpinan politik di partai pemenang pemilu, Partai Golkar. Penguasa juga diuntungkan dengan konflik-konflik internal yang terjadi pada beberapa partai besar seperti PPP dan PKB. Konflik itu justru membuat partai-partai tersebut mendekat pada kekuasaan. Akibatnya, di satu sisi, persebaran elite politikpun menjadi timpang. Pemerintah mengalami pengeroposan dari dalam karena banyaknya kekuatan politik yang bermain di dalamnya. Dalam kasus ini, memang rezim otoritarian telah berlalu, tapi rezim yang efektif tidak kunjung nampak pula. Terkait dengan kriteria ketiga, adanya supremasi hukum, pada tarap permukaan nampak berjalan. Tapi, penegakan hukum lebih mirip sebagai sebuah etalase politik daripada sebuah kinerja mandiri dan terlembaga yang dilakukan oleh para penegak hukum. Beberapa kasus besar yang ditangani para penegak hukum saat ini, misalnya, lebih banyak menjerat para elite penguasa lama yang notabene sekarang menjadi kekuatan oposisi. Beberapa orang yang terindikasi kasus pelanggaran hukum tertentu, namun berhasil merapat ke kekuasaan terjamin “keselamatan” mereka. Model penegakan hukum semacam itu hanya semakin membuat orang mengembangkan taktik-taktik baru pelanggaran hukum. Jika dahulu, misalnya, budaya korupsi menghuni ranah ketaksadaran, sekarang ia telah menjadi bagian dari praktik kebudayaan yang dilakukan secara sadar. Ia muncul dalam kesadaran ganda aparat birokrasi; sebagai aparatus negara modern dan kuasi aristokrat. Karakter beambtenstaat warisan kolonial memang masih menyisakan persoalan (bdk. Sutherland dalam Kayam, 1989). Bagi para penyelenggara pemerintahan yang berpenghasilan paspasan namun berpenampilan selaksa aristokrat, korupsi adalah cara produksi alternatif dan spekulatif. Selain itu, adanya supremasi hukum di sini lebih banyak berimplikasi pada rapuhnya kuasa negara, terutama, dalam mengontrol persaingan ekonomi. Selain karena perilaku koruptif aparat, para pengusaha kaya juga selalu menyewa pengacara papan atas yang mampu menyiasati tafsiran pasal-pasal sehingga meloloskan mereka dari jerat hukum. Kriteria keempat menyangkut keadaban sebuah rezim. Sebuah rezim disebut beradab manakala terjadi perpaduan antara civilized state dan civilized civil society. Negara beradab ketika ia memiliki legitimasi atas monopoli penggunaan kekuatan dan kekerasan. Secara hukum TNI dan Polri memiliki legitimasi itu. Persoalan terjadi para ranah masyarakat sipil. Di beberapa tempat masih terdapat unsur-unsur dari masyarakat sipil yang gemar memobilisasi kekuatan melakukan razia bahkan penghakiman sepihak tanpa aparat mampu mencegahnya. Kehadiran laskar-laskar yang seringkali mengatasnamakan agama tertentu dan melakukan aksi-aksi sepihak masih menjadi pemandangan yang menonjol baik di pusat maupun terutama di daerahdaerah. Konflik-konflik komunal di Kalimantan, Ambon, Poso dan Papua juga melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil yang bersenjata. Beberapa analis memang menyebutkan bahwa aparat berwenang memiliki keterlibatan baik dalam pemersenjataan maupun pembiaran aktivitas mereka. Namun, hal itu tidak mengurangi krisis keadaban yang terjadi dalam masyarakat sipil. Kriteria keempat tersebut memiliki korelasi dengan kriteria kelima tentang inklusifitas/eksklusifitas politik sebuah rezim. Dalam rezim reformasi, partisipasi publik memang dibuka secara lebar dan dijamin oleh konstitusi. Meski demikian, masih terdapat segmen tertentu dari rezim baik dari level negara maupun masyarakat sipil yang berwatak eksklusif dan membatasi partisipasi warganegara lainnya. Fatwa-fatwa penyesatan yang dilakukan oleh MUI dan diamini oleh berbagai ormas keagamaan adalah contoh dari pengekangan atas partisipasi demokratis. Hal itu ditambah dengan aksi penyerbuan massa terhadap para pengikut ajaran-ajaran tertentu yang tidak sesuai denganmainstream ajaran tertentu. Kampanye-kampanye penegakan syariat Islam oleh beberapa elemen umat Islam dalam beberapa hal juga merupakan kasus yang sama. Masyarakat Sipil Pascafordisme Jika menilik kategori standar mengenai masyarakat sipil, memang tidak pada tempatnya meletakkan organisasi-organisasi keagamaan dan etnisitas pada kategori tersebut (lihat Allan). Tapi, tanpa memasukkannya orang tidak akan mendapatkan penjelasan apapun tentang masyarakat sipil di Indonesia. Muhammad AS Hikam telah menjelaskan dengan baik peran strategis ormas-ormas keagamaan sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjadi pendorong demokratisasi di Indonesia. Varian lain dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia, tentu saja, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mulai berkecambah sejak tahun 1970-an, ormas kepemudaan dan organisasi intelektual. Cerita-cerita tentang organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia era orde baru sarat dengan cerita-cerita kepahlawanan yang romantis. Mereka tampil sebagai penggerak barisan oposisi dan sponsor kemandirian masyarakat. Meskipun, banyak pula dari mereka yang menjadi komprador negara, kepanjangan tangan negara di masyarakat atau bahkan bermuka dua. Watak organisasi masyarakat sipil di Indonesia mulai menampak pascareformasi, terutama, ketika terjadi migrasi besar-besaran aktivis organisasi masyarakat sipil menjadi politisi dan pejabat publik. Agenda demokratisasi yang menjadi misi reformasi-pun semakin gencar disorongkan. Dan, rezim hibrida-pun lahir dari perdebatan mereka. Namun, rezim hibrida selanjutnya melahirkan juga hibrida baru dalam organisasi masyarakat sipil. Penting dicatat, jalan demokrasi, selain pilihan, adalah juga prasyarat yang diberikan untuk mengakhiri krisis ekonomi. Hibriditas dalam konteks Indonesia, dengan demikian, harus diletakkan dalam konteks upaya Indonesia menyelesaikan krisis ekonominya yang sebagian besar dilakukan dengan menerima resep-resep tawaran IMF dan Bank Dunia. Indonesia sejatinya tengah mengulang kembali sejarah negara-negara Afrika dan Amerika Latin di awal 1990-an yang menempuh transisi demokrasi mereka melalui program penyehatan ekonomi. Dalam paket resep itu, demokratisasi memang menjadi prasyarat utama yang digariskan oleh lembaga-lembaga tersebut. Demokratisasi, dalam hal ini, menyangkut pemenuhan prosedurprosedur penyelenggaraan kekuasaan tertentu; mulai dari pemilu demokratis hingga good governance (bdk. Abrahamsen, 2004). Pada puncaknya, demokratisasi dimuarakan pada liberalisasi; the best government is the least government. Partisipasi publik dibuka lebar-lebar dengan menekan intervensi negara pada batas minimal; dunia usaha harus dibangkitkan kembali dengan menyemarakkan pasar investasi; beberapa perusahaan negara perlu disehatkan dengan melakukan privatisasi dan; aturan hukum dibuat secara ketat untuk menjamin persaingan ekonomi yang sehat. Demokratisasi dalam konteks itu bagi sebagian besar organisasi masyarakat sipil di Indonesia memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, ia adalah sebuah keharusan sejarah, namun di sisi lain, ia tidak diharapkan karena berkembang melalui intervensi asing. Namun, terlepas dari semua perdebatan tentang liberalisasi, masyarakat sipil-pun “dipaksa” untuk menempatkan diri dalam arus liberalisasi yang berlangsung. (Diper)lemahnya peran negara secara otomatis membuat masyarakat sipil mereguk keuntungan tersendiri. Di satu sisi, lembaga-lembaga donor asing lebih melirik mereka daripada negara. Di sisi lain, negara juga membutuhkan mereka demi mengais legitimasi dan menyewa tenaga professional mereka. Kucuran donor asing semakin melimpah ruah dan proyek pemerintah pun tak pernah sepi. Organisasi masyarakat sipil inipun bahkan melakukan hal-hal yang semestinya menjadi tugas negara; mulai penghitungan hasil pemilu hingga pengentasan kemiskinan. Merekapun juga mengambil alih banyak tugas-tugas legislatif dan yudikatif; mulai pengawasan kinerja pemerintah hingga investigasi kasus-kasus korupsi. Mereka menyadari posisi strategis ini, sehingga, tak heran jika pascareformasi, industri LSM pun semakin berkecambah. Maka, alih-alih menyelesaikan misinya sebagai motor gerakan sosial, organisasi masyarakat sipil justru berkembang menjadi industri jasa modern. Mereka memiliki kantor-kantor yang dikelola secara professional. Bagi institusi-institusi yang mapan, para aktivisnya mengisi lapisan kelas-kelas borjuis baru. Mereka tidak hanya bekerja di satu institusi, namun pada banyak lainnya. Lingkup kerja mereka tidak lagi nasional, namun dalam sistem jaringan transnasional. Institusi masyarakat sipil ini memang menjadi cara produksi kapitalis baru yang mulai meninggalkan sistem produksi massal a la perusahaan manufaktur. Mereka menyemarakkan apa yang disebut sebagai generasi kapitalisme pascafordisme dengan paradigma flexible production (Thompson…). Dalam pascafordisme terjadi transformasi bukan hanya tentang bagaimana kita membuat sesuatu, namun juga bagaimana kita hidup dan apa yang kita konsumsi. Kerja dalam cara ini adalah sesuatu yang integral dengan totalitas kehidupan; orang tidak dilokalisir dalam ruang bersekat atau dibatasi oleh waktu kerja, tapi dibiarkan menentukan ritmenya sendiri. Tidak seperti produksi massal yang mempekerjakan buruh tidak terampil, produksi fleksibel menuntut para pekerja yang terpelajar dan memiliki kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Produksi fleksibel terutama muncul dalam lembaga-lembaga penyedia jasa; klinik, firma hukum, jasa konsultan, institusi pendidikan dan sebagainya. Organisasi masyarakat sipil dapat dimasukkan di dalamnya dengan pertimbangan karakteristik yang sama. Perbedaannya hanya pada dimensi transaksinya; instansi profit pada umumnya melakukan transaksi horizontal dengan nasabah, customer atau klien, sementara ormas atau LSM bertransaksi secara vertikal dengan donator. Di sini, kemudian muncul persoalan tentang keadaban (civility) dan kewarganegaraan (civic) yang memberi karakter bagi masyarakat sipil. Keadaban tidak lagi sekadar menyangkut isu-isu kekerasan, namun juga isu kemandirian; sementara kewarganegaraan menyangkut tanggung jawab politis sebagai warganegara. Kedua isu saling bertautan satu sama lain. Kemandirian terhadap negara tidak lantas digantikan pada ketergantungan pada yang lain sehingga mengikis tanggung jawab kewarganegaraannya. Dan, organisasi masyarakat sipil di negeri ini, terbukti dihimpit oleh tekanan negara dan swasta. Secara ekonomi, organisasi masyarakat sipil tersebut adalah organisasi pemburu rente; mereka bergantung pada donor mana yang bersedia menerima program-program mereka atau memberikan proyek-proyek baru bagi mereka. Namun, secara politis, ada empat posisi yang jamak dipilih. Pertama, berkolaborasi dan menerima proyek-proyek pemerintah secara total. Kedua, menghindari kerjasama dengan negara dengan lebih membuka diri pada swasta. Ketiga, menolak kerja sama dengan negara maupun dengan pihak swasta tertentu, semisal lembaga donor internasional atau perusahaan industri berat. Keempat, menerima kerja sama dari manapun secara professional tanpa harus terikat. Pada umumnya, ormas dan NGO memilih posisi keempat. Dan, pada posisi ini, berbagai ideologi dan idealisme diperdebatkan, ditata ulang bahkan ditransgresikan. Di sini kita sampai pada perdebatan kita tentang hibriditas dan liminalitas. Apakah dengan memungut donasi swasta asing, orang telah menggadaikan kewarganegaraannya? Apakah dengan bekerjasama dengan pemerintah, orang telah membuang kemandiriannya? Apakah dengan menerima keduanya, orang telah melupakan idealismenya? Tiada satupun yang menyangkal bahwa diskursus tentang masyarakat sipil sendiri bukanlah diskursus yang tercipta karena pengalaman domestik, namun diskursus impor yang diapropriasi oleh pengalaman lokal. Di tempat asalnya, masyarakat sipil bersifat mandiri (dari negara) karena hidup beriringan dengan berfungsinya ekonomi pasar kapitalis. Organisasi-organisasinya hidup dari bisnis mandiri, seperti media, atau dari kesadaran filantropis masyarakatnya yang tinggi. Sementara, saat datang ke negeri-negeri berkembang, ide-ide ini dicangkokkan pada ragam organisasi yang ada. Seperti kita persaksikan, iapun selanjutnya dirawat oleh kapitalisme pasar; baik domestik maupun asing. Ia dipromosikan dalam misi liberalisasi dan demokratisasi yang salah satu idenya adalah berkurangnya intervensi negara (terhadap pasar). Namun soalnya, diskursus nasionalisme belumlah pudar seluruhnya. Di satu sisi, lembaga-lembaga kapitalis asing masihlah merupakan representasi dari kepentingan entitas-entitas tertentu berlabel bangsa, negara atau kawasan. Di sisi lain, berkurangnya intervensi negara, di sini lebih berarti lemahnya kekuatan dan kekuasaan negara. Karena soalnya selalu kapitalisme, maka, pada tahap domestik, para kapitalis nasional lebih berkuasa daripada institusi tertinggi negara. Dari perombakan kabinet SBY sejak edisi pertama hingga terakhir, misalnya, orang dapat melihat betapa kokohnya posisi Aburizal Bakrie, raja lumpur yang anak perusahaannya telah terbukti – secara sangat meyakinkan sekali – mengubur puluhan desa di Sidoarjo. Namun persoalan-persoalan di atas tidak selalu bekerja dalam aras logika tunggal, ia bersifat sangat kompleks. Dan, masyarakat sipil hibrida selalu menyiasatinya. Sebagaimana pasar yang bekerja mencapai tujuannya sendiri, masyarakat sipil inipun pada akhirnya berkembang menggapai identitasnya sendiri. Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Departemen Sosiologi UI