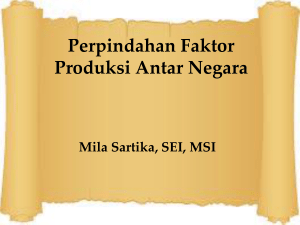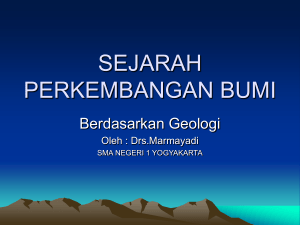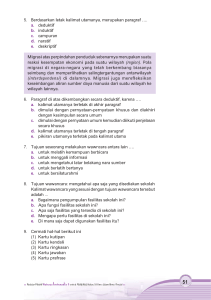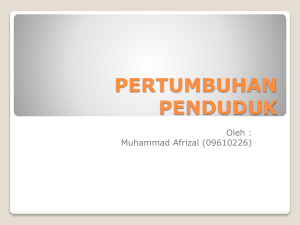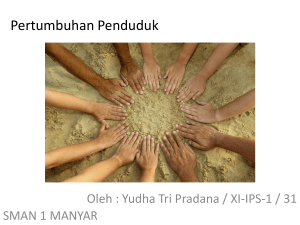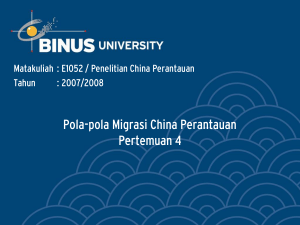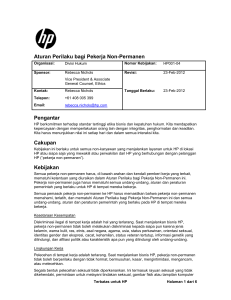1.4. Kegunaan Penelitian
advertisement

1 MAKALAH KOLOKIUM Nama Pemrasaran/NIM Departemen Pembahas 1 Dosen Pembimbing/NIP Judul Rencana Penelitian : : : : : Tanggal dan Waktu : Muhammad Indra/I34100075 Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Citra Dewi/I34100045 Dr. Ir. Ekawati Sri Wahyuni, MS/19600827 198603 2 002 Pengaruh Migrasi Sirkuler Terhadap Kondisi Sosial Rumah Tangga Petani (Kasus Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang) 7 Maret 2014, 10.00-11.00 WIB 1. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Dewasa ini problematika kependudukan di negara-negara sedang berkembang terutama di Indonesia menjadi hal yang sangat kompleks bagi pembangunan. Dinamika kependudukan akan selalu berkembang mengikuti perkembangan angka kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) serta terjadi perubahan dalam berbagai aspeknya, baik aspek jumlah, komposisi menurut jenis kelamin dan umur, pertumbuhan dan persebarannya. Sejalan dengan hal tersebut, menurut BPS tahun 2010 penduduk Indonesia terus bertambah dari waktu ke waktu. Ketika sensus pertama pada tahun 1961 dilakukan, jumlah penduduk Indonesia masih sekitar 97,1 juta jiwa, namun setelah hampir setengah abad berlalu, jumlah populasi penduduk Indonesia meningkat drastis dan telah mencapai 237,6 juta jiwa pada saat sensus 2010 dilakukan.1 Peningkatan jumlah penduduk ternyata sejalan dengan meningkatnya angka pertumbuhan angkatan kerja yang semakin lama semakin bertambah banyak namun tidak disejalan dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Dengan demikian terdapat suatu ketimpangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada. Mau tidak mau dengan kondisi tersebut menyebabkan banyak calon tenaga kerja baru sulit mendapatkan pekerjaan baik di sektor formal maupun di sektor informal karena persaingan yang sangat banyak. Hal yang serupa terjadi di sektor pertanian, ketersediaan lahan pertanian yang sudah demikian sempit sejalan dengan penduduk yang semakin padat. Namun masih banyak masyarakat khususnya kaum petani yang menggantungkan perekonomian rumah tangga pada lahan pertanian dan bekerja sebagai buruh tani di desanya maupun di desa lain yang berdekatan. Fakta menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tidak cukup mendapatkan akses pada tanah karena lahan-lahan pertanian telah dikuasai oleh para pemilik lahan yang sejumlah 0,2% atau kurang lebih 460 ribu orang dari total penduduk Indonesia pada tahun 2011 yang menguasai 56% aset nasional. Di dalam konsentrasi 56% aset ini, tidak kurang dari 62-87% dalam bentuk tanah.2 Hal-hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan mobilisasi di kalangan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain atau yang disebut dengan gerak penduduk (Shrylock dan Siegel 1973 dalam Rusli 2010:100). Migrasi sebagai salah satu bagian dari gerak penduduk telah membentuk suatu pola perpindahan penduduk (migrasi) di Indonesia yang dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas permanen (menetap di daerah tujuan) dan non-permanen (yang tidak menetap di daerah tujuan) dengan arah yang berubah (Ananta dan Chotib 1996). Migrasi permanen pada umumnya mempunyai ciri-ciri yakni terdapat suatu gerak perpindahan tempat tinggal penduduk yang secara menetap pada satu wilayah ke wilayah lainnya yang menjadi tujuan migrasi (Lee 1966 dalam Rusli 2010). Pada kota-kota besar (seperti Jakarta) yang menjadi daerah tujuan mobilitas permanen telah terjadi perambatan pada daerah sekitar kota tersebut (kota-kota seperti Bodetabek) yang menyebabkan menurunnya tingkat migrasi masuk pada kota besar tersebut namun telah 1 2 BPS. 2010. Hasil Sensus Penduduk 2010 Data Agregat per Provinsi. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia. Winoto J. 2011. Mengelola Pertanahan untuk Kemakmuran Rakyat. Majalah Bhumi Bakti. Edisi 10. Hal 24. 2 meningkatkan angka migrasi masuk ke daerah sekitarnya. Menurunnya migrasi masuk pada kota besar tersebut, diimbangi dengan meningkatnya mobilisasi non-permanen baik sirkuler maupun komutasi yang biasanya berciri jangka pendek, repetitif, atau siklikal, hal ini mempunyai suatu kesamaan dalam hal tujuannya yang memang sudah jelas tidak ingin untuk menetap secara permanen di daerah tujuan. (W Zelinsky dalam Rusli 2010:101). Fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota tersebut dapat menggambarkan bahwa di negara-negara sedang berkembang terutama di Indonesia kekuatan ekonomi masih terpusat di daerah perkotaan saja, sehingga dapat dicirikan oleh migrasi non-permanen dalam bentuk sirkulasi atau komutasi (Wahyuni 2000). Faktor-faktor yang berperan untuk mempengaruhi orang dalam melakukan migrasi sangat beragam dan kompleks karena migrasi merupakan proses yang secara selektif mempengaruhi setiap individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial, pendidikan dan demografi tertentu. Akibatnya mereka yang melakukan migrasi pada umumnya adalah para tenaga kerja yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu dan berasal dari lokasi yang memiliki kelebihan tenaga kerja juga berpenghasilan rendah menuju lokasi yang kekurangan tenaga kerja dan atau yang mampu memberikan upah lebih tinggi (Bandiono dan Salihar 1999 dalam Waridin 2002) dengan harapan dapat membuat mereka hidup lebih layak dari daerah asalnya. Beberapa penelitian sebelumnya mengenai migrasi menyebutkan bahwa alasan utama orang melakukan migrasi karena alasan ekonomi. Tentunya dengan tidak mengabaikan faktor budaya dan norma-norma masyarakat perdesaan setempat, telah terjadi pergeseran dalam strategi ekonomi masyarakat pedesaan yang semula hanya mengandalkan pertanian subsisten bergeser secara pasti menjadi ekonomi pasar yang selama ini dicirikan di perkotaan (sektor informal) melalui remittances migran sirkuler. Pengaruh migrasi terhadap pertanian dimulai saat adanya pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, seperti proporsi jumah tenaga kerja dibidang pertanian yang semakin berkurang karena sudah tidak ada minat bekerja di bidang pertanian atau semakin bertambah banyak tenaga kerja di bidang pertanian akibat tidak tersedianya lahan pertanian yang cukup untuk diolah. Pengalokasian waktu untuk kegiatan bertani juga semakin berkurang karena lebih banyak digunakan saat bekerja di tempat tujuan migrasi. Sehingga banyak petani yang melakukan migrasi desa kota untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang semakin lama semakin tidak dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan dari kegiatan bertani saja. Tidak hanya mempengaruhi terhadap sektor pertanian saja, melainkan juga berdampak pada pelaku utama dari pertanian tersebut yaitu petani. Kondisi sosial rumah tangga petani sedianya banyak yang berubah. Sehingga ini menjadi menarik untuk diteliti dalam mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam bidang sosial terutama pada tingkat pendidikan anak, pola jam kerja petani, peranan sosial di masyarakat dan pembagian kerja dalam rumah tangga petani. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi pengaruh dari migrasi sirkuler terhadap kondisi sosial rumah tangga petani. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu desa di Kabupaten Subang, yakni Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. 1.2. MASALAH PENELITIAN Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa alasan utama orang melakukan migrasi karena faktor ekonomi, namun selain faktor ekonomi terdapat beberapa faktor lain yang ikut b dalam fenomena migrasi sirkuler terhadap rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir. Sesuai dengan teori dorong – tarik atau Push – Pull Theory menurut Everett S. Lee (1966) dalam Mantra (1985), terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan migrasi. Lebih lanjut Lee menguraikan mengenai empat faktor yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan migrasi, yaitu faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, rintangan-rintangang yang menghambat serta faktor-faktor pribadi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan rumah tangga petani melakukan migrasi sirkuler di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan? 3 Pengaruh migrasi sirkuler pada rumah tangga di desa dapat memberikan peningkatan pendapatan dan perbaikan pada rumah tangga migran. Pengeluaran rumah tangga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun membuat kebutuhan rumah tangga semakin meningkat pula. Sehingga banyak calon migran memutuskan untuk bermigrasi dengan tujuan memperoleh pendapatan lebih. Pendapatan yang meningkat selanjutnya akan mempengaruhi status sosial dan mutu hidup rumah tangga (Refiani, 2006). Status sosial dan mutu hidup rumah tangga tersebut juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan anggota rumah tangga khususnya pendidikan anak. Selain itu, menurut Herdiana (1995) dalam Hermawan (2002), migrasi menimbulkan perubahan peranan dan tanggung jawab wanita, terutama pada saat kepala keluarga pergi ke kota atau melakukan migrasi sirkuler. Migrasi ini secara tidak langsung mempengaruhi kebiasaan dan pembagian kerja dalam rumah tangga di daerah asal. Namun, dengan melakukan migrasi desa kota dengan cara sirkulasi memungkinkan penduduk desa khususnya yang masih menjadi petani dapat mengerjakan pekerjaan pertanian sehingga pendapatan rumah tangga akan lebih baik (Hermawan 2002:3). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauhmana pengaruh migrasi sirkuler terhadap perubahan pendidikan anak, peranan sosial, pola jam kerja petani, dan pembagian kerja dalam rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan? 1.3. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh migrasi sirkuler terhadap kondisi sosial rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga petani melakukan migrasi sirkuler di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan. 2. Menganalisis pengaruh yang ditimbulkan dari migrasi sirkuler terhadap perubahan tingkat pendidikan anak, peranan sosial, pola jam kerja petani, dan pembagian kerja dalam rumah tangga petani di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan. 1.4. KEGUNAAN PENELITIAN Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi akademisi, pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumya mengenai kajian migrasi bagi sektor pertanian di suatu wilayah. Secara spesifik dan terperinci manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut: 1. Bagi akademisi: Bagi akademisi, penelitian ini menjadi proses pembelajaran dalam memahami fenomena sosial di lapangan. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dari perkembangan fenomena sosial mengenai pengaruh migrasi sirkuler terhadap kondisi sosial rumah tangga petani. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh. 2. Bagi pembuat kebijakan: Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan dalam menganalisis bagaimana seharusnya migrasi dijadikan suatu cara untuk memajukan dan membangun daerah-daerah yang tertinggal dari pembangunan. 3. Bagi masyarakat: Bagi masyarakat khusunya pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai migrasi sirkuler dan pengaruhnya bagi masyarakat khususnya para petani. 4 2. PENDEKATAN TEORETIS 2.1. TINJAUAN PUSTAKA Migrasi Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk atau gerak penduduk. Migrasi juga merupakan salah satu bentuk dari tipologi gerak penduduk yang cenderung bersifat permanen. Gerak penduduk mempunyai makna dalam ilmu demografi yaitu perpindahan penduduk (population mobility) atau secara khusus perpindahan wilayah (teritorial mobility) dari suatu tempat ke tempat lainnya yang mengandung makna gerak spasial, fisik, dan geografis (Rusli 2010:100). Lebih lanjut Rusli (2010) menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan migrasi apabila ia melakukan pindah tempat tinggal secara permanen dan relatif permanen (untuk jangka waktu minimal tertentu) dengan menempuh jarak minimal tertentu atau pindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis berarti unit administratif pemerintah baik berupa negara maupun bagian-bagian dari negara. Menurut Mantra (1985) mobilitas penduduk horizontal atau geografis meliputi semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah yang dimaksud lebih kepada batas administrasi yang ditetapkan oleh negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sunarto (1985) merumuskan migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke unit administrasi yang lain (United Nations 1970). Menurut Biro Pusat Statistik (1995) dalam Hermawan (2002) menetapkan migrasi sebagai proses berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas wilayah tertentu yang dilalui dalam perpindahan tersebut. Sunarto (1985) mengemukakan migrasi juga mengandung pengertian bahwa perpindahan seseorang melalui batas propinsi ke propinsi lain yang dalam prosesnya memerlukan jangka waktu enam bulan atau lebih, tetapi seseorang dikategorikan sebagai migran biarpun perpindahan kurang dari enam bulan atau sebelumnya telah berniat menuju ke tempat tujuan. Berbeda dengan definisi lain, Lee (1984) menyatakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen dapat terjadi jika tidak ada pembatasan dan sifat tindakan tersebut dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Dalam membicarakan konsep perpindahan penduduk akan selalu terkait dengan dimensi yang ditetapkan oleh Standing (1985), diantaranya dimensi ruang, yaitu penetapan tempat berdasarkan ciri-ciri wilayah yang menjadi tujuan migrasi dan dimensi waktu, yaitu periode atau selang waktu yang digunakan dalam proses migrasi, sehingga migrasi dapat dikategorikan menurut dimensi ruang dan waktu. Jika menurut dimensi ruang, secara umum terdapat dua jenis migrasi yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, sedangkan untuk migrasi internal adalah perpindahan penduduk yang terjadi pada unit-unit geografis satu negara. Gould (1993) dalam Hermawan (2002) juga mengemukakan bahwa migrasi merupakan fenomena yang bervariasi terdiri dari empat macam, yaitu migrasi desa ke desa, desa ke kota, kota ke desa, dan kota ke kota. Jika menurut dimensi waktu, menurut Rusli (2010) gerak penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu, gerak penduduk permanen dan non-permanen, yang terdiri dari sirkulasi dan komutasi. Bentuk gerak penduduk tersebut merujuk pada selang waktu yang digunakan seseorang untuk berdiam diri atau menetap di tempat tujuan perpindahan. Mobilitas permanen dan non-permanen pada dasarnya terletak pada ada tidaknya niat bertempat tinggal untuk menetap di daerah tujuan (Mantra 1985). Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa migrasi adalah segala bentuk gerak penduduk yang terkait dengan perpindahan tempat tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain selama periode waktu tertentu (permanen dan non-permanen). Orang atau pelaku yang melakukan migrasi disebut sebagai migran. Lebih spesifik Rusli (2010) menjelaskan bahwa seseorang dapat disebut sebagai migran jika telah melakukan migrasi lebih dari satu kali. Hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Standing (1991) dalam Sri Wahyuni (2003) yang menyatakan bahwa migran adalah mereka yang berpindah dalam masa antarsensus dan dalam masa sensus kedua tinggal di wilayah yang tidak sama dengan wilayah tempat tinggal pada waktu sensus pertama. 5 Migrasi Sirkuler Berdasarkan konsep gerak penduduk yang diungkapkan Rusli (2010) gerak penduduk nonpermanen dapat dibagi menjadi sirkulasi dan komutasi, secara umum bermakna sebagai gerak penduduk yang biasanya bercirikan jangka pendek, repetitif atau siklikal; ketiga ciri tersebut mempunyai kesamaan dalam hal tidak nampaknya niat yang jelas untuk mengubah tempat tinggal secara permanen (Zelinsky 1971 dalam Rusli 2010:101). Dalam sirkulasi, migran hanya berniat bergerak dan menetap di daerah tujuan pada periode waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan komutasi yang semata-mata merupakan gerak penduduk harian yaitu gerak yang berulang hampir setiap harinya antara tempat tinggal dan tempat tujuan. Jika dihubungkan dengan sektor pertanian Zulham dan Gunawan dalam Erwidodo et. al. (1992) mengemukakan hanya terdapat dua bentuk yaitu sirkulasi dan komutasi. Dugaan ini berdasarkan pemanfaatan waktu migran sirkuler dan komuter antara desa dan kota. Menurut Rusli (2010) migrasi sirkuler didefinisikan sebagai gerak berselang antara tempat tinggal dan tempat tujuan baik untuk bekerja maupun untuk lain-lain tujuan seperti sekolah. Seorang sirkulator tinggal di tempat tujuan untuk periode waktu dengan pola yang kurang teratur, diselingi dengan kembali dan tinggal di tempat asal untuk waktu-waktu tertentu juga. (Rusli 2010:101). Migrasi sirkuler menurut Mantra (1994) adalah gerak penduduk dari sutu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Pengertian migrasi sirkuler menurut Alatas dan Edi (1992) dalam Mahfudhoh (2006) adalah jenis mobilitas penduduk yang dipilih seseorang atau kelompok dengan maksud untuk tidak menetap di daerah tujuan dan pada waktu tertentu tetap kembali ke daerah asal. Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian migrasi sirkuler adalah gerak berselang penduduk antara tempat asal dengan tempat tujuan yang bersifat non-permanen dimana migran tidak mempunyai maksud atau niatan untuk menetap selamanya. Faktor-faktor Penyebab Migrasi Pada dasarnya orang melakukan migrasi selalu di latar belakangi oleh berbagai faktor baik dari individu itu sendiri maupun dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Menurut Everett S. Lee (1966) dalam Mantra (1985:181), terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami penyebab para migran melakukan gerak penduduk, diantaranya: (1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, (2) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan, (3) Rintangan antara, dan (4) Faktor-faktor individu. Gambar 1. Faktor-Faktor yang Terdapat Pada Daerah Asal. Daerah Tujuan, dan Rintangan Antara (Mantra 1985) Selain itu, terdapat dua faktor yang selalu terdapat di daerah asal maupun tujuan terkait dengan perpindahan penduduk, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Faktor positif merupakan faktor yang menarik seseorang untuk tidak meninggalkan daerah asalnya dan faktor negatif merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk meninggalkan daerah asalnya tersebut. Jika dilihat dari faktor pendorong dan penariknya, yang tergolong menjadi faktor pendorong antara lain: 6 (1) Makin berkurang sumber-sumber alam, (2) Menyempitnya lahan pekerjaan di tempat asal, (3) Adanya tekanan-tekanan dan diskriminasi politik, agama, dan suku, (4) Tidak cocok lagi dengan budaya atau adaptasi daerah asal, (5) Alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak berkembangnya karir pribadi, dan (6) Bencana alam. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa faktor pendorong dari daerah asal identik dengan faktor negatif yang dimiliki daerah asal dan faktor yang menarik dari daerah tujuan identik dengan faktor positif yang dimiliki daerah tujuan. Adapun faktor positif yang terdapat dari daerah asal yaitu menyebabkan penduduk untuk memilih tidak meninggalkan daerah asalnya, menurut mantra (1985:176) berkaitan dengan: (1) Jalinan persaudaraan dan kekeluargaan diantara warga desa sangat erat, (2) Sistem gotong royong pada masyarakat pedesaan jawa sangat erat pula, (3) Penduduk sangat terikat pada tanah pertanian, dan (4) Penduduk sangat terikat pula kepada daerah (desa) dimana mereka dilahirkan. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilvis E. Tahitu (2007) melihat faktor pendorong dan penarik dari sisi sosial dan ekonomi para migran yang melakukan migrasi ke daerah tujuan (Kota Ambon). Faktor pendorong dalam penelitiannya yang terkait dengan aspek sosial ekonomi, meliputi penghasilan, lapangan pekerjaan, produktivitas pertanian, dan akses terhadap pelayanan sosial. Namun, faktor pendorong utama para migran sirkuler untuk bermigrasi adalah faktor pendapatan atau faktor ekonomi. Kepemilikan lahan pertanian dan juga adat istiadat yang dianggap menekan kebebasan masyarakat juga menjadi faktor pendorong bagi sebagian migran untuk bermigrasi. Hal ini dimungkinkan karena dalam kehidupan sosial kemasyakatan berlaku norma atau aturan-aturan yang mengikat sehingga berimplikasi pada ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas. Faktor penariknya, meliputi penghasilan atau upah di daerah tujuan lebih besar, mudah mendapatkan pekerjaan dan terdapat pusat-pusat pemasaran yang mana hal-hal tersebut susah untuk didapatkan jika berada di daerah asal. Faktor penarik lainnya adalah ajakan teman yang telah lebih dulu bermigrasi dan adanya anggapan bahwa di Kota Ambon mudah mendapatkan pekerjaan Faktor kebebasan menentukan pilihan tanpa dibatasi adatistiadat di kota, dalam hal ini Kota Ambon menjadi penarik bagi para migran yang merasa kebebasan mereka di daerah asal dibatasi oleh adat-istiadat. Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh BPS (1995) dalam Hermawan (2002), banyaknya orang yang masuk ke suatu propinsi (migrasi) dipengaruhi besarnya faktor penarik propinsi tersebut bagi pendatang berupa industrialisasi, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan lingkungan hidup. Selain itu karena ada faktor pendorong seperti kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, saranan dan prasarana, pendidikan, fasilitas, dan kondisi lingkungan. Teori Migrasi oleh Ravanstein dalam Mantra (2000) bahwa migran berumur relatif muda lebih banyak melakukan mobilitas karena masih memiliki produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Dampak Migrasi Terhadap Pertanian Adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya kekurangan tenaga kerja di desa pada sektor pertanian. Hal ini dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor pertanian turun secara teratur. Pada Februari 2011, tercatat jumlah tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 42,48 juta jiwa. Jumlahnya menurun menjadi 41,20 juta jiwa pada Februari 2012. Kemudian berkurang lagi pada Februari 2013 menjadi 39,96 juta jiwa. Jadi, dalam dua tahun, jumlah tenaga kerja meningkat sebanyak 2,74 juta jiwa, tetapi di sektor pertanian berkurang sebanyak 2,52 juta jiwa tenaga kerja dalam dua tahun. Data ini jelas membuktikan terjadinya migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Gejala penurunan jumlah tenaga kerja petani dari waktu ke waktu ini diduga karena rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani terutama kaum muda. Hasil sensus pertanian tahun 2013 yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen petani negeri ini berumur di atas 45 tahun dan sekitar sepertiganya bahkan telah berumur di atas 55 tahun. Hal yang mempengaruhi keinginan para pemuda tidak mau terjun ke sektor pertanian karena pendidikan mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua mereka yang bekerja di sawah dan pendapatan yang rendah dari hasil pertanian dibandingkan di luar pertanian (Hermawan 2002). 7 Penyebab utama perubahan dalam sektor pertanian ialah pembangunan atau globalisasi. Perubahan yang disebabkan globalisasi pada sektor pertanian, yaitu ditinggalkannya sektor pertanian dan beralih ke sektor non-pertanian. Di tempat tujuan migrasi nantinya, sebagian dari mereka mempunyai kegiatan di sektor informal (seperti dibidang perdagangan, industri, pengolahan, transportasi, konstruksi, dan jasa). (Suharso 1996 dalam Hermawan 2002). Menurut Herdiana (1995) pelaku mobilitas menjadi penyebab lain berkurangnya kesempatan kerja di desa karena mereka memperkenalkan teknologi baru pada bidang pertanian di desa. Keluarga petani yang semula bekerja sama menumbuk pada berubah menjadi komersil, karena harus mengatur biaya penumbukan padi secara modern. Menurut Zulham dan Gunawan dikutip Erwidodo et.al (1992), mobilitas penduduk yang tidak tergantung lagi pada sekor pertanian lebih bersifat permanen. Migran ini pada umumnya melepas kegiatan di sektor pertanian karena pendapatan di luar sektor pertanian lebih besar. Kajian yang dilakukan oleh Sumaryanto dan Sudaryanto (1989) dalam Rohmadiani (2011) di Propinsi Jawa Tengah bahwa pola migran ternyata dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja dalam desa. Pada saat permintaan tenaga kerja di dalam desa cukup tinggi seperti pada saat musim tanam dan panen maka arus migrasi ke luar desa lebih kecil dibangdingkan masa lainnya. Pada saat musim paceklik, petani lebih memilih bermigrasi keluar desa dengan menjadi buruh di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Bekasi (Rohmadiani 2011). Hal tersebut dikarenakan jumlah pemilik lahan pertanian lebih kecil dibandingkan jumlah buruh tani sehingga tenaga kerja buruh tani berlebih. Hal yang terjadi adalah semakin banyak buruh tani yang membutuhkan pekerjaan tambahan, namun tidak tersedianya lahan pertanian yang cukup untuk diolah. Jika hal tersebut terus menerus terjadi, dikhawatirkan akan merubah sumber mata pencaharian petani yang tadinya diandalkan hanya dari bertani menjadi pekerjaan non-pertanian dan lebih memilih menjadi buruh dengan cara bermigrasi ke daerah perkotaan. Dampak Migrasi Terhadap Status Sosial Petani Berdasarkan data dari BPS tahun 2003, tingkat pendidikan petani masih didominasi oleh petani lulusan SD. Secara umum jumlah petani Tidak Sekolah 8,08%, tidak/belum lulus SD 13,39%, Lulusan SD 46,19 %, lulusan SLTP 10,67 %, Lulusan SLTA 8,95%, Diploma atau Perguruan tinggi 1,73%. Migrasi memiliki kaitan erat dengan ekonomi, sedangkan ekonomi ikut berpengaruh terhadap pendidikan. Russel (1993) menyatakan bahwa pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap pendidikan jelas kuat, dan secara dangkal tidak selalu jelas. Kalangan ekonomi kelas bawah, tidak mampu mengenyam pendidikan karena biayanya yang mahal, sedangkan masyarakat yang tidak berpendidikan tidak mampu meningkatkan mobilitas sosialnya. Caldwell sependapat dengan Gugler menyampaikan bahwa migran selama ini didominasi oleh mereka yang tidak mampu, tidak memiliki tanah, kurang terampil, dan peluang kerjanya sebagian besar tidak ada (Mulyadi 2006). Dengan migrasi diharapkan dapat menggantikan kekurangan yang dialami selama ada di desa. Kekurangan yang ada desa seperti daya jual pertanian yang rendah, rendahnya teknologi dan informasi di pedesaan, serta peluang pekerjaan yang sempit, sehingga seseorang melakukan migrasi di dorong oleh kondisi kemiskinan di pedesaan. Kondisi kemiskinan tersebut amat dipengaruhi oleh sempitnya kepemilikan tanah, tingginya modal produksi pertanian, serta daya jual hasil pertanian yang rendah. Kemiskinan ini turut memicu rendahnya pendidikan masyarakat pedesaan. Selain itu, masyarakat pedesaan juga mengutamakan prestise dan menghindari rasa sungkan jika bekerja di sektor informal di luar sektor pertanian. Rasa sungkan tidak akan di alami, dan penghargaan bisa diperoleh, jika pekerjaan sektor informal di lakukan di daerah lain. Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Marwell dalam teorinya Nature dan Nurture menjelaskan bahwa peran yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin (seksual) selalu terjadi. Pada setiap kebudayaan, wanita dan laki-laki diberi peran dan pola tingkah laku yang berbeda untuk saling melengkapi perbedaan dari kedua makhluk ini. Melalui pembagian peran atau pembagian kerja inilah yang berfungsi melengkapi kekurangan dari masing-masing jenis kelamin (Saidah 2013). Menurut Budiman (1982: 2) dalam 8 Saidah (2013) pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (seksual) ialah pembagian kerja atas perbeadaan biologis dan sosio-kultural, dimana wanita bersifat lemah lembut, bersifat melayani, ketergantungan, emosional, dan tidak bisa bekerja keras, sedangkan laki-laki makhluk yang berjiwa pemimpin, mandiri, kuat, dan rasional. Sehingga laki-laki dan wanita memiliki perannya masing-masing. Hal ini akan membudaya dalam masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Hal-hal yang menyebabkan munculnya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin menurut (Skolnick 1974: 131 dalam Budiman, 1982: 2), pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin muncul karena perbedaan psikologis yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis dan sosio-kultural dalam proses pembentukan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Budiman (1982: 36) dalam Saidah (2013) menjelaskan, ada beberapa hal-hal yang menyebabkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, diantaranya adalah (1) Faktor-faktor yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Kebutuhan ini didasarkan pada kebutuhan nyata dari sistem masyarakat tersebut; (2) Faktor-faktor yang didasarkan pada sistem psikokultural dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkannya dan mengembangbiakan sistem pembagian kerja ini. Sistem pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin ini menjadi sistem patriarkal yang bukan hanya sekedar sistem kepercayaan yang abstrak belaka, tetapi didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyebarkan dan mengembangbiakannya. Berdasarkan hal tersebut dalam dunia pertanian, pembagian kerja yang terjadi juga berdasarkan jenis kelamin. Menurut Hermawan (2002) pembagian kerja dalam pertanian ada perbedaannya, dimana suami biasanya mengerjakan dan mengolah sawah, sedangkan ibu rumah tangga berperan dalam mengurus keluarga seperti memasak, mengurus anak, dan memanjemen keuangan keluarga. Tidak jarang bahwa ibu rumah tangga ada yang mencari nafkah pada keluarga migran sirkuler dan bukan migran (Hermawan 2002). 2.2. KERANGKA PEMIKIRAN Gerak atau mobilitas penduduk non-permanen meliputi gerak secara sirkulasi dan komutasi, namun yang menjadi fokus penelitian adalah migrasi sirkulasi. Migrasi sirkulasi dalam hal ini adalah migrasi desa ke kota yang menyebabkan penduduk desa terpengaruhi untuk melaksanakan mobilitas ke kota. Dalam setiap gerak penduduk tersebut pasti dilatarbelakangi oleh faktor-faktor penyebab mengapa para penduduk tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Faktor utama yang menyebabkan para migran melakukan mobilitas adalah faktor ekonomi. Namun, selain itu faktor-faktor lain yang mendukung terjadinya mobilitas, seperti faktor penarik dan faktor pendorong atau lebih dikenal dengan teori push and pull factors. Faktor penarik berupa informasi yang di dapat mengenai kota, pendapatan yang tinggi, peluang kerja yang lebih luas di kota. Selain faktor penarik, terdapat fakor pendorong yang berupa hasil pertanian yang rendah di desa, peluang kerja yang terbatas di desa, kurangnya lahan pertanian. Migrasi sirkuler juga dapat mempengaruhi para masyarakat desa khususnya para petani untuk berlomba-lomba meningkatkan tingkat pendidikan rumah tangganya baik itu keterampilan maupun pengetahuan formal yang mereka miliki sebelum mereka melakukan migrasi ke kota. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan gerak penduduk masyarakat secara sirkuler dapat berpengaruh terhadap perubahan kondisi sosial rumah tangga petani migran. Dampak migrasi sirkuler yang ingin diteliti dalam penelitian ini secara sengaja dibataskan hanya pada kondisi sosial rumah tangga petani migran saja. Kondisi sosial ini berhubungan dengan perubahan tingkat pendidikan anak, peranan sosial, pola jam kerja petani, dan pembagian kerja. Secara umum kerangka penelitian ini ingin menjelaskan bahwa kondisi sosial rumah tangga petani dipengaruhi oleh dampak dari migrasi sirkuler dan pengaruh dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi sirkuler. Hal tersebut tergambar dengan ringkas pada gambar 2 berikut: 9 MIGRASI SIRKULER Desa Kota Faktor Pendorong Faktor Penarik Kondisi Sosial Rumah Tangga (RT) Petani Pembagian Kerja Pendidikan Anak Peranan Sosial Pola Jam Kerja Petani Gambar 1. Kerangka Pemikiran Keterangan: : Berhubungan : Mempengaruhi : Saling Mempengaruhi : Lingkup yang akan diteliti 2.3. HIPOTESIS PENELITIAN Untuk membantu penelitian ini dalam menganalisis pengaruh migrasi sirkuler kondisi sosial rumah tangga petani digunakan suatu hipotesa penguji sebagai berikut: 1. Semakin tinggi pengaruh faktor pendorong dan penarik terhadap migran maka tinggi tingkat pendidikan anak. 2. Semakin tinggi pengaruh faktor pendorong dan penarik terhadap migran maka rendah jumlah curahan waktu yang diperlukan untuk kegiatan bertani. 3. Semakin tinggi pengaruh faktor pendorong dan penarik terhadap migran maka tinggi perubahan peranan sosial di masyarakat. 4. Semakin tinggi pengaruh faktor pendorong dan penarik terhadap migran maka banyak peran kepala keluarga yang digantikan oleh istri dalam rumah tangga. terhadap semakin semakin semakin semakin 2.4. DEFINISI OPERASIONAL Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang harus didefinisikan secara operasional agar dapat memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Masing-masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurannya. Berikut adalah definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini: Tingkat Pendidikan (Ordinal) : Jenjang pendidikan formal tertinggi yang berhasil ditempuh oleh responden. Tingkat pendidikan dapat dikelompokkan menjadi: 1. Rendah : ≤ SD 2. Sedang : SMP 3. Tinggi : ≥ SMA/SMK 10 Tingkat Pendapatan (Ordinal) : Penerimaan materi yang diperoleh dari hasil pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan dari anggota rumah tangga per bulan dengan satuan rupiah. Tingkat pendapatan dapat dikelompokan menjadi: 1. Rendah : < Rp.500.000,2. Sedang : Rp.500.000,- s/d Rp.1.000.000,3. Tinggi : > Rp.1000.000,- Kepemilikan Lahan (Interval) : Besarnya luas lahan pertanian yang dimiliki oleh rumah tangga petani. Dapat dikelompokan menjadi: 1. Sempit : < 0,25 Ha 2. Sedang : 0,25 Ha s/d 0,50 Ha 3. Luas : > 0,50 Ha Informasi Kota (Ordinal) : kabar dan gambaran umum yang didapatkan oleh calon migran mengenai kota. Informasi kota ini diukur dari sumber informasi berasal: 1. Keluarga 2. Teman 3. Tetangga atau Orang Lain Peranan Sosial (Nominal) : Perbuatan dan atau perilaku yang ditampilkan anggota rumah tangga petani yang sedang melakukan migrasi sirkuler sehubungan dengan status sosial yang disandangnya (sebagai ayah, ibu, atau anak) terhadap lingkungan kemasyrakatannya. Peranan sosial diukur melalui perbandingan peranan antara suami dan istri pada keluarga petani migran dan non-migran Pola Pembagian Kerja (Nominal) : Pola pembagian tugas dalam rumah tangga yang didasarkan pada status individu yang ada dalam keluarga. Pola pembaian kerja diukur melalui perbandingan pembagian kerja yang dilakukan antara suami dan istri serta adanya tambahan kerja sampingan yang dilakukan oleh istri saat suami sedang bermigrasi sirkuler. Pola Jam Kerja Petani (Nominal) : Kecenderungan curahan waktu kerja petani yang diperuntukan dalam kegiatan bertani. Pola jam kerja petani diukur berdasarkan perbandingan curahan waktu kerja antara perbandingan curah waktu yang digunakan oleh petani dalam melakukan bertani dengan curah waktu yang digunakan untuk bekerja di tempat migrasi. 11 3. PENDEKATAN LAPANGAN 3.1 METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian penjelasan (explanatory research), yakni penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesa. Pedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui instrumen berupa kuesioner yang didukung oleh metode wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan perubahan kondisi sosial rumah tangga petani akibat pengaruh migrasi sirkuler. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh faktor pendorong dan penarik terhadap tingkat pendidikan anak, pola jam kerja petani, peranan sosial di masyarakat dan pembagian kerja dalam rumah tangga petani. 3.2 LOKASI DAN WAKTU Penelitian ini dilakukan di Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa keberadaan migran dapat dengan mudah diperoleh di desa ini dan menurut peneltian Lidiana (2011) migrasi keluar di kecamatan pamanukan lebih besar dibanding dengan migrasi masuk pada tahun 2007. Desa Pamanukan Hilir merupakan desa yang jumlah petaninya masih besar dan memiliki kemungkinan para petaninya melakukan sirkulasi karena berada di dekat dengan jalur Pantura. Kegiatan penelitian meliputi penulisan dan penyusunan proposal penelitian, kolokium, pengambilan data lapangan, pengolahan data dan analisis data, penulisan dan penyusunan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan laporan penelitian. Lama pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2014 Kegiatan Februari 1 2 3 4 2014 Maret April Mei 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Keterangan Penulisan dan penyusunan draft proposal penelitian Kolokium Perbaikan proposal penelitian Pengambilan data lapangan Pengolahan data dan analisis data lapangan Penulisan dan penyususan draft skripsi Sidang skripsi Perbaikan skripsi 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani Desa Pamanukan Hilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. Populasi sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani yang kepala keluarganya melakukan migrasi migrasi sirkuler, dengan kontrol rumah tangga petani yang kepala keluarganya tidak melakukan migrasi sirkuler. Responden merupakan istri dalam rumah tangga petani yang kepala keluarganya melakukan migrasi sirkuler. Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh migrasi sirkuler 12 terhadap kondisi sosial rumah tangga petani. Kontrol digunakan untuk membandingkan kondisi rumah tangga petani yang migran sirkuler dengan rumah tangga petani yang non-migran sirkuler. Metode pemilihan responden dilakukan dengan pengambilan sampel acak distrafikasi (stratified random sampling). Populasi yang akan diambil dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (strata) berdasarkan luas kepemilikan lahan dan dari setiap lapisan tersebut dapat diambil sampel secara acak. Dalam sampel berlapis, peluang untuk terpilih antara satu strata dengan yang lain mungkin sama, mungkin pula berbeda. Teknik bola salju (snowball) juga dilakukan kepada informan untuk mengetahui jumlah dan lokasi rumah tangga yang memiliki kriteria sebagai sampel penelitian. Bungin (2005) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode snowball peneliti menjadi penting untuk memanfaatkan jaringan sosial informan yang pernah dikontak pertama kali atau bertemu dengan peneliti sehingga dapat merujuk kepada orang lain yang berpotensi, berpartisipasi atau berkontribusi, dan mempelajari atau memberi informasi penting kepada peneliti. Jumlah sampel atau responden yang diambil sebanyak 60 orang pada rumah tangga petani dengan rincian 30 rumah tangga petani yang suaminya sedang melakukan migrasi sirkuler dan 30 rumah tangga petani yang suaminya sedang menetap di desa. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data yang berkaitan dengan lokasi penelitian, yaitu profil Desa Pamanukan Hilir 2010, data demografi Desa Pamanukan Hilir, dan data dari Badan Pusat Statistika mengenai potensi desa dan sesus penduduk tahun 2010, serta studi literatur-literatur bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian juga dilakukan untuk memperkuat hasil analisis penelitian. Data primer diperoleh dari hasil pengambilan data langsung di lapangan melalui instrumen berupa kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden dan informan. Wawancara mendalam diberikan kepada responden dan informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan dan diikuti dengan pemikiran responden yang berhubungan dengan pertanyaan. Wawancara tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh migrasi sirkuler terhadap konsisi sosial rumah tangga petani di Desa Pamanukan dan informasi-informasi lain mengenai pengaruh migrasi sirkuler. Responden diwawancarai sesuai dengan kuesioner yang telah disusun (Lampiran 2). 3.4 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA Data yang telah dikumpulkan menggunakan kuesioner akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan Microsoft Excel 2013 dan SPSS Statistics 20. Analisis data antara lain dilakukan dengan membandingkan antara petani yang bermigrasi sirkuler dan petani yang tidak bermigrasi sirkuler dalam hal pendidikan anak, peranan sosial, pola jam kerja petani, dan pembagian kerja. Data kuantitatif disajikan pada tabel-tabel. Analisis perbandingan dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan nyata yang dapat mempengaruhi keadaan sosial rumah tangga petani. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan Uji Chi-Square menggunakan dan dijelaskan secara deskripsi. Uji ini biasa digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara dua sampel yang saling independen dengan skala data minimal nominal. Selain analisis data kuantitatif, dilakukan pula analisis data kualitatif sebagai pendukung data kuantitatif. Data kualitatif akan diolah melalui tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penyimpulan hasil penelitian dilakukan dengan mengambil hasil analisis antar variabel yang konsisten. Seluruh hasil penelitian dituliskan dalam rancangan skripsi (Lampiran 3). 13 DAFTAR PUSTAKA Bungin B. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media Hermawan A. 2002. Faktor-Faktor Penyebab Migrasi Sirkulasi dan Pengaruh Migrasi Sirkulasi Terhadap Daerah Asal (Kasus Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 75 Hal. Irawan T. 2000. Mobilitas Penduduk Desa-Kota dan Dampaknya Terhadap Daerah Asal: Studi Kasus di Tiga Desa di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. [internet]. [Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2013]. Dapat diunduh di: http://www.digital.lib.itb.ac.id Lee ES. 1984. Suatu Teori Migrasi. Yogyakarta [ID]: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada. Mahfudhoh. 2006. Analisis Dampak Migrasi Sirkuler Terhadap Pembangunan Ekonomi Perdesaan (Studi Kasus Pada Rumahtangga Sektor Informal Perdagangan di Dua Kecamatan di Kabupaten Lamongan Jawa Timur). [Tesis]. Bogor [ID]; Institut Pertanian Bogor. 148 Hal. Mantra IB. 1985. Pengantar Studi Demografi. Yogyakarta [ID]: Nur Cahya. Mulyadi S. 2006. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta [ID]: Raja Grafindo Persada Refiani E. 2006. Faktor Penyebab dan Dampak Migrasi Sirkuler di Daerah Asal. [Skripsi]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor. 95 Hal. Rianse U, Abdi. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Alfabeta Rohmadiani LD. 2011. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani (Studi Kasus: Jalur Pantura Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang). Jurnal Teknik Waktu. [Internet]. Jurnal [dikutip tanggal 18 Februari 2014]. 9(2): 1412-1867. Dapat diunduh: http:// Rusli S. 2010. Pengantar Ilmu Kependudukan. Bogor [ID]: IPB Press. Singarimbun M, Effendi S. 2006. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3ES. 346 hal. Tahitu ME. 2007. Studi Tentang Migrasi Sirkuler di Kota Ambon. Jurnal Agroforestri. [Internet]. Jurnal [dikutip tanggal 2 Oktober 2013]. 2(3): 188-193. Dapat diunduh: http://jurnalee.files.wordpress.com/2013/06/studi-tentang-migrasi-sirkuler-di-kota-ambon1.pdf Wahyuni ES. 2000. Migrasi Wanita dan Persoalan Perawatan Anak. Jurnal Sosiologi Indonesia. 4(tidak ada nomor): 12-13 [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Profil Kemiskinan di Indonesia September 2012. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2010. 14 Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Responden: No. KUESIONER SURVEI PENGARUH MIGRASI SIRKULER TERHADAP KONDISI SOSIAL RUMAH TANGGA PETANI Kuesioner ini merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam rangka penulisan skripsi program sarjana yang dilakukan oleh: Nama / NRP : Muhammad Indra / I34100075 Departemen : Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas : Fakultas Ekologi Manusia Universitas : Institut Pertanian Bogor Peneliti meminta kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini secara jujur, jelas, dan benar. Informasi yang diterima dari kuesioner ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya. 1. 2. 3. 4. 5. Nama Responden : ……………………………….……………………………….. Nama Kepala Keluarga : ……………………………….……………………………….. Alamat Rumah Tangga : ……………………………….……………………………….. RT …. / RW …. Desa/Kelurahan …………………………Kecamatan………………... Kabupaten……………………… Nomor Telepon/HP : …………………………………. Berapa jumlah anggota rumah tangga yang tinggal bersama di rumah ini selama lebih dari 3 bulan terakhir? …….. orang (termasuk KRT, tidak termasuk tamu, pengunjung sementara, dan pembantu) A. KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA KOLOM JAWABAN 1 2 3 4 5 Kode anggota rumah tangga 6. Jenis kelamin anggota rumah tangga 7 Usia anggota rumah tangga Pendidikan terakhir anggota rumah tangga? 1. Tidak bersekolah/Tidak tamat SD 2. SD / Setara 8 3. SMP / Setara 4. SMA / SMK / Setara 5. Diploma / Sarjana / Lebih 15 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 Berapa luas kepemilikan lahan pertanian di desa asal? 1. < 0,10 Ha 2. 0,10– 0,20 Ha 3. 0,20 – 0,30 Ha 4. 0,40 – 0,50Ha 5. > 0,50 Ha Apa pekerjaan kepala keluarga di Desa? 1. Petani Pemilik 2. Petani Penggarap Pemilik 3. Petani Penggarap Bukan Pemilik 4. Buruh Tani Apa pekerjaan sampingan kepala keluarga di Desa? 1. Pedagang Warung 2. Pedagang Keliling 3. Kuli Pasar 4. Buruh Bangunan 5. Tukang Ojek 6. Serabutan Apakah suami Anda sedang melakukan migrasi sirkuler? 1. Ya 2. Tidak *jika menjawab “Ya” lanjut ke nomor 13; Jika menjawab “Tidak” lanjut ke nomor 1. Kemana biasanya suami Anda jika melakukan migrasi sirkuler? 1. Kota 2. Desa lain Sebutkan nama kota atau desa lain tempat tujuan migrasi anda? …………….…………….…………… Apa faktor utama kepala keluarga memutuskan untuk melakukan migrasi? 1. Pendapatan 2. Pendidikan 3. Luas Lahan 4. Informasi Bekerja pada sektor apa kepala keluaga saat sedang melakukan migrasi? 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Formal (Pegawai Negeri, Swasta, Industri) 3. Sektor Inforrmal (Pedagang, Jasa, Buruh) SUMBER PENGHASILAN RUMAHTANGGA Penyumbang Per Bulan (Rp) Usaha Tani (% Dijual) a. b. c. Gaji / Upah (Total): a. b. Usaha Keluarga / Wiraswasta (Total): a. b. Per Tahun (Rp) 16 21 22 23 Remitan (Total): a. b. Lain-lain: a. b. Total Pendapatan: B. FAKTOR PENARIK DAERAH TUJUAN 24. Apa saja alasan kepala keluarga Anda memutuskan untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut? 1. Pendapatan di daerah tujuan yang lebih tinggi. 2. Peluang kerja yang ditawarkan di daerah tujuan lebih luas. 3. Adanya informasi mengenai daerah tujuan 4. Lainnya: .................. *jawaban boleh lebih dari satu pilihan. 25. Darimana rumah tangga Anda mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan tersebut? 1. Keluarga yang sudah lebih dahulu bermigrasi 2. Teman yang sudah lebih dahulu bermigrasi 3. Tetangga atau Orang Lain 4. Mencari Sendiri C. FAKTOR PENDORONG DAERAH ASAL 26. Apa saja alasan suami Anda memutuskan untuk keluar dari desa asal? 1. Sempitnya kepemilikan lahan pertanian 2. Kurangnya tersedianya pekerjaan lain di desa asal. 3. Rendahnya tingkat upah di desa asal. 4. Lainnya: .................. *jawaban boleh lebih dari satu pilihan. D. PENGARUH TERHADAP PENDIDIKAN ANAK 27. Siapakah yang memperhatikan pendidikan anak? 1. Suami 2. Istri 3. Suami dan Istri 28. Darimanakah Anda membiayai pendidikan anak? 1. Hasil Bertani Saja 2. Hasil Migrasi (Remitan) Saja 3. Hasil Bertani + Remitan 29. Berapa persen pengeluaran rumah tangga untuk membiayai pendidikan anak? 1. < 25% dari total pengeluaran rumah tangga. 2. 25% - 50% dari total pengeluaran rumah tangga. 3. > 50% dari total pengeluaran rumah tangga. 17 30. Sampai sejauh mana Anda mampu menyekolahkan anak saat ini? 1. Sampai tingkat SMP 2. Sampai tingkat SMA / SMK / sederajat 3. Sampai tingkat Akademi / Diploma I / II / III 4. Sampai tingkat S1 atau lebih E. PERUBAHAN POLA JAM KERJA PETANI 31. Berapa lama jumlah suami Anda menghabiskan waktu saat bekerja di sektor pertanian dalam jangka waktu satu tahun (saat berada di desa)? 1. < 1 bulan 2, 1 – 2,5 bulan 3. 2,5 – 5 bulan 4. > 5 bulan 32. Berapa lama Anda menghabiskan waktu saat bekerja di sektor non-pertanian dalam jangka waktu satu tahun (saat berada ditempat tujuan migrasi)? 1. < 1 bulan 2, 1 – 2,5 bulan 3. 2,5 – 5 bulan 4. > 5 bulan F. PERANAN SOSAL 33. Dalam rumah tangga Anda, siapa yang biasanya hadir dalam rapat di desa? 1. Suami 2. Istri 3. Suami dan Istri 34. Dalam rumah tangga Anda, siapa yang biasanya ikut dalam kegiatan kerja bakti di desa? 1. Suami 2. Istri 3. Suami dan Istri 35. Dalam rumah tangga Anda, siapa yang biasanya ikut dalam pengajan rutin di desa? 1. Suami 2. Istri 3. Suami dan Istri G. POLA PEMBAGIAN KERJA 36. Siapa yang lebih dominan dalam mengerjakan dan mengolah lahan pertanian? 1. Suami 2. Istri 3. Suami dan Istri 37. Selain sebagai Ibu rumah tangga, apa pekerjaan sampingan Anda? 1. Buruh Tani 2, Buruh Pabrik 3. Pedagang Warung 4. Pedagang Keliling 5. Penjahit 18 Lampiran 2. Panduan Wawancara Mendalam A. Profil Lokasi Penelitian (Diperuntukan bagi Kepala Desa Pamanukan Hilir, Ketua RW dan RT serta informan lainnya yang mampu memberikan informasi terkait lokasi yang dijadikan subjek penelitian ini) Hari/ tanggal wawancara : Lokasi wawancara : Nama Informan : Umur Informan : Pertanyaan Penelitian : 1. Bagaimana perkembangan kondisi kependudukan di lokasi penelitian hingga saat ini (terkait migrasi sirkuler)? 2. Bagaimana perkembangan kondisi pertanian di lokasi penelitian hingga saat ini? 3. Bagaimana perkembangan mata pencaharian masyarakat di lokasi penelitian hingga saat ini? 4. Bagaimana perkembangan pendapatan masyarakat di lokasi penelitian hingga saat ini? 5. Bagaimana perkembangan tingkat pendidikan di lokasi penelitian hingga saat ini? 6. Kapan biasanya penduduk melakukan migrasi ke luar desa? 7. Kapan biasanya penduduk kembali lagi ke desa setelah bermigrasi? B. Perubahan Pola Pembagian Kerja, Peranan Sosial, dan Jam Kerja Petani Pada Rumah Tangga Petani yang Suaminya Bermigrasi Sirkuler 1. Apakah tugas suami dalam kegiatan bertani digantikan oleh istri pada saat suami pergi ke kota? 2. Apakah tugas-tugas dalam kegiatan bertani diserahkan kembali kepada suami setelah pulang ke rumah? 3. Selama suami bermigrasi tugas apa saja yang digantikan oleh istri dalam kegiatan bertani? 4. Siapa yang memutuskan pemilihan jenis tanaman yang ditanam dan penyewaan buruh tani? 5. Siapa yang lebih banyak berperan pada saat musim tanam dan musim panen berlangsung di desa? 6. Apakah peranan sosial suami di lingkungan rumah tangga akan digantikan oleh istri saat suami pergi ke kota? 7. Pada kondisi apa Anda merasa tidak mampu untuk menggantikan peranan sosial suami di lingkungan? 8. Mengapa suami Anda dalam setahun lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya untuk di tempat migrasi daripada menghabiskan waktu kerjanya untuk bertani? 9. Apakah Anda sebagai orang tua menginginkan anak Anda menjadi petani seperti orang tuanya? 19 Lampiran 3. Rancangan Skripsi 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Masalah Penelitian 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Kegunaan Penelitian 2. PENDEKATAN TEORITIS 2.1 Tinjauan Pustaka 2.2 Kerangka Pemikiran 2.3 Hipotesis 2.4 Definisi Operasional 3. PENDEKATAN LAPANGAN 3.1 Metode Penelitian 3.2 Lokasi dan Waktu 3.3 Teknik Sampling 3.4 Teknik Pengumpulan Data 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 4. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Profil Desa 4.2 Kondisi Geografis Desa 4.3 Kondisi Pendidikan di Desa 4.4 Kondisi Ekonomi di Desa 4.5 Kondisi Kependudukan di Desa 4.6 Jenis Pekerjaan di Desa 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MIGRASI SIRKULER 5.1 Faktor Pendorong yang Terdapat di Desa Asal 5.2 Faktor Penarik yang Terdapat di Tempat Tujuan 6. PENGARUH MIGRASI SIRKULER TERHADAP KONDISI SOSIAL RUMAH TANGGA PETANI 6.1 Tingkat Pendidikan Anak 6.2 Peranan Sosial Dalam Masyarakat 6.3 Pembagian Kerja Rumah Tangga Petani 6.4 Perubahan Pola Jam Kerja Petani 7. PENUTUP 7.1 Kesimpulan 7.2 Saran 8. DAFTAR PUSTAKA 9. LAMPIRAN