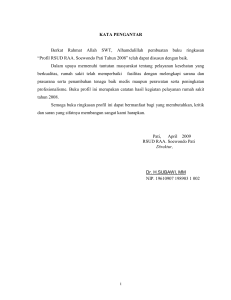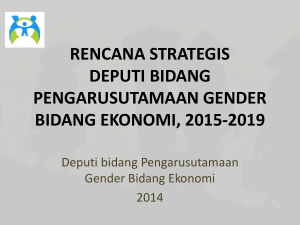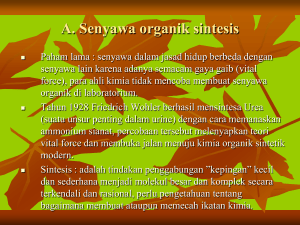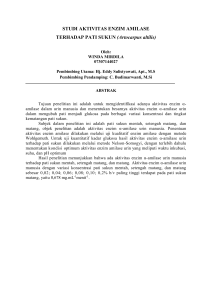BAB I PENDAHULUAN A. Mengintegrasikan Model
advertisement
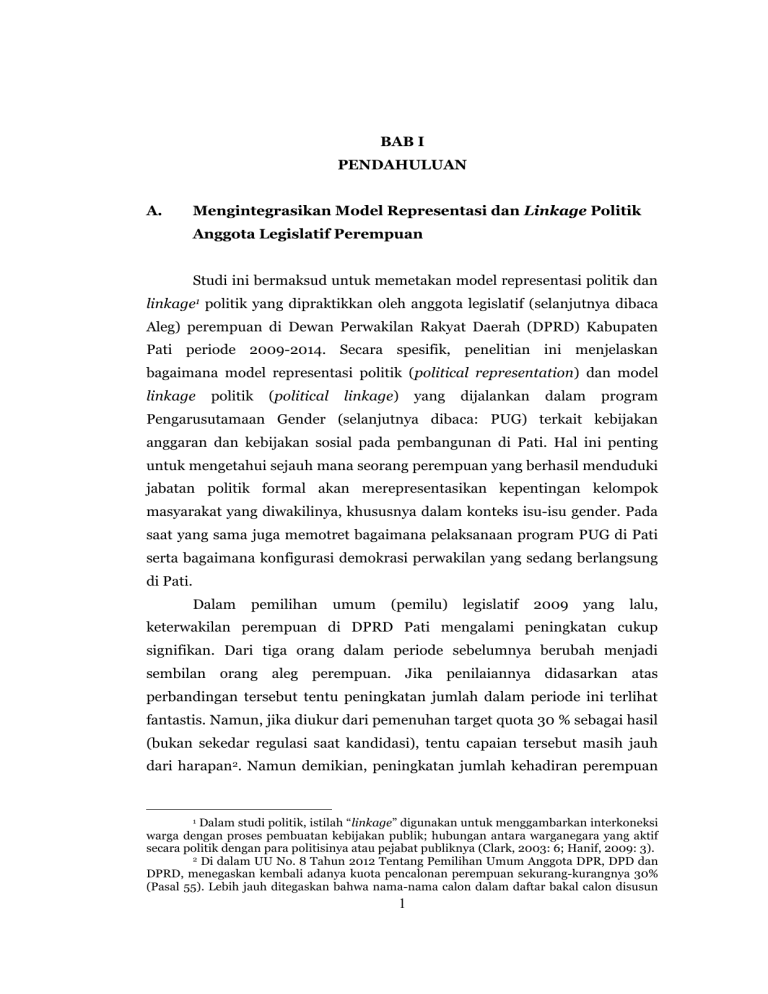
BAB I PENDAHULUAN A. Mengintegrasikan Model Representasi dan Linkage Politik Anggota Legislatif Perempuan Studi ini bermaksud untuk memetakan model representasi politik dan linkage1 politik yang dipraktikkan oleh anggota legislatif (selanjutnya dibaca Aleg) perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati periode 2009-2014. Secara spesifik, penelitian ini menjelaskan bagaimana model representasi politik (political representation) dan model linkage politik (political linkage) yang dijalankan dalam program Pengarusutamaan Gender (selanjutnya dibaca: PUG) terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial pada pembangunan di Pati. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana seorang perempuan yang berhasil menduduki jabatan politik formal akan merepresentasikan kepentingan kelompok masyarakat yang diwakilinya, khususnya dalam konteks isu-isu gender. Pada saat yang sama juga memotret bagaimana pelaksanaan program PUG di Pati serta bagaimana konfigurasi demokrasi perwakilan yang sedang berlangsung di Pati. Dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif 2009 yang lalu, keterwakilan perempuan di DPRD Pati mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari tiga orang dalam periode sebelumnya berubah menjadi sembilan orang aleg perempuan. Jika penilaiannya didasarkan atas perbandingan tersebut tentu peningkatan jumlah dalam periode ini terlihat fantastis. Namun, jika diukur dari pemenuhan target quota 30 % sebagai hasil (bukan sekedar regulasi saat kandidasi), tentu capaian tersebut masih jauh dari harapan2. Namun demikian, peningkatan jumlah kehadiran perempuan 1 Dalam studi politik, istilah “linkage” digunakan untuk menggambarkan interkoneksi warga dengan proses pembuatan kebijakan publik; hubungan antara warganegara yang aktif secara politik dengan para politisinya atau pejabat publiknya (Clark, 2003: 6; Hanif, 2009: 3). 2 Di dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, menegaskan kembali adanya kuota pencalonan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Pasal 55). Lebih jauh ditegaskan bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun 1 ini sedikit banyak bisa memberikan harapan bagi advokasi program PUG di Pati. Pemberlakuan sistem kuota memang untuk merekrut perempuan agar dapat menduduki jabatan politik sekaligus memastikan bahwa perempuan tidak terisolir dalam arena politik. Namun, lebih jauh lagi semangatnya adalah bagaimana perempuan yang hadir di arena legislatif mampu menjadi minoritas kritis (critical minority) meskipun dengan jumlah yang mungkin masih di bawah 30 % (bandingkan Dahlerup dalam Ballington dan Karam, 2005: 141-142). Pertanyaannya kemudian, apakah sesederhana itu bahwa kebijakan kuota secara otomatis akan mencapai tujuan idealnya, di tengah kuatnya struktur oligarki partai politik yang masih setengah hati dalam menjalankan kebijakan kuota perempuan terkait rekrutmen politik yang dijalankannya. Pada akhirnya, kebijakan kuota pun cukup rentan dibajak oleh elit-elit oligarki partai politik di mana konsiderasi utamanya justru didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan advokasi gender. Jika terjadi pembajakan semacam ini tentu perempuan yang menduduki kursi parlemen belum tentu memiliki perspektif gender. Sebaliknya, para aktivis perempuan yang memiliki agenda politik jelas untuk mengawal program PUG justru sangat mungkin tersingkir dan kalah. Kondisi semacam ini tentu patut disesalkan, akan tetapi jika itu kenyataan yang harus dihadapi, tentu tidak saatnya hanya sekedar mengutuknya. Perlu difikirkan upaya transformasi macam apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki wajah keterwakilan perempuan yang rusak tersebut. Di tengah ironi kebijakan kuota tersebut, tentu saja tidak perlu diperdebatkan kembali dan diposisikan secara diametral antara gagasan perwakilan perempuan berbasis kuantitas dan kualitas (subtantif). Seorang laki-laki yang memiliki perspektif gender, secara subtantif juga bisa bertindak untuk memperjuangkan program PUG. Namun, terkait dengan persoalanpersoalan yang berhubungan langsung dengan pengalaman perempuan (seperti kesehatan reproduksi perempuan), tentu pengetahuan perempuan berdasarkan nomor urut dan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon (Pasal 56 ayat 1 dan 2). 2 akan lebih empirik dibanding laki-laki. Artinya, kedua gagasan tersebut sama pentingnya dan perlu dijalankan secara beriringan. Hal ini menjadi pijakan dasar dalam studi ini. Oleh karena itu, mengkaji dinamika dan proses politik yang dihadapi perempuan paska kehadirannya di parlemen sepertinya juga penting untuk mendalami kompleksitas masalah yang terjadi. Dengan demikian, akan lebih terlihat bagaimana model representasi dan linkage politik yang dipraktikkan oleh para aleg perempuan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program PUG di Pati. Aleg perempuan di sini kemudian tidak dilihat sebagai entitas yang tunggal. Aleg perempuan yang hadir dari struktur oligarki partai politik atau struktur patriarki tentu berbeda dengan aleg perempuan yang memiliki perpektif gender dan pengalaman berpolitik yang cukup panjang. Namun, sangat mungkin kedua-duanya mempraktikkan hal serupa terkait dengan bentuk akuntabilitas mereka terhadap kelompok masyarakat yang diwakilinya. Di mana kesamaan tersebut lebih ditentukan oleh konteks politik yang dihadapinya. Pendek kata, segala tindakan politik tidak lahir dalam ruang yang kosong, ada konteks politik yang mempengaruhinya. Konteks inilah yang kemudian akan menentukan keputusan-keputusan politik yang diambilnya. Konteks politik tersebut juga yang akan mempengaruhi sejauh mana komitmen politik mereka untuk mengawal program PUG di Pati. Di satu sisi mereka bisa memiliki komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan kebijakan anggaran yang responsif gender, namun tidak mendapatkan dukungan dari para aktor lainnya, tentu upaya tersebut tidak akan menghasilkan capaian yang maksimal. Sebaliknya, mereka bisa jadi memang tidak memiliki komitmen politik yang jelas terkait program PUG, sehingga yang dilakukannya lebih memperlihatkan orientasi kepentingan pribadi. Kondisi yang kedua ini bisa bergerak ke arah yang cenderung pragmatis (baca: berperilaku koruptif dan menjadi predator anggaran), apalagi ketika konteks politiknya cukup kondusif bagi praktik tersebut. Keberadaan aktor di sekeliling mereka pun sangat mempengaruhi agenda politiknya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, tentu sikap politiknya akan mudah disandera oleh kepentingan 3 pihak lain. Bagaimana mungkin mereka berhasil memperjuangkan alokasi anggaran terkait program PUG, jika ternyata kekuatan politik yang ada disekelilingnya ternyata menghendaki perhatian pada “sektor yang lain”. Artinya, penilaian terhadap kualitas representasi para aleg perempuan tidak bisa mengabaikan konteks sosial politik yang melingkupinya serta konfigurasi proses demokratisasi yang ada. Sehingga percepatan pengembangan representasi politik perempuan agar bermanfaat bagi perempuan pada umumnya seperti yang dikemukakan oleh Dahlerup bisa dipahami secara kontekstual (bandingkan Dahlerup dalam Ballington, 2002: 158). Tindakan politik para Aleg perempuan juga akan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka yang tentu berbeda-beda (misalnya berbasis afiliasi keagamaan ataupun kelas sosialnya). Pengalaman-pengalaman pribadi merekalah yang akan mengkonstruksi cara pandang mereka di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbedaan pengalaman juga bisa membuat perempuan memiliki argumen yang berbeda terkait kehadiran mereka secara fisik di parlemen3. Selain itu, pengalaman mereka pada saat berkompetisi dalam pemilu, di mana melibatkan banyak tim sukses atau praktik politik uang (money politics), juga turut mempengaruhi bagaimana konstruksi mereka tentang konstituen atau masyarakat yang diwakilinya. Kajian tentang representasi politik perempuan bukanlah sesuatu yang baru. Namun, Kajian yang membedah dinamika politik yang dihadapi Aleg perempuan dengan menggabungkan pendekatan representasi politik dan linkage politik nampaknya relatif jarang. Beberapa studi yang ada misalnya, kajian yang dilakukan oleh Aris Arif Mundayat dan Siany Indria Liestyasari (2011:27-44), kajiannya melihat dinamika partisipasi politik perempuan di 3 Secara teoritik, setidaknya ada lima argumen terkait pentingnya representasi politik perempuan; argumen keadilan (justice argument), utilitarianisme (utility argument), argumen deliberasi demokrasi (deliberative democracy arguments), argumen simbolik (symbolic argument) serta argumen agency (agency arguments) (Lovenduski, 2008 : 48-52; Sawer, Tremblay dan Trimble, 2006 : 19; Farrelly 2004 : 181-205). Argumen keadilan menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Argumen utilitarian mengemukakan bahwa perempuan memiliki daya tarik dan gaya berpolitik yang berbeda dengan laki-laki sehingga kehadirannya mampu memperbaiki kualitas demokrasi. Argumen deliberasi demokrasi berpendapat bahwa kontestasi politik harus diperkaya dengan perspektif dan pengalaman perempuan. Argumen simbolik menyatakan bahwa perempuan butuh legitimasi secara politik. Terakhir, argumen agency berpendapat bahwa perempuan memiliki kepentingan berbeda dengan laki-laki yang harus dilindungi. 4 Kota Surakarta (2009-2010) dalam konteks hambatan struktural dan kultural yang dialamiya. Secara struktural, anggota legislatif perempuan tidak bisa berbuat banyak karena dia harus mengikuti kebijakan fraksi. Sedangkan secara kultural, kebanyakan masyarakat masih peyoratif terhadap perempuan bahkan menilai negatif figur perempuan yang vokal di depan publik, karena kuatnya budaya patriarkhi. Temuan kajian ini menegaskan bahwa partisipasi politik para Aleg perempuan dan perempuan Surakarta pada umumnya masih mengalami kendala struktural dan kultural, tanpa perhatian lebih jauh tentang dinamika linkage politik yang dijalankan oleh para Aleg perempuan. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Ani W. Spetjipto dan Shelly Adelina (2012) lebih memfokuskan pada persoalan bagaimana tiga partai politik terbesar (perolehan suaranya dalam pemilu 2009) menerapkan dan mewujudkan pengarusutamaan gender. Di mana temuan penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga partai tersebut tidak memiliki ketentuan tentang kebijakan partai untuk mewujudkan keadilan gender serta strategi pengarusutamaan gender. Menurut kedua peneliti tersebut, upaya yang dilakukan oleh ketiga partai itu hanyalah sebatas fokus utama terhadap perempuan (women focal point), yang kemudian muncul dalam wujud Departemen Perempuan di masing-masing partai. Studi ini cukup menarik karena kedua peneliti tersebut tidak terjebak dalam pendekatan yang esensialis. Selain itu, ada juga Lovenduski (2008) yang melakukan kajian tentang feminisasi politik4. Ia menjelaskan soal proses dan tantangan dalam upaya meningkatkan jumlah keterwakilan politik kaum perempuan di Inggris. Ia mengulas bagaimana strategi-strategi yang dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, di mana strategi quota menjadi alternatif yang paling populis di berbagai Negara. Ia pun memperlihatkan bagaimana peningkatan kehadiran perempuan di dalam politik mampu memberikan perubahan yang signifikan. Sekecil apapun jumlah kehadiran perempuan akan memberikan warna konfigurasi politik yang berbeda. Ia juga berusaha Menurut Lovenduski, feminisasi ini memiliki dua dimensi: pertama, mengintegrasikan perempuan ke dalam institusi politik formal. Kedua, mengintegrasikan keprihatinan dan perspektif perempuan di dalam debat politik dan pembuatan kebijakan (Childs, 2008:xix) 4 5 menjelaskan posisi yang berbeda antara feminisme kesetaraan (equality) dan feminisme perbedaan (difference) dalam memahami representasi politik perempuan. Kajian yang hampir senada juga dilakukan oleh Sarah Childs (2008) yang membahas mengenai perempuan dan partai politik di Inggris. Ada juga Beth Reingold (2000) misalnya mengkaji perilaku anggota legislatif di Arizona dan California, serta membandingkan keduanya. Ia menjelaskan bagaimana perbedaan antara anggota legislatif perempuan dan laki-laki ketika berbicara mengenai keprihatinan yang dialami oleh perempuan. Anggota legislatif perempuan menurutnya jauh lebih faham tentang keprihatinan yang dialami oleh perempuan dibanding dengan anggota legislatif laki-laki. Ia juga menguraikan bagaimana advokasi kebijakan yang dilakukan oleh para anggota legislatif ini terkait masalah yang dihadapi oleh kelompok perempuan. Begitupun juga Sawer, Tremblay dan Trimble (2006) melakukan kajian tentang representasi politik perempuan di parlemen dengan membandingkan kasus di empat negara; Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Seperti halnya juga Leslie A. Schwindt-Bayer (2010) melakukan kajian tentang anggota legislatif perempuan di Amerika Latin. Jika dibanding dengan kajian-kajian yang disebutkan tadi, penelitian yang akan penulis lakukan ini memiliki satu perbedaan yang mendasar. Penelitian ini berusaha mengintegrasikan dimensi model representasi politik aleg perempuan dengan model linkage politiknya. Upaya menggabungkan gagasan representasi dan linkage politik semacam ini boleh dibilang masih sangat minim. Dari sini kemudian bisa dilihat bagaimana berjalannya relasi kepentingan yang berkelindan antar aktor, atau lebih spesifiknya antara seorang wakil dengan pihak yang diwakilinya. Adapun signifikansi dari penelitian ini dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, penelitian ini memperlihatkan akar persoalan kenapa para Aleg perempuan mewakili atau tidak mewakili kepentingan kelompok perempuan. Serta juga mengungkapkan akar persoalan mengapa program PUG mengalamai stagnasi, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa aleg perempuan belum terlihat wujudnya yang signifikan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa realitas representasi politik yang dijalankan oleh para 6 Aleg perempuan itu sesuatu yang kompleks, di mana ada interdependensi antara kepentingan pribadi dan kepentingan gender. Keberhasilan mereka hanya bisa dinilai dengan cara mendalami kompleksitas tersebut. Tanpa upaya itu kita akan mudah menilai mereka gagal melakukan perubahan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kepentingan kelompok perempuan (baca: sebatas mengutuk ironi kebijakan kuota bagi perempuan). Hanya karena tidak melihat konteks politik yang melingkupi para anggota legislatif perempuan tersebut. Kedua, secara teoritik temuan penelitian ini menegaskan bagaimana pentingnya fungsi keagenan (agency) yang dijalankan oleh para aleg perempuan di tengah hambatan struktur yang cukup kuat. Artinya, kapasitas aktor cukup menentukan adanya upaya-upaya alternatif di tengah menguatnya proses depolitisasi demokrasi. Adanya kapasitas personal inilah yang memungkinkan beberapa aleg perempuan untuk melakukan inisiatifinisiatif terkait dengan program PUG atau pelayanan sosial bagi warga yang diwakilinya. Selain itu, diskursus representasi politik perempuan sepertinya memang harus dilengkapi dengan diskursus tentang linkage politik untuk melihat sejauh mana bekerjanya akuntabilitas seorang wakil kepada pihak yang diwakilinya serta bagaimana bekerjanya relasi kuasa antar aktor. B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana model representasi politik Aleg perempuan (periode 2009-2014) dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? 2. Bagaimana model linkage politik pengaruh model representasi politik dan linkage politik Aleg perempuan dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? 3. Bagaimana bentuk integrasi model representasi dan model linkage politik Aleg perempuan (periode 2009-2014) dalam program PUG terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial di Pati? 7 C. Tujuan Penelitian Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, untuk memetakan model representasi politik dan model “linkage” politik yang dijalankan oleh para aleg perempuan di DPRD Pati, serta berusaha mendesain integrasi kedua model tersebut. Kedua, untuk melihat pelaksanaan PUG (khususnya terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial) dalam pembangunan daerah di Pati serta peran para aleg perempuan untuk mengawal PUG tersebut. Ketiga, untuk memotret konfigurasi demokrasi lokal di tengah menguatnya proseduralisme demokrasi. D. Refleksi Teoritik: Representasi Politik, Linkage Politik, dan Pengarusutamaan Gender Dalam menjelaskan model representasi dan model linkage politik aleg perempuan di DPRD Pati ini, ada tiga hal yang perlu ditegaskan. Pertama, studi ini sepakat dengan gagasan tentang pentingnya politik kehadiran perempuan di lembaga perwakilan formal seperti dikemukakan oleh Anne Phillips. Menurut Phillips (1995: 5), gagasan ini menuntut adanya jumlah representasi yang setara antara perempuan dan laki-laki di dalam lembaga legislatif [demands for the equal representation of women with men]. Selain itu, gagasan ini juga juga menawarkan tuntutan adanya representasi yang seimbang bagi kelompok-kelompok etnis yang berbeda [demands for a more even-handed balance between the different ethnic groups] serta dimasukkannya anggota masyarakat yang terpinggirkan secara sosial [demands for the political inclusion of groups that have come to see themselves as marginalized or silenced or excluded] (Phillips, 1995 : 5). Namun, studi ini lebih jauh akan melihat politik kehadiran dalam konteks model representasi yang dijalankannya setelah berhasil hadir di parlemen dengan menggunakan beberapa jenis teori representasi, seperti Hanna F. Pitkin (1967) dan Jean Mansbridge (2003). Kedua, studi ini juga akan menjelaskan model linkage politik yang dipraktikkan selama berinteraksi dengan kelompok yang diwakilinya untuk 8 melihat dinamika kontestasi dan negosiasi kepentingan beragam aktor yang ada di sekeliling aleg perempuan. Dalam memahami model linkage politik tersebut, studi ini meminjam beberapa konsep dari Herbert Kitschelt terkait beberapa tipologi model linkage politik, seperti charismatic linkage, programmatic linkage, dan clientelist linkage. Tiga tipologi ini menjadi pijakan dasar dalam mendesain model linkage politik yang dijalankan oleh para aleg perempuan. Ketiga, studi ini memang tentang representasi dan linkage politik, namun, karena urusan publik yang menjadi area analisisnya adalah program pengarusutamaan gender (terkait kebijakan anggaran dan kebijakan sosial), maka di sini juga akan menggunakan beberapa pemahaman terkait konsep pengarusutamaan gender. Sedangkan untuk memahami kepentingan terkait dengan perempuan, studi ini meminjam konsepsinya Molyneux tentang tiga konsep yang sering diperbincangkan; kepentingan perempuan (women interest), kepentingan gender strategis (strategic gender interest) dan kepentingan gender praktis (practical gender interest) (Molyneux, 1985: 232233; Moser, 2003: 37-41). a. Model Representasi Politik: Tidak Taken for Granted Representasi Deskriptif Representasi merupakan suatu gagasan yang cukup kompleks dan sarat dengan perdebatan (Törnquist dalam Törnquist, Webster, dan Stokke, 2009: 6). Perdebatan-perdebatan tersebutlah yang kemudian menghasilkan konstruksi konsep representasi yang lebih variatif, dan menghasilkan tipologi-tipologi yang beragam. Secara literal, representasi ini bisa diartikan sebagai upaya menghadirkan kembali (a making present again) (Pitkin, 1967: 8). Dalam bahasa yang sederhana, representasi (baca: perwakilan politik) ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011 : 41). Dari sini dapat diketahui bahwa esensi dari sistem representasi adalah adanya 9 kewenangan (authorization) yang dimiliki seorang wakil disertai dengan pertanggungjawaban mereka (accountability) pada yang diwakilinya. Harus diakui bahwa gagasan tentang representasi ini cukup penting dalam diskursus demokrasi. Melalui bidang representasi inilah kualitas demokrasi bisa diukur. Ketika ada perbaikan di bidang representasi tentu mimpi untuk menuju demokrasi yang lebih subtantif dapatlah terwujud. Sistem representasi (perwakilan) yang ideal adalah representasi yang mampu menjamin terakomodasinya semua kelompok kepentingan, khususnya kelompok kepentingan yang termarjinal secara politik (misalnya perempuan). Sebagai kelompok yang marjinal, terbukanya kesempatan yang sama (equal opportunity) terkadang belum menjadi jaminan terwakilinya kepentingan perempuan secara memadai. Oleh karena itu, langkah-langkah alternatif dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya pembangunan daerah yang adil gender. Ketika berbicara tentang sistem perwakilan, maka setidaknya hal tersebut akan terkait dengan empat elemen utama; wakil, yang diwakili, sesuatu yang diwakili, dan konteks politik (Törnquist dan Warouw dalam Samadhi dan Warouw, 2009: 36). Pertama, wakil adalah sekelompok orang yang mewakili baik di lembaga perwakilan formal (di mana di sini adalah Aleg perempuan) maupun informal (organisasi masyarakat sipil dll). Kedua, adanya sekelompok orang yang diwakili di mana mereka bisa menjadi konstituen atau klien. Ketiga, adanya kepentingan, pendapat ataupun preferensi politik tertentu sebagai sesuatu yang diwakili, di mana di sini terkait dengan program PUG khususnya dalam konteks kebijakan anggaran dan kebijakan sosial. Keempat adalah konteks politik yang mendasari adanya perwakilan tersebut. Empat hal ini merupakan dimensi penting dalam melihat bekerjanya fungsi representasi politik (baca: representasi politik perempuan). Dalam berbagai studi tentang representasi politik perempuan, sebagian besar dari mereka (seperti Childs, 2008; Lovenduski, 2008; Sawer, Tremblay dan Trimble, 2006; Reingold, 2000; Stokes, 2005; Bayer, 2010) meminjam konseptualisasi representasi yang dibuat oleh Hanna F. Pitkin. Dalam konsepsi Pitkin (1967:11, Bevir, 2007:825), representasi dibedakan 10 dalam empat kategori; representasi formal (formalistic representation), representasi subtantif (substantive representation), representasi deskriptif (descriptive representation), dan representasi simbolik (symbolic representation). Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga-lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Representasi subtantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang-orang yang secara objektif serupa. Jika wakil berdiri untuk (stands for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik. Tipologi yang dibuat oleh Pitkin tersebut, pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri dalam kenyatannya, satu sama lain bisa saling berpadu dan terintegrasi. Sangat mungkin model representasi deskriptif terintegrasi dengan kedua model lainnya (subtantif dan simbolik) Sehingga untuk melihat model representasi politik yang dijalankan oleh para Aleg perempuan di DPRD Pati dalam program PUG ini, penulis tidak menerima begitu saja (taken for granted) konsepsi representasi deskriptif seperti yang dijelaskan oleh Pitkin. Kehadiran perempuan di lembaga perwakilan formal secara deskriptif memang mewakili perempuan, namun apakah kemudian hal tersebut otomatis menjadikannya bekerja untuk kelompok perempuan yang (diandaikan) diwakilinya. Di sinilah pijakan awalnya, bahwa representasi deskriptif tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang taken for granted. Maka dari itu, representasi deskriptif di sini diberi label pensifatan untuk memperlihatkan sejauh mana bekerjanya para aleg perempuan (apakah aktif, pasif, ataupun simbolik karena pada saat yang sama juga mewakili suatu ormas keagamaan tertentu). Di dalam logika representasi deskriptif, seorang Aleg perempuan idealnya memiliki cita-cita politik untuk mengabdi dan memperbaiki masalah yang dialami oleh perempuan. Pengabdian tersebut misalnya bisa dilihat melalui advokasi mereka atas program PUG dalam pembangunan di Pati, baik melalui advokasi kebijakan maupun interaksi langsung dengan kelompok 11 perempuan. Interaksi ini merupakan salah satu mekanisme untuk menjaring aspirasi konstituennya. Interaksi ini bisa dijalankan melalui aktor-aktor intermediari ataupun secara langsung tanpa adanya mediator. Dengan mekanisme seperti ini, bertambahnya jumlah perempuan di parlemen diharapkan akan memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi perbaikan kelompok perempuan pada umumnya. Namun, tuntutan perubahan semacam ini juga tidak bisa mengabaikan dinamika dan konteks politik yang mungkin menimbulkan dilema bagi seorang Aleg perempuan. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh mereka. Kompeksitas persoalan tersebut hadir karena seorang Aleg perempuan tidak hanya berhadapan dengan kepentingan kelompok perempuan. Sangat mungkin mereka dikelilingi oleh beragam kelompok kepentingan yang mana akan mempengaruhi kepentingan mana yang akan disuarakannya. Dalam konteks seperti ini, seorang Aleg perempuan berpotensi menjalankan fungsi representasi yang subtantif. Suatu bentuk representasi yang mengedepankan bagaimana cara seorang wakil bertindak untuk yang diwakili bukan sekedar cara berdiri seseorang demi orang lain (baca: perempuan). Representasi subtantif lebih berorientasi upaya memperjuangkan kepentingan suatu kelompok (Lovenduski, 2008 : 42). Perwakilan ini lebih melihat pada tindakan dan kebijakan yang dihasilkan oleh para wakil sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi kelompok kepentingan yang beragam. Artinya, penulis juga akan berusaha mengelaborasi bagaimana seorang Aleg perempuan di DPRD Pati bekerja mewakili kepentingan kelompok lain, selain kelompok perempuan. Representasi subtantif ini lebih melihat bagaimana representasi politik ide juga bisa dijalankan. Representasi ini tidak terjebak pada perbedaan identitas (laki-laki atau perempuan), namun lebih bertendens pada komitmen dan konsistensi seseorang dalam memperjuangkan kepentingan publik (public affairs). Pilihan analisis semacam ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan memiliki pengalaman opresi yang berbeda-beda sekaligus kepentingan yang beragam (Tong, 1998:313). Selain penindasan atas dasar jender, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Collins (1990) perempuan secara potensial juga 12 mengalami penindasan terkait kelas, ras, agama dan preferensi seksual (Ritzer dan Goodman, 2007 : 443). Konsep representasi politik itu mengandung dua dimensi penting, yakni dimensi di mana wakil tersebut berdiri untuk (stands for) dan bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Kedua dimensi ini semestinya tidak boleh dipisahkan. Artinya, seorang Aleg perempuan tidak dinilai sekedar perempuan), dia berdiri melainkan mewakili juga kelompok bagaimana dia tertentu (kelompok bertindak untuk memperjuangkan urusan-urusan publik (public affairs) pada umumnya. Namun, perhatian mereka terhadap kelompok perempuan semestinya menjadi parameter utama. Mereka boleh saja mewakili kepentingan kelompok manapun asalkan pada saat yang sama juga tidak mengabaikan kelompok perempuan. Sederhananya, apresiasi atas bentuk representasi subtantif mensyaratkan berjalannya fungsi representasi deskriptif dengan baik. Dengan tidak memisahkan kedua dimensi itu, representasi politik yang dijalankan para Aleg perempuan DPRD Pati kemudian tidak hanya dilihat dalam konteks tindakan konkretnya untuk mengadvokasi kepentingan perempuan saja, melainkan juga kemungkinan mereka turut mewakili kelompok masyarakat yang lain. Lebih tepatnya, representasi politik yang dijalankannya kemudian tidak hanya diukur dengan perhatian mereka atas kepentingan perempuan, melainkan perhatiannya juga atas isu-isu publik lain yang pada prinsipnya juga relevan dengan proyek feminisme5. Dengan demikian, konteks politik yang melingkupi mereka juga akan terdeskripsikan dengan baik. Serta fungsi mereka antara sebagai delegate atau trustee juga bisa dipahami secara proporsional. Sebagai delegate wakil semata-mata hanya mengikuti apa yang menjadi pilihan dari konstituen. Sebagai trustee, seorang wakil berhak mengambil keputusan dengan Proyek feminisme dalam pengertian sebagai gerakan transformasi menuju masyarakat yang adil dan setara di mana hubungan sosialnya dibangun tanpa alas dominasi. Gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sebuah sistem yang tidak adil. Gerakan yang berdiri pada level liberasi dari segala bentuk penindasan, baik struktural, kelas, personal, etnis maupun yang lainnya. Artinya, gerakan itu bukan semata-mata ingin menyerang lakilaki, namun tendensinya lebih pada sistem yang tidak adil serta citra patriarkal bahwa perempuan itu inferior (Fakih, 2008 : 102-173). 5 13 konsiderasi bahwa keputusan itulah yang terbaik karena dia memahami masalah yang dihadapi konstituennya (Marijan, 2011 : 39; Pitkin, 1967 : 43, 56). Jika demikian, seorang wakil yang memposisikan diri sebagai delegate tentunya akan lebih melihat pentingnya partisipasi warga yang diwakilinya, sehingga akan mendorong mekanisme penguatan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan publik. Selain konsepsi yang dikemukakan oleh Pitkin, ada juga Jean Mansbridge yang membuat kategori perwakilan dalam empat bentuk; promissory, anticipatory, gyroscopic dan surrogacy. Perwakilan promissory merupakan bentuk perwakilan di mana wakil dinilai berdasarkan janji-janji yang dibuat di hadapan konstituen pada saat kampanye. Perwakilan anticipatory adalah perwakilan di mana wakil justru berpikir soal pemilu yang akan datang berikutnya tanpa menghiraukan janji-janji kampanyenya. Perwakilan gyroscopic itu menekankan adanya seorang wakil yang berangkat dari pengalaman dirinya sendiri ketika memperbincangkan kepentingan konstituen. Selanjutnya perwakilan surrogacy adalah suatu perwakilan di mana seorang wakil berusaha mewakili konstituennya diluar daerah pemilihannya (Mansbridge, 2003 : 515; Marijan, 2011:41). Konsepsi yang disampaikan oleh Mansbridge tersebut bisa melengkapi konseptualisasi yang disampaikan oleh Pitkin serta memperkaya analisis untuk melihat realitas perwakilan politik. Artinya, tindakan seorang wakil akan lebih dicermati sebagai sesuatu “yang lebih politis”. Di mana seorang wakil dinilai dari konsistensinya untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, kepentingan pribadinya terkait persiapan dalam pemilu periode berikutnya, kesediaannya untuk mempertimbangkan suara aspirasi warga yang diwakilinya, serta komitmennya hanya pada konstituen di dapilnya atau warga secara keseluruhan. b. Model Linkage Politik: Dari Programtik, Kharismatik, hingga Klientelistik Dalam studi politik, istilah linkage dipahami sebagai interkoneksi warga dengan proses pembuatan kebijakan publik [the interconnections 14 between mass opinion and public decision (Clark, 2003: 6)]. Lebih spesifik, Kees Aarts berusaha menjelaskan dengan mengatakan bahwa: “The term 'linkage' refers to the various types of bonds which may exist between individual citizens, sosial organizations, and the political system. In some instances, these bonds are primarily organizational, as in the case of the formal and informal ties between sosial organizations and the political system; for example, the links between trade unions and sosial democratic parties. In other instances, ‘linkage’ refers to more subjective, individual feelings of attachment to organizations and to the political system. (Klingemann dan Fuchs, 2002: 227). Interaksi yang berlangsung ini tentu akan melibatkan beragam aktor yang mana juga disertai dengan tumpang tindihnya beragam kepentingan. Interaksi yang berlangsung pun sangat mungkin saling interdependensi antara menggunakan prosedur formal atau informal, atau mungkin juga antara menggunakan mekanisme demokratik dan non-demokratik. Berangkat dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa ada tiga entitas penting dalam proses “political linkage”; (1) warga negara (the people), (2) aktor/institusi intermediari, (3) urusan publik (the public matters) (Törnquist dalam Törnquist, Webster, dan Stokke, 2009: 10; Hanif, 2009: 3). Dalam konteks studi ini, warga negara kemudian dilihat sebagai subjek politik yang terdiri dari kelompok perempuan dan kelompok kepentingan yang lain. Sedangkan aktor/institusi intermediari di sini adalah mediator yang menghubungkan antara warga dengan urusan-urusan publik. Mediator yang digunakan ini bisa melalui partai politik, ormas-ormas keagamaan, LSM, ataupun tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat. Sedangkan urusan publik yang menjadi area analisis dalam studi ini adalah terkait program PUG dalam ranah kebijakan anggaran dan kebijakan sosial. Dengan mengkaji political linkage ini akan diketahui kelompok (baca: aktor) mana saja yang berinteraksi dengan Aleg perempuan. Pola hubungan seperti apa yang digunakan dalam membangun komunikasi dan berinteraksi dengan beragam aktor tersebut. Menurut Herbert Kitschelt (2000:845-846), setidaknya ada tiga model political linkage antara seorang politisi dengan warga negara yang menjadi konstituennya. Pertama, pola relasi itu terbangun didasarkan pada kharisma personal politisi tersebut bagi warga yang 15 diwakilinya (charismatic linkage). Kedua, pola hubungannya didasarkan pada bagaimana seorang politisi membuat program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, meskipun mereka ini tidak memilihnya (programmatic linkage). Ketiga, suatu bentuk relasi yang dibangun seorang politisi (patron) dengan warga yang diwakilinya (klien) dengan cara memberikan keuntungan materi agar klien tersebut memberikan dukungan (clientelist linkage). Selain pola hubungan seperti disebutkan tadi, yang menarik untuk dikejar lebih jauh adalah sejauh mana relasi yang terbangun itu menjelaskan relasi kuasa dan kontestasi kepentingan para Aleg perempuan. Bagaimanapun para Aleg perempuan ini adalah aktor politik yang memiliki tujuan dan maksud tertentu serta akan dihadapkan dengan konteks tertentu pula. Tujuan dan konteks tersebut kadang membuat mereka harus berkompromi dengan aktor manapun yang bisa membantu terpenuhinya tujuan mereka. Dalam kondisi seperti ini, mereka bisa menjadi penyambung lidah bagi aktor manapun yang memberikan keuntungan politik baginya. Relasi interdependensi semacam ini harus dibongkar lebih dalam agar terihat saling berkelindannya linkage politik yang terbangun. Tentu pola hubungan yang terbangun bisa terlihat demokratis, sebaliknya mungkin juga tidak demokratis. c. Pengarusutamaan Gender: Bukan Sekedar Proses Teknis Di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 pembangunan (9/2000) nasional Pengarusutamaan tentang Pengarusutamaan dijelaskan Gender adalah bahwa strategi yang yang Gender dimaksud dibangun dalam dengan untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Dalam studi ini, program PUG hanya dilihat dalam konteks kebijkan anggaran (budgeting) dan kebijakan sosial (sosial policy). Dengan demikian, setiap pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewajiban dalam mengintegrasikan gender dalam desain pembangunannya. 16 Pada dasarnya, PUG adalah gagasan tentang perencanaan (planning) pembangunan yang berkeadilan gender. Tujuannya adalah untuk membebaskan perempuan dari posisi yang subordinatif, mencapai kesetaraan hak sebagai warga negara (Moser, 2003 : 1). Sedangkan Shirin M. Rai (2003:16) mendefinisikan PUG sebagai berikut: “The process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy of making women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated.” Definisi yang dikemukakan Rai tersebut menegaskan bahwa yang menjadi titik tekan PUG adalah bagaimana mengatasi ketimpangan yang dialami oleh perempuan tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan laki-laki. Agar kedua jenis kelamin tersebut diperlakukan secara adil sebagai warga Negara. Selain sekedar proses teknis dalam proses perencanaan pembangunan, proses politis juga merupkan hal penting yang harus digarisbawahi dalam konteks PUG. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Razavi dan Miller (Dewi, 2006: 12) bahwa PUG harus dipahami sebagai: “Proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Politis, karena bertujuan untuk mengubah alokasi sumber daya, kuasa, kesempatan dan norma sosial.” Proses politis inilah yang justru sering menentukan berjalan tidaknya program PUG. Karena di sinilah relasi kuasa antar aktor bekerja dan saling menegosiasikan kepentingannya untuk menentukan ada tidaknya perubahan terkait alokasi sumber daya, kuasa, serta norma sosial. Setidaknya itulah gambaran sekilas tentang gagasan yang mendasar dari PUG yang dipahami dalam penelitian ini. Jika demikian, tentu saja PUG itu akan berlangsung di berbagai sektor, yang tentunya cakupannya lumayan luas. Sehingga seperti ditegaskan diawal penting dibatasi di sini bahwa program PUG yang dilihat hanya dalam konteks kebijakan anggaran dan kebijakan sosial. Artinya, bagaimana mewujudkan kebijakan anggaran yang responsif gender serta kebijakan sosial yang sensitif gender. Anggaran yang 17 responsif gender tidaklah bermakna anggaran yang hanya memperhatikan kepentingan perempuan dan mengabaikan jenis kelamin yang lain (baca: lakilaki). Konsepsi tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rhonda Sharp dan Debbie Budlender (Mastuti, 2006: 9) bahwa: “Anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran. Bahwa anggaran responsif gender terdiri atas seperangkat alat / instrumen dampak belanja dan penerimaan pemerintah terhadap gender.” Penegasan seperti ini penting untuk mengeliminasi kesalahpahaman yang sering muncul di mana anggaran responsif gender seolah-olah hanya diasosiasikan dengan jenis kelamin perempuan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kebijkan sosial adalah segala bentuk kebijakan yang terkait dengan pemenuhan pelayanan sosial dasar bagi warga Negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, perumahan, dan beragam tunjangan sosial yang bersumber dari pajak. Ada dua karakter kebijakan sosial yang cukup berbeda, pertama karakternya adalah “Social State Model” yang mana masih menuntut keaktifan individu dalam mengatasi risiko sosial yang dialaminya. Sedangkan yang kedua adalah karakter “Welfare State” di mana Negara benar-benar hadir menjadi aktor yang budiman dalam meminimalisir risiko yang ditanggung oleh seluruh warga Negaranya (Triwibowo dan Subono, 2009: 5). Sedangkan menurut Marshall (1965), kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan warga baik melalui pelayanan sosial maupun bantuan keuangan tunai (Suharto, 2005: 10). Beberapa definisi tentang kebijakan sosial tersebut, setidaknya bisa membantu untuk melihat sejauh mana perencanaan pembangunan di Pati memiliki komitmen dalam aspek pelayanan sosial. Kebijakan sosial di suatu daerah itu bisa merupakan inisiatif dan inovasi daerah yang bersangkutan, atau hanya sekedar menjalankan program kebijakan sosial yang memang diselenggarakan pada level nasional. Namun demikian, pada akhirnya yang 18 akan diuraikan di sini tentu saja hanya sebagian dari jenis kebijakan sosial, yang kemudian bisa menuntun untuk mengupas model representasi politik dan linkage politik aleg perempuan yang menjadi focus utama studi ini. E. Alur Pikir Penelitian Bagan I: Alur Pikir PUG (KEBIJAKAN ANGGARAN DAN KEBIJAKAN SOSIAL) ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN MODEL LINKAGE (LANGSUNG/ VIA MEDIATOR) MODEL REPRESENTASI DESKRIPTIF WARGA (KELOMPOK PEREMPUAN DAN KELOMPOK KEPENTINGAN LAIN) F. Definisi Konseptual dan Operasional Kesamaan persepsi antara penulis dan pembaca terkait berbagai konsep dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hal yang penting. Agar ada kesamaan persepsi tersebut, maka penulis akan menjelaskan definisi konseptual dan definisi operasionalnya. Selain itu, definisi konseptual dan operasional ini juga penting sebagai acuan dasar yang menuntun penulis selama proses mencari dan menggali data di lapangan. 19 Definisi-definisi konseptual yang dimaksudkan tersebut adalah sebagaimana di bawah ini: 1. Model representasi adalah sebuah bentuk praktik perwakilan politik yang dijalankan oleh seorang wakil bagi kelompok yang terwakili. Di mana perwakilan politik yang berlangsung ini bisa berbentuk dekriptif, subtantif, maupun simbolik. Perwakilan deskriptif terjadi ketika seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang-orang yang secara objektif serupa. Para wakil merupakan deskripsi dari konstituen yang memiliki karakteristik sama seperti warna kulit, jenis kelamin, dan kelas sosial. Sedangkan perwakilan subtantif berlangsung ketika seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili berbasiskan politik ide dan kepentingan. Bentuk perwakilan ini tidak mensyaratkan adanya kesamaan identitas antara wakil dan yang diwakili. Pembedaan kedua jenis representasi ini bisa dipahami dengan melihat dua dimensi penting perwakilan politik; berdiri untuk (stands for) dan bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. 2. dengan Linkage politik adalah interaksi atau interkoneksi warga proses pembuatan kebijakan publik. Interaksi yang berlangsung ini akan melibatkan tiga entitas penting; warga, aktor/institusi intermediari, dan urusan publik. Warga adalah subjek politik yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, yang terdiri dari kelompok perempuan dan kelompok kelompok kepentingan lain. Sedangkan aktor intermediari adalah para aktor yang menjadi jembatan penghubung antara warga dengan dengan bermacam urusan publik. Aktor ini berfungsi sebagai mediator dalam proses pembuatan kebijakan publik. Aktor ini meliputi partai politik, ormas keagamaan, pemimpin-pemimpin informal yang ada di masyarakat dan sebagainya. Sedangkan bentuk political linkage yang berlangsung di antara mereka bisa berbentuk kharismatik, programatik dan klientelistik. Dari definisi konseptual di atas, maka bisa diturunkan definisi yang lebih operasional sebagai berikut: 20 1. Model representasi adalah praktik perwakilan politik yang dijalankan oleh Aleg perempuan selama menduduki jabatan politik di lembaga perwakilan formal di DPRD Pati terkait program PUG dalam pembangunan daerah. Dalam proses advokasi program PUG tersebut, perwakilan politik yang dijalankan oleh mereka sangat mungkin aktif atau bahkan pasif. Pada saat yang sama mereka bisa saja mewakili kepentingan kelompok berbasiskan kesamaan identitas kultur keagamaannya. 2. Linkage politik adalah pola hubungan interaksi ataupun pertukaran yang terjadi antara Aleg perempuan dengan berbagai aktor (baik aktor intermediari maupun yang lain) yang ada di sekelilingnya terkait program PUG dalam pembangunan di Pati. Di mana interaksi yang dibangun oleh para Aleg perempuan ini bentuknya bisa berbedabeda di masing-masing aktor. Dengan aktor tertentu mereka mungkin mempraktikkan linkage kharismatik, sedangkan dengan aktor yang lain mungkin dengan linkage programatik ataupun linkage klientelistik. Dengan memahami bentuk political linkage tersebut akan terlihat juga bagimana relasi kuasa dan kontestasi kepentingan diantara mereka. G. Metode Penelitian a. Metode dan Jenis Penelitian Pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini cukup tepat digunakan untuk mengelaborasi pengalaman subjektif seseorang (Marsh dan Stoker, 2011:242). Di mana pengalaman yang dielaborasi dalam penelitian ini adalah pengalaman Aleg perempuan DPRD Pati terkait representasi politik dan linkage politik yang mereka jalankan. Penulis menggali informasi secara elaboratif dari para subjek penelitian ini, di mana ada sembilan aleg perempuan. Tidak hanya itu, dari informasi yang didapat pada akhirnya dikembangkan lagi dengan 21 menelusuri berbagai pihak terkait (baca: informan) untuk melengkapi jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis bisa mendapatkan kedalaman informasi dari pihak-pihak terkait. Kedalaman informasi ini membuat penelitian ini terhindar dari kecerobohan dalam menyimpulkan sebuah realitas sebagai sesuatu yang objektif. Melalui metode inilah kebenaran justru terlahir dalam proses yang intersubjektif, dan pada saat itulah kemudian penulis berusaha melakukan objektifikasi dan justifikasi dari proses yang intersubjektif. Artinya, pendapat salah seorang aleg perempuan bisa dikuatkan atau dilemahkan oleh aleg perempun yang lainnya. Sehingga semua data informasi yang diperoleh diperlakukan secara kritis dan dikonfrontasikan satu sama lain untuk menemukan pendapat yang paling kuat dari para informan yang ada. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam studi ini adalah studi kasus kasus tunggal (single case study), di DPRD Pati. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Robert E. Stake, di antara kelebihan dari pendekatan studi kasus adalah memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan teori (refining theory). Jadi, sangat mungkin penelitian atas suatu kasus tertentu akan memperkuat teori yang sudah ada, ataupun sebaliknya berpotensi memperbaiki atau mengevaluasinya. Selain itu, kompleksitas persoalan dalam setiap kasus yang diteliti juga bisa menjadi bahan penelitian lanjutan di kemudian hari. Studi kasus juga akan memperlihatkan bagaimana keterbatasan sikap generalisasi atas realitas sosial (Denzin dan Lincoln, 2009:313). Sehingga dimensi lokalitas suatu realitas sosial menjadi sangat diperhatikan. Dalam studi kasus ini, penulis mengelaborasi bagaimana model representasi politik dan model linkage politik yang dijalankan oleh para anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Pati. Jadi secara spesifik terfokus pada anggota legislatif perempuan. Pengalaman anggota legislatif perempuan di DPRD Pati mungkin terjadi di tempat lain dan mungkin juga tidak. Oleh karena itu, studi kasus ini tidak berpretensi menjelaskan realitas kasus yang terjadi di Kabupaten lain. Meskipun terbuka kemungkinan bahwa 22 temuan atas kasus di Pati ini bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena kasus di tempat yang lain. b. Teknik Pengumpulan Data Pelaksanaan pengumpulan data dalam studi ini menggunakan teknik observasi langsung, wawancara mendalam, dan kajian dokumen (Yin 2011:101-116; Creswell, 2007:138-141). Penulis menggunakan ketiga teknik ini secara bersamaan, di mana satu sama lain saling menguatkan sebagai sumber bukti. Teknik observasi langsung ini cukup membantu penulis untuk menemukan data tambahan, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Yin (2011:113) bahwa observasi atas lingkungan sosial atau unit organisasi tertentu akan memperkaya informasi untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti. Observasi juga akan memudahkan penulis untuk bisa mengakses setting sosial yang ada tanpa dituntut untuk berinteraksi langsung dengan partisipan, karena bersifat tidak mencolok (Adler dan Adler dalam Denzin dan Lincoln, 2009:529). Observasi ini nantinya penulis lakukan dengan cara mengamati tindakan dan perilaku para anggota legislatif perempuan selama berada di dalam gedung DPRD (saat rapat, sidang dan aktivitas lainnya) maupun di luar gedung ketika mereka berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang menjadi konstituennya. Penulis akan mencatat hasil pengamatan ini sebagai salah satu bahan yang akan menjelaskan hasil penelitian ini. Teknik selanjutnya adalah wawancara mendalam (indepth interview). Wawancara merupakan sumber informasi yang krusial dan esensial dalam melakukan studi kasus. Penulis akan melakukakan wawancara dengan semua anggota legislatif perempuan yang ada. Selain itu juga dengan Ketua DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi serta para aktor yang berada di ranah intermediari meliputi pengurus partai politik, pengurus ormas keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah, dll), aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, serta para tokoh masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan tipe open-ended, di mana penulis bisa mengajukan pertanyaan 23 pada informan kunci tentang fakta sebuah kasus di samping pendapat mereka tentang kasus tersebut (Yin 2011:108). Artinya, selain menggali kebenaran kasus secara akurat dan faktual, penulis juga akan meminta pada informan untuk memberikan penilaian subjektifnya atas kasus tersebut. Tentu pelaksanaan wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan, dan kalau dibutuhkan penulis juga akan menggali informasi dari para informan kunci melalui obrolan-obrolan informal jika cara seperti ini ternyata lebih strategis. Teknik yang terakhir adalah kajian dokumen. Kajian dokumen ini sangat penting untuk memverifikasi data dan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Bukti-bukti dokumenter ini bisa berupa artikel, laporan hasil penelitian, dokumentasi kegiatan, produk kebijakan semisal peraturan daerah, surat, maupun dokumen administratif yang lain. Meskipun bukti dokumenter ini bisa dipergunakan untuk memverifikasi hasil wawancara, namun bukan berarti merupakan sumber kebenaran mutlak. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan multi sumber. Masing-masing sumber akan diperlakukan secara teliti dan hati-hati agar terhindar dari kesalahan membuat penafsiran. Dari penggunaan teknik pengumpulan data tersebut, maka penelitian ini nantinya menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan adalah data hasil wawancara langsung dari para informan kunci secara mendalam. Sedangkan data sekundernya adalah semua bentuk dokumen pendukung yang menunjang penelitian ini. Pada prinsipnya, kedua jenis data ini sama pentingnya dan saling melengkapi satu sama lain. Lebih spesifiknya, dalam studi ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati periode 2009-2014. Secara keseluruhan mereka ini berjumlah tujuh (7) orang, dua orang berasal dari PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), masing-masing satu orang berasal dari Partai Demokrat, PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama), PDP (Partai Demokrasi Pembaruan), Partai Golkar, dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). 24 Mereka tersebut adalah sosok yang berbeda satu sama lain, baik terkait afiliasi partai politiknya maupun latar belakang kultur keagamaannya. Afiliasi partai politik dan latar belakang kultur keagamannya ini tentu akan mempengaruhi preferensi politik mereka. Sehingga mereka tidak bisa dibaca sebagai individu yang hanya menyandang identitas kelamin perempuan, melainkan juga memiliki afiliasi politik, identitas keagamaan ataupun kelas sosial tertentu. Keragaman identitas ini akan mempengaruhi bagaimana mereka melihat pengalaman opresi yang dialaminya atau yang dialami masyarakat yang diwakilinya. Selain mereka, tentu juga akan melibatkan aktor-aktor di level eksekutif dan ranah intermediari. Secara spesifik, informan di level eksekutif, seperti dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Serta aktoraktor intermediari yang dimaksudkan itu meliputi pengurus ormas keagamaan seperti Fatayat NU dan Aisyiah. Informasi dari masing-masing aktor tersebut sangat relevan dan dibutuhkan untuk bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. c. Teknik Analisis Data Dari sederetan data primer dan sekunder yang penulis peroleh, tentu tidak semuanya akan dinarasikan. Data-data tersebut akan diambil secara selektif sesuai kegunaannya. Penulis hanya akan memilih informasi-informasi yang memiliki relevansi erat dengan maksud penelitian ini. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Robert E. Stake bahwa keputusan untuk menentukan informasi mana yang penting dan dibutuhkan adalah otoritas peneliti (Denzin dan Lincoln, 2009:305). Sehingga merupakan keniscayaan jika kemudian penulis membuang beberapa informasi yang dianggap tidak terlalu krusial. Pendek kata, penulis akan mengabaikan data wawancara yang cenderung hanya retorika belaka dari informan yang bersangkutan. Setiap data informasi yang ada akan dipahami dan diinterpretasikan secara kritis dan reflektif untuk menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga ketiga sumber bukti yang ada (hasil observasi, hasil 25 wawancara, hasil kajian dokumen) akan penulis konfrontasikan satu sama lain untuk mengetahui informasi mana yang paling kuat. Pada dasarnya proses ekstraksi ini akan penulis lakukan sejak fase pengumpulan data hingga saat analisis data yang sudah terkompilasi. Lebih konkritnya, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, untuk mengkompilasi data ini setidaknya penulis akan menggunakan beberapa teknik seperti; mengelompokkan informasi di dalam daftar yang berbeda, membuat matriks kategori sekaligus memeriksa jenis data yang saling terkait, ataupun juga memasukkan informasi berdasarkan urutan kronologis ataupun skema waktu yang lain (Yin 2011:135). H. Sistematika Penulisan Pembahasan materi dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab. Bab pertama. Bab ini sebagai pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode peneltian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini merupakan pengantar untuk meyakinkan pembaca tentang mengapa penting untuk melakukan studi ini. Bab kedua. Bb ini menjelaskan konteks politik yang mempengaruhi model representasi politik dan linkage politik aleg perempuan. Konteks politik ini ditandai dengan program pengarusutamaan gender di Pati yang ternyata mengalami stagnasi. Stagnasi ini disebabkan oleh beberapa faktor; depolitisasi demokrasi, aleg perempuannya miskin perspektif gender, serta kuatnya struktur patriaki dan lemahny peran aktor intermediary. Di mana dari faktor-faktor yang ada, arus depolitisasi demokrasi menjadi faktor yang paling dominan. Di bagian akhir berusaha mendiskusikan tentang upaya transformasi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi stagnasi tersebut. Bab ketiga. Bab ini mendeskripsikan model-model representasi politik yang dijalankan oleh aleg perempuan, mulai dari model representasi deskriptif-aktif, deskriptif-pasif, hingga deskriptif-simbolik. Model-model tersebut ditandai oleh bagaimana komitmen politik para aleg jika dilihat dari 26 aspek gender-interest dan self-interest. Apakah lebih berorientasi pada gender-interest atau sebaliknya lebih pad self-interest, atau bahkan saling interdependensi di antara keduanya. Pada bagian akhir berusaha memetakan tentang pengaruh model representasi tersebut pada advokasi program PUG. Bab keempat. Bab ini memaparkan model-model linkage politik yang dijalankan oleh para aleg perempuan, mulai dari linkage pseudoprogramatik, linkage kharismatik, hingga linkage klientelistik. Di mana beroperasinya linkage tersebut ada yang dilaksanakn secara lngsung oleh aleg yng bersangkutan, namun juga lebih banyak yang melalui mediator (mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga broker politik berbasis tim sukses). Pada bagian akhir juga berusaha memetakan bagaimana pengaruh model linkage tersebut bagi advokasi program PUG terkait kebijakan anggaran dan sosial. Bab kelima. Sebagai pembahasan penutup, bab ini berisi tentang jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini sekaligus refleksi teoritiknya dalam konteks diskursus keterwakilan politik perempuan. [] 27