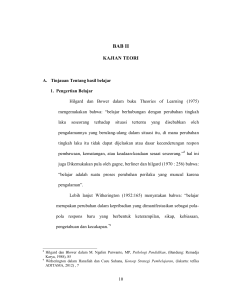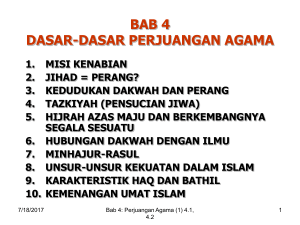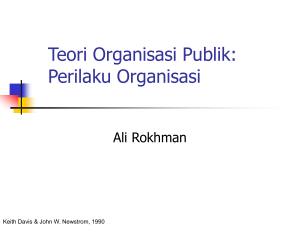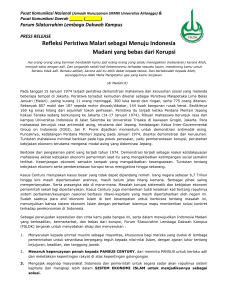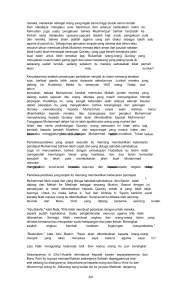Dialog teks dan Nalar publik
advertisement

Dialog Teks dan Nalar Publik1 Sebuah pengandaian konteks Oleh : Khaled an-Nadzif Hukum akan seperti penggilas besi seandainya di baliknya kita tidak boleh menyidik asal-usulnya di suatu masa, di suatu tempat (Goenawan Muhammad) Pendahuluan Seandaianya Al-Qur`an adalah buku hukum yang tanpa puisi. Seandaianya sabda Nabi layaknya Kepres yang tegas dan berbatas. Maka Islam mungkin sudah merupakan baju usang yang tak terpakai, teronggok di pinggiran sejarah, primitif dan bengis. Atau seperti kutipan dari Manuel, “Hanya mala dan sifat yang tak manusiawi”2, Tetapi bukan itu yang terjadi. Kitab suci Tuhan itu memukau bukan saja karena tata dan nilai yang diserukannya, tetapi juga karena maknanya yang misteri, kekuatannya untuk bergulat dan menjadi antitesa bagi kemusykilan peradaban, dan potensinya untuk berpesan terhadap pihak ketiga yang dengan diam mendengar dialognya. Tesis dan antitesis yang tak putus-putusnya adalah cerita tentang teks dan tafsir, yang berlaku untuk apa saja. Apalagi dalam hal naskah atau kitab yang penggubahnya sudah tak bisa dihubungi lagi atau memang tak bisa ditanya seperti Kitab Suci. Begitu sebuah teks selesai dan sampai ke tangan pembaca sang pengarang sudah mati seperti perkataan Roland Barthes yang terkenal3. Sang pengarang (l’auteur atau author), yang umumnya dianggap sebagai pemegang kunci kebenaran dan pemegang otoritas terakhir, harus dianggap sudah lepas kuasa. Sebab akhirnya setiap pembacalah yang membentuk tafsirnya sendiri. Mungkin sebab itu penafsiran Qur`an tidak mungkin ’’ditutup”. Persoalannya, tentu senantiasa ada dorongan ke arah penutupan proses tafsir. Ada lembaga yang dibentuk untuk menentukan mana tafsir yang tepat, mana yang harus dibabat. Ada kodifikasi yang dilakukan untuk mencegah kekacauan, ada lapisan baru pemegang hegemoni tafsir, baik yang dideking (dilindungi) oleh kekuasaan ataupun oleh tradisi.4 Makalah ini sedikit akan mengintip masalah ini. Bagaimana teks berhadapan dengan nalar publik. Apakah yang terjadi antara keduanya, dialog atau dogma?. 1 Makalah dipresentasikan dalam diskusi IKAMARU RAM 3 September 2007/2008 2 Kutipan dari 26 percakapan Manuel II, Dialog tentang Bizantium yang rapuh dan Islam yang bengis dan ganas, Belakangan Paus Benediktus juga mengutip penggalan dari 26 dialog ini tentang “Tuhan yang semau-maunya, tak dibatasi dengan kebenaran dan kebaikan” Goenawan Muhammad, Catatan Pinggir, Percakapan ke-7, Majalah Tempo Edisi. 30/XXXV/18 - 24 September 2006. 3 Goenawan Muhammad, Catatan Pinggir, Arkoun, Tempo, Edisi. 11/XXIX/15 - 21 Mei 2000 . 4 Ibid 1 Bagaimana perpindahan otoritas berlangsung. Bagaimana konstelasi ini berjalan di zaman Nabi. Sekaligus kemungkinan potensinya untuk Masyarakat Islam Indonesia. 1. Makna teks dan fenomena Nalar Publik. Abdul Jawwad Yasin menerjemahkan teks, atau yang disebutnya sebagai al-Islam alNasyi, sebagai yang otoritatif dan punya kandungan transendental, melingkupi hanya pada al-Qur`an dan al-Sunnah shahihah5. Kedua hal inilah yang pasti dan tak terbantah. Penghilangan otoritas keduanya akan menyebabkan dekonstruksi terhadap bangunan Islam secara keseluruhan. Namun perlu dicermati bahwa yang otoritatif secara otonom hanyalah al-Qur`an dan al-Sunnah secara tekstual, menurut apa yang dimaksudkan Tuhan didalamnya. Sedangkan konteks yang melingkupi, interpretasi yang berlangsung, maupun realitas sosial yang membentuk dan budaya yang terproduk dari keduanya sudah tak lagi punya otoritas otonom. Pun ada jenjang antara al-Qur`an dan al-Sunnah. Sedangkan nalar publik termanifestasi melalui ruang, waktu, budaya, kepentingan, tata sopan, juga kecenderungan intelektual per individu. Nalar publik ini juga bisa berarti fenomena sosial yang digerakkan oleh “kesadaran bawah sadar” komunitas. Pergulatan antara keduanya terjadi pada semua agama samawi, dimana teks turun sebagai awal, yang harus ditaati, di tengah komunitas yang sudah berbudaya dan punya seperangkat istiadat. 2. Tinjauan historis (al-Qur`an tidak turun dalam ruang hampa). Saat itu, Makkah adalah pusat peradaban arab. Sirkulasi ekonomi maupun legitimasi politik semuanya berpangkal di kota kecil itu6. Ada banyak nama besar yang bergaung di seluruh jazirah, dan masih berdengung hingga kini. Dan Muhammad Saw sebenarnya tak datang dengan hal yang baru. Ada semacam kerinduan pada masyarakat arab tentang mitologi Ibrahim, dimana “yang benar” tak terletak di berhala-berhala mereka tetapi jauh di masa lampau yang hilang. Pada masyarakat Madinah kecenderungan ini lebih kentara dengan berhembusnya rumor tentang akan datangnya Nabi Pembebas yang bersumber dari para rahib yahudi. Suatu ketika, seorang penguasa Bani Umayyah bernama Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Urwah bin Zubeir mengapa kaum Quraisy menentang dakwah Nabi. Urwah menjawab, “Ketika Nabi menyeru kaumnya dengan petunjuk dan pencerahan yang diturunkan kepadanya, mereka mulanya tidak menjauh, dan nyaris akan menanggapinya. Sampai kemudian Nabi menyebut-nyebut berhala mereka, maka datanglah sekelompok orang berharta melimpah mengingatkan mereka akan bahaya dakwah tersebut. Sejak saat itulah mereka menghindar dari Nabi, kecuali sedikit yang dijaga oleh Allah”. Menurut Al-Jabiri dan beberapa pengkaji tentang keyakinan Quraisy di masa Nabi, berhala-berhala bagi kaum Quraisy tidak sampai derajat “yang sakral” sehingga seseorang rela mati untuk mempertahankan kesakralannya.7 Berhala-berhala tersebut tak lebih dari 5 Abdul Jawwad Yasin, al-Sulthah fi al-Islam, al-‘aqlu al-Fiqh baina al-Nasy wa al-Tarikh, (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi) hal. 13. 6 Novriantoni Kahar, Al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam. 7 Al-Jabiri antara lain memberi alasan, misalnya, di Mekkah tidak terdapat kaum agamawan yang mengurusi secara khusus persoalan agama. Sementara itu, nama-nama Tuhan mereka, seperti Latta, Uzza, dan Manât, yang biasa disebut sebagai “anak perempuan tuhan” lebih berisifat hinaan daripada sakralisasi. Sebab, maklum bahwa kultur Arab ketika itu sangat tidak menyukai anak 2 simbol untuk menjaga sumber pendapatan dan tulang punggung ekonomi mereka. Makkah merupakan sentral berhala masing-masing kabilah tempat mereka berkumpul dalam ritual haji yang banyak mendatangkan devisa bagi suku-suku Quraisy. Rasionalisasi kekhawatiran mereka akan berhala tersebut tak lebih karena itu sama artinya dengan bertindak lancang atas sumber pendapatan dalam haji dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengannya. Kekuatiran akan kehilangan sumber-sumber pendapatan mereka, membuat Quraisy dengan keras menentang dakwah Nabi. Pada periode Makkah ini, ayat al-Qur`an yang turun bisa dibedakan dengan corak da’wah yang dijalankan Nabi. Al-Jabiri membagi dakwah Nabi pada periode Makkah ke dalam dua fase. Pertama, fase dakwah gerilya (sirran); dan kedua, dakwah terang-terangan (jahran). Di dalam fase dakwah gerilya (kurang lebih selama 3 tahun), ayat-ayat yang turun sebagai formasi akidah masih sangat menjauh dari kesan konfrontasi atas elit Quraisy. Dalam prakteknya, Nabi juga menghindari konfrontasi langsung dengan oknum-oknum ternama Quraisy. Tema yang diangkat pun masih berupa prinsip-prinsip umum yang mengandung universalisme syari’at, latar belakang dari agama-agama yang pernah diturunkan, dan penjelasan bahwa Islam adalah kelanjutan dari agama-agama tersebut. Seperti penegasan bahwa kaum pagan dan kafir akan mendapat sanksi dunia dan akhirat, bukan hanya karena kekufuran dan paganisme yang mereka anut, tapi juga disebabkan penguasaan mereka atas sumber-sumber kekayaan, dan ketidakpedulian atas kaum fakir miskin. Pada fase kedua dakwah periode Mekkah (fase terang-terangan), yang berlanjut dari tahun keempat kenabian sampai tahun 13, mulai terjadi konfrontasi langsung pada level akidah antara generasi awal Islam dengan elit Quraisy. Pada fase ini, ayat-ayat AlQur`an yang turun sudah mulai melakukan kecaman-kecaman dan secara eksplisit bertentangan dengan kepercayaan dan kepentingan kaum Quraisy. Fase ini disebut oleh Al-Jabiri sebagai fase dakwah terang-terangan dan konfrontasi atas berhala-berhala kaum kafir Mekkah. Pada fase ini juga reaksi Quraisy semakin keras, dari bentuk ejekan dan caci maki sampai pada penyiksaan jasmani. Sosok-sosok seperti Abu Lahab (paman Nabi sendiri), dan isterinya Ummu Jamil (saudara Abu Sufyan), elit-elit pembesar Quraisy seperti Walid bin Mughirah mulai tampil sebagai sosok-sosok yang memberikan tanggapan keras terhadap dakwah Nabi. Ketika momentum hijrah terbuka dan kaum muslimin menemukan kendali atas aset materiil maupun moril, metode dakwah yang dipakai pun berubah, seperti mengutus ekspedisi dan menyerang kafilah dagang Quraisy, bukan semata-mata karena takut dan melarikan diri dari kejaran Quraisy. Cara-cara berdakwah seperti ini, ketika itu “dapat dibenarkan” sebagai bentuk “embargo” ekonomi atas Makkah, demi menanti penyerahan total secara politis agar mereka selanjutnya memeluk Islam. Mulai fase ini, ayat-ayat partikular dan teknis turun. Seperti surat Al-Anfal yang memberikan tuntunan teknis distribusi jatah ghanimah, ayat-ayat mawaris, hudud, perang, dll. Pada periode Madinah ini, dialog yang terjadi antara kaum Muslimin, dengan segala tetek bengek rona permasalahanya, dan al-Qur`an sebagai bentuk apresiasi ketuhanan maupun sabda Nabi menjadi semakin intim. Perintah, sanggahan, bantahan, tawaran, dan solusi terjalin dalam perdebatan yang akrab. Persoalan warisan mencerminkan kompromi Islam antara teks dengan realitas. Pada masa Nabi, masyarakat Arab terbiasa melangsungkan pernikahan antar suku demi persaudaraan dan perempuan.Bagaimana mungkin mereka memberi nama “tuhan” mereka dengan nama-nama perempuan dan menyebutnya “anak-anak perempuan tuhan”?. Ibid. 3 persahabatan. Namun itu justru bermasalah dan menimbulkan konflik, sebab perempuan yang menjadi istri suku lain, hartanya otomatis menjadi milik suku suaminya waktu bagibagi warisan. Ini menyebabkan penumpukan harta pada suku suami. Oleh karena itu, masyarakat Arab kemudian meniadakan hak waris bagi perempuan agar tidak terjadi peperangan yang dipicu urusan warisan. Namun ketika Islam datang, Al-Qur`an justru memutuskan hak perempuan setengah dari hak laki-laki. Ketetapan itu berangkat dari iktikad untuk menghormati hak perempuan dalam konteks zaman itu, sekaligus juga apresiasi terhadap realitas yang terjadi. Dari contoh di atas, tampak jelas betapa Al-Qur`an tidak turun di ruang hampa, melainkan terkonstruksi secara kultural dan terstruktur secara historis. Artinya, selain sisi tekstualnya yang transenden dan sakral, ia juga hasil budaya dan produk pergulatan tradisi. Keadaannya yang membaku dalam tata lingkup linguistik arab dan sejarah penurunannya yang tidak serta merta mengindikasikan dengan jelas sisi ini. Al-Qur`an bukan 10 firman Tuhan yang diturunkan nan jauh di atas Mahameru, atau hukum Hammurabi yang tercetak mati di tugu batu. Al-Qur`an turun ditengah sekelompok manusia, yang kadang lupa, dan juga tak menerimanya dengan membuta. Ada bantahan, sanggahan, tawaran dari nalar penerimanya yang membuat kitab suci ini hidup dan berdinamika8. 3. Sebuah pengandaian konteks “Peradaban Islam adalah peradaban teks” demikian tesis Nasr Hamid Abu Zayd, pemikir asal Mesir yang sudah dikenal luas di dunia Islam itu (Abu Zayd: 2003). Pernyataan Abu Zayd dibenarkan oleh produk pemikiran Islam dari abad ke abad yang terus merujuk teks. Kitab-kitab fiqih, bisa dikatakan sebagai bentuk penjabaran dari peradaban teks tersebut. Berbeda dengan Barat yang memulai pergerakan pencerahannya dari titik konfrontasi terhadap dogma dan absolutisme gereja. Dengan penjelasan di atas, menjadi jelas bahwa teks tak bisa dilepaskan dari gerak peradaban umat Islam. Namun persoalannyaa adalah teks yang diartikan secara literal. Maksudnya, teks yang sesungguhnya merupakan produk sejarah, sintesis dari dialog dan pergulatan yang akrab antara Tuhan dan Nalar Publik masyarakat arab zaman Nabi --dan karena itu profan-- dalam prakteknya dipandang bertuah, sakral, dan melampaui sejarah. Maka yang terjadi adalah kesenjangan antara teks dan realitas kemanusiaan. Kesenjangan itu bisa berbentuk kegagapan akan ide-ide yang berasal dari “yang bukan salafus shalihin”, fundamentalisme yang akut9, sehingga menimbulkan rasa terasing, sikap anti Barat, serta upaya menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam yang dianggap “murni”. Upaya menggapai yang “murni” ini, memunculkan gerakan pemurnian (puritanisasi) atas hal-hal yang dianggap bukan asli Islam. 8 Contoh kasusnya dapat dicermati dari peristiwa pengharaman khamr, pembolehan berperang di bulan haram, kasus pembebasan Makkah, Deklarasi piagam Madinah, Hadits pembuahan pohon kurma, Hadits larangan memotong semak dan pepohonan di tanah haram kecuali sejenis pohon yang merupakan bahan baku rumah pada saat itu, pembolehan melakukan aksi militer dan embargo ekonomi, pembagian jatah ghanimah, ayat poligami, ayat hijab, dll. 9 Gejala ini bukan khas Islam, di setiap agama hampir pasti terdapat kelompok maupun personal yang berpusing dalam fenomena ini. Baruch Goldstein, seorang yahudi yang menembaki warga Palestina di Masjid Ibrahim, hebron. Kelompok Ku Klux Klan yang meneror orang hitam, dan beberapa lainnya memberikan potret dari gerakan ini. Lihat, Goenawan Muhammad, Catatan Pinggir, Tafsir yang fanatik, Edisi.05/XXIV/02-8April1994. 4 Kegagapan lain berupa ketidakmampuan mengaitkan antara Islam dengan persoalan kemanusiaan universal seperti kemiskinan, diskriminasi, eksploitasi, marginalisasi, kebodohan, korupsi, pelecehan seksual, dsb. Padahal, yang menjadi raison d’etre kehadiran Nabi justru untuk mengatasi problem-problem tersebut. Agenda perjuangan Nabi sesungguhnya adalah pembebasan manusia dari belenggu dan eksploitasi kelompok tertentu, pemerintahan yang egaliter terhadap semua golongan. Konsep tauhid beliau selalu bertalian erat dengan proses perubahan sosial dari tatanan yang eksploitatif menuju yang berkeadilan. Oleh karena itu, ketika Islam tidak lagi dikaitkan dengan ide besar transformasi sosial, maka sesungguhnya usaha tersebut telah mengkhianati semangat kelahirannya sendiri. Disinilah letak penting upaya menafsir ulang (rethinking) teks yang dikumandangkan intelektual muslim dari pelbagai penjuru dunia: Al-Jabiri (proyek Kritik Nalar Arab), Arkoun (Kritik Nalar Islam), Essack (Hermeneutika Pembebasan), Hanafi (Kiri Islam), Khaled Abou el-Fadl (yang otoritatif dan otoritarianisme) dan seterusnya. Tanpa meninggalkan teks, mereka menawarkan metodologi untuk mempertahankan eksistensi keberagamaan kita saat ini. Disini, teks diposisikan sebagai obyek, yang sekalipun otoritatif secara otonom namun membuka diri untuk terus berdialog dan bersinggungan dengan nalar publik yang terus berubah-ubah. Pendekatan-pendekatan seperti ini sebenarnya bukan barang asing di tubuh peradaban umat Islam sendiri. Kasus pembatalan had potong tangan, hukuman penjara untuk orang yang murtad dalam kondisi perang, penetapan milik Negara untuk tanah rampasan perang, diangkatnya seorang perempuan sebagai pengawas pasar, keempatnya pada zaman Umar, kemudian memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat pada zaman Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz yang menolak hadiah dalam posisinya sebagai birokrat, mengindikasikan dengan jelas betapa masyarakat Islam generasi awal memegang kontrol terhadap maslahat dirinya tanpa menghilangkan otoritas otonom dalam teks. Itu artinya, nalar publik, yang tersimpul dalam tradisi, budaya, kebutuhan Masyarakat, dan efektifitas Zaman harus diberikan porsi yang sesuai sehingga memungkinkan untuk berdialog dengan teks secara proporsional. Makna yang dimaksudkan oleh teks, dengan kata lain, tidak bisa dengan sewenang-wenang dibaca tanpa bersinggungan dengan gerak perabadan yang sedang berlangsung. Maka ketika sebuah hukum (yang partikular) ditiadakan karena bertentangan dengan nalar publik, itu tak berarti ia dihapus secara permanen, karena efektifitasnya mungkin akan terulang pada masa dan tempat yang lain. Kasus “batal atau tidaknya puasa karena berciuman dengan istri” mencerminkan dengan indah betapa akrabnya pembacaan seperti ini berlangsung di Zaman Nabi. Mahmud Muhammad Thaha menyebutkan bahwa konsep nasakh-mansukh tidak bisa dengan serta merta diberlakukan hanya dengan melihat urutan waktu turunnya ayat. Sifat universal dan partikular maupun sektoral dalam ayat juga harus diperhatikan. Alihalih mengatakan ayat-ayat Makkah dihapus oleh ayat-ayat setelah hijrah, tetapi yang seharusnya adalah ayat-ayat Madinah yang dihapus oleh ayat-ayat sebelum hijrah, mengingat sifat universal dan partikular dari kedua jenis ayat tersebut 10. Disini efektifitas ayat untuk menanggulangi atau memberi solusi terhadap fenomena yang terjadi lebih ditekankan sehingga sintesis yang terjadi bukan jumud dan ketundukan buta, melainkah sinergi dan perkelindanan yang hidup. 10 Hisam Rusydi al-Ghali, Bi al-Hujjat wa al-Burhan Laa Naskh fi al-Qur’an, (cairo: Maktab al-Aribi lil Ma’arif, 2005) hal. 29 5 Teks, pada akhirnya tidak bisa lepas dari konteks yang mengitari, historis pembacanya, dan “maksud tekstual” nya. “Maksud tekstual” di sini adalah visualisasi yang tergelar dalam struktur linguistik bahasa tersebut. Dengan menampik maksud tekstual dan struktur ekstratekstual sebuah teks, pembaca atau interpreter akan terjatuh pada apa yang disebut Abu Zayd sebagai pembacaan ideologis-tendensius (qira’ah talwiniyah mughridlah) atas teks. Pembacaan yang ideologis dan tendensius ini pada akhirnya melahirkan apa yang disebut Khaled Abou el-Fadl sebagai “hermeneutika otoriter” (authoritarian hermeneutic), sebuah pembacaan yang “paling benar sendiri”, “dipaksakan untuk diterima”, dan buta terhadap cela yang menempel pada dahi manusia. 4. Islam Indonesia, dialog ketiga. Ketika hadir lewat para saudagar, al-Qur`an memang bukan lagi sebundel Kitab suci yang puitik. Didalamnya sudah terbalut berbagai warna penafsiran dan pengejawentahan yang kadangkala lebih dominan dari teks aslinya. Apalagi Indonesia bukan padang pasir yang tandus. Peradaban dan tata sopan yang berlaku pun khas daerah tropis yang basah dan tak dikenal di arab. Maka teks menjadi sosok berbeda. Ia termanifestasikan dalam seperangkat adat yang diwarisi atau seorang yang suci. Masalah timbul ketika gugatan terhadap sang sosok muncul. Suara sumbang itu terdengar mungkin karena katidakpuasan terhadap otoritas yang tanpa batas, tuntutan akan hak, atau reaksi terhadap stimultan yang datang dari luar. Perdebatan dimulai. Argumen saling tumbuk. Masyarakat panik. Ketika perdebatan itu memanjang dan sang sosok mulai tak sabar, metode pun diganti. Bukan lagi mulut yang membantah, bukan lagi hujjah yang diacungkan. Fatwa diserukan. Dan pemusnahan pun dimulai. Yang murtad harus lenyap. Yang tak sehati harus mati. Tentu saja Atas Nama Tuhan. Indonesia bukan bumi Nabi. Wahyu pun tak turun di gerumbul tropis ini. Tapi justru itu tradisi mempunyai kedewasaannya disini. Perempuan lebih dihargai. Dan keris diselipkan di punggung, bukan di pinggang. Maka Islam Indonesia tidak bisa dan tidak boleh diterjemahkan dengan Islam Makkah atau bahkan Islam Zaman Nabi secara semena-mena. Ada dialog yang harus terjadi dan teks tidak boleh dibakukan menjadi satu bundel kitab yang bisu dan suci. Artinya, potensi nalar publik untuk berdialog dan bersinggungan dengan teks secara proporsional harus diangkat ke panggung realitas. Masyarakat harus mulai bangun untuk menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan “tiran dari langi” yang memaksa dan menaklukkan. Al-Qur`an tidak turun sebagai awal, dan bersamanya juga tidak ada sebaris batalion yang siap dengan senapan terkokang terhadap siapapun yang membangkang, atau sekadar bersuara sumbang. Ia hidup sebagai teman dialog akan musykil dan kesewenangwenangan, ketidakadilan, eksploitasi, permerkosaan hak, dan itu tidak akan tercapai kecuali kita sadar terhadap potensi antitesa dalam diri kita. Dengan demikian Islam di Indonesia tidak akan lagi tercitra sebagai setumpuk adat padang pasir yang garang dan memaksa, pesan Nabi pun akan tampak dalam balutan yang merangkul, bukan “Yang mencambuk” dan mengacungkan lembing terhadap liyan. Gagasan ini sebenarnya bukan barang baru. Hasbi Ash-Shiddiqi, (1904-1975) telah mengatakannya ditahun 1940, dan kembali mendengungkannya pada 196011. Mengkondisikan Islam Indonesia ini bukan berarti mengubah Syari’at atau memarginalkan orotitas teks. Karena keduanya adalah poros yang tak terbantah dan 11 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqh Indonesia, penggagas dan gagasannya, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal : 20 6 permanen. Yang berubah adalah tafsir, sintetis, dan solusi. Ini berarti, kalau toh poligami bisa dan mungkin diperbolehkan di arab, tetapi akan sangat berbeda ketika ditafsiri dan diterapkan di Indonesia. Atau meskipun Umat Islam adalah mayoritas, namun itu tak mewajibkan kita untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan demokratis saat ini dan kemudian mendirikan Khilafah Islam. Karena kita tak hidup di zaman dimana persaingan kabilah menjadi gesekan paling tajam terhadap kebebasan umat beragama, dan kolonial pun tak dilawan hanya dengan lembing dan tasbih Umat Islam tetapi juga dengan parang dan golok umat Kristen dan Budha atau Hindu. Dan Hukum-hukum Tuhan yang permanen, yang siapa berani mengingkarinya akan Kafir, fasiq, dan Dzalim, yang mengejawantah dalam nilai-nilai keadilan, egaliter, kebebasan, hak-hak asasi, dll tidak akan hilang begitu saja hanya karena kita tidak memotong tangan pencuri, mencambuk peminum arak, atau mewajibkan kerudung. Penutup Pada akhirnya, tak ada tafsir yang seperti kitab suci. Dan tak ada fatwa yang layak menempati sabda Nabi. Islam bukan kelompok, atau kubu, atau tembok yang kukuh, yang mengkapling-kapling dan menyingkirkan liyan. Ia adalah hasil dialog manusia dan Tuhan. Yang tak pernah tuntas, berhenti atau mati. Ia adalah sebuah pengandaian konteks. Tentang bagaimana yang kerap cela berhadapan dan mengharap sempurna, dan nirwana. Demikian, sehingga persoalannya bukan apakah akal lebih unggul atau teks lebih kuat, karena teks punya otoritasnya sendiri sedangkan akal juga punya potensi dimana ia menjadi sakral dan menggaungkan dian Ilahi. Bukan pula bagaimana mendamaikan polemik antara keduanya, karena polemik adalah niscaya, yang didalamnya manusia berbincang dan mengadu, bukan bagaimana mengalahkan Tuhan dengan akal, atau menuhankan nalar, tetapi bagaimana kita bisa mengenal-Nya secara lebih saksama. Dan bukan juga manakah diantara keduanya yang memastikan “Yang benar”, karena kebenaran hanya eksis ketika manusia berbahasa, atau ketika sekelompok orang mengatakan bahwa kebenaran itu sendiri tak pernah ada, dan di Atas Sana. Syahdan, di sebuah tembok di Kota Kaliningrad yang dulu bernama Köningsberg, tak jauh dari makam Kant yang merapat di dinding katedral kota itu, ada sebuah kutipan terkenal dari sang filosof, dipahat dalam bahasa Jerman dan Rusia. Terjemahan bebasnya: “Dua hal memenuhi pikiranku dengan rasa takjub dan terkesima: angkasa yang penuh bintang di atas sana dan hukum moral nun dalam diri manusia. Dan bagi saya, satu lagi, Tuhan yang dengan senyum berdialog dengan makhluk-Nya. 7