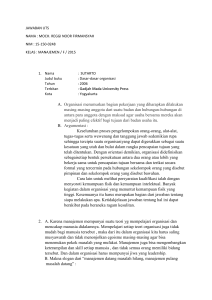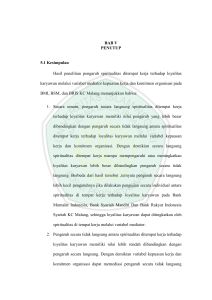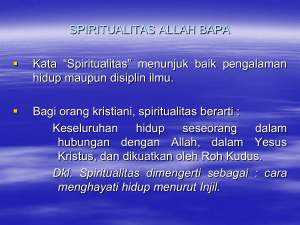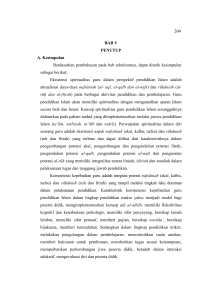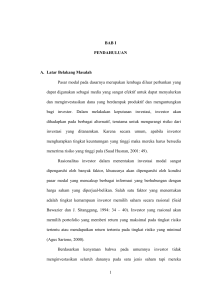Gairah Spiritualisme
advertisement
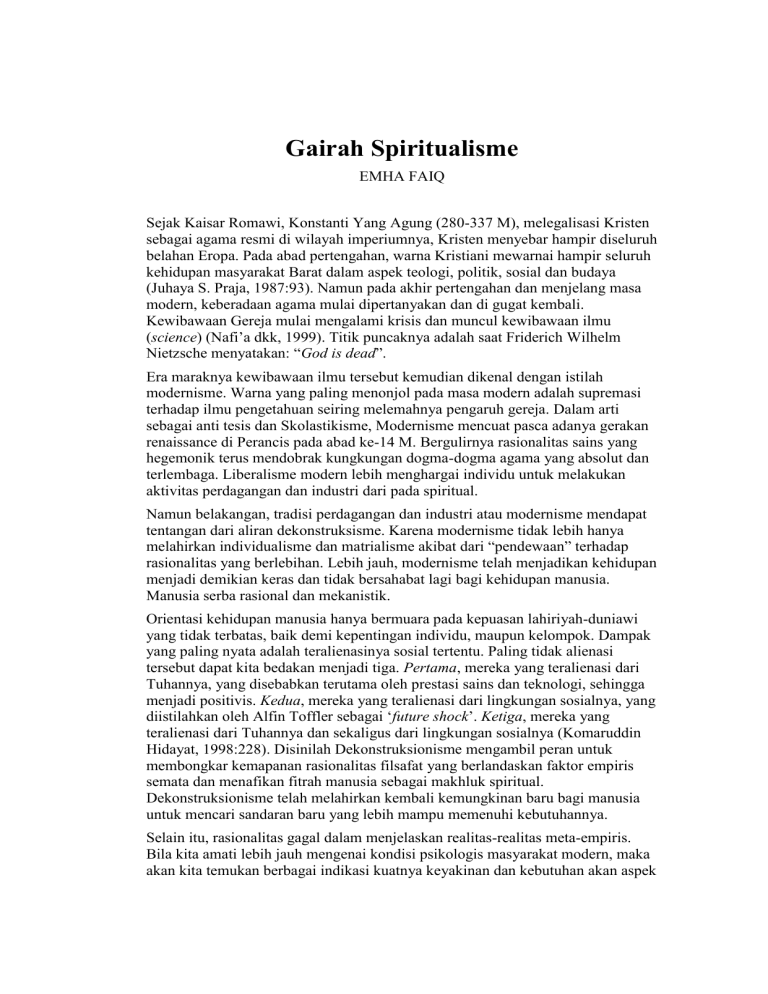
Gairah Spiritualisme EMHA FAIQ Sejak Kaisar Romawi, Konstanti Yang Agung (280-337 M), melegalisasi Kristen sebagai agama resmi di wilayah imperiumnya, Kristen menyebar hampir diseluruh belahan Eropa. Pada abad pertengahan, warna Kristiani mewarnai hampir seluruh kehidupan masyarakat Barat dalam aspek teologi, politik, sosial dan budaya (Juhaya S. Praja, 1987:93). Namun pada akhir pertengahan dan menjelang masa modern, keberadaan agama mulai dipertanyakan dan di gugat kembali. Kewibawaan Gereja mulai mengalami krisis dan muncul kewibawaan ilmu (science) (Nafi’a dkk, 1999). Titik puncaknya adalah saat Friderich Wilhelm Nietzsche menyatakan: “God is dead”. Era maraknya kewibawaan ilmu tersebut kemudian dikenal dengan istilah modernisme. Warna yang paling menonjol pada masa modern adalah supremasi terhadap ilmu pengetahuan seiring melemahnya pengaruh gereja. Dalam arti sebagai anti tesis dan Skolastikisme, Modernisme mencuat pasca adanya gerakan renaissance di Perancis pada abad ke-14 M. Bergulirnya rasionalitas sains yang hegemonik terus mendobrak kungkungan dogma-dogma agama yang absolut dan terlembaga. Liberalisme modern lebih menghargai individu untuk melakukan aktivitas perdagangan dan industri dari pada spiritual. Namun belakangan, tradisi perdagangan dan industri atau modernisme mendapat tentangan dari aliran dekonstruksisme. Karena modernisme tidak lebih hanya melahirkan individualisme dan matrialisme akibat dari “pendewaan” terhadap rasionalitas yang berlebihan. Lebih jauh, modernisme telah menjadikan kehidupan menjadi demikian keras dan tidak bersahabat lagi bagi kehidupan manusia. Manusia serba rasional dan mekanistik. Orientasi kehidupan manusia hanya bermuara pada kepuasan lahiriyah-duniawi yang tidak terbatas, baik demi kepentingan individu, maupun kelompok. Dampak yang paling nyata adalah teralienasinya sosial tertentu. Paling tidak alienasi tersebut dapat kita bedakan menjadi tiga. Pertama, mereka yang teralienasi dari Tuhannya, yang disebabkan terutama oleh prestasi sains dan teknologi, sehingga menjadi positivis. Kedua, mereka yang teralienasi dari lingkungan sosialnya, yang diistilahkan oleh Alfin Toffler sebagai ‘future shock’. Ketiga, mereka yang teralienasi dari Tuhannya dan sekaligus dari lingkungan sosialnya (Komaruddin Hidayat, 1998:228). Disinilah Dekonstruksionisme mengambil peran untuk membongkar kemapanan rasionalitas filsafat yang berlandaskan faktor empiris semata dan menafikan fitrah manusia sebagai makhluk spiritual. Dekonstruksionisme telah melahirkan kembali kemungkinan baru bagi manusia untuk mencari sandaran baru yang lebih mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu, rasionalitas gagal dalam menjelaskan realitas-realitas meta-empiris. Bila kita amati lebih jauh mengenai kondisi psikologis masyarakat modern, maka akan kita temukan berbagai indikasi kuatnya keyakinan dan kebutuhan akan aspek spiritual. Rasionalitas bisa saja menjelaskan mengapa apel jatuh kebumi, tetapi teori ini tidak akan sanggup menjelaskan ‘why there is something rather than nothing’ (Hidayat, 1998). Spiritualisme yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai spiritual yang terlepas dari agama formal dan bertumpu pada kesadaran manusia yang lebih tinggi (higher consciusness) untuk mewujudkan keharmonisan universal (universal harmony) (Nafi’a dkk, 1999). Mengapa masyarakat postmodem lebih menekankan pada aspek spiritualitas dan bukan agama, bukankah di dalam agama juga terdapat paket spiritualitas? Dengan logika paling sederhana, pertanyaan ini bisa dijawab, bahwa ada semacam simple projection bahkan trauma terhadap fenomena agama di masa lalu. Dimana agama telah mengalami pergeseran makna dan terlembaga sehingga kesakralan agama mengalami erosi. Bahkan bagi mereka agama telah menjadi titik api bagi terciptanya konflik dan perpecahan antar sesama akibat adanya klaim kebenaran (truth claim) antar pemeluknya. Agama tidak lagi memberikan keselamatan dan kasih sayang, melainkan persaingan. Hal ini didukung juga oleh paparan John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990) dalam bukunya Megatrend 2000 yang menyebutkan bahwa pada tahun 1997 terdapat kecenderungan tokoh-tokoh agama mulai meninggalkan ajaran agamanya. 5.557 biarawati meninggalkan ajaran agamanya. Bahkan seorang sosiolog Amerika, William d’Antonio menambahkan, pada tahun yang sama 94% warga Amerika mempercayai adanya Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki agama dan gereja yang jelas. Mereka tidak tertarik pada agama, tetapi merindukan kehadiran Tuhan. Bila spiritualitas tidak semata menjadi bahan kajian, melainkan penghayatan atau “the way of being “, maka seseorang senantiasa akan merasakan kehadiran Tuhan di mana pun dan kapan pun. Orang meyakini dan merasakan betul hubungan intim antara dirinya dan Dzat Yang Agung dan sekaligus Pengasih, maka tidak ada lain kecuali kestabilan dan ketenangan yang akan dirasakan. Posisi demikian ini tidak berarti melemahkan fungsi rasio dan nafsu, melainkan berbagai instrumen yang ada ini akan lebih terarah dan tidak pernah merasakan kekeringan energi dari ilahi (Hidayat, 1998). Adalah Komaruddin Hidayat, Direktur Pelaksana Yayasan Paramadina, menjelaskan, bahwa setelah seseorang berusaha mendapatkan pengetahuan tentang agama dan tentang Tuhan, yang tidak kalah pentingnya adalah ‘how to experience the God, means to experience our ferfection, to feel peace, happy and close to God’. Secara teoritis, Islam amat kaya dengan dimensi mistik (spiritualitas) ini dan barangkali merupakan paket yang bisa disumbangkan kepada masyarakat modern untuk menjawab kegelisahan yang menjeratnya. Dan memang, kini spiritualitas Islam reputasinya sedang memuncak. Selain karena spiritual Islam selalu bertumpu pada usaha untuk senantiasa menemukan kembali ajaran-ajaran murninya yang bersumber pada tauhid (tawhid). Ajaran Islam juga telah membuktikan “tesis-tesis” nya dalam membentuk masyarakat yang beradab, stabil, harmonis dan dinamis yang belakangan terkenal dengan tema masyarakat madani. Islam yang sebagian besar variabelnya adalah dimensi mistik (spiritualitas) telah mampu menciptakan masyarakat madani pada masa Nabi Muhammad yang kemudian diteruskan oleh keempat khalifah (khulafaur rasyidin)-nya. Jadi keraguan terhadap Islam hendaknya dikikis dengan bertolak pada kenyataan sejarah tersebut. Dan sekali lagi Islam bisa dijadikan alternatif terbaik bagi upaya penyejukan rohani dan nurani masyarakat modern yang telah lama mendambakan atmosfer madaniyah. Penulis adalah Mantan Ketua Umum PC. IRM Paciran-Lamongan dan kini sedang studi S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. SM-02-2003