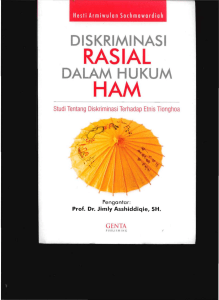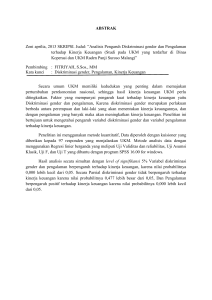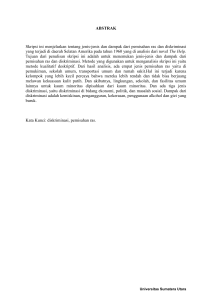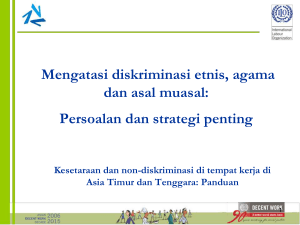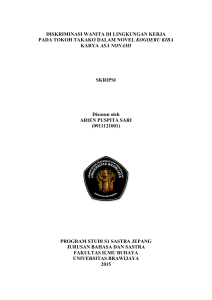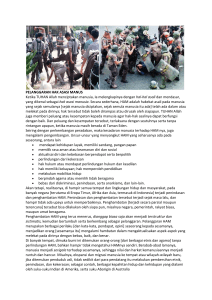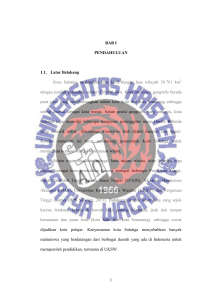draf laporan alternatif pelaksanaan konvensi penghapusan
advertisement

LAPORAN ALTERNATIF PELAKSANAAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL (ICERD) DI INDONESIA “Menguak Tabir Diskriminasi Rasial dan Impunity di Indonesia” BAB I : PENGANTAR ; REALITAS POLITIK DISKRIMINASI RASIAL Di INDONESIA 1. Dalam menyikapi laporan pemerintah Indonesia, NGO di Indonesia juga membuat laporan alternatif. Laporan ini final setelah diadakan konsultasi nasional Ngo pada tanggal 21-23 Juni 2007 di Bgoro, Jawa Barat, Indonesia. Konsultasi nasional Ngo ini diikuti oleh 25 anggota koalisi/lembaga dari beberapa daerah, antara lain, papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimanta, Sulawesi, Aceh-Sumatera. 2. Outline alternatif report ini memuat beberapa pokok bahasan, yaitu ; a. Back ground yang berisi pengantar realitas diskriminasi rasial di Indonesia terutama kebijakan yang ada dan diterapkan di Indonesia. Dalam bagian ini juga dijelaskan kelemahan umum penulisan laporan pemerintah. b. Tentang beberapa Tematik Issu. Dalam bab ini ada beberapa tematik issu yang dipilih berdasarkan General Recomendaton Komite CERD. Dari beberapa tematik issu tersebut, mengenai Impunity menjadi masalah yang dianggap paling krusial. Tematik issu tersebut adalah; 1) Kerangka Hukum 2) Impunity, yaitu kasus Peristiwa Mei 1998 yang juga dijadikan contoh kasus oleh pemerintah yang di klaim sudah di tangani. dan konflik etnis di Sampit Kalimanta Tengah, dan Sambas Kalimantan Barat. 3) Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, dalam hal ini tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia (SBKRI) dan masyarakat etnis Tionghoa sebagai stateles 4) Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat. 5) Tindakan Pembatasan terhadap etnis; Religius Etnik. 6) Pengabaian hak-hak Idps korban konflik etnis 7) Diskriminasi rasial di Papua 3. Diskriminasi secara kultural merupakan fenomena sosial yang terjadi di belahan bumi manapun di dunia, namun kemudian suatu negara melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya/individu di wilayahanya berdasarkan kebijakan-kebijakan merupakan pengingkaran atas harkat-harkat kemanusiaan yang sulit untuk ditolerir. Apalagi dalam konteks Indonesia yang konstitusinya mendasarkan diri kepada negara hukum (rechtstaat). 4. Diskriminasi rasial merupakan politik diskriminasi yang sudah berlangsung sejak lama di Indonesia, bahkan jauh lebih tua dari umur Republik Indonesia. Politik diskriminasi rasial berakar dan mulai diterapkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan kebijakan segregasi rasialnya, melalui pembedaan hukum keperdataan ‘Indische Staatsregeling’nya sejak tahun 1849, kemudian sangat mempengaruhi praktek-praktek dan politik diskriminasi rasial hingga saat ini. Kemudian antara 1953 sampai dengan 1970 banyak kebijakan negara yang menghasilkan berbagai praktek diskriminatif terhadap berbagai kelompok-kelompok di Indonesia, yang dalam cakupan ICERD 1965, salah satunya 1 adalah terhadap kelompok etnis Tionghoa. Berbagai peraturan tersebut meliputi kewajiban memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), pembatasan terhadap kelompok untuk mendapat pendidikan, pembatasan untuk menjadi pegawai negeri/tentara/polisi, pelarangan penggunaan bahasa (Mandarin), pembatasan kepemilikan tanah bahkan sampai dengan pelarangan berdagang pada wilayah daerah kabupaten/swatantra pada tahun 1959. 5. Diskriminasi rasial di Indonesia juga dilegitimasi oleh adanya konflik hukum (conflict of laws), yaitu berbagai pertentangan di dalam konstitusi (pertentangan antar pasal), pertentangan antar Undang-undang, dan pertentangan di dalam hirarki pertauran hukum dan perundang-undangan yang lain. Konflik hukum justru menjadi celah bagi terobosan berbagai kepentingan untuk melakukan tindakan diskriminatif secara lebih luas. 6. Kebijakan politik rasial tersebut yang kemudian dieskalasi dengan kegagalan negara untuk membangun kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya banyak mengakibatkan berbagai tindak-tindak rasialisme yang bermuara kepada kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa yang dilakukan secara sistematis, seperti pembunuhan massal etnis Tionghoa pada tahun 1840 oleh Belanda, kerusuhan di Bandung dan terakhir kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di berbagai kota di Indonesia. Negara tidak mampu memberikan perlindungan bahkan keadilan/pemulihan kepada korban-korban. 7. Tidak saja dalam konteks etnis Tionghoa, kebijakan diskriminasi juga dialami oleh masyarakat adat yang selama ini terampas hak-hak adatnya, antara lain hak atas tanah ulayatnya, hak atas pengelolaan sumberdaya alam, dan hak mereka untuk mendapatkan hak-hak sipil dan politik. 8. Pembatasan terhadap kebebasan berkeyakinan mengakibatkan pengingkaran atas hakhak sipil mereka sebagai warga negara, misalnya hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan, seperti yang dialami oleh masyarakat atau komunitas etnik yang menganut Kepercayaan Lokal. 9. Selama periode sebelum 1998, tidak ada upaya negara untuk melakukan penghapusan diskriminasi rasial, bahkan tidak jarang fakta-fakta diskriminasi tersebut tidak diakui sebagai diskriminasi. Kemudian baru pada tahun 1999, setelah terjadi reformasi dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, negara Republik Indonesia meratifikasi International Convention on Elimination of All Forms Racial Discrimination pada tahun 1999, karena desakan komunitas Internasional setelah terjadi kerusuhan rasial Mei 1998. 10. Sejak diratifikasi pada tahun 1999, upaya penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia khususnya menyangkut kebijakan-kebijakan yang diskrimatif berjalan lambat, walaupun janji politik sering diucapkan oleh politisi maupun pejabat pemerintahan. Beberapa langkah dan upaya pembaharuan hukum memang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia karena desakan dan inisiatif masyarakat yang juga telah melakukan beberapa upaya hukum. Langkah tersebut misalkan saja, perubahan politik untuk penghapusan diskriminasi rasial di Indonesia seperti diperbolehkannya penerbitan media berbahasa Mandarin, dijadikannya Hari Raya Tahun Baru Imlek sebagai hari Libur Nasional atau upaya penghapusan kewajiban SBKRI dengan Keppres No. 56 Tahun 1996 dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Misalnya berbagai kasus diskriminasi rasial masih terjadi dan negara belum melakukan perlindungan yang efektif atau pemidanaan atas diskriminasi rasial tersebut sekalipun itu dilakukan oleh aparat negara. Bahkan upaya hukum tersebut belum tercermin dengan masih berlakunya berbagai peraturan perundangan lainnya yang diskriminatif misalnya UU No. 23 tahun 2 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih diskriminatif maupun Peraturanperaturan Daerah (Ada UU yang lahir untuk menghapuskan praktek diskriminasi yaitu UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan namun disaat yang sama juga lahir UU yang diskriminatif yaitu UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) 11. Pemerintah Indonesia saat ini akan memenuhi kewajibannya sebagai negara pihak memberikan laporan implementasi dari ICERD. Dalam laporannya dituliskan banyak kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik dalam bidang legislasi maupun penyelesaian kasus. Namun pada kenyataannya laporan tersebut tidak semuanya berdasarkan fakta yang ada, baik dari perubahan legislasi mapun dari penangananan kasus. 12. Dalam proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pemerintah secara umum terdapat beberapa cacatan yang krusial terutama tentang materi subsansi dan fakta yang disajikan, yaitu ; a. Substansi yang disajikan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CERD, terutama batasan tentang basis diskriminasi yang digunakan. Secara umum laporan tersebut banyak yang menyimpang dari Pasal 1 CERD maupun General Recommendation No 14 : Definition of Discrimination ; 22/03/93. Contoh dalam konteks ini mengenai subtansi yang dilaporkan berbasis pada diskriminasi agama dan diskriminasi bagi orang cacat (Para. 132). Sehingga secara jelas laporan pemerintah tersebut secara umum tidak sesuai dengan ketentuan ICERD. b. Fakta-fakta atau kasus yang terjadi dan disajikan dalam laporan ini juga jauh dari realitas diskriminsi rasial, karena memang sejak awal substansi diskriminasi yang disajkan bukan berbasis pada ICERD. Contoh fakta / kasus yang tidak sesuai dengan CERD misalkan saja dapat ditemukan dalam beberapa contoh kasus diskriminasi yang berbasiskan agama seperti yang terjadi di Probolinggo maupun Malang (Para. 112), diskriminasi berdasarkan politik yang terjadi dalam aturan partai politik, mengenai Polisi cacat yang masih bekerja berbasiskan diskriminasi pada orang cacat (Para. 148), diskriminasi yang terjadi berdasarkan kemiskinan dan kerentanan masyarakat (Para. 151). c. Laporan pemerintah tidak fokus dan saling kontradiksi satu dengan yang lain. Kenyataan ini dapat dilihat dari pemakaian beberapa argumentasi hukum yang disajikan. Misalkkan saja UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat yang diklaim pemerintah sebagai UU yang mendorong pemberantasan diskriminasi, namun disisi lain dalam laporan tersebut UU itu juga melegitimasi praktek kekerasan yang berbasis agama. d. Klaim yang salah terhadap pekerjaan NGO. Hal ini terjadi misalkan terhadap riset yang dilakukan oleh lembaga UPC (Urban Poor Concorcium) terhadap diskriminasi orang miskin dan rentan yang juga dianggap masuk dalam CERD. Dalam masalah ini pemerintah tidak terlibat dalam riset tersebut, dan riset itu bukan berbasis CERD. 13. Pada akhirnya harapan besar kami, NGO di Indonesia, masyarakat umum dan seluruh korban agar summary eksekutif laporan alternatif ini dapat digunakan oleh Komite untuk melihat realitas kebijakan dan kasus diskrimininsi Ras di Indoneia. Sehingga Komite dapat membuat rekomendasi yang tepat dan sesuai dengan problem diskiminasi rasial di Indonsia. 3 BAB II TINJAUAN KRITIS TERHADAP LAPORAN PEMERINTAH : INFORMASI DAN ARGUMENTASI LAIN YANG RELEVAN TERKAIT DENGAN PASAL 1 SAMPAI PASAL 7 ICERD. Pasal 1 14. Secara formal defenisi diskriminasi telah tercantum dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain tercantum dalam Amandemen UUD 1945, UU N0. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Para. 86-88). Akan tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah (1) Apakah ada sanksi hukum bagi tindakan-tindakan diskriminasi (2) Apakah peraturan-peraturan tersebut telah menghapuskan praktek-praktek diskriminasi yang terjadi selama ini. (3) Apakah peraturan-peraturan tersebut menimbulkan atau tidak menimbulkan praktek-praktek diskriminasi baru. (4) apakah ada sinkronisasi perundangundangan/kebijakan hukum dari nasional sampai daerah yang sesuai dengan prinsip UUD 45 dan Konvensi. Laporan Pemerintah Indonesia tentang Pelaksanaan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial tidak menggambarkan / menjawab empat hal mendasar ini. 15. Pemerintah Indonesia tidak mendeskripsikan secara rinci defenisi diskriminasi dari konstitusi sampai seluruh peraturan perundang-undangan. Sehingga terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Intruksi Gubernur Yogyakarta No. 398/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non-Pribumi, yang melarang WNI Tionghoa memiliki tanah di daerah Yogyakarta, yang hal ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 16. Praktek-praktek diskriminasi masih berlangsung. Informasi dalam Para. 90 yang menyebutkan bahwa di Indonesia ada sanksi hukum bagi tindakan diskriminatif adalah sangat tidak benar. Karena yuridiksi UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Genosida. Yuridiksi UU Pengadilan HAM tersebut hanya mencakup satu element kejahaan dalam konteks diskriminasi yaitu kejahatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran berat HAM, sementara praktek diskriminasi juga mencakup pidana biasa. Dalam konteks ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup jenis tindak pidana biasa tidak mengatur mekanisme pidana bagi tindakan-tindakan diskriminasi. Pasal 2 17. Informasi dalam Para. 95, 100, 101, mengenai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan jaminan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada, contohnya peraturan yang dibuat oleh Gubernur Yogyakarta No. 398/I/A/1975 sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan bahkan dalam UU 23/2006 tentang Aminduk yang baru dibuat tahun 2006 juga masih melahirkan diskriminasi. Artinya, harmonisasi hukum belum terlaksana secara efektif bagi seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari jaman kolonial sampai saat ini. Disamping itu, belum ada implementasi hukum atau sanksi hukum bagi tindakan-tindakan diskriminasi. 4 18. Informasi dalam Para. 102 adalah benar. Akan tetapi klaim pemerintah tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Secara legal, masih banyak peraturan-peraturan bersifat diskriminatif yang masih berlaku. Antara lain seperti Instruksi Kepala Daerah DIY No. 398/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI non-Pribumi. Intruksi Kepala Daerah Yogyakarta ini melarang warga etnis Tionghoa memeliki tanah. (Rincian Peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif secara lengkap akan dilampirkan dalam Alternatif Report ICERD) 19. Paragraf 104, 105, 106, 107, tidak relevan dengan Pasal 2 konvensi. Kebijakan pembangun untuk daeah tertinggal indonesia bagain timur yang dipaparkan dalam laporan pemerintah sebenarnya bukan dalam rangka kebiajkan yang berbasis pada usaha untuk menghapuskan diskriminasi rasial, namun lebih pada kemiskinan stuktural dan yang paling mendapatkan manfaat adalah para investor, sebab dalam rencana pembangunan tersebut juga sinergi dengan perencanaan investasi di Indonesa bagian timur tersebut. 20. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia bagi warga Tionghoa (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) (Para.108) memang seharusnya dilakukan dan semestinya bisa terlaksana dengan efektif. Akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa tindakan diskriminasi masih dilakukan oleh pihak Bank (Para. 109). Dalam hal ini, perlu dipertegas apakah ada upaya-upaya atau mekanisme hukum yang dijalankan dan upaya pemulihan efektif bagi korban. 21. Poin 110 – 112 tidak masuk dalam yuridiksi ICERD karena poin kasus tersebut berdasarkan agama bukan ras. Disamping itu pula, fakta dalam Para. 110-112 missleading dengan fakta yang sebenarnya. Misalnya memang ada perencanaan pencatatan perkawinan bagi Penganut Kepercayaan dan agama diluar agama resmi di dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009. Tetapi rencana ini tidak terlaksana dengan baik. Seperti contoh kasus yang dialami oleh Sdri. Dewi Kanti (Penganut Aliran Kepercayaan), yaitu anak yang lahir dari perkawinannya hanya diakui negara sebagai anak dari Sdri. Dewi Kanti saja. Jadi anak yang lahir dari pernikahan di luar 5 (lima) agama yang diakui Negara hanya diakui sebagai anak dari pihak Ibu, dan pihak Ayah tidak diakui oleh negara. 22. Informasi tentang pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan diluar 5 (lima) agama yang diakui Pemerintah (Para. 110), belum bisa terlaksana dengan baik bagi seluruh agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Pencatatan perkawinan baru terlaksana bagi penganut Konghucu, sementara perkawinan bagi penganut Aliran Kepercayaan dan seluruh keyakinan yang melekat pada etnisitas belum dicatatkan. Kantor Catatan Sipil tetap menolak pendaftaran perkawinan bagi Penganut Kepercayaan sekalipun Pengadilan telah memerintahkan kepada pejabat terkait untuk mencatatkan perkawinannya. 23. Para. 111 tidak masuk dalam yuridiksi CERD. Hampir seluruh daerah di Indonesia masih menempatkan kolom Agama di dalam Kartu Identitas Penduduk (KTP). Kota Bogor (Para. 111) juga masih menempatkan kolom Agama. Bahkan dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada bulan Desember 2006 menyebutkan dalam Pasal 61 ayat 2 bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus mencantumkan agama. Dan bagi agama yang tidak diakui dikosongkan dalam KTP tersebut. 24. Infomasi pada Paragraf 112 tidak konsisten / saling bertentangan dengan Paragraf 114 dalam penggunaan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam Para. 5 112, disebutkan bahwa penahanan terhadap Ketua Kelompok yang disebut sebagai “Kelompok pengkhianat” adalah bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1985. Sedangkan dalam Para. 114, UU No. 8 tahun 1985 dijadikan sebagai pembenar untuk menyalahkan keyakinan yang dianut oleh Kelompok Ahmadiyah, dalam konteks ini ahmadiyah adalah Korban dari kekerasan yang berbasis agama. Fakta dilapangan adalah banyak kekerasan terjadi atas nama agama, dan pemerintah tidak melakukan apa-apa dan bahkan ikut terlibat contoh, kasus Ahmadiyah dan kasus penutupan gereja. 25. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat adalah produk perundang-undangan yang dibuat pada zaman Orde Baru untuk mengontrol aktivitas masyarakat dalam berorganisasi. UU tersebut justru menjadi pembatasan terhadap hak-hak berkumpul dan berasosiasi. Pada saat ini, undang-undang tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 26. Informasi dalam Para. 114, pemerintah menuduh bahwa Ahmadiyah adalah organisasi yang mendukung rasial. Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar bahkan Ahmadiyah dalam kontek Indonesia menjadi korban dalam kebebasan berkeyakinan dan beragama. Dalam kasus Ahmadiyah, tidak ada hubungan antara UU No. 8 Tahun 1985 dengan aktifitas dan keyakinan para kelompok Ahmadiyah. Statement/informasi tentang Ahmadiyah (Para. 114) sangat subjektif dan dapat menjadi sumber legitimasi kekerasaan terhadap Ahmadiyah, karena tidak mungkin kelompok Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas mengumumkan/mengklaim secara terbuka versi mereka mengenai Islam. Disamping itu, eksistensi kelompok Ahmadiyah sudah diakui sebagai badan hukum legal berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/23 Tanggal 1 Maret 1953. dan diakui sebagai Organisasi Masyarakat melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Pol No. 75/D.I/VI/2003. 27. Dalam kasus-kasus seperti ini Pemerintah tidak melindungi kelompok-kelompok minoritas dalam aliran-aliran keagamaan. Kekerasan, ancaman, pengrusakan rumah dan tempat ibadah, serta fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh kelompok Ahmadiyah tidak pernah diproses secara hukum. Pemerintah/aparat penegak hukum cenderung diam dan membiarkannya. Pasal 3 28. Adalah benar bahwa ada kemajuan terhadap penghapusan aturan hukum yang mengatur segregasi, namun penghapusan tersebut tidak menjamin efektifitas pencegahan dan penyelesaian segregasi yang ada. Contoh kasus tentang SBKRI dalam Para. 117, 118, 119, walaupun sudah ada Kepres No. 56 tahun 1996 yang mencabut tentang SKBRI, namun dalam prakteknya SKBRI masih berlaku dibeberapa daerah. Riset yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Indonesia (Komnas HAM) dan GANDI (Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi) di 4 (empat) kota yaitu Tanjung Pinang dan Batam, Medan, Manado dan Pontianak menemukan bahwa SBKRI masih berlaku dengan polapola antara lain 1 : a. SBKRI untuk pengurusan akta kelahiran anak dari perkawinan campuran. Dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagi anak warga keturunan diminta melampirkan SBKRI bersama Kartu Keluarga (Kasus di Tanjung Pinang). 1 Selengkapnya dapat dilihat hasil riset Komnas HAM dan GANDI, dalam buku “ SBKRI : Analisis dan Hasil Pemantauan”, halaman 79 – 109. November 2006. 6 b. SBKRI masih diharuskan dalam Pengurusan Ijin Usaha, pasport, dan. (Kasus di Medan). c. Sejak tahun 2003, Universitas Sumatera Utara, tidak mensyaratkan lagi SBKRI dalam pendaftaraan mahasiswa baru. (Kasus di Medan). d. Warga Negara Indonesia (WNI) yang keturunan India lebih banyak tidak memiliki dokumen resmi, seperti akte lahir, sehingga masih dianggap WNA (Kasus di Medan) 29. Contoh lain, dalam konteks Aceh, segregasi sosial malah dibuat oleh negara yaitu negara merekrut milisi berdasarkan etnis rasial yaitu etnis Jawa dan Sumatera untuk melawan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan mendesak pemecahan Aceh menjadi dua profinsi. Implikasinya sampai saat ini segregasi sosial itu masih ada dan dipelihara. Selain itu, saat ini pemerintah juga membuat draf UU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang berpotensi besar membatasi keanekaragaman ekspresi kultural dari banyak etnis di Indonesia dalam bentuk pengutamaan nilai-nilai cara berpakaian dan nilai-nilai perilaku tertentu. Berbagai macam kelompok etnis di Indonesia sudah melakukan penolakan atas RUU ini. 30. Langkah pembauran yang dilakukan Pemerintah dalam hal penghapusan segregasi (Para. 122), dapat mengakibatkan hilangnya identitas etnis. Seharusnya pemerintah mendorong integrasi bukan asimilasi (pembauran) Pasal 4 31. Informasi yang disampaikan dalam Paragraf 125 sampai 138, adalah tidak relevan dengan Pasal 4 Konvensi. Selain itu, sebagain besar infomasinya telah disampaikan pada bagian Pasal 2 Konvensi. 32. Dasi segi legislasi, tidak ada undang-undang yang mengatur sanksi hukum bagi tindakan diskriminasi. Informasi mengenai proses hukum bagi diskriminasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia adalah tidak benar, karena yuridiksi undang-undang ini adalah mengadili pelanggaran HAM Berat berupa Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Salah satu klasifikasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam UU ini adalah Penyiksaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan jenis kelamin. Sementara untuk tindakan-tindakan diskriminasi seperti dalam Para. 109 yaitu tindakan Bank yang meminta SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia), dan pegawai pemerintah yang menolak permintaan Candra Setiawan (Para. 113) tidak ada sanksi hukumnya. 33. Perlu ditegaskan, bahwa UU No. 26 tahun 2000 hanya menangani jenis kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM. UU 26/2000 ini hanya bisa menjangkau/mempidanakan tindakan penyiksaan yang berdasarkan diskriminasi rasial yang terjadi secara sistematis (systematic) atau meluas (widespread). UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM meski memuat pengakuan tentang sikap anti diskriminasi, akan tetapi tidak memuat sanksi pidana bagi praktek diskriminasi. Padahal bentuk-bentuk praktek diskriminasi –menurut CERD- mencakup pula jenis pelanggaran HAM biasa. Artinya sistem hukum (pidana) di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang pelarangan praktek diskriminasi rasial dalam kategori pelanggaran biasa. 34. Disamping itu dalam RUU KUHP yang sudah dibahas selama 20 tahun terakhir memuat pemidanaan praktek diskriminasi dalam pasal 286 dan 287, akan tetapi hanya dibatasi apabila praktek diskriminasi itu mengakibatkan kekerasan. Bisa disimpulkan bahwa 7 sistem legislasi dan hukum positif Indonesia tidak memadai untuk memerangi praktekpraktek diskriminasi rasial. Pasal 5 35. Secara umum Para.139 sampai Para. 151 tidak relevan dengan Konvensi CERD. Karena konsepsi dan kasus-kasus penghapusan diskriminasi yang disebutkan oleh Pemerintah bukan kasus-kasus diskriminasi berdasarkan diskriminasi rasial. 36. Khusus Para. 150. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada bulan Mei 1998 adalah kasus-kasus perkosaan terhadap etnis tertentu, pembakaran gedung-gedung perbelanjaan, pembunuhan, dan Penembakan Mahasiswa Universitas Tri Sakti. Namun Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian atau Kejaksaaan Agung. Selanjutnya hal ini akan dijelaskan dalam tematik Tentang Impunity. Pasal 6 37. Informasi pada Para. 152 sampai Para. 158 tidak relevan dengan Pasal 6 konvensi. Fakta yang terjadi di Indonesia adalah kasus-kasus diskriminasi rasial tidak ada yang diproses secara hukum melalui pengadilan, dan negara tidak melakukan pemulihan efektif bagi korban. 38. UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini belum ada gantinya. Pasal 7 39. Tidak ada satu kebijakan pendidikan untuk menghilangkan diskriminasi rasial,baik untuk umum maupun untuk aparatus negara. Hal ini bisa dilihat bahwa aparat negara masih banyak melakukan diskriminasi rasial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam contohcontoh di atas. Komentar atas Kesulitan-Kesulitan yang dihadapi Pemerintah dalam Penerapan Konvensi 40. Secara umum Pemerintah tidak melakukan upaya-upaya penanganan konflik khususnya yang terjadi di Kalimantan Barat antara etnis Madura dan Dayak. Hal ini bisa dilihat dari keadaan pengungsi kelompok etnis Madura yang sampai saat ini belum bisa pulang ke tempat tinggalnya. Negara belum memfasilitasi rekonsiliasi permanen diantara kedua belah pihak. Sehingga sampai saat ini secara psikologis, masyarakat etnis Madura belum berani pulang ketempat tinggalnya. Dan masyarakat etnis Dayak belum bisa menerima kehadiran mereka. 41. Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang multi budaya, multi agama, multi ras dan bahasa maka seharusnya hal ini telah disadari dari awal dengan membuat kebijakankebijakan yang sensitif terhadap konflik dan tidak mengandung potensi diskriminasi rasial. BAB III ISU TEMATIK 8 A. KERANGKA HUKUM 42. Di Indonesia, masih terdapat hukum yang diskriminatif dan bertentangan dengan konvensi ICERD. Hal ini disebabkan oleh adanya konflik hukum (conflict of laws), yaitu pertentangan di dalam konstitusi (UUD 1945), pertentangan antar Undang-undang (UU), dan pertentangan di dalam hierarki peraturan hukum dan perundang-undangan, seperti antara Peraturan Daerah (Perda) dengan UU di atasnya atau UU dengan konstitusi. 43. Konflik hukum terjadi disebabkan oleh adanya kepentingan para pembuat kebijakan, perspektif yang bias rasial (pengutamaan dan pembatasan), dan kepentingan dari kelompok modal. 44. Konflik hukum di dalam konstitusi muncul karena terjadi pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain. Misalnya, Pasal 28i Ayat 2 UUD 1945 mengatakan: setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini bertentangan dengan pasal 18b ayat 2 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kalimat sepanjang………dan seterusnya dalam pasal 18b Ayat 2 tersebut justru mengancam eksistensi masyarakat adat yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman. 45. Pertentangan antar UU misalnya, antara UU Administrasi Kependudukan (UU No 23/2006) dimana di dalamnya masih mengatur tentang pembatasan kepemelukan agama dan berkeyakinan, hal ini bertentangan dengan UU Hak Asasi Manusia (UU No 39/1999) yang menjamin kekebasan setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaannya. UU No. 23/2006 ini juga bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28E yang menjamin kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya. 46. Di tingkat daerah juga muncul Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Perda No. 6/2003 di Bulukumba (Sulawesi Selatan) tentang baca tulis alquran bertentangan dengan konstitusi pasal 28I ayat 3 tentang pengakuan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Perda ini akan membuat masyarakat adat Kajang Bulukumba kehilangan identits budayanya karena diwajibkan untuk mengikuti Perda tersebut. 47. Dalam kondisi konflik hukum ini, lahir juga sejumlah UU yang membatasi keberlanjutan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat adat (hal ini bertentangan dengan rekomendasi umum No 23 : masyarakat adat : 18/08/97 angka (4) huruf (c) menyediakan kepada masyarakat adat kondisi yang memungkinkan suatu pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik budaya mereka). Misalnya UU No 18/2004 tentang Perkebunan, UU tentang Perikanan, UU tentang Pertambangan, dan UU No 7/2004 Sumber Daya Air. Ketiga UU tersebut menjadi legitimasi para pemilik modal untuk merampas hak-hak masyarakat adat, terutama tanah, air, dan sumberdaya alam. 48. Bahkan sebelum amandemen UUD 1945, dalam praktek yang pernah terjadi dengan klausul yang sama tentang pengakuan bersyarat yang diatur dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan telah menyebabkan marginalisasi sistematik masyarakat adat yang hidup dan bergantung dari hutan. 49. Begitu juga dengan keberadaan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menjadi instrument bagi Pemerintah Daerah (Pemda) menafsirkan eksistensi masyarakat adat. Termasuk menafsirkan kalimat “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 9 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia” yang tertera dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945. 50. Dalam sejarahnya, pengakuan bersyarat merupakan warisan dari aturan kolonial Belanda yang membatasi hukum adat dan pemerintahan desa, kemudian sejak UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria) pengakuan bersyarat tersebut dipakai untuk hak ulayat dan hukum adat. Namun sejak reformasi, pengakuan bersyarat justru sangat meluas ke hak ulayat, adat istiadat, hak-hak tradisional, hukum adat dan lembaga adat (Rikardo Simarmata 2007: Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP: 312-313). 51. Meluasnya jangkauan pengakuan bersyarat dalam sejumlah kerangka normatif inilah yang melahirkan potensi diskriminasi secara sistematik dan legal terhadap hak-hak masyarakat adat. (bukan saja potensi tapi menjadi kenyataan di berbagai peraturan perundang-undangan) B. IMPUNITY DALAM KASUS DISKRIMINASI RASIAL 52. Pasal 6 ICERD menyebutkan ”States Parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, through the competent national tribunal and other State institutions, against any acts of racial discrimination which violate his human rights and fundamental contrary to this Convention, as well as the right to seek from such tribunal just and adequate reparation or satisfaction for any damage suffered as a result of such discrimination”. Pasal tersebut secara jelas mewajibakan negara untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban dan menghukum pelaku melalu keputusan pengadilan, serta melakukan tindakan efektif untuk pemulihan korban. 53. Dalam konteks Indonesia kewajiban Negara dalam pasal 6 tersebut belum terimplikasi, bahkan negara melakukan impunity terhadap kasus-kasus yang terjadi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, seperti tidak ada penyelesaian hukum atas kasus diskriminasi yang telah terjadi, prilaku aparat negara yang masih menunjukkan prilaku diskriminasi rasial, dan produk hukum yang dibuat berpotensi tinggi terjadinya tindakan-tindakan diskriminnasi. 54. Impunity yang terjadi dapat dilihat dari bagaimana negara menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Contoh adalah kasus kerusuhan MEI 98 dan kasus Sampit tahun 2001 yang merupakan kekerasan antara etnis Dayak dengan etnis Madura. 55. Di dalam laporan alternatif ini kami memilih kasus Mei 98 dan kasus konflik antar etnis di provinsi Kalimantan sebagai contoh bagaimana impunity terhadap kasus diskriminasi rasial yang terjadi, tanpa mengurangi arti pentingnya kasus lain. 1. Kerusuhan Mei 1998 56. Berbagai temuan, baik itu berasal dari investigasi NGO, jurnalisme atau reportase media massa, hingga temuan investigasi independen yang dibentuk negara menggambarkan bagaimana diujung periode Orde Baru (sesaat sebelum Soeharto mengundurkan diri), 1315 Mei 1998 terjadi sebuah pogrom, kerusuhan massal di berbagai kota besar di Indonesia; Jakarta, Medan, Surabaya, Palembang, Solo, dan Lampung. Di tengah-tengah kerusuhan massal tersebut terjadi tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia; mulai dari penjarahan harta benda, kekerasan fisik, hingga perkosaan terhadap perempuan Tionghoa. Pada momentum yang sama di kota-kota besar tersebut sentimen 10 rasial tampil secara terbuka. Kata-kata “milik pribumi” tertulis di berbagai rumah atau pertokoan untuk menghindari penjarahan oleh massa. 57. Di antara yang tersulit untuk diverifikasi rincian kebenarannya adalah jumlah korban perkosaan. Temuan dari sebuah NGO (Tim Relawan untuk Kemanusiaan) menyatakan 168 orang menjadi korban perkosaan, sebagian besar merupakan perempuan etnis Tionghoa. Sementara itu temuan resmi pemerintah, yaitu temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) menunjukan ada 85 orang menjadi korban kekerasan seksual, 52 orang di antaranya merupakan korban perkosaan dan sebagian besar juga berasal dari etnis Tionghoa dan dilakukan secara gang rape. Estimasi akurat jumlah korban sebenarnya tentu saja bisa melebihi angka-angka di atas mengingat sulitnya mengungkap jenis kejahatan paling keji ini lewat barang bukti atau kesaksian. 58. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, yaitu SK Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, SK Menteri Kehakiman, SK Menteri Luar Negeri, SK Menteri Negara Peranan Wanita, dan SK Jaksa Agung. TGPF dibentuk dalam rangka mengungkap dan menemukan pelaku, serta latar belakang peristiwa tanggal 13-15 Mei 1998. Pada laporan akhirnya, TGPF menyimpulkan bahwa peristiwa 13-15 Mei 1998 terjadi secara sengaja, terencana, terdapat pola, sistematis, dan diduga merupakan hasil pertarungan politik dari elit untuk memperebutkan kekuasaan. TGPF juga merekomendasikan beberapa hal: 1) Meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang dapat diungkap secara yuridis baik terhadap warga sipil maupun militer yang terlibat seadil-adilnya; 2) Meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban, dan meminta dengan segera kepada pemerintah untuk membentuk suatu komisi permanen yang melaksanakan program perlindungan terhadap saksi (victims and witness protection program); 3) Mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi internasional mengenai antidiskriminasi rasial, dan merealisasikan pelaksanaannya dalam produk hukum yang permanen, termasuk implementasi konvensi internasional anti penyiksaan; 4) Mendesak kepada Pemerintah untuk secara tegas segera melakukan proses yustisi bagi pihak-pihak yang secara terang-terangan menyebarkan kebencian rasial atau SARA; 5) Meminta kepada pemerintah untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa hal semacam itu tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Sayangnya rekomendasi TGPF ini tidak juga ditindaklanjuti oleh negara. 59. Mengingat respon negara yang sangat rendah atas laporan TGPF, penyelidikan atas tragedi Mei 1998 ini kembali dilakukan pada tahun 2003. Kali ini penyelidikan dijalankan oleh Komnas HAM karena adanya reformasi sistem hukum yang baru. Komnas HAM sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, bisa menjalankan fungsi penyelidikan independen. 60. Tidak berbeda jauh dengan temuan TGPF, Komnas HAM juga menemukan hasil yang sama, bahwa peristiwa 13-15 Mei 1998 merupakan sebuah tindak kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM, yang terjadi secara sistematis (systematic) atau meluas (widespread). Komnas HAM juga menegaskan terjadinya kekerasan berbasis rasial. 11 1.1. Penanganan Hukum Tragedi Mei 1998 61. Secara umum dapat dikatakan bahwa macetnya penanganan hukum atas tragedi Mei 1998 disebabkan oleh alasan-alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan macetnya penanganan Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, yaitu problem politik prosedural dan ketiadaan kemauan politik dari Jaksa Agung, Dewan Perwakilan Rakyat/DPR, dan Presiden RI. Belajar dari pengalaman KPP HAM TSS, 2 Komnas HAM merespon tuntutan masyarakat korban Mei 1998 dengan tidak membentuk Komisi Penyelidik ad hoc. Tetapi membentuk Tim Pengkajian Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 berdasarkan UU No.39/1999 tentang HAM dengan mandat kerja melakukan pengkajian atas berkas hasil penyelidikan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998. Setelah bekerja sekitar 12 bulan, paripurna Komnas HAM memutuskan untuk meningkatkan status tim sebagai penyelidik pro justicia guna penyelidikan dan pengumpulan data yang lebih lengkap. 3 62. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM membatasi ruang lingkup penyelidikan pada kerusuhan 13 – 15 Mei 1998 di Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Depok. Agar tidak mengulangi kegagalan dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, pada Maret 2003, Komnas HAM mendesak DPR untuk tidak mengeluarkan rekomendasi apapun mengenai kasus Mei 1998 sebelum proses penyelidikan yang dilakukan tim penyelidikan ad hoc dan proses penyidikan selesai dilakukan. Tim ad hoc menilai telah terjadi pelanggaran berat HAM yang ditandai dengan banyaknya korban dari warga sipil pada kerusuhan Mei 1998. 63. Tim ad hoc penyelidik memanggil saksi korban, pejabat sipil dan militer serta saksi ahli. Dalam perkembangannya, Komnas HAM memanggil sejumlah perwira tinggi TNI dan POLRI dengan melayangkan surat kepada Panglima TNI dan Kapolri. Namun, kembali TNI/Polri mangkir untuk hadir dalam penyelidikan ini. Tim Advokasi TNI secara resmi menyampaikan penolakan atas pemanggilan Komnas HAM terhadap sejumlah perwira TNI/Polri, dengan alasan tidak ada landasan hukum sah yang dapat dijadikan dasar pemanggilan. Tak kurang dua kali pemanggilan resmi yang disampaikan kepada para perwira TNI/Polri. Namun tetap gagal. Tim Advokasi TNI berpendapat bahwa kehadiran petinggi TNI/Polri harus berdasarkan rekomendasi DPR atas pembentukan pengadilan HAM ad hoc, sementara Komnas HAM berpendapat bahwa penyelidikan itu justru dilakukan guna mendorong untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran berat HAM. 64. Ketiadaan itikad baik itu membuat tim ad hoc mengupayakan pemanggilan paksa dengan mengirimkan surat kepada Kepala Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Juli 2003. Dalam surat tersebut, Kepala PN diminta untuk menerbitkan surat pemanggilan paksa dengan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri agar menghadirkan secara paksa para mantan pejabat TNI/Polri sebagai penanggungjawab keamanan kerusuhan Mei 1998. Namun PN Jakarta Pusat menolak upaya pemanggilan paksa. 2 Kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II atau yang dikenal sebagai Kasus TSS ini adalah kasus penembakan para mahasiswa di saat gelombang protes gerakan mahasiswa terjadi. Kasus Trisakti (12 Mei 1998) merupakan pemicu gelombang kerusuhan massal di Jakarta dan temuan investigasi TGPF menunjukan adanya keterkaitan kasus ini dengan kerusuhan 13-15 Mei 1998. Komnas HAM kemudian membentuk tim penyelidik independen (KPP HAM) Kasus TSS dan menyatakan telah terjadi pelanggaran berat HAM (sesuai ketentuan UU No. 26 Tahun 2000) dan menyerahkan laporannya ke Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan dan penuntutan dalam mekanisme Pengadilan HAM ad hoc. Jaksa Agung menolak melakukan penyidikan dengan alasan tidak ada rekomendasi politik dari DPR. 3 Keputusan Ketua Komnas HAM No.10a/KOMNAS HAM/III/2003 tentang Pembentukan Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Mei 1998. 12 65. Pada September 2003, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi Pelanggaran HAM berat dalam kasus itu. Dalam salah satu kesimpulannya disebutkan bahwa sedikitnya 20 orang aparat keamanan (TNI/Polri) serta sipil akan diminta pertanggungjawaban pidana baik primer maupun subsidair atas peran mereka dalam kerusuhan Mei 98. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM secara resmi menyerahkan surat kepada Jaksa Agung. Pada Oktober 2003, Jaksa Agung membentuk tim untuk mempelajari 18 berkas kasus kerusuhan Mei 1998. 66. Seperti berkas Trisakti, Semanggi I dan II, pihak Jaksa Agung yang diwakili Satgas HAM BR Pangaribuan dan Kapuspenkum Kemas Yahya Harahap saat menemui korbankorban Mei 1998 menjelaskan, Laporan Komnas HAM tentang Mei 1998 masih sumir dan tidak menyebutkan tersangka, sehingga hasil penelitian sementara Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa laporan itu akan dikembalikan. Atas hal ini, Ketua Komnas HAM meminta Kejagung tidak melempar tanggung jawab dalam meyelesaikan kasus Pelanggaran HAM berat kerusuhan Mei. Hal itu dikemukakan Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR Komnas HAM mendesak DPR segera memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc berkaitan dengan kasus kerusuhan Mei 98. 1.2. Mandegnya Penyidikan oleh Jaksa Agung 67. Secara resmi, pada 4 Maret 2004 Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan kasus kerusuhan Mei ke Komnas HAM. Menurut M.A. Rahman, untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM yang diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak 19 September 2003, pihaknya telah membentuk tim untuk meneliti, berdasarkan hasil penelitian tim berkas perkara tersebut belum lengkap Komnas HAM tetap melanjutkan menangani Kerusuhan Mei 98. Penanganan ketiga kasus ini sudah diserahkan kembali kepada Jaksa Agung pada Mei 2004. 68. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 17 Mei 2004, pihak Jaksa Agung menyatakan akan mengembalikan berkas hasil penyelidikan kepada Komnas HAM karena BAP belum dibuat Projusticia dan juga bukti awal tidak jelas, dan Kejaksaan juga menilai pelaku dan pembuat kebijakan tidak tergambarkan secara jelas. 69. Tepat pada 31 Juni 2004, berkas penyelidikan tragedi Mei 98 dikembalikan lagi oleh Jaksa Agung kepada Komnas HAM. Banyak kalangan menilai pengembalian berkas kasus Kerusuhan Mei 98 ke Komnas HAM lebih bersifat politis daripada pertimbangan hukum. Langkah itu dinilai sebagai kekeliruan besar karena merekalah yang seharusnya menindaklanjuti penyelidikan itu dengan penyidikan. 1.3. Kasus Mei 1998 : Kebekuan yang terus berlanjut 70. Hingga kini, kasus Kerusuhan Mei 1998 berhenti di tempat. Tidak ada inisiatif, baik dari Komnas HAM maupun Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan kebuntuan proses yang berlangsung sejak tahun 2003 lalu. Sejak diserahkannya berkas kasus ini oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung, tercatat 2 kali berkas tersebut bolak-balik dikembalikan dengan berbagai alasan yang bersifat yuridis formal. DPR sendiri juga tidak mengambil inisiatif untuk merekomendasikan adanya pengadilan HAM adhoc, sebagai tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. 13 71. Sementara dalam Rapat Kerja Jaksa Agung dengan Komisi II dan III DPR RI, Jaksa Agung menyatakan bahwa salah satu kendala penanganan kasus pelanggaran HAM berat yang selama ini telah terjadi adalah perbedaan persepsi yang substansi antara Kejaksaan Agung dengan Komnas HAM yaitu menyangkut pemahaman tentang ketentuan formil prosedural antara lain tentang pembuatan berita acara, proses penyelidikan dan batasbatas tugas dari kewajiban Komnas HAM selaku penyelidik dengan Kejaksaan Agung selaku penyidik, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab atas tindakan-tindakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing institusi hukum tersebut. 4 1.4. Rendahnya Inisiatif DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 72. Dalam rangka peringatan tragedi Mei 1998, untuk kesekian kalinya keluarga korban didampingi Kontras mempertanyakan perkembangan penyidikan kasus Mei 1998 di Kejaksaan Agung. Diterima oleh Kapuspenkum Suhandoyo SH serta Direktur Penanganan HAM Berat, Kejaksaan Agung menyatakan kesulitan untuk meminta penjelasan dari saksi untuk mengidentifikasi pelaku serta kurangnya bukti-bukti. Ditegaskan bahwa berkas kasus yang diserahkan komnas HAM itu tidak lengkap, sehingga kalaupun dipaksakan dilimpahkan ke pengadilan, perkara ini nanti akan bebas. Salah seorang keluarga korban, Budi Hartono menilai Kejaksaan Agung enggan menuntaskan penyidikan kasus tragedi Mei 1998 dan hanya melempar tanggung jawab ke instansi lain dengan tidak menindaklanjuti berkas dari Komnas HAM. 73. Dalam pertemuan dengan keluarga korban, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim G Nusantara menyatakan telah melakukan hearing sebanyak 4 kali dengan Komisi III DPR. Komnas HAM meminta DPR melakukan audit kinerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung atas tersendatnya kasus Mei dan Trisakti Semanggi. Sementara mantan tim penyelidik kasus Mei 1998 di Komnas HAM, Solahudin Wahid mengusulkan agar DPR segera merekomendasikan kepada presiden agar membentuk Pengadilan ad hoc untuk mengungkap tragedi Mei 1998. 74. Akhirnya, Rapat Intern Komisi III DPR RI tanggal 30 Juni 2005, menghasilkan kajian yang mendasarkan diri pada pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap peristiwa Kerusuhan Mei 1998, dan akan mengirimkan surat kepada Pimpinan Dewan tentang Sikap dan Pendapat Komisi III DPR, berupa : “Untuk kasus Kerusuhan Mei 1998, Komisi III DPR RI berpendapat untuk dilakukan pembahasan secara mendalam yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPR (Komisi atau Pansus). Dalam pertemuan terakhir keluarga korban dengan Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III menyatakan akan membahas hal ini dalam Rapat Paripurna dan akan mempertanyakan dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung. Hingga kini DPR belum juga membahas kasus Mei 1998 ini. 75. Pola impunitas seperti kasus Mei 1998 juga terjadi pada beberapa kasus yang lain, seperti kasus Sambas dan Sampit di Kalimantan yang pada intinya tidak terdapat penghukuman bagi pelaku maupun aparatus negara (pembiaran) dan reparasi bagi korban. 2. Kerusuhan/Konflik Etnis di Kalimantan 4 Bahan Jaksa Agung RI pada Rapat Kerja Gabungan Komisi II dan Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung RI, 7 Februari 2005. 14 Konflik yang terjadi di Kalimantan banyak yang melibatkan antara etnis Dayak dan Madura. Dua konflik besar dan sampai saat ini tidak tertangani adalah kasus Sambas (1998-1999) san kasus Sampit (2001). 2.1. Konflik Etnis di Sambas, Kalimantan Barat Tahun 1998-1999 76. Konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat – antara kelompok Dayak dengan Madura pendatang - meledak pada 1998. Peristiwa kekerasan akibat konflik etnik ini berlangsung selama hampir 1 tahun. Selama periode konflik tersebut jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak. Selain itu, dampak dari konflik ini menyebabkan terjadinya pengungsian dalam jumlah mencapai 68.000 orang. 77. Hal yang patut dipertanyakan adalah tanggung jawab negara untuk mencegah konflik dan memberikan rasa aman kepada warganya di Sambas. Bahkan sampai saat ini, tidak ada mekanisme yudisial yang bisa menghasilkan truth seeking atas kasus Sambas, tidak ada pejabat negara yang dihukum karena melakukan pembiaran (ommission), dan tidak ada mekanisme reparasi yang memadai bagi para korban. Begitu pula tidak ada mekanisme dari pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan perdamaian (rekonsiliasi), akibatnya prasangka dan ketegangan antara kedua etnis masih terus berlangsung. 78. Kasus yang terjadi di Sambas ditengarai sebagai salah satu pemicu timbulnya kasus kerusuhan antar etnis (Dayak dan Madura) yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah (2001) 2.2 Konflik Etnis di Sampit, Kalimantan Tengah Tahun 2001 79. Konflik etnis –antara kelompok Dayak dengan Madura pendatang- meledak pada 18 Februari 2001 di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Peristiwa kekerasan akibat konflik etnik ini berlangsung selama sekitar 10 hari. Selama periode konflik tersebut jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak: sekitar 341 dari pihak Madura dan sekitar 16 orang dari pihak Dayak. Selain itu ratusan rumah dibakar atau dirusak. Data itu didapat dari Polres Kotawaringin Timur. Pasca konflik juga ditandai oleh eksodus para pengungsi (IDPs) berjumlah hampir 30 ribu – dari pihak Madura - dari Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Sebagian besar dari pengungsi itu hingga saat ini belum juga berani kembali ke tempat tinggal semulanya karena masih merasa tidak terjamin keamanannya. 80. Hal yang patut dipertanyakan adalah tanggung jawab negara untuk mencegah konflik dan memberikan rasa aman kepada warganya di Sampit. Padahal sebelum pecah konflik, berbagai indikasi awal akan terjadinya konflik komunal sudah bisa dirasakan. Paling tidak sudah terjadi 3 kasus kriminal yang potensial akan menyulut konflik sosial yang lebih besar; kerusuhan Tumbang Samba (17 September 1999), kerusuhan Kumai (5 Juli 2000), dan kerusuhan Kereng Pangi (17 Desember 2000). Pasca ketiga kasus tersebut, di tengah-tengah masyarakat sudah beredar selebaran, isu-isu, teror, dan ancaman yang berisi kebencian etnis terhadap kelompok tertentu. Tanggung jawab negara juga kembali dipertanyakan karena sebelum konflik Sampit meletus di bulan Februari 2001, sebuah Yayasan Pendidikan Islam Al-Miftah yang bertempat di Pamekasan, Madura –yang memiliki cabang di Kereng Pangi - telah melaporkan adanya ancaman dan meminta pengangan dari pemerintah pusat dan daerah. 81. Pada bulan Mei 2001, sejumlah organisasi HAM –KontraS, YLBHI, PBHI, ELSAM, dan APHI- mengajukan gugatan terhadap penyelenggara pemerintahan RI, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang dianggap gagal memberikan rasa aman bagi 15 masyarakat dan membiarkan konflik berjalan. Gugatan lewat mekanisme legal standing ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 82. Pasca konflik sosial, Komnas HAM (2001) juga melakukan penyelidikan atas kasus Sampit tersebut dan hasilnya menunjukkan telah terjadi pelanggaran HAM. Sayangnya hingga saat ini tidak ada mekanisme yudisial yang bisa menghasilkan truth seeking atas kasus Sampit, tidak ada pejabat negara yang dihukum karena melakukan pembiaran (ommission), dan tidak ada mekanisme reparasi yang memadai bagi para korban. Akibatnya prasangka dan ketegangan antara kedua etnis masih terus berlangsung. 3. Penutup 83. Impunitas terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya: a) tidakadanya mekanisme yudisial maupun ekstra yudisial yang memadai untuk menghukum pelaku dan menghadirkan keadilan bagi korban; b) tidakadanya mekanisme truth seeking dan pembangunan rekonsiliasi dalam konflik etnis; c) tidakadanya mekanisme reparasi bagi korban; d) bahkan kejahatan yang berbasis rasial hanya dianggap sebagai kejahatan umum/biasa. C. DISKRIMINASI NEGARA TERHADAP ETNIS TIONGHOA 84. Walaupun keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia sudah lama sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, namun keberadaan mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan diskriminasi rasial antara lain dalam hal pengakuan status kewarganegaraan Republik Indonesia mereka dan permasalahan sebagian etnis Tionghoa yang diperlakukan sebagai stateless (tanpa kewarganegaraan). 1. Kewajiban Kepemilikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) 85. Permasalahan kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang disingkat SBKRI merupakan salah satu bentuk diskriminasi rasial oleh negara terhadap warga negara Indonesia etnis Tionghoa. Dalam kebijakan tersebut setiap warga negara Indonesia etnis Tionghoa diwajibkan memiliki SBKRI untuk membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesianya dalam berbagai pelayanan publik, seperti dalam pengurusan paspor, KTP, catatan sipil, permohonan kredit ke bank, dan sebagainya. Sementara untuk warga negara Indonesia bukan etnis Tionghoa cukup membuktikan dengan KTP atau Akta Kelahiran saja. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk pembedaan perlakuan atas dasar ras/etnis yang bertujuan mengurangi pengakuan atas status mereka, sebagaimana termasuk dalam cakupan bentuk diskriminasi rasial dalam definisi diskriminasi rasial pasal 1 ICERD. 86. Permasalahan SBKRI muncul pertama kali ketika dilegalisir UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal IV Peraturan Penutup UU No. 62 tahun 1958 menegaskan bahwa: “Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menerapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak, menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau 16 berdasarkan Undang-Undang lain”. Ketentuan ini sebenarnya berlaku secara fakultatif dan diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian UU ini ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B.3/4/12 tahun 1978, yang dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa “Setiap warganegara RI yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI”. 87. Namun kemudian dalam kenyataannya kebijakan tersebut ditindak-lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB 3/31/3 tahun 1978 kepada Semua Pengadilan Negeri dan Semua Kepala Perwakilan RI di luar negeri, dimana SBKRI hanya ditujukan kepada kaum peranakan. Dalam praktek hanya terhadap peranakan Tionghoa, sedangkan peranakan lain seperti Arab, India, dll tidak diberlakukan. 88. Persoalan SBKRI ini selalu muncul karena menjadi salah satu syarat yang selalu diminta oleh instansi-instansi terkait, seperti : jajaran Departemen Dalam Negeri, mensyaratkan untuk mengurus akta kelahiran, perkawinan, dan bahkan kematian sekalipun; jajaran Departemen Pendidikan Nasional masih mensyaratkan untuk keperluan sekolah; jajaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan mensyaratkan untuk keperluan usaha; bahkan jajaran Departemen Kehakiman & HAM sendiripun (dalam hal ini jajaran Imigrasi) menganggap SBKRI adalah ‘wajib’. 89. Walaupun berupa pembedaan perlakuan secara administratif, namun secara prinsip kewarganegaraan, kebijakan SBKRI menempatkan status kewarganegaraan kelompok etnis Tionghoa pada status “yang diragukan (status quo)” berbeda dengan kelompok warga negara Indonesia lainnya. Dalam perkembangannya penerapan SBKRI tersebut mengakibatkan terjadinya pembatasan atas akses warga negara Indonesia etnis Tionghoa kepada perguruan tinggi negeri, menjadi pegawai negeri atau TNI/Polisi, dan lain sebagainya pada periode tahun 1978 – 1999. Bahkan di beberapa daerah muncul Peraturan Daerah seperti di Kabupaten Banyumas yang masih membedakan tempat dan persyaratan pelayanan pencatatan sipil untuk etnis Tionghoa dengan mereka yang disebut golongan pribumi ataupun golongan peranaan lainnya seperti Arab, India, atau seorang WNI Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di daerah Yogyakarta berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY No. 398/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI non-Pribumi. Penerapan kebijakan SBKRI dan beberapa kebijakan yang diskriminatif masih berlaku hingga saat ini seperti tertulis dalam tabel peraturan perundangan yang diskriminatif yang terlampir dalam laporan ini. 90. Memang bahwa telah ada beberapa upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan SBKRI tersebut misalnya dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 yang menegaskan bahwa dalam hal pembuktian kewarganegaraan RI tidak dibutuhkan SBKRI dan cukup dengan Akta Kelahiran atau KTP bagi warga negara Indonesia, dan terakhir berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang diharapkan dapat menganulir praktek SBKRI, namun dikarenakan belum dicabutnya secara tegas Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B.3/4/12 tahun 1978 yang menjadi sumber hukum SBKRI, dan ketidaktegasan pemerintah RI terhadap birokrasi dalam hal penerapan SBKRI, SBKRI masih saja dipersyaratkan oleh Kantor Imigrasi dan Kantor Catatan Sipil hingga saat ini. Berbagai alasan seperti untuk mencegah masuknya imigran tanpa documen RRT ke Indonesia ataupun pemalsuan dokumen catatan sipil, yang sebenarnya merupakan permasalahan ketidakmampuan koordinasi antar-instansi pemerintahan, yang kemudian justru membebankan SBKRI itu kepada masyarakat. Masuknya beberapa imigran yang terkait dengan tindak terorisme ke Indonesia dengan dokumen palsu justru menunjukkan 17 irasionalnya penerapan SBKRI tersebut untuk WNI (Warga Negara Indonesia) etnis Tionghoa. 91. Pengalaman yang dialami oleh beberapa warga negara Indonesia etnis Tionghoa, seperti yang dialami oleh Sdr. Andrianto di daerah Kraton Lor, Pekalongan, yang masih dipertanyakan SBKRI-nya ketika mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia (23 Februari 2007), Sdr. Papang Hidayat yang masih dimintai SBKRI-nya ketika mengurus perpanjangan KTP-nya (Januari 2007, Jakarta) atau Sdr. Rico Permana (Kelapa Gading, Jakarta) yang dimintakan SBKRI orang tuanya ketika mengurus pernikahannya oleh pihak Gereja dikarenakan disyaratkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta (29 Januari 2007), menunjukkan political will setengah hati pemerintah RI untuk menyelesaikan permasalahan SBKRI dan diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Bahkan dalam laporan investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di beberapa kota pada tahun 2005 di beberapa kota Indonesia masih diterapkan kebijakan SBKRI tersebut. 92. Dengan masih adanya kebijakan SBKRI yang masih belum dicabut dan masih diterapkannya SBKRI oleh pejabat-pejabat atau aparatur yang berwenang atau lembaga pemerintahan seperti Kantor Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menunjukkan bahwa pemerintah RI belum secara konsekeuen memenuhi kewajiban negara pihak untuk mengkaji ulang, mengubah, mencabut atau membatalkan kebijakan yang masih berlaku atas diterapkannya kebijakan diskriminasi rasial SBKRI dan untuk mencegah, melarang dan menghapuskan segala bentuk praktek-praktek diskriminasi rasial sebagaimana diatur dalam ICERD pasal 2 huruf c, Pasal 3 dan Pasal 5 ICERD. 2. Permasalahan Etnis Tionghoa Yang Diperlakukan Sebagai Stateless (Tanpa Kewarganegaraan) 93. Selain permasalahan SBKRI, praktek diskriminasi rasial terhadap kelompok etnis Tionghoa di Indonesia adalah permasalahan masih adanya kelompok etnis Tionghoa yang diperlakukan sebagai stateless (tanpa kewarganegaraan) karena tidak mempunyai dokumen yang dapat membuktikan kewarganegaraan Republik Indonesianya. Ketiadaan dokumen seperti Akta Kelahiran, KTP ataupun SBKRI disebabkan karena hilangnya dokumen yang dimiliki karena bencana banjir atau kebakaran ataupun karena benang kusut kebijakan kewarganegaraan RI yang diakibatkan perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT Tahun 1955. 94. Dalam hal disebabkan karena benang-kusut kebijakan kewarganegaraan RI muncul pertama ketika Perdana Menteri RRT (Republik Rakyat Tiongkok) pada tahun 1955, Chou Enlai melakukan politik klaim bahwa berdasarkan asas kewarganegaraan ius sanguinis (keturunan) yang baru diadopsi oleh RRT saat itu, semua etnis Tionghoa yang ada di luar RRT termasuk di Indonesia adalah WN (Warga Negara) RRT. Akibatnya kemudian antara pemerintah RI dan RRT dilakukan perjanjian dwi-kewarganegaraan berdasarkan UU No. 2 Tahun 1955, yang mewajibkan semua etnis Tionghoa di Indonesia untuk menyatakan memilih kewarganegaraan RI atau RRT, terkecuali mereka yang menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pegawai Negeri, berjasa bagi negara RI, menjadi petani atau pernah mengikuti pemilihan umum 1955. Namun dalam kenyataannya beberapa mereka yang menjadi pengawai negeri, petani ataupun yang sudah mengikuti pemilihan umum, bahkan beberapa pemain bulutangkis yang berjasa seperti Tan Joe Hoek tetap diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan antara RI dan RRT, termasuk juga Liem Koen Hian, salah satu pendiri negara RI pada tahun 1945. 18 95. Apalagi kemudian pada saat berlangsungnya proses dwi-kewarganegaraan, Pemerintah RI mengeluarkan beleid Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959 tentang pelarangan WN Asing untuk berdagang di daerah kabupaten/Swatantra. Beleid ini kemudian mengakibatkan pengusiran dan eksodus besar-besaran terhadap etnis Tionghoa dari daerah tingkat kabupaten/swatantra walaupun sebenarnya mereka masih berstatus WNI. kebijakan yang menyulut diskriminasi etnis tionghoa dan berujung pada pengusiran secara besar-besaran tersebut, menyebabkan sebagian etnis tionghoa yang ada di tanah air pergi meninggalkan Indonesia, dan sebagian lainnya menetap. sebagian yang masih menetap itu, akhirnya menjalani proses penyelesaian dwi-kewarganegaraan. akan tetapi oleh karena proses tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak semua etnis tionghoa yang menetap, mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai bentuk pengakuan kewarganegaraan Indonesia. dalam hal ini, masih terdapat banyak etnis tionghoa yang tidak mendapatkan dokumen dimaksud. ketiadaan dokumen kewarganegaraan RI ini mengakibatkan etnis Tionghoa itu diperlakukan sebagai stateless. 96. Keadaan stateless ini berjalan demikian lama dan bergenerasi-generasi tanpa penyelesaian yang pasti dari pemerintah. Akibatnya, segala hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai warganegara, tidak mereka dapatkan. sebagai contoh: hak atas identitas (KTP), dan hak-hak untuk mendapatkan pelayanan publik lainnya. Kondisi ini pula mengakibatkan seluruh anak-anak yang lahir di Indonesia dari orangtua yang diperlakukan stateless ini tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana dilindungi oleh Konvensi Perlindungan Anak, khususnya hak untuk mendapatkan akte kelahiran. 97. Memang pada tahun 1980, atas inisiatif organisasi kemasyarakatan Indonesia bersama dengan pemerintah RI pernah memproses cepat mereka yang stateless tersebut sejumlah etnis Tionghoa dengan memberikan dokumen SBKRI, namun begitu diperkirakan masih menyisakan puluhan ribu orang di berbagai wilayah. (Data Departemen Kehakiman RI pada tahun 2001 diperkirakan berjumlah 30.000 orang). Setelah 1980 pun ada beberapa upaya kebijakan pemutihan akta kelahiran terhadap warga negara Indonesia bukan Tionghoa yang tidak mempunyai akta kelahiran. Namun pemutihan tersebut tidak pernah diberikan kepada etnis Tionghoa yang diperlakukan sebagai stateless. Beberapa upaya personal etnis Tionghoa untuk mendapatkan akta kelahiran selalu mendapatkan penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alasan ketiadaan kepemilikan SBKRI. 98. Permasalahan diskriminasi rasial tersebut berlangsung dalam waktu lama hingga saat ini. Permasalahan ini dialami, misalnya, oleh Tan Elim alias Momoy atau Tan Tian Lie dan Pui Nyin Wah yang dikarenakan orang tuanya tidak memiliki dokumen seperti SBKRI atau Akta Kelahiran tidak dapat mengurus KTPnya di Kelurahan Kedaung, Tangerang. Dalam contoh kasus serupa di daerah Tegal Alur dan Tangerang, jumlah etnis Tionghoa yang diperlakukan sebagai stateless karena tidak memiliki dokumen tersebut diperkirakan berjumlah 135 orang (Sumber data: Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia (LADI), Tegal Alur, Tangerang, Indonesia). Dan kasus-kasus serupa juga dialami oleh etnis Tionghoa di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, dan wilayah lainnya. 99. Dikarenakan status mereka sebagai etnis Tionghoa (yang selalu diprejudice sebagai orang kaya karena ketionghoaan mereka), dan kemiskinan, seringkali ketika berhadapan dengan pejabat dan kebijakan, meraka mengalami perlakukan diskriminasi yang bertingkattingkat. Dalam setiap program kesejahteraan pemerintah seperti pembagian beras untuk orang miskin atau bantuan langsung tunai, mereka menjadi kelompok yang termarjinalkan. Dalam himpitan ekonomi tersebut dan ketidakjelasan staus hukum 19 mereka, seringkali anak-anak perempuan mereka menjadi sasaran empuk traficking ke Taiwan. Dalam kelompok ini etnis tionghoa yang stateless mengalami diskriminasi rasial yang mengakibatkan beban ganda atas berbagai perlakukan diskrimnasi. 100. Dalam konteks ICERD, permasalahan stateless etnis Tionghoa tersebut merupakan permasalahan diskriminasi rasial. Berdasarkan General Recommendation CERD No. 30: Diskriminasi terhadap Bukan Warga Negara:01/10/2004 Point 16, terdapat kewajiban negara RI sebagai negara pihak ratifikasi ICERD untuk mengurangi dan menangani keadaan statelessness (tanpa kewarganegaraan) khususnya pada anakanak. Apalagi dalam konteks hukum nasional Republik Indonesia pun, Peraturan Kewarganegaraan RI baik itu UU No. 62 Tahun 1958 ataupun UU Kewarganegaraan RI yang berlaku saat ini yaitu UU No. 12 Tahun 2006, mempunyai prinsip pencegahan stateless (tanpa kewarganegaraan). D. DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT ADAT 1. Pendahuluan 101. General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples : 18/08/97. Point 1 menyatakan bahwa “ In the practice of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, in particular in the examination of reports of States parties under article 9 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the situation of indigenous peoples has always been a matter of close attention and concern. In this respect, the Committee has consistently affirmed that discrimination against indigenous peoples falls under the scope of the Convention and that all appropriate means must be taken to combat and eliminate such discrimination”. 102. Dalam general recommnendation point 1 tersebut jelas menyatakan bahwa ‘...the situation of indigenous peoples has always been a matter of close attention and concern. In this respect, the Committee has consistently affirmed that discrimination against indigenous peoples falls under the scope of the Convention and that all appropriate means must be taken to combat and eliminate such discrimination”. Point ini mendasari bahwa persolan diskriminasi terhadap Masyarakat Adat juga dapat masuk dalam ruang lingkup ICERD. 103. Sebuah pertemuan di Tanah Toraja pada tahun 1993, mendefenisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, politik, budaya, sosial dan budaya sendiri. Kingsbury (1995:33) memberikan ciri kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok masyarakat adat. Salah satu ciri yang disebut adalah adanya keterkaitan yang panjang (lama) dengan wilayahnya. Selain ciri tersebut, kelompok-kelompok masyarakat adat dapat dikenali dari ciri-ciri seperti: adanya pertalian budaya yang dekat dengan suatu areal pertanahan atau teritori tertentu, keberlanjutan sejarah dengan penghuni-penghuni tanah sebelumnya, perbedaan-perbedaan sosio ekonomi dan sosio kultural dengan penduduk di sekitarnya, karakteristik bahasa, ras, kebudayaan materiil dan spiritual dan sebagainya yang berbeda, dan dianggap sebagai “indigenous” oleh penduduk sekitarnya. 2. Bentuk Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. 104. Dalam hal ini, bentuk diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia terjadi dalam 4 (empat) hal yaitu dalam kasus Perampasan Tanah/sumber daya alam, Kebijakan Pembangunan, Politik Pencitraan dan Diskriminasi akibat Regulasi Negara 20 2.1. Perampasan Tanah dan Sumber Daya Alam: Awal Bencana bagi Masyarakat Adat di Indonesia 105. Secara umum, hak-hak masyarakat adat yang mendapat perlakuan diskriminastif adalah hak-hak yang berhubungan dengan tanah dan sumber daya alam yang merupakan wilayah adat. Sumbernya adalah penafiaan keberadaan mereka yang menimbulkan pembatasan, dan pengecualian sehingga menimbulkan dampak pada rusaknya hak–hak mereka terutama berbasiskan pada identitas. Kondisi ini masuk dalam ruang lingkup ICERD pasal 1 point 1. 106. Dari ciri-ciri masyarakat adat di Indonesia, hubungan mereka dengan tanah dan wilayah adat merupakan kunci dari keutuhan mereka sebagai masyarakat adat. Hal itu dikarenakan tanah merupakan satu-satunya ruang yang merupakan tempat bagi masyarakat adat untuk mengekspresikan dirinya. Tanah bagi masyarakat adat selain merupakan ruang ekspresi yang menghubungkan mereka dengan keyakinan, sejarah, budaya dan bahasa, tanah juga merupakan satu-satunnya ruang yang dapat mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 107. Secara umum juga, praktek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan General Recommendation point 5, “ The Committee especially calls upon States parties to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources and, where they have been deprived of their lands and territories traditionally owned or otherwise inhabited or used without their free and informed consent, to take steps to return those lands and territories. Only when this is for factual reasons not possible, the right to restitution should be substituted by the right to just, fair and prompt compensation. Such compensation should as far as possible take the form of lands and territories. 108. Selanjutnya dalam general recomendation (point 3) tersebut juga disebutkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat adat khususnya perampasan tanah dan sumber daya alam yang menimbulkan efek terancamnya identitas mereka. Hal ini juga bagian dari diskriminasi. Dalam konteks ini laporan alternatif memuat bagaimana kondisi masyarakat adat yang mengalami tindakan diskriminasi yang pada akhirnya menimbulkan dampak terancamnya identitas mereka, terutama berbasiskan masalah perampasan tanah baik oleh negara mapun oleh perusahaan. 109. Fakta yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia sangat memprihatinkan. Mereka secara sistematis terus menerus mengalami diskriminasi, terutama hilangnya akses mereka terhadap tanah dan sumber daya alam, yang berarti pembatasan dan pengrusakan terhadap ekspresi identitas masyarakat adat. Ini terjadi karena paradigma pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dikembangkan didasarkan pada konsep developmentalisme. Developmentalisme mensayaratkan adanya ketersediaan sumber daya alam. Untuk keperluan itu, negara mencaplok kepemilikan masyarakat adat atas Tanah Ulayat (pada umumnya, kepemilikan masyarakat adat didasarkan pada klaim historis). Hak Menguasai Negara (HMN) terhadap bumi, air, dan sumber daya alam lainnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan oleh pemerintah secara keliru, dimana pengelolaannya diserahkan pada sektor privat yang tentu saja mengutamakan keuntungan ekonomi pribadinya daripada kesejahteraan masyarakat. Dengan tafsir yang keliru tersebut, Negara menjadikan tanah-tanah ulayat masyarakat adat sebagai perkebunan skala besar yang kepemilikannya diserahkan pada kolaborasi pengusaha dan penguasa (pemerintah). Bahkan tanah ulayat masyarakat adat, yang 21 beberapa diantaranya merupakan Hutan Lindung kemudian diberikan kepada sektor pertambangan swasta dengan UU No. 19 Tahun 2004. Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang didasarkan pada paradigma developmentalisme di Indonesia, tak dapat dipungkiri telah mendiskriminasi masyarakat adat dari hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. 110. Misalnya hal ini terjadi terhadap masyarakat adat Denai pada tahun 2005 yang meminta tanahnya dikembalikan setelah dikuasai negara melalui PTPN II Sumatera Utara. Masyarakat Adat Denai tersebut tidak mendapatkan tanahnya kembali dan pemulihan atas perampasan tanah yang telah berlangsung lama, akan tetapi mereka justru ditembaki, dipukuli dan beberapa rumah dibakar oleh aparat Kepolisian dan preman yang dibayar. Begitu pula yang dialami oleh masyarakat adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang tanahnya juga dirampas oleh PT Perusahaan Perkebunan (PP) London Sumatera (Lonsum) Indonesia Tbk. Ketika mereka melakukan reclaiming mendapatkan represif oleh aparat kepolisian dan 39 orang masyarakat adat Kajang ditahan. Kedua kasus tersebut sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tidak ada upaya pemulihan bagi korban. Selain itu masih banyak lagi kasus lain yang sampai saat ini masih berlangsung. 111. Kasus yang serupa juga menimpa komunitas adat Karonsi’e Dongi (Luwu Timur, Sulawesi Selatan). Masyarakat Adat ini pernah terusir dari wilayah adatnya akibat diserang oleh DI/TII pada tahun 1950-an. Lalu, pada tahun 1970-an, komunitas ini berusaha kembali ke tanah adatnya tetapi mengalami kesulitan karena tanah adat tersebut sudah dikuasai oleh perusahaan Inko. Sampai saat ini, terdapat sekitar 40 Kepala Keluarga yang terus berusaha untuk menempati tanah di sekitar perusahaan, tetapi selalu mengalami intimidasi dan upaya pengusiran. Diskriminasi yang dialami oleh komunitas ini adalah: a) tidak bisa membangun pondok di sekitar tanah yang dikuasai oleh perusahaan; b) Anak-anak komunitas adat ini tidak bisa mengakses pendidikan, karena sekolah yang ada di sekitar mereka dikuasai oleh perusahaan dan hanya diperuntukkan bagi keluarga karyawan perusahaan. 112. Dari kasus tanah berimplikasi pada perampasan hak lain, seperti yang diatur dalam pasal 5 ICERD. Beberapa hak yang terlanggar adalah; 1) Hak atas Pesamaan di depan Hukum. Masyarakat adat Denai melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada aparat kepolisian, ternyata laporan tersebut tidak ditindak lanjuti. Bahkan Kepolisian setempat menghindari kasus tersebut dengan melimpahkan kasusnya kepada kepolisian yang lebih tinggi, sehingga masyarakat adat Denai kesulitan mengaksesnya. Pelanggaran terhadap hak ini secara gamblang tercermin dalam kasus ditolaknya laporan masyarakat adat Denai tentang tindakan kriminal berupa penggusuran dan pentraktoran terhadap lahan pertanian mereka oleh pihak PTPN II yang didukung oleh anggota Kesatuan Brimob (Polisi). Dalam posisi sebagai institusi yang melayani masyarakat, tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 22 terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Pasal 15 Ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan kewenangan institusi kepolisian secara umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya antara lain adalah; (a) menerima laporan dan/atau pengaduan, dan (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam kasus Denai dan Bulukumba, fungsi ini tidak dilaksanakan oleh institusi kepolisian di daerah-daerah tersebut, bahkan tindakan yang dilakukan adalah ikut terlibat dalam penggusuran lahan pertanian masyarakat adat (Denai), melakukan penembakan terhadap masyarakat adat (Bulukumba). Hal ini menggambarkan bahwa institusi ini selain melanggar produk hukum nasional (UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara) juga telah melanggar Hak setiap orang atas kesamaan dalam perolehan kesempatan dan pelayanan di tempat-tempat publik, seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. 2) Hak untuk Bebas dari Rasa Takut dan Kekerasan. Hal ini misalkan saja terjadi pada masyarakat adat Kajang yang mengalami kekerasan dan penahanan terhadap 39 orang. Ternyata tidak berhenti begitu saja, masih ada teror yang dilakukan oleh aparat berupa penggeledahan dan pengejaran masyarakat sampai ke desa-desa. 3) Hak untuk Mendapatkan Warisan. Peristiwa pentraktoran tanah-tanah pertanian di kampung Denai Sumatera Utara, dan juga peristiwa yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan, adalah pelanggaran terhadap hak ini. Tanah yang diklaim oleh masyarakat adat sebagaimana disebutkan di atas sebagai tanah mereka adalah tanah ulayat, dan perampasan terhadap tanah ini merupakan suatu tindakan yang sekaligus menghilangkan kesempatan bagi anak-anak dan cucu mereka untuk mendapatkan bagian/warisan dari tanah ulayat ini. 2.2. Kebijakan Pembangunan Terhadap Masyarakat Adat: Contoh kasus Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi 113. Taman Nasional Bukit Duabelas merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis dataran rendah di Provinsi Jambi yang secara astronomis terletak pada 1º44’35’’ LS 2º03’15’’LS, 102º31’37’’ BT - 102º48’27’’ BT. Semula kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan areal penggunaan lain yang digabung menjadi taman nasional. Kawasan TNBD mencakup tiga kabupaten dengan luas areal keseluruhan berdasarkan data sementara (DIPHUT, 2004), meliputi areal 58300 Ha. dengan rincian luas sebagai berikut : (a) Kabupaten Batanghari ± 65% (37000 Ha.), (b) Kabupaten Sarolangun ± 15% (9000 Ha.), (c) Kabupaten Tebo ± 20% (11500 Ha.). Taman Nasional Bukit Duabelas dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000, tanggal 23 Agustus 2000. 114. Dalam kawasan tersebut hidup sebagian besar Suku Anak Dalam ( SAD) yang secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 200.000 orang yang tersebar di tiga wilayah 23 (Bukit Duabelas, Bukit Tigapuluh, dan sepanjang Jalan Lintas Sumatera. Penetapan Kawasan Bukit Duabelas sebagai Taman Nasional yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi komunitas SAD, ternyata berujung dengan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak asasi SAD. Perubahan status kawasan bukannya bertujuan mempertahankan eksistensi SAD, tetapi berubah ujud menjadi alat untuk memaksa SAD keluar dari “kehidupan” mereka. 115. Mereka yang hidup secara nomaden dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan meramu, tidak mungkin dipaksa keluar dari hutan dimana mereka hidup dan menggantungkan diri, bahkan keyakinannya. Pola kehidupan yang mereka jalani, itu lebih disebabkan karena keterikatan adat istiadat yang begitu kuat. Hidup berkelompok dengan pakaian hanya sebagian menutupi badan. Hal ini juga diperkuat dengan keyakinan animisme yang mereka anut. Jika apa yang diinginkan pemerintah tetap dipaksakan, maka yang terjadi adalah seperti apa yang ditemukan Komnas HAM beberapa bulan lalu.bahwa terdapat 12 jenis Pelanggaran HAM terhadap Suku Anak Dalam di dalam kawasan Taman Nasional Bukit 12 Jambi. 116. Sesuai dengan rentetan peristiwa dan fakta yang dialami orang rimba atau SAD, terdapat perlakuan-perlakuan diskriminatif yang didasari atas alasan bahwa mereka adalah orang rimba oleh pemerintah yang menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Diantara pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sesuai dengan temuan Komnas HAM yang dicantumkan dalam surat Komnas HAM Nomor : 088/SR-KHU/III/07 yang menyatakan bahwa: a. Telah terjadi pelanggaran hak kelompok khusus, dimana pemerintah secara umum belum memberikan perlakuan dan perlindungan lebih terhadap Orang Rimba sebagai kelompok khusus dalam kebijakan pembangunan ; b. Telah terjadi pelanggaran atas tanah ulayat, dimana ada upaya berupa kebijakan taman nasional dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan perkebunan sawit., yang telah dan akan mengurangi dan atau tidak mengakui hak ulayat Orang Rimba ; c. Telah terjadi pelanggaran hak untuk hidup secara bermartabat, dimana telah terjadi pembatasan, pengurangan, dan pelarangan terhadap aktivitas kehidupan Orang Rimba sebagai akibat kebijakan taman nasional bukit duabelas ; d. Telah terjadi pelanggaran hak atas lingkungan hidup, dimana lingkungan alam sebagai habitat hidup dan sumber penghidupan Orang Rimba telah rusak, diantaranya oleh kebijakan hak pengusahaan hutan dan ekspansi perkebunan sawit ; e. Telah terjadi pelanggaran hak atas kesehatan, dimana pemerintah tidak menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang layak, mampu diakses, dan dapat diterima Orang Rimba ; f. Telah terjadi pelanggaran hak atas pendidikan, dimana pemerintah tidak menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak, mampu diakses, dan dapat diterima oleh Orang Rimba ; g. Telah terjadi pelanggaran hak atas informasi, dimana pemerintah tidak memberikan dan menyediakan informasi yang cukup, adil, dan transparan dalam kebijakan taman nasional dan kebijakan pemerintah secara umum ; h. Telah terjadi pelanggaran hak atas pengembangan diri, dimana program pemerintah untuk memukimkan Orang Rimba di desa telah menyebabkan kehidupan Orang Rimba tidak berkembang, bahkan sebaliknya. Hal ini menyebabkan pengembangan diri Orang Rimba terhambat ; i. Telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman, dimana telah terjadi ancaman dan pelarangan aktivitas hidup Orang Rimba, perusakan hak milik, dan penembakan 24 oleh oknum aparat keamanan perkebunan sawit yang menyebabkan ketenangan hidup Orang Rimba terusik dan terganggu ; j. Telah terjadi pelanggaran hak atas kepemilikan, dimana telah terjadi perusakan dan pemusnahan atas hak milik Orang Rimba, maupun upaya dari kebijakan taman nasional yang akan berpotensi menghambat, membatasi, dan mengurangi hak milik Orang Rimba ; k. Telah terjadi pelanggaran hak untuk berpartisipasi, dimana pemerintah tidak membuka dan mengajak partisipasi Orang Rimba dalam perencanaan, perumusan, dan implementasi kebijakan taman nasional, khususnya atas penyusunan buku rencana pengelolaan taman nasional ; l. Telah terjadi pelanggaran hak atas status kewarganegaran, dimana pemerintah tidak memberikan hak berupa akta kelahiran bagi setiap anak Orang Rimba yang lahir sebagai bagian dari perlindungan dan pengakuan atas keberadan Orang Rimba. 117. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang konkrit untuk menghentikan pelanggaranpelanggaran hak asasi manusia terhadap Suku Anak Dalam. Bahkan setelah dikeluarkannya temuan Komnas HAM, BKSDA Jambi sebagai salah satu instansi pemerintah tidak mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini menunjukkan belum adanya iktikad baik pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik diskriminasi terhadap Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas. 118. Sementara itu, khusus untuk pelanggaran terhadap hak atas status kewarganegaraan, pemerintah bukan saja tidak memberikan hak atas akta kelahiran, tetapi juga belum menyediakan fasilitas administrasi kependudukan yang dapat mengakomodir SAD di dalamnya. Ketidakjelasan tempat tinggal masing-masing individu orang rimba menjadi alasan untuk itu. Padahal dengan membuat sistem administrasi kependudukan yang sesuai dengan pola hidup berpindah-pindah SAD, masalah ini dapat diselesaikan. 2.3 Stereotype 119. Yang dimaksud dengan stereotip di sini adalah sudut pandang yang di(re)produksi secara terus menerus untuk melihat dan mengkategori komunitas lain sebagai komunitas yang serba negatif, seperti tidak beradab, terbelakang, bandel, malas, pembangkang, tidak modern, dan sebagainya. Paska 1965, stereotip seperti ini semakin menguat, khususnya melalui berbagai sosialisasi pengetahuan tentang komunitas-komunitas yang dianggap membahayakan eksistensi kelompok mayoritas dan stabilitas nasional. 120. Komunitas Sedulur Sikep misalnya, selama puluhan tahun telah menjadi sasaran stigma, baik dari Negara maupun dari kelompok agama lain. Masih banyak kelompok lain yang menyebut komunitas ini dengan sebutan komunitas Samin, tapi dalam arti pejoratif. Samin seringkali diucapkan dengan nada keras (misalnya, dasar Samin!!), sekedar untuk menunjukkan bahwa komunitas ini identik dengan pembangkangan terhadap aturan negara, seperti pembuatan KTP, bayar pajak, dan sebagainya. Stigma yang sama juga terjadi dalam hal proses menjalankan ritual perkawinan. Komunitas Sedulur Sikep memiliki tata cara tersendiri dalam hal perkawinan, tetapi dianggap sebagai tata cara yang tidak benar. Bahkan, pihak pemerintah seperti petugas Kantor Urusan Agama (KUA) selalu berusaha mengajak komunitas Sedulur Sikep untuk melakukan nikah massal yang difasilitasi oleh pemerintah (Kepala Desa dan Pejabat KUA). 25 121. Bahkan, akhir-akhir ini, stigma dan stereotip terhadap komunitas Sedulur Sikep sebagai komunitas “terbelakang” muncul dalam bentuk film yang sedang digarap oleh salah satu sutradara di Jakarta. Film yang sedang dalam proses pembuatan ini mengisahkan tentang kehidupan komunitas Sedulur Sikep, seperti perkawinan, hubungan seksual, dan pendidikan yang digambarkan sebagai kultur komunitas yang tidak modern. 122. Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu juga mengalami stigmatisasi yang tidak kalah memprihatinkan. Komunitas ini juga diidentikkan sebagai komunitas pembangkang yang tidak patuh kepada aturan hukum Negara, seperti tidak memiliki KTP, tidak memakai helm ketika berkendaraan, tidak mau melakukan pemberitahuan pelaksanaan ritual atau hajat tertentu. Bahkan, dalam hal berkeyakinan pun, mereka dituding sebagai kelompok yang suka mencampurbaurkan antara beberapa ajaran agamaagama resmi. Pada tanggal 26 April 2007 yang lalu, komunitas ini disidang oleh beberapa pejabat pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Agama (Depag), Polisi, Militer, dan Jaksa untuk dimintai keterangan mengenai seluruh aktivitas keseharian mereka. Intinya, pemerintah memaksa komunitas dayak Indramayu ini untuk patuh dan mengikuti seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia. 123. Komunitas Wetu Telu di Nusa Tenggara Barat dan Komunitas Gantarang Keke (Bantaeng, Sulawesi Selatan) mengalami stigma sebagai komunitas “muslim yang tidak sempurna.” Sehingga beberapa pesantren di sekitar Lombok selalu berusaha untuk membawa komunitas wetu telu dan Gantarang Keke ke jalan yang benar. Hal ini ditengarai oleh anggapan dari beberapa tokoh agama dan pesantren bahwa keislaman komunitas wetu telu dan Gantarang Keke bukanlah Islam yang sebenarnya karena mereka tidak pernah menjalankan ritual dan ajaran Islam sebagaimana yang dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan oleh mayoritas muslim di dunia. Dalam hal pernikahan pun, komunitas wetu telu harus mengalami dua kali acara pernikahan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut tata acara adat. Pernikahan melalui KUA ini adalah bentuk diskriminasi yang mereka alami karena terdapat unsur pemaksaan dari pemerintah, karena jika tidak, maka komunitas wetu telu dan keturunannya akan sulit mendapatkan hak administrasi kependudukan yang lain, seperti akte kelahiran, masuk ke sekolah formal, dan sebagainya. 124. Stereotip, khususnya dalam bentuk pemburukan terhadap praktik ritual keyakinan juga menimpa komunitas tau taa wana di Sulawesi Tengah terutama melalui misi-misi keagamaan yang dilakukan oleh kelompok misionaris Kristen dan Islam. Komunitas Parmalim (Sumatera Utara) yang sulit mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran, komunitas penghayat kepercayaan seperti Karuhun Urang dan Kapribaden didiskriminasi sebagai komunitas yang tidak berhak mendapatkan hak administrasi kependudukan, serta Komunitas Cikoang (Sulawesi Selatan) yang diserang oleh kelompok lain (salah satu pesantren) karena menganggap tradisi maudhu lompoa sebagai sesuatu yang bid’ah (heresy/tidak sesuai dengan ajaran asalnya) dan telah keluar dari tradisi dan ajaran Islam. 125. Stereotip terhadap beberapa komunitas local ini seringkali berbanding lurus dengan kategori mereka sebagai komunitas yang tidak memeluk salah satu agama resmi negara sehingga berdampak pada sulitnya mendapatkan hak sipil. Bahkan, ketidaksejajaran keyakinan komunitas adat dengan keyakinan kelompok mayoritas agama juga berdampak pada perlakuan kekerasan. Hal ini sempat menimpa komunitas Papuangan Mandar (Sulawesi Selatan), pada September 2003 yang lalu, ritual Mappasialla Manu (secara harfiah dimaknai sabung ayam) dibubarkan oleh aparat dan beberapa orang di antaranya 26 ditangkap. Aparat menganggap bahwa ritual itu merupakan bentuk perjudian dan harus dilarang. 2.4. Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat melalui Peraturan Daerah (Perda) 126. Selain diakibatkan oleh stereotip (stigma, stereotip, dll), diskriminasi yang dialami oleh komunitas local (adat dan etnik) adalah akibat adanya Peraturan Daerah (Perda). Keyakinan komunitas local tersebut digeneralisir sebagai penganut kepercayaan, sehingga segala bentuk aktifitas ritual keyakinan mereka diikat dalam terminologi ini. Beberapa bentuk Peraturan Daerah yang diskriminatif dan berimplikasi langsung kepada komunitas lokal, di antaranya: a. Di Bulukumba (Sulawesi selatan), terdapat Peraturan Daerah (Perda) No. 6/2003, tentang baca tulis al-quran, Peraturan Daerah No. 4/2003 tentang berpakaian muslimmuslimah, Peraturan Daerah No. 3/2002, tentang penertiban minuman keras. Peraturan Daerah ini sangat berdampak pada komunitas Kajang karena mereka juga diharuskan tunduk pada aturan ini. Perda di Bulukumba yang berkaitan dengan baca tulis al-Qur’an, jelas memarginalisasi dan mendiskriminasi keyakinan komunitas adat Kajang yang meyakini Pasanga ri Kajang (kitab suci), karena saat ini mereka juga diwajibkan untuk tahu baca al-quran. Sedang Perda yang berkaitan dengan minuman keras juga menghabisi keyakinan masyarakat kajang, yang pada saat acara adat menjadikan tuak sebagai bagian dari ritual, anehnya minuman keras untuk daerah pariwisata seperti di Bira dibolehkan. b. Perda Sumbar No 2/2007 tentang Nagari merupakan ancaman bagi eksistensi komunitas adat Mentawai. Pada waktu pengesahan perda tersebut, terjadi penolakan dari komunitas adat mentawai, tetapi Perda tersebut tetap disahkan. Munculnya perda ini disebabkan oleh politik pengutamaan atas salah satu adat di atas adat yang lain. Salah satu ancaman diskriminasi terhadap komunitas adat mentawai adalah hancurnya seluruh kultur dan tatanan masyarakat adat mentawai. 3. PENUTUP 127. Diskriminasi terhadap masyarakat adat timbul akibat kebijakan Negara maupun oleh perusahaan, terutama terkait pengusaan tanah dan sumber daya alam yang juga berimplikasi terhadap terlanggarnya hak – hak lain. 128. Kenyataan ini merupakan pelanggaran terhadap ICERD sesuai dengan General Recommendation (GR ) No. 23: Indigenous Peoples : 18/08/97 point 1. Apalagi secara khusus disebutkan problem tanah dan sumber daya alam dalam point 3 General Recommendation tersebut menjadi perhatian khusus oleh Komite. Dipertegas lagi pemerintah Indonesia gagal menjalankan point 5 GR tersebut. 129. Diskriminasi terhadap masyarakat adat juga bisa terjadi melalui Peraturan Daerah, seperti yang disebutkan dalam kasus Bulukumba dan Mentawai. Di satu sisi, diskriminasi terhadap masyarakat adat ini muncul dan diakibatkan bukan hanya oleh stigma yang dilekatkan kepada komunitas adat dan Perda, tetapi juga dalam bentuk pembiaran aparat yang tidak melakukan tindakan hukum terhadap tindakan diskriminatif yang terjadi. E. DISKRIMINASI RASIAL TERHADAP ETNIK Dan PENGABAIAN RELIGI ETNIK 27 130. Pasal 1 Point 1 ICERD menyebutkan bahwa yang dimaksud diskriminasi rasial dalam konvensi adalah shall mean any distinction, exlusion, restriction or preferance based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose of effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life. Definisi dari Pasal 1 point 1 tersebut menyebut suku bangsa/etnik. Dalam pengertian diskriminasi berdasarkan pasal 1 point 1 tersebut juga ditujukan untuk aktifitas yang “memilki maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian, atau pelaksanaan atas dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, bidang kehidupan yang lain” yang dilakukan dengan “pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pengutamaan”. 131. Dalam konteks Indonesia yang memilki jumlah suku bangsa/etnik yang sangat besar dengan berbagai ragam identitas yang melekat pada etnik tersebut. Acap kali kebijakan yang diambil bersifat diskriminatif terhadap mereka dan bahkan kebijakan yang tidak langsung berhubungan dengan etnik tersebutpun membawa dampak diskriminasi. 132. Masuk dalam cakupan pengertian pasal 1 point 1 CERD yang dijelaskan di atas, dapat dibuktikan bahwa peristiwa / kasus yang dialami oleh etnik baik secara individu maupun kelompok tergolong dalam pengertian pelanggaran pasal 1point 1 CERD. 133. Oleh karenanya dalam laporan ini disajikan fakta bagaimana kelompok etnik mengalami perlakuan diskrininasi dalm konteks diskriminasi rasial / masuk dalam yuridiksi pengertian ICERD. 1. Latar Belakang 134. Selama ini kepercayaan-kepercayaan lokal yang biasanya dianut oleh kelompok etnis atau sub-etnis tertentu tidak pernah diakui keberadaannya oleh negara. Padahal jumlah mereka sangat besar, tersebar hampir di seluruh pelosok Nusantara, dengan aneka ragam kepercayaan dan praktik-praktik ritual yang mereka anut dan lakukan. 135. Apa yang disajikan dalam ringkasan laporan ini barulah sketsa beberapa kelompok yang cukup menonjol dalam memperjuangkan hak-hak mereka terhadap tindakan diskriminatif negara. Masih sangat banyak kelompok kepercayaan lokal yang berbasiskan etnis atau sub-etnis lainnya di Nusantara yang, sayangnya, belum memperoleh perhatian. 5 Diharapkan dengan paparan ringkas dari beberapa kelompok di bawah ini dapat ditengarai pola-pola kebijakan diskriminatif yang telah menafikan hakhak sipil dan politik mereka. 2. Pola Kebijakan Diskriminatif 136. Ada tiga pola kebijakan diskriminatif yang selama ini diderita oleh kelompok-kelompok etnis tersebut, khususnya menyangkut penafian kepercayaan lokal mereka oleh negara. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kebijakan diskriminatif yang dilakukan negara bersifat sistemik, menyeluruh dan konsisten diterapkan sejak zaman Orde Lama sampai sekarang, yaitu ; 1. Pola pemilahan antara agama yang diakui dengan yang tidak diakui. 5 Sesuai dengan yuridiksi CERD, maka fokus perhatian di sini hanya diarahkan pada kepercayaan lokal yang bertautan erat dengan identitas etnis atau sub-etnis tertentu. 28 2. Pola penafian hak-hak sipil. 3. Pola dimasukannya kepercayaan lokal sebagai bagian dari agama yang diakui negara. 2.1. Pola Pemilahan Antara Agama yang Diakui Dengan yang tidak Diakui Negara. 137. Sekalipun selama ini tidak ada perundang-undangan atau peraturan tentang pemilahan antara agama yang "diakui" dengan yang "tidak diakui" negara, akan tetapi pada praktiknya apa yang disebut sebagai “agama” hanyalah enam agama yang disebut Penetapan Presiden No 1/PNPS/1965 (kini UU No 1/PNPS/1965). Dua catatan penting. Pertama, penyebutan enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) hanya ada dalam bagian penjelasan pasal 1, bukan dalam teks PNPS sendiri, yakni ketika menjelaskan tentang “agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia”. Kedua, Khonghucu sempat “dikeluarkan” dari daftar tersebut sebagai akibat Instruksi Presiden No. 14/1967 yang melarang praktik-praktik Agama, Kepercayaan dan Tradisi Cina dalam ranah publik. Baru setelah keluarnya Keputusan Presiden No. 6/2000 yang mencabut Instruksi Presiden sebelumnya umat Khonghucu dapat menarik nafas lega. 138. Munculnya UU No. 1/PNPS/1965 perlu ditelisik sungguh-sungguh karena berakibat sangat fatal terhadap kelompok-kelompok kepercayaan yang berbasiskan etnis atau subetnis. Seperti dapat dibaca dalam penjelasan resmi PNPS 1965, penetapan Presiden Soekarno itu lahir dari situasi saat itu di mana “hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebathinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama.” Situasi ini dinilai “telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama” (Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1/1965, I.2). Dengan kata lain, PNPS 1965 lahir untuk melindungi agama-agama (yang diakui negara) dari aliranaliran kebatinan/kepercayaan. 139. Mengapa langkah ini diambil? Dalam studinya yang sudah klasik, Niels Mulder 6 menyebut salah satu alasan yang melatarinya adalah bertumbuh suburnya kelompokkelompok kebatinan pada masa itu. Depag melaporkan bahwa pada tahun 1953 ada lebih dari 360 kelompok kebatinan di seluruh Jawa. Kelompok-kelompok ini memainkan peran menentukan sehingga pada Pemilu 1955 partai-partai Islam gagal memperoleh suara mayoritas, dan hanya mendapat 42 persen suara. Pada tahun yang sama BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) didirikan di bawah kepemimpinan Mr. Wongsonegoro. Tahun 1957, BKKI mendesak Soekarno agar mengakui secara formal bahwa “kebatinan” setara dengan “agama”. 140. Latar belakang inilah yang mendorong Depag, tahun 1961, secara resmi merumuskan apa yang disebut “agama” dengan lima unsurnya, yakni Tuhan, Nabi, Kitab Suci, Umat, dan pengakuan internasional. Maka, dengan langkah itu, kelompok-kelompok yang meyakini kepercayaan lokal digolongkan sebagai "belum beragama". Atau, lebih lugas lagi, "belum memeluk agama yang diakui oleh Negara". Untuk mengawasi kelompokkelompok ini, lewat SK No. 167/PROMOSI/1954 dibentuklah Panitia Interdepartemental Kepercayaan-kepercayaan di dalam Masyarakat yang, nantinya, pada tahun 1960 menjadi Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di 6 Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change, Singapore: Singapore University Press, 1978. 29 bawah Kejaksaan Agung. Kemudian, lewat Surat Edaran Departemen Kejaksaan Biro PAKEM Pusat No. 34/Pakem/S.E./61 tanggal 7 April 1961, lembaga PAKEM didirikan di setiap provinsi dan kabupaten. Di antara tugas PAKEM adalah mengikuti, memerhatikan, mengawasi gerak-gerik serta perkembangan dari semua gerakan agama, semua aliran kepercayaan / kebatinan, memeriksa / mempelajari buku-buku, brosurbrosur keagamaan/aliran kepercayaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 7 141. PAKEM sampai sekarang masih berdiri dan melakukan fungsinya. Bahkan sebagian tugas utamanya dicantumkan dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan. Dalam UU itu, menurut pasal 30:3 kejaksaan juga bertugas dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dengan, antara lain, melakukan “(c.) pengawasan peredaran barang cetakan; (d.) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e.) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama”. Pengendalian oleh negara yang efektif ini membuat banyak sekali aliran kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai kelompok etnis atau sub-etnis di Indonesia harus menemui ajalnya. Seperti dilaporkan Kompas (5 Agustus 1993), “Kahumas Kejaksaan Agung Soeparman, S.H., mengatakan sejak tahun 1949 hingga tahun 1992, telah terdapat 517 aliran kepercayaan yang ‘mati’ di seluruh Indonesia.” 142. Kebijakan pemilahan ini secara konsisten dilakukan oleh rezim Orde Baru dengan landasan hukum yang sangat kuat. Pada tahun 1978 MPR menetapkan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam TAP tersebut ditegaskan bahwa “Kepercayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama”. Berangkat dari ketetapan ini, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi No 4 dan 14 tahun 1978 yang menggariskan kebijakan inti mengenai aliran kepercayaan. Kedua hal ini disusul oleh Surat Menteri Agama No. B/5943/1978 tertanggal 3 Juli 1978 yang ditujukan kepada Gurbernur Jawa Timur. Surat ini menegaskan bahwa, karena aliran kepercayaan bukanlah agama (tetapi digolongkan oleh Menteri Agama sebagai “kebudayaan”), maka kepada mereka tidak ada tatacara sumpah, tatacara perkawinan dan sebagainya menurut aliran kepercayaan. Itu berarti, dalam soal perkawinan “hanya ada menurut agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 2.2. Penafian Hak-hak Sipil 143. Jelas kebijakan pemilahan di atas berakibat sangat fatal bagi kelompok-kelompok kepercayaan lokal yang dianut oleh berbagai etnis atau sub-etnis di Indonesia. Apalagi kolom “agama” merupakan kewajiban yang harus diisi mulai sejak Kartu Keluarga, KTP, sampai akta-akta sipil lain yang penting. Termasuk dalam UU No. 23/2006 mengenai Administrasi Kependudukan yang baru disahkan tanggal 8 Desember 2006 (pada rezim “reformasi”) pun masih mewajibkannya. UU ini menarik karena, untuk pertamakalinya, dalam dokumen resmi negara dipakai istilah “agama yang belum diakui negara” untuk merujuk pada kelompok-kelompok kepercayaan di luar enam agama yang diakui. Padahal kelompok-kelompok ini sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Mereka mencakup bukan hanya kepercayaan lokal, tetapi juga kelompok “agama berbasiskan etnis” seperti Sikh yang, dalam dunia internasional, diakui sebagai “agama”. 144. Pada tataran praktik biasanya kolom agama di KTP kelompok kepercayaan harus 7 Ahmad Baso, Islam Pascakolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme, Bandung: Mizan, 2005, h. 241. 30 dikosongkan atau ditandai dengan “--“. Ini, sudah tentu, menimbulkan kerawanan tersendiri karena, jangan-jangan, mereka dituduh “ateis” yang tidak punya tempat di negara ini. Banyak dari mereka yang, karena kekhawatiran ini terpaksa mengisi kolom agama dengan salah satu agama yang diakui negara, sekalipun mereka tidak mengimani atau mempraktikkan agama tersebut. 8 Yang lebih menyakitkan bagi kelompokkelompok ini, perkawinan mereka yang berdasarkan adat kepercayaan juga tidak diakui negara. Padahal dalam pasal 2:1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Akan tetapi, seperti dijelaskan Surat Meteri Agama No. B/5943/1978 tertanggal 3 Juli 1978 kepada Gurbernur Jawa Timur yang sudah dirujuk di atas, dalam soal perkawinan hanya ada tatacara agama. Akibatnya, pihak Catatan Sipil tidak mau mencatatkan perkawinan mereka. Perlakuan diskriminatif ini mendorong banyak kelompok kepercayaan untuk mengadu pada Komnas HAM. Laporan Gatra (4 Maret 2006, h. 28 – 31) menyebut 110 pasangan suami-istri di Cilacap, dan 30 pasangan lagi di Kebumen, Jawa Tengah, yang pernah melakukan upaya itu. Sudah tentu, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil saja dari berbagai kelompok kepercayaan lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. 145. Dengan tidak diakuinya perkawinan kelompok kepercayaan lokal, maka status anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi runyam. Umumnya, seperti dituturkan oleh Sdri. Dewi Kanti dari kelompok penghayat Sunda Wiwitan, Cigugur, ada formulir yang harus diisi agar anak hasil perkawinan kelompok kepercayaan mendapat “pengakuan”. Yang menarik, dalam formulir tersebut hanya disebutkan bahwa sang anak dilahirkan oleh seorang perempuan pada tanggal tertentu, dan tidak menyebut nama suami atau status pernikahannya. 146. Komunitas Sedulur Sikep merupakan bagian dari etnik Jawa yang tersebar di Pati, Blora, Kudus, dan Bojonegoro. Keyakinan mereka yang tidak ternasuk 6 agama resmi Negara berimplikasi pada beberapa perlakuan diskriminatif, di antaranya: a) dalam KTP mereka tidak dicantumkan identitas keyakinan; b) dibujuk untuk melakukan nikah massal menurut agama Islam; c) pelarangan pemakaman jenazah di pemakaman umum. 2.3. Karena Legalitas, Dipaksa Mengganti Kepercaannya dengan Agama Resmi 147. Akibat kerumitan-kerumitan di atas, banyak orang dari kelompok kepercayaan mengambil jalan pintas. Mereka mengisi kolom agama dalam akta sipil dengan salah satu agama yang diakui negara, atau menikah berdasarkan agama tertentu. Langkahlangkah ini diambil hanya untuk menghindari berbagai kesulitan yang harus mereka hadapi saat berhadapan dengan birokrasi negara. 148. Sementara itu, dari pihak negara juga mengalami kesulitan di dalam menangani masalah kepercayaan lokal yang beraneka ragam bentuk keimanan maupun praktik ritualnya. Sering kali, dalam soal ini, negara juga mengambil jalan pintas dengan menggolongkan banyak kepercayaan lokal ke dalam salah satu agama yang sudah diakui. Hal ini, misalnya, tercermin pada kebijakan Depag (Departemen Agama) terhadap masyarakat Tolotang di Sulawesi Selatan (Sulsel). Komunitas ini, dengan semena-mena, diletakkan oleh Depag di bawah pengawasan Dirjen Bimas Hindu Buddha berdasarkan SK No 2 dan 6 tahun 1966 yang “menunjuk Sdr. Makkatungeng untuk atas nama Direktur Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Hindu dan 8 Lebih jauh lihat laporan Forum Keadilan No. 50, 16 April 2006, h. 18 – 19, dan Majalah Playboy Edisi Indonesia, April 2006, h. 72 – 79. 31 Buddha melakukan pembinaan serta penyuluhan terhadap umat Hindu Tolotang.” Maka, akibatnya, masyarakat adat Tolotang diwajibkan beribadah di Pura dengan ritual seturut agama Hindu Bali yang sama sekali asing bagi mereka. 9 149. Pengalaman pahit komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan hanya contoh dari perlakuan yang hampir sama pada banyak komunitas penghayat kepercayaan lokal di berbagai tempat lain. Misalnya, komunitas Dayak yang menganut “kepercayaan lokal Kaharingan” juga dengan semena-mena dimasukkan ke dalam agama Hindu sejak tahun 1980. Ini juga dialami oleh komunitas Sikh di Medan yang mayoritas penganutnya dari etnis keturunan India, maupun komunitas-komunitas lokal lainnya. F. IDPs dalam Peristiwa Kekerasan Etnis di Kalimantan 1. Idps Etnis Madura : Konflik di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah 150. ICERD memberikan perhatian khusus terhadap IDPs seperti yang tercermin dalam Rekomendasi Umum No 22: art 5 and Refugees and Displaced Persons. 151. Dalam konteks Indonesia, salah satu persoalan IDPs yang berkaitan dengan ICERD terjadi dalam kasus kerusuhan antara etnis Dayak dengan Madura di Kalimantan Barat (Kasus Sambas/1998-1999) dan Kalimantan Tengah (kasus Sampit/2001). 152. Nasib masyarakat Madura yang menjadi IDPs akibat peristiwa Sambas sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Sekitar 68.000 IDPs sudah menempati relokasi yang berada di beberapa wilayah di Kab. Pontianak. Tetapi, masih terdapat upaya penolakan dari pejabat publik terhadap kembalinya masyarakat Madura ke tempat tinggalnya di Sambas. Bahkan beberapa pihak NGO yang mencoba memfasilitasi terdorongnya usaha-usaha untuk membangun rekonsiliasi di tingkat basis malah dituduh oleh pejabat publik dan tokoh masyarakat dengan tuduhan ‘ingin mengembalikan orang Madura ke Sambas’. Persoalan lain yang dialami IDPs adalah persoalan harta benda mereka yang tersebar diseluruh Kab. Sambas kurang dan bahkan tidak mendapat jaminan perlindungan Hukum dari pemerintah. 153. Di tempat relokasi yang tersebar di Kab. Pontianak seperti di Pulau Nyamuk dan Parit Haji Ali, IDPs juga menghadapi banyak permasalahan, di antaranya: a) lokasinya tidak memadai atau tidak cocok untuk lahan pertanian sehingga para IDPs kesulitan untuk membangun kehidupan baru sebagai petani; b) lokasinya merupakan lahan sengketa hukum sehingga menimbulkan sengketa pertanahan dengan masyarakat sekitar lokasi tersebut. Hal ini melanggar rekomendasi umum no 22 poin 2 huruf c yang berkaitan dengan pasal 5 konvensi. 154. IDPs yang berada direlokasi sebagian besar adalah kaum perempuan. Ditengarai persoalan kesehatan dasar tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini melanggar rekomendasi umum no 25. 155. Sampai hari ini Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat tidak mempunyai kebijakan yang memuat skenario truth seeking dan rekonsiliasi yang kondusif dalam membangun sebuah perdamaian di Kalimantan Barat. Ini dapat dilihat dari seringnya terjadi pergesekan sosial di dalam masyarakat yang berakhir dengan kekerasan etnis antar masyarakat. Hal ini melanggar pasal 7 konvensi. 9 Ahmad Baso, op.cit., h. 246 – 247. 32 156. Terjadi pembiaran oleh negara terhadap tindakan kekerasan etnis tanpa ada solusi hukum yang jelas sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya tindakan diskriminasi rasial. Diduga, pembiaran ini menjadi salah satu pemicu timbulnya kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Hal ini melanggar Pasal 5 ayat b. 157. Kasus yang sama terjadi pada IDPs akibat konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah pada tanggal 18 Februari 2001. Peristiwa kekerasan akibat konflik etnis ini berlangsung selama sekitar 10 hari. Selama periode konflik tersebut jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak: sekitar 341 dari pihak Madura dan sekitar 16 orang dari pihak Dayak. Selain itu ratusan rumah dibakar atau dirusak. Data itu didapat dari Polres Kotawaringin Timur. Pasca konflik juga ditandai oleh eksodus para pengungsi (IDPs) berjumlah hampir 30 ribu –dari pihak Madura- dari Kalimantan Tengah ke Pulau Jawa. Sebagian besar dari pengungsi itu hingga saat ini belum juga berani kembali ke tempat tinggal semulanya karena masih merasa tidak terjamin keamanannya. 2. Penutup 157. Tidak terpenuhinya hak-hak Idps korban konflik yang terjadi di Kalimantan dikarenakan pembiaran / tidak adanya kemauan dari aparat pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan persoalan ini. Pada kenyataannya relokasi paska konflik yang dilakukan pemerintah justru menjadi pemisahan antar etnis yang permanen. Sampai saat ini Idps tidak bisa kembali ke tempat tinggalnya secara aman. G. Diskriminasi Rasial di Papua 1. Gambaran Umum 158. Tanah Papua luasnya mencapai 422.000 Km hampir mencapai seperempat luas wilayah daratan Indonesia (sekitar 1,9 Km2) dan kaya sumber daya alam, seperti minyak, gas, emas, tembaga, kayu, uranium dan ikan.. 159. Penduduk Papua tergolong ras Negroit Melanesia berkulit hitam dan berambut keriting. Etnik Papua terbagi lagi dalam sub-sub budaya, masing-masing yang bahasanya mencakup 253 bahasa suku. 160. Dahulu pulau Papua adalah sebuah daerah koloni dari kerajaan Belanda, yang kemudian diserahkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui transfer administrasi dari kerajaan Belanda kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, dan dipertegas lagi dalam sebuah jajak pendapat yang diprakarsai oleh PBB 1969 yang oleh rakyat Papua dianggap tidak adil dan tidak demokratis. 161. Catatan sejarah diskriminasi rasial di Papua sudah berlangsung lama bahkan sebelum Papua masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah Belanda dan Jepang telah mempraktekan diskriminasi kepada masyarakat Papua. Sebagai contohnya adalah Belanda membatasi orang Papua untuk mengenyam pendidikan. Belanda hanya memberikan kesempatan kepada rakyat Papua yang orang tuanya memegang peranan penting atau yang membantu pemerintah kolonial Belanda. Setelah masuknya Papua kedalam NKRI, diskriminasi rasial masih di praktekan hingga saat ini. 162. Menanggapi situasi yang terjadi di Papua, Rodolfo Stevenhagen, Pelapor (Rapporteur) Khusus PBB untuk Indigenous People, dalam laporannya di sidang ke-61 tahun 2005 mengatakan, “Masyarakat adat Papua menderita karena diskriminasi yang meluas yang 33 mencegah mereka, dalam hal tertentu, untuk memperoleh akses ke dalam institusi-intitusi di masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan sendiri, seperti dalam hal pendidikan, perawatan, kesehatan, kesamaan pendapatan/penghasilan, pandangan masyarakat umum tentang perempuan, dan harga diri, 10 walaupun sudah ada Dewan Adat Papua dan Majelis Rakyat Papua. 2. Diskriminasi yang terjadi di Papua bisa dilihat dalam 2 (dua) hal; 2.1. Kebijakan Pembangunan 163. Kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat yang memprogramkan pembangunan untuk Indonesia di wilayah Timur ternasuk Papua, merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat umum tanpa ada program khusus yang berbasis penghargaan terhadap nilai – nilai lokal. Bahkan dalam konteks Papua pembangunan masih diliputi bias rasial dan stereotipe terhadap masyarakat Papua. Dalam konteks inilah kebijakan pembanguann menjadi sumber pelanggaran terhadap ICERD. 2.1.1. Tidak ada affirmatif action di bidang Ekonomi. 164. Tidak ada afirmatif action dalam kebijakan ekonomi sehingga mayarakat asli Papua sangat sulit bersaing dengan orang dari luar Papua. yang memiliki pengalaman dan naluri bisnis yang kuat. Faktor lain adalah Orang Papua sendiri masih dalam budaya transisi dari budaya meramu harus diperhadapkan pada sistem ekonomi modern. Selain itu pemerintah juga memberi peluang yang sangat kecil bagi orang asli Papua untuk mengembangkan ekonominya. Perbankan juga sangat sedikit memberikan Kredit bagi orang Papua untuk meningkatkan ekonominya. Di pasar-pasar orang asli Papua berjualan di trotoar jalan, mereka tidak menikmati faslitas perumahan pasar yang dikuasai oleh non Papua. 165. Belum adanya tindakan Affirmatif action ini menjadikan masyarakat Papua termarjinalkan dan kondisi inilah yang membuat masyarakat papua sangat rentan mendapat perlakukan yang diskriminatif. 2.1.2. Stereotip dan Diskriminasi Pekerjaan 166. Masyarakat Papua sering distereotipekan kurang terpelajar, berpenampilan kurang menarik, dan malas. Sehingga sangat menyulitkan mereka untuk mendapatkan perkerjaan di bidangbidang tertentu. Banyak supermarket di Papua yang tidak mempekerjakan orang Papua. Contoh lain adalah di perusahaan swasta seperti Freeport dan British Petroleum. Di Freeport misalnya karyawan asli Papua tidak pernah dipromosikan untuk menduduki tempat-tempat strategis walaupun mereka juga memiliki kemampuan dan kualifikasi yang tidak jauh berbeda dengan yang lain. Akibat dari tindakan diskriminasi ini, karyawan Papua membentuk wadah penampung aspirasi dengan nama “Tongoi Papua.” Mereka kemudian melakukan demo besar-besaran bulan April lalu menuntut pemberdayaan karyawan Papua dan peningkatan upah kerja. Sedangkan di perusahaan British Petroleum, masyarakat setempat dipekerjakan sebagai tenaga security perusahaan. 10 (Hermien Rumrar dan DR. Theodor Rathgeber., “Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua Barat”. Halaman 148) @2007, 34 167. Bentuk diskriminasi rasial lain adalah sebutan rasialis kepada masyarakat Papua paska penyerangan Markas Polisi Sektor Abepura tahun 2000 oleh kelompok tidak dikenal yang menyebabkan aparat polisi melakukan penyisiran. Dalam laporan KPP Komnas HAM untuk kasus Abepura Berdarah ditemukan ungkapan rasialis terhadap para tahanan pada saat dilakukan interogasi. Seperti, “kamu orang Papua hanya tau makan Babi, makanya otaknya sama seperti babi”. “Kamu harus makan daging biri-biri biar pintar sama dengan orang Makasar, Jawa dan Jakarta, “Kamu orang Papua rambut keriting, hitam dan lawo-lawo ( tidak tahu apa-apa / goblok). 2.2. Masyarakat Adat 2.2.1. Perampasan Tanah 168. Perampasan hak-hak masyarakat adat sering tejadi di Papua. Tanah-tanah adat dirampas untuk pembangunan transmigrasi, basis militer dan untuk kepentingan investor tanpa memberikan ganti rugi yang layak. Perampasan tanah-tanah adat ini tidak saja merusak ekonomi masyarakat yang mana mereka mengantungkan hidup dari tanah tersebut tapi juga merusak nila-nilai tradisi yang di lama dipegang. Masyarakat Papua selalu menganggap tanah sebagai “IBU’ yang mana tanah itu memberikan perlindungan / memberikan makan dan menganggap “Sungai” sebagai “air susu” yang mengalirkan air kehidupan. Ketika masyarakat melawan, ingin mempertahankan hak dan nilai tradisi mereka, maka dituduh menghambat pembangunan dan menjadi bagian dari separatis. Alasan tersebut dipakai sebagai pembenaran untuk menindak keras atau menciptkan mata rantai kekerasan baru. Contoh kasus adalah perlawan suku Amungme terhadap kehadiran PT Freeport, yang merusak tanah dan lingkungan serta pencemaran sungai. Banyak orang terbunuh karena mencoba mempertahankan hak-hak SDA mereka seperti kasus di daerah-daerah pertambangan seperti Hoya, Agandi, dll. Kasus ini telah dilaporkan oleh Gereja dan diselidiki oleh Komnas HAM tahun 1995. 2.2.2. Masalah Transmigrasi 169. Papua merupakan daerah tujuan utama transmigrasi. Dengan adanya program transmigrasi, lahan-lahan subur dan tanah hak ulayat adat di ambil. Sebagai akibatnya masyarakat adat / penduduk asli terpaksa tergeser. Banyak masyarakat terpaksa memilih tinggal di pegunungan. Implikasi lainnya adalah terjadi pengelembungan dalam perbedaan populasi masyarakt asli dan pendatang. Contoh kasus adalah tahun 1970 di Arso salah satu distrik pusat transmigrasi memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1000 orang. Namun setelah tahun 2000 jumlah penduduk di Arso menjadi 20.000 orang menjadikan penduduk asli sebagai minoritas. Selain itu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perumahan di daerah-daerah transmigran lebih lengkap daripada di kampung-kampung orang asli Papua. Misalnya di daerah Arso kita bisa melihat bahwa di desa-desa transmigran ada SMA dan SMP serta Puskesamas dari pemerintah, sedangkan di desa-desa orang asli Papua pemerintah tidak membangun pelayananan tersebut tetapi Gereja yang bertanggungjawab. 2 2.2.3. Stigmatisasi OPM 2 Kristina Neubauer 2002: Die soziokulturellen Folgen des Indonesischen Transmigrations programmes fuer die lokale Bevoelkerung Papuas am Beispiel der Region Arso. 35 170. Salah satu bentuk diskiriminasi yang dihadapi masyarakat Papua adalah stigmatisasi OPM. Pemerintah dan aparatus Negara membangun stigma bahwa orang Papua, khususnya masyarakat adat yang terdapat di pinggiran kota dan di dalam hutan diidentikkan dengan OPM dan pemberontak. Sehingga ada justifikasi membasmi mereka. Contoh kasus adalah rekayasa pembobolan gudang senjata di Wamena tahun 2003 yang di lakukan kelompok tidak dikenal. Aparat menuduh bahwa yang melalukan pembobolan itu adalah OPM. Aparat kemudian melakukan penyisiran dan menangkap dan melakukan pembunuhan. Banyak masyarakat yang tidak tahu menahu dan sebagain besar adalah warga sipil / petani menjadi korban dan dituduh kaki tangan OPM. Kasus ini dipakai sebagai justifikasi dibukanya satu batalyon baru di Wamena. Kasus hangat lain adalah pengungsian sekitar 10.000 masyarakat sipil di distrik Yamo Kabupaten Puncak Jaya pasca pembunuhan dua aparat TNI AD yang di lakukan kelompok milisi. Contoh kasus lain adalah kasus Mariedi kabupaten Bintuni. Masyarakat menuntut ganti rugi yang layak atas kayu-kayu yang di ambil oleh PT. DJayanti Group tetapi kemudian Brimob sebagai penjaga perusahaan menembak mati 5 warga karena dituduh terlibat gerakan OPM. Contoh lain adalah operasi ketupat dimana 11 masyarakat sipil dituduh sebagai anggota TPN/OPM di tangkap tanggal 22 November 2003. 171. Selain itu Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM). Yang menjadi target dari operasi Militer adalah rakyat Papua yang dituduh membangkang terhadap pemerintah Indonesia. Operasi ini hampir mencakup seluruh wilayah tanah Papua. Banyak rakyat Papua yang terbunuh selama diberlakukanya DOM karena dalam operasi militer tidak memakai sistim tebang pilih, yang ada adalah sistem sapu rata. Fakta kasus seperti yang terjadi di Wasior kabupaten Manokwari dimana aparat tidak membedakan orang yang bersalah atau tidak, namun hanya bertindak dengan melihat dari warna kulit dan rambut. BAB IV KESIMPULAN 172. Di Indonesia diskriminasi rasial masih terjadi, walupun ada kebijakan hukum yang menunjukkan perubahan yang baik. Hal ini disebabkan karena perubahan kebijakan hukum yang ada tidak komperhensif dan bahkan lahirnya kebijakan hukum yang baik tersebut juga disertai lahirnya hukum baru yang masih tetap memberlakukan diskriminasi. Dalam konteks ini terjadilah konflik hukum, bahkan konflik hukum ini terjadi di dalam konstitusi, pasal satu dengan pasal yang lainnya saling kontradiksi. 173. Selain terjadi kontradiksi di dalam kebijakan hukum yang mengatur diskriminasi rasial, diskriminasi yang terjadi juga diakibatkan oleh kelakuan aparat negara yang dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani setiap individu maupun warga negara tetap menerapkan kebijakan/perlakuan diskrinimasi. Perilaku aparatur negara ini mencerminkan bagaimana fenomena diskriminasi telah terjadi secara sistematis dan meluas. 174. Dalam konteks ini tidak ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya pembiaran atas fakta tersebut namun juga dapat dirasakan keterlibatan aktif para aparatur negara itu. 175. Diskriminasi rasial di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk. Korban yang paling banyak adalah etnis Tionghoa dan Masyarakat Suku Bangsa/Etnik terutama berkaitan dengan identitas kepercayaan dan keyakinan mereka. 36 176. Soal lain yang serius terjadi di Indonesia dalam implementasi ICERD ini adalah kebijakan Impunity terhadap penyelesaian berbagai kasus diskriminasi rasial, seperti kasus Mei 98, kasus Konflik antara masyarakat Dayak dengan masyarakat Madura di sambas dan Sampit, Kalimantan , maupun kasus lain. Pemerintah tidak menunjukkan usaha yang efektif untuk menyelesaikan berbagai kasus tersebut dan usaha efektif dalam memerangi impunity. 177. Persoalan IDPs yang berbasis kerusuhan etnik juga tidak diselesaikan, hak – hak pengungsi banyak dilanggar dan bahkan ditengarai persoalan IDPs yang berlarut – larut sampai saat ini karena masih adanya sudut pandang dan kebijakan yang bias rasial. 178. Begitu juga hal nya belum ada kebijakan hukum yang ditujukan untuk pemulihan korban diskriminasi secara efektif. Jika disebutkan bahwa telah ada Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tentang Penggantian dan Pemulihan bagi Korban Pelanggaran Berat HAM, itu tidak akan menjangkau korban diskriminasi rasial. Dan pada kenyataan implementasinya, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2002 tersebut tidak dapat di implementasikan walaupun untuk korban pelanggaran berat HAM. 179. Fakla lain pelanggaran ICERD adalah banyaknya pelanggaran terhadap Indigenous People dalam berbangai bentuknya, mulai dari perampasan tanah dan sumberdaya alam sampai penghancuran nilai – nilai lokalitasnya. 180. Dalam konteks Papua pelanggaran terhadap ICERD juga terjadi, bahkan problem mendasar pelanggaran tersebut sampai saat ini tidak diselesaikan. 181. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa diskriminasi rasial di Indonesia masih terjadi dan tidak ada penyelesaian efektif baik melalui kebijakan pembangunan, kebijakan hukum, maupun melalui pengadilan. BAB V PENUTUP 182. Pemaparan di atas membuktikan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dijalankan sampai sekarang mengakibatkan pelanggran terhadap ICERD dan terampasnya berbagai hak asasi manusia yang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. 183. Sumber dari berbagai problematika pelanggran ICERD seperti dipaparkan diatas adalah kebijakan pemerintah yang diambil dan pembiaran terhadap pelanggran tersebut. Apalagi UUD 45 ( kontitusi ) masih memiliki pasal yang melegetimasi pelanggaran terhadap ICERD. BAB VI REKOMENDASI 184. Bagi Pemerintah Indonesia; 1. Segera melakukan perubahan terhadap UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan. 37 2. Untuk Presiden segera memerintahkan Jaksa Agung untuk menggelar pengadilan peristiwa Mei 1998 dan konflik etnis di Sampit, Kalimantan Tengah, dan Sambas, Kalimantan Barat. 3. Segera menghapuskan kebijakan pengutamaan agama tertentu / agama resmi. 4. Membubarkan Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM). 5. Melakukan semua tindakan efektif untuk menjamin adanya pemberantasan diskriminasi rasial, terutama yang dilakukan oleh aparatur negara dan segera membuat aturan hukum yang memberikan sanksi terhadap tindakan diskriminatif tersebut. 6. Membuat kebijakan yang menjamin pemulihan korban. 7. Membentuk Desk khusus penanggung jawab pemberantasan praktek diskriminasi. 8. Mendesak pemerintah Indonesia untuk konsekuen mengimplementasikan ICERD. 9. Membuat kebijakan yang menjamin perlindungan hak-hak indigeneous people dan menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan masyarakat adat di Indonesia. 185. Bagi Komite; 1. Melakukan perubahan kebijakan dan hukum yang diskriminatif. 2. Mengambil langkah efektif dalam memerangi impunitas. 3. Merekomendasikan menggelar penyelesaian kasus Mei 1998 dan konflik etnis di Sampit Kalimantan Tengah, dan Sambas Kalimantan Barat melalui pengadilan yang kredibel dan kompeten, yaitu Pengadilan HAM. 4. Memberikan technical assistent. 5. Mengimplementasikan ICERD secara efektif dan konsekuen. LAMPIRAN : 1. Tabel Kebijakan yang Diskriminatif yang harus di cabut 2. Surat Komnas HAM tentang Temuan Pelanggaran HAM pada Suku Anak Dalam (Jambi) 38