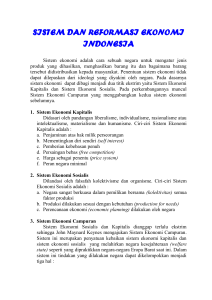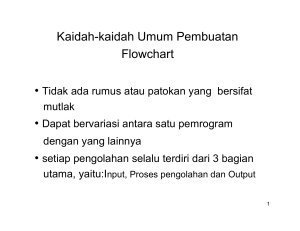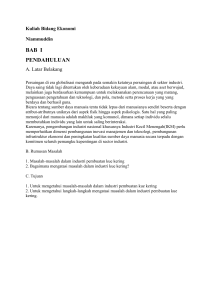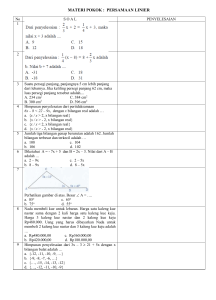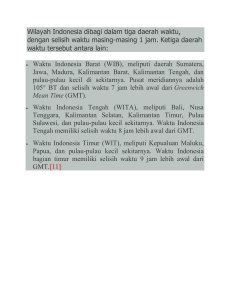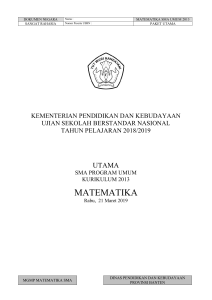Ekonomi Kerakyatan versus Ekonomi Neoliberal
advertisement
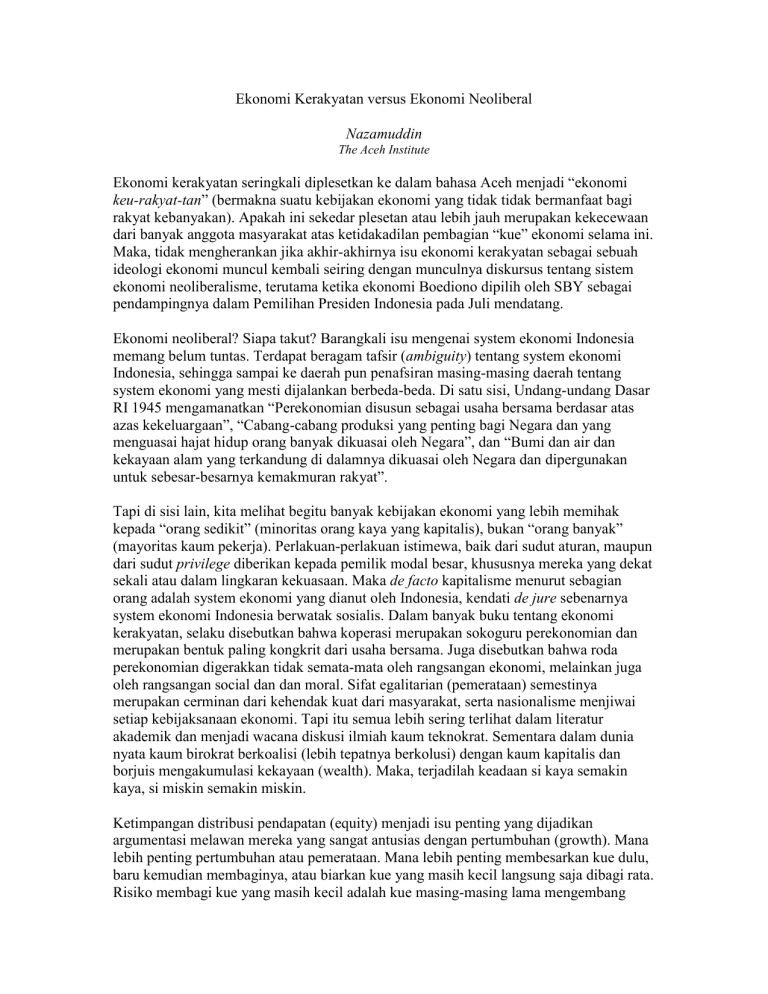
Ekonomi Kerakyatan versus Ekonomi Neoliberal Nazamuddin The Aceh Institute Ekonomi kerakyatan seringkali diplesetkan ke dalam bahasa Aceh menjadi “ekonomi keu-rakyat-tan” (bermakna suatu kebijakan ekonomi yang tidak tidak bermanfaat bagi rakyat kebanyakan). Apakah ini sekedar plesetan atau lebih jauh merupakan kekecewaan dari banyak anggota masyarakat atas ketidakadilan pembagian “kue” ekonomi selama ini. Maka, tidak mengherankan jika akhir-akhirnya isu ekonomi kerakyatan sebagai sebuah ideologi ekonomi muncul kembali seiring dengan munculnya diskursus tentang sistem ekonomi neoliberalisme, terutama ketika ekonomi Boediono dipilih oleh SBY sebagai pendampingnya dalam Pemilihan Presiden Indonesia pada Juli mendatang. Ekonomi neoliberal? Siapa takut? Barangkali isu mengenai system ekonomi Indonesia memang belum tuntas. Terdapat beragam tafsir (ambiguity) tentang system ekonomi Indonesia, sehingga sampai ke daerah pun penafsiran masing-masing daerah tentang system ekonomi yang mesti dijalankan berbeda-beda. Di satu sisi, Undang-undang Dasar RI 1945 mengamanatkan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”, dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tapi di sisi lain, kita melihat begitu banyak kebijakan ekonomi yang lebih memihak kepada “orang sedikit” (minoritas orang kaya yang kapitalis), bukan “orang banyak” (mayoritas kaum pekerja). Perlakuan-perlakuan istimewa, baik dari sudut aturan, maupun dari sudut privilege diberikan kepada pemilik modal besar, khususnya mereka yang dekat sekali atau dalam lingkaran kekuasaan. Maka de facto kapitalisme menurut sebagian orang adalah system ekonomi yang dianut oleh Indonesia, kendati de jure sebenarnya system ekonomi Indonesia berwatak sosialis. Dalam banyak buku tentang ekonomi kerakyatan, selaku disebutkan bahwa koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. Juga disebutkan bahwa roda perekonomian digerakkan tidak semata-mata oleh rangsangan ekonomi, melainkan juga oleh rangsangan social dan dan moral. Sifat egalitarian (pemerataan) semestinya merupakan cerminan dari kehendak kuat dari masyarakat, serta nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi. Tapi itu semua lebih sering terlihat dalam literatur akademik dan menjadi wacana diskusi ilmiah kaum teknokrat. Sementara dalam dunia nyata kaum birokrat berkoalisi (lebih tepatnya berkolusi) dengan kaum kapitalis dan borjuis mengakumulasi kekayaan (wealth). Maka, terjadilah keadaan si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin. Ketimpangan distribusi pendapatan (equity) menjadi isu penting yang dijadikan argumentasi melawan mereka yang sangat antusias dengan pertumbuhan (growth). Mana lebih penting pertumbuhan atau pemerataan. Mana lebih penting membesarkan kue dulu, baru kemudian membaginya, atau biarkan kue yang masih kecil langsung saja dibagi rata. Risiko membagi kue yang masih kecil adalah kue masing-masing lama mengembang menjadi besar. Bagi sebagian orang, kue perlu diperbesar dulu. Maknanya, kejarlah pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, tentu tak dapat dihindari kebijakan ekonomi yang kurang egaliter, seraya pada waktu yang bersamaan meluncurkan program-program penyejuk hati sejenis BLT, Askeskin, Jamkesmas, dan sejenisnya. Tidak lupa juga program beasiswa pada berbagai jenjang pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Tidak lupa juga proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak, walaupun mungkin tidak segera mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Kembali kepada sistem ekonomi. Indonesia sebagaimana banyak negara lain di dunia dewasa ini menganut sistem ekonomi campuran (mixed economy). Sebuah sistem ekonomi campuran adalah gabungan kapitalisme dan sosialisme di mana kepemilikan dan kontrol sumber-sumber ekonomi sebagian dikuasai oleh swasta dan sebagian lagi oleh pemerintah. Ada swasta yang berkembang bebas, tapi ada juga BUMN dan BUMD. Hanya saja masalahnya adalah ada swasta yang dimanjakan, ada swasta yang dianaktirikan. Ada yang terlalu besar, ada usaha kecil dan menengah ”bak kerakap tumbuh di batu”, hidup segan, mati tertunda dulu. Lain pula halnya BUMN, sering menjadi sapi perahan si penguasa dan manajemen yang tidak baik. Lain lagi BUMD, setiap tahun mendapat suntikan dana dari anggaran daerah, tapi setiap tahun pula mengalami kerugian. Kemana dana-dana itu? Bagi rakyat yang penting ada peluang usaha, ada peluang kerja, ada infrastruktur yang baik, dan ada keadilan ekonomi. Barangkali tidak benar juga kalau ada yang mengatakan banyak usaha kecil dan menengah tidak berkembang karena kurang modal. Mungkin ya sampai batas tertentu, tapi kelemahan dalam kewirausahaan (enterpreneurship) dan kecakapan bisnis adalah juga faktor penting. Tapi yang terakhir ini jarang dilakukan. Lebih sering adalah kebijakan pemerintah menyediakan kredit bersubsidi yang di banyak negara umumnya kebijakan demikian lebih sering gagal. Sungguh mengherankan jika kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang di Aceh, misalnya. Nama programnya sering langsung mendapat dukungan politis dari berbagai pihak. Tapi kenyataannya, yang terjadi kolusi dan koalisi jahat menguras uang rakyat. Contoh, dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) oleh pemerintah daerah Aceh. Dari sejumlah lebih dari Rp. 47 milyar yang diluncurkan sejak 2001 hingga 2008, rata-rata kredit macet (Non-Performing Loan) mencapai 92,4 persen. Artinya, dana yang semestinya bergulir dari satu orang ke orang lain yang membutuhkan, ternyata hanya kurang dari 10 persen yang kembali. Ke mana sisanya mengalir? Apakah uang yang milyaran itu mengalir ke orang-orang yang tepat? Atau segelintir kaum kapitalis yang kerjanya mengakumulasi kekayaan? Dan kekayaan itu digunakan kembali yang melanggengkan kekuasaan. Karena kekuasaan pada gilirannya berkoalisi dan berkolusi lagi dengan mereka. Inikah yang disebut ekonomi kerakyatan? Atau ekonomi keu-rakyat-tan !