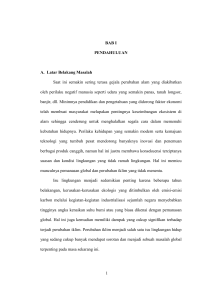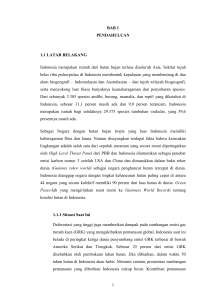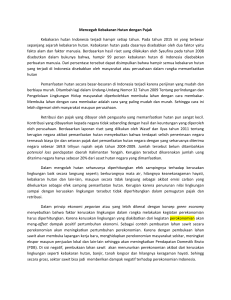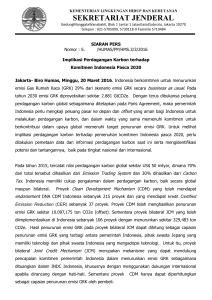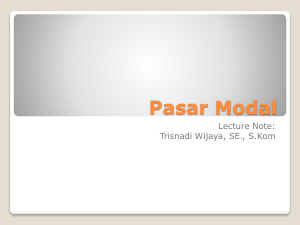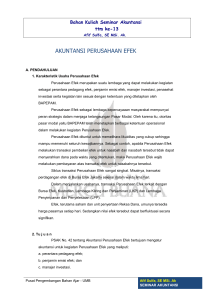kelompok 7 credit carbon - Blog UB
advertisement
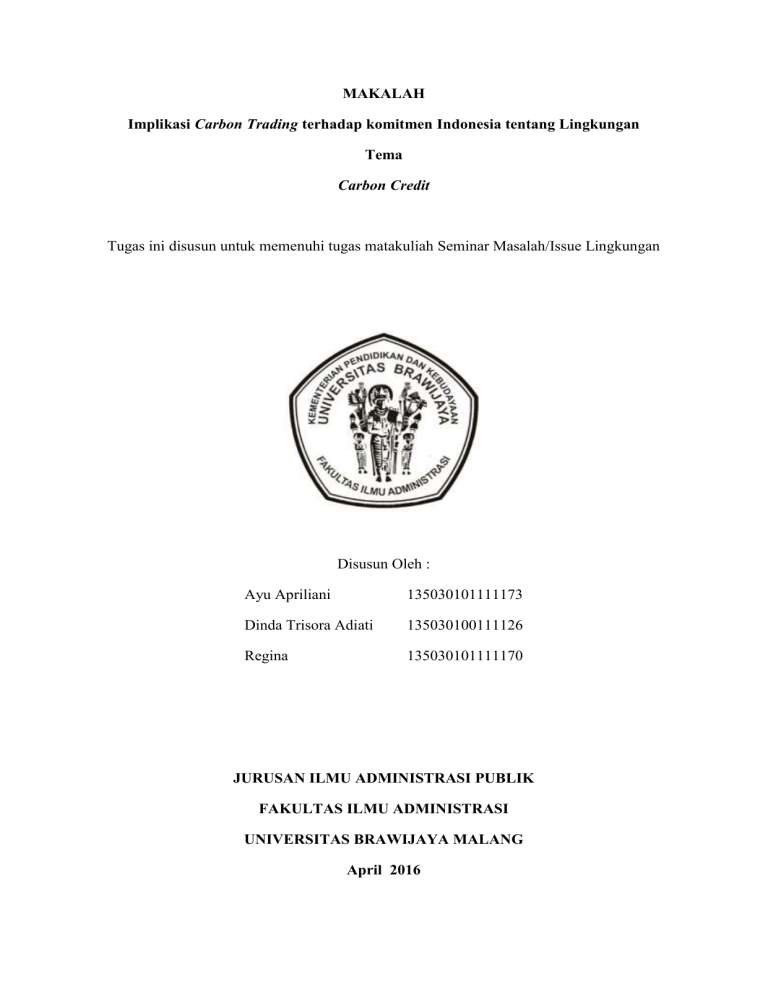
MAKALAH
Implikasi Carbon Trading terhadap komitmen Indonesia tentang Lingkungan
Tema
Carbon Credit
Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Seminar Masalah/Issue Lingkungan
Disusun Oleh :
Ayu Apriliani
135030101111173
Dinda Trisora Adiati
135030100111126
Regina
135030101111170
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
April 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya sebuah negara berkembang ingin meningkatkan perkembangan
ekonomi. Salah satu cara untuk meningkatkan laju ekonomi adalah dengan melakukan
industri manufaktur dimana cara ini sangat efektif untuk meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, beberapa industri mulai dibangun dengan
pesatnya sehingga banyak lahan yang dibuka untuk industri. Pembangunan yang dilakukan
tidak diimbangi dengan perhatian akan kelestarian lingkungan yang ada sehingga pada
akhirnya laju ekonomi yang meningkat menyebabkan sisi negatif pada lingkungan yaitu
rusaknya lingkungan, meningkatnya gas emisi rumah kaca dan masalah lingkungan yang
lainnya.
Meningkatnya gas rumah kaca (GRK) adalah karena deforestasi dan degradasi hutan
serta tingginya karbon dioksida dan karbon monoksida serta CFC yang dilepaskan ke
atmosfer sehingga menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan terjadilah perubahan
iklim dan suhu yang biasa dissebut dengan pemanasan global. Isu lingkungan mengenai
pemanasan global yang disebabkan akibat rusaknya lingkungan ini menjadi pembahasan
internasional karena masalah lingkungan merupakan masalah yang harus diurus oleh semua
negara didunia.
Namun, dalam tingkat global isu lingkungan ini menjadi perdebatan diantara beberapa
negara sehingga menghasilkan dua kubu. Perbedabatan ini berkenaan dengan keadilan antara
negara penghasil emisi tinggi dan rendah. Dimana beberapa negara mampu menghasilkan
carbon credit maupun carbon debit. Carbon debit, artinya negara atau perusahaan
menghasilkan GHG (greenhouse gas) lebih besar dari reduksi GHG sedangkan carbon credit,
artinya negara atau perusahaan mampu mereduksi GHG lebih besar dari GHG yang
dihasilkan. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan oleh
sebagian besar masyarakat dunia dalam protokol Kyoto yang ditandatangani oleh 180 negara
pada bulan Desember 1997. Protokol Kyoto melahirkan tiga mekanisme untuk memperbaiki
dan memelihara kelangsungan ekosistem global yang meliputi International Emission
Trading (IET) , Clean Development Mechanism (CDM), dan Joint Implementation (JI).
Protokol Kyoto di bawah naungan PBB dalam Kerangka-kerja konvensi perubahan iklim
(Framework Convention on Climate Change, FCCC) pada tahun 1997 telah menyepakati
bahwa negara-negara industri akan mengurangi tingkat emisi rata-rata 5,2% dibawah level
1990 pada tahun 2008 hingga 2012.
Berdasarkan kesepakatan ini, negara-negara industri harus melakukan berbagai cara
untuk mereduksi GHG agar memenuhi ketentuan tersebut. Persoalan muncul ketika mereka
tidak mampu mendapatkan teknologi yang efektif untuk mereduksi GHG, atau mereka tidak
mampu mendapatkan teknologi efisien untuk mereduksi GHG. Reduksi GHG tidak hanya
mengandalkan teknologi yang belum tentu efektif atau efisien, melainkan juga melalui
pemberdayaan sumberdaya alam. Reduksi GHG melalui pemanfaatan sumberdaya alam
merupakan alternatif yang dipandang efektif dan mungkin juga efisien dibandingkan reduksi
emisi melalui bisnis itu sendiri yang mungkin membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Persoalan lain muncul bila negara yang bersangkutan tidak memiliki lahan yang
memadai untuk konservasi sumberdaya alam dalam rangka mereduksi GHG. Akibatnya,
negara industri tersebut akan cenderung mengalami carbon debit. Bila negara pemegang
carbon debit tidak mampu menetralisir karbon sesuai kesepakatan dalam Protokol Kyoto,
maka mereka akan terkena penalti atau sanksi. Disisi lain terdapat beberapa negara yang
mampu menghasilkan carbon credit. Mekanisme dalam Protokol Kyoto mengakomodasi
kesulitan negara-negara industri yang mengalami carbon debit dan kelebihan negara-negara
lainnya yang menghasilkan carbon credit melalui perdagangan karbon internasional atau
International Emission Trading (IET).
Perkembangan di atas membuka peluang bagi negara-negara sedang berkembang
yang memiliki potensi dalam mereduksi greenhouse gas (GHG) atau carbon surplus. Negara
atau perusahaan yang memiliki surplus karbon dapat menjual kelebihannya kepada negara
atau perusahaan yang memililik defisit karbon. Potensi Indonesia cukup besar untuk
memasuki era perdagangan karbon tersebut.
Berdasarkan data ADB-GEF-UNDP
menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas reduksi karbon lebih dari 686 juta ton
yang berasal dari pengelolaan hutan, sedangkan perubahan fungsi hutan menimbulkan emisi
karbon lebih dari 339 juta ton, jadi terdapat surplus karbon sebesar 347 juta ton. Bila
dikurangi dengan penambahan emisi karbon dari aktivitas industri lainnya, Indonesia masih
memiliki surplus karbon lebih dari 8 juta ton. Dengan harga rata-rata per ton karbon saat ini
sebesar US$5, maka Indonesia berpotensi menjual sertifikat surplus karbon senilai US$40
juta atau sekitar Rp.360 milyar. Dengan demikian, jika Indonesia tetap dapat
mempertahankan dan menambah jumlah surplusnya maka akan terdapat pendapatan baru
bagi Indonesia melalui carbon trading ini.
Berdasarkan beberapa fakta diatas maka diangkat judul “Implikasi Carbon Trading
terhadap Komitmen Indonesia tentang Lingkungan”. judul tersebut diangkat karena di
Indonesia untuk sekarang ini sudah mulai terdapat pelaksanaan terhadap proyek-proyek untuk
mengurangi GHG (green house gas). Proyek tersebut dilakukan dalam sebuah daerah baik itu
pelaksanaan dari Indonesia sendiri maupun bekerja sama dengan negara maju seperti Jepang
untuk melakukan proyek-proyek penurunan emisi. Dengan demikian dapat diketahui
bagaimana insiatif dan pelaksanaan carbon trading di Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana inisiatif pasar karbon di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia ?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diitentukan tujuan penulisan makalah ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui inisiatif pasar karbon di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia.
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1 Protokol Kyoto
Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan
global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi
emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama
dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas
tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diberlakukan, Protokol
Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 °C dan 0,28 °C pada
tahun 2050. (sumber: Nature, Oktober 2003)
Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim). Kesepakatan ini dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997,
dibuka untuk penanda tanganan pada 16 Maret 1998 dan ditutup pada 15 Maret 1999.
Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan
Rusia pada 18 November 2004. Menurut rilis pers dari Program Lingkungan PBB:
"Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara
perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar
5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika
dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target
ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi ratarata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur
heksafluorida, HFC, dan PFC - yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima
tahun antara 2008-12. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni
Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang
diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia."
Protokol Kyoto adalah protokol kepada Konvensi Rangka Kerja PBB tentang
Perubahan Iklim (UNFCCC, yang diadopsi pada Pertemuan Bumi di Rio de Janeiro pada
1992). Semua pihak dalam UNFCCC dapat menanda tangani atau meratifikasi Protokol
Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga
Konferensi Pihak Konvensi UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang. Sebagian besar ketetapan
Protokol Kyoto berlaku terhadap negara-negara maju yang disenaraikan dalam Annex I
dalam UNFCCC.
Pada saat pemberlakuan persetujuan pada Februari 2005, kesepakatan telah
diratifikasi oleh 141 negara, yang mewakili 61% dari seluruh emisi . Negara-negara tidak
perlu menanda tangani persetujuan tersebut agar dapat meratifikasinya: penanda tanganan
hanyalah aksi simbolis saja. Menurut syarat-syarat persetujuan protokol, kesepakatan mulai
berlaku "pada hari ke-90 setelah tanggal saat di mana tidak kurang dari 55 Pihak Konvensi,
termasuk Pihak-pihak dalam Annex I yang bertanggung jawab kepada setidaknya 55 persen
dari seluruh emisi karbon dioksida pada 1990 dari Pihak-pihak dalam Annex I, telah
memberikan alat ratifikasi mereka, penerimaan, persetujuan atau pemasukan." Dari kedua
syarat tersebut, bagian "55 pihak" dicapai pada 23 Mei 2002 ketika Islandia meratifikasi.
Ratifikasi oleh Rusia pada 18 November 2004 memenuhi syarat "55 persen" dan
menyebabkan pesetujuan itu mulai berlaku pada 16 Februari 2005.
Hingga 3 Desember 2007, 174 negara telah meratifikasi protokol tersebut, termasuk
Kanada, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia dan 25 negara anggota Uni Eropa,
serta Rumania dan Bulgaria. Ada dua negara yang telah menanda tangani namun belum
meratifikasi protokol tersebut: Amerika Serikat (tidak berminat untuk meratifikasi) dan
Kazakstan. Pada awalnya AS, Australia, Italia, Tiongkok, India dan negara-negara
berkembang telah bersatu untuk melawan strategi terhadap adanya kemungkinan Protokol
Kyoto II atau persetujuan lainnya yang bersifat mengekang. Namun pada awal Desember
2007 Australia akhirnya ikut seta meratifikasi protokol tersebut setelah terjadi pergantian
pimpinan di negera tersebut.
2.2 Konsep Pasar Karbon
2.2.1 Pengertian Pasar Karbon
Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas
rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 equivalent) . Hak di sini dapat berupa hak
untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca .
Sedangkan jenis gas rumah kaca yang dapat diperdagangkan dalam pasar karbon umumnya
adalah enam jenis gas rumah kaca yang tercantum dalam Protokol Kyoto1, yang meliputi
meliputi karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrat oksida (N2O), hidrofluorokarbon
(HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF6).Keenam jenis gas rumah
kaca ini mempunyai potensi penyebab pemanasan global yang berbeda-beda. Karbon
dioksida, walaupun konsentrasinya paling tinggi di atmosfer, ternyata adalah gas rumah kaca
dengan potensi penyebab pemanasan global terendah di antara keenam jenis gas tersebut
sehingga menjadi angka acuan untuk indeks daya penyebab pemanasan global yang disebut
Global Warming Potential (GWP). Karena potensinya yang terendah, angka GWP untuk
karbon dioksida adalah 1. Gas metana mempunyai GWP sebesar 21. Artinya 1 ton metana
mempunyai potensi menyebabkan pemanasan global 21 kali lebih tinggi daripada 1 ton
karbon dioksida. Ini juga berarti bahwa mengurangi emisi gas metana sebanyak 1 ton setara
dengan mengurangi emisi karbon dioksida sebanyak 21 ton.
Jenis-jenis gas rumah kaca dan GWP-nya disampaikan dalam tabel di halaman berikut.
Jenis
PotensiPemanasan
Global
(GWP)
Karbondioksida
1
Metana
21
Nitratoksida
310
Perfluorokarbon
6.500-9.200
Hidrofluorokarbon
140-11.700
Sulfurheksafluorida
23.900
Tabel 1. Jenis-jenis gas rumah kaca
Untuk mendefinisikan pasar karbon, bisa dilihat dari definisi pasar, salah satunya
menurut William J. Stanton (Prinsip Pemasaran, 1987), pasar dalam arti luas adalah “orangorang (atau pihak-pihak) yang mempunyai kebutuhan/keinginan untuk dipenuhi, uang untuk
dibelanjakan, dan kemauan untuk membelanjakannya”. Dengan kata lain, Stanton
mendefinisikan pasar adalah jumlah total permintaan (demand). Mengacu pada definisi
Stanton, dapat kita definisikan bahwa pasar karbon adalah kumpulan kebutuhan/keinginan
terhadap hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 eq.). Selain
pasar karbon, ada juga istilah “perdagangan karbon”. Kedua istilah ini seringkali tertukar
dalam penggunaannya. Di dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang Dewan
Nasional Perubahan Iklim, perdagangan karbon didefinisikan sebagai “kegiatan jual beli
sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim”. Terlihat
perbedaan yang jelas antara istilah “pasar karbon” dan “perdagangan karbon” dimana pasar
(market) adalah penyebab bagi perdagangan.
2.2.2 Jenis-jenis Pasar Karbon
a. Pasar karbon sukarela (voluntary carbon market)
Permintaan pada pasar karbon ini terbentuk semata karena adanya keinginan untuk
mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bukan karena adanya kewajiban untuk itu. Keinginan
ini memicu terjadinya perdagangan karbon antara yang mmpunyai keinginan dengan
penyedia karbon yang kerap kali terjadi secara langsung (over the counter). Dalam beberapa
kasus, keinginan/kebutuhan tersebut digabungkan menjadi komitmen kolektif sehingga
pasarnya membesar dan dapat menarik keterlibatan pihak lain seperti perantara/ broker ,
investor maupun layanan bursa. Karena sifatnya yang mengandalkan keinginan dan niat baik
untuk mengurangi emisi karbon, volume pasar sukarela relatif kecil dan sulit diperkirakan.
Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa volume pasar karbon
sukarela cenderung naik dengan stabil.
b. Pasar karbon wajib
Kebalikan dari pasar karbon sukarela, pasar karbon jenis ini terbentuk karena ada
kebijakan yang mewajibkan pengurangan dan/atau pembatasan jumlah emisi gas rumah
kaca. Pasar karbon kemudian diterapkan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan tersebut
(policy tool). Protokol Kyoto adalah salah satu contoh kebijakan yang mewajibkan
pengurangan emisi gas rumah kaca namun memperbolehkan penggunaan pasar karbon untuk
memenuhinya. Volume pasar karbon wajib sangat bergantung pada rancangan dan lingkup
kebijakan pengurangan/pembatasan emisi yang diterapkan, sehingga relatif lebih mudah
diperkirakan dan direncanakan dalam jangka panjang.
2.3 Konsep Carbon Tradding
Carbon trading juga dikenal dengan istilah emissions trading. Carbon trading
merupakan salah satu rekomendasi Kyoto Protocol 1997, sebuah rencana internasional untuk
mengurangi enam gas rumahkaca utama penyebab perubahan iklim. Emission trading
merupakan istilah yang diterapkan dalam perdagangan sertifikat yang mencerminkan
berbagai cara untuk mengurangi emisi karbon sesuai dengan target yang dicantumkan dalam
sertifikat. Para partisipan dalam perdagangan karbon membeli dan menjual komitmen
kontrak (contractual commietments) atau sertifikat yang mencerminkan jumlah tertentu emisi
karbon (carbon-related emission) yang dapat dikurangi.
Dengan demikian Certified Emission Reductions (CERs) merupakan komoditas baru
dalam perdagangan dunia yang prospektif. Bila seluruh negara di dunia telah menyepakati
perdagangan karbon tersebut, maka CERs menjadi komoditas yang menguntungkan sama
halnya dengan sekuritas yang banyak diperdagangkan. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil
bila pada masa datang, perdagangan karbon menjadi komoditas yang laku seperti halnya
perdagangan minyak seperti sekarang ini. Perkembangan menunjukkan bahwa kebutuhan
CERs pada masa datang menjadi komoditi penting dalam pasar GHG yang berorientasi pada
kelangsungan ekosistem global. Analis memperkirakan ukuran pasar futures GHG pada tahun
2010 akan mencapai kisar US$10 milyar hingga US$1 trilyun. Ukuran tersebut diperkirakan
meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat
serta kelangsungan ekosistem global.
Carbon trading menggunakan skema khusus yang disebut sistem 'cap and trade'.
Berdasarkan komitmen Kyoto, sebuah negara dapat mengalokasikan ijin emisi gas
rumahkaca ('cap') kepada perusahaan-perusahaan. Jika sebuah perusahaaan terbukti
melakukan emisi kurang dari batasan yang diberikan, kelebihan ijin yang dimilikinya dapat
diperdagangkan ('trade') kepada perusahaan yang mengeluarkan lebih banyak polusi.
Sebaliknya, jika perusahaan gagal memenuhi target emisi, atau dengan kata lain
mengeluarkan CO2 lebih banyak dari batas yang diijinkan ('cap'), mereka dapat membeli
'carbon credit' dari perusahaan dengan emisi di bawah target. Carbon credit ini biasanya
diperdagangkan di 'over the counter (OTC) market'. Singkatnya, hal ini menegaskan bahwa
apa yang diperdagangkan di 'carbon trading' bukanlah karbon sesungguhnya, tetapi hak
untuk emisi CO2.
Untuk memahami bagaimana karbon diperdagangkan, perlu dipahami komoditi apa
yang diperdagangkan dan sistem yang menciptakannya. Ada dua komoditi yang
diperdagangkan, yang pertama adalah apa yang disebut allowance, dan yang kedua adalah
offset yang dapat diilustrasikan sebagai berikut :
1. Perdagangan “emisi yang tidak dipergunakan” (allowance trading)
Negara-negara yang ditarget penurunan emisi (annex I country) mempunyai
kewajiban untuk menurunkan emisinya pada periode komitmen I (2008-2012) sebesar 5% di
bawah tingkat emisi pada tahun 1990. Emisi total suatu negara dibatasi (Capped), dari emisi
yang dibatasi inilah nanti akan muncul allowances (kelebihan emisi yang tidak dipakai).
Allowances inilah yang boleh dijual kepada pihak lain yang tidak dapat menurunkan emisi
sesuai targetnya. Misalnya suatu negara A dibatasi emisinya sebesar 1 juta ton CO2. Target
emisi ini kemudian dibagi ke perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut.
Misalnya perusahaan A mendapat target emisi 100.000 ton, padahal sebelumnya
mereka mengemisi 110.000 ton CO2. Perusahaan tersebut harus melakukan penurunan emisi
sebesar 10.000 ton. Perusahaan A mampu menurunkan emisinya sampai 20.000 ton, sehingga
Perusahaan A memiliki “kelebihan emisi” 10.000 ton. Sementara itu perusahaan B (yang
memiliki target emisi sebesar 100.000 ton juga, padahal sebelumnya mengemisi 110.000 ton)
memilih untuk tidak menurunkan emisinya karena biayanya terlalu besar. Perusahaan B
berhak membeli “kelebihan emisi” dari perusahaan A yaitu sebesar 10.000 ton dengan biaya
yang lebih rendah. Inilah yang disebut perdagangan emisi (karbon). Perdagangan karbon
seperti ini disebut sebagai cap-and-trade system.
2. Perdagangan kredit berbasis proyek (offset trading)
Carbon offset adalah alat/sarana untuk mengkompensasi emisi yang dikeluarkan oleh
perusahaan ataupun pribadi. Dengan membayar orang lain (ditempat lain) untuk melakukan
usaha penyerapan karbon atau menghindari emisi karbon, pembeli offset karbon bermaksud
mengganti (atau dalam prinsipnya meng”offset”) emisi karbon yang telah mereka lakukan.
Misalnya perusahaan A mengemisi 110.000 ton CO2 pertahun. Pemerintah
menginginkan masing-masing perusahaan menurunkan emisinya menjadi 100.000 ton. Kedua
perusahaan tersebut diberi alternatif. Apabila mereka tidak mau menurunkan emisinya,
mereka dapat mendanai proyek di tempat lain yang dapat mereduksi emisi karbon hingga
10.000 ton. Perdagangan kredit berbasis proyek ini sering disebut juga baseline and credit,
atau offset trading. Dalam sistem ini, pembeli hanya dapat mengklaim pengurangan emisinya
melalui proyek yang benar-benar dapat dibuktikan bahwa pengurangan emisi terjadi dari
proyek tersebut dan bukan business as usual. Inilah yang disebut konsep additionality.
2.3 Konsep Redd+
Perdebatan mengenai REDD+ berawal dari perdebatan mengenai kerangka
implementasi konvensi perubahan iklim, Terutama Protokol Kyoto. Pasal 2 ayat 1 a (ii)
Protokol Kyoto menyebutkan: Protection and enhancement of sinks and reservoirs of
greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its
commitments under relevant international environmental agreements; promotion of
sustainable forest management practices, afforestation and reforestation (Melindungi dan
memperluas penyerapan dan penampungan Gas-gas Rumah Kaca tidak diatur oleh Protokol
Montreal, dengan mengingat komitmennya berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lingkungan
internasional; mendukung praktek-praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan,
penghijauan kembali dan penanaman hutan). hal yang tercantum dalam Protokol Kyoto ini
diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana Protokol Kyoto yang dibahas di CoP 7 di
Marrakesh, Maroko, 2001. Aturan pelaksana tersebut selanjutnya disebut Marrakech
Accords. Salah satu keputusan Marrakech Accords adalah mengenai penggunaan lahan,
perubahan tata guna lahan dan kehutanan, termasuk definisi, modalitas(cara) dan panduannya
atau disebut LULUCF (Marrakech Accord 11/CP.7,Lampiran 1 A).
LULUCF (Marrakech ACCORD)
Land Use, Land Use Change and Forestry merupakan salah satu hasil dari
Conference of Parties ke-7 yang kerap disebut Marrakech Accords . Kesepakatan ini
merupakan petunjuk pelaksanaan Protokol Kyoto yang memberi mandat tanggung
jawab pengurangan emisi bagi 38 negara-negara industri yang kerap disebut negaranegara Annex I. Besarnya kepentingan negara maju membuat lingkar perdebatan
LULUCF sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara industri tersebut.
Salah satu perdebatan kunci adalah definisi hutan. Eropa dan beberapa kelompok
negara maju yang telah kehilangan hutan tapi tergantikan oleh perkebunan,
mendorong definisi hutan juga mencakup perkebunan. Dalam hal ini negara maju
berhasil mengunci kemenangan diplomasinya dimana agregat emisi mereka tidak
bertambah dari sektor LULUCF tapi justru sebaliknya berkontribusi menyerap
karbon (carbon sink) lewat perkebunan. Karena itu, LULUCF di bawah Kyoto
Protokol tidak begitu populer.
Terkait dengan definisi hutan dan panduan mekanisme CDM yang memasukan isu
kehutanan aforestasi dan reforestasi, Marrakech Accords memutuskan beberapa panduan
dasar,antara lain sebagai berikut:
Definisi Hutan:
a. Areanya minimal 0,05-1 hektar
b. Tutupan tajuk lebih dari 10-30 persen
c. Ketinggian tajuk 2-5 meter
d. Hutan tertutup dengan variasi jenis
e. Semak belukar yang menutup rapat tanah atau hutan terbuka
f. Tegakan pohon alam dan perkebunan yang belum mencapai tingkat kepadatan jenis
atau keragaman jenis 10-30 persen atau ketinggian pohon 2-5 meter akan
diperhitungkan sebagai hutan jika wilayah-wilayah itu biasanya membentuk kawasan
hutan yang untuk sementara tidak berhutan karena intervensi manusia seperti dipanen
atau akibat dari penyebab alamiah tapi diharapkan kembali menjadi hutan.
Definition of Forests under the Kyoto Protocol (Promote Kant, 2006)
By the Decision 11/CP.7 of the Marrakech Accord the following definitions of forests,
afforestation and reforestation were adopted (UNFCCC, 2002), which were later
extended to land use, land-use change and forestry activities carried out under the
Clean Development Mechanism (CDM) of the Kyoto Protocol by Decision 19/CP.9
adopted at Milan (UNFCCC, 2004).
(a) “Forest” is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover
(or equivalent stocking level) of more than 10-30 per cent with trees with the potential
to reach a minimum height of 2-5 meters at maturity in situ. A forest may consist
either of closed forest formations where trees of various storeys and undergrowth
cover a high proportion of the ground or open forest. Young natural stands and all
plantations which have yet to reach a crown density of 10-30 per cent or tree height
of 2-5 meters are included under forest, as are areas normally forming part of the
forest area which are temporarily un-stocked as a result of human intervention such
as harvesting or natural causes but which are expected to revert to forest.
(b) “Afforestation” is the direct human-induced conversion of land that has not been
forested for a period of at least 50 years to forested land through planting, seeding
and/or the human-induced promotion of natural seed sources.
(c) “Reforestation” is the direct human-induced conversion of non-forested land to
forested land through planting, seeding and/or the human-induced promotion of
natural seed sources, on land that was forested but that has been converted to nonforested land. For the first commitment period, reforestation activities will be limited
to reforestation occurring on those lands that did not contain forest on 31 December
1989.
Definisi hutan sebagaimana ditetapkan dalam Marrakech Accord Tersebut agak
berbeda dengan definisi yang ditetapkan dalam Permenhut No. P.14/Menhut-II/2004, tentang:
Tata Cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih (MPB
/CDM) Dimana disebutkan bahwa: definisi Hutan adalah tingginya minimum 5 meter,
penutupan tajuknya minimum 30% dan luasnya minimum 0,25 ha. Saat ini Pustanling sedang
menggarap RSNI Penghitungan Deforestasi dan salah satu pembahasannya adalah mengenai
definisi hutan. Beberapa Definisi hutan yang sekarang sedang dalam proses pembahasan
Pustanling adalah sebagai berikut:
1. Hutan adalah hamparan lahan dengan luas minimum 0,25 ha yang ditumbuhi vegetasi
berkayu (pohon) berbagai jenis dan umur yang tajuknya menutup hamparan tersebut
minimum 30%.
2. Hutan dalam interpretasi citra penginderaan jauh adalah obyek berwarna hijau dengan
rona sedang hingga gelap, serta bertekstur halus hingga kasar pada tampilan gambar
dengan kombinasi R (Red):G(Green):B (Blue) dengan kanal R diisi dengan spektrum
SWIR, kanal G diisi dengan spektrum NIR, kanal B diisi dengan spektrum Red.
3. Hutan alam adalah suatu hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang
secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam
lingkungannya.
4. Hutan Lahan Kering adalah tipe hutan alam yang lantai hutannya tidak pernah
terendam air, baik secara periodik maupun sepanjang tahun.
5. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang terutama terdapat di sepanjang pantai atau
muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, lantai hutannya tergenang pada
waktu pasang dan bebas genangan waktu surut.
6. Hutan primer adalah areal berhutan yang ditumbuhi oleh spesies asli setempat,
sebagian besar tidak tersentuh oleh kegiatan manusia, baik langsung maupun tidak
langsung dan proses ekologi di hutan tersebut tidak terganggu secara signifikan.
7. Hutan rawa adalah hutan yang lantai hutannya secara periodik atau sepanjang tahun
terendam air.
8. Hutan sekunder adalah suatu keadaan masyarakat hutan yang pohon-pohonnya
didominasi oleh jenis pionir yang tumbuh setelah hutan itu mengalami gangguan dan
terbentuk rumpang (gap).
9. Hutan tanaman adalah hamparan lahan yang ditanami dengan vegetasi berkayu
(pohon), pada umumnya satu jenis, berkelas umur dengan luas minimal 0,25 ha.
Selain beberapa jenis hutan diatas, dapat diketahui beberapa jumlah tanaman penghasil
karbon yaitu sebagai berikut :
Jenis
Cepat Tumbuh
1. Mangium (Sumsel)*
2. Mangium**
3. Sengon (Jatim)*
4. Eucalyptus Grandis
(Taput)**
5. E. Globulus
(Australia
Tenggara)***
6. A.mearnsi (Australia
Tenggara)***
7. Campuran 5+6**
Lambat Tumbuh
1. Mahoni (Sumsel)*
2. Sungkai (Sumsel)*
3. Meranti (Bogor)**
4. Jati (Seradan,
Jatim)**
Sumber:
Usia
Kerapatan Kandungan Jumlah
(tahun) (ha)
Karbon
Karbon
(ton/ha)
(ton/ha/tahun)
6
8
8
3
1.111
711
1.111
99,85
240,800
134,31
16,64
30,10
16,79
31,948
11,5
25,264
11,5
36,202
11,5
48,143
20
10
1.111
1.111
202,99
41,97
60
10,15
4,20
18,640
5,8
*Ginting dan/and Prajadinata (2002,2003,2004,2005) dalam Wibowo dan Rufi’ie (2008)
dalam Kosasih, Agung dan Sumandri (2010)
**Berbagai sumber dalam Junaedi, (2008) dalam Kosasih, Agung dan Sumandri (2010)
***Forrester, et.al (2006)dalam Kosasih, Agung dan Sumandri (2010)
Selanjutnya, ada tiga istilah lain yang sudah tertuang dalam Protokol Kyoto yakni
aforestasi, sustainable forest management dan reforestasi. Ketiganya didefinisikan sebagai
berikut:
Aforestasi adalah konversi akibat tindakan langsung manusia dan tidak berhutan
paling tidak selama 50 tahun kemudian dihutankan kembali lewat penanaman, penyemaian
maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah. Reforestasi
adalah konversi akibat tindakan langsung manusia dari tidak berhutan menjadi berhutan.
Metodenya lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan
sumber-sumber benih alamiah di daerah yang dulunya berhutan tapi telah dikonversikan
menjadi daerah yang tidak berhutan Untuk Komitmen pertama (2008–2012) Tindakan
reforestasi dibatasi pada reforestasi yang akan dilakukan di wilayah-wilayah yang tidak
berhutan pada 31 Desember 1989. Sustainable Forest Management adalah praktek yang
sistemik untuk menjaga dan menggunakan tanah berhutan yang bertujuan memenuhi fungsi
sosial, ekonomi dan ekologi hutan yang relevan (termasuk keanekaragaman hayati) melalui
cara yang berkelanjutan. Keempat konsep ini setidaknya menggarisbawahi beberapa isu yang
menimbulkan perdebatan serius dalam perundingan perubahan iklim, termasuk ketika
perdebatan REDD mulai mengadopsi konsep-konsep tersebut.
Dalam perundingan perubahan iklim selanjutnya, embrio isu kehutanan yang sudah
berkembang dalam skema Kyoto mengalami perkembangan signifikan. Papua Nugini
Sebelum COP 11 Di Montreal tahun 2005 melihat perlunya upaya serius mengatasi emisi dari
deforestasi dan degradasi hutan. Inisiatif PNG ini didorong kuat oleh Kevin Condrad, duta
besar dan utusan khusus PNG untuk lingkungan dan perubahan iklim. Condrad menjalani
studi di Columbia Business School dengan fokus pada proyek penelitian mengenai apakah
uang dari kredit karbon setara dengan pendapatan dari logging. Logging yang tidak terkendali
memang menjadi masalah nasional di PNG. Karena itu, Condrad melihat isu perubahan iklim
sebagai peluang politik untuk merundingkan nilai ekonomi hutan dalam pasar karbon dan
menekan laju deforestasi.
Agar mendapat resonansi politik yang signifikan, Profesor Geoffrey Heal,
pembimbing proyek penelitian Condrad dalam proyek tersebut, mendukung Condrad untuk
membujuk Perdana Menteri PNG, Michael Somare, agar mendorong pembentukan koalisi
yang menyuarakan kredit karbon hutan dalam perundingan perubahan iklim. Pada Januari
2005, Somare menyerukan pembentukan Coalition for Rainforest Nationspada forum
pemimpin dunia yang diselenggarakan di universitas Columbia. Pada bulan Mei, dalam acara
Global Roundtable on Climate Change di universitas Columbia, Somare kembali
mengusulkan hal serupa dengan meminta rekan-rekannya dari negara-negara hutan hujan
seperti Peru, Kongo, Kosta Rika, Republik Dominika, Mozambik, Tanzania and Zambia
untuk membentuk koalisi tersebut. Koalisi negara-negara hutan hujan yang terbentuk ini
kemudian mengusung ambisi untuk memasukan sertifikat pengimbangan emisi terkait dengan
deforestasi dalam pasar emisi karbon global.
PNG kemudian menggandeng Kosta Rika yang juga sedang dililit utang untuk
mencari sumber alternatif pemulihan ekonomi. Dalam proposal kedua negara yang dibahas
pada COP Montreal tersebut, PNG dan Kosta Rika Mengajukan dua opsi kerangka hukum ke
depan: Pertama, Membuat protokol tambahan yang khusus mengatur emisi dari deforestasi
dan degradasi. Kedua, mengembangkan lebih lanjut substansi yang sudah tercantum dalam
Protokol Kyoto dan Marrakech Accords dengan salah satu tambahan penting yakni proyek
kredit karbon harus dibuat secara spesifik untuk isu deforestasi dan degradasi. Dengan Kata
lain, negara yang ingin dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
seharusnya diberi kompensasi secara finansial melalui mekanisme pasar karena sudah
melakukan upaya itu dengan menahan diri untuk tidak melakukan konversi hutan demi
pertumbuhan ekonomi.
Selain Papua Nugini dan Kosta Rika, proposal ini didukung oleh enam negara lain,
yakni: Bolivia, Republik Afrika Tengah, Chili, Kongo, Republik Dominika dan Nikaragua.
Negara-negara ini menjadi koalisi yang disebut dengan “Koalisi Negara hutan hujan”
(Coalition of Rainforest Nations) dan menunjuk universitas Columbia sebagai sekretariat.
Banyak negara lain menyepakati pentingnya isu yang disampaikan PNG dan Kosta Rika,
sehingga COP membentuk grup kontak, semacam panitia khusus, untuk merancang
kesimpulan yang menjadi bahan tindak lanjut dalam menjawab isu pengurangan emisi dari
deforestasi dan degradasi.
Dalam perkembangan selanjutnya, isu pengurangan emisi dari deforestasi dan
degradasi mendapat kerangka hukum awal dalam CoP 13 di Bali, 2007. Keputusan Bali,
disebut dengan Bali Action Plan (BAP), antara lain memberi dasar hukum pengembangan
skema dan proyek percontohan REDD saat ini. Dalam paragraf 1 b(iii) BAP disebutkan
bahwa:
Tindakan mitigasi internasional/nasional mencakup deforestasi dan degradasi tapi
juga menyangkut konservasi, sustainable forest management, dan perluasan stok
karbon di negara-negara berkembang. Dengan demikian, cakupan REDD dalam pasal
ini adalah deforestasi, degradasi, perluasan stok karbon, konservasi dan SFM. Konsep
ini persis mengikuti logika LUULUCF yang disepakati dalam Marrakech Accord,
sehingga kerap disebut REDD plus LULUCF.
Pasal lain dalam Bali Action Plan juga mengemukakan tiga hal terkait dengan REDD
yakni:
- Pengembangan proyek-proyek percontohan atau pilot project REDD
- Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi ke negara berkembang
- Panduan untuk proyek-proyek REDD lewat metodologi yang kokoh dan dapat dipercaya.
Tiga aspek ini menjadi landasan uji coba proyek REDD di berbagai lokasi, termasuk
di Indonesia. Pada COP 14 di Poznan, REDD yang ditetapkan dalam BAP paragraf 1 b (iii)
dipertegas tidak hanya meliputi deforestasi dan degradasi tetapi juga mencakup konservasi,
SFM, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari skema CDM. Perkembangan ini
kerap disebut REDD+. Sama seperti perdebatan REDD, dalam REDD+ isu yang tetap
diperdebatkan adalah cakupan. Namun beberapa isu lain yang muncul adalah cara
perhitungan dengan pendekatan nett dan gross, konsep sustainable forest management dan
persoalan tropical hot air.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Inisiatif Pasar Karbon di Indonesia
Kesalahpahaman masyarakat umum dan pemangku kepentingan tentang pasar karbon,
kerumitan sistemnya, dan tuntutan transparansi dalam setiap tahapannya menjadikan pasar
karbon masih menjadi pilihan alat pembangunan rendah karbon yang terakhir. Meskipun
demikian, Pemerintah Indonesia menyadari arti penting pasar karbon ini dalam rencana
pembangunan rendah karbon, mengingat manfaatnya dalam peningkatan efisiensi, investasi,
jumlah lapangan kerja, tingkat alih teknologi, dan manfaat dampingannya dalam
meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga mutu lingkungan. Perumusan
mekanisme dan kebijakan pasar karbon di Indonesia kemudian dimandatkan oleh pemerintah
kepada DNPI yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 tentang Dewan
Nasional Perubahan Iklim. Untuk melaksanakan hal ini, DNPI menerapkan strategi
pengembangan pasar karbon dalam tiga jalur yang dapat saling terkait, dengan tujuan untuk
menciptakan kemampuan nasional dalam memanfaatkan pasar karbon secara optimal bagi
pembangunan Indonesia yang rendah karbon dan adaptif terhadap perubahan iklim. Ketiga
jalur tersebut digambarkan sebagai berikut.
Pasar Karbon Multilateral
Tergantung
dari
hasil
perundingan
UNFCCC
Butuh keseimbangan antara mekanisme
yang fleksibel dan yang rigid
Membutuhkan
kesepakatan
Internasional
untuk kriteria lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan
Pasar Karbon Bilatral / Regional
Antara indonesia dan negara maju
Dapat menjadi mekanisme internasional
buat offsetting
Sekarang menjadi pusat perhatian dodalam
dan diluar perundingan
Pasar Karbon Domestik
Dimulai dari mekanisme offset sukarela
(SKN)
Dikembangkan
dan
diperdagangkan
di
Indonesia
Sederhana tapi rigid
Dapat disambungkan atau dikaitkan dengan
mekanisme yang lebih besar
Tabel : Strategi pengembangan pasar karbon di Indonesia
3.1.1 Pengembangan Pasar Karbon Multilateral
Perkembangan perundingan perubahan iklim di tingkat UNFCCC maupun dalam
berbagai inisiatif internasional yang mulai muncul mengharuskan Indonesia untuk melakukan
antisipasi pengembangan instrumen pasar karbon multilateral. Selain terlibat aktif dalam
pengembangan dan penyiapan instrumen pasar karbon multilateral yang baru, Indonesia juga
tetap memanfaatkan skema CDM, terutama sebagai pembanding (benchmark) bagi pasar
karbon yang dikembangkan.Dalam kegiatan pengembangan pasar karbon multilateral
Indonesia bergabung dalam kerjasama multilateral yang digagas Bank Dunia (The World
Bank) bertajuk Partnership for Market Readiness (PMR) dan diikuti oleh 13 negara donor
dan 16 negara pengimplementasi (implementing countries) . Kerjasama ini menarik dan
unik karena setiap negara pengimplementasi diberi kebebasan dalam mempersiapkan diri
untuk menghadapi pasar karbon pasca 2012 dan
dilakukan serangkaian kegiatan
pengembangan kapasitas serta pertukaran informasi antar negara peserta untuk mencapai
kesiapan dan kesepahaman yang lebih baik.
Sebagai salah satu negara pengimplementasi, Indonesia telah melakukan pemaparan
rencana pembangunan kesiapan pasar karbon multilateral melalui pengembangan instrumen
teknis dan kebijakan. Pada proposal yang telah disusun dan dipresentasikan di Barcelona,
Spanyol, pada bulan Mei 2013, Indonesia mengajukan beberapa rencana yang disetujui oleh
Partnership Assembly , yaitu:
1. Pengembangan rencana nasional yang komprehensif untuk pembiayaan berbasis pasar
(market based instrument initiative) . Rencana nasional ini diharapkan akan menjadi
rencana induk pengembangan pembiayaan berbasis pasar yang terintegrasi dengan
pembangunan rendah karbon di Indonesia.
2. Pembangunan sistem MRV emisi GRK untuk sektor industri padat energi dengan
pilot sistem MRV di sub sektor semen. Sub sektor semen dipilih karena merupakan
yang paling siap di Indonesia baik dari sisi kebijakan maupun teknis serta dapat
menjadi contoh bagi sub sektor industri lain. Kewajiban menurunkan emisi bagi
industri semen yang diamanatkan salah satu Peraturan Menteri Perindustrian juga
diharapkan bisa menjadi pendorong pengembangan pasar karbon domestik.
3. Pembangunan sistem MRV emisi GRK untuk sektor pembangkitan listrik dengan
pilot sistem MRV di sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), jaringan listrik
terbesar di Indonesia dengan jenis pembangkit paling beragam. Sektor kelistrikan juga
merupakan sektor dengan pertumbuhan emisi tertinggi di Indonesia dan dapat
dikembangkan menjadi salah satu sektor utama penunjang pasar karbon di masa
depan.
Selain inisiatif yang dilakukan dengan Bank Dunia melalui PMR, Indonesia juga aktif
dalam negosiasi UNFCCC, khususnya untuk pengembangan pasar karbon dalam perumusan
kerangka perjanjian perubahan iklim yang mengikat para pihak peserta konvensi pasca
Protokol Kyoto. Pada dasarnya, Indonesia sangat mendukung segala upaya pengembangan
pasar karbon dalam konteks pengurangan emisi gas rumah kaca secara global.
3.3.2 Pengembangan Pasar Karbon Bilateral dan Regional
Pengembangan pasar karbon bilateral dan regional di Indonesia terutama dilakukan
sebagai upaya mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon secara nasional dan
mengantisipasi prediksi akan berkurangnya pembiayaan berbasis pasar sejak berakhirnya
komitmen pertama dari Protokol Kyoto dan belum terbangunnya pasar karbon multilateral
yang lebih fleksibel dan bisa diikuti semua negara. Di bawah ini adalah inisiatif-inisiatif
pengembangan pasar karbon bilateral dan regional yang dikembangkan di Indonesia:
1. Joint Crediting Mechanism (JCM)
Kerjasama bilateral perdagangan karbon dengan Jepang. Sejak tahun 2010 Jepang
telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia dan beberapa negara lain untuk melakukan
perdagangan karbon antarnegara secara bilateral.
Selain
untuk
perdagangan karbon,
kerjasama ini juga didasari kepentingan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan
Jepang melalui proyek-proyek rendah karbon.
Sebagai negara maju, Jepang berkomitmen untuk
menurunkan emisi gas rumah
kacanya (GRK) sampai dengan level 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020. Target
tersebut akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dan melalui proyek
pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta Jepang namun dilakukan
di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang, melalui mekanisme JCM. Pilihan
bekerja sama dengan negara berkembang adalah yang terbaik bagi Jepang karena ia tidak
meletakkan komitmen untuk Protokol Kyoto sehingga tidak dapat mempergunakan CDM,
sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk pengurangan emisi di dalam negeri sangat tinggi.
Jepang akan mendapatkan kredit karbon dari pengurangan emisi dengan cara menanamkan
investasi atau membeli
pengurangan emisi, sedangkan Indonesia akan mendapatkan
investasi, transfer teknologi, dan kemungkinan pembagian kredit karbon dari proyek.
Pembagian kepemilikan kredit karbon dari proyek akan sangat tergantung dari jenis dan
besaran modal yang ditanamkan serta kesepakatan kedua belah pihak.
Jepang dan Indonesia telah merancang beberapa aturan dasar untuk implementasi
JCM yang diharapkan dandilakukan pada tahun 2013. Sebagai bagian dari persiapan tersebut,
Pemerintah Jepang melalui beberapa kementeriannya telah memberikan dana hibah kepada
perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan studi kelayakan (feasibility studies)
pelaksanaan proyek-proyek di bawah skema JCM di Indonesia. Sampai saat ini telah
dilakukan 57 (lima puluh tujuh) studi kelayakan, yang terdiri dari studi di bidang energi
terbarukan (dari sumber panas bumi, hidro, dan biomassa), efisiensi energi, transportasi
rendah karbon, Carbon Captured and Storage (CCS), pertanian rendah karbon, dan kegiatan
berbasis kehutanan. Dua aspek kelayakan utama yang dianalisis dalam studi-studi tersebut
adalah skema pembiayaan dan metodologi penghitungan emisi GRK. Metodologi yang akan
diterapkan harus dipastikan memenuhi standar ilmiah sehingga hasil pengurangan emisi dari
proyek JCM dapat diakui di forum/ mekanisme internasional.
Perjanjian kerjasama bilateral untuk implementasi JCM yang telah ditandatangani
oleh kedua negara pada bulan Agustus 2013, mempunyai implikasi bahwa JCM kemudian
akan dikembangkan secara bersama dalam kerangka pembangunan rendah karbon dan
perdagangan karbon antar kedua negara. Mekanisme JCM adalah kerjasama bilateral yang
mengedepankan investasi berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan rendah
karbon. Mekanisme ini akan menjadi insentif bagi perusahaanperusahaan Jepang untuk
meningkatkan investasi dalam kegiatan rendah karbon di Indonesia. Pemerintah Jepang
diuntungkan karena sebagian dari hasil penurunan emisi GRK di proyek-proyek investasi di
Indonesia akan dapat diklaim sebagai penurunan emisi negaranya. Indonesia juga
mendapatkan manfaat yang besar, baik manfaat ekonomi maupun lingkungan, dari kerjasama
JCM tersebut. Lebih jauh, JCM yang kemudian dimaksudkan untuk menjadi mekanisme
offsetting internasional, menyebabkan Indonesia dan Jepang, juga beberapa negara yang
mempunyai perjanjian yang serupa dengan Jepang, akan mempunyai posisi yang sama di
perundingan internasional untuk perubahan iklim, sehingga akhirnya JCM ini benar-benar
menjadi mekanisme internasional yang diakui UNFCCC.
2. Kerjasama dalam kawasan Asia Pasifik
Indonesia juga aktif terlibat dalam kerjasama antar kawasan di Asia Pasifik. Forum
yang pertama kali diinisiasi oleh Selandia Baru dan kemudian diikuti oleh lebih dari 15
negara di Asia Pasifik ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama jangka panjang dalam
pembangunan pasar karbon yang terintegrasi dalam kawasan.Kerjasama yang kemudian
disebut Asia Pacific Carbon Market Roundtable (APCMR) kemudian mempertimbangkan
kemungkinan-kemungkinan penyamaan standar, kerjasama dalam perencanaan pasar karbon
di kawasan Asia Pasifik, dan membuka peluang untuk diskusi pengembangan karbon
multilateral sebagai dasar negosiasi di UNFCCC
3. Kerjasama secara bilateral dengan negara sahabat lain
Kemungkinan untuk melakukan kerjasama bilateral seperti
dengan Jepang tidak
tertutup bagi negara sahabat lain. Kerjasama Indonesia dengan Jepang dapat diterapkan
dengan beberapa modifikasi yang diperlukan dengan negara sahabat yang berminat dalam
pengembangan pasar karbon dan pembangunan rendah karbon.
3.3.3 Pengembangan Pasar Karbon Domestik
Indonesia belum memiliki pasar karbon domestik seperti di beberapa negara lain.
Melihat perkembangan perekonomian serta kebijakan yang masih berpihak pada
pengembangan energi fosil, termasuk masih adanya subsidi energi, maka pengembangan
pasar karbon domestik masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dilakukan
dengan baik. Meskipun demikian, pengembangan satu sistem sertifikasi pengurangan emisi
berbasis mekanisme pasar maupun non pasar yang sistemnya serupa pasar karbon akan
bermanfaat bagi Indonesia sebagai dasar pengembangan pasar karbon domestik selanjutnya.
Menyadari pentingnya hal ini, DNPI melakukan inisiatif pengembangan program
GRK yang dinamakan Skema Karbon Nusantara (SKN). SKN adalah mekanisme sertifikasi
dan registrasi hasil kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca yang bersifat sukarela
(voluntary) , jadi tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mengikutinya. SKN sangat mirip
dengan Clean Development Mechanism (CDM) yang dijalankan UNFCCC. Perbedaannya
adalah pada keluaran (output) -nya.Keluaran sertifikasi CDM adalah kredit karbon yang
dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penurunan emisi dalam Protokol Kyoto,
sedangkan kredit karbon keluaran SKN tidak mempunyai kaitan
dengan kebijakan
pengurangan/pembatasan emisi gas rumah kaca apapun.Keluaran sertifikasi SKN adalah
kredit karbon yang akan dinamai Unit Karbon Nusantara (UKN). Satu UKN adalah setara
dengan penurunan satu ton karbon dioksida (CO2). Setiap UKN yang diterbitkan akan dicatat
dalam basis data registry SKN dan dapat digunakan untuk menggantikan emisi gas rumah
kaca yang dilepaskan (GHG offset ) oleh si pemilik UKN. Kepemilikan UKN dapat dipindahtangankan antara sesama pengguna registry sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan
kredit karbon di antara mereka.
SKN diharapkan mampu menarik perhatian sektor swasta yang berminat menurunkan
emisi GRK-nya karena setiap UKN yang diterbitkan adalah bukti bahwa kegiatan yang
dilakukan telah berhasil
menurunkan emisi gas rumah secara permanen, terukur dan
berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.Padatahun 2013 SKN telah memiliki enam
rancangan metodologi, dua panduan, satu calon pilot project , website yang memuat semua
perkembangannya, danmelakukan pembentukan kelembagaan secara resmi. SKN diharapkan
dapat beroperasi secara penuh di tahun 2014, sehingga Indonesia akan memiliki satu opsi
lagi dalam hal mekanisme pengurangan emisi guna mencapai target nasional. SKN ini dapat
juga difungsikan untuk memenuhi komitmen nasional Indonesia dalam pengurangan emisi
sebesar 26% pada tahun 2020 karena selama pembeli dan penjual UKN adalah entitas
Indonesia maka penurunan emisi yang dihasilkan adalah upaya domestik Indonesia.
Mekanisme SKN juga dapat digunakan apabila pemerintah ingin memberikan insentif pada
perusahaan atau entitas yang sudah melakukan penurunan emisi dan ingin mendaftarkannya
sebagai bagian dari komitmen nasional
3.2 Pelaksanaan Perdagangan Karbon di Indonesia
Balitbang Kementerian Kehutanan dengan diawasi oleh lembaga donator asal Jepang
Seven & I dan International Tropical Timber Organization (ITTO) merancang proyek yang
mendukung pelaksanaan REDD+ dengan memilih Taman Nasional Meru Betiri (TNMB).
Luas total Taman Nasional adalah ± 58.000 ha yang terdiri dari berbagai jenis vegetasi
dari pegunungan hingga pesisir. TNMB kaya akan keanekaragaman hayati dan masyarakat
yang tinggal di sekitar hutan telah memberikan dampak baik positif dan negatif terhadap
kelestarian hutan. TNMB memenuhi syarat untuk proyek REDD+ karena kawasan ini telah
mengalami deforestasi dan degradasi yang tidak terencana. TNMB telah dipilih sebagai
tempat untuk kegiatan demonstrasi (DA) dari REDD melalui proyek ITTO di kawasan
konservasi, untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh standar internasional yang
berkaitan dengan kredibel, terukur, terlapor, dan terverifikasi (MRV) guna pemantauan
pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan stok karbon.
TNMB sebagai wilayah konservasi memiliki stok karbon yang relatif tinggi,
oleh karena itu metodologi untuk mendukung REDD+ terutama dalam kawasan konservasi
penting untuk di eksplorasi. Pembelajaran dari kawasan konservasi, terutama terkait
dengan aspek metodologi untuk degradasi dan konservasi akan memberikan informasi yang
berguna untuk negosiasi REDD+ di UNFCCC.
Selain sebagai penjaga ekosistem dan habitat satwa, hutan di kawasan Taman
Nasional Meru Betiri (TNMB) di Jember, Jawa Timur, akan dijadikan kawasan percontohan
perdagangan karbon dari aktivitas penanaman pohon di lokasi lahan rehabilitasi hutan dengan
menggandeng masyarakat desa.Pihak TN Meru Betiri telah menggandeng masyarakat, untuk
ikut merehabilitasi lahan kritis seluas lebih dari 4.000 hektar, dengan memberikan hak
pengelolaan lahan kepada masyarakat untuk ditanami tanaman pokok atau pohon tegakan.
Program tersebut berhasil menghijaukan kembali lahan kritis. Keberhasilan program tersebut,
bisa dikompensasikan melalui skema perdagangan karbon.Dalam program ini, ITTO
menyiapkan dana sebesar US$900,000 untuk selama 4 tahun (Januari 2010-Desember 2014).
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Pengurangan gas emisi merupakan sebuah konsep yang muncul dalam konferensi atau
protokol-protokol yang diadakan. Salah satunya adalah protokol kyoto yang menggagas
tentang tuntutan bagi suatu negara untuk mengurangi emisi. Menurunkan emisi gas dilakukan
dengan cara carbon trading ataupun dengan konsep REDD+. Kedua konsep ini memiliki
pelaksanaan proyek-proyek yang saling berhubungan dan diharapkan dalam protokol kyoto
pada tahun 2020 peningkatan suhu karena perubahan iklim dapat diturunkan. Dalam
melakukan pengurangan emisi, Jepang dan Indonesia melakukan sebuah kerjasama dimana
Jepang memberikan dana hibah terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan Indonesia
untuk mengurangi GRK.
Dengan dijadikannya Taman Nasional Meru Betiri di Jember menunjukkan bahwa
Indonesia menyambut baik adanya perdagangan karbon. Selain itu perdagangan karbon juga
bersifat menguntungkan bagi Indonesia ketika sudah dilaksanakan. Indonesia dapat
mendapatkan dana dari negara-negara maju yang menjadi negara donor. Dalam perdagangan
karbon di TNMB dana dari perdagangan karbon digunakan untuk melestarikan hutan dan
untuk penghasilan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam melestarikan hutan setempat.
Dengan dipelopori TNMB diharapkan dapat membuka peluang bagi wilayah lain untuk dapat
ikut serta dalam perdagangan karbon. Pada dasarnya pelaksanaan perdagangan karbon ini
dapat mencegah bencana dan perubahan lingkungan atau yang biasa disebut dengan mitigasi.
4.2 Saran
Diharapkan dalam pelaksanaan perdagangan karbon dapat didukung dengan
keikutsertaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Masih
minimnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan karbon menjadi tugas bagi
pemerintah untuk dapat mensosialisasikan secara menyeluruh terutama pada masyarakat yang
berada disekitar hutan atau lahan terbuka hijau lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
-.-. Protokol Kyoto. (online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_Kyoto, diakses pada tanggal
15 April 2016)
Wahyuni,
Dina.
2008.
Apakah
Carbon
Trading?.
(online)
(http://dinawahyuni.blogspot.co.id/2008/01/apakah-carbon-trading.html, diakses
pada tanggal 16 April 2016)
Dewan
Nasional
Perubahan
Iklim.
2013.
Mari
Berdagang
Karbon.
(online)
(http://jcm.ekon.go.id/en/uploads/files/Document%20JCM/Media/buku_carbon_i
si.pdf, Diakses pada tanggal 16 April 2016)
Mansur, Eduardo. 2011. ITTO Thematic Programme on Reducing Deforestation and Forest
Degradation
and
Enhancing
Environmental
Services.
(online)
http://redd.ffpri.affrc.go.jp/events/seminars/_img/_20110216/04_Eduardo_Mansur.pdf.
Diakses pada 16 April 2016