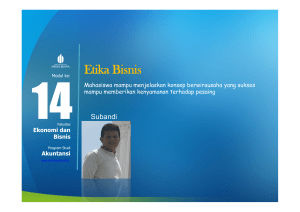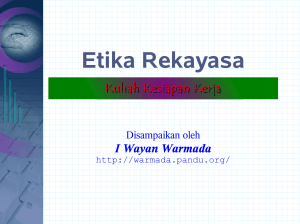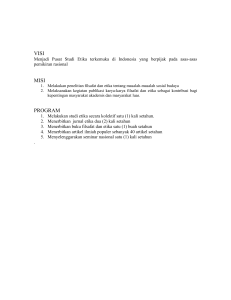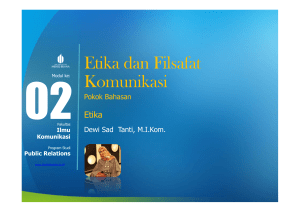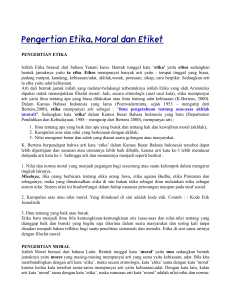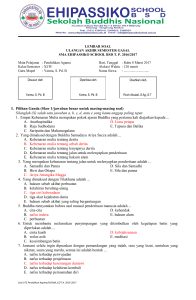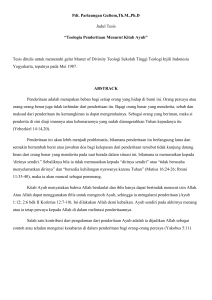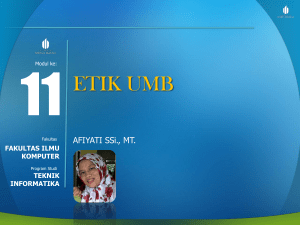pengantar - Studia Philosophica et Theologica
advertisement

PENGANTAR Studia philosophica et theologica pada nomor ini banyak mengelaborasi tema-tema filosofis teologis perbuatan manusia. Ide-ide relevan dari sebab itu berkisar pada persoalan pendidikan nilai, etika politik, etika hukum, etika perbuatan, otonomi manusia, penderitaan orang tak bersalah, keadilan, dan seterusnya. Manusia bertindak dan harus bertindak. "Harus bertindak" artinya bahwa tindakan manusia mesti memenuhi standar atau kriteria etis tertentu. Bahwa manusia bertindak, itu normal dan natural. Sudah dari sendirinya. Bertindak adalah ciri khas setiap makhluk hidup. Bahwa manusia harus bertindak, itu melukiskan eksistensi manusia secara mendalam, karena tindakan manusia mencetuskan nilai-nilai manusiawi. Tindakan manusia adalah pencetusan dirinya. Manusia secara konkret merepresentasikan diri dalam tindakannya. Maurice Blondel berkata bahwa tindakan manusia adalah representasi dirinya yang paling lengkap dan umum. Yang paling umum artinya tindakan manusia demikian representatif sehingga kenyataan bahwa manusia ditentukan oleh perbuatannya menyentuh siapa pun. Dengan perbuatannya manusia menghadirkan dirinya secara mempesonakan, memikat, dan menggugah. Tulis Blondel: "Perbuatan adalah fakta yang paling menyeluruh sekaligus konstan dalam hidupku." Blondel hendak menegaskan bahwa tindakannya adalah realitas yang paling meyakinkan perihal siapa dirinya. Jika manusia hendak mengkomunikasikan diri kepada sesamanya dalam hidup bersama atau kepada Tuhannya, dia pasti merealisasikannya dalam tindakan. Hampir tidak ditemukan sarana lain untuk itu selain melalui perbuatan. Studia menggagas tema perbuatan manusia dari berbagai sudut pandang: teologi Kitab Suci, filsafat kristiani, filsafat politik, tradisi hukum karma, etika kedokteran, dan fenomenologi agama. Di samping tema perbuatan, Studia juga menampilkan riset tentang telaah Kitab Suci oleh para penulis Karmelit abad Pertengahan. Semuanya mengkayakan refleksi kontekstual terpadu disiplin filsafat teologi, sebuah kontribusi pengkayaan seperti dimaksudkan oleh kehadiran jurnal ilmiah Studia ini. Ketua penyunting i Studia Philosophica et Theologica ISSN 1412-0674 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Hal. 68 - 167 DAFTAR ISI Pengantar ............................................................................................................. i ARTIKEL Kitab Suci dan Pendidikan Nilai B. A. Pareira .............................................................................................. 68 - 77 Ethics of Political Life. From the Christian-Philosophical Point of View Armada Riyanto......................................................................................... 78 - 89 Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum Yong Ohoitimur .......................................................................................... 90 - 105 Hukum Karma Dipandang dari Segi Etika S. Reksosusilo ............................................................................................ 106 - 119 Informed Consent dan Otonomi Manusia J. Sudarminta ............................................................................................ 120 - 127 Penderitaan Orang Tak Bersalah. Perspektif Fenomenologi Agama Donatus Sermada Kelen ............................................................................ 128 - 141 The Use of the Bible by Medieval Carmelite Writers H. Pidyarto ................................................................................................ 142 - 152 TELAAH BUKU Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Paulus Dwintarto ...................................................................................... 153 - 155 Index Studia Vol 1 ................................................................................................. 156 Biodata Kontributor ................................................................................................ 157 ii KITAB SUCI DAN PENDIDIKAN NILAI B.A. Pareira STFT Widya Sasana, Malang Abstract: The demand of value education is evident today. In Indonesia value formation occupies the certain place in the whole of frame education. Teachers, particularly those of the young people, are so much concerned with problem of value especially that of life, ethical relationship, and politics. This article elaborates the topics from biblical point of view, i.e., from the Old Testament. As the author gets involved in priestly formation in biblical territory with specialization of the Old Testament, the article shall draw closely ideas of ethical formation from the Book of Proverbs and of Ecclesiastes. Both Proverbs and Ecclesiastes are dealing with value education. Keywords: pendidikan, nilai, kaum muda, manusiawi. Persoalan pendidikan nilai ramai dibicarakan tahun-tahun terakhir ini. Perkelahian siswa-siswi antar sekolah di kota-kota besar dan banyak tingkah laku tidak terpuji yang lain membuat para pendidik di negara kita yang tercinta ini mulai berbicara kembali tentang pendidikan budi pekerti atau pendidikan nilai yang sudah lama tidak diberikan lagi di sekolah-sekolah. Persoalan kehampaan dan disorientasi nilai ini telah banyak ditanggapi oleh semua yang berkecimpung dalam pendidikan nilai untuk kaum muda.1 Persoalan ini menarik perhatian saya pula yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia Perjanjian Lama dan pendidikan para calon pelayan firman di STFT Widya Sasana Malang. Saya tidak tahu apakah dalam lokakarya-lokakarya yang diadakan pernah ditanyakan soal hubungan antara pendidikan nilai dan Kitab Suci. Saya melihat bahwa tema ini belum dibicarakan dan kiranya tidak perlu ditanyakan di sini alasannya. 1. Kitab Suci dan Nilai-Nilai Manusiawi Kitab Suci telah memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa.2 Hal ini memang belum terjadi di Indonesia, 1 2 68 Bdk. antara lain lokakarya KOMKAT tentang "Krisis Moral dan Pendidikan Nilai" yang diadakan di Denpasar dari 1-5 Oktober 1999 yang hasilnya dimuat dalam BKM = Berita Keuskupan Malang 26/5 (1999), 1016-1032; Daniel B. Kotan, "Krisis Moral dan Pendidikan Nilai", Ekawarta 20/1 (2000), 21-31; tulisan-tulisan dalam Umat Baru 33/193 (2000) yang berbicara tentang pendidikan nilai. Bdk. edisi khusus Concilium 1995/1 yang berjudul “The Bible as Cultural Heritage”. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 tetapi pasti pelan-pelan akan terjadi. Penerbitan Kitab Suci lengkap dalam bahasa Indonesia dan penggunaannya yang terus menerus dalam liturgi, studi di perguruan tinggi dan lectio divina dalam lingkungan dan kelompok pasti akan ikut menciptakan suatu bahasa dan budaya baru yang diilhami dan dibentuk oleh buku tersebut. Pendidikan nilai termasuk salah satu unsur dalam penerusan dan pengembangan kebudayaan serta mungkin merupakan unsur yang terpenting. Nenek moyang kita telah melakukan hal itu. Orang tua kita menceriterakan dongeng-dongeng ketika kita masih kecil dan memberikan nasihat ketika kita mulai lebih besar sampai menginjak umur dewasa. Pantun, gurindam dan yang semacam itu kita dengar pada peristiwa-peristiwa penting seperti perkawinan, membuka ladang, memetik panen dan perayaan-perayaan lain. Banyak kebenaran tentang hidup kita dengar dan banyak nasihat kita peroleh. Nilai-nilai hidup diteruskan. Kita dibentuk melalui hidup. Apabila kita membuka Kitab Suci, kita mungkin terkejut karena dalam buku kita yang berbicara tentang Allah ini terdapat sejumlah buku yang sangat manusiawi yang sebenarnya tidak pada tempatnya terdapat dalam Kitab Suci. Bukubuku ini ialah Ayub, Amsal, Pengkhotbah, Yesus bin Sirakh dan Kebijaksanaan Salomo yang semuanya termasuk dalam kelompok kitab-kitab yang disebut kitabkitab Kebijaksanaan. Dalam Perjanjian Baru kita miliki surat Yakobus yang sangat mirip tema dan bahasanya dengan kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab-kitab ini berbicara tentang persoalan hidup yakni bagaimana menghayati hidup ini secara benar agar menjadi orang yang berhikmat yang mencintai kebenaran, keadilan dan kejujuran (Amsal, Yesus bin Sirakh dan keenam bab pertama kitab Kebijaksanaan). Ada buku yang menyampaikan perdebatan orang-orang bijak Israel tentang salah satu persoalan yang paling memusingkan manusia yakni penderitaan khususnya penderitaan orang benar (Ayub), sedang yang lain memberikan kesaksian dari seseorang yang mencari arti dan makna hidup ini (Pengkhotbah). Buku-buku ini semuanya bergumul dengan nilai-nilai hidup yakni nilai-nilai yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi orang yang berwatak dan berhikmat. Buku-buku ini dapat dibaca oleh siapa saja karena jarang berbicara tentang TUHAN, Allah Israel. Kitab Suci adalah pula suatu buku ceritera karena hampir separo tertulis dalam bentuk ceritera. Ada macam-macam ceritera seperti ceritera pertengkaran antar perempuan, pertengkaran memperebutkan sumur, pengkhianatan dan pembunuhan, perang dan masih banyak lagi. Pada umumnya ceriteranya pendekpendek, tetapi ada juga ceritera bersambung seperti Yakub dan Esau, Yusuf dan saudara-saudaranya, Simson, Saul dan Daud serta perebutan kekuasaan dalam istana Daud. Ada pula yang dapat kita sebut cerpen atau hikayat seperti Rut, Tobit, Yudit dan Ester serta ceritera kenabian seperti Elia, Elisa, dan Yunus. Dalam ceriteraceritera semacam ini tampak watak seseorang sudut pandang penceritera dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya tentang suatu persoalan hidup. Ceritera memasukkan kita dalam dunia nilai dan penilaian. Dari uraian singkat di atas kita dapat melihat bahwa Kitab Suci adalah suatu buku yang memberikan perhatian besar pula kepada hal-hal yang bersifat manusiawi yakni kepada yang benar, mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, yang disebut B.A. Pareira, Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 69 kebajikan dan patut dipuji (bdk. Flp 4:8). Dari sebab itu, Kitab Suci dapat menjadi cermin dan sumber pendidikan nilai. Apabila hal ini terjadi, maka Kitab ini dapat memainkan peranan sebagai salah satu unsur yng membentuk kebudayaan baru di Indonesia. Tetapi bagaimana? Apa yang dikatakan kitab ini tentang pendidikan nilai? Bagaimana kita harus menggunakannya? Apa konsekuensi praktisnya untuk para pelayan firman? Persoalan-persoalan ini akan kita bahas secara singkat dalam uraian selanjutnya. 2. Kitab Amsal sebagai Buku Pendidikan Nilai Kitab Amsal adalah buku yang ditulis khusus untuk pembinaan kaum muda yakni untuk mendidik mereka menjadi orang bijak (1:1-6). Kitab ini mau membentuk manusia yang matang dalam berpikir, bijak dalam pertimbangan serta tajam dan peka dalam membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk. Kebajikan-kebajikan etis seperti memiliki kebenaran, keadilan dan kejujuran tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada pengertian dan permenungan terus menerus. Pendidikan itu tidak pernah selesai. Harus ada pembinaan terus-menerus. Tamat belajar atau mencapai gelar kesarjanaan berarti mulai belajar. Tanpa pendalaman yang terus menerus orang tidak mungkin maju dan menjadi rendah hati. Orang yang bijak ingin selalu maju dalam kehidupannya.3 Bagaimana kitab Amsal mendidik kaum muda menjadi orang bijak? Bukan melalui uraian-uraian sistematis, melainkan melalui amsal, ibarat, perkataanperkataan penuh hikmat dan teka-teki. Mengapa digunakan bentuk-bentuk ini? Karena memang inilah bentuk yang biasa digunakan dalam suatu masyarakat dengan tradisi lisan. Akan tetapi, penggunaan bentuk ini juga mempunyai makna yang lebih dalam. Hidup itu sebenarnya seperti amsal, ibarat atau teka-teki. Ada banyak hal yang tersembunyi. Kebenarannya tidak langsung ditangkap. Perlu ada pengamatan dan renungan. Ada banyak hal yang tak terduga dan mengejutkan. Ada paradoks, ada humor. Untuk mengertinya tidak cukup orang memakai akal budinya. Perlu keterlibatan dengan seluruh pribadi kita. Bentuk pembinaan yang paling utama ialah melalui amsal yakni puisi dua larik yang membentuk suatu kesatuan pengertian dan kebanyakan bersifat pernyataan (Ams 10-31). Kebanyakan amsal hanya mencatat kenyataan tanpa memberikan pertimbangan. Kami berikan satu dua contoh: "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran" (10:12); "Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya,/ tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang yang melarat ialah kemiskinannya" (10:15).; "seperti cuka bagi gigi 3 70 Tentang arti dan makna judul dan kata pengantar kitab ini, bdk. buku-buku tafsiran khususnya W. Mckane, Proverbs (Old Testament Library; London: SCM Press, 1980) dan B.A. Pareira, Pembimbing Kitab Amsal dan Tafsir Amsal 1-9 (STFT Widya Sasana Malang, 2002). Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 dan asap bagi mata,/ demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya" (10:26). Cukup tiga contoh ini yang semuanya kami ambil dari bab 10. Contoh yang pertama berbicara tentang kebencian dan kasih, yang kedua tentang kaya dan miskin dan yang ketiga tentang orang yang malas. Apa artinya amsal yang berbentuk pernyataan ini? Kedengarannya sangat dogmatis, tetapi sebenarnya memberikan ruang untuk berpikir dan menguji serta kemerdekaan untuk menentukan pilihan.4 Setiap amsal bisa memberi kesempatan kepada kaum muda untuk berdiskusi dan menguji kebenarannya dalam kenyataan hidup. Apa yang diungkapkan dalam Ams 10:15 misalnya tidak selalu benar dalam kenyataan dan hal itu diakui pula oleh kitab Amsal: "Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut" (11:4; bdk. 11:10; 10:16). Peristiwa revolusi yang menggulingkan kekuasaan tiran membuktikan hal itu. Salah satu amsal yang kami ambil sebagai contoh di atas berbentuk perbandingan. Ada banyak amsal perbandingan (10:20; 11:22 dan khususnya dalam bab 25 dan 26). Amsal mencatat persamaan yang dijumpai dalam hidup manusia dengan alam ciptaan yang lain. Manusia itu bagian dari ciptaan dan orang dapat mengenal diri sendiri melalui kehidupan sehari-hari. Kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran berdasarkan pengalaman dan bukan suatu kebenaran mutlak. Orang yang mencelakakan orang lain akan mencelakakan dirinya sendiri (26:27). Hal ini biasa terjadi dalam hidup. Kaum muda diminta untuk merenungkan hal tersebut dan menentukan sendiri apa yang harus dia lakukan . Kebenaran pengalaman bukanlah kebenaran yang mutlak.5 Pendidikan nilai adalah pendidikan untuk menjadikan orang menjadi manusia yang berhikmat, bukan manusia yang berilmu atau berfilsafat. Kaum muda harus tahu membedakan nilai-nilai dalam hidup ini dan mengadakan pilihan. Ada skala nilai dan karena itu mereka harus mempunyai prioritas nilai. Bentuk amsal yang digunakan untuk mengundang kaum muda mengadakan pertimbangan dan pilihan nilai ini ialah amsal yang disebut amsal "lebih baik". Contoh: "Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan" (12:9); "Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran, daripada penghasilan banyak, tetapi tanpa keadilan" (16:8); "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan" (17:1; bdk. selanjutnya 15:16,17; 16:19,32; 10:1,22; 21:9,19; 22:1; 25:7; 26:12; 27:4,5,6,10; 28:6,21). Dunia kita memang cenderung mengukur seseorang dari sudut kuantitatif (makin banyak) dan kualitatif (makin besar, tinggi, cepat, kuat, jauh). Dalam konteks semacam ini hampir tidak ada ruang untuk refleksi dan ugahari.6 Karena amsal-amsal "lebih baik" ini berbentuk pernyataan tanpa pendasaran, maka hanya melalui contoh-contoh yang 4 5 6 Bdk. Claus Westermann, Roots of Wisdom: The Oldest Proverbs of Israel and People (Louisville: WJK, 1955), 133. Ibid., 58-72. Ibid., 72. B.A. Pareira, Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 71 diambil dari kehidupan, prioritas nilai ini menjadi suatu tantangan yang mengasyikkan. Bentuk amsal "lebih baik" ini terdapat hampir pada semua bangsa. Orang bijak memberikan pendidikan nilai tidak hanya dengan menggunakan amsal, tetapi juga dengan memberikan nasihat yang sebagian besar dalam bentuk amsal empat larik (khususnya 22:17-24:22). Memang ini termasuk salah satu bentuk yang paling kuno dalam memberikan pendidikan. Nasihat-nasihat ini tidak pernah diberikan tanpa disertai alasannya. Motif atau alasan ini kadang-kadang diberikan dalam bentuk pertanyaan yang menunjukkan dampaknya (22:26-27). Nasihatnasihat ini biasanya diberikan dalam bentuk imperatif, tetapi ada juga dalam bentuk undangan yang penuh kasih: "Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita, jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur" (23:15-16; bdk. Yoh 14:15). Sangat menarik bahwa dalam 23:29-35 orang bijak memberikan nasihat tentang bahaya alkoholisme dalam suatu bentuk puisi yang jenaka. Penggunaan puisi dijumpai lagi dalam 24:30-34, tetapi bentuknya adalah suatu puisi naratif dan isinya tidak mengandung nasihat. Penyair hanya menceriterakan pengalamannya dan bagaimana dia merenungkan dan menarik kesimpulan dari pengalamannya tersebut. Seluruh buku pendidikan nilai yang kebanyakan menggunakan bentuk amsal ini dibuka dengan sepuluh wejangan yang dengan hangat mengundang kaum muda untuk mencari hikmat, memperlihatkan keunggulannya, menunjukkan persyaratanpersyaratannya dan mengingatkan bahaya yang dapat menggagalkan orang memperoleh hikmat (1:7-9:18). Menjadi orang berhikmat haruslah dilihat sebagai nilai yang paling tinggi dalam hidup manusia. Cinta akan hikmat itu haruslah didahulukan di atas segala sesuatu betapapun besarnya pengorbanan yang harus diberikan untuk memperolehnya. Hikmat harus dijadikan seperti kekasih kita. Mata dan hati kita harus selalu tertuju kepadanya. Memiliki hati yang demikian bukanlah hal yang gampang apalagi bagi kaum muda. Orang yang mau menjadi orang yang berhikmat harus belajar mendengarkan dari orang yang lebih berpengalaman, merenungkan apa yang didengarnya dalam hatinya dan tentu saja berusaha melaksanakannya pula. Betapapun sulitnya persyaratannya untuk menjadi orang berhikmat, kaum bijak tidak tanggung-tanggung menunjukkan semuanya itu kepada kaum muda dalam wejanganwejangan pembukaan ini. Mereka ingin mendorong kaum muda untuk mengejar hal yang paling tinggi dalam hidup ini. Mereka bahkan mengatakan bahwa "permulaan pengetahuan ialah takut akan TUHAN" (1:7). Tanah tempat bertumbuhnya pendidikan nilai ialah iman. Tanpa iman dan suasana iman orang tidak akan dapat bertumbuh menjadi manusia berhikmat yang sejati bahkan dapat gagal. Sikap hormat kepada Tuhan bukan unsur fakultatif dalam seluruh proses pendidikan, melainkan pertama dalam nilai.7 Perjalanan untuk menjadi orang berhikmat itu tidak mudah juga karena banyak godaan yang menghadang di jalan. Orang bijak menyebut dua godaan pokok. Godaan 7 72 Bdk. pula Yohanes Paulus II, Fides et Ratio, art.16-21 khususnya art.20. Akan tetapi, Paus lebih berbicara tentang hubungan akal budi dan iman dari sudut filsafat dan teologi. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 yang pertama datangnya dari teman-teman yang menawarkan alternatif hidup yang lain yang kelihatannya mengasyikkan, tetapi yang akhirnya mencelakakan (1:8-19). Godaan kedua datangnya dari nafsu manusia yang mencari kenikmatan palsu dan ada banyak godaan untuk itu khususnya yang datang dari perempuan lain (5:1-23; 6:20-34; 7:1-27). Sangat mengherankan bahwa bahaya ini sampai tiga kali dan secara cukup luas dibicarakan dalam bagian pembukaan ini. Kemungkinan besar yang masuk sekolah orang bijak pada waktu itu hanya anak laki-laki. 3. Pengkhotbah: Kesaksian Seorang yang Mencari Nilai Barang siapa pernah membaca buku ini dari awal sampai akhir pasti akan dibuat bingung dan mungkin tidak akan mau membacanya lagi. Terlalu banyak hal yang rasanya bertentangan satu sama lain, terlalu banyak hal yang sepertinya mematahkan semangat. Mau apa sebenarnya buku ini dan mengapa menjadi bagian dari Kitab Suci kita? Kitab ini sebenarnya merupakan kesaksian dari seorang yang dengan sungguh-sungguh mencari arti dan makna hidup ini.8 Dia mengamati dan merenungkan segala sesuatu yang dilihatnya, Dia mencoba mengalaminya sendiri, tetapi hatinya tidak pernah puas. Segala kebijaksanaan tradisional diujinya kembali dan rasanya tidak ada yang pasti. Hidup ini sebenarnya berwajah dua: "kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua (9:11). Dia lalu bertanya: "Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? (1:3); "Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya?” (2:23). Pertanyaan ini pertamatama memang menyangkut soal keuntungan, tetapi pada dasarnya menyangkut soal nilai. Hakikat hidup manusia itu sebenarnya tercermin dalam alam semesta ini (1:48). Memang ada pergerakan dan permulaan baru, tetapi selalu diulang hal yang sama. Sungai terus mengalir ke laut, tetapi laut tidak menjadi penuh. Apa artinya hal itu? Apa gunanya? Manusia juga terus menerus melihat dan mendengar, tetapi dia tidak pernah puas. Pernyataan Pengkhotbah ini kedengarannya berat sebelah, tetapi perlu diperhatikan bahwa orang bijak ini sebenarnya mau menekankan salah satu aspek dari hidup manusia yakni terus menerus berjerih payah, tetapi tidak ada hal yang pasti.9 Lalu bagaimana harus menghayati hidup ini? Tidak lain daripada menerima kenyataan ini sebagai apa adanya, sebagai berasal dari tangan Tuhan. Hal ini diungkapkan dalam puisinya yang terkenal tentang soal waktu (3:1-8,9-11,12-15). 8 9 Bdk. William P.Brown, Character in Crisis (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1996), 120-150). Bdk Roland Murphy, Ecclesiastes (WBC 23A; Dallas" Word Books, 1992), 9. B.A. Pareira, Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 73 Alangkah indahnya kalau semuanya dilakukan tepat pada waktunya! Tetapi siapa selalu dapat melakukan hal itu? Lalu apa nilainya kitab Pengkhotbah ini dan bagaimana hubungannya dengan pendidikan nilai? Kitab ini dapat dikatakan merupakan kesaksian dari seorang yang "gagal" menemukan hikmat, tetapi yang akhirnya menemukannya secara baru. Dia membongkar untuk membangunnya kembali. Kitab ini mengingatkan setiap orang yang mempunyai cita-cita dan rencana besar bahwa kegagalan termasuk dalam hakikat hidup manusia. Tidak adanya kemajuan tidak boleh membuat orang putus asa. Pengkhotbah membuktikan bahwa "sarana atau cara dan tujuan, usaha dan keberhasilan, kerja dan mencapai sesuatu tidak harus selalu berhubungan dalam hidup yang nyata ini. Mencapai suatu tujuan, yang setiap tujuan dapat sama seperti menjaring angin."10 4. Ceritera dan Pendidikan Nilai Kitab Suci kita penuh dengan ceritera-ceritera (bukan sejarah !). Ada macammacam ceritera sebagaimana ada macam-macam pengalaman hidup. Ada ceritera yang sangat teologis di mana keterlibatan Allah sangat kuat, tetapi ada pula ceritera yang sangat manusiawi di mana keterlibatan Allah hampir tidak tampak atau bahkan tidak tampak sama sekali. Muncul pertanyaan mengapa Kitab Suci kita begitu penuh dengan ceritera dan apa sebenarnya tujuannya? Berceritera termasuk bagian dari hidup manusia.11 Manusia adalah makhluk yang tahu berceritera. Dengan berceritera orang membagikan pengalamannya, tetapi berceritera terjadi hanya antara orang-orang yang sudah saling mengenal. Berceritera menjadi lancar dan mengasyikkan apabila ada persamaan perhatian dan kepentingan dan antara orang-orang yang saling mempercayai dan mencintai. Tidak semua orang tahu berceritera apalagi menulis ceritera. Seorang penulis ceritera (sastrawan) juga membagikan pengalamannya karena dia adalah seorang penceritera. Dia berceritera, tetapi ceriteranya ini adalah suatu dialog dengan dunia yang lebih luas di mana dia hidup. Dia bergulat dengan nilai-nilai yang dihayati suatu masyarakat dan dia mau berdialog dengan mereka melalui peran-peran yang ada dalam ceriteranya. Dia mengemukakan suatu persoalan dan mempunyai suatu pandangan tentang persoalan tersebut, tetapi tokoh-tokohnya juga memiliki pandangannya masing-masing. Dia berceritera dengan keahlian seorang penceritera sehingga kita terlibat dalam persoalan tersebut. Ceritera memasukkan kita dalam dunia nilai-nilai kehidupan dan membentuk sikap dan pandangan kita. Makin kuat suatu ceritera, makin kuat pula dampaknya. 10 11 74 William P. Brown, op.cit., 150. Bdk. Claus Westermann, Genesis 12-36 (London: SCPK, 1985) 44-50. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Ceritera mau menyampaikan kebenaran tentang suatu persoalan dalam kehidupan ini, tetapi sangat kerap bersifat ambigu. Tafsirannya bisa banyak dan bisa sangat berbeda serta berseberangan satu sama lain.12 Ceritera membangkitkan percakapan dan menimbulkan diskusi. Tujuannya ialah untuk membentuk persaudaraan dan bukan perpecahan. Kebenaran-kebenaran kehidupan itu tidak selalu jelas. Oleh sebab itu, manusia diundang untuk mencarinya bersama-sama. Kiranya sekarang menjadi jelas mengapa Kitab Suci kita mengandung begitu banyak ceritera dan ceriteranya juga bermacam-macam. Kitab Suci kita adalah suatu buku kehidupan. 5. Penggunaan Kitab Suci dalam Pendidikan Nilai. Kitab Suci memberikan perhatian besar kepada pendidikan kaum muda untuk menjadi manusia yang bijak, berbudi luhur dan berwatak. Melalui amsal, ibarat, kata-kata penuh hikmat, teka-teki, nasihat, wejangan, puisi, kesaksian dan ceritera. Kaum muda diundang untuk memahami kebenaran-kebenaran hidup ini, merenungkan rahasianya dan memutuskan apa yang harus dia lakukan. Hidup sejati terletak di dalam menjadi manusia yang berhikmat. Bagaimana sekarang kita menggunakan buku ini untuk pendidikan kemanusiaan kaum muda kita sekarang?13 Tidak gampang, tetapi justru di sinilah terletak tantangan bagi para pembina di lapangan untuk menggunakan buku ini secara kreatif. Dia harus tahu menggunakan buku ini sebagai cermin untuk melihat persoalan-persoalan kaum muda sekarang dan bagaimana memberikan pendidikan nilai. Dia harus menanyakan apakah bentukbentuk pendidikan yang digunakan oleh orang bijak pada zaman dahulu dalam suatu kebudayaan dengan tradisi lisan masih bisa digunakan sekarang ini dan bagaimana cara menggunakannya. Nenek moyang kita dan para sastrawan kita pada zaman sekarang juga berkecimpung dengan persoalan nilai. Persoalannya ialah bagaimana dua dunia ini bisa dipertemukan. Di samping itu Kitab Suci juga harus menjadi sumber pendidikan nilai. Persoalan-persoalan besar tentang hal nilai dan kemanusiaan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang bukan belum dikenal oleh orang-orang pada zaman Kitab Suci 12 13 Renungan Goenawan Mohamad tentang Dina dalam Tempo, edisi 12, 18 Juni 2000. 138 dapat diambil sebagai contoh. Ceritera tentang pembantaian orang-orang Sikhem secara licik oleh anak-anak Yakub karena Hemor telah mencemari Dina saudari mereka (Kej 34) menimbulkan pertanyaan: "Bagaimana mungkin Kitab Suci itu -di kalangan Kristen disebut Perjanjian Lama- menceriterakan dengan tanpa risih laku yang licik dan brutal orang-orang pilihan Tuhan? Siapkah Tuhan dengan dalih untuk membiarkan sikap yang sewenang-wenang: …" Penyair dan sastrawan besar ini mengemukakan pendapat seorang guru besar ilmu hukum di Amerika yang mengatakan bahwa Tuhan juga mencari keadilan bersama manusia. G. Mohamad lalu bertanya: "Tetapi dengan Tuhan yang seperti itu, siapakah yang akhirnya menentukan?" Tema pendidikan nilai ini kami batasi pada kaum muda yakni mulai dari anak-anak sampai kaum muda yang menginjak usia dewasa. B.A. Pareira, Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 75 dan betapa mereka menggeluti dan membicarakan sejumlah persoalan secara amat mendalam (misalnya hal penderitaan, bicara dan diam, kejujuran, keadilan dan kebenaran). Kita dapat belajar banyak dari para pengarang Kitab Suci. Di samping itu kaum muda kita harus dididik untuk belajar berkontak dengan Kitab Suci. Bagaimana caranya itu adalah persoalan seorang pembina yang harus belajar dari praktek. 6. Penutup Menjadi pendidik itu bukan soal gampang khususnya karena pendidikan itu juga harus menyangkut persoalan pembinaan nilai. Banyak persoalan kita hadapi. Kita diminta bukan hanya mempersiapkan orang menjadi manusia yang berilmu dan berfilsafat, melainkan pula yang siap menghadapi hidup ini dengan segala persoalannya sebagai manusia yang berwatak. Anak didik harus menjadi manusia merdeka yang mencintai segala sesuatu yang baik, benar dan indah. Bagaimana? Kitab Suci menunjukkan bahwa ada banyak jalan dan bagi orang yang mempelajari Kitab ini dengan sungguh-sungguh dia tahu bahwa dia banyak ditolong untuk menggeluti persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa kita sekarang dalam hal pembinaan nilai. Buku ini memang sudah sangat kuno, tetapi bisa menjadi baru bagi orang yang percaya bahwa Roh yang berdiam di dalam dirinya akan memberitakan kepadanya hal-hal yang akan datang (bdk. Yoh 16:13). Kitab Suci yang telah memainkan peranan dalam pembentukan kebudayaan Eropa dapat juga ikut membentuk kebudayaan bangsa kita. Akan tetapi, semuanya itu bergantung pada kita juga. BIBLIOGRAFI Pareira, B.A., Pembimbing Kitab Amsal dan Tafsir Amsal 1-9, Malang: STFT Widya Sasana Malang, 2002. Westermann, Claus, Genesis 12-36, London: SCPK, 1985. ---------, Roots of Wisdom; The Oldest Proverbs of Israel and People, Louisville: WJK, 1955. Kotan, Daniel B., "Krisis Moral dan Pendidikan Nilai", Ekawarta 20/1 (2000). Lokakarya KOMKAT tentang "Krisis Moral dan Pendidikan Nilai" yang diadakan di Denpasar dari 1-5 Oktober 1999 yang hasilnya dimuat dalam BKM = Berita Keuskupan Malang 26/5 (1999). Murphy, Roland, Ecclesiastes, Washington: Dallas Word Books, 1992. McKane, W., Proverbs (Old Testament Library), London: SCM Press, 1980. Brown, William P., Character in Crisis, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1996. 76 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Paulus, Yohanes II, Fides et Ratio, Ensiklik 1998. Majalah: Concilium 1995/1 yang berjudul "The Bible as Cultural Heritage". Tempo, edisi 12, 18 Juni 2000. Umat Baru 33/193 (2000) yang berbicara tentang pendidikan nilai. B.A. Pareira, Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 77 ETHICS OF POLITICAL LIFE - From the Christian-Philosophical Point of View Armada Riyanto STFT Widya Sasana, Malang Abstract : Sejak tata hidup bersama tampil dalam apa yang disebut polis, pergumulan politik merupakan pergumulan seputar bagaimana hidup bersama diorganisasi. Filsafat politik adalah filsafat yang mempromosikan nilai-nilai etis dalam penataan hidup bersama. Semangat peradaban Yunani awali memposisikan problem politis identik dengan problem etis. Hukum, keadilan, hak, kesetaraan, dan seterusnya adalah problem politis sekaligus etis. Artikel ini menggagas relasi antara politik dan etika dalam cakrawala pandang filsafat kristiani. Dengan filsafat kristiani dimaksudkan terutama ajaran para Paus yang dihimpun dalam dokumen-dokumen Social Teaching of the Church (Ajaran Sosial Gereja). Filsafat kristiani tidak membela nilai-nilai iman kristiani secara eksklusif melainkan nilai-nilai kebenaran etis universal manusiawi. Artikel merupakan elaborasi filosofis tema-tema pergumulan filsafat politik dan tanggapan Gereja. Keywords : politics, ethics, nature, natural law, right, obligation, power. The meaning of politics and its meaningful character is as evident today as it always has been since the time when political philosophy came to light in Athens. All political action aims at either preservation or change. When desiring to preserve, we wish to prevent a change to the worse; when desiring to change, we wish to bring about something better. All political action is then guided by some thought of better and worse.1 All political action has then in itself directedness towards knowledge of the good: of the good life, or of the good society. For the good society is the complete political good. 1. Tracing the relationship between political action and morality The classical theorists (especially Plato and Aristotle) strive to articulate what is called the "natural character" of man. "Natural" is here understood in contradistinction to what is merely human, all too human. A human being is said to be natural if he is guided by nature rather than by convention, or by inherited opinion, or by 1 78 Leo Strauss, What is political philosophy, Chicago & London 1988, 10. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 tradition. In the classical thought, the political action links closely with political virtue. In Plato the political action begins from the individual itself. A man is just if each of his parts does its work well and thus the whole is healthy (Republic, 444 d,e). The soul is in good order if each of its three parts (reason, spiritness, desire) has acquired its specific virtue, and as a consequence of this the individual is well ordered toward his fellow men and especially his fellow citizens.2 For Aristotle the state exists for the good life. Its goal or end (telos) is the well-being of its citizens. It is very easy to infer from this that the government should legislate for the good life, and that all citizens should have their well-being underwritten by state action. The ideal citizen for Aristotle is the virtuous citizen. The moral consideration of the political action in Aristotle is teleological -- that is, it has a telos, the virtue. Kant's central political conviction is that morality and politics must be related, since true politics cannot take a single step without first paying homage to morals. Morality and public legal justice must be related in such a way that morality shapes politics -- by forbidding war, by insisting on "eternal peace" and the rights of man -- without becoming the motive of politics (since according to Kant politics cannot hope for good will). Descartes does not think of any political action. Yet he breaks the old way of thought by his modern revolutionary cogito ergo sum (I think, therefore I am). By the word cogito (I think), I understand all that of which we are conscious as operating in us. And that is why not only understanding, willing and imagining but also feeling are here the same thing as thought. It is the first and most certain existential judgment.3 From this modernism of Descartes (who is said to be the first modern philosopher) the new era of the modern political thoughts begins with their first maestros, Machiavelli, Thomas Hobbes, John Lock and Rousseau. Machiavelli (is said to be the founder of the modern political thought) tries to effect a break with the whole tradition of political philosophy. He compares his achievement to that of men like Columbus. He claims to have discovered a new moral continent (of political action). The classical or traditional approach was based on the assumption that morality is something substantial: that is a force in the soul of man. He says that it was ineffective especially in the affairs of states and kingdoms. Against this classical assumption Machiavelli argues: virtue can be practiced only within society; ordinary men must be habituated to virtue by laws, customs and so forth. While the original educators, the founders of society, the prince cannot have been educated to virtue. He says that the founder of Rome was a fratricide. Man is not by nature directed toward virtue. And just as man is not by nature directed toward virtue, he is not by nature directed toward society. By nature man is radically selfish. One cannot define the good of society or the common good in terms of virtue. For Machiavelli, virtue is nothing but civic virtue, patriotism or devotion to collective selfishness.4 In him the political action should be done without moral judgments. 2 3 4 David Miller e.a (eds.), The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Oxford 1993, 374. Frederick Copleston, S.J., A History of Philosophy Vol. IV, New York 1985, 91. Leo Strauss, What is Political Philosophy, 42. Armada Riyanto, Ethics of Political Life 79 Hobbes takes a magnificent correction to Machiavelli. According to Professor Leo Strauss, Hobbes's correction of Machiavelli consists in a masterpiece of prestidigitation. Machiavelli wrote a book called On The Prince; Hobbes wrote a book called On The Citizen; i.e. Hobbes chose as his theme, not the practices of kingdoms and states, but rather the duties of subjects. He demands that natural right be derived from the state of nature: the elementary or primary wants or urges. These primary urges are of course selfish, that is, the desire for self-preservation. Or, in other word, it can be expressed negatively, the fear of violent death.5 This means that not the glitter and glamour of glory (Machiavelli) or virtue (classical theoriests) but the terror of fear of death stands at the cradle of civil society. A strong government therefore should be established in order to avoid the fear of violent death. The fear of violent death then turns into fear of government. Such a government should be a Leviathan, which is the "artificial man" with an absolute sovereignty to be feared of. In the consideration of Leo Strauss, whereas the pivot of Machiavelli's political teaching was glory that of Hobbes's is power. Power is infinitely more business like than glory. Power is the objective necessity. Power is morally neutral. In other word, we can say that in Hobbes, political action becomes the "top" of all moral judgments. After Hobbes, John Locke emerges brilliantly. Locke took over the fundamental scheme of Hobbes and changed it only in one point. He realized that what man primarily needs for his self-preservation is less a gun than food, or more generally, property. Thus the desire for self-preservation turns into the desire for property, for acquisition, and the right to self-preservation becomes the right to unlimited acquisition. The starting-point of Locke's political philosophy is that by nature human beings are equal and therefore nothing can put anyone under the authority of anybody else except his own consent. He makes use of the idea of a State of Nature - that is, the idea of men living together, without a common superior on earth, subject only to the dictates of natural law, until such time as they move voluntarily into political society. Natural law, according to Locke, constitutes and protects rights of life, liberty, and property; it requires men to keep their promises and to do what they can to secure the well-being of others; and it empowers them to punish transgressions.6 In Locke the political action links more closely with the natural law. The concept of natural law becomes something like a basis for political action. Rousseau revises his predecessors' opinion with the concept of general will. In Hobbes's and Locke's schemes, the fundamental right of man has retained its original status within civil society: natural law remains the standard for positive law; there remains the possibility of appealing from positive law to natural law. The appeal of Hobbes and Locke -- according to Rousseau - is ineffective. Rousseau argues that civil society must be so constructed as to make the appeal from positive 5 6 80 Cf. E. Armada Riyanto, Right and Obligation in Thomas Hobbes, Rome: The Gregorian University 1999, Chapter III. David Miller e.a. (eds.), The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, 293. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 law to natural law utterly superfluous. Rousseau expresses this thought as follows: the general will, the will of a society, in which everyone subject to the law must have had a say in the making of the law, cannot err. The general will, the will immanent in societies of a certain kind, replaces the transcendent natural right. Rousseau's political principles then are based on the concept of the general will. Rousseau therefore traces the foundations of the law and political society itself to the general will -- that is, the citizen body acting as a whole and freely adopting rules that will apply equally to each individual. According to Leo Strauss there are difficulties in Rousseau's doctrine of general will. For, such a concept lets one say that Rousseau's doctrine of the general will is a juridical, not a moral doctrine, and that the law is necessarily more lax than morality. One might illustrate this distinction by referring to Kant who declares in his moral teaching that every lie, the saying of any untruth, is immoral, whereas Rousseau declares in his juridical teaching that the right of freedom of speech is as much the right to lie as the right to say the truth.7 2. Ethics of Political Life in the Catholic Teachings Though the Church does not have (and indeed should not identified with) any political doctrine, system, and ideology, she must not keep silent in the midst of political problems of the world. She ought to be free to teach her whole doctrine (including her social doctrine) and pass moral judgment on political issues as required.8 "It is clear that the political community and the authority of the state are based on human nature and so belong to God's order, though the method of government and the appointment of rulers is left to the citizens' free choice. It follows that the political authority, either within the political community as such or through organization representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good […] When citizens are under the oppression of a public authority which oversteps its competence, they should still not refuse to give or do what is objectively demanded of them by the common good; but it is legitimate for them to defend their rights […] within the limits of the natural law and the law of the Gospel."9 From this excerpt we can say some fundamental elements of the true political ethics which must be considered in order to legitimate the authority: persons with their rights and dignity (the basis of human nature) which should be respected, order (it belongs to God's order), intensionality (towards the common good), 7 8 9 Leo Strauss, What Is Political Philosophy, 52. Cfr. Rodger Charles S.I. and Drostan McLaren O.P., The Social Teaching of Vatican II, Oxford 1992, 173 - 206. Gaudium et Spes, 74. Armada Riyanto, Ethics of Political Life 81 liberty (free choice), and moral obligation (not refuse to give or do what is objectively demanded of them by the common good […] within the limits of the natural law and the law of the Gospel). The Christian points of the ethics of political life have been formulated not only as a counter-responses to the philosophical theories (the first), but sprung also -- especially -- from the ongoing rational endeavor of actualization of the natural law, that is, the "law" which is given and engraved by God in the heart of human being (the second). A couple of these points will be asserted as the following. 2.1. Not only a counter-responses to the philosophical theories The Second Vatican Council's view of the fundamental reason why we establish political societies is quite clear. It is a positive view. We set up political communities because we want to find a fuller life through them. Individuals, families and the various groups that make up the civil community are aware of their inability to achieve a truly human life by their own unaided efforts; they see the need for a wider community where each one will make a specific contribution to an even broader implementation of the common good. Such a concept is frontally against Hobbes's argument which says that before entering into political society individuals were brutish and unsocial in the their primitive state of nature. The strong and absolute government is needed by social compact. A social compact is entered into wherein the individual surrenders his rights and the actual power of governing himself to a ruler or to the community, and receives in return the security, which the newly created state is able to insure through the use of coercive power. Hobbes's compact leaves no political right or independence in the individual. The surrender to the Leviathan State is complete. Rousseau holds that authority resides in the sovereign will of the people. The inalienable supremacy of this "general will" of the people leads to many of the evils of modern Liberalism. Locke leads to the protection of life and property too much. This leaves a maximum of freedom in the individual -- often exercised to the point of license at the expense of the common good. The culture of individualism is the very result of such a concept. The social contract theories of the State and civil authority have many errors in common. They are one in their denial of the social nature of man and the natural origin of the State. Law and authority rest on force rather than on reason. Rights and liberties rest precariously on the basis of a grant from the sovereign State or on popular will. The conflict between security and freedom is irreconcilable because the key to its solution -- the dignity and dignity of man -- is lost. More recently the anti-contractual school of thought has had its day -- and an evil day it was for the world. For Hegel (Philosophy of Right) the State is the divine idea as it exists on earth, and in it alone freedom obtains objectivity. The state is all and "exists for its own sake." As for the individual: "all the worth that the individual possesses, all spiritual reality, he possesses only through the State." Karl 82 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Marx, exponents of a materialistic and class view of society, regarded the State as nothing but an instrument of exploitation in the hands of an economically dominant class. According to Lenin, the "successor" of Marx, after the dictatorship of the proletariat seizes the State and trough its instrumentality brings about the liquidation of the economically dominant class and the advent of the classless society, the State will have no further function and will "wither away." Like communism and socialism, German's Nazism (Hitler) and Fascism (Mussolini) are based upon theories of the State anathema to the natural law teaching. These doctrines on the origin and nature of the State, civil authority and the relationship between individuals society and the State, stand condemned by the teachings of the social doctrines of the Church. 2.2. But also the ongoing actualization of the natural law The natural law is central to Catholic moral and social teachings. It is the kind of "reasoning" which "faith" informs. Perhaps the single most characteristic feature of traditional Catholic social teaching is that the Church can teach a morality and social problem which is applicable always, everywhere, and for everyone because it relies on the natural law as the basis for its teaching. The sense of natural law is neither "natural" nor is it "law." It is not "natural" in the sense that the natural moral law cannot be identified with physical, chemical, or biological laws of nature which try to express the way the natural world works. It is not "law" in the sense that is not a written code of precepts that carry public sanctions from the legislator.10 The meaning of the natural law is a law that determines what is right and wrong and that has power or is valid by nature, inherently, hence everywhere and always. Natural law is a "higher law". The advantage of using natural law is that the Church shows great respect for human goodness and trusts the human capacity to know and choose what is right. Also, by means of appealing to natural law, the Church can address its discussion and claims for the rightness or wrongness of particular action to all persons of good will, not just to those who share its religious convictions. On the political society. The Catholic teaching is that the state is a natural and necessary institution of mediate divine origin. It is a natural institution because it arises out of, and is necessitated by, the very nature of man. Individual endeavor and domestic society -- the family -- are incapable of providing all the means for a full development and right ordering of men in society. Here is the necessity of the state. Man's natural instinct moves him to live in civil society, for he cannot, if dwelling apart, provide himself with the necessary requirements of life nor procure the means of developing his mental and moral faculties. Hence, it is divinely ordained that he should lead his life -- be it family, social or civil -- with his fellow men among whom alone his several wants can be adequately supplied.11 But God has likewise des- 10 11 Richard M. Gula, S.S., Reason Informed By Faith, New York 1989, 220. Leo XIII, Immortale Dei (the encyclical on the Christian Constitution of States, issued November 1, 1885), as quoted in Francis J. Powers, C.S.V. (ed.), Papal Pronouncements on the Political Order, 21. Armada Riyanto, Ethics of Political Life 83 tined man for civil society according to the dictates of his very nature. In the Creator's plan, society is a natural means which man can and must use to reach his destined end. Society is for man and not vice versa. This is not to be understood in the sense of liberalistic individualism, which subordinates society to the selfish purpose of the individual, but only in the sense that by means of an organic union with society and by mutual collaboration the attaining of earthly felicity is placed within the reach of all. Furthermore, it is a society, which affords the opportunity for the development of the entire individual and social gift bestowed on human nature. These natural endowments have a value surpassing the immediate interests of the moment, for they reflect in society the divine perfection, which would not be the case if man were to live alone.12 On the civil authority. Authority, too, is an attribute of man's social nature. It is not the result of a contract or compact, of convention or of force; it is not even the result of sin. Man in society needs naturally authority and could not live an ordered life without it. Force or coercion is an incident of authority, but authority is much more than force. Its real sanction is reason and its chief function is directive. Authority is an indispensable element in political society since political society is a union of citizens who co-operate with their acts for the common good. Where there is a multitude, co-ordination and harmonious operation for the common good can only be arrived at if there be present a directive principle, without which there would be confusion and anarchy. This subordination is the universal law of nature. The welfare of man are subordinated to the control of his higher faculties of will and intellect.13 The efficient cause of authority in itself comes from God through natural law. Thus authority is derived from the same source from which comes society. God by willing mankind with all that is required by human nature also wills society. If God wills society for the maintenance and the perfection of mankind, He must likewise will political authority without which society could not be maintained much less reach its final end. If society is willed by God, certainly authority is also willed by God in the sense that it is from the same law of nature of which God is the author. The efficient cause of authority, that which brings it into existence, therefore is the will of God who created man and gave being to what man needed according to his nature; authority comes from God through natural law as do the other natural rights -- rights which are but the rational formulation of a natural inclination.14 Man therefore has a natural right to society and society is thus constituted in accordance with human nature and with natural rights. On the political obligation. As men are by the will of God born for civil union and society, and as the power to rule is so necessary a bond of society that, if 12 13 14 84 Pius XI, Divini Redemptoris (the encyclical on Atheistic Communism issued March 19, 1937), Ibid., 22. Cfr. Wilbur F. Trewik, The Political Theory of the Papacy as expressed in the Encyclicals of the last hundred years (Roma: Dissertationes ad lauream in Facultate Philosophiae apud Pontificium Athenaeum Angelicum de Urbe, 1955), 8. Cfr. Leo XIII, Diuturnum (the encyclical on Civil Government), in Francis J. Powers, C.S.V., (ed), Op.cit., 23. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 it were removed, society must at once disintegrate, if it were removed, society must at once disintegrate, it follows that from Him who is the Author of society has come also the authority to rule, so that whosoever rules, he is the minister of God. Wherefore, as the end and nature of human society so requires, it is tight to obey the just commands of lawful authority, as it is right to obey the just commands of lawful authority, as it is right to obey God who rules all things, and it is most untrue that the people have it in their power to cast aside their obedience whenever they so please.15 Foremost in this office comes the natural law, which is written and engraved in the mind of every man; and this is nothing but our reason commanding us to do right and forbidding sin. Nevertheless all prescriptions of human reason can have force of law only insofar as they are the voice and interpreters of some higher power on which our reason and liberty necessarily depend, for since the force of law consists in the imposing of obligations and the granting of rights, authority is the one and only foundation of all law -- the power, that is, of fixing duties and defining rights, as also of assigning the necessary sanctions of reward and chastisement to each and all of its commands. But all this, clearly, cannot be found in man, if, as his own supreme legislator, he is to be the rule of his own actions. It follows, therefore, that the law of nature is the same thing as the eternal law, implanted in rational creatures, and inclining them to their right action and end; and can be nothing else but the eternal reason of God, the Creator and Ruler of all the world.16 On liberty. In Leo XIII we know that true liberty is based on eternal law of God. Leo did not say anything yet about democracy as the ideal government that can guarantee liberty. "It is manifested that the eternal law of God is the sole standard and rule of human liberty, not only in each individual man but also in the community and civil society which men constitute when united. Therefore, the true liberty of human society does not consist in every man doing what he pleases […], but rather in this, that through the injunction of the civil law all may more easily conform to the prescriptions of the eternal law. Likewise, the liberty of those who are in authority does not consist in the power to lay unreasonable and capricious commands upon their subjects […], but the binding force of human laws is in this, that they are to be regarded as applications of the eternal law, and incapable of sanctioning anything which is not contained in the eternal law, as in the principle of all law. St. Augustine most wisely says: "I think that you can see, at the same time, that there is nothing just and lawful in that temporal law, unless what men have gathered from this eternal law."17 On the nature of freedom and equality in a true democracy. Pius XII did not only mention clearly democracy as the ideal government, but also asserted the liberty or freedom and equality are possible only in the true democracy. "In a people worthy of the name, those inequalities which are not based on caprice but on 15 16 17 Leo III, Humanum Genus (the encyclical on Freemasonry issued April 20, 1884), Ibid., 28. Leo XIII, Libertas Praestantissimum, (the encyclical on Human Liberty) Ibid., 53. Leo XIII, Libertas Praestantissimum (the encyclical on Human Liberty), Ibid., 156. Armada Riyanto, Ethics of Political Life 85 the nature of things -- inequalities of culture, possessions, social standing -- so long as they are not prejudicial to justice and mutual charity, do not constitute an obstacle to the existence and the prevalence of a true spirit of union and brotherhood. On the contrary, so far are they from impairing civil equality in any way, that they make evident its true meaning, namely, that in the eyes of the State everyone has the right to live his own personal life honorably in the place and under the conditions in which the designs of Providence place him. In contrast with this portrayal of the democratic ideal of liberty and equality in a people's government conducted by honest and farseeing men, what a spectacle is that of a democratic state left to the whims of the masses! Liberty, which is really a moral duty of the individual, becomes a tyrannous claim of freedom to give free rein to one's impulses and appetites at whatever cost or detriment to others. Equality degenerates to a mechanical level and becomes a colorless uniformity in which the sense of true honor, of personal activity, of respect for tradition, of dignity -- in a word, of all that gives life its worth -- gradually fades away and disappears."18 Equality and Liberty in a recent study. According to Giovanni Sartory who offers a well-done study of the theory of democracy revisited,19 liberty can be brought under four classes or types: (a) juridico-political equality; (b) social equality; (c) equality of opportunity as equal access, i.e. equal recognition to equal merit and equality of opportunity as equal start (or equal starting points), i.e., as equal initial material conditions for equal access to opportunities; (d) economic equality, that is, either the same wealth to each and all, or state ownership of all wealth. In accordance with the criteria of justice that inspire these equalities, and with the powers that correspond to them, those four types can be interpreted as follows: (a) to everyone the same legal and political rights, that is, the legalized power to resist political power; (b) to everyone the same social importance, that is, the power to resist social discrimination; (c) to everyone the same opportunities to rise, that is, the power to put one's own merits to account; and to everyone an adequate initial power (material conditions) to acquire the same ability and rank as everyone else; (d) to no one any economic power. On the criteria of equality. Sartory asserts there are a couple of criteria of equality: (1) the same to all, i.e. equal shares (benefits or burdens) to all; (2) the same to sames, i.e. equal shares (benefits or burdens) to equals and therefore unequal shares to unequal, and for this there are four prominent subcriteria: (a) proportionate equality, i.e. shares monotonically allocated in proportion to the degree of extant inequality; (b) unequal shares to relevant differences; (c) to each according to his merit (desert or ability); (d) to each according to his need (basic or otherwise). The first criterion -- equal shares to all -- is eminently the principle of the legal systems that provide equal laws and equality under the law. What are the limits of the first criterion? Sartory explains that in order to be what it is, a law not only imposes 18 19 86 Pius XII, Christmas Message 1944, in Ibid., 52. Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited, New Jersey1987, 344-361. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 hardships but eventually unjust hardships (because general rules cannot do justice to individual cases). Laws are not, cannot be, person-regarding, i.e. sensitive to persons and their differences. On the other hand, the counterpart of this insensitivity is that the criterion cannot be, so to speak, gerrymandered. When we say to each the same, there is no way of manipulating or twisting such a principle. The second criterion -- according to Sartory -- is no less cogent, or less defensible, than the first. The second also turns out to have a far more extensive application than the first. Its advantage consists of its flexibility, which allows not only that justice be done to subgroups but also, as we shall see, that equal results be attained. One might say that equality presupposes freedom. But it does not declare a value priority or that one is more important than the other. It is simply pointing out to a procedural linkage, namely, that liberty must materialize, in time and in fact, before equality. Liberty come first, then, on the simple consideration that equality without freedom cannot even be demanded. There is, to be sure, an equality that precedes freedom and bears no relation to it; but it is the equality that exists among slaves, among individuals who are equal either in having nothing or in counting for nothing, or both, equal in being totally subjected. In one sense, equality conveys the idea of sameness. In other sense, equality goes to connote justice. Two or more persons or objects can be declared equal in the sense of being -- in some or all respects -- identical, of being the same, alike. But justice too calls on the idea of equality. Aristotle says: "Injustice is inequality, justice is equality." 3. Brief Conclusion From the tracing of the philosophical ideas on the political action, we know that the questions were explored exhaustively consisted in the problems of regime, power, origin of the civil society with its political power, and their moral consequences. We have seen that elements of the social tradition of the Church sprung from the natural law were consolidated against the background of classical pagan philosophy and practical political developments over many centuries. St. Thomas (of whom -- we can say -- the social, philosophical, and theological teaching of the Church flows) presents us with the essential elements -- that political society grows out of human nature according to God's design, that the people have the right to choose their rulers and form of government, monarchy, aristocracy or democracy as they wish, though the best seems to be a form which incorporates elements of all three. Whatever the form of government, it must be for the common good in accordance with the divine eternal, divine revealed and natural laws -- which have their authoritative interpreter in the Church. Rulers who seriously neglect their duty of caring for the common good can be challenged and, in extreme circumstances, deposed. Yet, the today question of political life in the world is changing and growing more complexly than just problem of the origin of political authority. From Sartori's Armada Riyanto, Ethics of Political Life 87 study we know that the urgent problem remains in equality and justice. The recent socio-political problem jumps from "what the power is" to "how the power can be effective." In other word, the very problem is how to concretize justice and equality into practice. The story of the developing thought of the social teaching of the Church shows that after Medellin (the second meeting of the General Conference of Latin American Bishops at Medellin in 1968) the word "liberation" was used increasingly in Episcopal documents. And it angues for a freedom, a liberty denied in the present state of affairs. The crucial question arises whether it is good or not to use violence in order to gain liberty and justice.20 From these new phenomena, it is evident that social and philosophical studies of the Church should grow unceasingly. BIBLIOGRAFI Charles, Rodger S.I. and Drostan McLaren O.P., The Social Teaching of Vatican II, Oxford & San Francisco: Plater & Ignatius Press, 1992. Copleston, Frederick, S.J., A History of Philosophy Vol. IV, New York: An Image Books, 1985. Gula, Richard M., S.S., Reason Informed By Faith, New York: Paulist Press, 1989. Hobbes, Thomas, Leviathan, (ed. Edwin Curley), Cambridge: Hackett, 1994. Kant, Immanuel, "Introduction to Metaphysics of Morals" dan "Introduction to the Elements of Justice," dalam The Metaphysical Elements of Justice, translated by John Ladd. Indianapolis: The Bobbes-Merrill Co., 1965. Locke, John, Treatise of Civil Government, dalam Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, edited by Charles L. Sherman. New York: Appleton-Cetury-Crofts, 1937. Miller, David, ed. al (eds.), The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Oxford: Blackwell Publishers, 1993. Powers, Francis J., C.S.V. (ed.), Papal Pronouncements on the Political Order, Maryland: The Newman Press, 1952. Riyanto, E. Armada, CM, Right and Obligation in Thomas Hobbes (doctoral dissertation in the Gregorian University), Rome, 1999. Sartori, Giovanni, The Theory of Democracy Revisited, Chatham, New Jersey: Chatam House Publishers, 1987. Strauss, Leo, What is Political Philosophy, Chicago & London: The University of Chicago press, 1988. Strauss, L. - Cropsey, J., ed., History of Political Philosophy, Chicago: University press, 1963, 19873. 20 88 Cfr. Rodger Charles S.I. & Drostan Maclaren O.P, Op.cit., 246 - 247. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Trewik, Wilbur F., The Political Theory of the Papacy as expressed in the Encyclicals of the Last Hundred Years (Roma: Dissertationes ad lauream in Facultate Philosophiae apud Pontificium Athenaeum Angelicum de Urbe, 1955). Armada Riyanto, Ethics of Political Life 89 TUJUH TEORI ETIKA TENTANG TUJUAN HUKUM Yong Ohoitimur Universitas De La Salle, Manado Abstract : By the term "law" I mean system of law that exists in a political territory. Every system of law consists in some necessary elements such as basic laws or constitutions promulgated by the legislative, regulations made by the judicative, practical decrees announced by the executive. The article shall delve in the topic of ethical theory concerning the purpose of law. Why questioning ethically the purpose of law? By questioning it I try to draw what the ethical reasons of promulgating laws would be in political society. Consequently, every law should not be put into practice in a society, unless it is corresponding with that certain ethical reasons. In so doing, I shall survey the ideas of the seven political philosophers: Hobbes, Cicero, Locke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond. From this general survey, I discover that every theory has its own ethical reason which is in line with its anthropology and political philosophy. Besides, every theory finds necessary ethics in its own contemporary context. However, as Indonesia is struggling with law enforcement, it would be helpful to learn from their ethical theory of purpose of law. Keywords : hukum, politik, manusia, etika, kedamaian, keadilan. Dengan hukum di sini dimaksudkan sistem hukum yang berlaku secara sah dalam suatu teritori politis. Setiap sistem hukum paling kurang mengandung unsurunsur berikut: undang-undang atau peraturan-peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, keputusan-keputusan lembaga peradilan, tradisi dan prinsip-prinsip yang diakui oleh lembaga peradilan dengan efek yang mengikat secara legal, serta berbagai jenis lembaga hukum yang menentukan dan menjalankan prinsip-prinsip dan keputusan-keputusan legal. Oleh karena itu, setiap undang-undang atau keputusan hukum harus ditempatkan dalam bingkai sistem hukum tersebut. Dalam tulisan ini, dengan "tujuan hukum" dimaksudkan nilai sasaran atau apa yang mau dicapai melalui pemberlakuan secara sah suatu sistem hukum dalam negara atau masyarakat tertentu. Konsekuensinya, tujuan aktual suatu undang-undang atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan hakikat nilai tujuan sistem hukum. Karena itu, secara filsafati sungguh perlu direfleksikan pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi tujuan suatu sistem hukum. Tulisan ini merupakan suatu survei umum mengenai tujuan hukum menurut tujuh pemikir, yakni Hobbes, Cicero, Locke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond.1 Dari survei itu ditemukan dua hal funda1 90 Wellman, 1975:191-212. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 mental. Pertama, setiap teori menetapkan tujuan hukum sesuai filsafat manusia dan filsafat politik tertentu. Kedua, setiap teori menggagas tujuan hukum menurut konteks filsafatinya dalam jaman dan peradaban tertentu. Jika demikian, apa yang kiranya paling relevan dijadikan tujuan sistem hukum dan sasaran penegakan hukum di Indonesia dalam konteks kondisi aktual dan peradaban jaman sekarang? 1. Kedamaian dan ketertiban Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kedamaian.2 Ia bertolak dari suatu antropologi. Menurutnya, manusia dikuasai oleh dorongan-dorongan atau keinginan-keinginan irasional, bukan oleh kehendak bebas atau pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Perilaku manusia tidak diarahkan oleh nilai-nilai yang disadari atau oleh keputusan kehendak mengenai apa yang baik, melainkan oleh naluri untuk mempertahankan diri dan untuk memenuhi dorongandorongan alamiahnya. Di sini Hobbes mengesampingkan fakta kebebasan, kehendak bebas, rasionalitas, dan nilai-nilai moral yang bersumber dari pertimbangan akal budi. Itulah "keadaan alamiah" (state of nature) dari manusia. Berbeda dari Aristoteles yang menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial (zoon politikon) karena rasionalitasnya,3 Hobbes tidak menganggap sosialitas sebagai suatu karakteristik hakiki manusia.4 Secara primordial manusia tidak berhakikat sosial. "Keadaan alamiah" dicirikhaskan oleh anarki (state of anarchy), tanpa suatu organisasi politik ataupun sistem hukum. Konflik terbuka antar individu terus terjadi, karena setiap orang mengejar keinginannya yang bersumber pada tiga hal. Pertama, keinginan mendapatkan dan memiliki sesuatu mengkondisikan setiap orang untuk bersaing atau berkompetisi dengan sesamanya. Sesama dilihat sebagai lawan dan saingan yang mengancam. Kedua, rasa takut terhadap serangan dari lawan mendorong setiap orang untuk lebih dahulu memerangi sesamanya. Jadi, daripada diserang, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Ketiga, egoisme (dalam arti sikap dasar ofensif untuk mengejar kepenuhan bagi kepentingan, keinginan, dan kebutuhan diri sendiri saja) mendorong untuk mencapai kehormatan dan kemuliaan bagi diri sendiri melalui pemaksaan keinginan terhadap orang lain. Hobbes menyimpulkan, dalam state of nature, manusia melihat sesamanya sebagai serigala buas yang selalu mengancam (homo homini lupus), dan kehidupan bersama ditandai oleh perang semua lawan semua (bellum omnium contra omnes). Hidup manusiapun menjadi terasing, miskin, tak menyenangkan, brutal, dan pendek. Bertolak dari kondisi alamiah yang anti-sosial itu, Hobbes mengembangkan teori tentang perjanjian negara. Menurutnya, agar state of nature yang anarkis bisa 2 3 4 Hobbes, 1950: bab 13, 17, dan 26. Aristotle, Politics, buku I. Hobbes, Leviathan, chapter XIII. Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 91 diatasi, individu-individu mengadakan perjanjian untuk membentuk negara.5 Negara merupakan lembaga yang dibentuk oleh individu-individu. Setiap orang menyerahkan semua haknya kepada negara, sehingga negara menjadi lembaga adikuasa dan berkuasa mutlak: negara bagaikan Leviathan. Kekuasaan negara harus mutlak, karena keinginan-keinginan irasional, termasuk agresivitas atau "kebuasan" terhadap sesama manusia, hanya bisa dipadamkan oleh rasa takut terhadap kekuasaan yang lebih besar. Rasa takut dan rasa terancam individu yang satu terhadap yang lain diatasi oleh kekuatan negara. Dalam arti itu, ancaman dari negara terhadap rakyat merupakan syarat mutlak bagi terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Kekuasaan mutlak dari negara diekspresikan dalam bentuk hukum. Hukum dibentuk oleh negara, dan karena negara memiliki kekuasaan mutlak, apa yang dikehendaki oleh negara melalui hukum selalu dianggap adil. Undang-undang negara tidak pernah tidak adil. Keadilan identik dengan kepatuhan terhadap hukum negara. Hukum diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menjamin kedamaian dan ketertiban. Oleh karena itu setiap individu harus menyesuaikan perilakunya dengan hukum; hanya sejauh itu ia akan merasa aman dan terlindungi oleh negara. Sebaliknya, hidupnya akan terancam apabila ia bertindak melawan hukum. Singkatnya, memelihara kedamaian dan ketertiban merupakan tujuan hukum. Teori Hobbes boleh dikatakan bercorak realistis, karena ia mengakui fakta negatif kodrat manusia. Secara realistis, Hobbes melihat bahwa menurut kodratnya manusia memang cenderung egoistis. Selanjutnya, ia juga secara akurat menemukan bahwa kedamaian dan ketertiban merupakan tujuan penting yang dikehendaki oleh setiap negara dan masyarakat. Tidak ada satupun negara yang bisa bertahan tanpa kedamaian dan ketertiban. Keamanan dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi pengembangan kesejahteraan umum suatu masyarakat. Kehidupan setiap individu pun tergantung pada rasa aman dan damai. Untuk semua itu, hukum selalu perlu ditegakkan. Di sinilah letaknya kegamblangan dari teori Hobbes, yakni karena ia bertitik tolak dari asumsi negatif mengenai kodrat sosial manusia, maka kedamaian dan ketertiban dengan sendirinya jelas sebagai tujuan hukum. Akan tetapi, betapapun pentingnya, kedamaian harus dianggap sebagai tujuan minimal saja, dan bukan sebagai suatu tujuan yang mencukupi bagi masyarakat manusiawi. Artinya, tujuan yang sebenarnya dari suatu masyarakat atau negara bukanlah sekedar mempertahankan eksistensinya, melainkan menuju suatu eksistensi sosial di mana setiap anggota dapat mencapai kehidupan yang baik dan sejahtera. Apabila suatu negara gagal memberikan jaminan kedamaian dan kesejahteraan bagi para warganya, maka secara prinsipiil tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan eksistensinya. Konsekuensinya, negara dan sistem hukum harus mengarah kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada sekedar kedamaian dan ketertiban. Kedamaian dan ketertiban hanyalah "tujuan negatif" dari hukum, dalam arti absensi perang dan konflik terbuka. Harus terdapat sesuatu yang lain sebagai tujuan hukum. 5 92 Hobbes, Leviathan, chapters XIV-XV. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 2. Moralitas Marcus Tullius Cicero (106-43 BC), seorang Romawi pengikut Stoisisme, berpendapat bahwa tujuan kodrati dari hukum adalah moralitas. Hukum positif suatu negara (human law) dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tindakan-tindakan moral dengan memerintahkan perilaku yang secara moral baik, dan melarang perbuatan-perbuatan yang secara moral jahat.6 Perbedaan antara yang benar dan yang salah tidak bersifat konvensional, dalam arti tidak merupakan produk dari mores suatu masyarakat, tidak pula berupa keyakinan-keyakinan tertentu dari suatu bangsa atau sebuah komunitas. Diinspirasi oleh Stoisisme, Cicero berpendapat bahwa hukum moral terpatri dalam hakikat alam semesta. Hukum moral tidak lain dari hukum kodrat (natural law) yang di dalamnya Rasio ilahi memerintahkan perbuatan yang harus dilakukan dan melarang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dalam batasan itu, manusia bijaksana adalah manusia yang hidup sesuai dengan penentuan Rasio ilahi yang mengejawantah dalam Alam. Setiap orang mendapatkan sepercik Rasio ilahi yang mendorongnya kepada kebijaksanaan dan perbuatan yang benar. Namun manusia mewarisi juga kecenderungan-kecenderungan dan gairah-gairah yang dapat menjauhkannya dari perbuatan baik. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai sistem hukum yang mengarahkan dan mewajibkan para warganya untuk melakukan apa yang baik secara moral dan untuk menjauhi apapun yang jahat secara moral. Misalnya, hukum positif harus mewajibkan setiap warga negara untuk membayar utangnya dan untuk mengatakan kebenaran (tidak berdusta), karena perbuatanperbuatan ini diperintahkan oleh hukum kodrat. Sebaliknya, hukum positif harus melarang pembunuhan dan pemerkosaan, karena perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh hukum kodrat. Cicero menempatkan hukum moral dalam bingkai hukum kodrat yang merupakan pengejawantahan Rasio ilahi. Konsekuensinya, hukum moral harus bersifat rasional. Perintah dan larangan moral harus masuk akal. Hukum manapun yang menyimpang dari hukum moral harus dianggap tidak masuk akal, dan karena itu tidak bisa dibenarkan secara rasional. Jadi, apabila menurut akal sehat setiap orang yang berhutang diwajibkan untuk membayar hutangnya, maka hukum yang bertentangan dengan kewajiban itu tidak dapat dibenarkan. Begitu pula apabila hukum kodrat yang rasional melarang pembunuhan, maka hukum positif manapun harus melarang hal yang sama. Singkatnya, karena hukum moral menjadi hukum rasional, maka harus disimpulkan bahwa hanya tujuan yang rasional dari hukum positif yang sesuai dengan moralitas. Kedengarannya teori dari Cicero amat menarik, namun bukannya tanpa problem. Memang tidak diragukan bahwa dalam masyarakat manapun moralitas menawarkan standar-standar perilaku yang dengannya hukum positif dapat diuji. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa hukum selalu bertujuan pada pewajiban setiap 6 Cicero, 1928: buku I, 6-10; buku II, 4-5. Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 93 perbuatan yang baik secara moral dan pelarangan setiap perbuatan yang jahat secara moral. Sebagai contoh, tentu secara moral dianggap tidak pantas bahwa seorang anak bersikap terhadap orangtuanya tanpa rasa hormat. Namun kelancangan si anak tidak bisa dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Kalaupun ada hukum positif yang mengatur perilaku si anak, dikhawatirkan bahwa hukum tersebut tidak dapat dipaksakan (unenforceable) karena pemaksaannya bisa melanggar privasi keluarga. Suatu hukum yang unenforceable, menurut hakikatnya, akan menggerogoti penghargaan terhadap hukum itu sendiri. Hal yang sama bisa dikatakan tentang merokok. Secara medis bisa dibenarkan bahwa merokok berdampak buruk pada kesehatan si perokok. Akan tetapi tindakan merokok tidak bisa secara mutlak dilarang dengan hukum positif. Sejauh si perokok tidak merugikan atau mengganggu orang lain, misalnya, membakar barang orang lain dengan api rokoknya atau meniupkan asap rokoknya pada wajah orang lain, maka perihal merokok semestinya menjadi urusan pribadi si perokok dan tidak perlu diatur secara hukum. Jadi, walaupun merokok dianggap tindakan irasional karena merusak kesehatan, tetapi hukum yang melarang tindakan merokok bisa berarti melanggar hak individu atas kebebasan untuk hidup sesuai dengan pilihannya. Singkatnya, perbuatan yang salah secara moral tidak harus identik dengan perbuatan ilegal. Atau, luasnya wilayah moral dan wilayah hukum positif tidak sama. Jadi, tujuan hukum tidak dapat disederhanakan menjadi instrumen penyelenggaraan moralitas belaka dengan mewajibkan apa yang baik dan melarang apa yang jahat. Prinsip-prinsip dasar moral, seperti keadilan dan hormat terhadap martabat manusia sebagai person, tentu perlu menjiwai sistem hukum. Tetapi sistem hukum tidak bisa disamakan saja dengan sistem moral dan hukum positif semestinya tidak dianggap sebagai instrumen untuk menjalankan moralitas. 3. Hak-hak asasi manusia Pandangan bahwa tujuan hukum bertalian erat dengan hak-hak kodrati (natural rights), tercermin secara jelas dalam filsafat John Locke (1632-1704).7 Menurutnya, setiap individu manusia memiliki hak-hak kodrati, dan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Setiap warga negara memiliki berbagai hak legal yang didasarkan atas sistem hukum; misalnya, hak untuk memilih wakil rakyat dan hak untuk mendapatkan upah minimum yang layak. Namun sebagai manusia, setiap orang memiliki pula hak-hak kodrati, yakni hak-hak dasar sebagai manusia atau hak-hak yang tak terasingkan (inalienable rights) dari martabatnya sebagai manusia (human rights). Menurut Locke, hak-hak itu meliputi hak atas kehidupan (right of life), hak atas kebebasan (right of liberty), dan hak atas milik (right of property).8 Hak-hak tersebut bersumber dari kodrat manusia 7 8 94 John Locke, Second Treatise on Government, chapters I-III. Locke, 1937: bab 2 dan 9. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 dan independen terhadap setiap bentuk sistem hukum ataupun konvensi suatu masyarakat. Oleh karena itu, dengan kekuasaan politik yang mutlak sekalipun, tak seorangpun boleh mencabut atau menghapuskan hak-hak tersebut. Akan tetapi, penegakan hak-hak asasi bisa tidak pasti, terutama dalam kondisi sosial-politik yang anarkis atau di bawah pemerintahan tirani dan totaliter. Maka, menurut Locke, negara perlu didirikan sebagai institusi untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu warga negara. Hukum negara bertujuan untuk melindungi hidup setiap warga negara dengan melarang pembunuhan, mengamankan hak milik dengan cara melarang pencurian dan perampokan, dan menjamin kebebasan berbicara dan berserikat. Singkatnya, tujuan hukum ialah memastikan perlindungan dan penegakan hak-hak asasi. Hak-hak kodrati atau hak-hak asasi tidak diragukan sebagai nilai-nilai luhur dari martabat manusia. Kehidupan, kebebasan, dan hak milik sungguh hakiki bagi kehidupan yang baik dan beradab setiap orang. Seseorang tak akan bisa hidup tanpa kehidupannya diakui. Begitu pula kehidupan yang bermartabat sulit dibayangkan tanpa penghormatan terhadap kebebasan dan hak miliknya. Sebaliknya, hak-hak tersebut pun dengan mudah bisa dilecehkan atau disangkal. Oleh karena itu, demi kesejahteraan rakyatnya, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi dari setiap individu warga negara. Dalam batasan itu, negara didirikan untuk kepentingan warga negara, bukan sebaliknya warga negara bagi negara. Konsekuensinya, pemerintah harus menjamin dan mengembangkan kehidupan para warga negara, dan bukan mengeksploitasi atau menindas mereka. Dalam konteks inilah bisa dimengerti bahwa hukum dibuat oleh negara dengan tujuan untuk melindungi dan memastikan penegakan hak-hak asasi. Akan tetapi, dari perspektif filsafat moral, argumen di atas bisa dipersoalkan. Setiap warga negara memiliki berbagai hak, namun hak-hak tersebut umumnya adalah hak-hak legal yang dilindungi oleh hukum positif. Keistimewaan dari hak-hak legal ialah hak-hak tersebut tidak merujuk kepada suatu tujuan yang terletak di luar sistem hukum yang berlaku. Teori tentang hak-hak kodrati atau hak-hak asasi berasumsi bahwa selain memiliki hak-hak legal, setiap warga negara sebagai manusia masih memiliki lagi sejumlah hak yang sama sekali independen terhadap sistem hukum dan konvensi sosial. Bisa ditanyakan: Bukankah asumsi ini mengandung kontradiksi internal, karena "hak" menurut hakikatnya bersifat sosial dan apapun yang bersifat sosial tidak dapat dikatakan bercorak kodrati dalam arti sama sekali independen terhadap konteks sosial. Menurut hakikatnya, hak merupakan klaim yang bisa dituntut secara sah terhadap orang lain (Bertens, 1993: 178). Misalnya, saya mempunyai hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaanku. Apabila pada akhir bulan, majikanku tidak membayar upah yang menjadi hakku, maka saya akan memaksanya melalui pengadilan agar upah itu dibayar. Jadi, karena hak merupakan suatu klaim, maka setiap hak secara hakiki mengandung proses di mana si empunya hak bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Klaim tersebut akan tak berarti apabila tidak ada pihak lain yang terlibat dalam prosesnya. Menurut argumen ini, hak selalu punya konteks sosial tertentu, karena hak merupakan klaim dan masyarakat dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran klaim tersebut. Dalam arti itu, apa yang disebut "hak Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 95 kodrati" atau "hak asasi" sulit dideskripsikan sebagai hak dalam arti yang sesungguhnya, karena sifatnya yang independen terhadap konteks sosial. Konsekuensinya, sistem hukum positif tidak akan selalu mencukupi dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang bercorak independen secara kontekstual. Artinya, hukum positif hanya bisa "mendekati", tapi tidak bisa menjamin secara mutlak perlindungan hak-hak asasi manusia 4. Kebaikan umum (the common good) Menurut St. Thomas Aquinas (1225-1274), pencapaian "kebaikan umum" (bonum commune) merupakan tujuan hukum positif.9 Istilah Aquinas "bonum" sebenarnya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena kata "baik" dan "kebaikan" cenderung berkonotasi moral. Walaupun begitu, di sini "bonum" diterjemahkan sebagai "kebaikan", tetapi dalam arti yang dimaksudkan Aquinas, yakni sesuatu yang positif bagi manusia dalam rangka mencapai tujuan akhir hidupnya, yakni memandang kemuliaan Allah (visio beatifica Dei). Dalam arti itu, "kebaikan" selalu bersifat teleologis, hanya manusia yang bisa dengan kesadarannya terarah kepada kebaikan dan mencintai kebaikan.10 Kebenaran (truth) dan keadilan (justice) merupakan bentuk-bentuk partikular dari kebaikan. Dalam perspektif pengertian tersebut, sistem hukum positif harus terarah kepada kebaikan; tujuannya ialah menghasilkan kebaikan sebanyak mungkin dan mereduksi kemungkinan kejahatan sejauh mungkin. Kebaikan siapa yang harus diusahakan? Aquinas berpendapat bahwa, sebagai suatu instrumen dalam menjalankan kekuasaan publik, hukum harus memihak kebaikan umum masyarakat.11 Di satu pihak, kebaikan umum berbeda dari apa yang baik bagi seorang pribadi.12 Nama baik dan popularitas bisa menjadi contoh dari apa yang baik bagi seorang pribadi; dua hal itu tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai satu keseluruhan. Begitu pula kepentingan pribadi para penguasa sebagai pemegang kekuasaan politik negara merupakan bagian dari hal yang baik bagi pribadinya. Kebaikan umum berarti kondisi umum yang memungkinkan setiap individu warga negara untuk bisa mencapai apa yang positif bagi hidupnya sebagai manusia. Di lain pihak, kebaikan umum berbeda pula dari apa yang baik bagi umat manusia pada umumnya. Kebaikan umum suatu negara atau masyarakat berlaku hanya bagi warganya, dan tidak bagi seluruh umat manusia. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa "kebaikan" dan "kebaikan umum" berakar dalam konteks sosial tertentu. Apa yang menjadi kondisi fundamental bagi kebaikan umum dalam masyarakat yang satu, belum tentu berlaku bagi masyarakat yang lain. Dalam batasan itu, sistem hukum suatu negara harus bertujuan menjamin terwujudnya kebaikan umum. 9 10 11 12 96 Aquinas, Summa Theologica, I-II, q. 90. a.1-2; q. 92. a. 1; q. 95. a. 3-4. ST, I, q. 23, a. 7; II-II, q.34. a.1. Bdk. ST. II-II. q.64. a.3. ST. II-II, q. 42. a. 2. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Teori ini secara jelas melawan egoisme etis, yakni pandangan bahwa setiap pelaku moral harus selalu bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri. Kualitas baik dan jahat dari suatu perbuatan diukur berdasarkan efeknya terhadap kepentingan si pelaku. Menurut pandangan ini, sungguh tidak masuk akal bahwa suatu kepentingan pribadi dikorbankan demi kesejahteraan orang-orang lain. Hanya jika pengorbanan itu mendatangkan keuntungan pribadi, perbuatannya boleh dianggap baik dan masuk akal. Sebaliknya, kolektivisme ekstrim menganut paham bahwa tidak masuk akal kebaikan banyak orang dikorbankan demi kesejahteraan seorang pribadi atau demi orang-orang lain yang bukan warga masyarakat atau negara yang sama. Setiap negara atau masyarakat harus memperjuangkan kebaikan umum bagi warganya. Tetapi, dapat ditanyakan, apakah hukum suatu negara harus tidak peduli terhadap mereka yang bukan warga negara? Katakanlah bahwa hukum bertujuan hanya untuk melindungi kepentingan atau kebaikan umum, dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu saja, namun efek-efek hukum terhadap mereka yang bukan warga negara semestinya tetap relevan. Misalnya, penyusunan undang-undang imigrasi tentu harus mempertimbangkan kebaikan umum dari masyarakat suatu negara. Berarti, kebutuhan negara dan masyarakat akan para ahli atau tenaga kesehatan dari negara lain perlu diperhitungkan; begitu pula warga negara harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan masuknya para penjahat atau orang yang bisa menjadi beban bagi negara. Akan tetapi dalam peradaban sekarang, sistem hukum setiap negara perlu memperhitungkan pula kemungkinan datangnya orang-orang yang mencari suaka politik karena terancam hidupnya, begitu pula dengan para pengungsi dan kaum pekerja dari negara lain. Hukum negara pun perlu mengatur bagaimana warga negara dapat memberi perhatian kemanusiaan terhadap kaum miskin atau bantuan kemanusiaan bagi para korban perang dan korban bencana alam di negara lain. Singkatnya, jalur argumen ini mengingatkan bahwa tujuan hukum suatu negara seharusnya lebih luas dari sekedar memberikan jaminan terwujudnya kebaikan atau kesejahteraan umum bagi para warga negara saja. 5. Kemanusiaan Hukum suatu negara semestinya bertujuan memajukan kemanusiaan, tanpa membedakan warga negara dan orang asing. Artinya, jiwa suatu sistem hukum adalah memperjuangkan kesejahteraan siapapun sebagai manusia. Pandangan ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Dalam bukunya Principles of Morals and Legislation, Bentham tanpa ragu-ragu mempertahankan pendapat bahwa setiap hukum dan undang-undang harus dinilai menurut prinsip kemanfaatan.13 Sesuatu dianggap bermanfaat jika memiliki kecenderungan untuk menghasilkan efek-efek 13 Bentham, 1970: bab 1 dan 4. Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 97 yang baik dan menghindari efek-efek yang buruk. Karena Bentham percaya bahwa kebaikan dan kejahatan intrinsik dapat diukur menurut rasa senang dan rasa sakit, maka ia menyamakan kemanfaatan dengan kecenderungan untuk memperbesar kesenangan atau kebahagiaan dan mengurangi penderitaan atau kemalangan. Apakah sistem hukum dari suatu negara harus ditakar menurut manfaatnya bagi warganya saja atau bagi segenap umat manusia? Bentham tidak memberikan jawaban yang eksplisit. Ia sering menekankan pentingnya kesejahteraan umum suatu masyarakat atau komunitas. Dalam arti ini pandangan Bentham sejalan dengan teori Aquinas bahwa hukum harus bertujuan mencapai kesejahteraan umum. Akan tetapi, Bentham tidak berhenti di situ. Sebagai seorang utilitarian ia berpendapat bahwa setiap pelaku moral (moral agent) harus mengutamakan tindakan yang menghasilkan kebaikan dan yang menghindari kejahatan bagi setiap orang sejauh terjangkau oleh efek tindakannya. Dengan kata lain, nilai moral suatu perbuatan diukur berdasarkan kecenderungan efeknya yang baik dan menyenangkan bagi siapapun. Semakin banyak orang mengalami manfaat dari suatu perbuatan, semakin tinggi nilai moralnya. Prinsip "the greatest happiness for the greatest number" tidak dibatasi bagi warga negara atau anggota komunitas saja. Bagi Bentham, hak mendapatkan kebahagiaan dari suatu perbuatan moral bersumber dari status kemanusiaan, bukan status politik kewarganegaraan. Dengan latar-belakang pandangan tersebut, mudah dimengerti teori Bentham bahwa hukum harus bertujuan memajukan kemanusiaan atau memberikan kepastian bahwa setiap orang dapat hidup sewajarnya sebagai manusia. Memang secara praktis hukum suatu negara hanya ditujukan bagi warga negaranya. Namun apabila hukum tersebut menyentuh pula seseorang yang bukan warga negara, maka kesejahteraannya harus pula diperhatikan. Dasarnya, menurut Bentham, ialah kemanusiaan. Artinya, setiap sistem hukum harus bertujuan memperbesar kebahagiaan bagi semua orang sebagai manusia, tanpa memperhitungkan status sosial dan politiknya. Jadi, hukum harus netral atau liberal terhadap kesejahteraan semua orang. Kekuatan pandangan Bentham terletak pada asumsinya bahwa setiap pelaku moral punya kewajiban untuk melakukan perbuatan yang secara moral bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Konsekuensinya, para legislator perlu mendasarkan penyusunan sistem hukum dan undang-undang atas prinsip kemanusiaan (humanity). Berarti, hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat karena bisa berfungsi melindungi kepentingan manusia sebagai manusia. Sementara itu, suatu hukum disebut hukum yang adil apabila tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan obyek hukum menurut status sosial atau politik. Secara filsafati, pandangan ini berakar dalam dua prinsip dasar: pertama, tujuan hukum ialah memajukan kemanusiaan; kedua, setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa sehingga tindakannya menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Akan tetapi teori Bentham tentang tujuan hukum mengandung kelemahan juga. Dapat ditanyakan, apakah dalam penyusunan undang-undang, kesejahteraan atau kepentingan warga suatu negara harus diperhitungkan atau diperlakukan sama dengan orang asing? Jika, demi kemanusiaan, sistem hukum negara Inggris harus peduli pula terhadap orang-orang yang bukan berkewarganegaraan Inggris, maka 98 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 undang-undang keimigrasian Inggris harus mengizinkan siapapun dari negara manapun untuk datang dan tinggal di Inggris, negara yang dianggap lebih makmur. Hal ini jelas tak mungkin, mengingat kelonggaran undang-undang tersebut hanya berarti penurunan standar kesejahteraan umum di Inggris, selain membuka jalan bagi ketidakpastian sosial yang semakin besar. Oleh karena itu, betapapun kuatnya para utilitarian mempertahankan pendapatnya, para legislator akan tetap berpendirian bahwa mereka tidak berada pada posisi kewajiban moral untuk secara hukum memperlakukan orang-orang asing sama seperti warga negara. Dengan kata lain, kewajiban moral untuk selalu bersikap baik terhadap semua orang sebagai manusia, tidak mengandung konsekuensi logis bahwa sistem hukum suatu negara harus memperlakukan semua orang secara sama saja tanpa membedakan status politik kewarganegaraannya. Para legislator selalu berada pada posisi kewajiban moral khusus terhadap kesejahteraan warga negaranya. Sebagai pelaku moral, seorang legislator memang harus menghargai martabat manusia setiap orang. Namun sebagai legislator kewajibannya terbatas. Kesimpulannya, tujuan eksplisit dari sistem hukum suatu negara bukanlah kebaikan atau kesejahteraan segenap umat manusia, melainkan hanya kebaikan dan kesejahteraan warga masyarakat di wilayah hukum tersebut. 6. Kebebasan Seorang utilitarian memandang hukum dari perspektif manfaatnya, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan sebanyak mungkin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Akan tetapi, Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa tak seorang pun boleh diperlakukan sebagai alat atau tujuan bagi orang lain; masing-masing person harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya. Konsekuensinya, tak seorang pun boleh memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Setiap orang harus dihormati kebebasannya untuk memilih dan mengambil keputusan sesuai kehendaknya. Pandangan ini menyiratkan bahwa tujuan hukum ialah menjamin kebebasan. Dengan "kebebasan" Kant maksudkan kebebasan moral dari setiap orang untuk secara otonom memilih apa yang baik dari antara alternatif-alternatif dan untuk mengekspresikan kehendaknya dalam tindakan tanpa dibatasi oleh orang atau instansi eksternal lain. Setiap orang memiliki budi praktis (practical reason), yakni kemampuan untuk memutuskan secara rasional antara kemungkinan-kemungkinan bertindak. Konsekuensinya, setiap person harus dihormati, dalam arti ia diperkenankan oleh orang-orang lain untuk menggunakan kemampuan budinya dan mengambil keputusan sendiri tentang apa yang ia kehendaki. Akan tetapi kebebasan bukan hanya sekedar kehendak yang bebas (free will) atau kebebasan untuk memilih dari antara alternatif-alternatif yang ditawarkan. Kebebasan juga mewajibkan adanya kemampuan untuk melaksanakan apa yang baik yang dikehendaki. Karena itu, seorang person tidak bebas apabila ia bertindak melawan kehendaknya, misalnya karena ia dipaksa dari luar untuk bertindak demikian. Paksaan bisa berupa Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 99 pembatasan secara fisik (misalnya, dipasung atau dikurung dalam tahanan) ataupun secara mental (misalnya, ancaman teror, hukum yang diskriminatif). Oleh karena itu, hukum negara harus efektif untuk memaksimalkan kebebasan dari setiap person warga negara dan untuk meminimalkan pemaksaan-pemaksaan dalam masyarakat yang bisa membatasi atau menghilangkan kebebasan. Sesuatu yang sungguh menarik dari teori Kant tentang hukum adalah proyeknya tentang suatu ideal sosial yang tinggi. Ia mendefinisi masyarakat sebagai komunitas di mana otonomi dan kebebasan menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dari seorang person. Warga suatu masyarakat yang maju terdiri dari person-person yang otonom atau bebas, dalam arti memiliki kemampuan untuk memutuskan apa yang dikehendaki tanpa paksaan-paksaan eksternal. Jadi, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang bebas (free society). Namun, karena kebebasan di sini bersifat moral, maka masyarakat bebas mewajibkan setiap warganya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan oleh kehendaknya. Artinya, kebebasan atau kemandirian tidak bersifat sewenangwenang. Otonomi person menyatakan bukan saja kebebasan, melainkan juga tanggung jawab, baik dalam melaksanakan tindakan yang dikehendaki maupun terhadap orang lain dengan menghargainya sebagai tujuan pada dirinya. Dalam konteks ini, hukum berfungsi mengatasi konflik-konflik kehendak yang mungkin bisa muncul, sehingga kebebasan individu bisa terjamin dan masyarakat ideal bisa terwujud. Pertanyaannya, apakah hukum memang bisa menjadi alat yang efektif untuk memaksimalkan kebebasan moral seperti dimengerti Kant? Secara filsafati pandangan Kant mungkin tidak mengandung inkonsistensi logis, karena ia membedakan moralitas dan hukum. Dari premis tentang person yang otonom dan masyarakat bebas, bisa ditarik konklusi tentang tujuan hukum sebagai instrumen yang melindungi atau menjamin kebebasan. Namun pada lapisan praktis, agaknya terdapat suatu kontradiksi antara tujuan yang mau dicapai dan instrumen yang dipilih. Kebebasan atau otonomi, menurut Kant, berarti absensi pemaksaan eksternal. Seorang person dikatakan bebas apabila ia dapat memilih dan bertindak sesuai kehendaknya, tanpa paksaan apapun dari luar. Dalam arti itu, kebebasan moral bersifat personal. Untuk mencapai kebebasan tersebut, diperlukan hukum. Padahal, menurut hakikatnya, pemaksaan merupakan bagian dari hukum. Hukum yang sudah dikodifikasi secara absah oleh badan legislatif boleh dipaksakan kepada warga negara untuk ditaati. Kepatuhan hukum pun boleh dipaksakan melalui hukuman sebagai sanksi. Warga negara yang melanggar hukum atau menolak taat terhadap hukum bisa ditindak secara paksa menurut prosedur hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum yang menurut hakikatnya mengandung unsur paksaan tidak bisa dihargai sebagai instrumen untuk mencapai kebebasan atau otonomi--paling kurang apabila kebebasan dimengerti sebagai lawan dari pemaksaan. 100 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 7. Keadilan Diskusi mengenai hubungan kebebasan dan hukum sudah menyiratkan pentingnya keadilan. Otonomi atau kebebasan seorang individu harus tidak melanggar hak orang lain atas kebebasan. Oleh karena itu, dalam masyarakat bebas, hukum berfungsi menjamin tegaknya keadilan. Apakah "keadilan" bisa menjadi tujuan utama sistem hukum? Dalam bukunya Jurisprudence, Sir John William Salmond (wafat 1924), seorang ahli hukum terkemuka dari Inggris, berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah keadilan.14 Untuk memahami arti "keadilan" (justice) yang dimaksud, ia mempertentangkannya dengan "ketidakadilan" (injustice). Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan individual maupun berupa praktek berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (unfairly). Dalam arti itu, keadilan berarti fairness. Pertama, fairness mewajibkan bahwa "one treats like cases alike". Jadi, keadilan mengandaikan impartiality di mana baik favoritisme dan vindiktivisme tidak mendapatkan tempat. Kedua, fairness mewajibkan bahwa setiap orang diperlakukan sebagaimana mestinya. Artinya, tidak adil apabila semua anak pejabat dimenangkan dalam semua tender. Keadilan berarti mekanisme dan syarat tender semua proyek harus diaplikasi sebagai mana mestinya pada semua peserta tender secara fair. Jadi, setiap orang harus diakui eksistensinya dan dihargai kualitas atau jasa yang ditawarkannya. Hukum harus bisa menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Pertama, peraturan-peraturan setiap hukum pada dirinya harus adil, sehingga aplikasinya oleh pengadilan tidak akan memihak. Kedua, hukum harus bisa memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap warganya secara adil, dan bahwa setiap warga negara melakukan keadilan terhadap sesamanya. Dalam pelaksanaannya, lazimnya keadilan dibedakan atas keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berarti distribusi kepada para warga secara adil baik kesejahteraan maupun beban kehidupan bersama. Hukum perpajakan, misalnya, harus secara adil menentukan obyek pajak dan mewajibkan beban pajak kepada seluruh rakyat. Keadilan korektif berarti tindakan mengoreksi ketidakadilan yang sudah terjadi dengan mencari keseimbangan antara kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dan kompensasi yang harus diberikan. Misalnya, membiarkan para koruptor berkeliaran, jelas tidak adil; demi tegaknya keadilan, mereka harus dihukum sesuai kerugian yang telah diakibatkannya bagi negara. Hukum setiap negara semestinya bisa memastikan tegaknya keadilan distributif dan keadilan korektif dalam masyarakat. Salah satu kekuatan dari teori di atas ialah keadilan agaknya menjadi satusatunya tujuan yang paling pantas dari suatu sistem hukum. Walaupun mungkin beberapa hal lain bisa menjadi tujuan sekunder, keadilan menurut hakikatnya adalah tujuan yang paling pasti dari hukum. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan mengenai 14 Salmond, 1966: 60-65. Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 101 perilaku yang dapat dipaksakan oleh negara terhadap para warganya sebagai pedoman berinteraksi. Hukum terutama berfungsi mengatur wilayah interaksi atau hubungan dalam masyarakat, bukan wilayah kehidupan pribadi dari seorang individu. Terdapat banyak nilai, baik yang bersifat moral maupun yang non-moral, yang lebih termasuk dalam wilayah kehidupan individual daripada kehidupan sosial. Misalnya, wajar saja bahwa seorang person mencari kenikmatan atau kesenangan; sejauh tidak mengganggu atau merugikan sesama warga masyarakat, bentuk kenikmatan atau kesenangan tersebut tidak akan dipedulikan oleh negara atau masyarakat. Kemabukan dan sikap tergesa-gesa bisa menyebabkan pelanggaran moral; namun apa artinya itu jika tidak berpengaruh buruk apapun terhadap orang lain dalam masyarakat? Tetapi ketidakadilan merupakan masalah tersendiri. Harus diakui bahwa keadilan merupakan bagian dari moralitas mengenai bagaimana seseorang bersikap dan memperlakukan orang lain. Walaupun secara teoretis keadilan bisa dibedakan atas keadilan individual dan keadilan sosial, namun menurut hakikatnya keadilan selalu punya konteks sosial atau mengandung dimensi sosial hubungan antarmanusia. Keadilan menjadi keadilan karena dalam interaksi sosial hak orang lain dihargai; sebaliknya, ketidakadilan terjadi karena dalam interaksi sosial hak orang lain dilanggar atau dilecehkan. Oleh karena konteks atau dimensi sosial inilah, maka menurut Sir Salmond, keadilan merupakan tujuan utama dari sistem hukum. Akan tetapi, teori tersebut mengundang pertanyaan mengenai kriteria keadilan. Apa yang bisa dijadikan kriteria untuk mengukur keadilan? Kriteria berarti ukuran atau alat uji yang dengannya sesuatu bisa dinilai atau dipertimbangkan. Kertas lakmus dapat dipakai sebagai alat pengukur adanya unsur kimiawi asam; begitu pula termometer bisa dipakai untuk mengukur derajat temperatur. Tetapi dengan apa keadilan dan ketidakadilan diukur? Konon di Amerika Serikat terdapat jenis pajak pendapatan yang harus dibayar oleh seorang pegawai sesuai tingkat kesarjanaannya (the graduated income tax). Pemberlakuan jenis pajak ini dianggap tidak adil karena mereka yang bekerja keras sampai mendapatkan gelar sarjana harus membayar lebih mahal dari mereka yang malas atau tidak mau bekerja keras di bangku universitas. Sebaliknya, pemberlakuan tersebut dinilai adil karena seorang dengan gelar sarjana bisa mendapatkan gaji yang tinggi, dan oleh karena itu dapat pula dengan lebih mudah memberikan sejumlah uangnya kepada negara. Kasus hukuman mati bisa menjadi contoh lain tentang ketidakpastian kriteria keadilan. Apakah hukuman mati boleh dianggap sebagai perlakuan yang adil terhadap seseorang yang terbukti telah mencabut nyawa orang lain sehingga ia harus kehilangan nyawanya sendiri sebagai ganti? Atau, hukuman mati harus dianggap sebagai praktek yang kejam dan tak berperikemanusiaan? Apakah hukuman sebagai ganjaran (desert) merupakan kriteria dari keadilan, atau justru berarti suatu ketidakadilan? Agaknya kita harus tiba pada kesimpulan bahwa prinsip "treating similar cases similarly" dan "treating a person as he deserves" tidak selalu jelas dan pasti kriteria penerapannya. Maka sejauh kriteria keadilan dan ketidakadilan sulit diidentifikasi, sejauh itu pula keadilan sepatutnya tidak dijadikan tujuan utama hukum. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai, sesuatu yang memberi arah terhadap tindakan. Ketidakpastian tujuan tentu gagal memberikan arah yang 102 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 jelas, sehingga dengan sendirinya tidak jelas pula keberhasilan dan kegagalan tindakan akan diukur. 8. Penutup: Sebuah Sintesis Di atas sudah didiskusikan tujuh teori etika tentang tujuan hukum. Menurut teori-teori tersebut, sistem hukum suatu negara bisa terarah kepada tujuan mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asasi, memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia, melindungi kebebasan, dan mencapai keadilan. Masing-masing teori menekankan aspek tertentu yang tentu saja masih terbuka terhadap kritik dan diskusi lebih lanjut. Namun agaknya kondisi riil masyarakat sebagai konteks hukum harus dianggap sebagai faktor penentu bagi tujuan filsafati sistem hukum. Oleh karena itu perbedaan antara teori-teori tersebut di atas lebih tepat dibaca sebagai gagasan-gagasan yang mencerminkan kepelbagaian konteks dan ideal moral masyarakat menyangkut sistem hukum. Jika demikian, dalam konteks masyarakat Indonesia sekarang, apa yang harus ditekankan sebagai tujuan hukum dan penegakan supremasi hukum? Di satu pihak, secara negatif dewasa ini masyarakat kita ditandai oleh tiga hal paling fundamental: pelanggaran hak-hak asasi manusia melalui berbagai bentuk konflik dan tindak kekerasan, hilangnya supremasi hukum yang memustahilkan tegaknya keadilan dan berkembangnya demokrasi, dan semakin meluasnya pengrusakan terhadap lingkungan hidup. Di lain pihak, dari perspektif peradaban jaman ini, hak asasi, demokrasi, dan lingkungan hidup sedang menjadi pokok-pokok keprihatinan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum dan sasaran penegakan supremasi hukum harus pula dicari dalam bingkai tiga pokok keprihatinan tersebut. Baik dalam tindak kekerasan dan konflik, serta hilangnya supremasi hukum, maupun dalam aksi-aksi perusakan lingkungan hidup, manusia selalu menjadi korban. Oleh karena itu, sistem hukum perlu diarahkan kepada terjaminnya kedamaian, pengakuan hak-hak asasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Tiga faktor ini bisa diringkaskan menjadi kebaikan manusia dan keutuhan tata ciptaan. Jadi, sistem hukum bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi manusia dan menjamin keutuhan tata ciptaan. Jika demikian maka agaknya teori Aquinas dan Bentham sudah berada dalam arah relevan. Kebaikan dan kesejahteraan harus menjadi imperatif moral yang paling fundamental. Hanya kebaikan (the good) yang secara rasional pantas menjadi tujuan tindakan manusia. Kebaikan perlu selalu dikehendaki, dipilih, dan diperjuangkan. Mengapa harus tindakan ini dilakukan dan tindakan lain dihindari? Jawabannya, karena tindakan ini menghasilkan kebaikan, sedangkan tindakan yang lain itu menghasilkan kejahatan. Mengapa suatu hukum atau peraturan boleh diterima? Jawabannya, karena hukum tersebut mengarah kepada kebaikan. Kalaupun dijawab bahwa hukum tersebut melindungi kebebasan dan hak asasi, maka penalaran pada akhirnya akan menuntun kepada kesimpulan bahwa kebebasan dan hak asasi perlu Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 103 dilindungi agar kebaikan bisa dicapai. Jadi, pada akhirnya kebaikan harus menjadi rujukan terakhir bagi para legislator untuk menyusun suatu peraturan hukum. Dalam arti itu kebaikan harus menjadi tujuan hukum. Kebaikan siapa yang harus menjadi tujuan hukum? Aquinas sudah menjawab bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai kebaikan umum dalam suatu komunitas atau negara. Bentham memperluas perspektifnya sehingga kebaikan atau kesejahteraan umum tidak lagi dibatasi dalam bingkai dikotomi warga negara dan orang asing. Hal itu berarti hanya kebaikan manusia yang pantas menjadi tujuan hukum. Akan tetapi, para etikawan lingkungan hidup telah mengingatkan kita bahwa "moral patient" perlu diperluas dari antroposentrisme sampai meliputi pula unsur sistem ekologi. Itu berarti manusia bukanlah satu-satunya makhluk yang kebaikannya pantas diperjuangkan. Masalah dan hewan tingkat tinggi yang bisa mengalami rasa senang dan rasa sakit. Namun tingkat pencemaran air dan udara, penebangan hutan dan penggalian tambang secara liar turut mempengaruhi derajat kebaikan ataupun kesengsaraan yang bisa dialami oleh manusia dan hewan. Kesimpulannya, walaupun dalam keseluruhan tata ciptaan, manusia tidak disederajatkan dengan hewan dan tumbuhan, namun perlindungan terhadap kebaikan semua makluk ciptaan harus menjadi tujuan hukum. Hukum harus bisa melindungi manusia dan semua makluk ciptaan lain dari semua bentuk kekerasan, kekejaman, dan perusakan. Maka negara, khususnya para legislator dan penegak hukum, punya kewajiban moral untuk memikirkan, menyusun dan menyelenggarakan sistem hukum yang relevan, baik untuk melindungi kebaikan manusia dalam masyarakatnya maupun untuk melindungi keutuhan serta kelestarian alam semesta sebagai satu kesatuan. Dalam bingkai itulah fungsi hukum yang lain mendapatkan tempatnya secara kontekstual, yaitu hukum berfungsi mempertahankan kedamaian dan ketertiban, melindungi hak-hak asasi, menjamin kepastian akan tegaknya keadilan sosial. BIBLIOGRAFI Aquinas, Thomas, Summa Theologica, Translated by Fathers of the English Dominican Province. Westminster, Maryland: Christian Classics, 1981. Bentham, Jeremy, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Edited by J.H. Burns and H.L.A. Hart. London: Athlone Press, 1970. Bertens, K., Etika, Jakarta: Gramedia, 1993. Cicero, De Legibus, dalam De Re Publica, De Legibus, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Loeb Library, 1928. Hobbes, Thomas, Leviathan, New York: E.P. Dutton, 1950. Kant, Immanuel, "Introduction to Metaphysics of Morals" dan "Introduction to the Elements of Justice," dalam The Metaphysical Elements of Justice, translated by John Ladd. Indianapolis: The Bobbes-Merrill Co., 1965. 104 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Locke, John, Treatise of Civil Government, dalam Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, edited by Charles L. Sherman. New York: Appleton-Cetury-Crofts, 1937. Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1971. Salmond, Sir John William, Jurisprudence, edited by P.J. Frizgerald. London: Sweet and Maxwell, 1966. Wellman, Carl, Morals and Ethics, Washington: Washington University Press, 1975. Yong Ohoitimur, Tujuh Teori Etika 105 HUKUM KARMA DIPANDANG DARI SEGI ETIKA S. Reksosusilo STFT Widya Sasana, Malang Abstract : Karma is a law that sprung from the Hindu tradition centuries ago. Nevertheless, it is still actual; and as a law it can be useful to cope the present challenge of evil made by human conducts in the paradigm of “jungle law.” I believe that the karma law can even lead positively society to the moral and civilized one. Civil society of Indonesia needs the karma law. This article is my personal attempt to underline the important role of the karma law in building up Indonesian civil society especially in terms of lawful enforcement to prevent evil occurred daily. The theme shall be dealt with in the following scheme: 1) the karma law in Hinduism, 2) ethics of human conducts, 3) conscience and ethical reasoning, 4) the karma law and ethics, 5) some coclusive points. Keywords : karma, hukum, etika, perbuatan Indonesia merindukan suatu sistem hukum yang ampuh untuk mencegah aneka tindak kejahatan yang melanda demikian hebat akhir-akhir ini. Saya berpendapat bahwa hukum karma merupakan salah satu kemungkinan yang dapat digunakan sebagai semacam pembasmi kejahatan yang berpola hukum rimba, serta demi tercapainya masyarakat yang bermoral, beramal dan berbudaya sebagaimana dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Namun dari segi etika (ilmu tentang tingkah laku) beberapa hal sehubungan dengan hukum karma ini perlu diperjelas agar dapat digunakan sebagai suatu hukum yang dapat dipakai untuk mengatur tingkah laku. 1. HUKUM KARMA1 Karma berasal dari bahasa Sansekerta, dari kata dasar kar artinya “berbuat”, “melakukan sesuatu”. Karma artinya “berbuat”, ”melakukan sesuatu”. Karma artinya “perbuatan”, ”kelakuan”. Pengertian hukum karma merupakan bagian dari pola 1 106 Mengenai hukum karma, lihat William K. Maloney, “Karman: Hindu and Indian Concepts”; Misuno Kögen, “Karman: Budhist Concepts”, in Mircea Eliade (chief ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 8, New York, 1987. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 pikir bangsa Hindu yang sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum bangsa Arya memasuki daerah India (± 5.000 seb. M.) Sebagai hukum, hukum karma sering diartikan hukum sebab akibat. 1.1. Dasar pemikiran hukum karma Seluruh alam semesta, termasuk manusia berasal dari satu dasar yang disebut Brahman, karena semua timbul dari satu dasar ada berbudi dan penuh bahagia (Sat, Cit, Ananda), maka semua yang ada berada dalam keserasian yang berbahagia, dalam suatu keteraturan yang disebut rta. Semua serba teratur, tidak ada yang serba kebetulan, semua ada tempatnya, semua tindakan membawa akibatnya, semua kejadian ada sebabnya, semua sudah diatur. Dalam keteraturan rta, maka semua yang ada memiliki “keberadaan” sendiri-sendiri. Binatang berada dan bersikap, berlaku “keberadaan” secara binatang; manusia berada dan bersikap, berlaku sebagai manusia. Semua yang ada memiliki dharma-nya sendiri-sendiri. Sehubungan dengan ini maka karma manusia haruslah sesuai dengan dharma manusia. Jadi arti hukum karma pada titik tolak pertama ialah hukum yang berbunyi: “Manusia haruslah berbuat sesuai dharma-nya sebagai manusia.” 1.2. Manusia sebagai yang hidup di dunia Hidup manusia dari muda sampai tua dibagi dalam 4 tahap:2 1. Brahmacarya: tahap seorang belajar menuntut ilmu; 2. Grhastha: tahap seseorang berkeluarga, beranak istri; 3. Vanaprasttha: tahap hidup menyepi di hutan, mulai meninggalkan hal-hal dunia fana ini; 4. Samnyasa: tahap mencapai kesempuranaan hidup melalui yang tinggi. Tahap-tahap hidup ini mencerminkan filsafat hidup orang India kuno. Tujuan akhir hidup mereka bukanlah untuk menikmati hidup enak di hari tua atau di akhirat, tetapi untuk lepas dari putaran hidup (samsara) di dunia ini. Namun orang India kuno juga realistis. Mereka sadar bahwa sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Manusia juga harus melakukan dharmanya, hidup sebagai manusia yang menggunakan benda-benda dunia ini. Karena itu tujuan hidup manusia diungkapkan dalam empat macam : 1. Mencapai artha (kekayaan); 2. Mencapai kenikmatan/ kesenangan (kama); 3. Mencapai puncak hidup baik dengan mencapai kesempurnaan dalam jabatan hidupnya (Dharma), dan 4. Mencapai kesempurnaan hidup yang mengatasi hal-hal duniawi (Moksha). 2 Empat tahap kehidupan (Ashraman) mulai diajarkan oleh para Brahman ketika posisi mereka mulai menanjak. Lihat M. Winternitz, History of Indian Litterature, New Delhi, 1972, 232-233. S. Reksosusilo, Hukum Karma 107 Hidup manusia ditengah masyarakat ditentukan oleh dharmanya sendiri (Sva Dharma)3 , manusia yang ditentukan dalam tata aturan tugas manusia sebagai Brahmana: Pembina kebudayaan, agama dan kesusilaan atau sebagai Ksatrya: para prajurit dan para pejabat pemerintahan atau sebagai Vaisya yaitu para pedagang para petani, para pengrajin dan sebagai Sudra yaitu para buruh dan pekerja. Dalam pengertian filsafat hidup manusia India kuno, empat macam bidang hidup ini bukan mengkotak-kotakkan manusia dalam lapisan yang terpisah-pisah namun merupakan suatu pembagian tugas demi keteraturan hidup manusia. Apa artinya seorang Ksatrya tanpa bimbingan para Brahmana? Apa artinya seorang ahli bangunan tanpa buruh kasar yang mengerjakan bangunan? Masing-masing tugas jabatan memiliki sifat dan sikap tertentu: Seorang brahmana harus bersikap tenang, memiliki pengendalian diri yang tinggi, tidak keburu nafsu, hidup murni, sederhana, jujur, penuh pengetahuan dan kebijaksanaan, ia seorang yang beriman dan penuh takwa. Seorang ksatrya ialah pelindung rakyat dan masyarakat, ia harus bersifat tegas, berani, penuh tekad dan akal dalam menghadapi persoalan, murah hati dan penuh wibawa. Seorang vaisya ialah seorang yang mengatur hal-hal kebendaan, ia harus tekun, rajin, jujur, hemat. Seorang sudra ialah seorang pekerja, ia harus rajin, tekun, taat. Selanjutnya perlu kita ungkap sedikit mengenai pandangan hidup tentang jiwa manusia. Kebanyakan pemikiran Hindu berpendapat bahwa jiwa ialah: suatu rohani yang kekal, yang masuk dalam kurungan badan jiwa masih terikat oleh ikatan badani. Apakah lain selama jiwa masih terikat oleh ikatan badani? Apakah yang membuat ikatan badani itu? Yang membuat ikatan badani ialah karma manusia. Dalam seluruh konteks ajaran Hindu Kuno mengenai manusia, hukum karma dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum Karma menetapkan agar manusia berbuat dengan dharma-nya, sesuai jabatan (varna) yang didudukinya. Setiap perbuatan membawa “buahnya”, buah itu berbentuk keadaan konkret, dan juga keadaan yang membekas pada jiwa manusia yang menentukan karakter manusia, yang menentukan kemana jiwa berpindah setelah manusia itu mati. Setiap perbuatan manusia meninggalkan “bekasnya” dan membawa “buahnya”, buah baik yang dinikmati manusia maupun buah-buah buruk yang harus dideritanya. Pada saat manusia mati jiwa itu masih penuh dengan “buah-buah perbuatan manusia itu, dan manusia itu lahir kembali, reinkarnasi, dalam keadaan lain yang baru. Kalau “buah baik” yang dominan maka manusia lahir dalam tingkat yang lebih baik dari hidup sebelumnya; kalau “buah buruk” yang dominan maka manusia lahir dalam keadaan yang lebik buruk, bahkan dapat lahir kembali sebagai binatang. Dengan demikian manusia akan hidup terus berganti keadaan sesuai karmanya, Inilah hukum karma. Dalam alam pikiran Hindu Kuno dan juga dalam alam pikiran Buddhisme hidup terus begitu itu dirasakan sebagai beban, karena bagaimanapun nikmatnya 3 108 Empat kasta sudah dikenal pada masa Atharva Veda. Waktu itu kasta merupakan pembagian tugas, bukan pemisahan eksklusif soal martabat. Lihat, M. Winternitz, Ibid., 123. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 hidup di dunia ini selalu penuh dengan kedukaan. Kedukaan yang adalah akibat dari alam yang serba berubah ini; kedukaan yang berasal dari kodrat alam ini.Sebab itu manusia India Kuno dan manusia Buddha ingin lepas dari putaran karma, putaran perbuatan, putaran hidup yang disebut samsara, mereka ingin mencapai Moksha, atau pada orang Buddha mencapai Nirvana. Pada situasi alam pikiran seperti ini hukum karma tidak memiliki daya tarik apa-apa bagi orang Hindu Kuno maupun bagi orang Buddha. Pengertian yang mengatur perbuatan mereka ialah pengertian “hukuman” yang dapat diterapkan oleh pengusaha melalui hukum-hukum yang sudah tertulis dalam kitab agama maupun kitab hukum negara. Hukumanlah yang menjadi pengatur tingkah laku. Orang berbuat baik karena takut dihukum, orang meninggalkan perbuatan jahat karena takut dihukum. Namun dalam perkembangan selanjutnya, terutama dalam Buddhisme ada pergeseran pemikiran mengenai tujuan hidup. Kalau dulu Nirvana diartikan keadaan “lepas” dari segala yang “dunia ini”, maka mulai timbul pemikiran bahwa Nirvana ialah keadaan menikmati kenikmatan. Bagaimana kenikmatan itu dapat diperoleh? Kenikmatan dapat diperoleh melalui “pahala” dari perbuatan (karma). Perbuatan itu adalah baik karena membawa pahala, dan dengan pahala manusia dapat mengecap kenikmatan. Sebaliknya perbuatan itu jahat karena membawa “yang tak berpahala” dan “yang tak berpahala” membuat orang mengalami penderitaan.4 1.3. Antara “perbuatan” dan “buahnya” Pandangan pertama mengajarkan karma ialah perbuatan itu sendiri; perbuatan itu membawa “pahala”, maka perbuatan itu membawa akibat kenikmatan; kalau perbuatan itu membawa “yang tak berpahala”, maka perbuatan itu membawa akibat penderitaan. Disini karma adalah perbuatan itu sendiri yang membawa “pahala” atau membawa “yang tak berpahala”. Kenikmatan dan penderitaan dapat dikatakan hasil kelanjutan dari perbuatan itu sendiri. Pandangan kedua ialah perbuatan kita membawa “pahala” atau “yang tak berpahala”, pahala itu mengakibatkan karma baik dan karma mengakibatkan/ membawa kenikmatan; sedangkan perbuatan lain membawa “yang tak berpahala”, hal itu mengakibatkan karma buruk yang lalu membawa penderitaan. Dalam pandangan kedua ini karma berlainan dari perbuatan itu sendiri namun karma baik, atau membawa pahala dan kenikmatan; karma buruk, “yang tak berpahala” dan penderitaan tetap berhubungan dengan perbuatan. Bagaimana hubungan antara perbuatan dengan kenikmatan dan penderitaan? Dalam hal ini lagi ada dua pendapat. Pendapat yang satu mengatakan hukum karma 4 Lihat Misuno Kögen, Op.Cit., 266-268. S. Reksosusilo, Hukum Karma 109 berarti setiap perbuatan membawa akibatnya sendiri-sendiri yang tidak dapat dielakkan dan harus ditanggung sendiri secara penuh. Pendapat yang lain mengajarkan akibat dari perbuatan dapat dihitung secara kumulatif, sehingga suatu penderitaan akibat perbuatan yang membawa “yang tak berpahala” dapat dikurangi atau dihilangkan oleh kumpulan kenikmatan dari “pahala” perbuatan-perbuatan lainnya. Perbuatan mana yang “berpahala” dan mana yang “tidak berpahala”, dengan cermat ditetapkan dalam kitab-kitab agama mereka yang mengandung ajaran mengenai “nilai” dan “harga” dari perbuatan. Bagaimanakah penilaian dari ajaran hukum karma menurut pemikiran Hindu dan Buddha ini dari segi Etika? 2. KAIDAH-KAIDAH ETIKA TENTANG PERBUATAN5 Etika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan / tingkah laku manusia dari segi penilaian baik dan jahat. Etika bertitik tolak dari suatu kaidah dasar: manusia harus melakukan yang baik dan menghindari / tidak melakukan yang jahat. Persoalan pokok etika ialah kapankah perbuatan dapat masuk penilaian etis, faktor-faktor apa yang menentukan nilai etis, dan bagaimana menentukan nilai etis? Apakah yang dimaksud “baik”, apa yang dimaksud perbuatan “jahat”? Bagaimana menentukan “baik” dan “jahat”? Dalam bagian ini saya akan menguraikan tentang soal kapan suatu perbuatan masuk penilaian etis, faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana menentukan nilai etis. Dalam etika ditegaskan bahwa manusia mempunyai kodrat kemanusiaan, tingkah lakunya berbeda dari binatang. Namun sebaliknya sebagai makhluk berbadan, badannya bertindak sesuai kaidah hukum alam mekanisme gerakan tubuh, jantungnya berdegup memompa darah, dadanya naik turun menghembuskan dan menghirup udara dalam bernafas. Anggota tubuh melakukan gerakan refleks dan sebagainya. Semua tingkah laku badan manusia sebagai mekanisme gerak tubuh tidak termasuk penilaian etis. Dada yang naik turun karena bernafas tidak bisa dihitung masuk perbuatan baik atau perbuatan jahat. Memicingkan mata karena silau tidak masuk penilaian baik atau perbuatan jahat. Dalam etika yang masuk penilaian etis ialah perbuatan yang dilakukan dengan tahu dan mau. Keduanya, tahu dan mau merupakan syarat untuk suatu perbuatan yang bebas dan karenanya bisa dipertanggungjawabkan. Tahu berarti akal budi manusia mengerti penuh bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Mau memaksudkan setelah tahu, 5 110 Austin Fagothey, Right and Reason, Mosby Company, New York 1972, 13-34. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 manusia menimbang-nimbang mengenai perbuatan itu lalu memutuskan melakukan perbuatan itu, dan menjalankan berdasarkan keputusan ini. Tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Ketidak-tahuan. Kalau orang tidak tahu bahwa suatu perbuatan itu jahat dan kalau dia melakukan itu, secara etis perbuatannya tidak dapat dinilai jahat. Dia bukan orang jahat. Meskipun secara obyektif dia melakukan perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat yang dilakukan karena tidak tahu menjadi kurang jahat dari pada perbuatan jahat yang dilakukan dengan pengetahuan penuh. Nafsu. Nafsu ialah gelora emosi yang membuat manusia kurang jernih penalarannya dan bertidak emosional. Suatu nafsu yang mengaburkan kejernihan akal budi kita, sebelum kita melakukan perbuatan itu, mengurangi nilai etis perbuatan kita. Namun suatu nafsu yang sengaja dikobarkan-kobarkan jika menyeret seseorang ke suatu perbuatan, maka perbuatan itu akan mendapat penilaian etis yang lebih. Kebiasaan. Oleh kebiasaan orang melakukan perbuatan tanpa berpikir panjang; oleh karena kebiasaan sesuatu perbuatan menjadi “biasa”, “tidak apa-apa”. Bagaimana penilaian etisnya? Jika perbuatan dimulai agar nanti menjadi terbiasa maka kebiasaan menjadi tanggung jawab penuh si pelaku. Kalau perbuatan dimulai tanpa maksud menimbulkan kebiasaan, dan perbuatan itu sendiri tidak bersifat menimbulkan kebiasaan, maka kebiasaan yang terjadi mengurangi tanggung jawab. Kalau perbuatan yang dimulai pada hakekatnya diketahui akan menimbulkan kebiasaan melalui rasa “ketagihan”, maka meskipun perbuatan itu dimulai tanpa maksud menimbulkan kebiasaan , tetap kebiasaan yang timbul menjadi tanggung jawab kita. Faktor berikut yang dipengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang dalam melakukan perbuatan ialah rasa takut yang dikaitkan dengan intimidasi, ancaman, paksaan. Bagaimana kita menilai perbuatan yang dilakukan karena takut dan karena paksaan? Rasa takut pada prinsipnya hanya mengurangi nilai etis serta tanggung jawab kita. Berbuat baik karena takut dimarahi ibu tetap bernilai perbuatan baik, hanya saja nilainya kurang. Perbuatan jahat yang dilakukan karena takut merupakan perbuatan jahat, dan tetap tanggung jawab kita meskipun faktor “karena takut” dapat sedikit meringkankan tanggung jawab kita. 3. HATI NURANI DAN PENALARAN ETIS6 Darimana kita tahu bahwa suatu perbuatan itu baik atau jahat, jawabannya ialah dari hati nurani. Apakah hati nurani itu? Hati nurani sebetulnya akal budi kita yang sebelum kita melakukan suatu perbuatan menyatakan suatu prinsip mengenai perbuatan lalu juga menunjukkan apakah perbuatan konkret yang akan dilakukan itu termasuk prinsip itu atau tidak; selanjutnya hati nurani itu merupakan akal budi 6 Austin Fagothey, Ibid., 40-41. S. Reksosusilo, Hukum Karma 111 yang mengajak dan membolehkan kita melakukan perbuatan itu karena telah ditunjukkan bahwa perbuatan itu baik atau melarang kita melakukan perbuatan itu karena telah ditunjukkan bahwa perbuatan itu pada prinsipnya jahat. Setelah melakukan perbuatan, akal budi kita atau memuji kita karena telah melakukan perbuatan baik atau mencela diri kita karena telah melakukan perbuatan jahat. Suara hati nurani ialah suara akal budi kita sendiri. Namun kita dapat bertanya : dari mana akal budi kita tahu perbuatan mana masuk perbuatan baik, perbuatan mana masuk perbuatan jahat? Para ahli keagamaan sering secara umum sekali menyatakan bahwa “Prinsip-prinsip perbuatan baik dan jahat telah dimasukkan oleh Tuhan ke dalam batin manusia.” Ungkapan ini kalau dimengerti secara benar memang dapat diterima, namun kalau dimengerti secara harafiah dapat menyesatkan. Dari segi ilmu keagamaan kita dapat mengetahui bahwa semua agama yang ada di dunia ini pada dasarnya dan pada garis besarnya mengajarkan kaidah perbuatan yang sama: Semua agama mengatakan mengambil milik orang lain itu jahat, memberi derma itu baik. Berkata yang tidak benar itu jahat, berkata jujur itu baik. Perselisihan dan peperangan itu tidak baik, perdamaian dan ketentraman itu baik. Membunuh dan menganiaya seseorang tanpa alasan itu jahat, berbelas kasihan kepada sesama itu baik. Semua agama juga menganjurkan agar manusia memuja Tuhan. Dalam kenyataannya nanti tiap agama mengembangkan dasar-dasar umum itu secara lebih terinci, sehingga masing-masing agama berbeda satu sama lain. Kesamaan kaidah dasar mengenai apa yang baik dan apa yang jahat yang diketemukan dalam setiap agama itulah yang menyebabkan timbul pemikiran bahwa “Tuhanlah yang menanamkan kaidah-kaidah dasar itu”. 3.1. Beberapa teori etis7 Teori teleologi. Teori mengatakan manusia dalam bernalar mengenai perbuatannya akan didorong oleh tujuan (telos) atau akibat dari perbuatannya. Lalu menurut teori ini perbuatannya yang berakibat kegunaan, kebahagiaan dan kenikmatan akan membuat perbuatan itu baik nilainya, akibat yang merupakan kesengsaraan dan penderitaan akan membuat perbuatan itu jahat nilainya. Tetapi semua pengikut teori ini toh tetap mengakui kaidah dasar bahwa dalam mencari kegunaan, kenikmatan orang itu boleh sewenang-wenang mengikuti nafsu. Teori deontologi (wajib). Teori ini mengatakan bahwa manusia menilai suatu baik atau buruk bukan dari akibatnya tetapi dari keyakinan dasar bahwa perbuatan itu adalah WAJIB. Suatu perbuatan adalah baik karena itu baik dan manusia wajib melakukan yang baik. Namun bagaimana wajib itu ditentukan? Wajib ini ditentukan oleh prinsip dasar nalar manusia yang mengatakan: a) Sesuatu yang seyogyanya ditaati seluruh manusia yang bernalar, menjadi wajib; b) Manusia harus 7 112 Peter Singer (ed.), A Companion to Ethics, Oxford 1993, 161-205. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 dihargai sebagai manusia dan bukan dianggap suatu alat belaka; c) Nalar manusia menolak perbuatan yang sewenang-wenang dan menarima suatu peraturan yang adil. Teori etika kodrat manusia. Teori ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa semua yang ada ini berada dan “berlaku” menurut kodrat dan hakekat benda itu : Hakekatnya dan kodratnya air itu basah dan mengalir. Karena itu air itu basah dan mengalir. Binatang buas itu kodratnya makan daging sebab itu dia makan daging. Manusia itu kodratnya ialah makhluk berbudi, karena itu perbuatannya harus sesuai dengan kodratnya itu. Disamping itu kodrat setiap makhluk ialah mencapai kesempurnaan kodratnya, maka juga manusia mengarah kepada perkembangan dirinya sebagai manusia makhluk berbudi. Teori Hukuman dan Pahala. Teori ini mengatakan bahwa manusia cenderung melakukan sesuatu kalau mendapat pahala dan tidak melakukan sesuatu karena hukumnya. Kebanyakan agama mengikuti teori ini sebab itu dalam setiap agama suatu perbuatan yang diajarkan sebagai perbuatan baik disertai dengan pahala yang akan diterima dan perbuatan jahat yang diajarkan disertai pula dengan hukuman yang akan diterimanya, agar manusia tidak melakukan perbuatan jahat itu. Teori ini membuat etika terkait dengan agama dan dengan hukum (baik hukum agama mau pun hukum profan (non agama). Sehubungan dengan agama: Dalam hal ini agama yang mengajarkan perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang terlarang; disertai dengan pahala serta hukumnya. Pengikut agama akan mengikuti perbuatan baik, karena ingin mendapat pahala sedangkan mereka tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena takut kena hukumannya. Sehubungan dengan negara: Setiap negara ingin bahwa negaranya tertib, rakyatnya patuh, sehingga negara manjadi aman dan dapat mencapai tujuannya. Untuk mencapai ketertiban ini negara atau pemerintah membuat aturan-aturan atau hukum. Melalui teori diatas bahwa manusia didorong melakukan sesuatu karena ingin pahala atau takut hukuman, maka hukum negara melekatkan hukuman dan sanksi–sanksi pada peraturan-peraturan mereka, serta memberi pahala kepada warga negara yang setia patuh pada aturan negara. Dalam teori ini suatu perbuatan yang sesuai dengan yang diajarkan itu baik dan akan mendapat pahala; sedangkan perbuatan yang melanggar larangan itu jahat dan akan mendapat hukuman. Perlu dikatakan bahwa teori ini kurang berkenan kepada para pemikir ilmu etika, karena hukuman dan pahala merupakan motif yang kurang kuat untuk mendasarkan “kebaikan” ataupun “kejahatan” suatu perbuatan. 3.2. Pandangan Meta-Etis8 Dalam prakteknya ada banyak teori dan ajaran yang mencoba mendasari tingkah laku manusia. Banyak pemikir ilmu etika sekarang sadar bahwa tidak mudah 8 Ibid., 421-442. S. Reksosusilo, Hukum Karma 113 menemukan satu teori etika tentang perbuatan yang berlaku di seluruh dunia. Ada perbuatan yang dalam masyarakat tertentu dianggap baik oleh masyarakat lain dianggap kurang baik. Dan masing-masing masyarakat mempunyai penalaran masing-masing. Dari semua kenyataan itu para pemikir etika mengemukakan pandangan atas teori-teori etika yang ada dan merangkum dalam satu pandangan. Pandangan yang merangkum ini disebut pandangan meta-etis. Ada beberapa meta-etis : a) Relativisme Etis. Mengingat bagitu banyaknya padangan tentang perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang buruk, maka dapat disimpulkan bahwa etika itu relatif. Karena itu dalam berbuat kita harus melihat situasi dan kondisi setempat. Kalau di suatu tempat suatu perbuatan dinilai baik maka kita lakukan. Kalau suatu perbuatan dianggap jahat ya tidak kita lakukan. b) Pandangan Relativisme Etis ditentang oleh pandangan meta-etis yang menganut absolutisme etis. Dunia akan kacau kalau masing-masing dibiarkan mengikuti patokan etis bagi perbuatan sesuai pandangan masing-masing. Juga relativisme etis tidak dapat memberi jalan keluar kepada orang yang bingung. Dalam masyarakat A umpamanya : memberi uang pelicin itu baik, tanda tahu terima kasih, dalam masyarakat B memberi pelicin itu tidak baik, tidak jujur. Nah, bagaimana seorang yang terdidik dalam pola masyarakat B harus bertindak menghadapi kasus uang pelicin yang adalah biasa dalam masyarakat A? Haruskah ia menyesuaikan begitu saja, meskipun hatinya mengatakan bahwa memberi pelicin itu tidak baik? Sebab itu pandangan absolutisme etis mengatakan harus ada patokan perbuatan baik yang berlaku universal di seluruh dunia, sehingga apa yang menurut patokan itu jahat bagi orang Amerika harus juga diakui jahat bagi orang Indonesia, bagi orang Rusia, dan sebagainya. Dewasa ini memang umat manusia berusaha mencapai suatu patokan yang universal ini, dan rupanya sudah ada patokan dasar dalam “Declaration of Human Rights” yang ditandatangani oleh bangsa-bangsa di dunia pada tahun 1948. Memang dalam penerapannya banyak hal masih dipengaruhi oleh situasi sejarah, budaya, agama dari masing-masing negara, namun sebagai garis besar “Declaration of Human Rights” itu cukup diterima sebagai patokan etis untuk menentukan apakah suatu perbuatan baik dan jahat. Dalam ilmu etika rupanya manusia memilih jalan tengah antara absolutisme etis dan relativisme etis dalam arti sebagai berikut: memang harus ada patokan yang pada garis besarnya manusia menyetujui sebagai patokan menentukan baik dan jahat (Absolutisme), namun penerapannya di masing-masing masyarakat dapat menunjukkan tekanan dan nuansa yang berbeda. Pada umumnya dari segi agama manusia cenderung ke pola pemikiran absolutisme. Apa yang sudah ditetapkan oleh ajaran agama sebagai perbuatan baik harus dijalankan, apa yang sudah ditetapkan sebagai larangan harus secara universal tidak boleh dilanggar, dan hal itu harus berlaku untuk seluruh umat manusia. 114 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 4. ETIKA DAN HUKUM KARMA Beberapa pokok pikiran mengenai etika hukum karma: Titik tolak ajaran hukum karma ialah pemikiran yang timbul dari kepercayaan keagamaan yang bertitik tolak bahwa alam semesta ini berasal dari makhluk tertinggi yang menempatkan semuanya dalam tempatnya yang teratur. Tidak ada kejadian yang tanpa sebab, tidak ada kejadian yang tanpa akibat. Selanjutnya hukum karma berlandaskan pemikiran bahwa ada jiwa yang akan hidup terus setelah manusia meninggalkan dunia ini. Perbuatan manusia dalam hukum karma dihitung dalam lingkup sebab akibat dari kejadian fisik baik organik maupun anorganik. Keadilan dalam hukum karma ialah keadilan “keseimbangan yang muncul dalam prinsip” seperti “gigi dibalas dengan gigi, mata dibalas dengan mata”. Hukum karma prinsipnya hukum sebab akibat yang mutlak, sehingga kalau akibat suatu perbuatan tidak segara tampak dipastikan perbuatan itu akan mendapat akibatnya (pahala atau hukuman). Entah nanti di kemudian hari, entah nanti di akhirat. Bagi perbuatan manusia pelaksanaan hukum sebab akibat menimpa manusia itu sendiri dan di-laksanakan oleh makhluk tertinggi (Tuhan). Pelaksanaan hukum sebab akibat oleh Tuhan tidak diketahui oleh manusia (hukum karma tingkat tinggi). Manusia tidak tahu kapan, siapa yang menjadi pembalas, balasan apa yang akan mengenai dirinya, dimana balasan itu akan tiba, dan bagaimana balasan itu akan menimpa. Hukum Negara dikaitkan dengan pelaksanaan hukum karma tingkat rendah dimana pelaksanaanya masih dapat diperkirakan dan manusia mampu mempengaruhi. Dalam ilmu etika, hukum didefinisikan peraturan dari akal budi yang nalar, diumumkan oleh pihak yang berhak dan berkuasa untuk kepentingan umum. Sebagai peraturan, hukum memerintah dan mewajibkan. Peraturan dari akal budi yang nalar artinya hukum bukan peraturan yang emosional, sewenang-wenang tetapi hasil pemikiran akal budi. Hukum menjadi sah apabila diberlakukan oleh pihak yang punya kuasa. Hukum bukan urusan setiap orang tetapi urusan orang yang berhak mengatur. Aturan itu harus diumumkan dan dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Hukum dimaksudkan untuk kepentingan umum. Hukum adalah peraturan untuk kepentingan umum. Perintah seorang penguasa kepada seorang bawahannya untuk kepentingan pribadi penguasa bukanlah hukum. Ada beberapa macam hukum: Hukum Fisik / Hukum Alam. Aturan yang mengarahkan makhluk tak berakal budi untuk mencapai tujuannya. Aturan ini ditetapkan oleh Tuhan pencipta semesta alam; dilaksanakan dalam keteraturan oleh kodrat masing-masing makhluk alam; hukum ini dapat diketahui dan dirumuskan oleh akal budi manusia. Hukum Moral Natural. Hukum yang mengatur tingkah laku manusia melalui kodratnya sebagai manusia yang berakal budi, bersandar pada kehendak yang bebas S. Reksosusilo, Hukum Karma 115 yang membuat tingkah lakunya mempunyai nilai baik dan buruk dan si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Hukum ini diberikan oleh Tuhan penguasa atas umat manusia melalui kodrat manusia yang adalah makhluk berakal budi, dapat diketahui penggunaan akal budi yang nalar dengan tujuan kesempurnaan dan kebahagiaan umat manusia. Hukum Manusia. Peraturan dibuat oleh manusia untuk mengatur tingkah laku manusia (bawahan) demi kepentingan bersama/kepentingan umum. Dari segi hukum, termasuk hukum yang mana hukum karma itu? Titik tolak hukum karma ialah hukum fisik sebab akibat dan masuk dalam manusia secara analogi dalam kepercayaan dan agama, dimana hukum sebab akibat diterapkan pada perbuatan manusia. Dari segi etika murni: hukum karma bukanlah moral karena tidak mengatur tingkah laku manusia, tetapi hanya mengajarkan bahwa semua perbuatan akan mendapat balasannya. Artinya manusianya sendiri masih harus mengatur tingkah laku sesuai hukum etika (dan penalaran etis). Dia hanya diberitahu oleh hukum karma bahwa perbuatannya akan mendapat balasan atau hukuman. Mengenai harapan bahwa hukum karma dapat dipakai untuk membasmi hukum rimba, bagaimana hal ini dipandang dari sudut kajian etis? Seperti diuraikan di atas, manusia mendapatkan norma-norma etis atau moral dari pendidikan atau kepercayaan serta agama yang dianutnya. Hukum karma itu termasuk penalaran etis yang berdasarkan hukuman dan pahala. Bagi mereka yang menganut penalaran ini memang lalu memandang hukum karma sebagai sesuatu yang perlu diperhitungkan. Namun harus diperhatikan bahwa ada penalaran etis yang lain. Juga perlu diperhatikan bahwa di kalangan pemikir etika berpendapat bahwa melakukan suatu perbuatan karena ada pahalanya atau takut mendapat hukumannya itu dari segi etika bukanlah suatu sikap yang terpuji. Ilmu Etika memang cenderung kearah sikap tanggung jawab akal budi, dimana akal budi mengatakan sesuatu perbuatan itu baik, dan manusia mengikuti perbuatan yang baik itu karena “kebaikannya yang instrinsik” bukan karena pahala atau karena hukuman, inilah ideal manusia beretika atau bermoral. Memang mengingat kelemahan budi dan kehendak manusia, kadang-kadang perlu ada dorongan lahir dari hukum manusia yang diungkapkan antara lain melalui hukum negara. Dalam hubungannya ini apakah tidak dapat dikatakan: Jadi hukum karma kan lalu dapat membasmi perbuatan jahat setara dengan hukum negara? Dalam menjawab pertanyaan ini perlu diperhatikan: Seseorang kalau penalaran etisnya sudah menjurus ke arah melakukan perbuatan kalau ada hadiahnya, atau takut hukuman biasanya hanya betul-betul patuh kalau hadiahnya konkret dan hukumannya itu konkret. Orang akan cenderung mencari akal untuk dapat tidak patuh tetapi dapat menghindari hukuman. Kekurangan hukum karma dari segi ini ialah justru keberlakuan hukum karma ini (terutama yang tingkat tinggi) tidak bisa diketahui secara konkret. Hanya keberlakuan yang tingkat rendah, dalam hukum negara dapat diketahui. Atas dasar inilah dapat dirasakan bahwa hukum karma tidak ampuh untuk membasmi perbuatan jahat. Kalau berlakunya melalui hukum negara orang mencari akal untuk menghindari hukuman, kalau berlakunya dalam tingkat tinggi, setelah Tuhan Yang Maha Kuasa orang justru tidak bisa tahu 116 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 kapan, bagaimana dan sebagainya. Hal ini membuat orang tidak takut. Bukankah terjadi para koruptor justru tambah kaya dan jaya ? Secara konkret sering tampak hukum karma tidak adil. Pencuri ayam dihukum 1 bulan, koruptor 100 juta dihukum 24 bulan. Padahal kalau mau adil betul, kalau harga ayam Rp. 10.000,- mencuri ayam dihukum 1 bulan. Maka koruptor 100 juta rupiah harus dihukum 10.000 x bulan. Inilah sebabnya orang tidak terlalu takut pada hukum karma. Memang penganut hukum karma akan meningkatkan daya persuasi hukum karma perbuatannya. Itu dengan menyatakan “manusia tidak dapat lolos dari pahala atau hukuman perbuatannya”, “Tuhan Maha Adil Dan Mahakuasa”. Namun dasarnya tetap manusia tidak tahu kapan, bagaimana, di mana, karena itu sejauh manusia dapat melihat konkretnya di dunia ini orang tidak akan terpukau oleh hukum karma. Orang mulai peduli terhadap hukum karma, kalau manusia berpikir ke arah dunia akhirat, namun “ dunia akhirat sebagai konkret” itu lalu masuk jajaran agama. Agama dalam pemikiran etika, termasuk meta etis yang mengarah ke pemikiran absolutisme etis agama. Karena hukum karma termasuk meta etis, maka keampuhan harus dilandasi dulu oleh pengetahuan moral / etika baik melalui pendidikan etika, pendidikan agama maupun melalui pendidikan moral Pancasila. Dalam pendidikan agama dan moral Pancasila diajarkan, ditunjukkan dan dilatihkan perbuatan mana yang baik dan yang buruk. Dalam etika manusia diberi pandangan bagaimana berpikir menghadapi manusia lemah yang cenderung ke arah yang jahat dengan memakai persuasi pahala dan hukuman. Untuk memperkuat persuasi pahala dan hukuman orang dapat memakai iman kepada keadilan Tuhan, orang dapat memakai hukum karma. Tetapi harus diingat bahwa memotivasi perbuatan melalui rasa takut hukuman dan demi pahala dari segi etika merupakan suatu yang kurang nilainya. Orang yang kesadaran etiknya tinggi berbuat sesuatu karena melihat “kebaikan intrinsik”, bukan demi pahala atau takut hukuman. Pada kenyataannya di banyak buku keagamaan yang mengajarkan hukum karma dan dalam uraian tentang hukum karma selalu juga disinggung tentang perbuatan baik dan buruk yang juga dijabarkan dalam ajaran etika. Juga di banyak buku keagamaan ada petunjuk yang konkret mengenai pahala dan hukuman perbuatan manusia. Misalnya: Seorang Ulama Islam pernah saya dengar mengajarkan: “Perbuatan amal dalam bulan Ramadhan, akan mendapat pahala 700 kali lipat” (Renungan di suatu bulan Ramadhan di TV). Dalam Injil dikatakan “Siapa meninggalkan harta untuk mengikuti Kristus, akan mendapat pahala 100 kali ganda”. Sebaliknya juga diberi gambaran hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan terlarang. Namun semua macam ajaran dan uraian itu termasuk dalam suasana lain dari ajaran etika murni. Semua ajaran itu masuk suasana iman, suasana ajaran “dari Tuhan” suatu suasana meta etis. Sedangkan etika murni adalah ajaran petunjuk dari nalar dan akal budi. Dalam Etika dicoba diberi alasan–alasan yang lalu memberi “kebaikan intrinsik” dari suatu perbuatan. Dalam agama ajaran itu sudah masuk absolutisme S. Reksosusilo, Hukum Karma 117 moral. Ajaran ini baik, karena sudah diajarkan Tuhan, manusia tinggal harus menerimanya (dan memang manusia yang beriman menerimanya). Dalam ajaran mengenai perbuatan dalam hukum karma tidak diteliti secara nalar sendi dan dasar perbuatan, karena itu uraiannya kurang mendalam mengenai tingkah laku sendiri. Justru akal budi manusia dalam etikalah yang lalu menggarap liku-liku tingkah laku itu dengan lebih luas dan terinci. Tadi disinggung bahwa dalam ajaran keagamaan hukum karma juga diberi ukuran konkret pahala dan hukuman perbuatan tetapi juga konkretnya hukuman dan pahala itu masih berupa, kalau boleh pakai istilah saya “konkret akhirat” bukan “konkret dunia ini” Karena itu dampaknya dapat menciptakan suasana batin yang tegang. Jelasnya begini : saya berbuat baik karena yakin akan pahalanya, jadi saya hitung-hitung terus, menunggu terus mana pahalanya. Kalau pahala belum datang, saya lalu berkata : yaah, tunggu nanti di akhirat. Sementara itu harus terus berbuat baik yang kadangkadang sukar. Nah, menunggu begini ini membawa ketegangan. Juga ketakutan akan hukuman akhirat merupakan “ketakutan” yang menegangkan, karena saya tak pernah tahu apakah perbuatan jahat saya sudah dihukum dan “karma”-nya sudah dihapus, lalu saya dapat mulai hidup baru yang bersih. Hukum karma hukum yang menegangkan. “Menunggu pahala dan ketakutan hukuman” yang tak pernah nyata inilah yang menyebabkan orang mudah tergiur untuk memilih harta benda yang nyata di dunia ini dan nekad saja melakukan perbuatan jahat yang dilarang agama. Kalaupun manusia berbuat baik dan meninggalkan yang jahat karena hukum karma, sifatnya selalu “tegang terpaksa” tidak berdasar tanggung jawab yang sadar, yang menjadi ideal manusia yang beretika tinggi. 5. KESIMPULAN Setelah segala uraian di atas, maka kami tarik kesimpulan: 1) Hukum karma adalah ungkapan hukum sebab akibat dalam segi perbuatan manusia, dalam arti ini hukum karma ialah universal, namun tidak masuk secara hakiki dalam etika yang intinya ialah menelusuri hakekat dan norma perbuatan manusia melalui akal budi. 2) Hukum karma memasuki hanya sebagian dari penalaran etis, yaitu penalaran etis yang mendasarkan buruk baik pada hukuman dan pahala. 3) Hukum karma sebagai pola pikir meta etis cenderung ke arah absolutisme etika agama, lalu kurang dapat dipakai menghadapi bermacam-macam pandangan etis dari bermacam-macam masyarakat manusia. 4) Hukum karma karena secara “konkret dunia” kurang (tidak dapat diketahui) secara kejiwaan hanya membawa keadaan jiwa yang tegang; karenanya orang cenderung tidak mengakuinya atau berusaha mengabaikannya. 118 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 5) Sebagai sarana menggalakkan hidup baik, membasmi kejahatan memang dapat berguna selama dikaitkan dengan iman dan absolutisme moral agama. Bahkan banyak agama di dalam ajarannya mencari usaha untuk tidak hanya menekankan hukum karma. Agama Hindu mencoba menekankan teori moksha. Agama Buddha yang mulai dari nirvana, memang menjurus ke arah hukum karma, namun akhirnya juga mencari bentuk pelepasan karma. Agama Islam dalam aliran sufi juga menekankan ketenangan mistik dari pada mencari pahala amal. Agama Kristen lebih menekankan Tuhan yang berbelas kasih dari pada Tuhan yang adil, Tuhan yang menghukum dan memberi pahala. Etika moral kristen menekankan cinta kasih dari pada ingat pahala dan hukuman. 6) Sebagai kesimpulan akhir yang juga merupakan saran, hukum karma dapat berguna mendorong manusia berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Namun dari segi etika perlu sekali dilandasi dengan sikap etis yang bertanggung jawab. Karena itu perlu ditekankan pendidikan dan penghayatan serta pengalaman norma-norma etika melalui pendidikan etika, moral Pancasila serta akhlak keagamaan. BIBLIOGRAFI Eliade, Mircea (ed.), The Encyclopedia of Religion, vol. 8, New York: Macmillan Publishers 1987. Fagothey, Austin, Right and Reason, New York: Mosby Company 1972. Singer, Peter (ed.), A Companion to Ethics, Oxford: Blackwell 1993. Winternit, Maurice, History of Indian Litterature, vol. 1, New Delhi: Oriental Book 1972. S. Reksosusilo, Hukum Karma 119 INFORMED CONSENT DAN OTONOMI MANUSIA J. Sudarminta STF Driyarkara, Jakarta Abstract : One of the crucial points in territory of medical service is ethical problem of informed consent. Is it necessary that a patient should be involved in decision making with regard to her/his medical treatment in spite of her/his ignorance? The question is crucial, as in fact a patient comes to a medical doctor or hospital simply because of his/her surrender to be treated insofar as he/she can recover his/ her health. It is almost impossible to consider that by coming to a hospital the patient is doubtful about medical treatment done in that hospital. In this article I try to draw some ethical considerations up from the fact that in spite of the patient’s ignorance regarding medical treatment, he is the autonomous person. The logical consequence of autonomy is that the person is free from any assumption that can reduce his/her authority upon his/her body. So, the article shall delve into discovering the relationship between informed consent and human autonomy. Keywords: informed consent, otonomi, pasien. Apakah para pasien perlu sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai apa yang akan diperbuat dalam rangka pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan mereka? Apakah mereka selalu harus dimintai persetujuan untuk apa yang akan dilakukan oleh dokter terhadap mereka? Bukankah pelibatan dan permintaan persetujuan macam itu malah akan menghambat kelancaran kerja? Apalagi, bukankah dengan datang pada dokter atau masuk rumah sakit mereka sudah mempercayakan diri mereka kepada dokter beserta tim medisnya? Seberapa jauh para pasien perlu diberitahu mengenai risiko dan keuntungan dari langkahlangkah pengobatan dan tindakan-tindakan lain yang harus diambil demi pemulihan kesehatannya? Bagaimana dengan pasien yang kalau diberitahu toh tidak mengerti apa maksudnya, atau pasien yang sengaja tidak mau tahu mengenai keadaan dirinya yang sebenarnya dan pokoknya dibuat lebih enak badan: masih perlukah mereka diberitahu? Apakah dokter wajib memberitahukan kemungkinan risiko yang akan terjadi dan alternatif pengobatan yang bisa diambil terhadap pasien, atau hal itu hanya dapat diharapkan berdasarkan kebaikan sang dokter? Itulah beberapa pertanyaan yang kadang muncul dalam praktek pelayanan medis. Pertanyaan-pertanyaan tersebut erat terkait dengan apa yang lazim disebut “informed consent”. Sebelum menelaah hubungan antara “informed consent” dan otonomi manusia – yang merupakan fokus perhatian makalah ini – kiranya perlu diperoleh keterangan terlebih dulu mengenai apa yang dimaksud dengan “informed consent”. 120 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 1. Pengertian Informed Consent Secara harafiah informed consent berarti persetujuan bebas yang didasarkan atas informasi yang diperlukan untuk membuat persetujuan tersebut. Dilihat dari pihakpihak yang terlibat, dalam praktek dan penelitian medis, pengertian “informed consent” memuat dua unsur pokok, yakni: (1) hak pasien (atau subyek manusiawi yang akan dijadikan kelinci percobaan medis) untuk dimintai persetujuan bebasnya oleh dokter (tenaga riset medis) dalam melakukan kegiatan medis terhadap pasien tersebut, khususnya apabila kegiatan itu memuat kemungkinan resiko yang harus ditanggung oleh pasien; (2) kewajiban dokter (tenaga riset medis) untuk menghormati hak tersebut dan untuk memberikan informasi seperlunya, sehingga persetujuan bebas dan rasional dapat diberikan oleh pasien. Dalam pengertian “persetujuan bebas” terkandung kemungkinan bagi si pasien untuk menerima atau menolak apa yang ditawarkan dengan disertai penjelasan atau pemberian informasi seperlunya oleh dokter (tenaga riset medis). Dilihat dari hal-hal yang perlu ada agar “informed consent” dapat diberikan oleh pasien, maka, seperti dikemukakan oleh Tom L. Beauchamp dan James F. Childress,1 dalam pengertian “informed consent” terkandung empat unsur, dua menyangkut pengertian “informasi” yang perlu diberikan dan dua lainnya menyangkut pengertian “persetujuan” yang perlu diminta. Empat unsur itu adalah: (1) pembeberan informasi; (2) pemahaman informasi; (3) persetujuan bebas; dan (4) kompetensi untuk membuat persetujuan. Mengenai unsur pertama, pertanyaan pokok yang biasanya muncul adalah sampai seberapa jauh pembeberan informasi itu perlu dilakukan. Dengan kata lain, sampai seberapa jauh seorang dokter wajib memberikan informasi yang diperlukan agar persetujuan yang diberikan oleh pasien atau subyek riset medis dapat disebut suatu persetujuan yang informed. Dalam menjawab pertanyaan ini dikemukakan adanya tiga standar pembeberan, yakni (a) standar praktek profesional (the professional practice standard); (b) standar pertimbangan akal sehat (the reasonable person standard); dan (c) standar subyektif atau orang per orang (the subjective standard).2 Dengan “standar praktek profesional” dimaksudkan kaidah-kaidah prosedural yang secara resmi sudah dibakukan dan dijadikan landasan praktek profesi, dalam hal ini profesi medis. Patokan umum tentang berapa banyak dan informasi macam apa yang perlu disampaikan oleh dokter kepada pasien ditetapkan berdasarkan kebiasaan dalam praktek oleh kelompok profesi dokter. Hanya kesaksian ahli dari anggota kelompok profesi itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah seorang dokter telah melanggar hak pasien untuk mendapat informasi seperlunya atau tidak. Standar praktek profesional dibuat berdasarkan keyakinan bahwa peran utama dokter adalah untuk bertindak demi kepentingan medis yang paling baik bagi 1 2 Dalam bukunya Principles of Biomedical Ethics, New York. Oxford: Oxford University Press, 1983, hlm. 70. Ibid., hlm. 74-79. J. Sudarminta, Informed Consent dan Otonomi Manusia 121 pasien. Kewajibannya untuk membeberkan informasi adalah sekunder dan tergantung pada pertimbangan dan putusan medis tentang kepentingan yang paling baik bagi pasien. Maka garis-garis panduan pelaksanaan pembeberan informasi lebih ditentukan oleh standar perawatan medis daripada oleh hak-hak pasien. Sebagai kriteria yuridis atau legal biasanya standar praktek profesional ini yang diacu. Akan tetapi karena standar tersebut kadang masih terlalu memihak pada kepentingan dokter dan rumah sakit, maka belakangan juga semakin ditekankan perlunya dipakai “standar pertimbangan akal sehat”. Yang dimaksud adalah ukuran tentang seberapa banyak informasi dan informasi macam apa yang perlu dibeberkan pada pasien tidak hanya ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan putusan kelompok para ahli medis, tetapi juga berdasarkan pertimbangan akal sehat biasa. Maka yang dijadikan pedoman adalah informasi material mana berdasarkan pertimbangan obyektif akal sehat perlu disampaikan agar pasien dapat mengambil keputusan yang rasional. Sedangkan yang dimaksud dengan “standar subyektif” atau standar orang per orang adalah tolok ukur yang dikaitkan dengan situasi dan kondisi masing-masing pasien yang bersangkutan. Macam informasi yang perlu diberikan dan seberapa banyak, perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien yang bersangkutan. Karena persetujuan bebas pasien mengenai apa yang akan diperbuat terhadap dirinya bukan hanya merupakan suatu putusan teknis-medis maupun yuridis belaka, tetapi juga suatu putusan moral, maka pertimbangan khusus menyangkut pribadi pasien yang bersangkutan, seperti misalnya kepercayaan dan sistem nilainya, sejarah kesehatannya, ciri-ciri watak dan perilakunya, sedapat mungkin juga ikut diperhitungkan. Konsep “informed consent” dapat dikatakan merupakan suatu konsep yang relatif masih baru dalam sejarah etika medis. Secara historis konsep itu muncul sebagai suatu prinsip yang secara formal ditegaskan hanya setelah Perang Dunia II, yakni sebagai reaksi dan tindak lanjut dari apa yang disebut pengadilan Nuremberg,3 yakni pengadilan terhadap para penjahat perang zaman Nazi. Prinsip “informed consent” merupakan reaksi terhadap kisah-kisah yang mengerikan tentang pemakaian manusia secara paksa sebagai kelinci percobaan medis di kamp-kamp konsentrasi. Sejak pengadilan Nuremberg, prinsip “informed consent” cukup mendapat perhatian besar dalam etika biomedis. Dalam aturan no. 1 Kode [Etik] Nuremberg dapat kita temukan rumusan sebagai berikut: “Persetujuan bebas subyek manusiawi secara mutlak esensial. Ini berarti bahwa orang yang terlibat haruslah memiliki kemampuan legal untuk memberikan persetujuan; ia mestilah berada dalam situasi yang memungkinkan untuk melaksanakan kuasa bebasnya untuk memilih tanpa campur tangan dalam salah satu bentuk paksaan, pemalsuan, penipuan, kekerasan, atau bentuk-bentuk hambatan dan pemaksaan lain; ia juga harus memiliki pengetahuan cukup dan pemahaman tentang perkaranya sehingga ia mampu membuat keputusan yang ia pahami dengan terang. Unsur yang 3 122 Ibid., hlm. 66; Carolyn Faulder, Whose Body Is It?: The Troubling Issue of Informed Consent, London: Virago Press Limited, 1985, hlm. 12. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 disebut belakangan ini mengandaikan bahwa sebelum subyek manusiawi yang akan menjalani eksperimen itu memberikan persetujuannya ia harus diberitahu mengenai sifat, lamanya, dan maksud dari eksperimen tersebut; metode dan sarana yang akan diambil; semua ketidakenakan dan bahaya-bahaya yang mungkin terjadi; dan dampaknya terhadap kesehatannya atau pribadinya yang mungkin terjadi akibat partisipasinya dalam eksperimen.” Dalam hukum Inggris-Amerika, ajaran tentang “informed consent” juga berkaitan dengan kasus-kasus malapraktek dokter yang melibatkan perbuatan tertentu pada tubuh pasien yang kompeten tanpa persetujuannya. Perbuatan tertentu pada tubuh pasien yang kompeten tanpa persetujuannya dalam kasus-kasus tersebut dipandang tidak dapat diterima lepas dari pertimbangan kualitas pelayanan. Mengingat pentingnya “informed consent” dalam pelayanan medis, maka dalam salah satu butir panduan (yakni butir no. 11) dari “Butir-butir Panduan Etis untuk Lembaga-Lembaga Pelayanan Medis Katolik” di Amerika terdapat pernyataan sebagai berikut:4 “Pasien adalah pembuat keputusan utama dalam semua pilihan yang berhubungan dengan kesehatan dan perawatannya. Ini berarti ia adalah pembuat keputusan pertama, orang yang diandaikan memprakarsai keputusan berdasarkan keyakinan hidup dan nilai-nilainya. Sedangkan pembuat keputusan sekunder lainnya juga mempunyai tanggung jawab. Jika si pasien secara hukum tidak mampu membuat keputusan atau mengambil inisiatif, seorang pelaku yang lain yang menggantikan si pasien—biasanya keluarga si pasien, kecuali kalau sebelumnya pasien telah menunjuk orang lain atau kalau saudara kandungnya dianggap tidak memenuhi syarat—bertanggungjawab untuk berusaha menentukan apa yang kiranya akan dipilih oleh si pasien, atau jika itu tidak mungkin, berusaha menentukan apa yang akan paling menguntungkan bagi si pasien. Para pemegang profesi pelayanan kesehatan juga merupakan pembuat keputusan kedua, dengan tanggung jawab menyediakan pertolongan dan perawatan untuk pasien sejauh itu sesuai dengan keyakinan hidup dan nilai-nilai mereka. Kebijakan dan praktek rumah sakit harus mengakui serangkaian tanggung jawab ini. Para pemegang profesi pelayanan kesehatan bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang mencukupi dan untuk memberikan dukungan yang memadai kepada si pasien, sehingga ia mampu membuat keputusan yang dilandasi pengetahuan mengenai perawatan yang semestinya dijalani. Perlu disadari bahwa bantuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam perawatan kesehatan. Kebijakan dan dokumen mengenai “informed consent” haruslah diupayakan untuk meningkatkan dan melindungi otonomi pasien, bukan pertama-tama untuk melindungi rumah sakit dan petugas pelayanan medis dari perkara pengaduan hukum.” 4 Dikutip dalam Richard A. McCormick, Health and Medicine in The Catholic Tradition, New York: Crossroad, 1987, hlm. 11 dan hlm. 107. J. Sudarminta, Informed Consent dan Otonomi Manusia 123 2. Hubungan antara informed consent dan otonomi manusia Setelah kita lihat pengertian umum tentang “informed consent”, bagaimana latar belakang historis kemunculannya dan rumusan kode etiknya, kini dapat kita masuki pembicaraan tentang hubungan antara pengertian tersebut dengan otonomi manusia. Kita mulai dengan mendalami pengertian otonomi manusia. Istilah “otonomi” yang berasal dari akar kata Yunani autos (diri sendiri) dan nomos (hukum, aturan, penentuan), secara harafiah berarti “penentuan dan pengaturan diri sendiri”. Istilah tersebut pertama kali dipakai untuk menunjuk pada pengaturan dan pemerintahan sendiri dalam negara-kota (polis) Yunani Kuno. Dalam konteks moral, konsep “otonomi” pertama kali ditekankan oleh Immanuel Kant yang memperlawankannya dengan konsep “heteronomi” (penentuan dari luar; heteros = asing, luar). Bagi Kant, moralitas secara hakiki mengandaikan adanya pribadi yang otonom, yakni pribadi yang menyadari bahwa hukum moral bukan merupakan suatu penentuan sewenangwenang dari luar dirinya, melainkan suatu penentuan bebas diri manusia sendiri sebagai makhluk rasional. Pribadi yang bermoral otonom adalah pribadi yang melaksanakan kewajiban moralnya bukan karena takut dihukum atau mau mencari pujian dari luar, tetapi karena ia sendiri memang menghendakinya, karena ia menyadari bahwa hal itu bernilai pada dirinya dan bahwa dalam melakukan kewajiban tersebut ia memenuhi tuntutan kemanusiaannya. Secara umum, istilah otonomi berarti kebebasan untuk memilih, menentukan diri dan bertindak tanpa hambatan, paksaan atau campur tangan dari luar. Salah satu prinsip etika dasar yang juga penting untuk etika biomedis adalah prinsip otonomi. Prinsip ini merupakan suatu perintah moral yang mewajibkan kita untuk menghormati otonomi manusia. Setiap manusia, sebagai makhluk yang rasional dan berkehendak bebas, adalah seorang pribadi yang wajib dihormati otonominya. Menghormati otonomi manusia berarti mengakui haknya sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan kebebasan untuk memilih, menentukan diri dan bertindak sesuai dengan kesadaran akan apa yang diyakininya sebagai paling baik untuk dirinya. Seperti pernah dikemukakan oleh I. Kant, sikap hormat terhadap otonomi manusia pada dasarnya berakar dalam prinsip hormat terhadap manusia sebagai pribadi atau person. Salah satu rumusan yang dia berikan sebagai imperatif kategoris berbunyi: “Bertindaklah sedemikian rupa, sehingga Anda memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam diri orang lain, senantiasa sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai sarana.”5 Sama sekali tidak menghormati otonomi orang berarti memperlakukan orang itu melulu sebagai sarana, karena ia diperlakukan berdasarkan hukum atau aturan yang sama sekali tidak ia kehendaki. Sama sekali menolak pertimbangan dan putusan seseorang atau menghalanginya untuk melaksanakan kemampuannya untuk menentukan diri secara 5 124 Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, Translated by Thomas K. Abbot, New York: The Bobbs-Merrill Co., 1949: hlm. 46. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 rasional berarti melecehkan martabat kemanusiaannya sebagai person, karena keluhuran martabat manusia sebagai person justru paling nyata dalam tindakannya menentukan diri secara rasional. Apa hubungan semua ini dengan prinsip informed consent? Prinsip informed consent yang mewajibkan dokter atau periset medis untuk meminta persetujuan bebas pasien atau orang yang akan dijadikan subyek percobaan medis seraya memberikan informasi yang diperlukan guna dapat mengambil keputusan secara bebas rasional, pada dasarnya berakar pada prinsip hormat terhadap otonomi manusia. Dan prinsip hormat terhadap otonomi manusia sendiri pada gilirannya merupakan salah satu perwujudan sikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia sebagai person. Fungsi pokok diberlakukannya prinsip informed consent adalah untuk melindungi dan memajukan otonomi pasien sebagai individu manusia.6 Memang pemberlakuan prinsip itu juga dapat berfungsi sebagai perlindungan pasien dan subyek manusiawi dari kemungkinan tindak sewenang-wenang, penipuan, kekerasan, penyalahgunaan dan pemerasan terselubung yang dilakukan oleh petugas atau periset medis.7 Dengan demikian informed consent berfungsi menghindarkan pasien atau subjek manusiawi dari berbagai resiko yang merugikan dirinya. Akan tetapi kesemuanya itu akan lebih dapat dihindarkan kalau otonomi individu manusia lebih dihormati dan dimajukan. Informed consent dimaksudkan agar komunikasi antara seorang pemegang profesi medis dan seorang pasien dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga pasien dapat dihindarkan dari situasi ketidaktahuan (entah karena kurang informasi atau karena informasi yang ia terima tidak dapat ia pahami) untuk mengambil keputusan secara otonom. Di sini unsur pemberian informasi yang mencukupi dan pemahaman atas informasi yang diberikan tersebut dipandang penting untuk dapat mengambil keputusan secara otonom. Menghormati otonomi manusia dalam hal ini juga berarti mengakui hak pasien untuk mengetahui keadaan dirinya dan untuk mengambil keputusan tentang apa yang akan diperbuat oleh petugas medis terhadap tubuhnya. Tubuh pasien sebagai tubuh manusia tidak boleh diperlakukan melulu sebagai seonggok daging hidup dengan jaringan, organ dan fungsi kerjanya secara biologis. Tubuh pasien adalah bagian integral dari keluhuran martabat pribadinya sebagai manusia, maka perlu diperlakukan dengan hormat.8 Pasien, 6 7 8 Tom L. Beauchamp & James F. Childress, ibid., hlm. 67. Alexander Capron, seperti dikutip oleh Tom L. Beauchamp & James F. Childress (idem), misalnya menyebutkan enam fungsi pemberlakuan prinsip informed consent, yakni: a. pemajuan otonomi individu; b. perlindungan pasien dan subjek manusiawi; c. penghindaran dari penipuan dan kekerasan; d. dorongan bagi para pemegang profesi medis untuk memeriksa diri; e. pemajuan pengambilan keputusan yang rasional; f. pelibatan publik (dalam memajukan otonomi sebagai nilai sosial umum dan dalam mengontrol penelitian biomedis). Dalam Discourse to the members of the 35th General Assembly of the World Medical Association, tgl. 29 Oktober 1983, Paus Johanes Paulus II antara lain menyatakan sebagai berikut: “Setiap pribadi manusia dalam ketunggalannya yang secara mutlak unik, tidak hanya terbentuk oleh rohnya, tetapi juga oleh tubuhnya. Maka dalam tubuh dan melalui tubuh, orang bersentuhan dengan pribadi manusia sendiri dalam realitasnya yang konkret. Maka, menghormati keluhuran martabat manusia berarti menjaga identitas manusia ini corpore et anima unus [tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan], sebagaimana pernah dinyatakan oleh Konsili Vatikan II [dalam Gaudium et Spes, no. 14, par. 1]. J. Sudarminta, Informed Consent dan Otonomi Manusia 125 walaupun dalam keadaan lemah dan tergantung pada orang lain, tetap mempunyai otonomi atas tubuhnya, sehingga apa yang mau diperbuat atas tubuh tersebut sudah selayaknya kalau mendapat persetujuannya. Dalam etika biomedis, prinsip otonomi memang bukan satu-satunya prinsip yang perlu dipegang, karena dalam pelaksanaan perlu diperhatikan juga prinsipprinsip lain, seperti prinsip tidak melakukan yang buruk (the principle of non-maleficence), prinsip melakukan yang baik (the principle of beneficence), dan prinsip keadilan (the principle of justice). Setiap prinsip tidak berlaku mutlak pada dirinya sendiri, tetapi berlaku prima facie. Artinya, prinsip itu pada dirinya sendiri mengikat sejauh tidak ada prinsip lain yang bertabrakan dengannya. Bila terjadi tabrakan, mana yang harus didahulukan, baru dapat ditentukan mengingat faktor-faktor yang senyatanya ada dalam kasus konkret. Melulu mempertahankan prinsip otonomi matimatian tanpa mengindahkan prinsip-prinsip yang lain, dalam kenyataan seringkali lebih merugikan banyak pihak (termasuk kepentingan pasien sendiri) daripada menguntungkannya. Dalam praktek medis, misalnya dikenal apa yang disebut paternalisme, yakni tindakan yang membatasi otonomi pasien dengan maksud mencegah kerugian bagi dirinya atau melakukan sesuatu yang baik yang tidak dapat ditempuh dengan cara lain. Ini berarti mendahulukan prinsip berbuat baik di atas prinsip otonomi. Prinsip informed consent, yang seperti sudah dikemukakan di atas mempunyai fungsi pokok untuk melindungi dan memajukan otonomi manusia, memang dimaksudkan untuk melawan bentuk-bentuk paternalisme yang cenderung melecehkan kemampuan dan kebebasan pasien untuk menentukan diri secara rasional. Akan tetapi, seperti pernah dikemukakan oleh Dr. K. Bertens dan dr. Sutanto Gandakusuma,9 tidak semua bentuk paternalisme secara moral tidak dapat dibenarkan. Apalagi, dalam pelaksanaan, prinsip otonomi juga seringkali erat terkait dengan kondisi sosio-budaya dan politik suatu masyarakat. Dalam masyarakat Barat, di mana alam liberalisme cukup dominan atau kebebasan individu dijunjung tinggi, sikap paternalistik secara keras ditolak. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, prinsip otonomi, dan dengan demikian juga prinsip informed consent, sangat ditekankan. Sedangkan di Indonesia, di mana budaya feodal dan paham kolektivisme di sanasini masih menggejala ditambah lagi dengan kehidupan politik yang cenderung alergi terhadap kebebasan individu, prinsip otonomi dan dengan demikian juga prinsip informed consent masih belum banyak dilaksanakan. Akan tetapi, karena salah satu arus besar dalam perkembangan zaman yang ditandai oleh budaya global dewasa ini adalah meningkatnya kesadaran manusia akan otonominya, maka di Indonesia pun prinsip informed consent akan semakin tidak dapat diabaikan oleh para petugas medis. Apalagi kalau tingkat pendidikan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat bertambah serta tuntutan ke arah demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan semakin besar, maka para pasien dan publik pada umumnya juga akan semakin kritis dan sadar akan hak-haknya. Mereka akan menuntut haknya untuk diberi 9 126 Dalam “Paternalisme: Penyakit Para Dokter?”, Seri Etika Biomedis, no. 3, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, 1987. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 informasi secukupnya dan semakin dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka. Aturan-aturan hukum yang akan menjamin hak-hak pasien kecenderungannya juga akan semakin diperjuangkan. Apakah para pemegang profesi medis siap menghadapi tantangan ini? Moga-moga demikian halnya. BIBLIOGRAFI Beauchamp, Tom L. & Childress, James F. Principles of Biomedical Ethics. New York. Oxford: Oxford University Press, 1983. Beauchamp, Tom L. & Walters, (Eds.). Contemporary Issues in Bioethics. Belmont, CA: LeRoy Wadsworth Publishing Company, Inc., 1978. Bertens, Dr. K. dan Sutanto Gandakusuma, dr. “Paternalisme: Penyakit Para Dokter?” dalam Seri Etika Biomedis, No. 3. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, 1987. Faulder, Carolyn. Whose Body Is It? The Troubling Issue of Informed Consent. London: Virago Press Limited, 1985. Fletcher, Joseph. Morals and Medicine. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979. Kant, Immanuel. Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals. Transl. By Thomas K. Abbott. New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1949. McCormick, Richard A. Health and Medicine in The Catholic Tradition. New York: Crossroad, 1987. Ramsey, Paul. The Patient as Person, Exploration in Medical Ethics. New Haven: Yale University Press, 1970. Warner, Richard. Morality in Medicine. An Introduction to Medical Ethics. Sherman Oaks, CA: Alfred Publishing Co, Inc., 1980. J. Sudarminta, Informed Consent dan Otonomi Manusia 127 PENDERITAAN ORANG YANG TAK BERSALAH - Perspektif Fenomenologi Agama Sermada Kelen Donatus STFT Widya Sasana, Malang Abstract: The article is the modification of my paper seminar in German held in Bonn University 1992. The material was taken from the article of Prof. Hans-Joachim Klimkeit, “Der leidende Gerechte in der religionsgeschichte – Ein Beitrag zur problemorientierten “Religionsphänomenologie (the suffering of the just person in history of religion - a contribution to phenomenology of religion). The author modifies it and rewrites the idea in three parts: phenomenology of religion that exposes problem orientation, history of religion that articulates the reality of the suffering of the just, and the application of the topics in modern context of our life. Keywords: fenomenologi, agama, orang tak bersalah, penderitaan. Bahan tulisan ini didasarkan pada artikel Professor Hans-Joachim Klimkeit, dengan judul Der leidende Gerechte in der Religionsgeschichte - Ein Beitrag zur problemorientierten “Religionsphänomenologie” (Orang tak-bersalah yang menderita dalam Sejarah Agama - Satu sumbangan untuk Fenomenologi Agama yang berorientasi pada problem). Penulis menggodoknya kembali ke dalam tiga bagian. Diawali dengan pemberian arti terhadap Fenomenologi Agama yang berorientasi pada problem, lalu arti Fenomenologi Agama yang demikian coba ditemukan dalam empat stadium historis yang di dalamnya gagasan keadilan dan konsep tentang penderitaan orang yang tak bersalah diartikulasikan, lalu pada bagian terakhir penulis membuat aplikasi yang mungkin berguna untuk realitas kehidupan modern. 1. ARAH BARU FENOMENOLOGI AGAMA Fenomenologi agama dalam arti klasik tidak menonjolkan usaha penetapan dan penentuan ruang lingkup historis dan sosiologis, yang menjadi tempat munculnya fenomen-fenomen religius. Fenomenologi ini yang tentu berlandaskan pada pemahaman fenomenologi Husserl hanya melukiskan dan membandingkan fenomenfenomen religius “sebagaimana fenomen-fenomen itu tampak pada kita”.1 Bila kita 1 128 Klimkeit, Hans-Joachim: Der leidende Gerechte in der Religionsgeschichte. Ein Beitrag zur problemorietierten “Religionsphänomenologie”. In: Religionswissenschaft. Eine Einführung. Zinser, Hartmut (Hg.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988, hlm. 164, bdk. Hamersma, Harry: Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1984, hlm. 114-117. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 berhadapan dengan obyek tertentu dan hendak berkata-kata tentangnya, kita membiarkan obyek itu bersama gejala-gejalanya berbicara kepada kita. Kita hanya melukiskan bagaimana obyek itu tampil pada kita sebagaimana adanya. Husserl mengemukakan metode reduksi sebagai alat bantuan untuk itu: menyingkirkan segala sesuatu yang bersifat subyektif, menyingkirkan seluruh pengetahuan kita tentang obyek yang diselidiki dan menyingkirkan tradisi pengetahuan yang membentuk kita. Kita harus “kembali kepada benda itu sendiri” (Zurück zu den Sachen selbst) supaya hakekat benda itu dapat kita tangkap secara intuitif. Untuk memperluas konsep klasik itu, Gerard van der Leeuw mengemukakan keterkaitan subyek dalam setiap perspektif dan perlukisan. Fenomenologi agama yang dikembangkan Gerard van der Leeuw turut meneliti hubungan yang saling mempengaruhi antara subyek dan obyek ketika subyek berhadapan dengan obyek yang mau diteliti.2 Tetapi pendekatan fenomenologis dari G. van der Leeuw belum lengkap sepenuhnya, karena van der Leeuw tidak memperhitungkan proses hermeneutis untuk mengerti kehidupan religius seperti metode hermeneutik yang dikembangkan oleh Otto Friedrich Bollnow dan Wilhem Dilthey. Justru untuk mengerti arti dari fenomen-fenomen religius secara lebih mendalam, proses hermeneutis dipandang penting; proses ini memberi tempat bagi penjelasan menyeluruh yang bersifat historis, sosiologis, psikologis dsb. Fenomenologi yang memperhitungkan proses itu membuka horizon untuk penelitian lebih lanjut tentang karakter religius yang melekat pada semua fenomen. Mircea Eliade ketika meneliti secara historis fenomen-fenomen religius dari berbagai macam agama berlangkah lebih jauh menuju hal-hal yang bersifat meta-historis, yaitu “Hierophani” (penampakan Yang Kudus dalam ruang dan waktu) sebagai obyek penelitian sejarah agamanya.3 Tetapi Fenomenologi yang dipromosikan Eliade tidak hanya berhenti pada usaha perlukisan bentuk-bentuk penampakan Yang Kudus dalam struktur ruang dan waktu. Ia menelusuri juga problem-problem manusiawi universal yang berhubungan dengan penampakan Yang Kudus itu. Justru garis pemikiran Eliade itulah yang memberi inspirasi kepada ahli ilmu agama untuk memberikan satu arah baru pada fenomenologi agama. Hans-Joachim Klimkeit menyebutnya “problemorientierte Religionsphänomenologie”, yaitu satu fenomenologi agama yang berorientasi pada problem-problem humanistik yang universal.4 Titik tolak perlukisan fenomenologis dalam arah baru ini tidak hanya terarah kepada perlukisan bentuk-bentuk lahiriah, ritus, kultus, simbol-simbol, dsb., tetapi juga perlu menyentuh pertanyaan-pertanyaan mendasar dan universal yang menimpa umat manusia di sepanjang sejarahnya. Beberapa pertanyaan dasar yang universal dapat kita sebutkan demikian. Bagaimana dapat dipahami hubungan manusia dengan nasib hidup yang menimpanya dan kebebasannya? Bagaimana dapat dijelaskan 2 3 4 Ibid, hlm. 164. Ibid, hlm. 165, bdk. Eliade, Mircea: Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1986, hlm. 21-37. Ibid, hlm. 165. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 129 hubungan antara otonomi dan heteronomi dalam setiap agama di sepanjang sejarah umat manusia? Bagaimana dapat diperlihatkan penyelenggaraan ilahi terhadap hidup setiap manusia dan proses realisasi diri manusia? Bagaimana dapat dipecahkan persoalan-Theodizea? Salah satu contoh yang menjadi tema utama tulisan ini justru termasuk dalam lingkaran problematika humanistik universal itu, yaitu persoalan penderitaan orang-orang yang tak bersalah dan hukum keadilan. Bagaimana persoalan ini disikapi oleh manusia di sepanjang sejarahnya dan apa gambaran keadilan dalam fase-fase sejarah umat manusia? Dengan merujuk kepada arah baru dari Fenomenologi agama yang demikian, kita coba menemukan dan mengerti struktur dasar problematika penderitaan orangorang yang tak bersalah dalam satu horison yang memuat garis-garis pemikiran dasar tentangnya pada beberapa stadium historis tertentu. Hans-Joachim Klimkeit mentematisir gagasan Hans Heinrich Schmid dalam manuskrip Schmid tentang keadilan dan problematika yang berhubungan dengan itu. Bahan-bahannya diolah dari berbagai macam sumber seperti dari dunia Mesir kuno, Yunani kuno, dunia Timur kuno, dari sumber Perjanjian Lama dsb.5 Stadium historis di sini dimengerti sebagai fase-fase pengalaman manusia akan problematika manusia tak bersalah yang menderita dalam konteks pemahaman tentang keadilan. 2. KEADILAN DAN PENDERITAAN ORANG YANG TAK BERSALAH DALAM TERANG FENOMENOLOGI AGAMA 2.1. Keadilan dan penderitaan orang yang tak bersalah dalam kebudayaan arkais Kebudayaan arkais secara umum merujuk kepada kebudayaan kuno atau tua dan dikenakan pada kebudayaan asli sebelum dimulainya tradisi tulisan.6 Di dalam kebudayaan arkais, hidup manusia banyak sekali ditentukan oleh nasib yang menimpa manusia secara tak terduga. Nasib memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat “tidak dapat diramal dan tidak dapat dikalkulasikan”. Kekuatannya dengan sifat seperti itu justru melingkupi manusia. Untuk berhadapan dengan kekuatan nasib seperti ini, manusia arkais berusaha untuk mengamankan dirinya dari genggaman nasib melalui perbuatan kultis dan magis. 5 6 130 Ibid, hlm. 165-166. Kebudayaan arkais bisa mencakup kebudayaan lisan yang memiliki semua tradisi yang tidak menemukan dan mengembangkan tulisan. Penemuan tulisan menurut Wilhem Dupré jatuh pada zaman Neolitikum, dan masa itu dipandang sebagai garis pemisah antara kebudayaan lisan dan kebudayaan tulisan. Dupré memasukkan kebudayaan suku pemburu, pengumpul hasil hutan, suku pengembang cocok tanam dan pemelihara ternak ke dalam kebudayaan kuno atau tua. Dupré, Wilhem: Ethik und Religion in schriftlosen Kulturen. In: Ethik in nichtchristlichen Kulturen. Antes, Peter u.a. (Hg.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1984, hlm. 168-173. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Dalam fase ini orang hampir tidak berbicara apapun tentang penderitaan manusia yang tidak bersalah.7 Belum ada refleksi banyak tentang pengalaman manusia yang demikian. Itu tidak berarti bahwa tidak ada persoalan tentangnya. Persoalan kemanusiaan universal seperti persoalan tentang kematian, tentang keadilan, tentang kekuasaan nasib, dsb. sudah ada saat itu, tetapi konsepsi tentang satu tata tertib yang adil dan terpercaya untuk menegakkan keadilan sebagai satu keutamaan manusiawi belum dipikirkan banyak, meskipun struktur kehidupan sosial-ekonomis dan rohaniah mungkin berjalan baik. Di dalam kebudayaan arkais tidak ditemukan satu konsepsi yang memuat pemahaman-pemahaman refleksif tentang satu tata tertib menyeluruh yang dijadikan sebagai alat untuk menjamin tata tertib hidup manusia. Karakter “tidak dapat diramal dan tidak dapat dikalkulasikan” pada kekuatan nasib justru membayangi dan melatarbelakangi hidup manusia arkais secara buta dan gelap. Meskipun buta dan gelap, kekuatan nasib tetap berperanan secara hiduphidup untuk menuntun hidup mereka. Menariknya bahwa manusia arkais dengan jelas mengungkapkan dan memperlihatkan kekuatan-kekuatan nasib ini melalui ceritera-ceritera mitos dan melalui kepercayaan kepadanya. Di Yunani kuno Moiren adalah para dewi penentu nasib yang memainkan peranan terhadap manusia secara tak terduga, sebelum terciptanya pemahaman tentang Themis, yaitu dewi pelindung hukum, dan Dike, yaitu dewa penegak keadilan.8 Di Mesopotamia pengertian “Me” memperlihatkan satu kekuatan nasib yang bersifat gelap dan tidak dapat dikalkulasikan, meskipun “Me” mempunyai banyak arti.9 “Me” mengungkapkan pengaruh dewa langit “An” terhadap raja. Dalam satu lagu yang ditujukan kepada dewa langit orang memohon kepada dewa ini bagi kepentingan raja Lipitistar von Isin supaya “Me” bersatu erat dengan sang raja. Di dalam masyarakat arkais di Indonesia kita dapat menemukan kekuatan-kekuatan penentu nasib itu melalui kepercayaan masyarakat akan takdir10 atau melalui ceritera mitos 7 8 9 10 Kliemkeit, Hans-Joachim: Der leidende Gerechte... Op.cit., hlm. 166-167. Di dalam mitologi Yunani, Moiren adalah ketiga putri dewa Zeus dan Themis. Ketiga putri itu adalah Klotho sebagai pemintal benang kehidupan, Lachesis sebagai penentu nasib hidup, dan Atropos sebagai pemotong jalan kehidupan yang tidak dapat dihindari manusia. Themis adalah personifikasi ilahi dan pelindung hukum. Dia (Themis) adalah puteri Uranos (dewa langit) dan Gaä (dewi bumi). Themis dan Zeus melahirkan tiga puteri dengan nama Horen dan tiga puteri dengan nama Moiren. Dike menurut Hesiod adalah satu dari tiga Horen. Itu berarti bahwa Dike juga puteri dari Themis dan Zeus. Dike dipersonifikasikan dengan hukum dan tata tertib. Sebelum hukum dan tata tertib dipahami, sudah ada kekuatan-kekuatan nasib yang menjelma dalam Moiren. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Lexikonverlag. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1976. Band 6, hlm. 823; Band 12, hlm. 264; Band 16, hlm. 387; Band 23, hlm. 401. Terjemahan yang tepat kata “Me” ke dalam bahasa lain menurut Schmid hampir tidak mungkin dibuat. Schmid sendiri membagikan pengertian “Me” ke dalam tiga kelompok. “Me” berarti: 1. Tata tertib, yaitu tata tertib dunia dan tata tertib budaya, juga tata tertib ilahi yang bersifat kekal dan tak berubah. 2. Suruhan, perintah, peraturan, keputusan dsb. 3. Kekuatan ilahi yang khusus (fungsi ilahi) atau kuasa ilahi, kekuatankekuatan ilahi, divine power, kekuasaan yang numinous, mana dsb. Schmid, Hans Heinrich: Gerechtigkeit als Weltordnung. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968, hlm. 61-65. Takdir berasal dari bahasa Arab dan berarti ketentuan, perkiraan, ukuran, ketetapan, keputusan. Dalam Ilmu Tauhid, takdir dimaksudkan keputusan Tuhan yang berlaku bagi semua makhlukNya, termasuk manusia. Allah paling berkuasa untuk menentukan baik atau buruk bagi manusia. Pengertian teologis ini mewarisi sisa-sisa pengertian arkais tentang kekuatan-kekuatan nasib yang menggenggam manusia. Surat Wedhatama Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 131 seperti misalnya ceritera mitos tentang “Hambaruan” dari suku Ngaju-Dayak, Kalimantan.11 Beberapa contoh yang disebutkan para ahli fenomenologi ini menyingkapkan satu gagasan dasar bahwa kekuasaan nasib atau takdir atas hidup begitu kuat, sehingga manusia arkais dalam fase ini harus menerimanya sebagai sesuatu yang wajar ada. Orang tidak perlu mempersoalkannya. Bila seseorang menderita, maka penderitaannya pun diterima sebagai satu nasib atau takdir. Satu konsep tentang keadilan yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk refleksi tentang ada tidaknya dosa dan kesalahan manusia yang menderita belum terpikirkan. 2.2. Keadilan dan penderitaaan orang yang tak bersalah dalam fase kedua Sejarah Mesir kuno mencerminkan fase kedua pengalaman manusia yang sudah agak berbeda dengan pengalaman manusia dalam kebudayaan arkais. Fase ini adalah fase kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mengikuti satu hukum tata tertib dunia yang mencakup dan meliputi semua bidang kehidupan.12 Di dalam hukum tata tertib ini si penguasa bertugas untuk menjamin tata tertib dunia ini yang dipandang dan dinilai sebagai tata tertib kosmis yang bersifat ilahi. Relasi sosialekonomis dan politis dalam masyarakat, bahkan terbentuknya kerajaan, tidak hanya membiarkan bertumbuhnya satu mitos tentang kosmos yang teratur dan chaos sebagai lawannya, tetapi juga memungkinkan berkembangnya pemahaman tentang satu hukum tata tertib kosmis yang bersifat ilahi, hukum tata tertib yang menjamin baik kehidupan masyarakat maupun kehidupan perorangan. Tata tertib ini adalah satu keseluruhan yang menuntun segalanya secara teratur; dia adalah satu tata tertib yang adil dan benar, karena dia memperlihatkan tata tertib kosmis yang bersifat ilahi. Keadilan identik dengan hukum tata tertib kosmis yang ilahi. 11 12 132 dan Wulangreh mengingatkan manusia akan takdir. Effendi, Mochtar, S.E. Dr : Ensiklopedi Agama dan Filsafat. Buku 6. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001, hlm. 108-109, bdk. Magnis-Suseno, Franz: Etika Jawa. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. 135-137 dan 151-152. Hambaruan adalah jiwa manusia, dan juga jiwa binatang. Hambaruan menggerakkan tubuh. Ia boleh dikatakan substansi kehidupan atau kekuatan hidup. Pada umumnya Hambaruan memiliki karakter tak berpribadi dan dapat meninggalkan tubuh ketika manusia tidur atau tampak dalam mimpi berupa manusia lain. Ia hanya berada dalam manusia yang masih hidup. Ketika manusia mati, Hambaruan kembali bersatu dengan Mahatala, wujud tertinggi suku Ngaju-Dayak dan membangun tujuh substansi (emas, perak, besi, padi, dsb.) sedemikian sehingga tercipta Hambaruan yang baru. Hambaruan yang baru ini kembali lagi ke bumi, dan bila Hambaruan yang baru ini lebih banyak dilengkapi oleh salah satu substansi itu, maka dia dengan substansi yang dominan itu menentukan karakter dan nasib dari manusia yang baru dilahirkan. Misalnya bila Hambaruan yang baru itu didominir oleh substansi besi, maka manusia yang baru dilahirkan itu akan berkarakter keras dan berkehendak teguh. Manusia tidak dapat mengubah nasibnya yang telah ditentukan oleh kekuatan ilahi (Hambaruan yang kembali ke bumi). Zoetmulder, Piet & Stöhr, Waldemar: Die Religionen Indonesiens. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1965, hlm. 174-175. Klimkeit, Hans-Joachim: Der leidende Gerechte... Op.cit., hlm. 167-170. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Dalam kebudayaan Mesir kuno tata tertib kosmis yang demikian disebut “maat”. Untuk merealisir “maat” di dunia, orang perlu mempraktekkan ajaran-ajaran dasar yang akan disebut di bawah. Paralelnya dapat kita temukan dalam berbagai macam kebudayaan tradisional hingga kini. Di dalam ungkapan kebijaksanaan Mesopotamia orang menemukan pengertian “me” yang memuat adanya ide tentang tata tertib yang adil itu. Tata tertib yang utuh di dalam kehidupan masyarakat dan negara dijamin hanya melalui persatuan raja dengan “me”. Paralel yang lain dijumpai di dalam ceritera mitos Yunani. Pengertian dasar tentang “themis” dan “dike”, dan kemudian “nomos”, mengungkapkan konsep tentang keadilan ilahi yang bersifat kosmis. Di Iran pengikut Zoroasther mengenal tata tertib itu dengan nama “asha”, di India “rta” sebelum periode Veda dan “dharma” sesudah masa Veda, di Cina faham “taoisme”, juga gagasan “rukun dan hormat” dalam masyarakat Jawa seperti yang dilukiskan Franz Magnis- Suseno.13 Semuanya tidak perlu dilukiskan secara rinci di sini. Hal yang terpenting di sini ialah bahwa terdapat satu prinsip dasar tentang keadilan. Prinsip itu didasarkan pada tata tertib ilahi yang bersifat kosmis. Kebudayaan Mesir kuno mengenal ajaran tentang prinsip dasar ini yang dijabarkan dalam ajaran etisnya, yaitu bagaimana manusia harus merealisir tata tertib kosmis yang bersifat ilahi itu. Bunyi dari ajaran itu adalah demikian, seperti tersurat dalam ajaran 6. dari Ptahotep: “Janganlah melakukan teror di antara manusia. Sebab Allah akan menghukumnya dengan cara yang sama....”.14 Teror, kekerasan dan pembunuhan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib yang ilahi. Teror itu menandakan bahwa tata tertib kosmis yang ilahi tidak berfungsi baik; manusia tidak menghayatinya dalam hidup konkrit. Akibatnya ialah bahwa manusia mendapat hukuman dari Allah setimpal dengan perbuatannya itu. Sebaliknya, bila manusia menjaga tata tertib ilahi dan menghayatinya dalam perbuatan konkrit, ia mendapat imbalan kebahagian; ia mempraktekkan keadilan. Campur tangan ilahi di dalam hidup manusia dan balasan yang setimpal dari Allah betul-betul sesuai dengan perbuatan manusia. Itulah gagasan dasar keadilan yang hanya tercermin dalam berfungsinya hukum tata tertib ilahi yang kosmis itu. Prinsip itu dikenal dalam fenomenologi agama dengan sebutan “Tun-Ergehen-Zusammenhang” (Prinsip kaitmengait antara perbuatan dan imbalannya). 13 14 Franz Magnis-Suseno menyebut dua kaidah dasar kehidupan masyarakat Jawa, yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang, tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan. Prinsip rukun bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis. Prinsip hormat memainkan fungsi yang menentukan dalam interaksi sosial. Setiap orang memainkan peranannya sesuai dengan aturan-aturan tata krama, yaitu sesuai dengan derajatnya, tempatnya, kedudukan dan tugasnya dalam masyarakat. Dengan sikap hormat yang tepat terhadap orang lain atas dasar itu, tata tertib masyarakat terjamin utuh dan selaras. Bila kedua prinsip ini dihayati, tata tertib kosmis yang ilahi berjalan baik, yaitu kesatuan numinous antara manusia, masyarakat, alam dan alam adikodrati. Bdk. Magnis-Suseno, Franz: Etika Jawa... Op. cit., hlm. 38-90. “Übe nicht Teror unter den Menschen. Denn Gott straft mit Gleichem...”. Klimkeit, Hans-Joachim: Der leidende Gerechte... Op. cit., hlm. 168. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 133 Dalam konsep tentang keadilan yang demikian, orang dapat berbicara tentang penderitaan manusia yang tidak bersalah. Penderitaan orang yang tak bersalah dimengerti sebagai akibat dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan tata tertib kosmis yang bersifat ilahi. Perbuatan yang tidak sesuai ini adalah satu pelanggaran dan satu kesalahan. Karena itu si pelakunya harus menebus pelanggarannya itu melalui pengalaman penderitaan. Orang yang menderita adalah orang yang harus menanggung akibat kesalahannya, karena dia tidak terlibat dalam penegakan tata tertib kosmis yang ilahi itu. Dalam prinsip ini tidak ada ruang pengertian tentang satu penderitaan yang ditanggung oleh orang yang tidak bersalah. Karena dia bersalah, maka dia harus menderita. Ide tentang penghakiman terakhir di zaman eskatologis sebetulnya berasal dari prinsip “Tun-Ergehen-Zusammenhang” ini, yaitu bahwa balasan sesudah kematian diperoleh atas dasar perbuatan manusia di dunia ini. 2.3. Keadilan dan penderitaan orang yang tak bersalah dalam fase ketiga Fase ketiga memperlihatkan satu fase pengalaman yang menandakan ketidakberfungsinya tata tertib ilahi. Tata tertib kosmis yang dipandang ilahi hancur oleh karena pengalaman penderitaan yang tidak sesuai dengan prinsip “Tun-ErgehenZusammenhang”, atau paling kurang, pengalaman penderitaan itu mempertanyakan kembali keabsahan prinsip tersebut.15 Sejarah agama menunjukkan beberapa fenomen yang mencerminkan problematika ini, sebagaimana disebut beberapa contoh di bawah ini. Sumber-sumber Mesopotamia, teristimewa empat sumbernya16 , yaitu Ayub Sumeria; ludlul bêl nêmeqi; Theodizea Babylonia dan AO 4462, mencerminkan problematika itu, bahwa pengalaman konkrit akan penderitaan membuktikan adanya pemahaman lain daripada prinsip “Tun-Ergehen-Zusammenhang” sebagai prinsip keadilan. Ajaran bahwa orang yang menderita adalah akibat dosa dan kesalahannya tidak cocok lagi. Sebagai contoh, kita menyebut syair tentang “Ayub Sumeria”. Syair ini menceriterakan tentang seorang laki-laki yang menderita begitu hebat. Penderitaannya bukan karena akibat kesalahannya, tetapi karena kekuasaan jahat menimpanya dan dewa membiarkannya menderita. Orang-orang bijak yang masih berpegang kuat pada ajaran keadilan menurut prinsip “Tun-Ergehen-Zusammenhang” menawarkan penjelasan kepadanya dengan meyakinkan dia bahwa penderitaannya itu adalah akibat dosa dan kesalahannya. Mereka mempertahankan ajaran itu sebagai satu ideologi dan dogma, dan setiap orang yang menderita harus dimengerti sesuai dengan pengertian ideologis-dogmatis itu. Menurut mereka sikap yang paling tepat dari dia yang menderita adalah mengakui kekuasaan para dewa dengan penuh iman 15 16 134 Ibid, hlm. 170-179. Schmid, Hans Heinrich: Wesen und Geschichte der Weisheit. Berlin: Verlag Alfred Töpelmann, 1966, hlm. 6165. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 dan rendah hati lalu menerima kekurangannya sendiri sambil memuji keadilan para dewa. Tetapi syair tentang “Ayub Sumeria” ini memperlihatkan adanya alternatif pemahaman yang lain. Titik tolaknya adalah pengalaman empiris akan penderitaan yang konkrit, dan pengalaman konkrit ini dikonfrontir dengan pengertian ideologisdogmatis itu.17 Dengan demikian, arti ideologis dan dogmatis itu tidak mutlak berlaku, bahwa penderitaan adalah akibat dari dosa dan kesalahan si penderita. H. H. Schmid dalam bukunya “Wesen und Geschichte der Weisheit” (Hakekat dan Sejarah Kebijaksanaan) menunjukkan dua kemungkinan pemahaman ketika dia berbicara tentang “Ayub Sumeria”, meskipun belum jelas untuk dia, mana dari kedua kemungkinan pemahaman itu melatarbelakangi syair “Ayub Sumeria”. Dua kemungkinan pemahaman itu adalah pemahaman tentang penderitaan dengan bertolak dari perlukisan tentang realitas empiris dari si penderita yang tidak bersalah sebagaimana ada dalam realitas historisnya, dan kemungkinan kedua adalah pemahaman tentang penderitaan dengan bertolak dari perlukisan dogmatis yang keluar dari satu gambaran fiktif tentang realitas. Problematika penderitaan orang yang tak bersalah dalam syair “Ayub Sumeria” dipertajam dalam buku “Ayub” dari Kitab Perjanjian Lama. Dalam pengalaman konkrit Ayub, ajaran kebijaksanaan “Tun-Ergehen-Zusammenhang” tidak lagi manjur, malah hancur. Pemahaman tentang keadilan pun harus berubah. Ayub menetapkan pendirian dasarnya bahwa dia sungguh menderita tanpa dosa dan kesalahannya; ia menderita secara tidak adil. Pendirian dasarnya ini tercermin jelas dalam penolakannya terhadap nasihat ketiga kawannya (Ayub 3 - 31) dan Elihu (Ayub 32 - 37); nasihat mereka masih terpaku pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan “Tun-Ergehen-Zusammenhang”. Ayub memang menolak argumentasi mereka dan tiba pada satu pengenalan bahwa dengan penderitaan yang ditanggungnya tanpa dosa dan kesalahannya, satu kebijaksanaan baru yang tidak doktriner menjadi mungkin dan tersingkap. Kebijaksanaan baru itu ialah bahwa Ayub harus menerima dan mengakui secara irrasional setiap tata tertib kosmis yang dapat menimpanya setiap waktu dan di mana saja; penderitaannya tanpa dosa dan kesalahannya tidak dijelaskan secara rasional, malah Ayub didorong untuk melihat dan menerima nasib penderitaan dalam satu horison hukum kosmis yang melingkupinya. Schmid berkomentar bahwa di dalam ceritera ini si penulis buku “Ayub” tidak memusatkan perhatian pada penyembuhan penyakit dan penderitaan Ayub, tetapi pada pengakuan akan satu hukum kosmis yang kemudian sangat kuat dilukiskan secara teologis pada bagian “Jawab Tuhan kepada Ayub” (Kitab Ayub 38 dst.). Penderitaan Ayub dalam ayat-ayat yang memuat jawaban Tuhan terhadap Ayub- perlu dipahami sebagai yang sudah tercakup dalam keseluruhan realitas Allah yang berfungsi untuk mengatur dan menjamin tata tertib kosmis. Dalam bagian keempat dari Kitab Ayub, seperti yang dikutip dari Schmid (Ayub 40, 6-42, 6), ditonjolkan keunggulan Yahwe atas ketakberdayaan Ayub dan usaha Ayub untuk menentukan tempatnya dalam hukum 17 Ibid, hlm. 133-135. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 135 tata tertib kosmis yang juga berada di bawah kuasa Allah. Dengan pengenalan dan pemahaman Ayub itu, prinsip kebijaksanaan lama “Tun-Ergehen-Zusammenhang” tidaklah merupakan satu “prinsip tertutup yang sudah baku”. Hukum keadilan perlu ditafsir secara baru berdasarkan pada pengalaman historis empiris dari orang yang menderita tanpa dosanya sendiri. Ahli fenomenologi agama melihat problematika itu dalam lingkungan budaya lain seperti hukum karma dan dharma di India, satu dua ajaran dalam Buddhisme, ajaran Zoroasther di Iran dan Konfusianisme di Cina, dsb. Kita menyebut salah satunya, yaitu Konfusianisme di Cina. Meskipun problematika penderitaan seperti yang dialami Ayub tidak banyak direfleksikan di Cina, problematika itu menurut Klimkeit dapat kita lacak pada konsep “Tao” dalam etika Konfusianisme. Etika Konfusianisme yang menghidupkan kembali ajaran tentang “tao” adalah satu jawaban terhadap tidak berfungsinya tata tertib kosmis pada masa Chou.18 “Tao” dimengerti sebagai tata tertib etis yang adil. Orang harus menghayati “tao” dengan jalan melaksanakan kebajikan (te) yang dituntut kepadanya dan menjalankan ritus serta adat istiadat (li) yang diturunkan kepadanya. Keadilan dicapai melalui jalan itu, dan orang yang bertindak dengan jalan demikian disebut “orang yang berbudi luhur”, seperti tersurat dalam Kitab Lun-yü XV, 17: “Orang yang berbudi luhur memandang keadilan sebagai hal yang hakiki. Ia melaksanakannya menurut tata aturan sopan santun, mengungkapkannya dengan kerendahan hati, melengkapinya dengan kejujuran serta ketulusan hati. Itulah cara hidup seorang yang berbudi luhur”.19 Dengan jalan itu pula seorang yang berbudi luhur membawa pengaruh kepada lingkungan sekitarnya, termasuk sesama dan bawahannya. Dia adalah tiang pokok masyarakat. Harmoni dan keadilan terjamin olehnya. Tetapi bila dia tidak menghayati “tao”, harmoni terganggu dan masyarakat mengalami penderitaan. Meskipun tidak direfleksikan secara eksplisit penderitaan orang yang tak bersalah, tapi dalam terang konsep tentang gangguan harmoni, karena “te” dan “li” sebagai perwujudan “tao” tidak dijalankan, orang-orang yang tak bersalah, malah masyarakat seluruhnya, dapat turut menderita. Kesimpulan dari pokok ini ialah bahwa keadilan tidak dipahami dalam satu prinsip dogmatis yang tertutup. Penderitaan orang-orang yang tidak bersalah merupakan satu fakta historis-empiris yang membuka pemahaman baru untuk membebaskan diri dari satu prinsip kebijaksanaan yang tidak lagi cocok untuk realitas 18 Dinasti Chou berkuasa atas China dari abad 11 sampai dengan 256/249 seb. M. Pada masa ini orang berpegang pada prinsip tata tertib kosmis yang berfungsi untuk menjaga etika dan melindungi kekuasaan dinasti. Pemilik tata tertib kosmis ini adalah dewa langit “T’ien” yang puteranya adalah raja sendiri. Raja bertanggungjawab untuk menjaga ritme kosmis dalam peredarannya agar tata tertib kosmis itu berfungsi baik. Konfusius (551-479) yang mengalami banyak penderitaan, ketidakadilan dan kesengsaraan di masanya mengubah etika yang dipraktekkan raja dan sesama masanya secara radikal. Konfusius menekankan praktek kebajikan seperti kebaikan, kebijaksanaan dan keberanian serta pelaksanaan yang tepat terhadap adat istiadat dan ritus-ritus (li). Eliade, Mircea: Geschichte der religiösen Ideen. Band 2: Von Gautama Buddha bis zu den Anfängen des Christentums. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 1979, hlm. 16-17 dan 27-29. 19 “Der Edle hält die Gerechtigkeit für das Wesentliche: gemäß den Regeln des Antstandes übt er sie, mit Bescheidenheit äußert er sie, mit Aufrichtigkeit vollendet er sie. Das ist die Art des Edlen.” Klimkeit, HansJoachim: Der leidende Gerechte... Op. cit.,hlm. 179. 136 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 empiris-historis. Justru di sinilah letak problematika keadilan dan kategori pemahaman keadilan, ketika keadilan menyentuh pribadi-pribadi manusia tak bersalah yang harus menderita. 2.4. Keadilan dan penderitaan orang yang tak bersalah dalam keseluruhan realitas yang penuh misteri Keseluruhan realitas yang penuh misteri lebih banyak menunjuk kepada satu ruang lingkup, yang di dalamnya keseluruhan realitas dialami sebagai yang saling meresap atau saling menerobos antara dimensi kekinian beserta realitas hidup di dunia ini (Diesseits) dan dimensi eskatologis beserta realitas dunia seberang (Jenseits) atau antara realitas yang imanen dan yang transenden. Proses ini berjalan tersembunyi (verborgen), tidak kentara dan rahasia.20 Fase ketiga sudah memberi peluang untuk pemahaman terhadap proses dalam fase ini yang boleh dikatakan memberi ciri pada gejala perkembangan dunia modern. Dalam kaitan dengan gagasan keadilan, keseluruhan realitas yang penuh misteri ditandai oleh proses saling meresap dan saling menerobos antara perwujudan keadilan di dunia seberang di zaman eskatologis dan perwujudan keadilan di dunia kini dan di sini. Ahli fenomenologi agama menyebut beberapa fenomen religius yang mencerminkan proses saling resap-meresap atau saling terobos-menerobos antara kedua dimensi itu. Menurut Schmid ditemui juga, selain dalam buku Ayub, satu garis pemikiran dasar tentang keadilan dan penderitaan orang yang tak bersalah, satu garis pemikiran dasar yang membangun mata rantai Kitab Perjanjian Lama seperti dalam tradisi Abraham (Kej. 15, 1-6), Injil sinoptik dan interpretasi Paulus tentang Kerajaan Allah pada Rom. 14, 17-18. Abraham menderita karena pada masa tuanya dia belum mempunyai putera sebagai alih-waris harta miliknya dan dia berusaha mengerti keadilan Allah dalam pergulatannya dengan kenyataan dirinya. Kontinuitas problematika yang semacam terbaca dalam versi Injil sinoptik tentang Kerajaan Allah dan sabda bahagia yang lebih berorientasi pada zaman eskatologis, dan keadilan Allah, di samping damai dan sukacita, ditafsir Paulus sebagai tanda pengenal perwujudan Kerajaan Allah. Schmid melihat adanya satu garis pemikiran dasar, yaitu bahwa perwujudan keadilan hanyalah perbuatan Allah sendiri dan bahwa manusia mengambil bagian dalam karya Allah itu sambil percaya kepada Allah dan kepada janjiNya di masa depan di zaman akhir. Pemikiran ini memuat satu gambaran eskatologis tentang Kerajaan Allah, kekuasaan Allah dan keadilanNya (Jenseits), yang tanda-tandanya dan perwujudannya sudah dimulai di dunia ini kini dan di sini (Diesseits). Dengan bertolak dari garis pemikiran ini, penderitaan mendapat satu arti yang tidak bersifat “jenseitig” (di dunia seberang pada zaman akhir) dan juga tidak bersifat “diesseitig” (di dunia kini dan di sini), tetapi mendapat satu arti dalam proses 20 Ibid, hlm. 179-181. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 137 “saling resap-meresap dan saling terobos-menerobos” antara perwujudan keadilan yang “jenseitig” dan perwujudan keadilan yang “diesseitig”. Proses ini justru menandai keseluruhan realitas yang penuh misteri itu. Paulus menjabarkan proses ini dalam peristiwa Yesus Kristus sebagai wahyu keadilan dan pemberi arti terhadap penderitaan orang yang tak bersalah. Menarik juga bahwa fenomenologi agama menunjuk proses serupa dalam Islam dan Buddhisme. Proses saling terobos-menerobos antara perwujudan keadilan dalam dimensi esktalologis dan dalam dimensi kini dan di sini dialami dalam kerelaan untuk mati sebagai martir pada kelompok Shî’ah.21 Kelompok ini menemukan jalannya sendiri untuk berperang melawan kekuasaan duniawi yang tidak lagi mencerminkan kekuasaan Allah yang kelihatan di atas dunia. Melalui perjuangannya mereka memperoleh pemahaman ke dalam dimensi keseluruhan realitas yang penuh misteri, ketika mereka berperang melawan kekuasaan politis Kalifat Mu’âwîyah. Pemahaman itu menghantar mereka untuk berani menempuh jalan penderitaan demi kehendak Allah, bahkan berani untuk mati demi Allah. Dalam Buddhisme proses serupa tercermin dalam ajaran Mahayana-Buddhisme. Meskipun Buddhisme awal dan klasik tidak mengenal paham tentang penderitaan yang sia-sia tanpa dasar, karena semua penderitaan menurutnya disebabkan oleh kelobaan, tapi MahayanaBuddhisme menggambarkan adanya satu hubungan baru dengan penderitaan melalui paham tentang “Bodhisattva”.22 Klimkeit menjelaskan bahwa Bodhisattva yang mengambilalih dan menanggung penderitaan dengan rela untuk membebaskan penderitaan orang lain memberikan satu arti tentang penderitaan dalam keseluruhan realitas yang penuh misteri itu, keseluruhan realitas yang tercermin dalam dimensi kini dan di sini (Diesseits). Fase keempat ini memberi warna khusus pada gagasan pokok tentang sejarah keadilan dan penderitaan. Problematika keadilan dan penderitaan orang yang tak bersalah dalam konteks historis dimengerti sebagai realisasi dari proses keseluruhan realitas tersembunyi yang saling resap-meresap atau saling terobos-menerobos antara dimensi eskatologis dan dimensi kini dan di sini. Proses itulah yang menjadi titik 21 22 138 Shî’ah adalah kelompok pengikut Husein. Husein dan banyak pengikutnya dibunuh di Karbala, Irak, oleh pengikut Yasid; Yasid adalah putera kalifat Mu’âwîyah ( 661-680). Menurut tradisi Islam, Husein dan pengikutnya dipandang sebagai martir, karena mereka berjuang membela kebenaran, membela kekuasaan yang sah atas kalifat atas dasar pertalian darah dengan nabi Muhammad dan menempuh jalan Allah. Mereka menolak Yasid sebagai pengganti pemimpin kekuasaan Kalifat Mu’âwîyah. Husein sendiri adalah cucu Muhammad atau putera Fatima yang adalah puteri nabi Muhammad. Husein adalah seorang saleh, jujur, asketis dan terpandang di mata jemaatnya. Ibid, hlm.180-181, bdk. Ayoub, Mahmoud, Dr.: Redemptive Suffering in Islâm. The Hague: Mouton Publishers, 1978, hlm. 93-120, bdk. Cahen, Claude (Hg.): Fischer Weltgeschichte Band 14, Der Islam 1. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968, hlm. 32-37. Bodhisattva menurut kepercayaan Mâhâyana-Buddhisme adalah hakekat-hakekat yang sudah mengalami pencerahan (Erleuchtung) seperti Buddha. Mereka adalah hakekat orang-orang yang berusaha mencapai pencerahan atau yang sudah mencapai pencerahan. Mereka dapat menunda mengalami pencerahan sebelum semua makhluk tertebus. Mereka hidup untuk orang lain, bersikap belas kasih dan berkehendak untuk membahagiakan orang lain. Boddhisatva dengan rela menempatkan penderitaan dunia dan manusia ke atas pundaknya sendiri. Ibid, hlm. 181, bdk. Schumann, Hans Wolfgang: Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme. München: Eugen Diederichs Verlag, 1995, hlm. 160-161. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 fokus penelitian sejarah agama dan fenomenologi agama, bila manusia modern mengalami kembali fakta-fakta tentang keadilan dan ketidakadilan, tentang penderitaan orang yang tak bersalah dan problem Theodizea, tentang arti dan tujuan hidup, dsb. 3. PARADIGMA TEORETIS DAN FENOMENOLOGI AGAMA Pada bagian terakhir dari tulisan ini, kita coba menggarisbawahi lagi pemikiran Eliade dan penerusnya, yang menempatkan fenomenologi agama dengan arah baru seperti yang disebutkan sebelumnya. Titik pusat penelitian fenomenologisnya ialah penampakkan Yang Kudus dalam ruang dan waktu - dalam bahasa teologis perwahyuan diri Allah dalam ruang dan waktu - serta problem-problem universal kemanusiaan yang berhubungan dengan penerimaan manusia terhadap penampakan Yang Kudus itu. Pembicaraan tentang tema pokok kita, yaitu tentang gagasan keadilan dan problem penderitaan orang yang tak bersalah, merupakan penjabaran arah baru penelitian fenomenologis itu, dan hal itu tercermin dalam perlukisan yang dibuat Schmid tentang empat stadium historis. Kita menemukan bahwa masing-masing stadium historis tersebut memiliki paradigma teoretisnya yang diartikan sebagai perangkat keyakinan dan pemahaman atau juga gagasan penuntun (Leitbegriff) dengan tujuan untuk mengerti dan memberi arti terhadap problem-problem humanistik - universal itu. Kita tidak mengulang lagi apa paradigma teoretis dari masing-masing stadium itu, tapi kita dengan jelas melihat adanya pergeseran paradigma dari stadium ke stadium, dari stadium pertama yang meminta kita untuk memahami problematika dengan bingkai pengertian tentang kekuatan nasib, lalu dengan bingkai pengertian tentang satu tata tertib kosmis yang ilahi, lalu dengan bingkai pengertian tentang satu dasar pengalaman empiris yang mempersoalkan pemahaman doktriner-fiktif, dan yang terakhir dengan bingkai pengertian tentang proses terobos-menerobos antara dimensi eskatologis dan dimensi historis konkrit sekarang di dunia ini. Dalam setiap fase historis apa pun, juga dalam keempat stadium historis itu, manusia dihadapkan dengan pengalamannya akan kontingensi. Filsafat agama bergelut juga dengan persoalan kontingensi ini, terutama ketika realitas konkrit seperti penderitaan orang-orang yang tak bersalah menjadi sasaran refleksi kritis. Persoalan Theodicea, yaitu pertanyaan tentang pembenaran penderitaan melalui premis bahwa ada eksistensi Allah yang maha pengasih dan maha kuasa, adalah satu usaha filosofis untuk menggeluti pengalaman kontingensi itu.23 Fenomenologi agama dengan arah baru, selain menjadi alat bantuan filsafat agama untuk menetapkan paradigma teoretis yang membingkai pengalaman manusia akan kontingensi dalam fase historis tertentu, 23 Wuchterl, Kurt: Philosophie und Religion. Zur Aktualität der Religionsphilosophie. Bern: Verlag Paul Haupt, 1982, hlm. 30-37; 164-171. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 139 juga membuka terobosan-terobosan baru untuk refleksi filosofis tentang fenomenfenomen religius yang dikaitkan dengan problem-problem kemanusiaan universal; refleksi filosofis ini dapat saja membuahkan paradigma teoretis yang baru. Kita coba merefleksikan stadium historis yang keempat, karena stadium ini boleh dikatakan sedang mencerminkan situasi perkembangan dunia dewasa ini. Proses terobos-menerobos antara dimensi eskatologis dan dimensi historis kini dan di sini dalam keseluruhan realitas yang penuh misteri dapat diungkapkan dengan kata-kata lain. Proses itu sebetulnya adalah proses ketegangan antara dua kutub tarik-menarik dalam pengalaman manusia modern, yaitu antara realitas dunia sekular dengan diwakili oleh ilmu pengetahuan dan teknologi di satu kutub, dan di kutub lain realitas dunia sakral (Yang Kudus) dengan diwakili oleh kelahiran kembali berbagai macam gerakan religius, termasuk gerakan radikal fundamental yang berbasiskan agama. Realitas dunia sekular sedang meraja atas dunia konkrit dan atas manusia modern sedemikian, sehingga jejak-jejak transendental dari dunia seberang tampak pudar, dan dalam keadaan yang demikian, realitas dunia sakral semacam “menampakkan diri” bagai jejak-jejak di atas padang pasir; realitas ini menuntut untuk ditemukan kembali. Jejak-jejaknya mempesona untuk ditelusuri. Bahasa anthropologi Eliade menyebutnya sebagai ketegangan antara dua kutub dalam diri manusia, yaitu antara “homo religiosus dan homo areligiosus”. Bila kita mengamati gejala-gejala dunia modern, maka persoalan tentang keadilan dan penderitaan orang-orang yang tak bersalah memang termasuk sebagai gejala-gejala modern yang sangat aktual. Kita menyinggung saja soal peperangan, konflik, dan kekerasan di seantero dunia; semuanya membawa korban bagi manusia yang tidak berdosa. Agama dalam konteks realitas hidup modern ini tampak tidak berdaya (ohnmächtig) untuk berkonfrontasi dengan manifestasi kekuatan sekular yang sedang berkuasa; sistem ajaran agama, upacara-upacara ritual dan struktur organisasi religius menjadi tidak manjur, malah direkayasa untuk kepentingan-kepentingan sosial, politis dan ekonomis. Gerakan fundamentalisme agama sebetulnya menunjukkan ketidakmampuan agama untuk menghadapi realitas kekuatan sekular. Dalam fase ini bukanlah soal Islam, Kristen, Buddhisme, Hindu dsb, tetapi soal realitas religius yang disebut Schmid sebagai realitas transenden yang berasal dari dunia seberang, dan realitas ini sedang berada dalam proses untuk menyusup dan menerobos masuk ke dalam realitas sekular melalui kebangkitan kembali kesadaran humanis - religius untuk menawarkan keselamatan atau pembebasan dari ancaman pembinasaan total manusia. Fungsi aktual fenomenologi agama ialah mendeteksi dan melukiskan dengan bantuan refleksi kritis-filosofis ancaman pembinasaan total manusia, baik ancaman pembinasaan yang berasal dari dampak-dampak negatif kekuatan sekular maupun yang berasal dari instrumentalisasi agama untuk tujuan yang tidak religius. 140 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 BIBLIOGRAFI Ayoub, Mahmoud, Redemptive Suffering in Islâm, the Hague: Mouton Publishers, 1978. Cahen, Claude (Hg. ), Fischer Weltgeschichte Band 14, Der Islam 1, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. Dupré, Wilhem, “Ethik und Religion in schriftlosen Kulturen”, in Ethik in nichtchristlichen Kulturen, Antes, Peter u.a. ( Hg. ). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1984. Eliade, Mircea, Die Religionen und das Heilige. Elemente der Religionsgeschichte, Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1986. ————, Geschichte der religiösen Ideen. Band 2: Von Gautama Buddha bis zu den Anfängen des Christentums, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 1979. Effendi, Mochtar, S.E., Ensiklopedi Agama dan Filsafat, Buku 6, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001. Hamersma, Harry, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1984. Klimkeit, Hans-Joachim, Der leidende Gerechte in der Religionsgeschichte. Ein Beitrag zur problemorietierten “Religionsphänomenologie“, in Religionswissenschaft. Eine Einführung, Zinser, Hartmut ( Hg.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1988. Moiren, Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Lexikonverlag. Mannheim: Bibliographisches Institut, 1976. Magnis-Suseno, Franz, Etika Jawa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Schmid, Hans Heinrich, Gerechtigkeit als Weltordnung, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1968. Schmid, Hans Heinrich, Wesen und Geschichte der Weisheit, Berlin: Verlag Alfred Töpelmann, 1966. Schumann, Hans Wolfgang, Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme, München: Eugen Diederichs Verlag, 1995. Wuchterl, Kurt, Philosophie und Religion. Zur Aktualität der Religionsphilosophie, Bern: Verlag Paul Haupt, 1982. Zoetmulder, Piet & Stöhr, Waldemar, Die Religionen Indonesiens, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 1965. Sermada Kelen Donatus, Penderitaan Orang Yang Tak Bersalah 141 THE USE OF THE BIBLE BY MEDIEVAL CARMELITE WRITERS Henricus Pidyarto STFT Widya Sasana, Malang Abstraksi : Sejak zaman Patristik, orang percaya bahwa teks-teks Alkitab mengandung makna yang amat kaya. Orang percaya bahwa teks suci mengandung makna literal (makna seperti apa adanya) dan makna-makna rohani yang dapat disimpulkan dari makna literal. Sebagai contoh: yang dimaksud dengan kota Yerusalem dalam Alkitab adalah sebuah kota suci di Palestina (makna literal), tetapi juga Gereja Yesus Kristus (makna Kristologis-ekklesiologis) atau jiwa orang beriman (makna moral/ ropologis) atau surga (makna anagogis). Meskipun orang yakin bahwa makna literal itu penting dan menjadi dasar untuk makna-makna rohani, namun nyatanya para penulis abad pertengahan begitu mudah menekankan makna rohani. Dalam artikel ini kami memberikan contoh-contoh yang kami ambil dari para penulis Karmelit abad pertengahan yang merupakan anak dari zamannya. Keywords: bible, literal sense, allegorical sense, Carmelite writers The aim of this article is twofold: on the one hand, to present a brief and overall picture of the use of the Bible and its interpretation in the Middle Ages, and, on the other hand, to see how Carmelite writers have something in common with their contemporary writers with regard to the use of the Bible. Since the material is so extensive, in this article we have to limit our research to some selected Carmelite writings. 1. The use and the exegesis of the Bible in the Middle Ages1 The Middle Ages covers a long period of approximately one thousand years (from fifth to fifteenth century C.E.), and as far as the history of biblical exegesis is concerned, it ranges from the end of the period of old patristic exegesis to the times 1 142 See Robert M. Grant - David Tracy, A Short History of the Interpretation of The Bible (London: SCM Press,19842); Raymond E. Brown, “Hermeneutics,” in Raymond E. Brown - Joseph A. Fitzmyer -Roland E. Murphy (ed.), The Jerome Biblical Commentary (London: Geoffrey Chapman, 1968) II:41; Henri de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture (Paris: Aubier, 1959-1964); Jo. Ticheler, Didyme l’Aveugle et l’exégèse allégorique [doctoral dissertation] (Nijmegen: Dekker en van de Vegt, 1977). Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 when theology became a holy science independent from biblical exegesis. However, it is still possible to make a brief outline of the medieval exegesis. As a matter of fact, during those times there was hardly any significant novelty in the interpretation of the Bible. During this period the main characteristics of the patristic and monastic exegesis are maintained faithfully. In order to describe the medieval exegesis, it is worth citing here the famous couplet concerning the fourfold meaning of the Bible:2 Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quod agas, quo tendas anagogia. (The letter shows us what God and our fathers did; The allegory shows us where our faith is hid; The moral meaning gives us rules of daily life; The anagogy shows us where we end our strife.) The idea of the four senses of the Bible must be ascribed to patristic origin, namely to John Cassian (died ca. 435) or to other earlier Fathers of the Church (e.g. Clement of Alexandria or Augustine). The formulation of that famous couplet, however, becomes popular due to the quotation of the couplet by Nicholas of Lyra (died 1340). It expresses the medieval opinion that biblical texts have four meanings (1 + 3), that is: literal meaning and spiritual meaning which in its turn consists of three meanings (allegorical, moral/tropological and anagogical).3 By literal sense is meant history (namely certain persons, events or things) of which biblical texts inform us. By allegorical meaning is meant the Christological meaning that can be deduced from the literal sense; but as far as the Church belongs to Jesus Christ, then by allegorical sense is also meant Ecclessiological sense. Strictly speaking, this allegorical meaning should be sought only in Old Testament texts, because the literal sense of the New Testament texts are already speaking of Christ and/or his Church. By moral or tropological sense is meant the morality that can be deduced from the literal sense. It means that a fact/reality told in the Bible is useful as an instruction for the conduct of the Christian. Finally, by anagogical meaning is meant the eschatological event as our definitive future that is implied in the literal sense. The classical and pedagogical description of the four senses of the Bible is the city of Jerusalem. Literally interpreted, Jerusalem is the holy city in the Holy Land; allegorically it represents the Church; tropologically it stands for the human soul and anagogically it stands for the heavenly Jerusalem. Another example is given by St. Thomas Aquinas. The “Fiat lux” of Gen 1:3 has the historical meaning 2 3 Cited from Grant - Tracy, op. cit., 85. Concerning the order of “letter - allegory - tropology” or the inverted order “letter - tropology - allegory” and its theological implication, see Alonso Schökel, Il dinamismo della tradizione (Brescia: Paideia, 1970) 24 30; he summarizes Henri de Lubac’s extensive explanation on this theme. Henricus Pidyarto, The Use of The Bible 143 of the creation of physical light. Allegorically it means the birth of Jesus in the Church, tropologically it means the enlightment of the soul by Christ, and anagogically it means our entering into eschatological glory through Christ (In Galatas, cap. v, lect. 7). Even though there exists also a variety in the number of the biblical senses — sometimes its number is reduced to 3 or enlarged to 7 in connection with the seven seals or the seven spirits mentioned in the Book of Revelation (5:1 and 1:4 respectively)— the most popular scheme is the fourfold scheme. It becomes also the pattern of some theological treatises, liturgical ceremonies and prayers, homilies, and books classification in quite a few libraries. This fact reveals that the division of biblical meaning into four senses permeates the frame of thinking of medieval Christian society. The teaching on the four senses of the Bible only shows us that the Bible is regarded as God’s Word, written by the inspiration of the Holy Spirit. It is therefore very rich in meaning. The Bible is like an unfathomable ocean or a heavenly expanse or an impenetrable forest of divine mysteries. The biblical texts have different colours of meaning like the tail of a peacock. But those multiple and unpredictable meanings of the Bible cannot be found unless through Lectio Divina , i.e. through a constant reading and re-reading of the Bible under the guidance of the Holy Spirit, in purity of heart and prayer. Even though it is the medieval conviction that the literal sense has historical importance (=historia est fundamentum), we can say that in the medieval exegesis in general, but especially in monastic mysticism and in the pastoral ministry (e.g. in preaching), the spiritual sense gets more attention than the literal sense.4 The medieval writers tend to consider the history (facts, things or events) as simple facts, without investigating them critically. Therefore, they think the literal sense is clear enough. Consequently, they quite often pass hastily to the more-than-literal or spiritual senses, especially when the literal sense is difficult to understand.5 We must say that the medieval interpretation is often exaggerating in deducing spiritual senses out of the biblical texts. Of course, there have been some periods when a more serious attention was paid to the literal sense (e.g. to philological aspect). It is worth mentioning the Carolingian revival (8th - 9th century).6 In the schools of the Carolingian revival more attention is paid to the study of grammar, rethorics, original languages of the Bible, or other sciences that may help any exegete to understand better the literal meaning of biblical texts. Along with those studies, revisions of the Latin Bible, “introductions” to each book of the Bible, commentaries, and a sort of appendix to the commentaries which is called “quaestiones et responsiones “ (i.e. theological ques- 4 5 6 144 See Brown, art. cit., n. 41; Grant, op. cit., p. 85; Schökel, op. cit., 26. Schökel, 26. Pierre Riché, “Strumenti di lavoro e metodi dell’esegeta in epoca carolingia,” in Pierre Riché, Jean Châtillon - Jacques Verger, Lo studio della Bibbia nel Medioevo latino (Brescia: Paideia, 1989) 19-38. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 tions that may arise from biblical texts and their rational answers) are composed. In addition to catena (=marginal notes on biblical texts taken largely from patristic commentaries), the Carolingian revival introduces the use of glosses (=commenting notes put either in the margin, between the biblical texts or separately from the biblical texts as an appendix). It is interesting to note that the books that attract more commentators are Genesis, the Song of Songs, Psalms, Kings, Matthew and the Pauline letters.7 The impetus initiated by the Carolingian revival to seek the literal sense as the basis of other senses continues to exist and becomes stronger and stronger in the twelfth century European schools and universities. This new development in the biblical interpretation is due to the influence of Saint Bernard and most of all of Saint Thomas Aquinas. Beginning from the 13th century the study of the literal sense of the Bible becomes more and more dominant in schools and in a special way in universities. Two universities are worth mentioning here: Paris and Oxford. More and more university people learn Hebrew and Greek, grammar and dialectic. The editing of the whole Bible and its division into chapters and verses is done during this period; it is surely a great help for writers in making references to the biblical texts. The verbal concordance is composed. The analitical and contextual study of the Bible becomes more familiar. Quite a few commentaries on the biblical books (wholly or partially) are written; it seems that the most preferred books to comment on are Genesis, Psalms and the Song of Songs as the Appendix II shows us. All these tools for exegesis reflect the increasing conviction that the literal sense of the Bible is fundamental for the spiritual senses. St Thomas says,8 Si può argomentare soltanto partendo dal senso letterale e non dai sensi denominati allegorici ... Nulla della sacra Scrittura andrà, tuttavia, perduto, poiché nulla di necessario alla fede è contenuto nel senso spirituale senza che la Scrittura ce lo comunichi chiaramente altrove nel senso letterale (Ia, q. I, a. 10). A similar conviction is found in the saying of Albert the Great, “The literal sense is the primary sense wherein lies the basis for the three spiritual senses” (Summa theologica Ia,I,5,4) or of Bonaventura, “Who despises the letter of the Scriptures will never get to the spiritual comprehension.” This increasingly stronger appreciation of the literal sense of the Bible results in the decline of spiritual exegesis in universities. But it does not mean that spiritual exegesis is rejected. It is still used besides literal exegesis, especially in homilies. The reason for that is as follows. For most of medieval Christian writers the spiritual sense is not an external addition or adornment to biblical texts or an “adaptation” of biblical texts to the spiritual needs of the Christian life but constitutes an essential element of the biblical meaning. The spiritual senses 7 8 Riché, art. cit., 33. Cited from Verger, art. cit., 110. Henricus Pidyarto, The Use of The Bible 145 are, using Thomas Aquinas’ words, “de necessitate sacrae Scripturae.”9 Since God is the author of the Bible, it contains unfathomable mysteries that reveal the unity of the history of salvation. It should be noted here that the birth of mendicant orders gave a great contribution the history of exegesis. The mendicant friars, dedicating themselves to the study of theology and the Bible as preparation for their apostolate, offer to universities famous theologians and exegetes. The mendicant friars, especially the Carmelites during the 14th and 15th century, are more dominant in biblical field than secular priests, as the appendix I shows us. 2. The use of the Bible in the writings of some Carmelite writers Two preliminary notes should be made here. Firstly, the documents studied here are limited to four documents: 1) Ignea Sagitta of Nicholas the Frenchman; for the text and its enumeration of the lines we follow Adrianus Staring, Nicolai Prioris Generalis Ordinis Carmelitanum Ignea Sagitta” in Carmelus (1962) 271-307; 2) the writings of John Baconthorpe in A. Staring, Medieval Carmelite Heritage (Rome: Institutum Carmelitanum, 1989, 185-253) 3) the work of Philip Ribot in E. Boaga, Nello Spirito e nella virtù di Elia (Roma: Commissione Internazionale per lo studio del carisma e Spiritualità, 1990, 53-83) 4) the Rule. Secondly, it will not be shown here how biblical allusions correspond to the Vulgate. As a matter of fact, it is always difficult to know whether differences in biblical quotations and allusions are caused by different Vulgate versions used by a writer or by his liberal use of the Bible. It should be noted that, before the so-called Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti Quinti Pont. Max. jussu recognita atque edita was published in 1592 by the command of Pope Clement VIII, there had existed several editions of the Vulgate. Those pre-Clementine Vulgates are often mixed up with reminiscences of the Old Latin text (=Vetus Latina). 1. Ignea Sagitta A. Staring rightly says that the author of Ignea Sagitta is a man well-versed in Scriptures.10 That this work is impregnated with biblical references is revealed by 9 10 146 Verger, 104. Carmelus (Vol. 9, 1962) 251 (“Optime versatus est in Sacra Scriptura et novit etymologias scientiae biblica temporis”). Cf. also B. Edwards, Sword (Vol. XXXIX, No. 2, 1979) 6. Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 the fact that it has at least 189 biblical allusions. In our judgement the author of Ignea Sagitta uses the Bible in the following ways: 1. By quoting (completely or partly) biblical texts, even though sometimes there is a slight difference from the Clementine Vulgate, as the following examples show us: Ignea Sagitta I:2-3 Lam 4: 1 Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum! Heu me, Mater! quae me genuisti, Religio sanctissima, de altitudine excellentis ac eminentis scientiae circumcisionis spiritualis olim merito nuncupata, propter te Propheta lamentatur ... Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus, dispersi sunt lapides sanctuarii in capite omnium platearum! Ignea Sagitta I:38-39 Lam 1: 6 Unde iterum Propheta propter te lamentatur dicens: “Egressus est a figlia Sion omnis decor eius, et principes eius velut arietes non invenerunt pascua” Et egressus est a filia Sion omnis decor ejus; facti sunt principes ejus velut arietes non invenientes pascua ... Ignea Sagitta I: 60 Psalm 68:10 Verumtamen, quoniam zelus domus tuae comedit me, hunc statum considerans tuum, Mater mea religiosissima, vehementis tristitiae compellor suspiria emittere lacrimosa. Quoniam zelus domus tuae comedit me ... 2. By borrowing biblical words/terms, mostly without taking into consideration their proper context or their original meaning. Some examples can be given here. In Ignea Sagitta the Order is compared to Jerusalem; therefore what is said of Jerusalem in the Book of Lamentations is said of the Order. The writer himself says in I: 34, “Agnosce, Mater, agnosce omnia ista de te dicta” (here “omnia ista” refers to the Book of Lamentations). The Order is also compared Henricus Pidyarto, The Use of The Bible 147 to the man who falls into the hands of the robbers on his way from Jerusalem to Jericho (Lk 10:29f.). Or again, the former state of the Order is compared to the good pasture of Ps 22:2 with “the pasture” being interpreted spiritually (II: 2023). On the other hand, the stepsons of the Order (i.e. those who abandon solitary life and live in cities) are compared to the “princes” of Jerusalem who wander in the trackless wastes (cf. Ps. 106:40) or to the Israelites who dwelt among the heathen (referring to Ps. 105:35-36 and Lam 1:3). In the opening greeting (“Omnibus suis concaptivis pauper Nicolaus salutem et Spiritus Sancti consilium permanens in aeternum) the terms concaptivis of Rm 16:7 and concilium and in aeternum of Ps 32:11 are borrowed freely. Then in I: 58-59, “the stone of offense” (lapides offensionis) and “stumbling-blocks” (petrae scandali) referring to the stepsons of the Order are terms borrowed from Is 8:14 where the two words refer to God. Similarly, “Non sic impii, non sic” of Ps 1:4 is used as a direct address to the stepsons of the Order, whereas in Ps 1:4 the phrase is not an appellation. In some cases, however, the writer borrows biblical words and idioms in their original sense, e.g. I: 28, “pacis vinculo” of Eph 4:3; IV: 2829 “to clap hand over mouth” of Job 21:5 meaning to be silent out of shame or wonder; etc. 3. By quoting verses (partly) and combining them with other verses so as to make a mosaic of texts: I: 30-33 (Lam 1:8; 1:7; 1:8; 1:2); II: 27-35 (Lam 4:2; 2:14ab and 2:18b-19); II: 39-52 (Lam 1:13; 1:11; 3:45; 1:18; 1:15-16; 1:19; 1:16; 4:14; 2:22 and 4:6). 4. By using biblical texts interpreted spiritually, especially tropologically. E.g. in I: 40 the pasture of Lam 1:6 is understood as spiritual consolation. In Ch. VI many biblical figures (Abraham, Moses, Jesus) are mentioned as models for solitary hermits. 5. The most frequently quoted books are Ps (48 times) and Lam (26 times). That Ps is the most frequently cited book is very understandable, since in the past every hermit should know the Psalms by heart. That Lam is second to Ps is understandable as well, because in this work the Order is compared to the fall of Jerusalem spoken in Lam. From the above data we can conclude that the writer of Ignea Sagitta proves to be the son of his times when biblical interpretation is predominantly spiritual; he shows himself very familiar with the Bible to such an extent that the words of the Bible become his own words. That is why it is not easy to distinguish the writer’s words from biblical words, unless one is quite familiar with the Vulgate or one makes use of a verbal concordance. 2. Philip Ribot’s work In the selected texts of Ribot as we find them in E. Boaga’s Nello Spirito e nella virtù di Elia we can find at least 182 biblical references (OT 84 and NT 98). The two books most frequently cited are Psalms and Mt (at least 25 times each). A 148 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 closer examination of the way Ribot uses the Bible results in the following conclusions: 1. Compared with Ignea Sagitta, Ribot’s work makes a good use of biblical texts in a simpler way. There are more direct quotations (almost equally from OT and NT) taken in their literal sense. The reason seems to be the fact that Ribot’s work aims at describing the ideal of a hermit’s life in imitation of Elijah. Therefore Ribot cites biblical texts that in themselves contain spiritual meaning, and accordingly do not need to be interpreted spiritually or tropologically. E.g. ch. IV (on controlling one’s own will and carnal desires) is full of biblical texts in their literal sense. Outside such texts, Ribot treats Scriptures with spiritual-tropological interpretation. He often tries to see the historical sense but then he prefers the mystical/spiritual sense (“non solum historice, sed potius mystice,” Ch. 2). It is interesting to see how he gets to the moral interpretation through the etymology of biblical names or words. From etymological sense he goes further to spiritual sense. E.g. the phrase “contra Iordanem” of 1 Kgs 17:2-4 is interpreted as “against our sins.” Why? Because “Iordan” means “descensio” (=descent). From this literal-etymological sense he goes further to say that “Iordan” means sins, because sins are spiritual descent or degrading state of human souls. Then Wadi Carith, which etymologically means separation, is interpreted as charity. The reason for that is Ribot’s conviction that only charity (Caritas) is a real separation from Jordan, which means sins. Ribot follows the etymological science common in his times. Sometimes Ribot expounds biblical texts in their historical-literal sense (e.g. the story of Elijah and King Achab of 1 Kgs 17-18). In some cases, we can feel the influence of Jewish interpretation of Scriptures, in so far he puts emphasis on the historicity of biblical stories. In his work Ribot deals with biblical stories as if they were all strictly historical facts. Ribot seeks biblical stories to legitimate the existence of the Carmelite Order as Elijah’s successors. The basis for that succession is found in Sir 48:8, “Prophetas facis successores post te.” John the Baptist is identified with Elijah (see Liber II, ch. 1). Another interesting thing in Ribot’s work is the shift from one symbolism to another. In Liber I ch. VIII the ravens are explained allegorically as the prophets, but then the hermits themselves are described as young ravens that should wait until their black feathers grow in order to be fed. 3. John Baconthorpe a. Speculum de institutione ordinis Even though John Baconthorpe taught Scriptures at a university, his exegesis is very spiritual. He argues that the Order has a very old history, going back to the time of Elijah. His argumentation is as follows. According to Is 35:1-2 (“Datus est ei decor Carmeli”) Mount Carmel is given to Mary. So Mary is continually called the owner or mistress (domina) of Carmel. Citing biblical texts, Baconthorpe goes fur- Henricus Pidyarto, The Use of The Bible 149 ther to say that many prophets and kings came to honor her. Now since Carmel should not be abandoned to solitude the Order was instituted to continue the devotion to Mary. The biblical texts are taken as proof, overlooking their literal-historical sense. In ch. II he uses typological exegesis, comparing Elijah and Elisha to Jesus. We can find at least 31 references to OT and 10 to NT. Since Elijah and Elisha are seen as predecessors of the Carmelites, it is understandable that the two books of Kings are the most frequently quoted. Unlike Nicholas the Frenchman and Ribot, Baconthorpe always gives clear reference to the Bible, namely mentioning the chapters of a book. However, he sometimes makes mistakes: e.g. in Speculum II: 58 he refers to Is 32 instead of Is 35:4; in lines 66-67 of the same chapter he refers to Jn 29 (which does not exist) instead of Jn 12. Judging from these mistakes and from the inverted order of biblical words we may conclude that Baconthorpe knows the Bible by heart, and seemingly quotes it from memory. In general the biblical quotations in this work are taken in their literal sense: he quotes them as a kind of historical facts. b. Tractatus Super Regulam In this treatise Baconthorpe describes Mary as the model of religious life, because she lives up to the three evangelical counsels spoken of in the Rule. There are 2 references to OT and 16 to NT (including the biblical allusions we can find in the Rule cited by Baconthorpe). Generally speaking, his exegesis is predominantly literal. The biblical texts speak of morality and, since the Rule is a “moral/tropological” text, Baconthorpe did not need to make spiritual exegesis out of non-spiritual texts. c. Compendium historiarum et iurium ... In this work there are very few references to the Bible: only 3 to OT and 1 to NT (not counting the biblical references that are taken from Peter Comestor’s Historia scholastica). The first biblical quotation is from Is 35:2 (“Gloria Libani data est ei, decor Carmeli et Saron”); this verse is considered as the basis for the belief that Mary is the owner of Mount Carmel (line 5-6). All the other references are given as historical facts to legitimate the history of the Order. d. Laus religionis Carmelitanae In Book I, ch. III the fertility and excellent quality of Carmel is compared to Mary’s superiority over other human beings. Song 2:2 is interpreted as spoken by Jesus to Mary (Liber I, Cap. III: 35-36 which reads, “Unde de ipsa dicit Christus: ‘Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias’”). She is (using the words of 150 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Psalm 67:17) a mount “in quo beneplacitum est Deo habitare in eo” (Liber I, Cap. III: 37-38). Baconthorpe even cites Is 10:18 and interprets it as speaking about Mary. In fact, the verse in its original context has nothing to do with Mount Carmel in Holy Land. There the Hebrew word karmillo should be translated “his plantation” or “his fruitful land” (Vulgate: carmeli ejus). Is 10:18 is a curse to Assyrian land and plantation (=karmel). Thus, by playing on the words Baconthorpe uses spiritual exegesis. Biblical allusions are often borrowed to justify every honour or attribute given to Mary, even though originally those texts have nothing to do with Mary. The same can be said of the other books (Liber II - VI). In our judgement, Baconthorpe makes good use of the Bible; he is familiar with the Bible. He rarely quotes the texts in their literal-historical sense. But he very often uses spiritual exegesis. 4. The Rule The Rule itself urges the Carmelites to be continually occupied with the Word of God, “die ac nocte in lege Domini meditantes” (par. 7; cf. par. 4 etc.). It is logical that for the composer of the Rule himself the prayerful reading of the Bible in Lectio Divina plays an important role in his life. So it is not surprising then that the Rule is so impregnated with biblical terms and themes.11 These are only two examples: 1. “Albertus, Dei gratia Ierosolomitane Ecclesie vocatus patriarcha, dilectis in Christo filiis B ... in Domino salutem et Sancti Spiritus benedictionem” (of Prologue) must be inspired by the introductory greetings in the Pauline letters in terms of its structure (name of sender - his status through God’s grace - the beloved addressee - benediction) and its wording (vocatus, Domino, in Christo). Cf. the greeting in Rm 1:1; Eph 1:1; 2 Cor 1:1. - Par. 14 of the Rule is a mosaic of biblical texts (OT and NT): “Accingendi sunt (cf. Ex 12:11) lumbi (Eph 5:14) cingulo (cf. Is 11:5) castitatis.” “Gladius autem Spiritus, quod est verbum Dei (Eph 5:17) abundanter habitet (cf. Col 3:16) in ore et in cordibus vestris (cf. Dt 30:14). Et quaecumque vobis agenda sunt (cf. 1 Cor 10:31; 1 Pe 4:11), in verbo Domini fiant.” In some cases the composer of the Rule just borrows biblical words, e.g. oratorium ... in medio (par. 10 - cf. Ez 48:8); “vita hominis super terram” (par. 14 - cf. Job 7:1). But in most cases biblical texts are used as the composer’s own words in their literal sense. This is understandable since the Rule is meant to give a set of rules for the hermits’ life. Therefore, biblical texts that contain moral teachings can be taken in their literal sense and be quoted as support for the commands and exhortations given by the Rule. Taking into consideration the above observations, we can conclude that the composer of the Rule is a man of God’s Word. He is so familiar with God’s Word to such an extent that the biblical phrasing and ideas become his own. Accordingly, biblical terms, words and themes become his own and he can refer continually to them, quote them from memory and adapt them slightly to his own needs. Henricus Pidyarto, The Use of The Bible 151 3. General conclusions The above study of the use of the Bible in some Carmelite documents show the following characteristics: (1) The writers/composers of those documents are men of God’s Word. Lectio Divina must play central role in their spiritual life, so that their familiarity with the Scriptures is amazing. (2) They often borrow biblical words as their own without informing their readers. (3) They are sons of their times: their biblical interpretation is predominantly spiritual (moral, topological) without paying too much attention to the literal sense of the texts they quote or use. In some cases, the Carmelite writers treat the biblical stories as historical facts in the strict sense of the word. BIBLIOGRAPHY Brown, Raymond E., “Hermeneutics,” in Raymond E. Brown - Joseph A. Fitzmyer - Roland E. Murphy (ed.), The Jerome Biblical Commentary, London: Geoffrey Chapman, 1968. Edwards, B., Sword, Vol. XXXIX, No. 2, 1979. Grant, Robert M. - David Tracy, A Short History of the Interpretation of The Bible, London: SCM Press,19842. Lubac, Henri de, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Ecriture, Paris: Aubier, 1959-1964. Riché, Pierre, “Strumenti di lavoro e metodi dell’esegeta in epoca carolingia,” in Pierre Riché, Jean Châtillon - Jacques Verger, Lo studio della Bibbia nel Medioevo latino, Brescia: Paideia, 1989. Schökel, Alonso, Il dinamismo della tradizione, Brescia: Paideia, 1970. Secondin, Bruno, ed., La regola del Carmelo. Ticheler, Jo., Didyme l’Aveugle et l’exégèse allégorique [doctoral dissertation], Nijmegen: Dekker en van de Vegt, 1977. Carmelus, Vol. 9, 1962. 152 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 Telaah Buku Judul Buku Penulis Penerbit Tebal : : : : Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Sindhunata Kanisius, Yogyakarta 2000 258 halaman Dalam majalah TEMPO edisi 28 Januari – 3 Februari 2002, dimuat ulasan tentang praktek jual beli gelar-gelar kecendikiawanan di Indonesia. Sediakan beberapa belas juta rupiah, maka Anda berhak untuk menyandang gelar master, doktor tanpa harus membuat riset, thesis, dan disertasi. Tapi tentu jangan tanya kualitas. Itulah salah satu potret buram pendidikan di Indonesia. Masih banyak permasalahan lainnya. Kita akan menarik nafas panjang. Prihatin. Tapi prihatin saja tidak mengubah keadaan. Perlu ada terobosan pemikiran dan kebijakan. Dalam semangat untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, Universitas Sanata Dharma, Yayasan Kanisius Pendidikan, Majalah Basis, dan Penerbit Kanisius dengan dukungan penuh dari The Ford Foundation menyelenggarakan seminar bertemakan “Quo Vadis Pendidikan di Indonesia”, 21-23 Agustus 2000. Seminar ini menampilkan beberapa pakar pendidikan yang memiliki hati dan idealisme akan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Sumbangan pemikiran mereka dikumpulkan dalam 2 buku. Buku pertama berjudul Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita dan buku kedua adalah buku yang akan kita lihat ini. Salah satu kekurangan besar dalam sistem pengajaran di sekolah-sekolah adalah kurangnya penanaman budaya ingin tahu (B. Suprapto Brotosiswojo, hlm. 97). Guru hanya mengajarkan pengetahuan atau teori yang sudah jadi. Murid tidak diajak untuk melihat bagaimana proses pencapaian teori/pengetahuan, penerapan, analisis, dan sintesis (Andi Hakim Nasution, hlm. 165). Mungkin saja karena gurunya juga tidak tahu atau tidak mau direpotkan. Ironisnya guru bangga dengan murid yang duduk dan mendengarkan dengan tenang. Murid yang cemerlang adalah yang mampu menghafal secara persis ajaran gurunya. Andi Hakim Nasution mengisahkan cerita lucu sekaligus tragis yang melukiskan situasi pendidikan kita. Pada waktu itu, di salah satu kota kabupaten, ada ceramah tentang matematika dan sains. Yang diundang meliputi wakil murid SD, SLTP, dan SMU dari semua kecamatan. Juga diundang guru pendamping serta tokoh bimbingan tes. Dalam acara tanya jawab seorang murid bertanya: “Kalau saya jadi astronot dan membawa kipas; apakah akan terjadi angin bila saya mengipas-ngipaskan kipas di ruang angkasa?” Ternyata tak satu pun guru pendamping dan tokoh bimbingan tes yang mampu menjawab. Para siswa tertawa. Padahal para guru dan tokoh bimbingan tes itu menguasi teori tentang terjadinya angin. Sayang tidak bisa mengaplikasikannya. Telaah Buku 153 Pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berkaitan dengan pranatapranata sosial lainnya seperti politik, ekonomi, budaya, dan juga dengan segala dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Dalam artikelnya “Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia” (hlm. 18) Mochtar Buchori menyatakan bahwa pendidikan selalu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan. Karena itu kondisi kehidupan pendidikan pada waktu sekarang akan mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik di masa depan. Dia mencontohkan fenomenon historis generasi politik dari dua periode: 1908–1945 dan 1959-1998. Periode 1908-1945 ditandai oleh para pemimpin politik yang penuh dedikasi dan gigih dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia sementara periode 1959-1998 ditandai oleh para pemimpin politik yang berjuang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mengapa timbul kontras yang begitu tajam dalam rentang 90 tahun (1908-1998)? Salah satu jawabannya adalah terjadinya perbedaan kualitas pendidikan antara dua generasi tersebut. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari arus globalisasi. Globalisasi bukan hanya soal keterbukaan antar negara tetapi lebih pada saling ketergantungan (interdependency) yang bersifat asimetris, artinya satu negara lebih bergantung pada negara lain daripada sebaliknya (J. Soedjati Djiwandono, 105). Negara maju yang kuat dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, industri, teknologi akan lebih bertindak sebagai subjek sedangkan negara berkembang sebagai objek. Dalam banyak hal negara maju akan mempengaruhi negara berkembang. Salah satunya adalah menyebarnya nilai-nilai tertentu seperti materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Menghadapi dampak negatif dari globalisasi tersebut maka negara mutlak perlu untuk mempelopori pendidikan nilai di berbagai tatanan masyarakat termasuk di sekolahsekolah (hlm. 110). Dampak lain dari globalisasi adalah munculnya industrialisasi pendidikan. Bagaimana ini dimengerti? Beberapa universitas di Australia, Amerika, dan Eropa gencar berpromosi ke Asia supaya anak-anak Asia dari keluarga-keluarga kaya kuliah di tempat mereka. Anak-anak Asia ini menjadi tambang emas untuk mengisi kas keuangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut (Ariel Heryanto, 42). Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia pun kita dengan mudah mendapati iklan sekolah atau universitas di media cetak maupun elektronik atau di pusat-pusat perbelanjaan, berjajar dengan iklan shampo, celana jeans, parfum, dll. Menghadapi aneka permasalahan dalam bidang pendidikan yang pertamatama harus dilakukan adalah merumuskan visi pendidikan. Djohar menawarkan suatu praksis pendidikan yang berwawasan ekologi. Ekologi pendidikan adalah semua kondisi lingkungan anak yang dapat berakibat terhadap terjadinya perubahan perilaku anak, yang mencakup perilaku berpikir, mengendalikan diri, dan sosial budaya (hlm. 114). Alex Lanur mengkaji visi pendidikan secara filosofis. Menurutnya kunci untuk memahami pendidikan adalah memahami manusia sebagai persona (hlm. 185). Dalam manusia terdapat beberapa struktur dasar yakni: (1) manusia adalah makhluk jasmaniah-rohaniah; (2) manusia adalah makhluk individual-sosial; (3) manusia adalah makhluk yang bebas, dan (4) manusia adalah makhluk yang menyejarah. Alex Lanur menguraikan makna dari masing-masing struktur dasar itu dan implikasinya terhadap 154 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 pendidikan. Misalnya, karena manusia adalah makhluk jasmaniah-rohaniah maka pendidikan jasmani, keterampilan tangan, kepekaan panca indera, perlu dimasukkan dalam sistem pendidikan. Demikian juga dengan kemampuan-kemampuan jiwa yakni seluruh daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam buku ini masih ada banyak tulisan dari pakar pendidikan yang tidak dikutip di atas. Tetapi pada intinya saat membaca buku ini kita diajak untuk melihat pendidikan dari berbagai aspek dan sudut pandang dengan segala permasalahannya. Karena buku ini merupakan kumpulan makalah yang temanya dibuat berdasarkan kompetensi pengarangnya maka tidak mudah untuk merangkaikan jalinan ide yang satu dengan yang lain. Benang merahnya hanya satu yaitu: pendidikan. Meski demikian dalam lampiran disajikan 2 buah rangkuman yang mencoba untuk mengakomodir ide-ide penting yang tersebar dalam makalah-makalah tersebut. Karena pendidikan bukan hanya urusan guru, dosen, pemerintah melainkan seluruh komponen masyarakat maka buku ini patut dibaca oleh semua orang untuk membuka wawasan dan sumber inspirasi dalam membenahi pendidikan di Indonesia. Karena dengan meningkatkan kualitas pendidikan kita meningkatkan kualitas bangsa ini.. Paulus Dwintarto Telaah Buku 155 INDEX Studia Philosophica et Theologica Volume 1 (Maret & Oktober 2001) ARTIKEL Handoko, P.M., Rekan-Anggota dan Rekan-Pembangun Kerajaan Allah: Pendasaran Teologis untuk Penghayatan Iman yang Merangkul 29 - 37 Jainuri, Achmad, Allah, Universalitas, dan Pluralitas 38 - 43 Kelen, D. Sermada, Penderitaan Orang yang Tak Bersalah. Perspektif Fenomenologi Agama 128 - 141 Ohoitimur, Yong, Tujuh Teori Etika tentang Tujuan Hukum Pareira, B.A., Kitab Suci dan Pendidikan Nilai 90 - 105 68 - 77 Pidyarto, Henricus, The use of the Bible by Medieval Carmelite Writers Reksosusilo, S., Hukum Karma Dipandang dari Segi Etika 142 - 152 106 - 119 Riyanto, E. Armada, Fides et Ratio: Menggagas Pertautan Filsafat dan Teologi plus Implikasinya dalam terang Ensiklik Fides et Ratio 1 - 28 ————, Ethics of Political Life. From The Christian-Philosophical Point of View Sudarminto, J., Informed consent dan Otonomi Manusia 78 - 89 120 - 127 Sudhiarsa, Ray, Social Construction of Balinese World and Christianity, 44-54 Wijanarka, Robert, On Humanism: Exploring the concept of Humanism in Indonesia 55 - 61 TELAAH BUKU Abimantrono, A., Global/Lokal. Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia Th. X-2000 Dwintarto, Paulus, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan 153 - 155 Dwintarto, Paulus – Didik P., Fifty Key Contemporary Thinkers 156 64 - 65 62 - 63 Vol. 1 No. 2 Oktober 2001 BIODATA KONTRIBUTOR B.A. Pareira, Doktor Teologi Kitab Suci dari Universitas Gregoriana, Roma; sebelumnya menyelesaikan lisensiat Kitab Suci di Biblicum, Roma; dosen Kitab Suci Perjanjian Lama di STFT Widya Sasana, Malang. Donatus Sermada Kelen, M.A., Master filsafat bidang studi ilmu perbandingan agama dari Universitas Bonn, Jerman; dosen filsafat ketuhanan di STFT Widya Sasana Malang. E. Armada Riyanto, Doktor Filsafat dari Universitas Gregoriana, Roma; dosen etika, filsafat politik, dan metafisika di STFT Widya Sasana, Malang. H. Pidyarto, Doktor Teologi Kitab Suci dari Universitas Santo Thomas, Roma; sebelumnya menyelesaikan lisensiat Kitab Suci di Biblicum, Roma; dosen berbagai mata kuliah Kitab Suci Perjanjian Baru. J. Sudarminto, Doktor Filsafat dari Fordham University, USA; dosen beberapa mata kuliah filsafat di STF Driyarkara, Jakarta sekaligus menjabat Ketua STF. Paulus Dwintarto, Mahasiswa STFT Widya Sasana Malang, program Magister teologi. S. Reksosusilo, Doktor Filsafat dari Universitas Santo Thomas, Roma; dosen beberapa mata kuliah filsafat ketimuran dan filsafat nusantara, filsafat sosial. Yong Ohoitimur, Master filsafat diselesaikan di Institut Filsafat Universitas Katolik Leuven, Belgia, dan doktoral di Universitas Gregoriana Roma; rektor Universitas Katolik De La Salle Manado; dosen filsafat, etika, Islamologi dan ilmu perbandingan agama di STF Seminari Pineleng, Manado. Biodata Kontributor 157