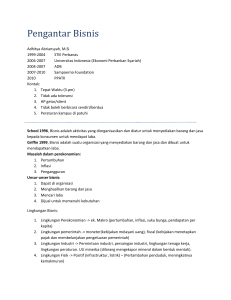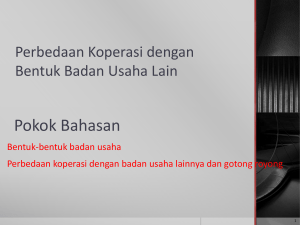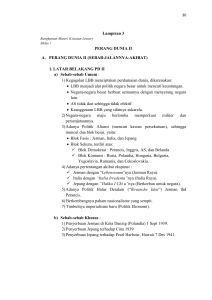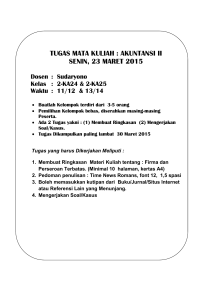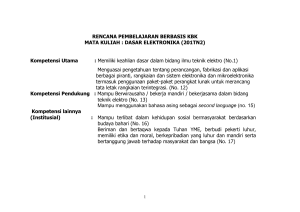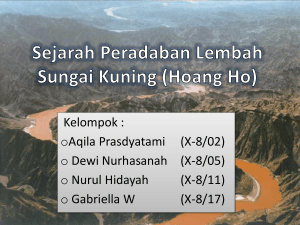Bab I
advertisement

Pendahuluan Dalam beberapa dasawarsa terakhir, Jepang secara meyakinkan eksis dan memantapkan diri menjadi salah satu negara adidaya. Pilar-pilar kiprahnya berakar dan tertanam kuat di bidang ekonomi, industri, keuangan, dan teknologi. Bahkan tidak berlebihan bila dikatakan kekuatan militernya dewasa ini merupakan salah satu yang terbesar dalam konstelasi percaturan antarbangsa. Kapasitas semacam ini, sebenarnya, memungkinkan Jepang untuk mempengaruhi kondisi dan situasi lingkungannya, khususnya dalam radius negara tetangga dan kawasan, baik yang dekat maupun yang jauh. Sebagai negeri kalah-perang dalam Perang Dunia II, adalah logis jika pencapaian Jepang menumbuhkan inspirasi dan sekaligus menjadi idaman berbagai negara dalam kelompok Dunia Ketiga. Dia menjadi simbol dan pemicu bagi negara yang ingin membangun perekonomian nasionalnya. Jepang mempunyai daya tarik yang sangat kuat bagi negara yang ingin melestarikan kebudayaan nasionalnya, di tengah fakta bahwa globalisasi yang tak terelakkan itu cenderung menggerus dan menggusur sendi-sendi budaya lokal/nasional. Pendek kata, Jepang muncul sebagai sebuah patron, sosok negara yang perlu ditiru kalau ingin maju. Dan itu memang terjadi. Langkah-langkah menduplikasi kiat sukses Jepang sedang giat-giatnya dilakukan oleh sejumlah negara, terutama di Asia. Singapura, misalnya, mampu menjadi salah satu “macan” Asia setelah mengambil langkah “Learn from Japan”; Malaysia mulai tinggal-landas menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia berkat menerapkan kebijakan “Look East Policy” di awal 1980-an; Muangthai memiliki Pusat Pengkajian Jepang, yang secara khusus meneliti bidang kebudayaan dan peradaban Negeri Matahari Terbit; dan Indonesia—dengan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia—berupaya mencermati lebih jauh model dan pelaksanaan pembangunan nasional Jepang. Salah satu cara yang dilakukan Jepang adalah dengan menciptakan adanya kesamaan persepsi dari seluruh lapisan masyarakat bangsanya dalam melihat apa yang terbaik bagi mereka. Kesamaan persepsi ini terlihat dalam kebijakan yang diambil oleh negarawan Meiji ketika merumuskan kebijakan nasionalnya pada tahun 1868. Dari Wakon Kansai ke Wakon Yosai Awal abad ke-17, tepatnya tahun 1602, imperialisme Barat (dalam hal ini bangsa Belanda) mendirikan kongsi dagangnya (VOC) di Batavia. Pada tahun yang sama, pemerintahan militer Tokugawa di Edo (Tokyo sekarang)—yang saat itu berpenduduk 1-1,5 juta jiwa (populasi London atau Paris hanya 860 dan 650 ribu jiwa)—menerapkan kebijakan sakoku (politik pintu tertutup). Kebijakan politik pintu tertutup ini pada awalnya hanya melarang orang Jepang pergi ke luar negeri dan melarang orang asing datang ke Jepang. Aturan itu menjadi lebih keras pada 1632, dengan melarang juga orangorang Jepang yang berada di luar negeri kembali ke Jepang. Kebijakan sakoku yang berlangsung hingga 1867 sama sekali tidak mengakibatkan Jepang kehilangan kontak dengan Barat yang sudah maju akibat revolusi industri. Informasi mengenai perkembangan yang terjadi di luar Jepang tetap dapat dikuasai dengan baik oleh penguasa militer Tokugawa melalui sebuah pulau kecil, Dejima, Nagasaki. Lokasi ini memang diplot sebagai tempat untuk melakukan transaksi dagang dengan Belanda dan Cina. Dari orang-orang Belanda inilah (baik yang pedagang maupun informan Tokugawa) informasi berupa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa diserap Jepang, dan ilmu pengetahuan ini dikenal dengan nama rangaku (ilmu Belanda). Kebijakan melihat ke dalam (inward looking) ini dirancang antara lain untuk menumbuhkan harga diri dan kebanggaan nasional. Konsolidasi di kalangan segenap warga negara Jepang ditempa dengan militan. Kehormatan mereka sebagai anak bangsa ditumbuhsuburkan demi dan atas nama nasionalisme. Semasa pelaksanaan politik pintu tertutup inilah, rakyat Jepang yang sudah satu bahasa—bahasa Jepang—memadukan energi, kesadaran dan komitmen tentang Jepang sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Dengan gairah besar untuk menciptakan Jepang yang kuat, semboyan Wakon Kansai (Spirit Jepang, Teknologi Cina) yang dianut Jepang sejak periode kuno mulai ditinggalkan. Penyebabnya tidak lain karena Cina sudah kedaluwarsa untuk dijadikan sebagai soko guru, dia sudah menjadi vasal Barat (Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman). Mafhum bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai Barat, kepada anak negeri dikumandangkan semboyan baru: Wakon Yosai (Spirit Jepang, Teknologi Barat). Motivasi untuk bisa setara dengan Barat ini semakin kuat dirasakan rakyat Jepang di pengujung pemerintahan militer Tokugawa (bakumatsu). Pada 1853, ketika Commodore Matthew Perry dengan armada lautnya (kurofune-kapal hitam) mendarat di Uraga (Teluk Tokyo), dan memaksa Jepang membuka pelabuhannya bagi kepentingan kapal-kapal Amerika Serikat yang akan menuju ke koloni mereka di Filipina, Cina dan Guam. Penguasa militer Tokugawa dan kaum intelektual Jepang menyadari, sekali mereka memberikan kesempatan kapal-kapal Amerika mendarat di pelabuhan Jepang, maka hal yang sama juga akan diminta oleh imperialis Barat lainnya. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan, ketika armada Perry datang kembali pada 1854, Jepang dibuka secara paksa. Alhasil, konsesi pembukaan pelabuhan yang diberikan kepada Amerika berturut-turut dapat juga dinikmati oleh kapal-kapal Rusia, Prancis, Inggris, Belanda, Jerman dan lainnya. Kenyataan ini membuka mata rakyat Jepang, seiiring dengan tumbuhnya kerisauan yang mudah diterka. Mereka khawatir akan mengalami nasib seperti Hindia-Belanda, Filipina, Malaya, Singapura, Cina, Vietnam. Karenanya, harus ada yang dilakukan agar Jepang tidak terjerembab menjadi koloni imperialis Barat. Debat dan pertikaian pro-kontra di kalangan rakyat mencuat ke permukaan. Isu pokok yang menjadi pergumulan adalah bagaimana/dengan cara apa kelangsungan bangsa dapat dipertahankan. Rakyat Jepang yang progresif (diwakili oleh samurai muda dari empat han atau semacam provinsi militer yakni, Satsuma - sekarang Provinsi Kagoshima; Choshu - Yamaguchi; Hizen 2 - Saga, dan Tosa - Kochi, keempat han ini biasa disingkat dengan SATCHOHITO) menghendaki agar Jepang segera membuka negara secara resmi terhadap dunia luar. Di lain pihak, rakyat Jepang yang konservatif (diwakili oleh pemerintahan militer Tokugawa) gigih mempertahankan kebijakan politik pintu tertutup. Keduanya memiliki kesamaan sikap dalam satu hal: (tetap) muliakan posisi Kaisar. Melalui dialog intensif yang panjang (14 tahun), rakyat Jepang pada 1867 mampu mencapai kesamaan persepsi tentang masa depan bangsanya. Bahwa Jepang hanya akan dapat berdiri tegak dalam posisi setara dengan negara-negara imperialis Barat, bahkan melebihi, apabila ilmu dan teknologi yang dimiliki Barat dapat dikuasai. Untuk menguasai ilmu dan teknologi Barat itu, diperlukan suatu kebijakan nasional yang dipahami oleh setiap individu rakyat Jepang. Prasyarat untuk menciptakan dan mewujudkan kebijakan nasional tersebut adalah tegaknya pemerintahan yang kuat. Konfigurasi pemerintahan yang ada, yang secara de facto tidak cukup progresif mendukung tercapainya impian besar itu, harus dirombak. Jalan satu-satunya untuk itu adalah dengan mengkonsentrasikan semua hak dan wewenang memerintah di satu tangan. Individu panutan pemangku jabatan tersebut tak lain dari Kaisar. Dipelopori oleh samurai muda terpelajar dari han SATCHOHITO, seperti Saigo Takamori, Ito Hirobumi, Okuma Shigenobu, Okubo Toshimichi, Iwakura Tomomi, Kido Koin, Goto Shojiro, Eto Shinpei, Sakamoto Ryoma, Itagaki Taisuke, pada 3 Januari 1868, berhasil membentuk pemerintahan baru. Masa pemerintahan Kaisar Mutsuhito, dengan kurun waktu 15 tahun bertahta, dijadikan momentum bagi kemajuan Jepang; dan julukan yang cocok untuk itu adalah Meiji (pencerahan). Seluruh kebijakan yang berasal dari masa pemerintahan militer Tokugawa dinyatakan tidak berlaku. Jepang menggariskan kebijakan nasional FUKOKU KYOHEI (Negara Kaya, Militer Kuat), melalui perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur politik, ekonomi dan industri. Kaisar Mutsuhito menempatkan orang-orang muda yang terpelajar, berani, berdedikasi tinggi dan berdisiplin di dalam struktur pemerintahannya. Sumber daya manusia yang terampil, kritis, berani, pandai, dan berdedikasi guna memberdayakan infrastruktur yang kuat tersebut direkrut dengan mengacu pada kecakapan, integritas dan kualifikasi pendidikan. Sadar akan pentingnya pendidikan (kaum fungsionalis malah memandang hal ini sebagai faktor terpenting, faktor yang menentukan) dalam pembangunan nasional, pemerintah Jepang pada tahun 1872 membentuk Kementerian Pendidikan. Setahun kemudian, pemerintah mengambil prakarsa mengirim pemuda-pemuda yang terseleksi dengan ketat untuk menimba ilmu dan teknologi di Barat. Dalam tempo yang bersamaan, pemerintah juga mendatangkan para pengajar yang berkualitas dari Barat. Kesungguhan orientasi Jepang dalam menjalankan dua program pencerdasan ini sepenuhnya menjalankan prinsip: dari dana nasional, oleh dana nasional, dan untuk (kemaslahatan) nasional. Kebijakan bidang pendidikan ini merupakan implementasi dari salah satu di antara Lima Sumpah Suci Kaisar (GO KAJO NO GO SEIMON) yang berbunyi, “Pendidikan adalah penting bagi pembangunan nasional. Untuk itu, ilmu dan teknologi harus dituntut ke berbagai penjuru muka bumi demi kemajuan Jepang”. Buah dari suatu perencanaan yang baik itulah yang dinikmati Jepang sebagai ganjaran dalam tempo tak terlalu lama. Gabungan antara mereka yang pulang dari luar negeri dan yang dididik pengajar asing di dalam negeri, pada 1880-an, menghasilkan rerata kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Jepang bahkan membukukan rekor sebagai negara pertama di Asia yang memiliki UUD modern—sederajat dengan konstitusi yang dimiliki imperialis Barat. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang mampu memiliki industri besi dan baja dengan mendirikan pabrik besi dan baja Yahata. Jepang menjadi negara pertama di Asia yang mampu membuat kapal tenaga uap dan listrik dengan kontruksi baja. Begitulah, Jepang mencatatkan diri sebagai pionir di Asia pada masa itu, dalam berbagai terobosan. Patut ditambahkan, posisi Jepang pada akhir abad ke-19 sudah berada pada lima besar dunia. Pada titik tertentu, apa yang disebut dengan pencapaian tujuan nasional sepatutnya diuji, dikritisi dengan tajam. Sudah tercapaikah kebijakan nasional itu? Secara kuantitatif dan kualitatif bagaimana? Benar bahwa Jepang mampu memproduksi berbagai komoditas hingga mereka potensial menjadi negara kaya. Namun, produk-produk tersebut dihadang proteksi pasar—sebuah instrumen hasil rekayasa kubu imperialis Barat. Jepang dilarang memasarkan hasil-hasil produksinya di daerah jajahan kaum imperialis. Diktum ini diturunkan dari (dan sekaligus mengawetkan) mitos menyedihkan tentang keunggulan ras kulit putih atas ras-ras lain. Jepang pantas kecewa dan sakit hati. Mereka akan kaya (Fukoku) jika produk-produknya bisa dipasarkan di dalam negeri dan, yang terpenting, di pasar internasional. Adakah kiat untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional? Jawabannya: ada. Yakni menerapkan strategi ala imperialis Barat, dengan memainkan kartu troef kekuatan senjata dalam arti luas. Merujuk pada rancang bangun Angkatan Laut Prancis dan Inggris di samping keperkasaan Angkatan Darat Jerman, Jepang pun berhasil memodernisasikan Angkatan Perangnya. Kyohei (militer kuat) kah Jepang? Ini pun perlu pengujian dan pembuktian. Mind set dalam pengujian ini tentu saja dalam rangka legitimasi tentang Jepang (yang) kaya. Negara pertama yang menjadi sasaran Jepang adalah Cina. Memanfaatkan momentum sengketa seputar teritori Korea, Jepang menggelar perang dengan Cina, 1894-1895. Bermodalkan tentara yang berdisiplin tinggi, terlatih baik, jiwa patriotisme, dan persenjataan modern, Jepang dengan mudah mempecundangi Cina. Sebagai pemenang perang, Jepang berhak atas Korea, berhak mengoperasikan jalur kereta api Manchuria Selatan, dan memiliki hak yang sama dengan imperialis Barat untuk berdagang di Cina. Peristiwa ini membuktikan; berkat perencanaan yang baik, dijalankan dan diawasi dengan baik, oleh orang-orang yang baik; kebijakan nasional FUKOKU KYOHEI membuahkan hasil. Kinerja yang ditunjukkan Angkatan Perang Jepang, diakui atau tidak, merisaukan imperialis Barat. Rusia yang merupakan seteru bebuyutan Jepang menghasut Jerman dan Perancis agar 3 menghalangi Jepang mengoperasikan jalur kereta Api Manchuria Selatan. Provokasi itu berhasil. Intervensi tiga negara, yang menghalangi apa yang menjadi hak Jepang berdasarkan konvensi sesama imperialis, terasa menyakitkan. Pelecehan tersebut menggelorakan pride kebangsaan orang Jepang. Kini, di depan mata, Rusia nyata-nyata memposisikan diri sebagai musuh. Hanya 10 tahun seusai perang Jepang-Cina, saat kemampuan dianggap memadai, Jepang berperang melawan Rusia, 19041905. Berbeda dari perang 1894-1895, perang kali ini adalah perang antara ras berwarna/kuning yang dianggap lemah dan ras kulit putih yang (dimitoskan) unggul. Hasilnya, lagi-lagi Jepang berjaya. Kemenangan ini memulihkan sepenuhnya hak Jepang atas Manchuria Selatan dan Shakhalin. Kemenangan itu penting artinya bagi keberhasilan masa depan ekonomi Jepang sekaligus menaikkan kasta mereka menjadi warga baru kaum imperialis. Secara psikologis, sukses Jepang membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Asia yang masih terjerat belenggu imperialis Barat. Belajar pada Jepang Terlepas dari sikap dan tingkah laku yang diperagakan Jepang dewasa ini, tetap perlu dikaji bagaimana usaha yang mereka jalankan sehingga muncul menjadi negara maju. Di antara sejumlah faktor yang penting digarisbawahi sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional Jepang adalah adanya kebijakan yang mandiri dari pemerintahan Meiji dalam melaksanakan program kerja; pemanfaatan tenaga ahli luar negeri secara selektif dan ketat; penggunaan teknologi dan peralatan Barat sebagai penyokong proses mengajar dan belajar; pengambilan inisiatif dan kepemimpinan pada satu tangan; berkonsentrasi pada industri kunci yang dijalankan oleh masyarakat pribumi. Kemandirian dalam menjalankan program kerjanya, pada saat mengawali modernisasi, memang bertautan dengan sebuah situasi yang unik. Sampai sebegitu jauh, Jepang tidak pernah tersentuh oleh intervensi asing. Imunitas semacam ini menjadikan Jepang tangguh dalam memelihara budaya nasionalnya, dan itu merupakan salah satu modal penting dalam menggulirkan roda modernisasi. Historisitas sejumlah negara maju menunjukkan, mereka mencapai tingkatan tersebut tanpa melepaskan pertautan dengan akar budaya dan sejarahnya sendiri. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan nasional yang menisbikan perspektif sejarah bangsa yang bersangkutan akan berujung pada kesia-siaan. Dan dalam hal Jepang, fungsi lokomotif yang dijalankan negara dalam proses pembangunan ekonomi dan industri menjadi sangat kondusif dengan dukungan budaya yang relatif homogen. Di pihak lain, jasa dan peranan yang dimainkan tenaga kerja asing dalam pembangunan nasional Jepang tentulah mencatatkan sumbangan tersendiri. Namun, dengan policy yang tegas dan nyali politik yang memang layak ditegakkan sebagaimana mestinya sebuah negara berdaulat, Jepang memplot tenaga ahli asing ini sepenuhnya di bawah kontrol bumiputra. Bagaimana manusia Jepang menangani para tenaga kerja asing ini bisa dilihat dari pernyataan berikut: “To make sure that foreigners did not endanger the political and economic independence of Japan, the government reserved all the important positions for the indigenous people and made use of foreigners only as employees in the sense of servants. After completing their designated tasks, they were then dismissed, not uncommonly, in order to make room for other foreign specialists (Piper, 1976:168, dikutip dari Kyalo, Mativo, 1989:135, Ph.D Thesis). Kebanyakan negara Asia, yang umumnya pernah merasakan penjajahan imperialis Barat, kondisi seperti ini yang justru tidak dimiliki. Di kebanyakan negara Dunia Ketiga, yang notabene berada di kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika, kita melihat rencana pembangunan berskala nasional—dalam konteks ekonomi, politik, sosial, dan budaya—yang dijalankan pascapenjajahan. Malangnya, yang disebut dengan rencana pembangunan nasional itu pada umumnya sekadar dimensi miskin dari sebuah cetak biru (blue print). Kita makin banyak menyaksikan intervensi langsung perusahaan multinasional terhadap negaranegara Dunia Ketiga. Kita menyaksikan hal ironis ketika pemerintah yang naif justru lebih memihak kepentingan (ekonomi dan politik) pihak asing alih-alih menjawab kebutuhan riil rakyatnya. Akibat ketergantungan finansial, misalnya, sebuah negara dengan mudah masuk ke dalam perangkap negaranegara maju, baik melalui instrumen moneter mantan penjajahnya maupun melalui lembaga-lembaga keuangan internasional. Seharusnyalah pembangunan nasional disusun bukan dengan semangat menjiplak model pembangunan negeri lain, melainkan secara komprehensif dirancang untuk memenuhi sebesar-besarnya pengharapan rakyat. Melihat apa yang telah Jepang jalankan, ada tanya yang rasanya perlu untuk dijawab oleh kita semua. Pertanyaan itu adalah, “Apakah ada kebijakan nasional yang mendasari kegiatan yang berskala nasional, misalnya pengiriman atau keberadaan karya siswa Indonesia di luar negeri? Kalau ada kebijakan nasional untuk hal yang satu ini, apakah dana yang dikeluarkan untuk karya siswa tersebut berasal dari dana nasional? Kalau jawabannya ya, pertanyaan berikutnya adalah, Apakah persepsi karya siswa tersebut sama terhadap kebijakan nasional yang ingin dicapai tersebut? Kalau jawabannya juga ya, maka apa yang dicapai Jepang juga akan bisa dicapai oleh Indonesia. Tapi kalau ada jawaban terhadap pertanyaan di atas yang ‘tidak’, untuk satu pertanyaan saja, maka usaha untuk maju akan terhambat. Apalagi kalau jawaban yang diberikan semuanya adalah ‘tidak’, maka tugas yang maha beratlah yang kita emban. Meskipun masih sekitar 11 persen rakyat Indonesia yang belum bisa membaca (apalagi bisa mengerti) tentang apa yang menjadi kajian dari isi buku ini, marilah kita samakan persepsi kita mengenai apa yang dimaksud dengan satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air, dan pada akhirnya akan bermuara pada apa itu pembangunan nasional. Melalui media sejarah, diharapkan kita akan mampu melihat dan mengkaji ulang tentang apa saja yang perlu kita ambil dari pengalaman bangsa yang terlebih dahulu maju dari kita, dan sebaliknya, faktor apa saja, yang meskipun milik kita, tapi 4 menghambat langkah untuk maju, harus pula disingkirkan jauh-jauh dari ruang lingkup masyarakat bangsa ini.© Bab I Jepang dan Perang Dunia II Hukum Besi Sejarah dan Harga Diri Bangsa Tidak ada pemenang perang yang sudi disejajarkan dengan pecundangnya. Sang pemenang niscaya mendiktekan kehendaknya kepada pihak yang ia taklukkan. Jerman harus menelan pil pahit semacam itu pasca-Perang Dunia I, setelah kubu Sekutu memenangi perang. Mereka diwajibkan membayar pampasan perang dengan sebuah nominal yang, menurut hitung-hitungan awam, hanya mungkin terlunasi dalam tempo puluhan tahun. Itu pun jika keadaan ekonomi Jerman normal. Normal dalam arti tanpa beban pengeluaran untuk rekonstruksi dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat ganasnya mesin-mesin perang. Padahal, kerusakan fisik dengan nilai nominal yang relatif dapat dikonversikan ke dalam angka-angka itu menjadi berlipat ganda dengan bobot kerugian tak terukur yang ditanggungkan Jerman: banyaknya korban jiwa baik militer maupun sipil dan—ini yang terdahsyat—hancurnya moral rakyat. Para negarawan Jerman menyadari betul, upaya pemulihan harkat dan derajat Jerman sebagai sebuah bangsa adalah beban raksasa di pundak mereka. Sepanjang hampir dua dasawarsa (1918 hingga pertengahan 1930-an) Jerman dengan tekun mengkonsolidasikan diri. Secara perlahan mereka membenahi segenap potensi yang mereka miliki. Target yang mesti diwujudkan adalah terbebas dari hutang dan penghinaan. Sebab, begitulah hukum besi sejarah merumuskan aksiomanya: “pemenang tidak pernah mau disejajarkan dengan pihak yang kalah”. Hasrat eksistensial pemulihan jati diri hanya dapat dicapai dengan kesungguhan dan kerja keras seluruh lapisan rakyat. Adolf Hitler, pemimpin dengan kharisma yang kuat, segera mengambil prakarsa. Terapi demi menegakkan (kembali) pride bangsa Jerman secara jitu diturunkan dari diagnosis yang berwawasan pendekatan budaya. Jerman lamat-lamat menggeliat dan melepaskan dari tekanan negara-negara pemenang Perang Dunia I. Hitler mendapat dukungan berkat kuatnya rasa keunggulan ras di dalam sanubari rakyat Jerman. Ras Aria, setidaknya dalam versi mereka, merupakan ras superior, sehingga tidak pada tempatnya mereka dinistakan ras-ras lain yang lebih rendah. Berkat kerja keras, Hitler dengan Nazismenya berhasil menyatukan rakyat Jerman. Setelah merasa mampu tidak saja berkata, tetapi juga merealisasikan kata-kata tersebut dalam tindakan, pada bulan September 1939 sang Fuhrer membuka babak baru dalam sejarah peradaban manusia, yakni berperang untuk keluar sebagai pemenang. Serangan kilat (blittzkrik) terhadap Polandia pada bulan September ini menjadi awal dari Perang Dunia II yang berlangsung selama kurang lebih enam tahun (sampai dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu, 15 Agustus 1945). Dalam situasi yang berbeda, apa yang dialami bangsa Jerman juga dihadapi bangsa Jepang. Meskipun tidak berstatus negara pecuncang dalam Perang Dunia I, sejumlah sikap yang dipertontonkan pihak Barat dalam praktik percaturan masyarakat internasional secara kasat mata merupakan penghinaan terhadap keberadaan Jepang sebagai satu bangsa. Jepang yang merasa kedudukannya setara dengan Barat dipaksa menyetujui perjanjian laut Washington tahun 1922 yang megatur kuota jumlah kapal Jepang. Mereka hanya diizinkan memiliki 3 buah kapal, sedangkan Amerika dan Inggris, masing-masing 5 buah kapal; Jepang dihambat oleh Amerika dan Inggris dalam perdagangan dunia, dan puncak diskriminasi itu: Jepang diharuskan ke luar dari seluruh wilayah yang menjadi urat nadi perekonomiannya. Adakah sebutan lain yang lebih cocok selain ‘penistaan eksistensial’ untuk semua perlakuan terhadap Jepang? Apa yang bisa mereka perbuat? Hikmah penting kesemena-menaan pihak Barat ini mengkristalkan harga diri Jepang sebagai sebuah bangsa. Dendam pun menemukan habitat yang subur untuk, pada saat yang tepat, berbicara dalam bahasa yang representatif untuk itu yakni bahasa senjata. Perang Pasifik Setelah pemerintah Jepang menerima memorandum pemerintah Amerika Serikat pada 2 Oktober 1941—tentang keharusan Jepang menarik seluruh pasukannya dari daratan Cina dan Vietnam di samping menghentikan dukungan dan hubungannya dengan rezim boneka Wang di Cina (Chiang, 1979: 202)—pihak Jepang menyadari bahwa perundingan yang selama ini dijalankan dengan Amerika tidak akan memberikan keuntungan apa pun bagi Jepang.1 Karena itu, satu-satunya pilihan guna mendukung gerakan Jepang untuk maju ke selatan adalah dengan jalan perang menghadapi Amerika Serikat dan sekutunya (Mayer, 1984: 43). Untuk merealisasikan rencana ini, pada 5 November 1941, armada Angkatan Laut Jepang dipusatkan secara rahasia di Teluk Sahaku, Kepulauan Kyushu (Toyama, 1974: 203). Tujuan 5 pemusatan ini tidak lain untuk bersama-sama bertolak ke jurusan timur dan menyerang Pangkalan Armada Angkatan Laut Amerika Serikat, Pearl Harbor, di Kepulauan Hawaii. Setelah semua kapalkapal perang ini terkumpul, pada 26 November 1941, iring-iringan Armada Angkatan Laut Jepang berangkat melaksanakan misi rahasia, yakni melakukan serangan pendadakan. Armada ini terdiri dari 353 pesawat terbang yang diparkir di atas 6 kapal induk, 11 kapal perusak, 8 kapal tangker, 3 kapal penjelajah, 3 kapal selam, dan 2 kapal tempur. Operasi direncanakan Laksamana Yamamoto Isoroku, pemimpin tertinggi seluruh Armada Angkatan Laut Jepang yang pernah belajar di Amerika Serikat ini (Fujimoto, 1975: 91), dipimpin oleh Laksamana Nagumo dan dibantu oleh Laksamana Kusaka, Kepala Staf Angkatan Laut Jepang. Pada 8 Desember waktu Jepang atau 7 Desember waktu Hawaii tahun 1941 (Showa 16), pukul 07.00 di hari Minggu yang cerah, Pearl Harbor dibombardir dari laut dan udara. Dalam serangan ini Jepang berhasil menghancurkan 16 kapal perang dan 300 pesawat terbang Amerika Serikat (Toyama, 1974: 207). Pembokongan terhadap Pearl Harbor ini menandai berawalnya Perang Pasifik, yang menjadi bagian dari Perang Dunia II. Dengan gerak cepat Jepang, berhasil menguasai dan menduduki daerah-daerah yang kaya akan minyak, dimulai dengan jatuhnya Malaya pada 9 Desember 1941, berturut-turut jatuh pula Singapura, Filipina, Indonesia (yang masih bernama Hindia Belanda) dan Hongkong. Hanya dalam jangka waktu 6 bulan, bendera Hino Maru berkibar dari Lashio di Birma sampai ke Kepulauan Wake di Pasifik Tengah. Pada awal perang, Jepang tampaknya berada dalam posisi yang ofensif. Tetapi, sejak pertengahan tahun 1942 situasi mulai berubah. Tepatnya ketika Jepang mengalami kekalahan dalam pertempuran laut di Midway, sejak 3 hingga 6 Juni 1942. Kedudukan menjadi berbalik dan sejak saat itu Jepang mulai berada dalam kondisi defensif. Kekalahan demi kekalahan dialami Jepang diikuti dengan gerakan maju Sekutu, di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, terus menapak dan akhirnya mencapai daratan Jepang. Penyebab kekalahan Jepang ini tidak lain karena seluruh industri dalam negeri Amerika, yang lebih baik keadaannya dibanding Jepang, dipusatkan pada pembuatan alat-alat yang berguna bagi keperluan perang. Di samping itu, faktor penentu lainnya adalah terdapatnya beda pendapat yang besar dan berlarut-larut dalam tubuh Angkatan Perang Jepang, antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut, dalam memutuskan masalah-masalah politik nasional sejak terjadinya insiden Jembatan Markopolo tanggal 7 Juli 1937 (Mayer, 1984: 39). Selama Perang Dunia II, strategi negara Sekutu adalah mengalahkan terlebih dahulu musuh yang berada di medan perang Eropa, setelah itu baru bersama-sama menghadapi Jepang di medan perang Pasifik (Eisenhower, 1948: 657). Strategi ini tepat, karena letak Jerman dan Italia berada di tengah lingkungan negara Sekutu di Eropa, sehingga kedua negara ini akan dengan mudah dikepung dan diserang dari segala arah. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, Amerika memperoleh kebebasan untuk tetap dalam prinsip yang dianutnya, yakni, selain turut aktif membantu sekutu di medan perang Eropa, juga terus menghadapi Jepang di medan perang Pasifik (Eisenhower, 1948: 55). Akibat menyerahnya Italia pada tahun 1943, psikologi peperangan di medan Eropa menyumbangkankan nilai tambah tersendiri bagi kekuatan Sekutu. Konstelasi ini menyebabkan posisi Jerman makin terpojok, dikepung dan diserang dari berbagai arah, sehingga kejatuhannya hanyalah tinggal soal waktu. Pihak Sekutu pun menuntaskan tugas tempur mereka, Jerman menyerah pada 7 Mei 1945. Berakhirnya perang di medan Eropa memungkinkan pengalihan seluruh potensi Sekutu untuk menghadapi Jepang di medan perang Pasifik. Ofensif besar-besaran di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur terbukti terlalu tangguh bagi Jepang. Bulan Juni 1945, tentara Sekutu mendarat di Pulau Okinawa. Kedudukan pulau ini sangat strategis bagi kedua belah pihak. Bagi Sekutu, tanpa bantuan kapal induk sekalipun, seluruh kota besar Jepang sudah berada dalam jangkauan pesawatpesawat pembom berat Sekutu yang berpangkalan di Okinawa.2 Bagi Jepang, jatuhnya Okinawa berarti ancaman serius yang memojokkan mereka ke ambang kekalahan. Ketika daratan Jepang dilanda suasana kalut akibat serangan udara dan laut Sekutu pada bulan Juli 1945, pemimpin negara-negara Sekutu mulai memperkirakan bahwa Perang Dunia II di medan perang Pasifik akan segera berakhir. Seumpama Jepang masih menyisakan jurus-jurus pamungkas untuk mengatasi gempuran Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur telah siap dengan rencana berikut: mendaratkan pasukannya di pulau-pulau utama Jepang pada bulan November 1945. Begitulah, para pengambil keputusan dari pihak Sekutu berembuk dan mempersiapkan paket kebijakan politik yang akan mereka berlakukan seusai perang, sebuah skenario pascakekalahan Jepang. Deklarasi Potsdam Di medan perang Eropa, kekalahan Jerman yang terjadi begitu cepat sama sekali di luar perkiraan Sekutu. Para pemimpin negara Sekutu dengan sendirinya perlu segera mengadakan pertemuan guna merundingkan langkah-langkah yang akan diberlakukan terhadap Jerman. Dengan cepat pula ditetapkan Potsdam menjadi lokasi perundingan, sebuah kota kecil di Berlin bagian timur, yang berlangsung 17 Juli hingga 2 Agustus 1945. Perundingan yang dihadiri oleh H. S. Truman (Presiden Amerika Serikat), W. L. Churchill (Perdana Menteri Inggris), dan I. V. Stalin (Perdana Menteri Uni Soviet). Ketika perundingan berlangsung, posisi W. L. Churchill digantikan oleh Atlee, yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru (Tadashi, 1983: 231). Agenda perundingan Postdam mencakup: cara dan besarnya hukuman yang akan dikenakan atas Jerman; kondisi negara-negara Timur Tengah; masalah Polandia, Afrika, Australia, Bulgaria, Hungaria, Rumania, Cekoslawakia, Turki dan Jepang. Energi terbesar dalam pembahasan selama 17 hari itu tersedot untuk pembahasan masalah Jerman. Keputusan prinsipiil kubu Sekutu adalah perlucutan senjata dan demiliterisasi Jerman secara total. Semua industri Jerman yang dapat dipakai untuk memproduksi keperluan perang, karena itu, harus dimusnahkan. Rakyat Jerman harus diyakinkan 6 bahwa, sebagai bangsa yang kalah perang, tak dapat menghindari tanggung jawab. Mereka harus sadar bahwa risiko kehancuran ekonomi dan sanksi perlucutan senjata adalah akibat dari perang yang dikibarkan NAZI.3 Oleh karena itu, semua yang berbau NAZI harus dilenyapkan. Agar bibit-bibit militerisme tidak bertunas lagi, program pendidikan rakyat Jerman harus diawasi dengan ketat. Demokrasi harus disebarluaskan (Greenville, 1974: 236). Dalam hal Jepang, pemimpin negara-negara Sekutu dalam forum ini mempunyai kesamaan pandangan. Mereka sependapat, negara-negara Sekutu yang terlibat langsung dalam perang melawan Jepanglah sebagai pihak yang mempermaklumkan deklarasi. Bagaimanapun juga, Sekutu berkepentingan memperkecil jumlah korban jiwa dari medan peperangan ketika kekalahan Jepang semakin nyata. Lantaran Uni Soviet masih terikat dalam Perjanjian Netralitas 4 dengan Jepang, tentu tidak etis Stalin ikut membubuhkan tanda tangan dalam deklarasi itu. Posisinya digantikan oleh Chiang Kai Shek dari Cina, yang merupakan seteru abadi Jepang. setuju dan Deklarasi Potsdam—yang ditandatangani oleh ketiga pemimpin pemerintahan negara Sekutu: Amerika Serikat, Cina dan Inggris—diumumkan pada 26 Juli 1945. Teks lengkap Deklarasi Potsdam berbunyi sebagai berikut: 1. Kami Presiden Amerika Serikat, Presiden Pemerintahan Nasional Republik Cina, Perdana Menteri Inggris Raya, yang mewakili ratusan juta rakyat kami, telah berunding dan sepakat agar Jepang diberi kesempatan untuk mengakhiri peperangan ini. 2. Angkatan Darat, Laut dan Udara yang luar biasa dari Amerika Serikat, Inggris Raya dan Cina, yang diperkuat berlipat ganda oleh tentara dan Armada Udara dari Barat, telah dipersiapkan untuk memberikan pukulan terakhir terhadap Jepang. Kekuatan militer ini ditopang dan disemangati oleh keinginan semua negara Sekutu untuk meneruskan perang melawan Jepang sampai Jepang berhenti melawan. 3. Akibat dari perlawanan Jerman yang sia-sia dan tanpa perasaan terhadap kekuatan rakyat dunia yang merdeka merupakan contoh yang mengerikan bagi rakyat Jepang. Kekuatan yang kini tertuju pada Jepang adalah lebih besar daripada yang dihadapi oleh NAZI, yang telah menyebabkan kehancuran tanah-tanah, industri dan seluruh rakyat Jerman. Penggunaan penuh kekuatan militer kami, dengan dukungan resolusi kami, akan berarti kehancuran total bagi Angkatan Bersenjata Jepang dan juga tidak dapat dihindarkan kehancuran total bagi tanah air Jepang. 4. Waktunya telah tiba bagi Jepang untuk memutuskan apakah Jepang akan terus dikendalikan oleh penasihat-penasihat militer yang berkeinginan sendiri, yang dengan perhitungan-perhitungan bodohnya telah menyebabkan Kerajaan Jepang di ambang kehancurannya, ataukah Jepang akan mengikuti jalan yang dapat diterima oleh akal sehat. 5. Berikut adalah syarat-syarat kami. Kami tidak akan menyimpang darinya. Tidak ada alternatif-alternatif. Kami tidak akan mengulur waktu. 6. Karena kita berkehendak menciptakan suatu orde kedamaian, keamanan dan keadilan yang baru, kekuasaan dan pengaruh dari pihak-pihak yang telah membohongi dan menunjukkan rakyat Jepang ke jalan yang salah dalam usaha menguasai dunia harus dihilangkan dan disingkirkan untuk selama-lamanya. Hal ini akan mustahil terwujud bila militerisme yang tidak bertanggung jawab belum dienyahkan dari muka bumi. 7. Bila orde tersebut telah tercipta dan bila bukti-bukti bahwa kekuatan peperangan Jepang telah dilenyapkan, maka tempat-tempat baru dalam kewilayahan Jepang akan ditentukan oleh Sekutu, dan akan diduduki untuk mengamankan tujuan dasar dari deklarasi ini. 8. Syarat-syarat Deklarasi Kairo akan dilaksanakan, dan kedaulatan Jepang akan terbatas sampai pada pulau-pulau Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku dan pulau-pulau kecil lainnya yang akan kami tentukan. 9. Kekuatan militer Jepang, bila telah sama sekali tanpa senjata, akan diizinkan untuk kembali ke tanah airnya dengan kesempatan untuk menuju pada kehidupan yang damai dan produktif. 10. Kami tidak bermaksud memperbudak ataupun menghancurkan Jepang sebagai suatu negara, tetapi keadilan yang kuat akan ditunjukkan kepada semua penjahat perang, termasuk mereka yang telah melaksanakan kekejaman terhadap tawanan-tawanan pihak kami. Pemerintah Jepang harus menyingkirkan semua halangan bagi pembangunan dan penguatan demokrasi di antara rakyat Jepang, kebebasan berbicara, agama, pemikiran, dan rasa hormat terhadap hak-hak asasi manusia harus diciptakan. 11. Jepang akan diizinkan mendirikan industri-industri yang dapat membantu ekonominya, dan diizinkan untuk memperbaikinya, tetapi tidak untuk industri yang memungkinkan Jepang dapat bersenjata lagi bagi peperangan yang akan datang. Jalur-jalur dan pengendalian bahan baku juga akan diizinkan. Pada akhirnya, partisipasi Jepang dalam perdagangan dunia internasional juga akan diizinkan. 12. Kekuatan-kekuatan pendudukan Sekutu akan ditarik dari Jepang segera setelah hal-hal di atas tercapai, serta bila pemerintahan yang damai dan bertanggung jawab menurut kehendak bebas rakyat Jepang telah terbentuk. 13. Kami berseru kepada pemerintah Jepang agar memproklamirkan penyerahan tanpa syarat dari semua Angkatan Perang Jepang, dan memberikan jaminan yang cukup dan benar dalam pelaksanaannya. Pilihan lain bagi Jepang adalah kehancuran total dan cepat (Mosley, 1966: 352-353). 7 Sehari kemudian, 27 Juli 1945, isi Deklarasi Potsdam ini sudah diketahui oleh pemerintah Jepang. Kabinet Suzuki Kantaro segera mengadakan pertemuan guna membahasnya. Di samping itu, diminta juga jasa baik Uni Soviet untuk menjadi perantara dalam mencari jalan damai (Kazutoshi, 1968: 14). Setelah melalui perdebatan yang sengit—antara kelompok yang setuju menerima isi Deklarasi di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Togo Shigenori, dan kelompok yang menolak di bawah pimpinan Menteri Peperangan Jenderal Anami Korechika—Kabinet menyepakati langkah atas jalan keluar versi pihak Sekutu. Sikap yang diambil pemerintah Jepang, bertolak belakang dengan harapan Sekutu, justru menjalankan politik Mokusatsu atau membunuh secara diam-diam isi Deklarasi Postdam. "Kita akan terus melanjutkan perang," demikian Suzuki Kantaro mengumumkannya (Toyama, 1974: 237). Reaksi Jepang itu menegaskan posisi perlawanannya. Para penandatangan Deklarasi Potsdam mafhum bahwa pemerintah Jepang telah menolak mentah-mentah tawaran penyelesaian damai. Mau tak mau, Sekutu melaksanakan amanat Deklarasi yang mungkin dianggap Jepang gertak sambal. Pada 6 Agustus 1945, pemerintah Jepang merasakan apa yang dimaksud dengan “kehancuran total dan cepat” dalam butir ke-13 Deklarasi Potsdam. Hiroshima dibumihanguskan dengan sebuah bom atom yang pertama kali terjadi dalam sejarah peradaban manusia, yang dalam sekejap menewaskan 100.000 penduduk Hiroshima (Toyama, 1974: 238). Berselang 3 hari, pada 9 Agustus 1945, Kota Nagasaki mengalami nasib yang serupa. Menunggangi kejadian ini, Uni Soviet yang masih terikat perjanjian damai dengan Jepang mengumumkan perang pada tanggal 8 Agustus 1945. Tentara Merah dengan cepat melintasi tapal batas Manchuria. Mereka hanya memerlukan waktu dua jam untuk menggasak tentara Kwantung yang terkenal itu hingga tidak berdaya (Kazutoshi, 1968: 22). Dihadapkan pada situasi pelik seperti ini, terlebih mengingat kentalnya polarisasi dua kelompok dalam menyikapi Deklarasi Potsdam, Kaisar memutuskan menerima Deklarasi Potsdam. Langkah ini diambil dalam Konferensi Kekaisaran yang berlangsung pada 14 Agustus 1945 (Ienaga, 1978: 231). 5 Keesokan harinya, 15 Agustus 1945, berkumandanglah rekaman suara Kaisar pada seluruh rakyat Jepang. Isinya adalah pernyataan pemerintahan Jepang untuk mengakhiri peperangan dan menyerah pada Sekutu sesuai dengan isi Deklarasi Potsdam. Jepang telah menyerah, meski belum seorang pun prajurit Sekutu yang menginjakkan kakinya di Tokyo. Imbauan Kerajaan untuk menyerah ini tidak begitu saja ditaati oleh rakyat Jepang. Beberapa anggota dari Kesatuan Udara Angkatan Laut yang berkedudukan di Pangkalan Udara Atsugi dekat Tokyo bersikeras meneruskan perang sampai titik darah penghabisan. Segelintir personel Angkatan Darat membunuh Komandan Divisi Pengawal Kerajaan, dan mencoba mencegah penyiaran pidato Kaisar. Meski terjadi penyangkalan di sana-sini, pada hakikatnya mayoritas rakyat Jepang menerima kekalahan. Lebih-lebih pengumuman untuk menyerah ini langsung keluar dari mulut Kaisar yang sangat mereka hormati. Rakyat Jepang sebenarnya mau meneruskan perang demi Kaisar mereka, tapi Kaisar sendiri memutuskan menyerah dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang digariskan Sekutu, hingga rakyat mematuhi perintah Kaisar. Faktor kejiwaan inilah yang memudahkan rakyat Jepang untuk menerima kenyataan kalah perang dengan tenang (Eto, 1974: 8). Penandatanganan Dokumen Penyerahan Sebagai tindak lanjut dari keputusan pemerintah Jepang menerima semua syarat Deklarasi Potsdam dan menyerah pada Sekutu, pada tanggal 2 September 1945, di atas geladak kapal Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, dilakukan upacara penyerahan militer secara resmi kepada negaranegara yang tergabung dalam blok Sekutu. Di samping Jenderal Douglas MacArthur sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu atas Jepang, ikut menandatangani dokumen penyerahan ini C. W. Nimitz (wakil Amerika Serikat); Hsu Yung Ch'ang (Cina); Bruce Fraser (Inggris); K. Derevyanko (Uni Soviet); T. A. Blamey (Australia); L. Moore Cosgrave (Kanada); Leclerc (Perancis); C. E. L. Helfrich (Belanda); dan L. M. Isitt (Selandia Baru), sedangkan pihak Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu dan Jenderal Umezu Yoshijiro (Collier, 1946: 272). Dokumen penyerahan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 2 September 1945 itu berbunyi sebagai berikut: 1. Kami, yang bertindak atas perintah dan atas nama Kaisar Jepang, Pemerintah Jepang dan Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang, dengan ini menerima syarat-syarat yang ditentukan dalam deklarasi yang dikeluarkan oleh pemimpin pemerintahan Amerika Serikat, Cina dan Inggris Raya pada tanggal 26 Juli 1945 di Potsdam, dan seterusnya didukung oleh Republik Sosialis Uni Soviet, yang mana keempat kekuatan tersebut di sini seterusnya disebut sebagai Kekuatan Sekutu. 2. Kami dengan ini menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Kekuatan Sekutu dari Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang, seluruh tentara Jepang, dan seluruh tentara di bawah kekuasaan Jepang di mana pun berada. 3. Kami dengan ini memerintahkan semua jajaran Angkatan Bersenjata di mana pun berada, semua rakyat Jepang, untuk menghentikan permusuhan ini demi memelihara dan menyelamatkan semua kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang, benda-benda militer dan sipil dari kerusakan; menaati semua persyaratan yang ditentukan oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, ataupun oleh badan-badan pemerintah Jepang yang ditunjuknya. 4. Kami dengan ini memerintahkan Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang untuk mengeluarkan perintah-perintah kepada semua pemimpin Angkatan Bersenjata Jepang, dan semua Angkatan Bersenjata di bawah kekuasaan Jepang di mana pun berada, untuk menyerahkan diri tanpa syarat beserta semua kekuatan yang ada di bawah kekuasaannya. 5. Kami dengan ini memerintahkan semua pejabat sipil, militer dan Angkatan Laut untuk mematuhi dan melaksanakan semua pernyataan, perintah dan petunjuk yang dikeluarkan oleh 8 Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, lembaga yang ditunjuk atau berada di bawah wewenangnya guna penyerahan ini dapat terlaksana dengan baik, dan kami memerintahkan semua pejabat tersebut untuk tetap dalam jabatannya, dan meneruskan semua tugas-tugas nonperang, kecuali bila secara pasti dibebastugaskan oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, atau oleh lembaga yang berada di bawah wewenangnya. 6. Kami dengan ini mengambil langkah demi Kaisar, Pemerintah Jepang dan penerusnya untuk menjalankan semua persyaratan Deklarasi Potsdam dengan rela, dan akan mengeluarkan perintah atau mengambil tindakan apa pun yang mungkin diperlukan oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, ataupun oleh wakil-wakil lain yang ditentukan oleh Kekuatan Sekutu, demi terlaksananya tujuan Deklarasi Potsdam ini. 7. Kami dengan ini memerintahkan Pemerintah Kekaisaran Jepang dan Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang untuk segera membebaskan semua tawanan perang Sekutu dan anggotaanggota sipil yang kini berada di bawah kekuasaan Jepang, dan menyediakan perlindungan, perawatan, pemeliharaan dan pemindahan segera ke tempat yang ditentukan. 8. Kekuasaan Kaisar dan Pemerintah Jepang untuk memerintah negara akan ditentukan oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, yang akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan syarat-syarat penyerahan ini. Ditandatangani di Teluk Tokyo, Jepang pada pukul 09.04. I pada tanggal dua bulan September, 1945. Mamoru Shigemitsu Atas perintah dan atas nama Kaisar Jepang dan Pemerintah Jepang Umezu Yoshijiro Atas perintah dan atas nama Markas Besar Tentara Kerajaan Jepang Diterima di Teluk Tokyo, Jepang pada jam 09.08. I pada tanggal dua bulan September, 1945. Untuk Amerika Serikat, Republik Cina, Kerajaan Inggris, Republik Sosialis Uni Soviet, dan untuk kepentingan negara-negara lain dalam Perserikatan Bangsa-bangsa yang berperang dengan Jepang. Douglas MacArthur Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu C. W. Nimitz Wakil Amerika Serikat Hsu Yung Ch'ang Wakil Cina Bruce Fraser Wakil Inggris K. Derevyanko Wakil Uni Soviet T. A. Blamey Wakil Australia L. Moore Cosgrave Wakil Kanada Leclerc Wakil Perancis C. E. L. Helfrich Wakil Belanda L. M. Isitt Wakil Selandia Baru Dengan ditandatanganinya Dokumen Penyerahan ini, Jepang memasuki masa pendudukan Sekutu yang berlangsung hingga 28 April 1952, bertepatan dengan efektif dan absahnya masa pemberlakukan hasil Perjanjian Perdamaian San Fransisco yang ditandatangani pada 8 September 1951. Masa Pendudukan Sekutu 9 Masa-masa pahit yang dialami bangsa Jerman karena kehancuran rezim NAZI pada tahun 1945 juga dialami bangsa Jepang. Dengan penyerahan tanpa syarat militer dan pengambilalihan kekuasaan tertinggi negara oleh Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, Jepang tidak lagi menjadi bangsa yang berpengaruh terhadap bangsa-bangsa di sekelilingnya, ia bahkan kehilangan hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan dikebiri untuk menjalankan kedaulatan dalam negeri ataupun luar negeri. Sejak 2 September 1945 hingga berlakunya perjanjian damai San Fransisco pada 28 April 1952, Jepang praktis kehilangan eksistensinya sebagai subyek dalam percaturan politik internasional. Negara-negara Sekutulah yang selanjutnya mendiktekan, pabila dan sejauh mana Jepang diizinkan ikut campur tangan dalam menentukan nasib sendiri ataupun untuk menjalin kerjasama-kerjasama yang berskala antarbangsa. Dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur ditugasi menjalankan kebijakan negara-negara Sekutu yang akan diberlakukan atas Jepang. Secara teoretis, semua kebijakan MacArthur atas nama negara-negara Sekutu. Dalam praktek, apa yang diterapkan atas Jepang tak lain dari pelaksanaan kehendak pemerintah Amerika, yang dirumuskan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Peperangan, Kementerian Angkatan Laut, dan lembagalembaga lain sebelum berakhirnya perang (Quigley dan Turner, 1956: 91). Langkah awal Jenderal MacArthur adalah melucuti Jepang. Alasannya, trauma bangsa-bangsa di sekelilingnya yang mem-fait accompli Jepang sebagai ancaman yang sangat membahayakan. Jadi, demi mempertahankan keamanan dan perdamaian dunia, Jepang harus dilumpuhkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak berdaya untuk memulai agresi baru. Pihak Sekutu menganggap Jepang sebagai pemicu Perang Pasifik (butir 4 Deklarasi Potsdam), karenanya setiap potensi sumber kekuatan Jepang perlu dilumpuhkan. Dengan kebijakan ini, MacArthur menumpas elemen perlawanan Jepang terhadap Sekutu. Langkah berikutnya, mengadili mereka yang dianggap terlibat dalam politik agresi; pembubaran Zaibatsu; pemisahan Shinto dari negara; reformasi pendidikan; reformasi pertanian dan sebagainya. Kebijakan ini pun praktis merealisasikan sebuah pernyatan Presiden H. S. Truman, "Langkah apa pun yang akan dijalankan terhadap Jepang harus didasari oleh dua prinsip, yakni adanya jaminan bahwa Jepang tidak akan lagi menjadi ancaman bagi Amerika, atau perdamaian dan keamanan dunia, serta terbentuknya pemerintahan yang damai dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis" (Quigley dan Turner, 1956: 93). Amerika masih melihat sebuah sumber kekuatan Jepang paling fundamental yang mesti dibasmi. Sumber yang dimaksud tidak lain dari Konstitusi Meiji, dengan lembaga Kaisar sebagai intinya. Sekutu tak puas dengan hanya Jepang yang tidak kuat, mereka berhasrat mengubah Jepang menjadi sama sekali berbeda dengan Jepang yang mereka hadapi dalam Perang Pasifik. Dengan pijak yuridis penyerahan tanpa syarat Deklarasi Potsdam dan klausul Dokumen Penyerahan, Jenderal MacArthur merasa mantap melaksanakan misi penggusuran konstitusi Jepang. Konstitusi Meiji yang ditengarai sebagai sumber kekuatan Jepang sebagai satu bangsa dengan konstitusi yang sama sekali baru. MacArthur mengawali dengan menisbikan predikat suci Kaisar dalam pandangan rakyat Jepang. Gagasan tersebut cukup jitu, meski sungguh tidak mudah mewujudkannya di alam nyata. Pada 8 September 1945, Jenderal Courtney Whitney menyarankan Jenderal Douglas MacArthur memanggil Kaisar ke Markas Besar Pasukan Pendudukan Sekutu, lalu memberinya perintah-perintah untuk dilaksanakan. Ide stafnya ini pada hemat MacArthur hanya akan membuat rakyat Jepang merasa terhina, karena dalam pandangan mereka Kaisar itu suci. MacArthur cukup yakin dengan kiat dan siasatnya, "Kita akan menunggu biar Kaisar sendiri yang akan datang pada kita" (Mosley, 1966: 337). Apa yang kemudian terjadi? Di Istana, Kaisar mendengar berita bahwa beberapa menteri dan pegawai Istana dituduh sebagai penjahat perang. Dia terpanggil untuk menghadap secara langsung kepada Jenderal Douglas MacArthur di Markas Besar Pasukan Pendudukan Sekutu. Pada kesempatan itu Kaisar menyatakan bahwa dialah yang sepenuhnya bertanggung jawab. Pertemuan tanggal 27 September 1945 itu menjadi amat krusial karena Kaisar menyerahkan diri kepada kebijakan yang akan diambil oleh Jenderal Douglas MacArthur (Mosley, 1966: 341). Keesokan harinya, 28 September 1945, rakyat Jepang melihat di halaman muka surat kabar mereka sendiri gambar Kaisar yang berdiri dalam sikap formal di samping Jenderal Douglas MacArthur yang berkacak pinggang, tanpa dasi, tanpa uniform. Jiwa mereka terpukul (Eto, 1974: 10). Fakta ini sedemikian mengguncangkan sendi-sendi harga diri yang dianut massa rakyat. Di dalam sanubari rakyat Jepang diam-diam timbul pertanyaan, apa makna kesetiaan yang selama ini kami tegakkan? Apa arti kepercayaan yang kami pelihara secara turun-temurun? Masihkah Kaisar merupakan simbol suci dan sekaligus pilar utama keberadaan bangsa Jepang? Rekayasa MacArthur sukses. Pertanyaan dan gugatan seperti inilah yang ia rangsang tumbuh di kalangan rakyat Jepang. MacArthur coba menunjukkan bahwa Kaisar mereka adalah seorang manusia biasa, seperti mereka juga. Namun, yang lebih penting bagi MacArthur adalah Kaisar bersedia melakukan perubahanperubahan terhadap Konstitusi Meiji. Kesimpulan Sebagaimana Jerman, keterlibatan Jepang dalam PD II dipicu faktor hutang dan penghinaan oleh negara-negara lain. Jika Jerman memikul hutang dan penghinaan dari sesama ras putih akibat kalah dalam satu pertarungan terhormat, yakni Perang Dunia II; Jepang dihina akibat diskriminasi rasial hampir sepanjang panjang peradaban. Sejarah memposisikan ras kuning Asia sebagai centeng ras putih Eropa dan Amerika yang duduk sebagai raja. Keinginan ras kuning Asia untuk naik “kasta” dianggap berlebihan. Legenda bahwa masyarakat Jepang berasal dari keturunan Ameterasu Omikami (Dewa Matahari) malah dijadikan bahan olok-olok. Legenda ini dimitoskan, mitos ini disosialisasikan secara luas melalui slogan-slogan. “Kami adalah anak-anak tuhan. Negara-negara di sekitar kami adalah saudara-saudara muda kami. Mereka pun, kalau tidak anak Tuhan, masih saudara dekat atau 10 saudara jauh dari anak-anak Tuhan.” Sayangnya, perilaku tentara Kekaisaran Jepang Raya selama PD II melenceng jauh dari bahkan mengkhianati ‘mandat’ mereka sebagai anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara mudanya bersikap tidak peduli ketika Jepang diperlakukan secara hina oleh Sekutu, khususnya Amerika. Berhasilkan pendudukan Amerika Serikat atas Jepang selama kurun waktu 2 September 1945 sampai dengan 28 April 1952? Tolok ukur untuk itu adalah seberapa mampu Amerika menciptakan situasi damai di Jepang. Dari sekian banyak masalah yang dihadapi Sekutu (baca: Amerika Serikat), agaknya masalah penyusunan Undang-undang Dasar Baru Jepang 1946-lah yang merupakan tugas terberat. Sebagai Pemimpin Tertinggi Pasukan Pendudukan Sekutu atas Jepang, Jenderal Douglas MacArthur harus mempertimbangkan berbagai segi dengan ekstra hati-hati. Khususnya menyangkut kebijakan yang berhubungan langsung dengan eksistensi Kaisar. Dari rekan satu blok (Sekutu), Rusia menuntut Kaisar diadili di pengadilan militer, kalau perlu divonis hukuman mati. Tuntutan ini jelas sangat ekstrem. Dalam kalkulasi strategis Amerika, Jepang justru perlu dirangkul sebagai mitra, yang kelak dapat berfungsi sebagai dinding kokoh dalam membendung laju faham komunis yang makin berkembang di Asia Timur. Pembahasan pada Bab II akan dimulai dengan uraian tentang latar belakang pemikiran untuk mengubah UUD Meiji dengan suatu UUD yang baru, lalu bagaimana proses perubahan itu terjadi dan, pada akhirnya, bagaimana bentuk Undang-undang Dasar Jepang yang baru tersebut. Dengan demikian, diktum hukum besi sejarah yang telah dibahas dalam Bab I bisa lebih dipahami.© Bab IV Jepang dan Negara Dunia Ketiga: Cara Baru, Gaya Lama Pengantar Lingkaran pengaruh yang menorehkan hegemoni Jepang atas kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara bukanlah kisah 20, 30 atau 40 tahun terakhir. Sejak abad ke-19, plot kedua wilayah ini sedemikian sentral dalam strategi kebijakan politik luar negeri Tokyo. Makna geostrategis wilayah ini sangat penting dalam bingkai keamanan nasional Jepang; setara dengan Amerika Tengah atau Karibia bagi Amerika Serikat atau Eropa Timur bagi Masyarakat Ekonomi Eropa. Didukung kinerja ekonomi dan militernya, Jepang mengambil alih peran klasik Barat sebagai negeri imperialis-kolonialis. Langkah Jepang menganeksasi Kepulauan Ryukyu bahkan berlanjut dengan ekspansi ke Taiwan dan Korea. Secara beriringan, dengan pilar-pilar perusahaan multinasional raksasa, yakni zaibatsu,31 mesin ekonomi Jepang membanjiri negara-negara kawasan dengan beragam produk. Slogan "Asia untuk Asia" sebagai “kawasan bersama” Asia Timur gencar dikumandangkan pada tahun 1930-an. Skenario besar di balik slogan itu adalah menjadikan wilayah ini; baik dalam arti politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual; berkiblat ke Tokyo. Sejarah membuktikan, cita-cita menancapkan hegemoni regional ini tidak pernah mati meski mereka kalah perang. Sejak tahun 1945, dengan bantuan Amerika Serikat, Jepang berhasil memperbarui cara lama dan menciptakan pasar baru di kawasan ini. Apa rahasianya? Jawabannya tak lain dari: penerapan strategi yang jitu. Sejak awal 1970-an, rambahan itu tertuju pada pemusatan orientasi ke kawasan ini. Mereka memposisikan diri menjadi rekanan dagang, sumber modal, dan pemasok dana bantuan luar negeri terpenting bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Hampir tak ada dana dialokasikan ke kawasan-kawasan lain. Mereka menggelongtor wilayah ini dengan model total football yang pernah diperagakan kesebelasan Belanda. Kondisi ini by nature dan by design menciptakan pola dominasi dan subordinasi. Jepang naik kelas menjadi ‘godfather’ sedangkan negara-negara kawasan menjadi sangat (dan makin) tergantung secara ekonomi. Skala perdagangan dan investasi antara keduanya secara permanen tidak pernah setara. Ekspor Jepang ke kawasan ini terutama berupa teknologi tinggi, modal, dan barang-barang jadi; sedangkan Jepang hanya mengimpor barang-barang setengah jadi—selanjutnya diproduksi oleh industri kecil dan menengah yang bersifat padat karya. Pabrik-pabrik atau industri tersebut nota bene perusahaan berbendera Jepang. Kecuali dengan negara yang kaya sumber alam seperti Indonesia, Brunei dan Malaysia, perdagangan Jepang dengan negara-negara di kawasan Asia Timur selalu surplus. Dominasi ekonomi ini membuahkan nilai tambah politik bagi Tokyo. Jepang 11 memperoleh hak ekonomi khusus yang lebih besar dari pemerintahan negara-negara kawasan, dan itu berarti pelestarian pola ketergantungan secara ekonomi dan politik. Sehingga, tidaklah berlebihan bila para ilmuwan dan pengamat politik menyebut bahwa Jepang berhasil mencapai "Kawasan Kerjasama Kemakmuran Asia Timur" (East Asian Co-prosperity Sphere) melalui kebijakan perniagaan baru (neo-merkantilisme), sesuatu yang gagal mereka capai melalui praktik imperialis dengan cara militer pada masa PD II.32 Strategi Tokyo memantapkan hubungan ekonomi yang asimetris ini menjadi pilar penyangga penting bagi kebijakan Keamanan Terpadu Jepang untuk menganekaragamkan kebutuhannya terhadap minyak, energi, gas bumi, bahan baku, dan pasaran bagi produksi industrinya. Sehubungan dengan ini Jepang menuai kritik pedas, tidak saja dari kubu ASEAN, negara-negara industrialis baru (NIC’s), tetapi juga dari Cina. Kesemuanya menggugat asimetri hubungan ekonomi dengan Jepang. Namun, ketergantungan terhadap barang-barang, jasa, dan modal Jepang telanjur mendalam dan akut. Ujung-ujungnya, pada status posisi tawar yang begitu rendah, ikhtiar mereka menegosiasikan konsesi-konsesi yang dapat memperbaiki keadaan yang tidak saling menguntungkan ini manjadi sesuatu yang musykil. Keadaan yang Sesungguhnya Angka-angka statistik berikut berbicara sendiri tentang kedudukan Jepang sebagai mitra dagang dengan tingkat ketergantungan yang besar bagi Asia Timur. Benar bahwa impor Jepang negara-negara ASEAN pada 1988 sebesar $23,369 miliar, atau sedikit melampaui nilai ekspornya yang $23,027 miliar; tetapi data statistik ini tak mengubah konstelasi antara keduanya. Kecuali dengan Indonesia, Jepang menangguk surplus perdagangan yang sangat besar dengan Muangthai, Singapura, dan Filipina. Diurut dari negara dengan derajat ketergantungan paling rendah, posisi itu secara berturut-turut ditempati Singapura (15,6%); diikuti oleh Malaysia (22,1%); Muangthai dan Filipina (24,6%); Brunei Darussalam (37%), dan Indonesia yang tertinggi (38,4%). Sebaliknya, ketergantungan Jepang terhadap negara-negara ASEAN sedemikian kecil, yakni Indonesia (2,7%); Malaysia (1,8%); Muangthai (1,7%); Filipina (0,83%);Brunei Darussalam (0,26%); dan Singapura (0,25%). Dalam neraca perdagangannya dengan negara-negara industri baru (NIC’s) di Asia Timur; Jepang secara tetap mengalami surplus besar. Pada 1988, Jepang menikmati surplus sebesar $3,615 miliar atas Korea Selatan dengan Korea Selatan, dengan Taiwan sebesar $S8,739 miliar, dan dengan Hongkong sebesar $9,587 miliar. Neraca perdagangan Jepang dengan NIC’s juga tak seimbang. Nilai total perdagangan Korea Selatan dan Jepang adalah 24,2% berbanding 0,60%; Taiwan-Jepang (20,9% : 0,51%); Hongkong-Jepang (10,8% : 0,71%). Kondisi ini diperkuat dengan kemampuan Jepang membuat jaringan guna mengatasi kendala impor nontarif yang dimaksudkan mencegah terciptanya pembagian pasar untuk persaingan barang-barang impor. Pada waktu yang bersamaan—dengan nilai yen yang masih di bawah nilai won Korea, won Taiwan, dan dolar Hongkong—Jepang memangkas keuntungan yang hendak dicapai ketiga negara NIC’s ini. Kebijakan Seoul dan Taipei berinvestasi pada industri berat dan teknologi tinggi ataupun Hongkong dalam industri yang padat karya, pada akhirnya, menngawetkan ketergantungan mereka terhadap impor perangkat modal Jepang. Hubungan dagang Jepang dengan Cina dan Vietnam secara statistik bisa dikatakan sangat berbeda. Pada tahun 1988, hampir tiga dekade sesudah Cina berjuang keras mengubah posisi surplus berlebihan yang dinikmati Jepang, impor Jepang dari Cina mencapai $9,861 miliar, sedikit di atas ekspor Jepang ke Cina, senilai $9,347 miliar. Keseimbangan ini bisa terwujud berkat dua upaya yang berjalan serentak, yakni protes yang terus-menerus dan kecerdasan Beijing menerapkan formula kebijakan ekonomi yang baik, di samping revaluasi nilai yen. Terhadap Vietnam, ekspor Jepang tetap bernilai $194 miliar, senilai dua kali lebih besar dari impor Jepang yang besarnya $96 miliar. Walaupun begitu, hubungan dagang Jepang dengan Cina dan Vietnam tak beranjak dari pola neokolonial klasik. Sebagaimana telah disebut di atas, kawasan Asia Timur tetap merupakan prioritas investasi Jepang. Aliran investasi Jepang ke kawasan ini secara tetap adalah meningkat, meskipun tidak sekuat arus modal Jepang ke negara-negara industri maju. Konsekuensi logisnya, kawasan ini dengan sangat cepat bergantung pada besarnya nilai modal yang dikucurkan Jepang. Kecuali di Filipina, para investor Jepang saat ini menikmati bagian terbesar dari modal yang mereka investasikan pada seluruh negara-negara di kawasan Asia Timur. Masuknya modal Jepang ke kawasan ini berlangsung dalam tiga gelombang dengan volume yang makin lama makin besar. Gelombang modal pertama terjadi pada tahun 1960-an, yang umumnya ditanamkan pada industri padat karya, seperti industri tekstil dan alat-alat elektronika. Sampai tahun 1966, total investasi perusahaan Jepang di ASEAN sebesar $166 juta, tidak sampai seperempat investasi Amerika. Gelombang modal kedua, pada awal 1970-an, diprioritaskan untuk industri kimia, baja dan industri pengolahan sumber daya alam; dengan berbagai ekses terhadap lingkungan. Sampai tahun 1976, Jepang menginvestasikan 75% atau sebesar $4 miliar, atau lebih dari sepertiga investasi Amerika di kawasan yang sama.33 Pertengahan 1980-an, lembaga-lembaga ekonomi seperti bank dan asuransi merupakan sasaran utama gelombang modal ketiga modal Jepang. Pada 1985, 1986, dan 1987 Jepang mengguyurkan dana sebesar $1,43 miliar, $2,32 miliar, dan $4,86 miliar; di sisi lain, porsi Amerika adalah $55 juta, $405 juta, dan $2,2 miliar. Pada tahun 1988, total modal asing Jepang berjumlah $5,5 miliar. 34 Sejak 1951 hingga 1988, Kementerian Perdagangan Jepang memperkirakan angka kumulatif investasi Jepang di Asia Timur berjumlah $30 miliar, atau sekitar 21% dari total investasi asing mereka. Angka ini akan membengkak jika digabung dengan data penanaman modal ulang (reinvestasi) Jepang yang berjumlah sekitar setengah total investasi mereka di kawasan ini.35 Menguatnya nilai tukar yen terhadap dolar (dari 250 yen untuk US $1 pada 1985 menjadi 150 yen pada tahun 1986) tampaknya merupakan alasan utama gelombang ketiga modal Jepang. Ketersediaan tenaga kerja murah, sumber alam yang mudah dan murah dan berbagai kemudahan dari negara-negara tujuan menjadikan wilayah ini amat menarik. Dengan gerak cepat, perusahaan Jepang berskala kecil, menengah ataupun besar membanjiri kawasan ini. Di sisi lain, meningkatnya permintaan Asia Timur terhadap produk-produk Jepang makin memacu gairah mereka menggarap kawasan ini. Sekadar contoh, perusahaan Sony mampu menjual 8% produknya 12 ke negara-negara ASEAN, dengan proyeksi peningkatan 10 hingga 20% dalam dasawarsa 1990-an. Jumlah ekspor Jepang ke negara-negara ASEAN bahkan lebih besar dibanding ekspor Jepang ke negara-negara industri maju.36 Dinamika intern di dalam kawasan memaksa Tokyo meggeser dan menyesuaikan gerakan arus modalnya. Meningkatnya komponen upah tenaga kerja dan penerapan berbagai hambatan oleh Korea dan Taiwan berakibat biaya produksi tak lagi kompetitif. Karenanya, kedua negeri yang melejit masuk ke dalam kelompok negaranegara industri baru (NIC’s) itu tak lagi menjadi sasaran investasi yang menarik. Jepang pun berpaling ke negaranegara pengekspor baru (NEC’s), yang upah tenaga kerjanya murah tapi memiliki infrastruktur dan pasaran lokal yang setara dengan NIC’s. Jepang menggunakan pola penempatan modal yang berbeda di sasaran ini pola berbeda. Dalam dua tahun beruntun, dari 1986 ke 1987, investasi Jepang di Malaysia melonjak sekitar 297%; di Muangthai (63%); di Indonesia (60%), dan di Filipina (31%). 37 Sepanjang kurun waktu 1980-an, Muangthai merupakan primadona. Pada 1986, investasi 35 perusahaan Jepang berjumlah $124 miliar. Setahun kemudian, jumlah itu meningkat dua kali lipat, yakni 130 perusahaan dan $250 miliar.38 Namun, bulan madu itu tak berlangsung lama. Berbagai kendala tidak terelakkan akibat mahalnya harga tanah, meningkatnya upah buruh dan biaya hidup. Pada tahun 1990-an investasi Jepang ke Muangthai mungkin akan semakin menyusut.39 Meskipun terkendala oleh lemahnya infsrastruktur, produktivitas yang rendah dan ketidakpastian politik dan ekonomi akibat peristiwa pembantaian di Lapangan Tiananmen, Juni 1990; Cina tetap menjadi negara paling penting bagi penanaman modal Jepang di Asia Timur, setelah Muangthai. Ketersediaan tenaga kerja murah dan kondusifnya peraturan pemerintah untuk berpartisipasi pada pasaran senilai $1,2 miliar merupakan faktor yang menggiurkan bagi investor Jepang. Itu sebebnya perusahaan Jepang beramai-ramai mengalihkan operasi dari Korea dan Taiwan ke daratan Cina. Magnitude Cina semakin besar karena pemerintah Cina yang mengikuti langkah negara-negara Asia Timur lainnya, yakni mengiizinkan para investor asing beroperasi di daerah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) miliknya. Alhasil, semakin banyak perusahaan Jepang yang beroperasi, baik berdasarkan prinsip kerjasama maupun sepenuhnya berstatus modal asing/PMA Jepang.40 Sama dengan bidang-bidang usaha lainnya, sektor industri jasa juga merupakan elemen yang semakin penting dalam total investasi Jepang di luar negeri. Pusat-pusat perbelanjaan Jepang mendirikan cabangcabangnya di berbagai penjuru Asia Tenggara. Hasilnya? Pada 1988, terdapat 13 pusat perbelanjaan Jepang di Hongkong; 7 buah di Singapura; 5 buah di Bangkok; dan sebuah di Kuala Lumpur dan Taipei. Di Singapura, pusat-pusat perbelanjaan Jepang ini telah menguasai 35 sampai 45% dari total 100% yang tersedia, dan secara tetap dan terencana terus meningkatkan penguasaan atas pasar dengan menjalankan strategi mematikan dan membeli pusat-pusat perbelanjaan milik lokal yang terancam bangkrut akibat kalah bersaing. Jakarta dan Manila adalah dua kota besar yang tak luput dari bidikan Jepang. Pada tahun 1992, di Jakarta sudah berdiri dengan megahnya pusat-pusat perbelanjaan Jepang seperti Shogo dan Yaohan. Eksploitasi kawasan Asia Tenggara oleh jaringan kuat pusat perbelanjaan Jepang dapat terwujud antara lain karena kebijakan Tokyo. Pemerintah memberlakukan kebijakan “Undang-undang Dagang Skala Besar” (Large-Scale Retail Law), untuk melindungi ribuan pedagang eceran skala kecil Jepang dari kehancuran akibat tidak mampu bersaing dengan pusat-pusat perbelanjaan besar Jepang. Pembatasan jatah beroperasi pusat-pusat perbelanjaan besar—pada hari dan jam kerja tertentu—mendorong mereka merambah pasar luar negeri. Ekspansi pusat-pusat perbelanjaan Jepang juga didorong oleh mahalnya harga tanah dan biaya pembangunan gedung, mengingat Tokyo merupakan daerah termahal di dunia. Kenaikan nilai tukar yen pada pertengahan sampai akhir 1980-an ikut mempercepat ekspansi tersebut, di samping mendongkrak daya beli masyarakat Jepang di luar negeri menjadi sangat kuat. Setelah beroperasi, pengguna terbesar jasa pusat perbelanjaan ini adalah turis Jepang. Mereka bisa membeli produk Jepang pada harga dasar, karena aturan bersama dari pedagang Jepang bagi konsumen dalam negeri tidak dapat diterapkan secara ketat di luar negeri. Di Hongkong, 25 sampai 30% dari seluruh nilai penjualan pusat perbelanjaan berasal dari orang Jepang, dan mereka semuanya berbelanja di pusat perbelanjaan Jepang.41 Bagi satu negara, kepentingan politik dan ekonomi luar negeri biasanya merupakan kebijakan yang saling berkaitan. Kombinasi kepentingan ini secara cerdik dibalur dengan pencitraan melalui apa yang disebut “Dana Bantuan” (Aid). Mayoritas rakyat Amerika Serikat boleh jadi memiliki kebanggaan tersendiri berkat predikat negaranya sebagai pemberi donor terbesar bagi negara-negara di kawasan Asia Timur sampai dengan tahun 1970an. Setelah itu, posisinya digantikan Jepang. Sejak 1970-an itu pula, Jepang menjadi negara donor terbesar bagi kawasan ini. Secara bertahap, Jepang memperluas skala dan volume dana bantuannya ke berbagai kawasan dunia. Pada tahun 1989, untuk pertama kalinya sejak dana bantuan luar negeri dicanangkan pasca-Perang Dunia II, Jepang menggusur posisi Amerika. Dana bantuan luar negeri Jepang pada tahun 1989 ini berjumlah $8,9 miliar, sedangkan Amerika hanya $7,6 miliar.42 Bantuan luar negeri Amerika dan Jepang terhadap Asia Timur merepresentasikan garis kebijakan yang berbeda. Bagi Amerika, aid pada dasarnya dijalankan untuk dua maslahat yang saling berkaitan, yakni menciptakan ekonomi global yang liberal dan sebagai alat penahan gerak laju komunisme. Sedangkan karakter bantuan luar negeri Jepang murni bersifat dagang, yang dirancang untuk mencapai tujuan geoekonomi Jepang. Derajat kepentingan Amerika dan Jepang terhadap Asia Tenggara tercermin dalam jumlah total dana bantuan luar negeri mereka. Hampir 50% dana bantuan luar negeri Jepang mengalir ke kawasan ini, sedangkan Amerika Serikat hanya mengalokasikan 10%. Pada tahun 1981 dan 1982, lima besar negara penerima dana bantuan luar negeri pemerintah (ODA) Jepang adalah negara-negara di kawasan Asia Timur. Sebesar 37,5% dari total ODA Jepang diterima oleh 6 negara di kawasan ini: Indonesia (11,4%), Korea Selatan (6.7%), Muangthai (6,2%), Cina (5,9%), Filipina (5,8%), dan Malaysia (2,6%). Sedangkan dana bantuan Amerika dalam jumlah yang cukup berarti hanya 2 negara, yakni Indonesia (1,9%) dan Filipina (0,9%). Dalam tahun 1990, negara-negara yang tergabung dalam NEC’s menerima 29% dari total ODA Jepang; adapun yang mereka terima dari Amerika hanya 11% dari total aid negara adidaya itu. 13 Target yang menjadi sasaran Jepang, yakni menciptakan daerah Asia Timur ke dalam kawasan pengaruh ekonominya, tercapai sudah. Mimpi yang menjadi kenyataan ini mungkin jadi tak membuat mereka merasa arrive. Sebuah pertanyaan yang sangat logis dan absah adanya muncul di sana: masihkah ada ambisi lain yang dimiliki Tokyo terhadap kawasan ini, apa gerangan agenda yang kudu mereka wujudkan selain pengejawantahan prinsip penghisapan demi mempertahankan kemakmuran ekonomi belaka? Sejak dipulihkannya status Jepang dalam perjanjian perdamaian San Fransisco tahun 1951, negara ini berhasil—sekali lagi, atas bantuan Amerika Serikat--keluar dari berbagai kendala internal dan eksternal akibat kalah dalam PD II. Dengan cara yang brilian, setelah keadaan ekonominya pulih, Jepang mempelopori ide berdirinya Bank Pembangunan Asia (ADB) pada tahun 1966. Sebagai penggagas dan sekaligus pemilik dana terbesar bank ini, pimpinan tertinggi atau presiden ADB merupakan hak prerogatif Jepang. Sejak saat itu, Jepang mulai terlibat dalam pembicaraan mengenai berbagai isu-isu regional. Jepang memainkan peran pengisi kekosongan kekuatan di Asia Tenggara pada tahun 1970-an; menyusul penarikan mundur tentara Amerika dari daratan Vietnam, jatuhnya Indo Cina ke tangan Komunis; dan usaha memperkuat dan memperdalam kerjasamanya dengan negara-negara ASEAN pada tahun 1977. Di pengujung tahun 1970 dan di sepanjang tahun 1980-an, Jepang aktif menjadi penengah untuk menyelesaikan friksi antara ASEAN dan Vietnam. Motif Jepang memainkan peranan ini cukup kompleks. Di satu pihak, seperti juga ASEAN, Jepang mengkhawatirkan potensi ekspansi komunisme Vietnam, yang akan akibatkan ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan itu sangat merugikan kepentingan Jepang. Di pihak lain, Jepang amat berkepentingan memelihara Vietnam dengan 65 juta penduduk itu sebagai sebuah pasar potensial. Jepang dapat berpartisipasi mencegah sengketa antarfraksi di dalam negeri maupun antara Vietnam dan negara tetangganya. Keberhasilan Jepang sebagai penengah sengketa intern dan ekstern Vietnam membuahkan berbagai konsesi berupa proyek-proyek yang, langsung ataupun tidak langsung, berasal dari pemerintah Vietnam. Pada kurun waktu 1980-an ini, dalam forum pertemuan tahunan negara-negara industri maju (G-7), Jepang memproklamirkan diri sebagai juru bicara negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, alihalih jadi penyalur aspirasi negara-negara di kawasan Asia Timur ini, Jepang justru memelintirnya—mengalihkan perhatian atas kritik negara-negara kawasan dan negara-negara industri maju yang mencerca pemberlakuan rintangan pasaran domestik Jepang dan praktek neomerkantilis Jepang. Kalangan lain melihat, Tokyo mengambil alih dan memimpin kawasan Asia Timur ini sebagai sarana untuk mengimbangi blok ekonomi perdagangan yang sudah ada, yakni Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) di Eropa Barat, di samping menghadapi keberadaan blok perdagangan Amerika Utara (NAFTA). 43 Terlepas dari pandangan ini, klaim perwakilan yang diemban Jepang terasa tidak cukup valid bila dilihat dalam arti ambisi mereka sebagai pemimpin, Jepang memang berambisi menjadi pemimpin bagi kawasan ini. Terjemahan ambisi itu adalah perolehan keuntungan ekonomi dan wibawa politik, dengan harga murah (sekadar kesanggupan membayar biaya minimal atas biaya-biaya politik, ekonomi dan militer yang ditimbulkannya) untuk mempertahankan status kepemimpinannya. Berbagai studi yang dilakukan pihak swasta dan pemerintah, baik secara pribadi maupun kelompok, sejak 1980-an, menelaah sepak terjang ‘kepemimpinan’ Jepang dalam blok ekonomi regional kawasan Asia Timur. Kajian-kajian tersebut secara kategoris memunculkan beberapa pertanyaan yang bersifat mendasar: apa dan bagaimana seharusnya bentuk organisasi ekonomi yang cocok untuk kawasan Asia Timur? Negara-negara mana saja yang (layak/tidak) menjadi anggota blok ekonomi ini? Haruskah Jepang dengan kemampuan ekonominya seperi saat ini tampil sebagai pemimpin? Akibat adanya trauma masa lalu terhadap Jepang yang masih menghantui negara-negara di kawasan ini, perlukah sistem kepemimpinan blok ekonomi ini dibuat dengan sistem kolektif (kepemimpinan bersama)? Apa saja tanggung jawab (detail) yang terpikul di pundak pemimpin blok ekonomi ini? Sebuah studi paling ideal tentang bagaimana strategi mendaulat kepemimpinan Jepang di dalam blok ekonomi ini tercermin dalam kajian mendalam Badan Perencana Ekonomi Jepang (EPA) berjudul "Promoting Comprehensive Economic Cooperation in the International Economic Environment Undergoing Upheaval: Towards the Creation of an Asian Network". Dalam kajiannya, EPA secara eksplisit menyatakan, sasaran yang ingin dicapai adalah mengintegrasikan NIC’s dan ASEAN ke dalam satu sistem ekonomi regional yang didominasi oleh Jepang. Istilah untuk menggambarkan keadaan ini adalah 'san-i-ittai' (tiga bagian dalam satu tubuh), analogi yang diambil adalah tubuh manusia. Jika blok ekonomi yang diinginkan sudah terbentuk, dia adalah tubuh. Sedangkan otak dan sebagian besar otot yang berfungsi untuk mengoperasikan tubuh tadi berlokasi di Tokyo. Otak bertanggung jawab mengkoordinasikan kebijakan makro ekonomi dan industri di seluruh negara anggota, yang diperankan oleh Kementerian Keuangan (MOF) bersama Kementerian Industri dan Perdagangan Internasional (MITI). Hampir semua kementerian yang berkaitan dengan ekonomi (Ekuin) melakukan kajian dan memajukan rekomendasi sebagaimana EPA. Kelompok pemikir MOF bernama 'Komite Riset Asia-Pasifik', yang diketuai oleh mantan Presiden Bank Pembangunan Asia, Yoshida Taroichi, memformulasikan rancang bentuk blok ekonomi regional versi mereka. Komite ini melibatkan perwakilan dari semua kementerian terkait dan diorganisasikan ke dalam sekitar 9 sub komite. Buku putih MITI tahun 1988 itu mencatat bahwa integrasi yang dimaksudkan sebenarnya sudah mulai terjadi, dan mengajukan strategi untuk merangsang terciptanya integrasi yang lebih luas. Laporan MITI ini cukup realistis mengingat pembicaraan tentang penciptaan integrasi regional sudah menjadi tema dalam banyak pembicaraan tingkat tinggi antarpejabat pemerintah dari negara-negara di kawasan ini, seperti dalam Konperensi Kerjasama Ekonomi Pasifik (PECC); Forum Jepang-ASEAN; Pertemuan antar-Menteri Ekonomi; dan berbagai pertemuan tak resmi lainnya, yang melibatkan komunitas akademisi dan kalangan bisnis. Di atas skenario-skenario yang disusun tersebut, hal terpenting tentulah bagaimana mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Dalam upaya ini, bagian paling krusial dalam membangun sebuah blok ekonomi yang berskala regional adalah bagaimana meyakinkan negara-negara anggota bahwa persekutuan ini bermaslahat bagi sesama. Secara khusus, Jepang tentunya tak lupa menyusun kalkulasi bahwa mereka (bakal) memperolehan 14 keuntungan lebih banyak ketimbang biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Kiat Jepang adalah melaksanakan apa yang biasa dijalankan oleh manusia dan perusahaan Jepang dalam rangka bertahan hidup. Istilah untuk ini dikenal dengan strategi nemawashi 44 (rekayasa); yang tidak saja menuntut kepeloporan pihak dalam negeri, tetapi sekaligus dukungan proaktif dari pemerintah negara-negara kawasan dalam proses pembentukan blok ekonomi regional ini.45 Sasaran akhir tak lain dari penguasaan menyeluruh terhadap blok ekonomi regional yang sudah terintegrasi dengan baik. Apa kebijakan yang dijalankan Jepang terhadap Asia pada dekade 1990-an tidak ada bedanya dengan strategi yang mereka gunakan pada saat pembentukan Bank Pembangunan Asia di pertengahan 1960-an. Yakni seolah-olah tidak tertarik membuat suatu organisasi, tapi secara cermat justru menyiapkan cetak biru organisasi tersebut. Jadi, ide pembentukan blok ekonomi regional di negara-negara kawasan disuarakan melalui/memanfaatkan mulut pemerintah negara lain. Atas ‘aspirasi’ itu, Jepang muncul dengan paket organisasi regional yang diinginkan, serta merta dengan privilese posisi kepemimpinan mereka. Melalui rekayasa semacam ini, terbentuknya organisasi ekonomi regional hanya membutuhkan formalitas untuk bisa beroperasi. Secara bersamaan, Jepang pun terhindar dari kritik dan tudingan bahwa mereka begitu ambisius. Satu contoh menarik dari kasus di atas tampak dari cara Tokyo menanggapi apa yang dilontarkan PM Australia Bob Hawke pada tahun 1988 tentang perlunya dibentuk OECD bagi Asia. Sikap Jepang ketika itu adalah berpura-pura tidak berhasrat, sebagaimana tercermin dari pernyataan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Jepang, "Kita tidak berniat merealisasikan rancangan yang diajukan PM Hawke, tapi kita bisa melihat dan mengerti apa manfaat ide yang dia ajukan, dan kita berharap bisa bahu membahu memikirkan dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi dan menjalankan kerjasama regional. 46 Pihak Jepang sangat khawatir dicap sebagai negara yang mempelopori bentuk kerjasama apa pun pada tingkat bilateral ataupun regional di Asia. Jika persepsi semacam ini muncul ke permukaan, mereka akan dikritik dan bahkan dihujat NAFTA dan MEE yang membenci neomerkantilisme Jepang. Mengatasnamakan blok ekonomi kawasan lalu mengeksploitasi kekayaan di kawasan tersebut melalui biaya yang seminimal mungkin, Jepang benar-benar menjalankan prinsip neomerkantilisme secara murni. Wajah neomerkantilisme itu bahkan tetap terbaca dalam kebijakan pemberian dana bantuan luar negeri. Sifat bantuan mereka tidak sekadar mengikat terhadap barang dan jasa Jepang, atau memperbanyak dan memperkuat jaringan penanaman modal Jepang; tetapi sudah sampai pada tahap melakukan resturkturisasi total terhadap perekonomian di negeri-negeri kawasan sehingga kawasan menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi Jepang. Dengan kata lain, bantuan tersebut identik dengan usaha memajukan seluruh dimensi perekonomian Jepang. Kawasan (yang konon dibantu) justru diperlakukan sebagai lokasi perusahaan Jepang untuk mengolah bahan baku dan energi hingga menghasilkan barang-barang jadi; sekaligus sebagai pangsa pasar yang sangat luas dan wilayah yang merupakan pengaruh dari produk-produk Jepang. Kondisi seperti inilah yang dialami oleh negara-negara di kawasan terdekat Jepang seperti kawasan Asia Timur, ASEAN, dan sebagainya. Strategi integrasi regional terhadap satu kawasan ini terlihat dalam "New Asian Development Plan and the ASEAN-Japan Development Fund", hasil kajian MITI tentang rencana pembentukan suatu struktur kebijakan bagi kerjasama ekonomi Jepang dengan negara lain untuk masa yang akan datang. Bentuk bantuan luar negeri Jepang meluas dari sekadar proyek-proyek infrastruktur, semacam dam dan pembangunan jalan, menjadi usaha untuk mendukung pembangunan sektor industri tertentu. Untuk itu, pejabat pemerintah Jepang melakukan pembicaraan resmi dengan pemerintah calon negara penerima bantuan bilateral. Kesepakatan prinsip yang dicapai disusul dengan studi intensif guna menentukan sasaran industri strategis yang reasonable untuk pengembangan— sepanjang tidak berbenturan dengan strategi industri Jepang. Akhirnya, master plan kebijakan ekonomi makro dan kebijakan industri ini disampaikan kepada panitia pengarah (steering committee). Panitia ini beranggotakan para pejabat pemerintah kedua negara dari kementerian ekonomi dan organ terkait lainnya. Dalam orientasi kerjanya, panitia ini berkiblat pada seluruh instrumen kebijakan industri Jepang yang dianggap berhasil dalam pelaksanaannya. Instrumen-instrumen ini antara lain riset, impor, ekspor, harga dan jumlah produksi, hambatan impor, pajak. Dengan strategi ini, melalui jaringan lembaga ODA-nya seperti OECF, JICA, JETRO, Jepang berlomba-lomba mencari jalan untuk menangkap mangsa di berbagai belahan bumi ini. Penutup Kombinasi antara kemampuan industri dan strategi niaga Jepang di satu pihak dan lemahnya pemerintah negara-negara Dunia Ketiga di pihak lain makin menguatkan pengaruh Jepang di negara-negara kawasan, bahkan untuk masa-masa mendatang. Cara lama yang diterapkan Jepang melalui militerisme terbukti gagal. Dengan cara baru, yakni mempraktikkan neomerkantilisme—diawali dengan pemisahan antara domain ekonomi dan domain politik dan, setelah kendali ekonomi terkuasai, antara keduanya menghablur begitu rupa dalam sebuah persenyawaan yang musykil dipisah-pisahkan—Jepang berhasil mencapai tujuan-tujuan politik dan ekonomi atas kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dengan biaya murah meriah. Pesimisme dan ironi mungkin sebuah benang merah yang agak permanen membelenggu negara-negara kawasan, karena kawasan tetap akan menjadi habitat yang menyenangkan bagi praktek neomerkantilisme Jepang.© Bab III Kebijakan Politik Luar Negeri Jepang Pengantar Kalau kebijakan luar negeri suatu negara dilihat secara a priori, maka dimensi politik, ekonomi, militer dan budaya merupakan komponen yang membentuk kebijakan tersebut. Dengan demikian, para pelaku pembuat keputusan akan 15 mengaktualisasikan dan mengimplementasikan dimensi-dimensi ini dalam melaksanakan hubungan luar negerinya dengan negara lain. Siapa dan bagaimana peranan dari para pelaku yang terlibat dan berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara adalah pokok bahasan makalah ini, negara yang dijadikan kasus adalah Jepang. Perdebatan yang sering ditemukan pada setiap tulisan yang membahas kebijakan politik luar negeri Jepang adalah dalam menentukan atau memutuskan organ-organ, individu atau kekuatan koalisi mana yang bertanggung-jawab dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri negara ini. Dilihat dari sudut pandang ilmuwan yang menekuni bidang ini, mereka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah ilmuwan yang berpendapat bahwa partai yang berkuasa mempunyai peranan yang penting dalam menentukan politik luar negeri Jepang. Mereka yang menghimpun diri dalam kategori ini bisa disebut kelompok mayoritas. Ilmuwan yang berada pada kelompok kedua berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri Jepang dibuat atas kerja sama tiga kekuatan elit - partai yang berkuasa, Partai Demokrasi Liberal (PDL), kaum Birokrasi Senior, serta Kelompok Dunia Usaha. Kelompok ketiga adalah ilmuwan yang melihat betapa rumit dan berbelit-belitnya proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang, sehingga kebijakan yang dihasilkan perlu dilihat dari pendekatan yang lebih pluralistik, dimana koalisi yang tercipta selalu berubah-ubah dengan teratur, tergantung pada situasi, waktu dan isu-isu yang muncul. Sedangkan kelompok terakhir adalah ilmuwan yang berpendapat bahwa kebijakan politik luar negeri Jepang saat ini lebih banyak diputuskan oleh kaum birokrat juga cenderung menguat, sehingga menempatkan pentingnya lembaga birokrasi seperti departemen luar negeri sebagai organ yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan yang diambil. Sasaran tulisan ini ialah mencoba melihat para pelaku, lembaga yang biasa terlibat dan mempunyai pengaruh atas pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang. Mereka-mereka ini adalah partai yang berkuasa (PDL), Partai oposisi, Parlemen, Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Perdana Menteri, serta Kelompok Ekonomi dan bisnis. Masing-masing dari organ ini akan diuraikan secara berurutan, bagaimana garis besar dari mekanisme struktur proses pembuatan kebijakan politik yang mereka jalankan dalam konteks dunia politik Jepang. Partai Demokrasi Liberal (PDL)14 Satu hal mendasar yang perlu dipertimbangkan pada saat menganalisa PDL adalah kekuasaan partai ini secara ekslusif berasal dari para anggotanya yang duduk dalam parlemen. Hal ini dapat dimengerti, sebab organisasi lokal partai pada tingkat propinsi dan distrik pada hakekatnya tidak efektif; oleh karena itu semua posisi kunci dalam partai ditempati oleh anggota yang duduk di parlemen15. Semua aktifitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan partai dijalankan melalui struktur formal yang dibentuk dalam tubuh partai. Salah satu lembaga yang paling penting adalah Dewan Riset Masalah Kebijakan atau Policy Affairs Research Council (PARC). Lembaga ini terdiri dari 17 divisi16, dan anggotanya adalah semua anggota partai yang duduk di parlemen. Ke 17 divisi ini secara mudah bisa mengadakan kontak kesegenap jajaran kementerian dan ke panitia tetap yang ada pada majelis tinggi dan rendah parlemen Jepang. Selain dari 17 divisi ini, PARC juga memiliki badan atau panitia khusus yang dibentuk atas dasar pertimbangan ad hoc guna menjawab berbagai masalah yang muncul secara spesifik dari waktu ke waktu 17. Sebagai contoh, dibentuknya panitia khusus Ryukyu pada tahun 1957. Tugas panitia ini adalah bertugas untuk mengkaji dan mengupayakan proses pengembalian Ryukyu ke tangan Jepang dari pendudukan Amerika Serikat. Sepuluh tahun setelah hasil kerja panitia ini memperlihatkan hasil yang positif, dua Komite Penyelidik Khusus dari Divisi Masalah Luar Negeri dan Divisi Masalah Keamanan dalam PARC ditugaskan oleh PDL untuk meneliti problem yang akan muncul sehubungan dengan kembalinya Ryukyu ke tangan Jepang. Satu hal yang menarik dari mekanisme kerja partai ini yang patut disimak adalah adanya ketentuan, bahwa setiap anggota partai yang duduk di parlemen harus menjadi anggota dari salah satu atau dua divisi yang terdapat dalam PARC, tapi tidak boleh lebih dari itu. Meskipun demikian, para anggota ini bisa berpartisipasi dalam setiap komite khusus yang mereka minati18. Untuk menjadikan segala yang disetujui dan diputuskan oleh masing-masing divisi PARC ataupun komite khusus sebagai kebijakan partai, maka keputusan atau sasaran kebijakan itu terlebih dahulu harus dibahas dan disepakati oleh lembagalembaga lain yang ada dalam tubuh partai. Begitu hasil kerja dari suatu divisi atau komite khusus ini membuahkan keputusan atau sasaran kebijakan, maka keputusan atau sasaran kebijakan itu harus disahkan atau disetujui oleh Komisi Pertimbangan PARC19. Begitu mendapat pengesahan dari Komisi ini, maka keputusan inipun harus dimajukan kepada Dewan Eksekutif Partai di PDL, masih ada individu yang juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam tubuh partai. Mereka ini adalah Presiden Partai - yang dalam waktu yang bersamaan juga adalah Perdana Menteri, serta biasanya merupakan pimpinan20 dari fraksi terbesar dan terkuat dalam tubuh PDL, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Eksekutif, dan Ketua PARC. Presiden partai adalah sosok yang memiliki figur sangat penting dalam peta politik Jepang. Dianggap penting, karena dia mampu menjamin bahwa keseimbangan antar fraksi terwakili dalam setiap organ partai dan lembaga kementerian lainnya. Dia harus terlebih dahulu mengangkat Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Eksekutif dan Ketua PARC sebelum menggunakan haknya sebagai Perdana Menteri untuk menunjuk seseorang sebagai anggota kabinetnya. Dalam pelaksanaannya, pimpinan teras partai bersama dengan Kepala Sekretariat Kabinet, yang biasanya adalah Kepala Biro Konsultasi bagi Presiden Partai, memberikan saran dan komentar kepada Presiden Partai mengenai calon-calon yang diajukan untuk jadi anggota kabinet, dan meyakinkan bahwa keseimbangan antar fraksi adalah atau sudah terwakili sebagaimana mestinya dalam pos-pos tertinggi dari masing-masing kementerian21. Dalam konteks pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang, pertanyaan yang bisa diajukan adalah apa peranan PDL ini ?. Dari telaah literatur yang dilakukan, memang tak dapat disangkal bahwa PDL mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang. Ketika negosiasi antara Jepang dan Uni Soviet dalam perjanjian perdamaian tahun 1956 sedang berlangsung, peranan dari politikus PDL sangat dominan22. Begitu juga dengan kasus kedatangan Perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Peking tahun 1972 yang menandai pengakuan secara formal pemerintah Jepang terhadap pemerintahan rakyat China. Sehingga boleh dikatakan peranan yang dimainkan oleh politikus saat itu jauh lebih superior dari apa yang dilakukan oleh kementerian luar negeri dalam kelompok pembuatan keputusan 23. Kuatnya peranan PDL dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang tidak terlepas dari dominasi yang mereka miliki dalam parlemen. Boleh dikatakan partai ini selalu menguasai hampir dua pertiga dari seluruh jumlah kursi yang ada dalam 16 parlemen. Dengan demikian, mereka mampu membentuk pemerintahan tanpa harus berkoalisi 24, yang pada akhirnya bisa mengontrol perangkat pengambilan keputusan negara. Partai Oposisi Kebanyakan partai oposisi setelah PD II cenderung untuk berada pada posisi yang agak "kiri" dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Dua partai yang berhaluan kiri yakni Partai Sosialis Jepang (PSJ)25 dan Partai Komunis Jepang (PKJ) menginginkan Jepang tidak terlibat aliansi dengan negara manapun, demiliterisasi, dan pengurangan - kalau tidak sampai pada tahap penghapusan adanya Pasukan Bela Diri (JIETAI) dan Perjanjian Bilateral Keamanan Jepang - Amerika Serikat. Partai yang berhaluan lebih moderat adalah Partai Sosialis Demokrat (PSD) dan partai Komeito - partai yang pada mulanya menjadi perpanjangan tangan organisasi Budha Soka Gakkai dalam lapangan politik. Kedua partai ini tidaklah begitu radikal dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Mereka menginginkan agar Jepang menjalankan politik yang non aliansi - jauh dari ketergantungan terhadap perlindungan Amerika Serikat. Apa yang dapat disumbangkan oleh partai oposisi ini dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang ?. Dalam hal ini, partai oposisi boleh dikatakan sangat sedikit atau tidak sama sekali punya peranan. Selain aktifitas dari beberapa pemimpin partai oposisi yang secara individual memainkan peranan pada saat Perdana Menteri Tanaka Kakuei berkunjung ke Cina, maka partisipasi formal dari lembaga partai oposisi dan anggotanya adalah tidak ada 26. Parlemen27 Peranan parlemen dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri terlihat dengan jelas dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal tertentu UUD Baru Jepang 1946. Pasal 41 menyatakan bahwa parlemen adalah organ tertinggi dari kekuasaan negara, dan merupakan satu-satunya organ pembuat undang-undang negara. Tambahan pula, UUD memberikan kekuasaan padanya untuk menjalankan fungsinya sebagai organ yang mengesahkan perjanjian, yang tentu saja dengan syarat adanya suara mayoritas dari kedua kamar. Disamping itu, parlemen juga punya hak untuk meminta pertanggungan-jawab Perdana Menteri dan para menteri dalam kabinet untuk memasukkan laporan tentang perjanjian yang bersifat international. Meskipun secara teori parlemen bisa berbuat banyak dalam proses pembuatan keputusan kebijakan politik luar negeri, tapi dalam kenyataannya adalah jauh dari itu. Kebanyakan ilmuwan sependapat bahwa tidak banyak peran yang dianggap berarti dimainkan oleh parlemen. Rendahnya peran lembaga ini untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan tidak lain karena lemahnya kedudukan kaum oposisi dalam parlemen, sehingga membuat mereka tidak efektif untuk berkompetisi dengan partai yang berkuasa. Kabinet Kalau kita mengacu pada aturan main yang terdapat dalam UUD Baru 1946, ada 11 pasal yang memuat ketentuan mekanisme kerja dari kabinet. Pasal 65 menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif berada dalam tangan kabinet. Selain melaksanakan jalannya pemerintahan yang bersifat umum, kabinet juga menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) melaksanakan undang-undang dengan benar, serta menjalankan roda pemerintahan; (2) merampungkan masalah-masalah luar negeri; (3) mengadakan perjanjian dengan persetujuan parlemen; (4) menjalankan pelayanan umum, selaras dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang; (5) menyiapkan anggaran belanja dan mengajukannya ke parlemen; (6) membuat peraturan pemerintah selaku pelaksana tugas yang telah diatur dalam UUD dan UU; serta (7) membuat keputusan mengenai amnesti umum, amnesti khusus, pengurangan hukuman,penundaan hukuman dan pengembalian hak 28. Walaupun kesan yang nampak adalah besarnya wewenang yang diberikan UUD baru 1946 kepada kabinet, sama halnya dengan parlemen, lembaga ini tidak banyak mempunyai pengaruh terhadap terjadinya proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang. Kementerian Luar Negeri Sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri, kementerian ini memiliki unit khusus yakni biro-biro yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Masalah-masalah bilateral sepenuhnya ditangani oleh biro regional yang dapat dipecah menjadi seksi Asia, Amerika, Eropa dan Osenia, serta Timur Tengah. Masing-masing biro ini diketuai oleh seorang direktur, mereka memiliki otonomi penuh dan bertanggung-jawab dalam memonitor dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan wilayah kekuasaannya. Masing-masing biro dalam prakteknya dipecah lagi menjadi beberapa divisi yang dioperasikan oleh seorang kepala divisi-dalam hal ini dibantu oleh staf yang bertugas untuk memelihara dan mempertahankan pengetahuan serinci mungkin mengenai daerah atau kawasan yang menjadi tanggung jawabnya, dan bertanggung jawab juga dalam memberikan masukan kepada Direktur Biro. Masukan atau usul yang muncul biasanya berasal dari divisi, yang kemudian diteruskan melalui jalur komando ke Biro. Setelah itu, usulan ini oleh biro diteruskan kepada Wakil Menteri Luar Negeri, yang merupakan karir tertinggi dalam jenjang kementerian luar negeri. Sosok dari Wakil Menteri Luar Negeri ini adalah figur yang dikenal baik oleh lingkungan dan mendapat simpati dari berbagai kalangan politik, khususnya Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Disamping perannya sebagai penghubung antara kementerian luar negeri dengan organ atau individu yang terkait dalam jajaran pemerintah, dia juga penengah antara biro-biro tertentu dengan Menteri Luar Negeri. Para Duta Besar dan seluruh pegawai kedutaan turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui usaha mereka dalam mengumpulkan dan melaporkan informasi dari tempat mereka bertugas ke pemerintah pusat. Kondisi seperti ini akan semakin dianggap sangat penting, apabila dihadapkan pada proses negosiasi untuk masalah yang khusus pula. Dimana posisi lembaga ini dalam pembuatan kebijakan berskala nasional ?. Dalam banyak kasus yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai sejauh mana peranan dari suatu lembaga dalam menentukan kebijakan luar negeri Jepang, dapat disimpulkan kementerian luar negeri kalah bersaing dengan partai yang berkuasa. Hal ini terlihat dalam kasus perjanjian perdamaian Jepang - Uni Soviet. Begitu juga dalam kasus pengakuan Jepang terhadap pemerintahan rakyat Cina. Dalam kedua kasus ini, peranan dari anggota kementerian luar negeri banyak dinilai oleh para ilmuwan hanya sebagai sub ordinasi dari kaum politik29. 17 Perdana Menteri Menurut UUD baru Jepang 1946, Perdana Menteri sebagai figur yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan politk Jepang tergambar dari kekuasaan yang dia miliki untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang. Dia punya hak untuk menunjuk ataupun memecat menteri dalam jajaran pemerintahannya, tanpa harus berkonsultasi kepada anggota parlemen atau kabinet. Meskipun dalam kenyataannya, dia jarang melakukan hal ini. Biasanya pemberhentian seorang menteri oleh Perdana Menteri ini lebih banyak dilakukan dalam rangka adanya pergantian anggota kabinet, dan hal ini paling tidak terjadi sekali dalam setahun. Perdana Menteri bertugas untuk menjalankan pengawasan dan terhadap berbagai lembaga yang berada dibawah naungannya; mewakili kabinet dalam memajukan RUU serta melaporkan masalah luar negeri secara umum kepada parlemen. Semua hukum dan peraturan kabinet harus ditandatanganinya sebelum diberlakukan efektif. Tambahan pula, dia juga memimpin sidang kabinet, memutuskan perselisihan pendapat yang terjadi antar menteri dalam kabinetnya, dan bisa membatalkan peraturan yang telah dibuat oleh para anggota kabinetnya. Pendapat ilmuwan terhadap peran dari Perdana Menteri dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang adalah beragam. Ada yang berpendapat bahwa perannya tidak begitu penting, kejatuhan katayama dan Kishi sebagai Perdana Menteri merupakan dasar pemikiran dari grup ini. Grup lain menilai bahwa peran dari Perdana Menteri saat ini lebih baik dibandingkan dengan para pendahulunya dari masa sebelum perang, hal ini didasarkan atas kekuasaan yang dimilikinya untuk mengangkat dan memberhentikan anggota kabinet. Kelompok Dunia Usaha Komunitas dunia usaha Jepang yang mempunyai peranan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan politik Jepang terdiri dari tiga kelompok. Mereka-mereka ini adalah pemimpin dari organisasi MNC Jepang (Zaikai); Kelompok Industri (Gyokai), dan Korporasi perorangan (Kigyo). Zaikai secara harfiah mengacu pada pimpinan grup industri dan keuangan yang secara tekun menyediakan waktunya untuk aktifitas dari satu atau lebih organisasi ekonomi. Organisasi terpenting diantaranya ialah Keidanren (Federasi Organisasi Ekonomi); Keizai Doyukai (Komite Untuk Pengembangan Ekonomi); Nippon Shoko Kaigaisho (Kamar Dagang dan Industri Jepang), dan Nikkeiren (Federasi Manajer Bisnis). Gyokai mewakili kepentingan kaum industriawan, yang terpenting dan kuat berasal dari sektor baja, elektronika dan perbankan. Fungsi utama dari pemimpin Gyokai adalah untuk mengendalikan persaingan kepentingan yang terjadi antar korporasi perorangan dalam ruang lingkupnya sendiri, dan membentuk hubungan yang erat dengan kelompok politisi dan birokrasi dalam administrasi pemerintahan dalam rangka memberikan masukan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan yang luas dari dunia industri Jepang, sebelum memutuskan atau menjalankan suatu kebijakan 30. Penutup Dari uraian diatas, beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: Peranan lembaga lebih kuat bila dibandingkan dengan peranan individu dalam proses pembuatan keputusan kebijakan politik luar negeri Jepang. Lembaga yang paling banyak berperan dalam hal ini adalah partai yang berkuasa (PDL); kementerian luar negeri; dan dunia usaha. Peran dari lembaga lain kalaupun ada, boleh dikatakan kecil. Keterlibatan PDL dan kementerian luar negeri dalam hal ini adalah bersifat langsung, sedangkan lembaga lain tidak langsung.