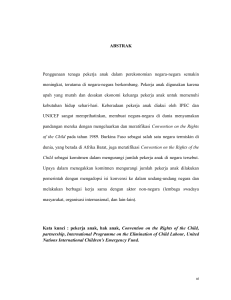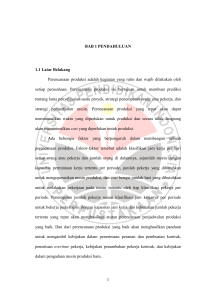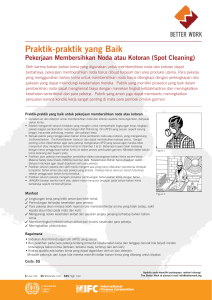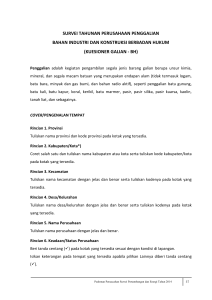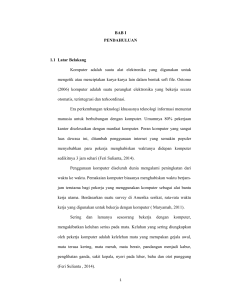policy brief_paper 6
advertisement

Policy Brief Ekonomi Politik Relasi Industri di Indonesia: 1980 – 2004 Oleh: Raymond Atje, Mochamad Pasha, dan Udin Silalahi 1. Pendahuluan Krisis ekonomi 1997/98 menandai sebuah era baru relasi industri di Indonesia. Perhatian utama pemerintah adalah stabilitas politik dan pergerakan tenaga kerja yang bebas dianggap berpotensi mengancam stabilitas tersebut. Stabilitas politik dianggap sebagai kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pembangunan ekonomi, khususnya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam tulisan ini, hubungan industrial adalah praktik yang berhubungan dengan persetujuan kolektif, trade unionism, dan relasi tenaga kerja-manajemen, didalamnya termasuk institusi dan asosiasi dimana melaluinya interaksi tersebut dimediasi. Hubungan industrial melibatkan interaksi antara majikan, pekerja, dan pemerintah (tripartite). Tulisan ini membahas tentang bagaimana pasar tenaga kerja Indonesia telah ditransformasi oleh krisis 1997/98 dan transformasi politik yang mengikutinya, dari yang relatif fleksibel sebelum krisis menjadi relatif kaku setelah krisis. Kefleksibelan pasar tenaga kerja tergantung dari biaya penggantian tenaga kerja, seperti biaya memperkerjakan dan memberhentikan. Semakin tinggi biayanya, maka semakin tidak fleksibel pasar tenaga kerja. Biaya tersebut tergantung kelimpahan relatif tenaga kerja dan peraturan tenaga kerja yang berlaku. Dari sudut pandang ekonomi murni, jika suatu perekonomian memiliki surplus tenaga kerja, maka pasar tenaga kerjanya cenderung fleksibel, walaupun tidak demikian dengan Indonesia. 2. Hubungan Industrial Sebelum Krisis Kebijakan pada tahun 1980-an dan awal 1990-an cenderung memihak pada industri-tetapi tidak harus mengorbankan kepentingan pekerja. Pergerakan tenaga kerja dikontrol ketat oleh pemerintah. Pendekatan yang dilakukan pemerintahan Soeharto (Orde Baru) pada serikat, dipengaruhi persepsi peran destabilisasi pergerakan serikat di masa lalu ketika ketidaktenangan industri menimbulkan masalah bagi pemerintah. Lalu, pemerintah mengambil sikap yang lebih lunak terhadap pergerakan pekerja, tetapi mengalami kesulitan untuk mempertemukan kebebasan serikat dengan kebutuhan untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 1 Bagi pemerintah Orde Baru, jenis serikat yang ada sebelum 1965 terlalu bersifat politik, jauh dari batas toleransi. Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah menerapkan top-down approach pergerakan pekerja. Terdapat tiga aspek dari pendekatan ini: 1 Kerusuhan pekerja merajalela pada tahun 1950-an dan pertengahan 1960-an. Dilaporkan bahwa antara 1951 dan 1956, terdapat rata-rata 400 pemogokan per tahun dan melibatkan 5% pekerja upahan. Serikat pekerja yang mendominasi merupakan aliran garis kiri yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), (Manning, 1998). Pertama, mendorong organisasi pekerja. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memperbesar kontrol atas organisasi-organisasi pekerja tersebut. Langkah pertama adalah dengan membebaskan serikat pekerja yang ada dari intervensi luar, baik organisasi politik atau sosial. Langkah kedua adalah dengan menyatukan mereka ke dalam satu payung organisasi, yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang pada tahun 1985 berubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Langkah ketiga adalah dengan memperkenalkan hubungan industrial panca sila yang menyediakan suatu set prinsip untuk menuntun pelaksanaan praktiknya. Tujuan utama dari hubungan industrial panca sila adalah untuk mengontrol kerusuhan dan aksi mogok untuk mendorong investasi. Pekerja yang terlibat dalam perselisihan akan dituduh anti ideologi negara, anti panca sila (Manning, 1993). Kedua, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Manfaat yang dirasakan oleh sebagian kecil pekerja, bukanlah hasil tekanan yang mereka timbulkan melalui proses politik, tetapi merupakan hasil inisiatif elit politik. Peningkatan kesejahteraan pekerja dari ‘atas’ bertujuan untuk menggalang dukungan dan mencegah tumbuhnya ketidakpuasan. Melaluinya, pemerintah ingin menyatakan dirinya sebagai pemerintah yang baik, yang selalu memperhatikan kesejahteraan pekerja. Inisiatif pemerintah Orde Baru untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja adalah: (1) kebijakan upah minimum yang bertujuan mengurangi kemiskinan dengan menjamin suatu tingkat upah minimum untuk hidup; (2) kebijakan jaring pengaman sosial; dan (3) kebijakan terkait standar kondisi kerja. Ketiga, melibatkan militer dalam hubungan industrial. Pada awalnya, militer dilibatkan dalam mendesain hubungan industrial yang akan dipelihara pemerintah, yaitu yang meningkatkan kestabilan politik dan ekonomi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, militer juga dilibatkan dalam penyelesaian perselisihan pekerja, baik sebagai mediator antara pekerja dan pihak manajemen (yang dalam lingkungan yang korup, akan lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja, karena kemampuannya untuk menyuap), maupun terlibat langsung dalam bisnis (baik mengelola dan memiliki perusahaannya sendiri, atau pun hanya sebagai pekerja pada perusahaan swasta). Militer dilibatkan dalam bisnis bukan karena kemampuan bisnisnya, tetapi karena memiliki kekuatan untuk memaksa (coersive power). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer, mampu menahan usaha formal penyelesaian perselisihan yang merugikan perusahaan (Manning, 1993). Dalam lingkungan yang seperti itu, aktivitas rente (rent-seeking) dan korupsi tidak dapat dihindarkan. 3. Hubungan Industrial Setelah Krisis Keberhasilan hukum pekerja sebelumnya, pada tahun 2000 Menteri Tenaga Kerja, Bomer Pasaribu, mengeluarkan kebijakan, UU No. 150/2000, mengenai pesangon dan dana pensiun untuk para pekerja yang di PHK dan pensiun. Undang-undang tersebut mengharuskan majikan menyediakan pesangon bagi pekerja yang di PHK, termasuk bagi pekerja yang dipecat karena melakukan pelanggaran besar, seperti halnya pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri dan pensiun. Undang-undang tersebut juga menspesifikasikan jumlah uang pensiun dan pesangon yang harus diberikan berdasarkan lamanya pekerja tersebut bekerja. Undang-undang tersebut terlihat bagi banyak orang sebagai sesuatu yang negatif dan nampaknya dapat merugikan pekerja dan pemulihan ekonomi. Hal yang dikritik terutama mengenai nilai yang disaranan untuk menjadi uang pesangon dan pensiun yang dianggap memberatkan majikan. Perhatian utama mereka adalah bahwa biaya untuk memutuskan hubungan dengan pekerja akan meningkatkan pertimbangan perusahaan untuk berpikir dua kali sebelum mempekerjakan pekerja baru. Dan, seperti yang akan dibahas lebih lanjut lagi, terdapat pula fakta-fakta yang mendukung hal tersebut. Pasar Pekerja Menjadi Kaku Sebagai hasil dari berbagai kebijakan yang jelas pro-pekerja, pasar pekerja yang tadinya fleksibel saat sebelum krisis, setelah krisis menjadi lebih kaku. Secara terus-menerus hal tersebut membutuhkan biaya yang membebankan bagi perusahaan untuk memecat pekerja mereka bahkan untuk alasan yang legal. Sementara itu, seperti yang telah diketahui, cara alternatif untuk mengatasi hal itu adalah melalui kontrak jangka tertentu dan menggunakan jasa kontak telah ditolak. Satu konsekuensi yang tidak diinginkan dari adanya kebijakan pekerja yang kaku adalah bahwa, kecuali mereka benar-benar membutuhkannya, perusahaan-perusahan tidak akan menambah pekerja. Hal tersebut mungkin dapat menjelaskan dua fenomena setelah krisis. Pertama, pemulihan industri padat karya yang relatif lambat, contohnya tekstil, garmen, alas kaki, dan sebagainya setelah krisis. Kedua, industri padat modal seperti otomotif dan elektronik menjadi menjadi sumber penting ekspor dalam sektor manufaktur. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, terlihat jelas bahwa pemerintah gagal untuk memperkirakan bagaimana perubahan dari kebijakan pekerja akan mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan, dan pekerja pada khususnya. Bukti empiris dari dua kutipan dibawah ini menyediakan bukti dari pernyataan tersebut. Doing Business Survey Bank Dunia (2006) mendemonstrasikan kerasnya kebijakan yang kaku terhadap sektor bisnis di Indonesia2. Laporan tersebut memuat banyak kumpulan index namun index yang relevan untuk studi ini adalah Hiring and Firing Workers sub index. Indonesia berada di posisi ke-122 dalam Difficulty of Hiring Index dan posisi ke-131 dalam Diffulty of Firing Index, dari 155 negara. Indonesia terlihat memiliki biaya pemecatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara dan wilayah lain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Biaya pemecatan di Indonesia bernilai sebesar 144.8 minggu gaji, dibandingkan dengan rata-rata yang bernilai 60 minggu gaji, yang lebih dari dua kali lipat dari rata-rata. Dalam hal ranking diantara negara-negara yang termasuk dalam sampel, Indonesia mendapat posisi lima terbawah, diantara 155 dalam hal biaya pemecatan, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan biaya pemecatan yang sangat tinggi. Indeks tersebut memberikan gambaran yang buruk untuk sektor bisnis, dengan begitu kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan pasar semakin terancam. Laporan Bank Dunia tersebut juga menyediakan argumen pendukung bahwa Undang-undang Perburuhan yang kaku menyebabkan lambatnya pemulihan sektor padat karya. 2 Dikutip dari McLeod (2007) Gambar 1. Biaya Pemecatan (Jumlah Minggu dari Gaji) Sumber: Diolah dari McLeod (2007) Studi yang dilakukan oleh CSIS (2008) mengenai pekerja di industri tekstil, pakaian, dan alas kaki (TCF) menyediakan lebih banyak alasan pendukung mengenai peningkatan biaya pemecatan dan penyewaan pekerja yang dihadapi oleh perusahaan setelah krisis ekonomi 1997/98. Hasil dari studi tersebut terlihat pada Tabel 1. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama periode 1990-1997, sebelum ditetapkannya Undang-undang buruh yang baru, guncangan ekonomi pada industri TCF diikuti dengan adanya perubahan tingkat pekerja dalam rata-rata 7.4 bulan. Dalam era setelah krisis (1999-2005), penyesuaian dalam tingkat akibat guncangan ekonomi berlanjut pada tingkat yang sangat rendah, contohnya 41.6 bulan atau sama dengan hampir 3.5 tahun. Penyesuaian pekerja yang paling lambat terletak pada sektor tekstil, yang membutuhkan 58 bulan untuk menyesuaikan terhadap guncangan ekonomi tersebut. Sebelum krisis, sektor tersebut hanya membutuhkan 5.83 bulan untuk menyesuaikan. Pada posisi kedua adalah sektor alas kaki yang membutuhkan 38.6 bulan untuk melakukan penyesuaian setelah krisis dibandingkan dengan 7.98 bulan sebelum krisis. Tabel 1. Dampak dari Biaya Gaji Nominal pada Tingkat Pekerja Sector/Sub sector TCF industry Textile s Apparel Footwear Other TCF Industries 1990 -1997 Year Month 0.61 7.36 0.49 5.83 0.70 8.36 0.66 7.98 0.59 7.10 1999 -2005 Year Month 3.47 41.6 4.84 58.0 2.57 30.8 3.22 38.6 5.53 66.3 Sumber: Diolah dari CSIS (2008) Penyesuaian yang lamban pada tingkat pekerja selama periode 1999-2005 mengindikasikan biaya pemecatan dan penyewaan yang tinggi. Yang jelas, saat membandingkan era sebelum dan sesudah krisis, kebanyakan studi menunjukkan bahwa pasar pekerja menjadi sangat kaku pada periode yang kedua. Seperti yang diargumentasikan oleh Alisjahbana dan Purnagunawan, (2004) dan juga Manning dan Roesad (2007), transformasi dari pasar pekerja fleksibel sebelum krisis yang menjadi kaku setelah krisis dikualifikasikan sebagai bagian dari biaya penyesuaian akibat penggunaan kebijakan pekerja yang baru. Pendekatan Coaseian dalam Hubungan Industrial Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pemerintah gagal dalam usaha terakhirnya merevisi Undang-undang No.13/2003, yang dipandang perusahaan sebagai kebijakan yang sangat pro pekerja. Terdapat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang ingin direvisi oleh asosiasi perusahaan. Terutama pasal-pasal yang mengatur tentang outsourcing, pesangon, dan kontrak jangka pendek. Akibat dari Undang-undang ini, perusaaan terpaksa menemukan jalan lain. Dalam hal ini teori Coase terjadi dalam dunia institusi pekerja. Selama biaya tawar-menawar tidak begitu besar dan terdapat pihak yang memiliki hak dalam keputusan, pihak-pihak yang terlibat dalam tawar-menawar tersebut akan menyetujuan pembagian reward dari usaha bersama tersebut.. Revisi Hukum pekerja Jalan keluar terbaik dari masalah antara manajemen dan buruh ini adalah dengan merevisi Undang-undang perburuhan dengan tujuan spesifik yaitu untuk menciptakan keseimbangan kekuatan antara manajemen dan pekerja. Hal tersebut akan sangat meningkatkan hubungan industri yang selama ini terdistorsi oleh Undang-undang yang sedang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, revisi undang-undang harus memperhitungkan kepetingan industri dan kepentingan pekerja. Hal tersebut dapat dicapai dengan meminta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti mereka yang selalu terlibat dalam negosiasi antara Apindo dan beberapa persatuan pekerja. 4. Kesimpulan Terdapat alasan yang kuat untuk meninjau kembali semua peraturan yang membentuk dasar hubungan industrial di Indonesia. Pelajaran penting yang dapat dipetik terutama dari hubungan industrial setelah krisis adalah ketika rezim hubungan industrial lebih berpihak pada satu pihak daripada yang lainnya, maka permasalahan pasti akan muncul. Seperti yang telah didiskusikan di atas, hubungan industrial selelah krisis berpihak pada pekerja daripada pihak menajemen. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak terduga, yaitu pasar tenaga kerja menjadi kaku, yang menimbulkan biaya tinggi bagi pendirian industri dan pekerja, khususnya pencari kerja. Rezim hubungan industrial yang ada mendistorsi keseimbangan yang rapuh antara pihak manajemen dengan pekerja. Saat ini, merupakan hal yang vital bagi pemerintah untuk menyusun undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban majikan dan pekerja dengan seimbang, yang akan memperbaiki hubungan industrial. Undang-undang tersebut harus menyediakan kejelasan dan kepastian dalam hubungan industrial.