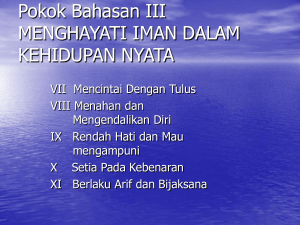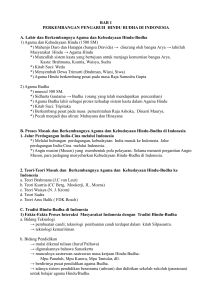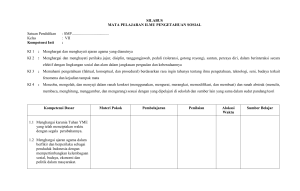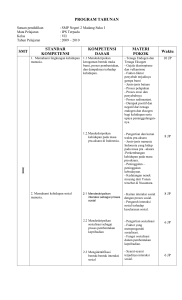ARTIKEL PENELITIAN
advertisement

DEWATANISASI INSANI: PEMAKNAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN HINDU Nengah Bawa Atmadja Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Jln. Udayana Singaraja Abstrak: Kajian pustaka menunjukkan, bahwa hakikat pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Hindu adalah mendewatakan manusia atau dewatanisasi insani guna mewujudkan divine human (daiwisampat) yang sekaligus berarti mencegah kemunculan insan berkarakter keraksasaan (demonic human, asurisampat). Agama Hindu kaya akan resep-resep divine human. Dewatanisasi menuntut penamanan resep-resep divine human di dalam pikiran dan kecerdasan manusia. Manusia berkarakter kedewataan ditandai oleh pikiran, ucapan dan tindakan yang taat pada resepresep divine human yang bersumberkan pada agama dan tata aturan lainnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Abstract: Literary study shows that education essence in perspective of Hindu education philosophy is to deify human or human divinisation in order to realize the divine human (daiwisampat) and also to prevent the appearance of demonic human character (asurisampat). Hindu is rich in divine human recipes. Divinisation demands the divine human recipes investment in mind and in human intelligence. Divine human is marked by intelligence, utterance and action that obey to divine human recipes sourced of religion and other rules that is used in society life. Kata kunci: pendidikan, divine human, pikiran, ucapan dan tindakan Kajian Atmadja (2008) terhadap berbagai karya tulis tentang filsafat ada banyak pengertian tentang filsafat. Namun di balik keragaman pemaknaan ini gagasan Keraf dan Dua (2001: 34) menarik dikemukakan yang menyatakan, bahwa “... Filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebagai tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan bukan penyataan.” Gagasan ini memberikan petunjuk, bahwa filsafat pada hakikatnya adalah bertanya dan terus bertanya guna mendapatkan jawaban yang mendalam (sedalam-dalamnya), luas (seluas-luasnya) dan holistik (seholistik-holistiknya) mengenai suatu realitas, ide atau konsep yang bersifat fundamental (Atmadja, 2010; Woodhouse, 2000). Berkenaan dengan itu maka (ber-) filsafat berarti “... proses bertanya dan menjawab dan bertanya dan menjawab terus tanpa henti. Itulah filsafat sebuah quest, sebuah pencarian, sebuah question tentang berbagai ide” (Keraf dan Dua, 2001: 16). Apa pun bisa dipertanyakan secara filosofis, termasuk di dalamnya tentang pendidikan sehingga melahirkan bidang kajian, yakni filsafat pendidikan (Knight. 2007; Jalaluddin dan Idi, 2007; Djumransjah, 2006; Alwasillah, 2008; Surakhmad, 2009; Fudyatanta, 2006). Kebanyakan buku teks filsafat pendidikan memuat gagasan teoritikus Barat. Hal ini dapat dicermati pada buku teks filsafat pendidikan yang ditulis oleh Djumransjah (2006: 26) yang mengutip pendapat Freeman Butt tentang hakikat pendidikan sebagai berikut. a. Pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. b. Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini, individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatih dan dikembangkan. 56 57 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 43, Nomor 7, April 2010, hlm.56 - 65 c. Pendidikan adalah proses pertumbuhan. Dalam proses ini individu dibantu mengembangkan kekuatan, bakat, kesanggupan, dan minatnya. d. Pendidikan adalah rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang menambah arti serta kesanggupan untuk memberi arah bagi pengalaman selanjutnya. e. Pendidikan adalah proses. Melalui proses ini, seseorang penyesuaikan diri dengan unsurunsur pengalamannya yang menjadi kepribadian kehidupan modern sehingga dalam mempersiapkan diri bagi kehidupan masa dewasa yang berhasil (Freeman Butt dalam Djumransjah, 2006: 26). Pola ini tampak pula pada buku teks filsafat pendidikan yang ditulis Saduloh (2003) yang mengutip makna pendidikan menurut Hoogeveld, Henderson, Hummel, Langeveld, dll. Jikalau pun ada buku teks filsafat pendidikan yang menyinggung tentang filsafat Hindu sebagaimana yang dilakukan oleh Jalaluddin dan Idi (2007) hanya bersifat selintas. Pemakaian gagasan Barat dalam memaknai pendidikan tidaklah salah, mengingat ilmu berdimensi sosial, dalam arti, dia adalah milik publik sehingga seseorang bisa meminjamnya, asalkan mengikuti etika ilmiah. Walaupun peminjaman gagasan Barat sah adanya, namun usaha untuk memunculkan gagasan lain yang bercorak gagasan non-Barat sangat penting. Hal ini berkaitan dengan munculnya evolusi pemikiran manusia, yakni mulai dari pemikiran kosmosentris, berlanjut ke teosentris, antroposentris, lalu sampai kepada logosentris. Pemikiran logosentris merupakan karakteristik pemikiran filsafat postmodern. Filsafat postmodern sangat disukai oleh kelompok ilmuwan Kajian Budaya (Cultural Studies) (Ritzer, 2003; Alwasilah, 2008; Barker, 2004; Jones, 2009; Sugiarhato, 1996). Ciri filsafat ini antara lain tidak tunduk kepada narasi-narasi besar – pada umumnya teori-teori dari dunia Barat, melainkan mencoba menggali narasi-narasi kecil – gagasangagasan lokal termasuk di dalamnya berbagai kearifan lokal di dunia Timur. Pencarian ini, tidak hanya untuk memperkaya teori-teori yang sudah ada, tetapi yang lebih penting adalah untuk melakukan resistensi atau bahkan pembongkaran terhadap teori-teori yang telah mapan. Bertolak dari gagasan filsafat postmodern maka kajian terhadap pemikiran dunia Timur yang bersumberkan dari ajaran agama dan kearifan lokal, tidak saja penting, tetapi juga sangat mendesak guna mengimbangi kuatnya hegemoni pemikiran Barat. Dalam konteks inilah dicoba untuk mengkaji tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan filsafat pendidikan. Manurut Alwasillah (2008), Surakhmad (2009), Knight (2007) dan Jalaluddin dan Idi (2007) filsafat pendidikan mengkaji pendidikan secara filosofis antara lain mempertanyakan tentang “Apa itu pendidikan? Dalam rangka menjawab pertanyaan ini dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai buku teks tentang Agama Hindu antara lain ditulis oleh Titib (1996, 2003), Sivananda (2005, 2006), Tapasyananda (2008), Singh, 2004, 2007), Anandamurti (2008), Pandit (2005), Pendit (2005, 2007), Zimmer (2003), Machwe (2000), Saraswati (2009), dll. Kajian terhadap buku-buku teks filsafat pendidikan dan buku teks yang memuat teoriteori sosial budaya tidak bisa diabaikan, baik sebagai perbandingan maupun pengayaan wawasan teoretik. Ungkapan-ungkapan kebahasaan tentang pendidikan pada buku teks tersebut dicari makna denotatif dan konotatif sehingga pemahaman atas masalah yang dikaji bisa lebih tuntas (Barthers, 2007; Culler, 2003; Hoed, 2008; Ricoeur, 2002, 2006). Kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan dari cara-cara berpikir kefilsafatan, yakni kesadaran diri, kemenyeluruhan, penembusan, dan fleksibilitas (Knight, 2007: 9-11). Dengan cara ini diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam, luas, dan holistik tentang hakikat pendidikan menurut Agama Hindu yang berlanjut pada kemanfaatannya, yakni menambah narasi alternatif tentang pendidikan sehingga hegemoni pemikiran Barat tertandingi, baik pada tataran kognisi maupun praksis pendidikan. Nengah Bawa Atmadja, Dewatanisasi Insani : Pemaknaan Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat… 58 PEMBAHASAN Tuhan yang diberikan label Maha Tahu dan Maha Pencipta, selain menciptakan manusia dan alam semesta, Tuhan memberikan pula agama wahyu. Agama Hindu sebagai agama wahyu, terkodifikasi dalam bentuk kitab suci Veda. Veda disertai dengan aneka teks tafsir, seperti kitab Brahmana, Upanisad, Wiracarita, dan lain-lain sehingga melahirkan seperangkat ajaran agama yang bersifat kontekstual (Mittal, 2006; Prabhavananda, 2006; Saraswati, 2009; Pandit, 2005). Agama Hindu sangat kaya akan ide-ide filsafat, tidak saja tercermin pada ajarannya, tetapi juga pada munculnya aneka aliran filsafat dalam Agama Hindu (Pendit, 2007). Berkenaan dengan itu tidak mengherankan jika filsafat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Agama Hindu. Walaupun kaya akan filsafat, namun Agama Hindu tidak mengenal istilah filsafat, melainkan memakai istilah darshana. Istilah darshana disamakan dengan filsafat. Kata darshana berarti melihat atau mengalami. Pemaknaan seperti ini memberikan petunjuk, bahwa filsafat dalam konteks Agama Hindu, tidak hanya merupakan spekulasi metafisika, tetapi didasari pula oleh data langsung. Pengalaman langsung adalah sumber darimana pikiran India mengalir, dan ini diterima sebagai dasar filsafat di India (Prabhavanda, 2006). Gagasan ini menarik, karena menunjukkan kesamaan dengan gagasan Alfred North Whiteheid (dalam Bria, 2008: 23) tentang filsafat yang dianggap memiliki dua wajah sekaligus, yakni rasional dan empiris. Hubungan antara keduanya bersifat dinamis, saling menguji, menjelaskan, menjustifikasi, bahkan memfalsifikasi. Kata kuncinya adalah kesesuaian antara kerangka dan materinya. Hal ini harus diusahakan oleh filsafat, sehingga darshana tidak hanya memuat pemikiran spekulasi metafisika, tetapi memuat pula pengalaman atau meminjam ide Immanuel Kant memadukan antara rasionalisme dan empirisme (Atmadja, 2010; Tjahjadi, 2007). Walaupun filsafat Hindu sangat menghargai olah pikiran dan pengalaman, namun ada aspek penting yang membedakannya, yakni penghargaan terhadap intuisi (Sivananda, 2006). Gejala ini berkaitan dengan hakikat manusia, yakni memiliki kesadaran supra yang memberikannya kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan secara intuitif yang di dalamnya mencakup olah rasa dan olah batin (Singh, 2005, 2004; Acarya, 1991). Jadi, dalam rangka mendapatkan pengetahuan, filsafat Hindu tidak hanya bermuatan olah pikiran (rasionalisme) dan olah pengalaman (empirisme) atau memadukan wadah rasional dan empiris sebagaimana yang lazim berlaku pada filsafat Barat, melainkan meminjam gagasan Knight (2007) memperhatikan pula intusi yang di dalamnya mencakup kesadaran supra, olah rasa dan olah batin. Namun di balik pencarian kebenaran secara falsafati maka peran Agama Hindu sebagai sumber kebenaran tidak bisa diabaikan. Agama Hindu adalah kebenaran yang berdimensi kewahyuan sehingga kualitasnya bersifat absolut dan tak tercampuri (murni). Teks suci Veda dan tafsirnya, tidak saja memuat tentang tata kelakuan keagamaan, tetapi memuat pula aneka tata kelakuan sosial. antara lain tentang pendidikan. Cakupannya sangat luas dan kompleks sehingga bisa menjawab permasalahan pendidikan yang lazim dipertanyakan dalam filsafat pendidikan. Bertolak dari kenyataan ini tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa Agama Hindu mengenal filsafat pendidikan atau secara lebih spesifik bisa disebut Filsafat Pendidikan Hindu. Adapun gagasan Filsafat Pendidikan Hindu tentang hakikat pendidikan (Apa itu pendidikan?) adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah dewatanisasi insani Manusia adalah makhluk pendidikan (homo educadum), sebab berkemampuan mendidik dan dididik (Suhartono, 2006). Begitu pula kelangsungan hidup manusia baik sebagai sistem organisme maupun kepribadiannya, dan sistem sosial bentukannya, bergantung pada pendidikan 59 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 43, Nomor 7, April 2010, hlm.56 - 65 (Parsons, 195; Much, 2008). Realitas ini disadari oleh Agama Hindu, terbukti dari kenyataan, bahwa Agama Hindu banyak mengkaji masalah pendidikan. Hal ini telah berlangsung sejak awal, terlihat pada ungkapan-ungkapan teks kuno sebagai berikut. (1) Sa vidya ya vimuktaye (Pembelajaran adalah yang membebaskan manusia) (2) Vidya tritiyo netrah (Pembelajaran seperti mata ketiga) (3) Vidyayamrihtamashnute (Pembelajaran membuat manusia abadi) (4) Na hi jnanen sadrisnham pavitramih vidyate (Tidak ada yang lebih murni di dunia ini daripada pengetahuan) (5) Vidya balam chandrabalamstathaiva (Mudah-mudahan kekuatan pengetahuan dan kekuatan bulan menganugrahi kamu sekalian) (6) Vidya gurunam guruh (Pengetahuan merupakan gurunya guru) (7) Kim kim na sadhyati Kalpalateva vidya (Apa yang tidak dijumpai oleh pembelajaran itu? Ia merupakan sebuah tumbuhan magis atau pohon kebijaksanaan) (8) Vidya vihinah pashuh (Seseorang yang tanpa pembelajaran adalah binatang) (Machwe, 2000: 162-163). Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan bahwa Agama Hindu sangat menghargai pentingnya pengetahuan bagi kehidupan manusia. Gagasan ini sangat tepat, terbukti dari adanya kenyataan, bahwa pada era postmodern atau pascakapitalis saat ini, sumber ekonomi dasar tidak lagi alatalat produksi, modal, daya alam, dan tenaga kerja, melainkan pengetahuan (Drucker, 1997). Begitu pula keunggulan negara negara-negara kapitalis global tidak bisa dilepaskan dari kemahakayaan modal (ilmu) pengetahuan yang diaktualisasikan dalam berbagai produk teknologi canggih. Perolehan pengetahuan didapat melalui pembelajaran. Kemampuan belajar merupakan aspek penting bagi eksistensi manusia, tidak hanya karena belajar adalah pintu gerbang bagi pengetahuan, tetapi juga karena kemampuan belajar adalah aspek penting yang membedakan manusia daripada binatang – perilaku binatang terprogram secara naluriah. Namun manusia tidak saja mengenal pembelajaran – aktivitas yang lebih menekankan pada pemupukan kognisi, tetapi mengenal pula pendidikan – aktivitas pembentukan watak atau karakter insani (Knight, 2007). Agama Hindu menyebut pendidikan dengan istilah aguronaguron atau asewakadharma. Pendidikan bisa dilakukan di sekolah atau pada zaman Veda disebut sakha atau patasala. Pada masyarakat Bali mengenal istilah asrama, pasraman atau katyagan (Titib, 2003; Prabhavananda, 2006). Apa pun nama lembaga pendidikan, baik asrama maupun sekolah, pasti memiliki tujuan – hakikat manusia sebagai makhluk teleologis. Dengan mengacu kepada Suhartono (2006: 80) tujuan pendidikan adalah “... pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri. Dewasa dalam perkembangan badan, cerdas dalam hal perkembangan jiwa, dan matang dalam hal berperilaku”. Gagasan Suhartono (2006) menarik dicermati, mengingat bahwa kata pendewasaan yang sebagai salah satu dimensi tujuan pendidikan merupakan turunan dari kata dalam Bahasa Sanskerta, yakni dewasa (dewa dan sya yang berarti memiliki sifat sebagai dewa). Titib (2003) menjelaskan makna kata dewasa sebagai berikut. Bila kita kaji tentang makna pendidikan mengandung arti mengantarkan seorang anak menuju ke tingkat dewasa atau kedewasaan .... maka kata dewasa ini dapat dikaji maknanya dengan kata dewa atau devata, dimaksudkan seorang itu dalam perilakunya sudah memiliki sifat-sifat kedewataan (Daiwisampat), karena kata dewasa (dewasya) berasal dari kosa kata bahasa Sansekerta, yang artinya memiliki sifat dewa, juga berarti yang bercahaya, tentu diharapkan perilaku anak mengikuti ajaran ketuhanan atau memancarkan nilai-nilai ketuhanan, tidak sebaliknya dikuasai oleh sifatsifat keraksasaan (Asurisampat) (Titib, 2003: 4). Dengan demikian, dilihat dari makna kata dewasa, maka tujuan pendidikan bukanlah men- Nengah Bawa Atmadja, Dewatanisasi Insani : Pemaknaan Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat… 60 jadikan peserta didik agar dewasa dalam arti perkembangan badaniah seperti dikemukakan Suhartono (2006), tetapi lebih mengarah kepada menjadikan insan berkarakter kedewataan (daiwisampat) atau divine human yang sekaligus berarti mencegah kehadiran manusia berkarakter keraksasaan (asurisampat) atau demonic human. Dengan meminjam pendapat Surakhmad (2009) gagasan ini jelas bernuansa filosofis, sebab kandungannya tidak sekedar memenuhi hasrat ingin tahu tentang hakikat pendidikan, tetapi memuat pula cita-cita ideal tentang tujuan pendidikan – mewujudkan divine human. Pendek kata, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Hindu pada hakikatnya adalah proses mendewatakan manusia atau dewatanisasi insani yang sekaligus berarti mencegah kemunculan insan berkarakter raksasa (deraksasani insani). Dengan kata lain bisa pula dikemukakan, bahwa hakikat pendidikan menurut pandangan Filsafat Pendidikan Hindu memiliki wajah ganda, yakni dewatanisasi insani dan deraksasanisasi atas manusia (membasmi sifat-sifat raksana) sehingga melahirkan insan ideal, yakni divine human atau daiwisampat, bukan manusia berkarakter raksasa, asurisampati atau demonic human. Ciri-ciri Divine Human Pemaknaan pendidikan sebagai dewatanisasi insani atau deraksasanisasi insani guna membentuk daiwisampat atau divine human, bukan manusia asurisampati atau demonic human, memberikan petunjuk, bahwa Agama Hindu menggunakan konsep oposisi biner (rwa bhineda) dalam melihat eksistensi manusia. Gagasan ini berkaitan erat dengan pandangan Agama Hindu tentang hakikat manusia, yakni secara substansial terdiri dari unsur tubuh, pancaindra, pikiran (manah), budi (budhi, kecerdasan), dan atman (rokh, spriton, kesadaran) (Singh, 2004, 2007). Kepemilikan tubuh dan pancaindra memunculkan hasrat atau kama. Hasrat selalu berkecenderungan untuk menikmati sesuatu yang menyenangkan. Gagasan ini tidak jauh berbeda daripada gagasan Aristoteles tentang tujuan hidup manusia, yakni mencari nikmat dan menghindarkan rasa sakit (MagnisSuseno, 2010). Pengaktualisasian hasrat atau kama selalu dibayangi oleh sattwa guna – tendensi-tendensi benar dan patut dan tamas guna – tendensi-tendensi salah dan tidak patut. Bayangan tattwa guna dan tamas guna tidak bisa dilenyapkan, karena keduanya melekat pada tubuh manusia. Akibatnya, dalam memenuhi hasrat manusia selalu berpeluang untuk berbuat baik (sattwa guna) atau sebaliknya, yakni berbuat kejahatan (tamas guna) (Singh, 2004, 2007; Sudharta, 2001, 2009; Pandit, 2005). Dengan demikian, secara psikogenetik manusia adalah makhluk berkarakter ganda, yakni kedewataan dan keraksasaan sehingga melahirkan divine human dan demonic human. Manusia selalu berpeluang untuk berbuat kebajikan (sattwa guna) atau sebaliknya, yakni berbuat kejahatan (tamas guna) baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kemana peluang karakter manusia, apakah sattwa guna (divine human) atau tamas guna (demonic human), bergantung pada dominasi proporsi masing-masing sebagai satu kesatuan dalam tubuh manusia (Pendit, 2005). Kemunculan perbuatan baik atau buruk dalam memenuhi hasrat, selain karena kemelekatan sattwa guna dan tamas guna pada tubuh manusia, bergantung pula pada pengendalian pikiran (manah) dan kecerdasan (budhi) (Singh, 2004, 2007; Sudharta, 2001). Pikiran dan kecerdasan memberikan pertimbangan atas dasar rasionalitas dan moralitas atau akal sehat dan rasa, yakni rasa malu, salah, takut, dan dosa (Atmadja, 2010). Tubuh dan pancaindra sebagai sumber hasrat – manusia pabrik hasrat, selalu menuntut kenikmatan optimal. Akibatnya, terjadi Bratayuddha yang ajeg dalam tubuh manusia, yakni perang antara partai Korawa, simbol tubuh, pancaindra dan hasrat berlandaskan tamas guna, dan partai Pandawa, simbol tubuh, pancaindra, dan hasrat yang dikendalikan oleh manah dan budhi berlandaskan sattwa guna. Jika Korawaisme (Duryadanaisme), tubuh, pancaindra, dan 61 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 43, Nomor 7, April 2010, hlm.56 - 65 hasrat mengalahkan Pandawaisme manah, budhi dan sattwa guna. Maka muncul tindakan manusia bersifat tamas guna atau keraksasaan. Jika terjadi hal yang sebaliknya, yakni Pandawaisme (Yudistiraisme), manah dan budhi mampu mengendalikan Korawaisme tubuh, pancaindria hasrat, dan tamas guna maka muncullah tindakan sattwa guna atau kedewataan. Gagasan ini menimbulkan implikasi, bahwa pendidikan sebagai dewatanisasi insani secara ideal diarahkan kepada pembentukkan manusia berkarakter ideal, yakni: pertama, mampu mengendalikan dominasi dan hegemoni tubuh, pancaindra dan hasrat atas manah (pikiran) dan budhi (kecerdasan). Atau sebaliknya, menjadikan manah dan budhi sebagai kekuatan dominatif dan hegemonik atas tubuh, pencaindra, dan hasrat. Kedua, sattwa guna mengendalikan tamas guna. Ketiga, pengikut setia partai Pandawa (Pandawaisme, Yudistiraisme) dan mengabaikan partai Korawa (Korawaisme, Duyadanaisme). Keempat, karakter kedewataan mengendalikan karakter keraksasaan atau divine human mengendalikan demonic human. Walaupun berpihak pada daya manah dan budhi, sattwa guna, Pandawaisme atau divine human, namun tidak berarti, bahwa daya tubuh, panca-indra, hasrat, tamas guna, Kowaisme atau demonic human, karena secara substansial tidak bisa dilenyapkan, bahkan harus ada dalam konteks kehidupan manusia. Unsur-unsur ini tidak bisa dinolkan, tidak saja karena sattwa guna dan tamas guna melekat secara psikogenetik dalam tubuh manusia, tetapi juga karena sesuai dengan hukum rwa bhineda, yakni pemilahan atas dua hal berbeda secara berlawanan dalam konteks dialektika kebermaknaan. Misalnya, kebaikan, kebajikan atau dharma tidak bisa lepas dari kejahatan, keburukan atau adharma. Mahabrata memberikan penggambaran tepat tentang hal ini, yakni partai Korawa memang kumpulan orang-orang jahat, namun ada pula titik kebaikannya, misalnya kehadran tokoh Bisma. Pandawa memang kumpulan orang-orang baik, namun ada celanya. “Bukankah mereka suka berjudi?’ Begitu pula pascabratayudha, karena Kowara mati secara total, maka Pandawa sebagai simbol kebajikan juga mati satu persatu. “Mengapa Pandawa mati?” Sebab, keberadaan Pandawa sebagai simbol kebajikan tidak bermakna lagi, karena tidak ada keburukan (Atmadja, 1984). Gagasan seperti ini bisa pula dicermati pada teodise Agustinian yang menyatakan, bahwa “... Kejahatan secara aksidental disebabkan oleh kebaikan; atau kejahatan adalah ‘ketiadaan kebaikan’ (privatio boni) (Bria, 2008: 52). “Bukankah kebaikan pun dapat muncul dari pengalaman akan keburukan, a blessing in disguise?” (Bria, 2008: 82). Dengan demikian, walaupun Agama Hindu menganut azas oposisi biner, namun meminjam Gunawan (2010), berbeda daripada ide Aristoteles yang menganut azas bivalensi yang memuat pemilahan atas dua bagian, di mana manusia harus memilih “ini” atau “itu. Ibarat sebuah film coboy, pelaku lakonnya terbagi dua, yakni “orang baik” dan “orang jahat”. Sebaliknya, Agama Hindu, begitu pula Agama Buddha menganut azas oposisi biner bukan bivalensi, melainkan multivalensi yang terkait dengan Logika Samar atau Fuzzy Logic. Multivalensi dalam Logika Samar mencoba melihat nuansanuansa dalam menangkap kebenaran. Ada “orang baik tetapi ada cacatnya” dan “orang jahat tetapi ada segi baiknya. Tak ada manusia yang sempurna, tetapi selalu ada cacatnya. Kondisi bivalensi dalam logika samar menyatu dengan sang diri mengikuti rentangan waktu atau sang kala, sehingga tidak mengherankan jika bukan pada hari ini, maka sepanjang hidupnya, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang manusia selalu berpeluang untuk berbuat tidak baik (salah) atau sebaliknya berbuat kebajikan. Berkenaan dengan itu maka dewatanisasi insani sebagai proses dan tujuan pendidikan, arahnya bukan melenyapkan daya tubuh, pancaindra, hasrat, tamas guna, Korawaisme atau demonic human secara total, melainkan mengendalikannya agar melahirkan manusia yang berpihak pada daya manah, budhi, sattwa guna, Pandawaisme atau divine human. Dalam konteks inilah maka pendidikan sebagai dewatanisasi Nengah Bawa Atmadja, Dewatanisasi Insani : Pemaknaan Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat… 62 insani harus menanamkan berbagai indikator tindakan yang mencerminkan divine human. Kajian terhadap berbagai teks Agama Hindu, yakni Veda (Titib, 1996; Bose, 2000; Saraswati, 2009; Mittal, 2006) dan berbagai teks tafsirnya, terlihat misalnya pada karya Tapasyananda (2008), Pandit (2005), Sudharta (2007, 2009), Sivananda (2005), dan lain-lain, dapat diketahui, bahwa banyak tata kelakuan atau resep bertindak yang semestinya ditanamkan guna mewujudkan divine human. Misalnya, (1) bhakti kepada Tuhan; (2) ahimsa (nirkekerasan); (3) cinta kasih (Tuhan adalah cinta kasih dan cinta kasih adalah Tuhan; (4) tidak sombong; (5) sabar; (6) dermawan atau murah hati; (7) tidak egois; (8) memiliki rasa syukur; (9) memiliki rasa terimakasih; (10) mampu mengendalikan pikiran, kemarahan, keinginan (indria) dan diri sendiri; (11) menganggap setiap manusia sama derajatnya; (12) membuang kebencian dan kekejian; (13) hidup sederhana secara berkemaknaan; (14) melakukan kebaikan termasuk di dalamnya rela berkorban untuk kesejahteraan orang lain; (15) memberikan pengampunan; dan (16) percaya pada diri sendiri, dll. Pendek kata, Agama Hindu menye-diakan tata kelakuan atau resep bertindak yang amat kaya guna mewujudkan divine human melalui dewatanisasi insani. Secara umum hal ini bisa disebut resep divine human atau resep daiwisampat. Orang Hindu tidak saja sebagai orang yang memiliki Agama Hindu, tetapi juga sebagai warga negara dan masyarakat. Negara dan masyarakat memiliki tata aturan, yakni dharma negara. Sedangkan Agama Hindu disebut dharma negara. Orang Hindu sebagai warga masyarakat dan negara merupakan pula warga masyarakat dunia. Apalagi pada era globalisasi secara disadari maupun tidak, manusia berada pada lingkungan kampung global (Atmadja, 2010). Kondisi ini menimbulkan implikasi, bahwa pendidikan sebagai dewatanisasi dalam konteks mewujudkan divine human, tidak cukup hanya menginternalisasikan ajaran Agama Hindu (dharma agama), melainkan wajib pula menginternalisasikan tata aturan masyarakat dan negara atau dharma negara dalam skala nasional dan global agar interaksi sosial antarwarga dalam lingkup negara dan atau antarnegara berjalan secara berkedamaian. Namun apa pun bentuk resep divine human, maka penanamannya dilakukan pada pikiran manusia. Gagasan ini berkaitan dengan filsafat Vedanta dan Katha Upanisad tentang hakikat manusia yang terdiri dari tubuh dan roh (atman). Tubuh dapat diibaratkan dengan kereta. Rokh adalah penumpang kereta. Kecerdasan adalah kusirnya. Pikiran adalah tali kendali, dan pancaindria adalah kuda-kudanya (lima ekor kuda penanda lima alat indria). Jiwa adalah penikmat atau penderita, tergantung pada pikiran dan indria-indrianya (Singh, 2004, 2007). Gagasan ini memberikan petunjuk, bahwa dewatanisasi insani pada dasarnya adalah menanamkan resepresep divine human di dalam pikiran manusia. Aneka resep divine human ini tidak sekedar disimpan dalam pikiran – berfungsi sebagai peta kognisi, tetapi sekaligus juga mengendalikan pikiran (aspek evaluatif). Gagasan ini sangat penting mengingat pendapat Sivananda (2005) sebagai berikut. Ketika anda sudah berhasil mengendalikan pikiran, maka anda akan memiliki kendali atas tubuh anda. Tubuh hanyalah bayangan dari pikiran. Ia hanyalah konstruksi yang dibuat oleh pikiran untuk mengekspresikan dirinya. Tubuh akan menjadi budak anda ketika anda sudah berhasil menaklukkan pikiran (Sivananda, 2005: 28). Sebagaimana terlihat pada perumpamaan di atas, yakni pikiran adalah tali kendali kuda (pancaindria) yang menarik kereta (tubuh), dan kusir (kecerdasan) adalah pemegang tali kendali, maka implikasinya, sejauh mana pikiran mampu mengendalikan tubuh dan pancaindria, bergantung pula pada kusir (kecerdasan). Berkenaan dengan itu maka pendidikan sebagai dewatanisasi insani tidak cukup hanya menanamkan resep-resep divine human dalam pikiran, melainkan membutuhkan pula peningkatkan kecerdasan. Dalam konteks inilah teori-teori kecerdasan, yang mencakup kecerdasan emosional, intelektual, spiritual, dan sosial (Efendi, 2005) 63 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 43, Nomor 7, April 2010, hlm.56 - 65 tidak bisa diabaikan guna mewujudkan divine human. Pencermatan terhadap resep-resep divine human seperti dikemukakan di atas – hanya contoh kecil tentu bisa digali lebih dalam lagi pada teks Agama Hindu, bisa berfungsi ganda, yakni menambah daya pikir dan kecerdasan. Agama Hindu amat kaya akan resep dinine human tidak kalah pentingnya daripada agama yang lain maupun teori-teori sosial budaya. Aneka resep divine human yang ditanamkan, baik dalam pikiran maupun pembentukkan kecerdasan, kebermaknaannya terlihat dalam perubahan pada peta kognisi yang berlajut ke praksis berbentuk tindakan dan ucapan bercorak divine human. Divine human tidak saja menuntut perubahan pada pikiran – kaya aspek kogintif dan evaluatif, melainkan menuntut pula konsistensi pada ucapan dan tindakan atau Tri Kaya Parisudha - pikiran (manacika), ucapan (wacika) dan (kayika) membentuk suatu kesatuan. Namun kunci utamanya, tetapi terletak pada pikiran, karena pikiran sebagai gudang ide berwujud aspek kognisi dan evaluatif adalah rajendra, yakni raja yang berkuasa mengendalikan alat indra, tubuh dan hasrat. Jika manusia berhasil mengendalikan pikiran dengan menggunakan idea yang ada di dalam pikirannya, baik sebagai peta kognisi maupun aspek evaluatif yang berlanjut pada penguasaan atas alat indria, tubuh dan hasrat, maka peluang bagi kemunculan divine human sangat besar. Berkenaan dengan itu maka gagasan Finger dan Asun (2004) bahwa pendidikan adalah perubahan pikir sebagai identik dengan proses pengembangan dewasa – bermakna memiliki karakter dewa, sama dengan gagasan Filsafat Pendidikan Hindu tentang pendidikan sebagai dewatanisasi insani – proses menjadikan manusia sebagai makhluk berkarakter dewa atau deraksasanisasi insani – proses menjadikan manusia agar menanggalkan karakter keraksasaan. Gagasan Agama Hindu tentang kemanunggalan tubuh dengan sattwa gana dan tamas guna, begitu pula manusia adalah pabrik hasrat dan pikiran acap kali gagal mengendalikannya, bahkan hasrat (tubuh, pancaindria) menguasai pikiran sehingga peluang manusia untuk berbuat buruk selalu terbuka. Gagasan ini menimbulkan implikasi, bahwa pendidikan sebagai proses mendewasakan (dewasanisasi) atau mendewatakan manusia (dewatanisasi) tidak berhenti hanya pada saat manusia mencapai taraf kedewasaan biologis, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Selain keewasaan secara biologis, manusia menuntut pula kendewasaan secara sosiobudaya yang berlangsung sepanjang hayat. Usaha mewujudkan kedewasaan secara sosiobudaya tidak mudah, baik karena faktor psikogenetik – manusia memiliki tubuh, pancaindria, hasrat, dan tamas guna maupun karena pengaruh lingkungan sehingga sepanjang perjalanan hidupnya, manusia selalu berpeluang untuk berbuat kejahatan. Berkenaan dengan itu maka gagasan UNESCO bahwa manusia harus melaksanakan pendidikan permanen, yakni menciptakan masyarakat di mana setiap orang belajar tanpa dibatasi oleh waktu, sangatlah tepat. Perubahan sosial dan budaya mengharuskan manusia, baik yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa untuk secara terus-menerus mendewasakan pikirannya (Finger dan Asun, 2004). Gagasan ini sangat cocok dengan Filsafat Pendidikan Hindu yang melihat, bahwa manusia adalah multivalensi yang terkait dengan logika samar, sehingga tidak ada manusia yang murni baik atau sebaliknya, yakni murni jahat. Berkenaan dengan itu maka dewatanisasi tidak saja menjadi suatu keharusan bagi manusia, tetapi juga berlangsung sepanjang hayat. Jika dewatanisasi berhenti, maka hasrat yang menyatu dengan virus tamas guna bisa memunculkan penyakit, yakni perilaku menyimpang pada sistem sosial – yang paling hebat apa yang oleh Whitehead (dalam Bria, 2008) disebut kejahatan moral. PENUTUP Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa Agama Hindu memiliki Filsafat Pendidikan Hindu yang bersumberkan pada Veda dan teks tafsirnya, dikombinasikan dengan rasionalisme, empirisme dan intuisi sehingga Nengah Bawa Atmadja, Dewatanisasi Insani : Pemaknaan Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat… 64 kebenaran yang didapat juga bersifat metafisik. Topik-topik yang lazim dikaji dalam filsafat pendidikan ada di dalam Agama Hindu, di antaranya adalah pendidikan. Agama Hindu menggariskan, bahwa hakikat adalah proses untuk mewujudkan manusia berkarakter kedewataan, daiwisampat, divine human atau Pandawaisme. Sebaliknya, mencegah timbulnya manusia yang berkarakter keraksasaan, asurisampat, demonic human atau Korawaisme. Berkenaan dengan itu maka hakikat, proses, dan tujuan pendidikan dalam perspektif Filsafat Pendidikan Hindu bisa disebut sebagai dewatanisasi insani atau deraksasanisasi insani. Pencapaian sasaran dewatanisasi insani dilakukan dengan cara menanamkan resep-resep divine human di dalam pikiran dan kecerdasan peserta didik. Dalam konteks ini Agama Hindu memuat ajaran yang rinci tentang resep-resep divine human sebagaimana terlihat pada kitab suci Veda dan teks-teks tafsinya. Penanaman resep-resep divine human amat penting, tidak semata-mata berguna bagi pengendalian pikiran, tetapi berlanjut pula pada penguatan kecerdasan yang berujung pada pengendalian tubuh dan pancaindria. Jika pikiran dan kecerdasan kaya akan resep-resep divine human, maka tubuh dan pancaindria akan terkendalikan sehingga tercapai human divine, tidak saja dalam pikiran, tetapi juga pada ucapan dan tindakan. Manusia secara psikogenetik dan sosiobudaya selalu berpeluang untuk berbuat jahat. Karena itu, dewatanisasi harus berlangsung sepanjang hayat dikandung badan. DAFTAR RUJUKAN Alwasilah, A.C. 2008. Filsafat Bahasa dan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Culler, J. 2003. Barthers. (Ruslani Penerjemah). Yogyakarta: Jendela. Anandamurti, S.S. 2008. Pengetahuan Spritual di dalam Kitab Weda. (A’C Vibhakarananda Avt Penerjemah). Denpasar: Ananda Marga Indonesia. Djumransjah. H.M. 2006. Filsafat Pendidikan. Malang: Banyumedia Publishing. Atmadja, N.B. Wiracarita Ajaran Agama Hindu. Singaraja: Akademi Pendidikan Agama Hindu Singaraja. Atmadja, N.B. 2008. Buku Ajar Filsafat Ilmu Pengetahuan Jilid I. Singaraja: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Atmadja, N.B. 2010. Ajeg Bali Pergerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi. Yogyakarta: KLiS. Barker, C. 2004. Cultural Studies Teori dan Praktik. (Nurhadi Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Drucker, P.F. 1997. Masyarakat Pasca Kapitalis. (Tom Gunadi Penerjemah). Bandung: Angkasa. Efendi, A. 2003. Revolusi Kecerdasan Abad 21 Kritik MI, EI, SQ dan Successful Inteligence atas IQ. Bandung: Alfabeta. Finger, M. dan J.M. Asun. 2004. Quo Vadis Pendidikan Orang Dewasa. (Nining Patikasari Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Kendi. Fudyatanta, Ki. 2006. Filsafat Pendidikan Barat dan Filsafat Pendidikan Pancasila Wawasan Secara Sistematik. Yogyakarta: Amus. Gunawan M. I. 2010. “Aristoteles dan Buddha”. Harian Kompas, Selasa, 29 Juni 2010. Halaman 6. Barthers, R. 2007. Petualangan Semiologi. (S.A Herwinarto Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hoed, B.H. 2008. Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya. Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Bahasa, UI Depok. Bria, E. 2008. Jika Ada Tuhan Mengapa Ada Kejahatan Percikan Filsafat Whitehead. Yogyakarta: Kanisius. Keraf, A.S. dan M. Dua. 2001. Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Kanisius. Bose, A.C. 2000. Panggilan Veda. (I Wayan Maswinara Penerjemah). Surabaya: Paramita. Knight, G.R. 2007. Filsafat Pendidikan. (Mahmud Arif Penerjemah). Yogyakarta: Gama Media. 65 Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 43, Nomor 7, April 2010, hlm.56 - 65 Jalaluddin, H. dan A. Idi. 2001. Filsafat Pendidikan Manusia, Filsafat dan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group. Saraswati, S.C. 2009. Peta Jalan Veda. (Hira Gindwani dan Ni Putu Anggia Jenny Penerjemah). Denpasar: Media Hindu. Magnis-Suseno, F. 2009. Menjadi Manusia Belajar dari Aristoteles. Yogyakarta: Kanisisu. Singh, T.D. 2004. Seri Vedanta dan Sains Kehidupan dan Asal Mula Jagat Raya. (Tim Penerjemah). Bali:Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia. Pandit, B. 2005. Pemikiran Hindu Pokok-pokok Pikiran Agama Hindu dan Filsafatnya. (IGA Dewi Paramita Penerjemah). Surabaya: Paramita. Parsons, T. 1951. The Social System. Glencoe, III: Free Press. Pendit, N.S. 2005. Vedanta Percik-percik Renungan Swami Vivekananda Permata Warisan Filsafat dan Etos Kerja Modern. Denpasar: Penerbit Bali Post. Singh, T.D. 2007. Kehidupan dan Evolusi Spiritual. (Made Wardhana Penerjemah). Bali: Yayasan Institut Bhaktivedanta Indonesia. Sivananda, S.S. 2005. Pikiran Misteri dan Penaklukannya. Surabaya: Paramita. Sivananda, S.S. Penebar Ceritra Kebajikan. (I Made Aripta Wibawa Penerjemah). Surabaya: Paramita. Pendit, N.S. 2007. Filsafat Hindu Dharma Sad-Darsana Enam Aliran Astika (Ortodok). Denpasar: Bali Post. Sudharta, T.R. 2000. Sarassamuccaya Smerti Nusantara (Berisi Kamus Jawa Kuno-Indonesia). Surabaya: Paramita. Prabhananda, S. 2006. Agama Veda dan Filsafat. (I Nyoman Ananda Penerjemah). Surabaya: Paramita. Sudharta, T.R. 2001. Ajaran Moral dalam Bhagawad Gita. Surabaya: Paramita. Machwe, P. 2000. Kontribusi Hindu terhadap Ilmu Pengetahuan dan Peradaban. (Ida Bagus Putu Suamba Penerjemah). Denpasar: Widya Dharma. Suhatono, S. 2006. Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: ArRuzz. Surakhmad, W. 2009. Pendidikan Nasional Strategi dan Strategi. Jakarta: Kompas. Mittal, M. 2006. Pesan Tuhan untuk Kesejahteraan Umat Manusia Intisari Veda. (I Wayan Punia Penerjemah). Jakarta: Paramita. Tapasyananda, S. 2008. Filosofis dan Keagamaan Swami Vivekananda. (IGA Dewi Paramita Penerjemah). Surabaya: Paramita. Much, R. 2008. “Teori Parsonian Dewasa Ini: Sebuah Pencarian Sintesis Baru”. Dalam A. Giddens dan J. Turner ed., Social Theory Today Panduan Sistematis Tradisi dan Tren Terdepan Teori Sosial. (Yudi Santoso Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tjahjadi, S.P.L. 2007. Tuhan Para Filsuf dan Ilmuwan dari Descartes sampai Withehead. Yogyakarta: Kanisius. Ricoeur, P. 2002. The Interpretation Theory Filsafat Wacana Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa. (M. Hery Penerjemah). Yogyakarta: IRCiSoD. Titib, I M. 1996. Weda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan. Surabaya: Paramita. Ricouer, P. 2006. Hermeneutika Ilmu Sosial. (M. Syukri Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wavana. Ritzer, G. 2003. Teori Sosial Postmodern. (M. Taufik Penerjemah). Yogyakarta: Kreasi Wacana. Sadullah, U. 2003. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta. Tapasyananda, S. 2008. Wejangan Filosofis dan Keagamaan Swami Vivekananda. (IGA Dewi Paramita Penerjemah). Surabaya: Paramita. Titib, I M. 2003. Menumbuhkembangkan Pendidikan Budhi Pekerti pada Anak (Perspektif Agama Hindu). Bandung: Gabesa Exact. Woodhouse, M.B. 2000. Berfilsafat sebuah Langkah Awal. (A.N. Permata dan P. H. Hadi Penerjemah). Yogyakarta: Kanisius. Zimmer, H. 2003. Sejarah Filsafat India. (Agung Prihantoro Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.