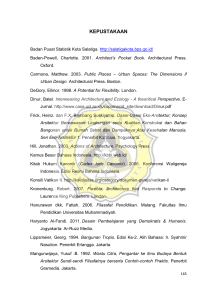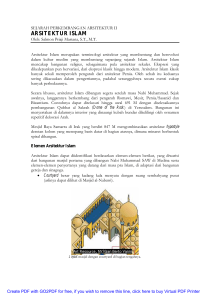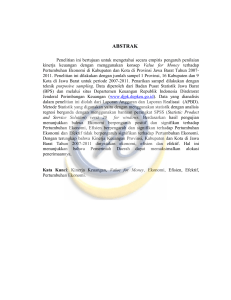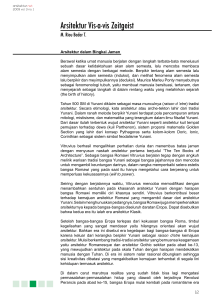bab viii kesimpulan dan saran
advertisement

BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN tneCpK[yon\ tancep kayon103 Dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati Manunggaling Kawula Gusti pada arsitektur Jawa’ dihasilkan beberapa konsekuensi yang tidak hanya berlaku pada ranah filsafat arsitektur tapi juga pada konsep perancangan arsitektural dan pemahaman ‘Jawa’. Konsekuensinya kesimpulan terbagi menjadi beberapa bagian baik arsitektur maupun non-arsitektur. 8.1. Konsekuensi Pemahaman Jawa Penetapan bahwa Surakarta dan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa atau yang lebih dikenal dengan Negarigung (Koentjaraningrat, 1994), perlu dicermati, sebab penetapan itu hanya berlaku pada pemahaman politikkebudayaan. Penggunaan pemikiran Koentjaraningrat tersebut tepat jika disadari betul bahwa alur telaahnya ada pada alur politik-kebudayaan. Dalam kasus arsitektural pada penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini terbukti Klaten dan Bantul mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ‘pusat’ dalam pemikiran filsafat arsitektur Jawa. Bahkan jika ditarik kepada kesimpulan yang ekstrim, tiap arsitektur Jawa adalah ‘pusat’ bagi sekelilingnya, karena di tiap karya arsitektur Jawa terdapat ‘perkawinan’ bapa-angkasa dan ibu-bumi. Tiap karya arsitektur Jawa adalah samudra manthan dan/atau axis mundi/the center of the world. 103 Adegan jejer yang dilakukan pada bagian akhir dari babak pathet manyura pada pagelaran wayang kulit purwa. Adegan ini dapat dikatakan sebagai adegan penutup dari seluruh rangkaian cerita yang dibawakan dalang pada suatu pagelaran wayang kulit purwa. Pada adegan ini, ditampilkan adegan hadirnya sejumlah besar tokoh-tokoh wayang yang menjadi pemenang perang brubuh secara lengkap. Setelah itu, dalang akan melakukan antawacana / dialog pendek sebagai penutup cerita. Dan selanjutnya, wayang gunungan atau kayon akan diambil oleh dhalang dan ditancapkan di tengah-tengah geber/ kelir wayang (layar wayang) menandakan bahwa seluruh pagelaran telah selesai. Dari peristiwa penancapan wayang berbentuk gunungan atau kayon oleh dalang inilah kemudian timbul istilah tancep kayon. (Palgunadi, 2002, p. 166) Jadi perlu kehati-hatian dan kecermatan memahami Negarigung dalam penelitian arsitektur Jawa, apakah hal itu sesuai dengan bahasan dan alur pikir yang ingin dibangun atau perlu membuat batasan teritori tersendiri. 8.2. Konsekuensi Filsafat Jawa Tinjauan kritis juga berlaku pada tataran filsafat Jawa. Disertasi Zoetmulder dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris sama sekali tidak menyebut tentang Manunggaling Kawula Gusti. Pemahaman tersebut muncul pada bab VII yang menjabarkan kondisi bersatunya antara Tuhan dan manusia. Namun saat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat Manunggaling Kawula Gusti itu muncul sebagai judul utama. Tidak hanya dari penambahan kalimat saja pada bagian judul buku, disertasi Zoetmulder memahami ‘perpaduan/penyatuan’ antara Tuhan dan manusia sebagai sebuah keadaan/tempat yang statis, atau dengan kata lain kondisi itu tercapai saat manusia telah meninggal (terekspresi dalam kata mulih). Dua hal ini yang kemudian menjadi catatan tersendiri dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini. Hal tentang penambahan kalimat Manunggaling Kawula Gusti ternyata pada Serat Dewaruci, sebab tidak ditemukan kata manunggaling dalam serat tersebut, yang ada adalah Pamoring. Jika kemudian diperhatikan lebih kritis, penelitian Zoetmulder berada pada ranah filsafat teologis. Konsekuensinya, perlu dilakukan ‘penterjemahan’ dari filsafat teologis ke filsafat arsitektural. Dengan demikian dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini digunakan kata pamoring yang mempunyai kaitan dengan pemahaman amor/awor dan makna dari omah. Hal lain yang menjadi konsekuensi pada filsafat Jawa adalah kisah Dewaruci mempunyai kesetaraan makna dengan kisah samudra manthan dan tantrisme, ketiganya berbicara tentang dialektika monistik. Penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini memang tidak menelusur secara sejarah atau mengkaji secara arkeologi budaya, namun yang perlu menjadi catatan adalah adanya kesamaan ide dasar dari ketiganya. 8.3. Konsekuensi Filsafat Arsitektur Pada bagian ini akan disimpulkan konsekuensi yang terjadi pada filsafat arsitektur, baik filsafat arsitektur Heidegger maupun filsafat arsitektur Jawa. 8.3.1. Filsafat Arsitektur Heidegger Filsafat Arsitektur Heidegger merupakan karya dari Heidegger itu sendiri, bukan hasil dari interpretasi pemikiran filsafat ke dalam ranah arsitektur. Filsafat arsitektur memang juga mampu dikembangkan dengan melakukan interpretasi pemikiran filsafati ke dalam ranah arsitektur, seperti dari pemikiran Derrida yang diinterpretasi oleh Peter Eisenmann, atau pemikiran Deleuze-Guattari yang diinterpretasi oleh Greg Lynn. Namun filsafat arsitektur dari Heidegger adalah buah pikir dari Heidegger bukan hasil dari interpretasi. Pemikiran Heidgger juga – diduga - terpengaruh dengan pemikiran filsafati ‘timur’ dengan kemampuan pemikiran metafisikanya. Filsafat arsitektur Heidegger bukan hanya Building Dwelling Thinking, tapi terdapat juga di The Things dan ….Poetically, Man Dwells…. Konsekuensinya perlu dirumuskan ulang filsafat arsitektur Heidegger yang menampung pemikiran dari ketiga kertas kerja tersebut. Filsafat arsitekur Heidegger dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Bangunan Idea (The Things’ Building): pemahaman mendasar bahwa ‘bangunan’ bukan saja dipandang secara ‘fisik’ tapi juga ‘meta-fisik’. ‘Bangunan’ bisa berupa konstruksi berpikir yang menampung idea/gagasan. ‘Bangunan’ dalam pemikiran Heidegger adalah sebuah ‘kelowongan’ yang mampu menampung sesuatu. ‘Bangunan’ bukanlah semata fisik berbatas, tapi sebuah potensi penampungan yang mengumpulkan dan menyatukan (das Verweilen). b) Hunian Empat Dimensi (The Fourfold Dwelling). ‘Bangunan Idea’ tersebut antara lain menampung ‘idea/gagasan’ tentang ‘berhuni’. Telah dijelaskan di atas bahwa ‘kelowongan’ yang terdapat dalam ‘bangunan idea’ tersebut bersifat mengumpulkan dan menyatukan. Dalam ‘hunian empat dimensi’ inilah Heidegger mengumpulkan dan menyatukan 4 unsur yaitu ‘bumi/earth’; langit/sky; ke-manusiaan/mortal dan ke-tuhan-an/divinities. c) Berpikir Puitik (Poetically Thinking). Dengan gagasan ‘mengumpulkan dan menyatukan’ empat unsur dalam ‘bangunan idea’-nya Heidegger tidak hanya berpikir rasional, tapi juga berpikir secara intuitif. Kemampuan berpikir rasional-intuitif inilah yang diduga terpengaruh dari pemikiran ‘timur’. Rasional-intuitif merupakan cara berpikir Heidegger secara puitik untuk menunjukkan kebenaran hakiki suatu hunian/dwelling. Heidegger menulis karya filsafat yang kemudian dikenal dengan Being and Time (dalam bahasa Jerman berjudul‘Sein und Zeit’), karya inilah yang kemudian dikenal sebagai karya masterpiece dari Heidegger. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa ternyata filsafat Being and Time bukanlah kerja Heidegger yang utuh dan sempurna, sebab karya tersebut adalah karya yang ‘belum selesai’. Heidegger hanya menyelesaikan satu bagian – itupun belum sempurna karena masih menyisakan satu divisi lagi – dari tiga bagian yang direncanakan. Namun Heidegger cukup rajin menulis dan banyak tulisan-tulisannya dalam bentuk makalah kuliah atau seminar. Karena bentuknya yang cukup pendek dan ringkas, penelitian tentang filsafat Heidegger – terutama untuk filsafat arsitektur – perlu memperhatikan karya-karya lain untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap pemikiran Heidegger akan suatu hal. 8.3.2. Filsafat Arsitektur Jawa Filsafat Arsitektur Jawa (yang bersumber pada filsafat Pamoring Kawula Gusti) tidak berbicara pada tataran material/fisik, tapi pada tataran nonmaterial/meta-fisik atau juga sering juga disebut tan-ragawi, namun lebih khusus lagi pada aspek spiritual. Namun cara berpikir filsafat arsitektur Jawa terjadi secara gradual/ bertahap. Hal ini yang dipahami sebagai dialektika filsafat arsitektur Jawa. Tahapan itu adalah : a) Dialog Dualistik-Kontras, yaitu dialog yang lebih berada pada ranah praksis keilmuan. Dialog ini lebih mengutamakan perbedaan. Dengan acuan pada pemikiran Heidegger, dialog dualistik-kontras lebih mengutamakan rasional dengan cara pemahaman ‘mata’ atau ‘pembacaan’ fisikal/material. b) Dialog Dualistik-Mediatif, yaitu dialog yang berada pada ranah teoritikal keilmuan. Tataran ini lebih mementingkan ‘kesamaan’. Heidegger memahami ‘ranah’ ini melalui pemahaman intuitif. Di sini bukan lagi memahami ‘yang hadir’ tapi sesuatu yang ‘tidak hadir’ di balik ‘kehadiran’, atau sering disebut dengan pemahaman meta-fisik. c) Monolog Monistik-Spiritual, adalah tingkat tertinggi yang berada pada ranah filsafati keilmuan. Pada tataran inilah Heidegger tidak/belum mampu ‘mengapainya’. Monolog monistik-spiritual adalah suatu pemahaman akan adanya ke-tunggal-an/keperpaduan dari segala yang berpasangan. Alat pahamnya bukan lagi rasional dan intuitif (cara ‘baca’dengan alat paham mata) tapi rasa/pure feeling (cara ‘dengar’dengan alat paham ‘telinga’). Arsitektur Jawa mengenal tipe atap tajug yang melingkupi suatu tempat ‘khusus’ (biasanya cungkup makam atau atap tempat ibadah – Masjid), namun ‘jejak/trace’ tersebut terlacak juga pada hunian orang Jawa yaitu dengan elemen struktur ander. Sedangkan dalam pemahaman sumbu horisontal, monolog monistik-spiritual terjadi di bagian terjauh, yaitu di senthong tengah pada hunian arsitektur Jawa omah; atau pada Masjid Agung jika pada kompleks Masjid Agung (Surakarta dan/atau Yogyakarta). Tahapan berpikir di atas, terutama pada monolog monistik-spiritual merupakan pembeda sekaligus sebagai aspek yang belum/tidak dibahas dalam filsafat arsitektur Heidegger. Filsafat arsitektur Jawa tidak hanya ‘mengumpulkan dan menyatukan’ tapi lebih pada proses ‘perkawinan’. Jika dalam Heidegger dikumpulkan 4 dimensi – yang sebenarnya hanyalah dialog dualistik – maka dalam filsafat arsitektur Jawa ‘meng-kawin-kan’ dua sumbu, yaitu dua sumbu horisontal – manusia dengan manusia; dan manusia dengan alam – serta satu sumbu vertikal yaitu antara manusia dengan Sang Pencipta. ‘Pengumpulan dan penyatuan’ tidak membawa dampak generatif bagi ‘penghuni’ arsitektural. Namun dalam arsitektur Jawa, ‘perkawinan’ dua sumbu tersebut membawa dampak bagi ‘penghuninya’ yaitu ‘anak’ yang berwatak vertikal, mengacu pada filsafati Sangkan Paraning Dumadi (kesadaran akan dari mana asal dirinya dan kemana dia akan kembali) dan watak ‘horisontal’, yang mengacu pada nilai filsafati Memayu Hayuning Bawana (kesadaran akan tugas untuk memperindah kehidupan di dunia). Pada saat bersamaan arsitektur Jawa menjadi sarana ‘pengingat/reminder bagi orang Jawa terhadap nilai-nilai filosofi yang ada dalam kehidupan mereka. Dengan demikian arsitektur Jawa juga mengandung dan menyimpan nilai-nilai spritualitas dalam elemen-elemen arsitekturnya. 8.4. Konsekuensi Arsitektur Bagian ini berbicara tentang konsekuensi pada tataran praksis arsitektural, yaitu konsekuensi pada konsep perancangan dan konsekuensi pada aplikasi. 8.4.1. Konsekuensi Konsep Perancangan Konsep dwelling dari Heidegger mempunyai konsekuensi bahwa tidak hanya mengumpulkan fourfold dalam karya arsitektur tapi mempunyai dimensi preservation/ pemeliharaan. Dengan demikian penerapan konsep dwelling dalam arsitektur mempunyai kewajiban untuk melestarikan alam sekelilingnya. Heidegger memang hanya berbicara bumi-langit; kemanusiaan-ketuhanan, namun makna dari empat elemen tersebut sangat luas. Bumi tempat manusia hidup harus dijaga dan dipelihara supaya tidak mempengaruhi keberadaan langit – dan ini yang bisa dikatakan aspek mistik dari Heidegger – dan keberadaan dan keberlangsungan ketuhanan. Konsep manjing dari filsafat arsitektur Jawa mempunyai konsekuensi juga. Konsep manjing tidak hanya sekedar mengumpulkan dan memelihara tapi mempunyai konsekuensi pada aspek generatif / berkembang biak dalam proses perkawinan yang bertujuan pada ‘keberlanjutan/sustainable’, keberlangsungan proses kehidupan. Konsep manjing adalah konsep yang memahami sebuah proses kebaharuan dalam kehidupan, sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Dimensi konsep ini adalah sumbu horisontal – tercermin dalam filsafat memayu hayuning bawana – dan sumbu vertikal – yang tercakup dalam filsafat sangkan paraning dumadi. Dengan kata lain, penerapan konsep manjing merupakan pertanggungjawaban manusia Jawa terhadap alam sekelilingnya dan kepada Sang Maha Peng-ada. 8.4.2. Konsekuensi Aplikasi Arsitektural Konsekuensi aplikasi arsitektural dalam sudut pandang filsafat arsitektur Heidegger tidak banyak hal baru yang bisa disimpulkan, karena hal itu telah disajikan dengan sangat tepat dalam karya Peter Zumthor. Kepekaan memahami site dan potensinya, serta keputusan arsitektural yang demikian detail menunjukkan pemahaman yang luar biasa terhadap pemikiran Heidegger. Totalitas tersebut juga tercermin dalam buku-buku yang ditulis oleh Zumthor yang merupakan aplikasi teori arsitektural dari pemikiran Heidegger. Bahkan tidak berhenti pada hal itu saja, Zumthor juga memilih bekerja di kota Haldenstein, sebuah kota kecil di Pegunungan Alpen di Swiss, bersama sebuah tim kecil terdiri dari 15 orang104. Pemilihan hunian Zumthor tersebut setara dengan pondok Heidegger di Todtnauberg. Di sisi lain, karya Adi Purnomo yang ‘terbaca’ secara pemahaman filsafat arsitektur Heidegger dan ‘terdengar’ dalam pemahaman filsafat arsitektur Jawa, membuktikan bahwa karya kontemporer arsitek Indonesia mempunyai kemampuan untuk ‘terbaca’ sekaligus ‘terdengar’. Karya arsitektur memang mempunyai kemampuan yang multitafsir, namun saat karya arsitektur mampu dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda (‘manca’ dan ‘jawa’), pada saat itulah karya tersebut mempunyai nilai lebih. Kehadiran karya Adi Purnomo juga sebagai konsekuensi definisi ‘Jawa’ yang mengacu pada kualitas kepribadian. Arsitektur ‘Jawa’ tidak lagi terpaku pada ‘joglo’ atau ‘limasan’ tapi menembus ruang dan waktu, sebab yang dipahami bukan lagi fisik tapi ‘semangat’ ke-Jawaannya105. Dengan demikian ke-ego kesukuan menjadi ‘luntur’, sesuai dengan makna dari pernyataan berikut: luwih jawa tinimbang wong jawa. Sebuah pernyataan yang menembus batas-batas ke-suku-an dan lebih mendepankan mental/kualitas hidup kepribadian individu. 104 Sumber: http://www.pritzkerprize.com/laureates/2009/bio.html Seperti yang didengungkan oleh Prijotomo dan Galih W. Pangarsa bahwa ‘arsitektur tradisional’ sudah mati. Arsitektur Nusantara selayaknya mengikuti jaman dan perkembangan masa (arsitektur nusantara mengkini). 105 8.5. Saran [golek\ golek106 Sikap sombong yang amat tidak terpuji jika beranggapan bahwa semua aspek arsitektural Jawa telah terjawab dalam disertasi ini. Ada begitu banyak ‘catatan kritis’ yang harus dilanjutkan penelitiannya. Dari sekian banyak ‘catatan’ yang tertinggal dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini adalah sudut tinjau yang digunakan. Sudut pandang penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini berada pada ranah filsafat ke ranah arsitektur, sehingga banyak pemahaman yang bersifat ideal dan teks book. Unsur fenomena yang terjadi di masyarakat ‘kurang’ mendapat perhatiaan. Inilah yang dapat diisi dalam penelitian lanjutan dengan dasar penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini. Dengan kata lain melakukan pemeriksaan terhadap pemahaman-pemahaman yang telah terungkap dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini dengan menghadirkan kenyataan-kenyataan lapangan. Kenyataan lapangan tersebut bisa berupa kenyataan lapangan di masa lalu atau bahkan pergeseran nilai yang terjadi di masa sekarang. Sudut tinjau ‘wayang’ mungkin akan semakin menarik dan jauh lebih lengkap jika kemudian yang dihadirkan adalah sosok ‘Semar’ sebagai salah satu tokoh ‘asli’ hasil pemikiran orang Jawa (tidak terdapat dalam cerita Mahabharata atau Ramayana versi India atau versi ‘manca’ lain). Sosok ‘Semar’ sangatlah tepat dijadikan landasan awal pemahaman monistik-spiritual sebab dalam diri Semarlah terkandung ‘ke-dewa-an’ dan ‘ke-manusia-an’ (dalam pengertian tamsil); 106 Suatu adegan yang pada dasarnya sudah berada diluar babak pathet manyura dan sudah pula di luar babak pagelaran wayang kulit purwa, tetapi sering dimainkan oleh dalang setelah ia menyelesaikan seluruh pagelaran wayang kulit purwa. Adegan golek dilaksanan oleh seorang dalang wayang kulit purwa menggunakan wayang golek, yang kemudian disingkat penyebutannya menjadi golek. Istilah golek berarti boneka. Dalam hal ini wayang yang dimainkan oleh dalang berbentuk wayang golek dan menggambarkan seorang penari wanita, lengkap dengan riasan dan pakaian tarinya. Tujuan dari adegan ini adalah untuk menyuruh penonton ‘mencari makna dan hakikat inti cerita pada pagelaran wayang kulit purwa’ yang telah dibawakan sang dalang. Istilah golek dalam bahasa Jawa mempunyai dua pengertian yang berbeda. Pertama, istilah golek dapat diartikan sebagai boneka. Kedua, istilah golek dapat juga diartikan sebagai mencari. Kalimat golekana atau galeka berati carilah. Rupanya, sejumlah dalang ingin mengatakan dengan menggunakan bahasa sandi/bahasa perlambang, bahwa seseorang yang telah menonton pagelaran wayang kulit purwa seharusnya bisa mencari dan menemukan berbagai hikmah, pelajaran hidup, filsafat, atau wejangan yagn dikandung dalam seluruh rangkaian cerita wayang yang telah dibawakan oleh dalang. (Palgunadi, 2002, p. 167) bukan laki bukan perempuan; tidak menangis, tidak tertawa serta perwujudan dari liring sepuh sepi hawa, awas roroning atunggil (KGPAA Mangkunagoro IV, 1975). Secara arsitektural juga dikenal dengan tipe Joglo Semar Tinandhu, Limasan Semar Tinandhu, Limasan Semar Pinondhong dan Rumah Kampung Semar Pinondhong, juga terdapat tipe atap untuk Masjid yaitu: Tajug Semar Sinongsong, Tajug Semar Sinongsong Lambang Gantung dan Tajug Semar Tinandhu (Hadiwidjojo & Prijotomo, 1993). Pertanyaan mendasar mengapa elemen atap tersebut memakai sebutan ‘Semar’ dalam tipe atap yang digunakan? Apakah ada kaitannya dengan monistik-spiritual? Hal-hal itulah yang belum bisa terjawab tuntas dalam penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini. Sebuah peluang ‘penelitian’ lanjutan. Hasil penelitian ‘konsekuensi filsafati’ juga bisa di-seret ke ranah urban planning. Pemahaman Santoso terhadap kota-kota di Jawa (Santoso, 2008) dapat menjadi ‘teori pembanding’ terhadap monolog monistik-spiritual, dengan pertanyaan mendasar apakah dalam pemahaman kota Jawa terdapat aspek spirtual? Asumsinya jika monistik menjadi nilai filsafati yang ada dalam kehidupan orang Jawa, maka segala aspek ‘bentukan fisik’ akan mengacu pada nilai tersebut, termasuk dalam perencanaan kotanya. Aspek lain yang bisa diangkat dengan dasar penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini adalah pada kesetaraannya terhadap kebudayaan di Indonesia/nusantara yang berbasis pada kebudayaan agraris. Apakah monistikspiritual juga terjadi pada bentukan arsitektural pada kebudayaan berbasis agraris? Atau bisa juga diperluas hingga suku bangsa berbasis maritim, seperti Bugis yang mengenal posi’bola, sebagai tiang induk dalam hunian suku Bugis (Arifuddin & Darjosanjoto, Vol.3. No.2. March, 2011, Part IV). Dan masih banyak aspek yang bisa dikembangkan lagi. Saran-saran diatas merupakan jabaran dari peluang-peluang penelitian lanjutan. Saran tersebut disampaikan sebagai sebuah konsekuensi manfaat penelitian yang membuka wawasan baru di bidang penelitian arsitektur. Kumpulan saran yang berupa kumpulan topik penelitian tersebut seakan memberi kesan bahwa penelitian ‘konsekuensi filsafati’ ini belum selesai dan hanya memunculkan topik penelitian baru. Pada kenyataannya saran itu dimunculkan karena memang ‘ruang lingkup’ penelitian arsitektural di bidang filsafat arsitektur belum banyak dilakukan sehingga menimbulkan kesan tersebut. Inilah lahan garapan yang begitu luas dan belum tergarap dengan baik.