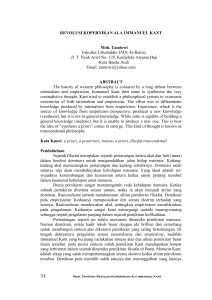imajinasi dan transendensi: pembacaan destruktif heidegger atas
advertisement

IMAJINASI DAN TRANSENDENSI: PEMBACAAN DESTRUKTIF HEIDEGGER ATAS DOKTRIN SKEMATISME KANT Skripsi Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai Gelar Sarjana Filsafat Islam Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Diajukan oleh Adry Nugraha NIM: 0033118781 JURUSAN AQIDAH-FILSAFAT FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M DAFTAR ISI Kata Pengantar .......................................................................................................... iii Daftar Isi .................................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG MASALAH .................................................... 1 B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH .......................... 5 C. TUJUAN PENELITIAN ...................................................................... 7 D. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 8 E. METODE PENELITIAN ..................................................................... 9 F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN ....................................................... 9 BAB II GAGASAN TRANSENDENSI DALAM KANT DAN HEIDEGGER DAN PEMBACAAN DESTRUKTIF ATAS “CRITIQUE” ........................................................................................... 11 A. TRANSENDENTALISME KANT DALAM “CRITIQUE OF PURE REASON” ............................................................................................. 13 1. Sekilas Biografi Hidup dan Karya Immanuel Kant ......................... 13 2. “Kritik Rasio Murni” sebagai Filsafat Transendental ...................... 14 3. Transendensi Subjek dalam Momen Sintesis Murni: Analisis Skema (Skematisme) dan Peran Imajinasi .......................................... 20 B. MARTIN HEIDEGGER: TRANSENDENSI SEBAGAI PEMAHAMAN ADA ......................................................................... 27 1. Sekilas Biografi Hidup dan Karya ................................................... 27 2. Transendensi atau Eksistensi dan Gagasan Destruksi .................... 28 3. Destruksi Heidegger atas “Critique” Kant: Sebuah Tinjauan Umum .................................................................................................. 34 VI BAB III DESTRUKSI SKEMATISME: MEMBACA ULANG RELASI ESENSIAL ANTARA IMAJINASI, INTUISI WAKTU DAN RASIO MURNI ....................................................................................... 39 A. WAKTU DAN IMAJINASI TRANSENDENTAL: PEMBACAAN KE ARAH TEMPORALITAS TRANSENDENSI ........................... 40 1. Representasi Waktu dalam Tiga Horizon Waktu: Imajinasi Transendental sebagai Asal Mula Waktu ............................................ 43 2. Representasi Waktu sebagai Keseluruhan: Waktu sebagai Dasar bagi Imajinasi Transendental (Temporalitas) ...................................... 46 B. IMAJINASI TRANSENDENTAL DAN KEDUDUKAN RASIO DALAM DESTRUKSI HEIDEGGER ................................................ 48 C. IMAJINASI TRANSENDENTAL DAN GAGASAN TENTANG TRANSENDENSI TERBATAS .......................................................... 53 D. IMPLIKASI KONSEP TRANSENDENSI HEIDEGGER TERHADAP PEMIKIRAN ETIKA DAN KEAGAMAAN ............... 58 1. Destruksi atas “Critique” sebagai Ontologisasi Pemikiran Kant: Konsekuensi Penting dalam Pemikiran Etika ...................................... 59 2. Transendensi dan Kecenderungan Religius: Pemahaman Ada sebagai Efek Ketidakhadiran ............................................................... 64 BAB IV PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................... 70 A. KESIMPULAN .................................................................................... 70 B. REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN LEBIH LANJUT …….... 72 DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 75 VII iii KATA PENGANTAR Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengizinkan penulis merampungkan skripsi ini. Sebagaimana kerja-kerja ilmiah lain, skripsi ini berisikan pembahasan tentang sesuatu yang sebenarnya bukan hal asing. Tapi terkadang orang menjadi kehilangan perhatian terhadap sesuatu yang telah begitu akrab, sehingga ketika diungkapkan, ia menjadi tampak asing. Yang asing, namun sekaligus akrab, yang penulis maksud di sini adalah fenomena transendensi. Ia akrab karena setiap aktivitas pemahaman kita selalu ditandai oleh fenomena ini, namun menjadi asing ketika ia berusaha ditegaskan (asserted) secara reflektif atau teoritis. Dalam Islam, sebuah ajaran di mana hati kita tinggal di dalamnya, kita dilatih untuk menjadi akrab dengan sesuatu yang transenden dan asing. Allah, malaikat, iblis, surga, neraka adalah transenden dan “asing”. Semua itu berusaha diakrabkan karena kita, demikian Islam mengajarkan kepada kita, selalu berada dalam determinasi atau pengaruh hal-hal asing itu (petunjuk Allah, pembagian kerja para malaikat, godaan iblis, atau harapan akan kebahagiaan sempurna di surga), terlepas manusia mengakuinya atau tidak. Untuk mengakrabkan yang asing itu, Islam pada saat yang sama melatih kita untuk menjadi asing terhadap sesuatu yang akrab—misalnya dengan bertanya bagaimana: Kita diajak berpikir tentang bagaimana kehidupan itu muncul dari kematian (misalnya, manusia yang bermartabat muncul dari setetes air yang hina) atau bagaimana segala sesuatu itu memiliki ukuran-ukuran yang proporsional dan akurat. Dalam skripsi ini, penulis tidak hendak membahas konsep transendensi dalam Islam, tetapi konsep transendensi dua pemikir Eropa yang terletak bermil- iv mil jauhnya dari kehidupan Islam. Mungkin saja konsep transendensi dua pemikir ini tidak memiliki kaitan sama sekali dengan konsep transendensi dalam Islam. Namun demikian, fenomena transendensi adalah fakta universal. Universal bukan karena isinya tetapi bentuknya. Setiap kebudayaan mungkin memiliki ajaran atau penafsiran yang berbeda tentang apa itu yang transenden, tetapi mungkinnya penafsiran-penafsiran ini berdasar pada semacam struktur yang sama. Struktur dari fenomena transendensi inilah yang berusaha penulis bahas dalam skripsi ini. Menurut penulis, ada keuntungan tersendiri membahas struktur transendensi dengan melacaknya pada para filsuf Eropa, terutama yang lahir di zaman modern, karena konsep transendensi yang dibangunnya adalah hasil pergulatan dengan berbagai perubahan orientasi dan pergeseran nilai masyarakat Eropa, suatu perubahan yang lambat laun juga mulai dirasakan oleh kita, orang-orang yang tinggal di Timur. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Tatang Haetami dan ibunda Yayat Khoeriyah atas dukungannya dan kesabarannya menunggu detikdetik terakhir masa kuliah penulis. Kemudian kepada Dr. H.M Amin Nurdin M.A. (Dekan Fakultas Ushuludin), Drs. Agus Darmaji M.Fils. (Ketua Jurusan AqidahFilsafat), Drs. Ramlan A Ghani (Sekretaris Jurusan Aqidah-Filsafat), dan Dr. Fariz Pari, M.Fils., selaku pembimbing skripsi, penulis ucapkan terima kasih atas kebaikannya meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak bisa penulis lupakan juga seluruh dosen Fakultas Ushuludin dan Filsafat atas jasa mereka yang telah menempa intelektualisme penulis. v Penulis juga berterima kasih kepada saudara-saudara tercinta yang juga turut menunggu dan banyak membantu dalam kerja ini: H. Muhammad Iqbal, Lc., Dzulfikar S.Pd., Silma Juwita A.Ma., Budi Haryanto S.Pd., Kemal Abdul Malik S.Ag., Nandang Nur Muhammad S.Ag, Eman, Abduh, Yanto, Mawan, Pendi, Angga, Atep, Bambang, dan Fatoni. Terakhir, namun tetap istimewa, penulis berterima kasih kepada teman-teman penulis: Akib, Saidiman, Cimong, Jejen, Seif, Dubun, Agus, Lilis, Evi, Hajid, Acun, Faat, Shaleh dan Shaleh, Nugi, Zaim, Iqbal Hasanudin, Bana dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan. Mereka adalah teman-teman yang menyenangkan. Semoga skripsi ini secara khusus bermanfaat untuk mereka, untuk dikomentari secara kritis atau mungkin dibantah sama sekali. Ciputat, Desember 2008 ADRY NUGRAHA 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Di sepanjang sejarahnya, manusia tidak pernah berhenti berikhtiar menafsirkan fenomena-fenomena transendensi yang mereka saksikan. Fenomena transendensi yang saya maksudkan di sini merujuk pada dua hal: ia bisa merujuk pada “sesuatu yang tersembunyi di seberang” penampakan yang terlihat, bisa juga merujuk pada semacam “kemampuan untuk melampaui apa yang tampak sebagai fenomena”—untuk yang terakhir ini saya menyebutnya kapasitas transendental. Dalam kebudayaan-kebudayaan primitif, fenomena transendensi mula-mula disadari dalam peristiwa gerak atau adanya kehidupan. Dalam kepercayaan animisme misalnya, terdapat penafsiran bahwa di balik sesuatu yang hidup atau yang bergerak, ada sesuatu yang tersembunyi yang memungkinkan gerak tersebut. Sesuatu yang tersembunyi itu ditafsirkan sebagai roh atau entitas-entitas spiritual yang karena ia hidup dan memiliki kehendak, maka manusia dianggap perlu untuk memberinya persembahan-persembahan. Penafsiran atas fenomena transendensi ini terus berlangsung, bahkan pada zaman modern di mana sains mulai tumbuh dan spekulasi-spekulasi mistis mulai ditransformasi ke dalam penyelidikan-penyelidikan rasional dan empiris (metafisika). Kita dapat memulainya dari Descartes (1596-1650). Sebagai bapak filsafat modern, Descartes memperkenalkan suatu metode penyelidikan yang belum pernah dilakukan oleh para filsuf sebelumnya, yaitu metode keraguan. Dengan metode keraguan, dia meragukan semua hal yang dia indera sebagai sesuatu yang sejati (self-evident). Dalam keraguannya dia mengatakan bahwa bisa 2 saja apa yang kita lihat, dengar dan rasakan ini adalah ilusi atau pantulan dari kenyataan yang sesungguhnya; bisa jadi apa yang kita lihat dan rasakan ini adalah tipuan sempurna dari sesosok roh jahat. 1 Semua hal yang tertangkap oleh indera, menurut Descartes selalu dapat diragukan dengan cara seperti ini; sebuah fakta yang menunjukkan bahwa pengalaman inderawi kita adalah sesuatu yang tidak kokoh, tidak sempurna dan senantiasa membutuhkan semacam fondasi yang ajeg. Hanya ada satu hal yang tidak bisa diragukan menurutnya, yaitu fakta “aku yang meragukan”. Kita dapat meragukan semua hal yang kita alami, tetapi “aku yang meragukan” itu sendiri bukanlah sesuatu yang dapat diragukan. Pada titik ini, Descartes sampai pada gagasan tentang “aku yang meragukan” sebagai “aku berpikir” (cogito). Menurutnya, substansi “aku berpikir” inilah yang merupakan fondasi bagi pengalaman. Sebagai fondasi yang self-evident, substansi “aku berpikir” (res cogitans) bukanlah sesuatu yang berkeluasan sebagaimana dunia yang kita alami (res extensa); ia melampaui (transcende) atau berada di seberang (meta) kenyataan inderawi (physica). 2 Kita dapat menyebut cogito Descartes sebagai “yang transenden”. Bersamaan dengan lahir dan berkembangnya sains-sains positif, pandangan Descartes di atas selanjutnya memancing perdebatan baru di wilayah epistemologi dan metafisika. Kita dapat menyebut filsuf-filsuf seperti Leibniz, Kant, Hegel, Hume, atau Husserl yang masing-masing melahirkan mazhabmazhab baru pemikiran. Namun demikian, perspektif cogito Descartes rupanya 1 Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), h. 26 2 Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997). H. 30. lihat juga David West , An Introduction to Continental Philosophy, (Cambridge: Polity Press, 1996), h. 13 3 masih terus dipertahankan sehingga pemikiran mereka tampak seperti sebuah penafsiran ulang konsep cogito tersebut. 3 Upaya-upaya manusia untuk menafsirkan “yang transenden” barangkali tidak dengan sendirinya menegaskan adanya “yang transenden” sebagai substansi rahasia yang menjadi fondasi kenyataan--entah itu subek cogito, roh absolut, tabula rasa, atau pun ego transendental--, tetapi jelas bahwa munculnya penafsiran semacam ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kapasitas transendental. Dengan kata lain, adanya penafsiran ini menunjukkan bahwa manusia mampu melampaui (transcend) apa yang hadir sebagai fakta. Menurut saya, kapasitas semacam ini penting dan menarik untuk diselidiki. Pasalnya, kapasitas transendental ini tidak hanya terimplikasi dalam peristiwa penafsiran tentang adanya “yang transenden” tetapi juga ditunjukkan dalam peristiwa pemahaman sehari-hari manusia. Pemahaman manusia adalah sejenis kapasitas transendental. Ketika seorang penulis menulis sebuah karya dengan penanya, dia memahami apa itu pena, buku, meja tempat dia menulis, dan pemahaman atas dirinya sebagai seorang penulis. Aspek transendentalnya terletak pada kenyataan bahwa pena, buku, atau pun meja yang hadir dalam indera-indera sensorisnya sebagai kumpulan sensasi berupa warna, bentuk, kepadatan, bau, atau pun keluasan itu tidak hadir dalam kesadarannya sebagai sensasi-sensasi inderawi yang berserakan (chaotic), melainkan “melampaui”-nya (transcend), yaitu sebagai “sesuatu” yang utuh, tertentu, dan dapat digunakan. 3 David West , An Introduction to Continental Philosophy, (Cambridge: Polity Press, 1996), h. 8-41 4 Jika kita mengartikan transendensi sebagai “kemampuan untuk melampaui”, kita juga akan menemukan bahwa transendensi memiliki dimensi keterarahan. Merujuk kembali pada contoh di atas, mungkinnya sang penulis memahami pena yang digunakannya sebagai sesuatu yang utuh, tertentu dan dapat digunakan, adalah karena pemahaman dia bukan hanya terarah pada sensasisensasi inderawi yang hadir dalam pikirannya, tetapi juga terarah pada “yang bukan sensasi-sensasi inderawi” atau, lebih tepatnya, pada yang “bukan-entitas” (non-entity). Dengan kata lain, kapasitas yang mengarahkan pikirannya pada nonentitas memungkinkan dia memahami sensasi-sensasi inderawi yang hadir kepadanya sebagai “entitas” yang tertentu. Di sini, kita karenanya dapat mendefinisikan fenomena transendensi lebih spesifik, yaitu sebagai keterarahan pada yang bukan-entitas (non-entity), yang karena bukan-entitas, ia tidak dapat didefinisikan. Tetapi, jika pengetahuan dimungkinkan oleh adanya keterarahan pada nonentitas yang tak terdefinisikan, maka apakah yang dapat kita bicarakan tentang non-entitas tersebut? Penyelidikan filosofis seperti apakah yang dapat dibangun untuk menunjukkan bahwa keterarahan pada non-entitas ini bersifat konstitutif terhadap pengetahuan akan entitas? Dalam pergulatan filsafat modern yang secara umum dipengaruhi oleh paradigma Cartesian, pertanyaan semacam ini hampir tidak ada sama sekali. Benar bahwa ketika Descartes meragukan representasi inderawi sebagai representasi yang mensyaratkan adanya fondasi self-evident, dia telah menangkap dimensi transendensi dalam pemahaman. Tetapi, segera setelah Descartes menegaskan fondasi itu adalah “aku berpikir” sebagai res cogitans (res = sesuatu/entitas) yang di dalamnya terkandung ide-ide bawaan (innate ideas), 5 hakikat transendensi sebagai keterarahan pada non-entitas menjadi luput dalam penyelidikannya. B. PEMBATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH Dalam skripsi ini, saya hendak mengulas pemikiran Heidegger tentang transendensi. Saya memilih Heidegger karena dalam filsafatnya, gagasan transendensi dikemukakan secara eksplisit. Dia mengatakan bahwa transendensi itu tidak lain adalah pemahaman Ada. Dimensi keterarahan transendensi pada non-entitas juga menjadi jelas dalam pemikirannya karena pemahaman Ada itu bagi Heidegger adalah pemahaman terhadap non-entitas. Ada (Being) adalah nonentitas (non-beings). Pemikiran Heidegger tentang Ada ini dapat ditemukan dalam karya utamanya, “Being and Time”, di mana dia mengungkapkan fenomena pemahaman Ada, karakter dan strukturnya. Namun demikian, dalam skripsi ini saya tidak mengulas pemikiran transendental Heidegger secara langsung, dengan semata-mata merujuk pada “Being and Time”, melainkan melalui pembacaan destruktifnya terhadap “Critique of Pure Reason” Kant. Destruksi adalah pembacaan yang berusaha mengeksplisitkan gagasan pemahaman Ada dalam suatu teks filosofis. Rencana pembacaan destruktif ini sebenarnya merupakan bagian integral dalam “Being and Time”, di mana Heidegger merencanakan destruksinya atas tiga tokoh utama dalam filsafat: Aristoteles, Descartes, dan Kant. Pembacaan destruktif Heidegger atas Kant dapat ditemukan dalam “Kant and the Problem of Metaphysics”, karya lain yang ditulis setelah “Being and Time”. Dalam buku ini, Heidegger menafsirkan filsafat Kant dalam perspektif pemahaman Ada. Kant sendiri memang mengatakan bahwa filsafatnya adalah 6 filsafat transendental, tetapi “filsafat transendental” yang dimaksud Kant di sini adalah penyelidikan filosofis tentang cara bagaimana subjek memiliki pengetahuan tentang objek. Terminologi “pemahaman Ada” Heidegger adalah sesuatu yang asing bagi Kant. Namun demikian, menurut Heidegger, gagasan pemahaman Ada sebenarnya selalu terimplikasi dalam setiap teks filosofis, dan tugas pembacaan destruktif adalah mengeksplisitkannya. Karena itu, tidak heran jika dalam “Kant and the Problem of Metaphysics”, Heidegger menafsirkan filsafat transendental Kant sebagai filsafat tentang pemahaman Ada. Cara pembacaan Heidegger ini memang membuat kita sulit membedakan mana pemikiran Kant dan mana pemikiran Heidegger. Tetapi ini memberi keuntungan tersendiri, karena Heidegger dengan demikian tidak hanya mempraktikkan suatu jenis pembacaan tetapi juga mengemukakan gagasan transendensinya secara lebih jelas dalam terminologi-terminologi tradisional yang lebih umum. Terkait dengan pembacaan destruktif Heidegger, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, Heidegger bertolak dari doktrin skematisme Kant untuk menemukan tesis tentang pemahaman Ada dalam pemikirannya. Doktrin skematisme sendiri adalah doktrin penerapan konsep-konsep pada objek-objek pengalaman, di mana terdapat tiga faktor pengetahuan yang terlibat dalam proses tersebut: intuisi, rasio, dan imajinasi. Kedua, bertolak dari pembacaannya atas beberapa problem dalam skematisme Kant, Heidegger menegaskan bahwa esensi transendensi (kapasitas transendental), atau yang dalam Kant disebut pengetahuan murni, terletak pada imajinasi transendental. Ketiga, karena imajinasi transendental merupakan faktor esensial dalam pembentukan pengetahuan murni, Heidegger melakukan pembacaan ulang terhadap konsep imajinasi tersebut dan 7 melihat kaitannya dengan rasio murni dan intuisi murni (waktu). Keempat, bersamaan dengan itu, Heidegger juga pada akhirnya mengkaji ulang konsep rasio murni dan intuisi murni (waktu) Kant dan dari sana menarik beberapa konsekuensi cukup penting dalam pemikirannya tentang transendensi sebagai pemahaman Ada. Tesis-tesis di atas adalah tesis-tesis hasil destruksi, yang terbentuk dari minat Heidegger terhadap tema transendensi, esensi, struktur, serta perannya dalam pembentukan pengetahuan manusia tentang objek atau dunia. Jika kita hendak menyederhanakan alur pembacaan destruktif Heidegger tersebut, kita dapat mengatakan bahwa pembacaannya itu bertolak dari doktrin skematisme dan berakhir pada konsepsi imajinasi transendental. Tentu saja, dalam destruksinya terdapat juga tema-tema lain yang menjadi target pembacaannya, tetapi itu dilakukan sejauh dalam kaitannya dengan imajinasi transendental; sebagai konsekuensi dari hasil pembacaannya atas konsep imajinasi. Karena itu, fokus ulasan tentang destruksi Heidegger atas Kant dalam skripsi ini diarahkan pada tema skematisme dan imajinasi transendental. C. TUJUAN PENELITIAN Dengan menjelaskan konsep transendensi dalam Kant dan Heidegger serta pembacaan destruktif atas pemikiran Kant, skripsi ini bertujuan: 1. Memahami fenomena dan struktur pemahaman transendental (kapasitas transendental) dengan merujuk pada pemikiran Kant dan Heidegger. 2. Memahami gagasan transendensi Kant dalam perspektif pembacaan destruktif Heidegger. 8 3. Mengulas tesis-tesis destruksi Heidegger atas doktrin skematisme Kant dan membandingkannya dengan tesis-tesis Heidegger dalam “Being and Time”. 4. Mempertimbangkan konsekuensi pembacaan destruktif tersebut dan kemungkinan penafsiran baru dari titik tolak pemikirannya. D. TINJAUAN PUSTAKA Barangkali telah banyak literatur-literatur berbahasa Indonesia yang mengulas secara khusus pemikiran Heidegger. Sepanjang pengetahuan penulis, literatur-literatur tersebut umumnya mengulas pemikiran Heidegger dalam Being and Time, yaitu, pemikiran tentang Dasein yang dimaksudkan Heidegger sebagai analisis eksistensial dalam rangka ontologi fundamental. Salah satu literatur yang mengulas pemikiran Heidegger di level ini adalah buku yang ditulis oleh Dr. Franky Budy Hardiman, Heidegger dan Mistik Keseharian: Suatu PengantarMenuju “Sein und Zeit” (Jakarta: Gramedia, 2003). Ada juga tulisan lain berupa esai yang mengulas pemikiran Heidegger yang dibandingkan dengan pemikiran Nietzsche, yaitu esai Fitzgerald K. Sitorus yang bertajuk Mengatasi “Surga”, Mengiyakan “Dunia”: Tentang Pembacaan Heidegger atas Nietzsche (Jurnal Filsafat Driyarkara: TH. XXVI NO 1). Ulasan yang sama juga ditemukan dalam bab terakhir buku Nietzsche yang ditulis oleh St. Sunardi (Yogjakarta: LKiS, 2001). Hingga saat ini, penulis belum menemukan buku atau pun esai berbahasa Indonesia yang secara khusus mengulas destruksi Heidegger terhadap doktrin skematisme Kant. Karena itu, ulasan tersebut dirasa perlu, dan skripsi ini ditulis untuk maksud tersebut, walaupun tentu saja ulasan saya tentang destruksi Heidegger atas Kant masih sangat terbatas. 9 E. METODE PENELITIAN Penulisan skripsi ini menggunakan metode analitis-kritis dan sepenuhnya didasarkan pada khazanah kepustakaan. Referensi-referensi yang diacu dalam skripsi ini dibagi ke dalam dua bagian: referensi primer dan referensi sekunder. Referensi primer adalah referensi yang ditulis langsung oleh pemikir yang tengah dikaji, baik dalam bentuk buku, esai, artikel, wawancara, surat, ataupun catatancatatan yang tidak terpublikasi. Sementara referensi sekunder adalah referensi yang ditulis oleh para komentator yang berisikan komentar atas pemikiran tokoh dalam salah satu segi atau berbagai segi gagasannya. Penelitian ini tidak berusaha membandingkan secara rigid pemikiran Immanuel Kant dengan Heidegger melainkan semata-mata mengulas pemikiran Heidegger. Karena itu, analisis akan terutama diarahkan pada pemikiran Heidegger dan pembacaannya terhadap Kant, bukan pemikiran Kant itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini, saya mengacu pada teknik penulisan skripsi yang dirumuskan oleh tim CEQDA, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) (Jakarta: CEQDA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007) F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Berdasarkan uraian tentang latar belakang, perumusan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, sistematika pembahasan akan disusun sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan skripsi yang berisikan latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 10 Bab II berisikan ulasan tentang konsep transendensi Kant dan Heidegger yang dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang destruksi Heidegger atas filsafat Kant. Bab III menguraikan isi dari destruksi Heidegger atas doktrin skematisme Kant. Saya menguraikannya dengan cara melihat hubungan antara imajinasi transendental, rasio murni dan intuisi murni, di mana imajinasi transendental ditekankan sebagai faktor esensial dalam pembentukan transendensi (atau sintesis murni). Dalam bab ini saya juga memasukkan beberapa konsekuensi dari destruksi Heidegger atas Kant, di samping tesis destruktif Heidegger lainnya yang menurut saya cukup penting untuk dibahas, yaitu, ide keterbatasan. Bab IV adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. 11 BAB II GAGASAN TRANSENDENSI DALAM KANT DAN HEIDEGGER DAN PEMBACAAN DESTRUKTIF ATAS “CRITIQUE” ∗ Titik singgung pemikiran Immanuel Kant dan Martin Heidegger dapat ditemukan dalam gagasan transendensi. Sebagaimana telah disinggung, kata transendensi merujuk pada kemampuan manusia “melampaui” (transcend) kenyataan faktual atau apa yang kita sebut sebagai “kesan-kesan” inderawi (impressions). 1 Baik Kant atau pun Heidegger berusaha mengungkapkan gejala transendensi dengan pendekatannya masing-masing. Kant mengemukakan gagasan transendensinya dalam perspektif hubungan representatif subjek-objek; objek dikenali oleh subjek ketika objek dalam wujudnya berupa kesan-kesan (impressions) dihadirkan pada subjek untuk dideterminasi. Aspek determinasi dalam proses representasi ini menurut Kant berciri transendental, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip normatif atau keniscayaan (necessity) yang tidak memiliki sumbernya pada pengalaman akan kesan-kesan, melainkan “melampaui”-nya (transcend). Heidegger sementara itu membangun gagasan transendensinya dalam perspektif pemahaman-Ada. Dia melakukan analisisnya dalam dua cara: analisis eksistensial dan destruksi sejarah ontologi. Yang pertama berusaha memeriksa fenomena ketersingkapan Ada (pemahaman Ada). Yang ∗ Dalam skripsi ini saya, “Critique of Pure Reason” ditulis singkat menjadi “Critique” sementara “Kant and the Problem of Metaphysics” ditulis singkat menjadi “Kant and the Problem”. 1 Tentang arti transendensi, lihat dalam Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 1118-1122. Transendensi berasal dari kata trans yang berarti seberang, atas, melampaui, dan scandere (memanjat). Bandingkan dengan kata eksistensi yang berarti “tampil keluar” (ex-sistere: ex: keluar, sistere: tampil) yang dalam tradisi filsafat sering disejajarkan dengan momen aktualitas. Ibid., h. 183-184 12 kedua (destruksi) adalah sejenis pembacaan yang menelisik impuls-impuls implisit dalam sebuah teks filosofis. Dengan pembacaan ini, Heidegger memperlihatkan ketakterhindaran gagasan pemahaman Ada dalam teks yang didestruksi dan, karenanya, analisis eksistensial menjadi sesuatu yang tak terhindarkan juga. Baik Kant atau pun Heidegger tumbuh dalam suasana pemikiran di mana paradigma-paradigma sains mulai diyakini dan metafisika, sebagai disiplin yang dulu pernah begitu akrab dengan doktrin-doktrin gereja, mulai dipertanyakan keabsahannya sebagai sebuah disiplin. Suasana pemikiran ini menjadi alasan mengapa Heidegger dan Kant meminati tema transendensi dalam filsafatnya. Heidegger, juga Kant, sepakat akan ketidakmungkinan metafisika ditegakkan sebagai disiplin ilmiah. Namun demikian, menurut mereka, setiap pertanyaan metafisis (kosmologis, psikologis, teologis) merupakan kecenderungan alamiah (natural propensity) yang merujuk pada struktur transendensi; struktur yang bukan hanya menjadi dasar bagi munculnya pertanyaan-pertanyaan metafisis, melainkan juga merupakan faktor konstitutif bagi mungkinnya penyelidikanpenyelidikan ilmiah dan ilmu-ilmu murni seperti matematika. Sains, metafisika dan seluruh bentuk pengetahuan atau pemahaman manusia, menurut Kant dan Heidegger, mengandaikan semacam kapasitas transendental. Dalam dua bagian pertama dari bab ini, saya akan menjelaskan secara garis besar bagaimana gagasan transendensi dikemukakan oleh Kant dan Heidegger. Selanjutnya, ulasan bab diakhiri dengan penjelasan tentang tesis-tesis dasar dalam pembacaan destruktif Heidegger atas konsep transendensi Kant, yang, sebagaima akan kita lihat, bermuara di sekitar doktrin skematisme. 13 A. TRANSENDENTALISME KANT DALAM “CRITIQUE OF PURE REASON” 1. Sekilas Biografi Hidup dan Karya Immanuel Kant Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Konigsberg Prusia Timur, sebagai anak keempat yang tumbuh dalam keluarga buruh sederhana. Keluarganya amat kental dengan ajaran Kristen Pietis Luterean. Pendidikan akademisnya dimulai ketika dia berusia delapan tahun. Dengan rekomendasi Franz Albert Schultz, seorang pendeta dan teolog yang amat dihormati ibunya, dia masuk ke Collegium Fredericianum pada tahun 1732. Di sekolah ini dia mengikuti studi-studi klasik dan bahasa Latin. 2 Karir pemikiran Kant bisa dikatakan lambat. Baru pada tahun 1770, Kant ditunjuk sebagai ketua bidang studi logika dan metafisika di universitas Konigsberg. Dalam pidato inagurasinya, dia menyatakan minatnya untuk merekonstruksi filsafat. Minat tersebut baru dibuktikan sepuluh tahun kemudian, tepatnya ketika Kant menginjak usia 50-an, dengan terbitnya Critique of Pure Reason. 3 Buku tersebut seringkali dianggap sebagai karya puncak Immanuel Kant. Menyusul terbitnya Critique, Kant menulis karya-karya berikutnya dalam rentang waktu yang relatif singkat, di antaranya: Prolegomena to Any Future Metaphysics (1782), Foundation for the Metaphysics of Morals (1785), Metaphysical Foundation of Natural Science (1786), Critique of Practical Reason 2 Ernst Cassirer, Kant’s Life and Thought, pen. James Haden (Yale University Press, 1981), h. 13-14 3 Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), h. 477 14 (1788), Critique of Judgment (1790), Religion Within the Limits of Reason Alone (1793), Toward Eternal Peace (1795), dan Metaphysics of Morals (1797). 4 Sejak awal karir pemikirannya atau dalam karya-karya yang ditulisnya, amat jelas bahwa Kant memiliki perhatian yang sangat besar terhadap metafisika. Minat ini kenyataannya mencirikan suasana pemikiran Jerman abad delapan belas, di mana metafisika mulai dipertanyakan dan berusaha diperbarui, fondasinya dan nilai pengetahuannya. 5 Terbitnya Critique of Pure Reason karenanya penting dilihat sebagai ikhtiar Kant mengklarifikasi problem-problem metafisika yang muncul pada zamannya, di samping problem-problem pengetahuan secara umum. 2. “Kritik Rasio Murni” sebagai Filsafat Transendental Umum diakui bahwa “Critique of Pure Reason” adalah karya monumental Kant yang menjelaskan posisi pemikirannya yang orisinal. Sebagaimana tergambarkan dalam judulnya, “Critique of Pure Reason” bermaksud menelisik perihal rasio. Ulasan tersebut oleh Kant disebut “kritik” karena Kant bermaksud menentukan batas-batas kemampuan rasio. 6 Kant membedakan antara kritik rasio dengan penggunaan dogmatis (dogmatic employment) rasio. 7 Dengan penggunaan dogmatis rasio Kant merujuk pada penyelidikan-penyelidikan metafisika pada zamannya, di mana rasio dipaksa untuk menerka-nerka (random groping) wilyahwilayah di luar pengalaman (supersensible realm). Dalam arti ini, kritik rasio bukan sejenis metafisika dalam “pengertiannya yang tradisional” karena rasio 4 Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), h. 477 5 Paul Guyer (ed.), The Cambridge Companion to Kant (Cambridge: Cambridge University Press), h. 1996 28-29 6 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 59 7 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 57 15 dalam “Kritik Rasio Murni” tidak digunakan untuk berspekulasi tentang wilayahwilayah di seberang fenomena atau penampakan melainkan untuk melihat dirinya sebagai fakultas pengetahuan yang berisikan prinsip-prinsip atau konsep-konsep a priori. Dalam kritik rasio murni, rasio digunakan untuk melihat rasio itu sendiri dengan cara menganalisis cara kerjanya, pembentukan konsep-konsepnya dan hubungannya dengan pengalaman. “Kritik Rasio Murni” oleh Kant disebut juga filsafat transendental di mana “transendental” berarti “tidak membicarakan objek” melainkan “cara”. 8 Dalam “Kritik Rasio Murni”, Kant tidak membicarakan “objek-objek” pengetahuan (mis, organ-organ tubuh, struktur materi, gerak benda, sifat-sifat cahaya, dan sebagainya) melainkan “cara” bagaimana objek-objek tersebut “diketahui” oleh subjek. Menurut Kant, cara subjek mengetahui objek adalah dengan merepresentasikannya. Representasi terjadi melalui intuisi dan rasio dan pengetahuan adalah representasi “sintetis” keduanya. Representasi intuisi adalah representasi data-data pengalaman kepada subjek secara langsung (immediate representation)—subjek berhubungan langsung dengan objek-objek pengalaman—sementara representasi rasio adalah representasi determinatif atas data-data yang dihadirkan intuisi untuk membentuk konsep-konsep—karenanya disebut representasi tak langsung (mediate representation). Sintesis, sementara itu, berarti momen diterapkannya konsep-konsep rasio pada objek-objek yang diintuisi. Sebagai filsafat transendental, apa yang menjadi perhatian Kant dalam “Critique”-nya adalah problem sintesis murni atau sintesis a priori ∗ , yaitu, sintesis 8 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 59 ∗ A priori berati “mendahului pengalaman” sementara “murni” berarti “tidak didapat dari pengalaman”. Dalam skripsi ini, dua istilah tersebut akan sering dipertukarkan dengan maksud 16 antara intuisi murni dan pikiran murni, karena menurut Kant dalam momen sintesis ini kita dapat mengetahui secara esensial “cara” subjek membentuk seluruh pengetahuannya (matematika, sains, bahkan metafisika), suatu tahap di mana subjek memperlihatkan kapasitas transendentalnya (transendensi). 9 Filsafat transendental Kant sebagai penyelidikan terhadap “cara” subjek mengetahui objek (modus pengetahuan subjek), dengan demikian, menemukan arah penyelidikannya pada kemungkinan sintesis a priori. Pemikiran Kant tentang sintesis a priori ini merupakan gagasan yang bisa dikatakan cukup baru pada masanya karena dalam pemahaman tradisional, sintesis selalu berarti a posteriori (setelah pengalaman atau hasil dari pengalaman); bahwa semua konsep yang diterapkan pada pengalaman (sintesis) adalah berasal dari pengalaman. Apa yang memungkinkan saya memahami konsep batu, misalnya, dan menerapkan konsep tersebut dalam pengalaman adalah karena saya sebelumnya telah terlatih atau terbiasa mengalami (melihat dan merasakan) berbagai jenis batu. Semua konsep itu berasal dari pengalaman, dan karenanya, tidak ada sintesis yang mendahului pengalaman. Dalam pandangan ini, rasio ditempatkan sebagai penerima data-data pengalaman (impressions) dan hanya berperan merefleksikan data-data tersebut menjadi ide-ide atau konsep-konsep—termasuk konsep kausalitas juga lebih merupakan refleksi rasio atas pengalaman; bukan sesuatu yang “secara niscaya” terjadi dalam pengalaman. 10 Salah satu konsekuensi fatal dari pandangan ini adalah bahwa semua gagasan keniscayaan, baik menyangkut “substansi” suatu yang sama. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 43 9 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 93 10 David Hume, An Enquiry Cocerning Human Understanding, dalam Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), h. 343-344 17 objek atau pun “relasi kausal” antar objek, karena tidak memiliki dasarnya dalam pengalaman, maka ide keniscayaan itu tidak lain semata-semata kebiasaan (custom). Pengalaman hanya memperlihatkan kepada kita fakta-fakta yang bergantian berupa kesan-kesan (impressions), tidak lebih dari itu. 11 Dalam “Critique”, Kant menolak pandangan di atas dan menunjukkan bahwa tidak semua konsep itu berasal dari pengalaman. Kant melakukan analisis “deduktif” dalam “Critique”-nya untuk memperlihatkan bagaimana ketika subjek merepresentasikan secara langsung objek-objek pengalaman melalui intuisi, momen representasi tersebut selalu diikuti oleh determinasi rasio yang cara kerjanya tidak ditentukan oleh pengalaman melainkan berdasarkan “aturanaturan” yang dia sebut konsep-konsep murni. Kant menyebutkan dua belas konsep murni dalam “Critique”-nya yang terhimpun dalam empat kategori: kesatuan, pluralitas, keseluruhan (kategori kuantitas), realitas, negasi, limitasi (kategori kualitas), substansi, kausalitas, komunitas (kategori relasi), kemungkinan, eksistensi, keniscayaan (kategori modalitas). 12 Konsep-konsep ini menurut Kant tidak didapat dari pengalaman (pure) karena tidak satu pun dari konsep-konsep ini menyatakan ciri fisik suatu objek. Sebaliknya, konsep-konsep ini mendahului (prior) pengalaman dan menjadi syarat (conditions of possibility) bagi terbentuknya pengetahuan. Kant sepakat bahwa pengalaman itu hanya mengajarkan kepada kita fakta-fakta (matters of fact). Namun, karena itu pula Kant berpendirian bahwa mesti ada aturan-aturan normatif yang menstruktur pikiran (atau rasio) subjek yang dengannya aktivitas determinasi (determinasi 11 David Hume, An Enquiry Cocerning Human Understanding, dalam Walter Kaufmann & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997), h. 367 12 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 113 18 rasio atas pengalaman) memiliki “bentuk” (form). Keniscayaan mungkin tidak dapat ditemukan dalam fakta-fakta pengalaman tetapi ia dapat ditemukan dalam struktur rasio subjek yang menyertainya. 13 Struktur rasio yang berisikan konsepkonsep murni itulah menurut Kant yang memungkinkan terbentuknya sintesis a priori. Namun demikian, gagasan sintesis adalah gagasan keterikatan konsep pada pengalaman. Suatu konsep dapat dikatakan sah jika konsep tersebut dapat diterapkan pada pengalaman. Karena itu, bagi Kant, walaupun konsep-konsep a priori itu adalah konsep-konsep yang mendahului pengalaman, konsep-konsep tersebut hanya memiliki “arti” sejauh mereka dapat diterapkan pada pengalaman (pada objek-objek pengalaman). Dengan kata lain, konsep-konsep murni tersebut tidak memiliki validitasnya ketika mereka dipisahkan dari pengalaman. Pada titik ini, Kant menegaskan batas-batas rasio, dan itulah yang dia maksud dengan “kritik” rasio murni. Rasio murni—fakultas yang mensuplai konsep-konsep murni—dieksplorasi secara menyeluruh untuk dipertimbangkan (kritik) kemampuan dan batas-batasnya dalam membentuk pengetahuan. 14 Sebagai kritik rasio murni, filsafat transendental Kant memperlihatkan antinomi-antinomi rasio untuk melihat mungkin tidaknya rasio memiliki pengetahuan tentang hal-hal di luar pengalaman (meta-fisika). Kant menemukan dalam analisis antinominya, bahwa ketika rasio dibiarkan berspekulasi tentang hal-hal di luar pengalaman, tesis-tesis rasio menyangkut hal-hal tersebut akan selalu menemukan anti- 13 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 44 14 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 14, 32 19 tesisnya, yang keduanya (tesis dan antitesis) sah secara rasional. 15 Dari sudut pandang inilah, Kant berkesimpulan bahwa metafisika sebagai salah satu produk kerja rasio tidak dapat dikatakan “ilmiah” karena konsep-konsep yang dikemukakannya tidak dapat diterapkan dalam pengalaman. Tentang sikapnya terhadap metafisika, Kant sejak awal dalam pengantarnya sudah menunjukkan sikap ketidakpuasan. Baginya metafisika adalah spekulasi sembarang atas kenyataan-kenyataan di luar pengalaman yang tidak bisa dibuktikan dan selalu berakhir pada antinomi, sebagaimana yang dia uraikan di beberapa sub-bab terakhir “Critique”-nya (The Antinomy of Pure Reason). Sikap kritis ini terutama terbangun di bawah pengaruh Hume, seorang eksponen mazhab empirisme radikal yang mempertanyakan kapasitas rasio dalam membentuk pengetahuan secara a priori, dan bahwa pengalaman merupakan sumber ultim bagi pengetahuan. 16 Namun demikian, walaupun Kant berpandangan kritis terhadap metafisika dan sepakat dengan empirisme dalam beberapa tesis tentang rasio dan pengalaman, dia menunjukkan bahwa metafisika merupakan gejala transendensi yang sudah selalu ada pada manusia. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan: “Apakah yang dapat kita ketahui?”, “apakah yang harus kita lakukan?”, dan “apakah yang dapat kita harapkan?”. Bagi Kant, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengimplikasikan bahwa manusia selalu terarah pada hal-hal yang 15 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 385 16 Ernst Cassirer, Kant’s Life and Thought, pen. James Haden (Yale University Press, 1981), h. 84-85 20 melampaui pengalaman, melampaui fakta-fakta, dan itu adalah sejenis kemampuan transendental bagi Kant. 17 Persoalannya bagi Kant adalah: “apakah hakikat dari transendensi tersebut?”. Dalam “Critique” kita menemukan jawabannya dalam analisis pembentukan sintesis murni di mana rasio memiliki peran krusial. Transendensi bagi Kant adalah momen terbentuknya sintesis murni (sintesis a priori), dan rasio murni adalah faktor esensial dalam proses tersebut yang berfungsi menyuplai konsep-konsep murni sebagai aturan determinasi pikiran. 3. Transendensi Subjek dalam Momen Sintesis Murni: Analisis Skema (Skematisme) dan Peran Imajinasi Dalam “Critique” kita menemukan bahwa konsep transendensi Kant didefinisikan sebagai pengetahuan murni (disebut juga pengetahuan a priori). Pengetahuan, sementara itu, didefinisikan sebagai representasi sintetis intuisi dan pikiran. Intuisi adalah fakultas pengetahuan yang “menghadirkan” (representing) data-data pengalaman yang berciri partikular secara langsung. 18 Pikiran (rasio) sementara itu adalah fakultas (kemampuan mental) yang menetapkan keumumankeumuman (generalities) dari data-data yang dihadirkan oleh intuisi—keumumankeumuman itu Kant menyebutnya “konsep”.19 Pengetahuan sebagai sintesis berarti terbentuknya relasi konseptual antara pikiran dan intuisi. Prinsip ini berlaku juga dalam pengetahuan a priori sebagai pengetahuan yang tidak didapat dari pengalaman (tidak terkondisikan oleh pengalaman akan objek-objek). Dengan 17 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 56, 635 18 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 65-66 19 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 92-97 21 kata lain, pengetahuan a priori juga dinyatakan sebagai representasi sintetis antara rasio dan intuisi. Hanya saja, representasi sintetis yang terjadi adalah sintesis “intuisi murni” dan “pikiran murni” (rasio murni), sehingga sintesis dalam pengetahuan a priori disebut “sintesis murni” atau “sintesis a priori”. Pertanyaan dapat dikemukakan: jika dengan “murni” berarti “tidak diperoleh dari pengalaman” lantas pengetahuan apakah yang dihasilkan dari sintesis intuisi murni dan rasio murni?; apakah yang diketahui dalam momen transendensi sebagai pengetahuan murni? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu terlebih dahulu mengenal konsep kunci dalam pemikiran Kant tentang pengetahuan sebagai sintesis. Momen pengetahuan sebagai sintesis mengandung pengertian bahwa terbentuknya pengetahuan itu bukanlah ketika konsep itu terbentuk melainkan ketika konsep itu dapat diterapkan pada objek. Demikian halnya dalam pengetahuan murni atau transendensi sebagai hasil dari sintesis murni; ia terbentuk ketika konsep-konsep murninya dapat diterapkan pada objek-objek pengalaman. Pertanyaan Kant adalah “bagaimana sintesis semacam itu mungkin?”. Upaya Kant untuk menjelaskan mungkinnya “sintesis murni” (baca: mungkinnya konsep-konsep murni diterapkan pada objek-objek pengalaman) dapat ditemukan dalam salah satu bagian penting “Critique”-nya, The Schematism of The Pure Concept of Understanding, di mana Kant menjelaskan bahwa konsep-konsep yang diterapkan pada objek selalu mengandaikan pembentukan “skema”. 20 Skema adalah representasi prosedur universal yang dengannya suatu konsep dapat memberikan gambaran universal tentang objek secara tidak terbatas 20 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 180 22 pada objek-objek tertentu. 21 Sementara konsep hanya menyatakan “ciri-ciri umum” (ens commun) suatu objek, skema menyatakan ciri umum tersebut sebagai aturan pemahaman (rule) bagi semua objek, yang aktual dan yang mungkin, dalam bentuk “gambaran” atau “citra” (image) skematik. ∗ Peristiwa terbentuknya skema dapat dengan mudah ditemukan dalam ilustrasi peristiwa pemahaman sehari-hari. Ketika saya melihat meja dan memahaminya, misalnya, hal itu menunjukkan terjadinya sintesis antara konsep meja dengan sensasi-sensasi meja (warna, bentuk, kepadatan, bau dan sebagainya) yang diintuisi. Namun demikian, meja yang saya pahami sekarang ini melampaui “sekadar” penggabungan konsep dan intuisi. Saya bukan hanya dapat menggambarkan “detail-detail” dari meja tersebut atau menangkap “ciri umum” dari detail-detail tersebut tetapi juga menangkap “aturan umum” tentang bagaimana meja itu seharusnya, “aturan” yang tidak hanya berlaku bagi meja yang sedang saya lihat tetapi bagi semua meja yang “mungkin” saya lihat. 22 Representasi skema merupakan gagasan niscaya dalam menjelaskan proses sintesis sebagai peristiwa penerapan konsep pada objek-objek pengalaman. Tanpa skema, tidak akan ada sintesis yang itu berarti penerapan konsep-konsep ke dalam pengalaman menjadi tidak mungkin. Dalam “Critique”, persoalan yang hendak dijawab oleh Kant adalah penerapan konsep-konsep murni pada objek-objek pengalaman. Penerapan konsep-konsep ini tidak seperti penerapan konsep-konsep empiris (konsep meja, 21 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 182-3 ∗ Secara harfiah, skema berarti diagram atau rancangan yang berisikan petunjuk-petunjuk dasar tentang sesuatu. 22 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 182 23 batu, buku, kuda dan sebagainya) yang mengandaikan skema empiris— sebagaimana sudah dijelaskan di atas dengan contoh konsep meja. Untuk konsepkonsep murni, penerapannya pada objek-objek pengalaman (sintesis murni) mengandaikan pembentukan skemanya sendiri yang oleh Kant disebut skema transendental. Skema ini, karena sifat murninya (transendental), tidak merepresentasikan aturan-aturan konseptual bagi objek-objek inderawi (skema empiris). Skema transendental, menurut Kant, “tidak lain adalah determinasi waktu” berdasarkan aturan-aturan konsep murni dalam kaitannya dengan rangkaian waktu (time-series), isi waktu (time-content), urutan waktu (timeorder), dan cakupan waktu (time-scope) dari suatu objek. 23 Skema substansi, misalnya, menyatakan hubungan antara yang tetap dan yang berubah dalam waktu. 24 Skema ini merupakan determinasi waktu suatu objek dalam kaitannya dengan tatanan waktunya (time order). Contoh lain dari kategori yang sama adalah skema kausalitas—substansi dan kausalitas berada dalam satu kategori, yaitu, kategori relasi. Skema kausalitas menyatakan hubungan urutan waktu (time order) dari dua peristiwa objek di mana ketika yang satu dialami (mis, air dimasak), yang lain menyusul (mis, air menjadi panas). Demikian, determinasi waktu merupakan wujud penerapan konsep-konsep murni pada objek-objek pengalaman. Kant mengantisipasi kemungkinan pandangan bahwa konsep substansi, atau konsep-konsep murni lainnya, itu muncul dari determinasi waktu. Karena itu, dia menegaskan bahwa determinasi waktu hanya mungkin sejauh ia mengikuti 23 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 185 24 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 184-185 24 aturan-aturan determinasi (konsep-konsep murni) yang sudah sejak awal (a priori) terbentuk. Dalam contoh skema substansi misalnya, determinasi tentang apa yang bertahan dan yang berubah dalam waktu hanya mungkin dalam kaitannya dengan konsep substansi. Tanpa konsep substansi, tidak ada aturan untuk menentukan apa yang bertahan dan apa yang berubah dalam waktu. 25 Konsep-konsep murni bagi Kant adalah aturan-aturan determinasi yang terbentuk mendahului peristiwa determinasi. Sekarang kita sudah sampai pada posisi untuk menjawab pertanyaan “apakah yang diketahui dalam pengetahuan murni?”. Dari penjelasan di atas, pertanyaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain: “apakah yang diketahui dalam skema transendental?”. Dalam kasus skema konsep empiris (skema empiris), apa yang direpresentasikan adalah aturan-aturan konseptual bagi objek dan karena setiap konsep empiris memiliki sumbernya dalam pengalaman, maka tidak sulit untuk menemukan kesejajaran antara skema konsep empiris dengan objeknya; misalnya, “aturan” binatang berkaki empat (skema) dengan kucing yang berkaki empat (objek penerapan). Skema transendental, sementara itu, hanya merupakan determinasi waktu dan apa yang diketahui dalam determinasi waktu tersebut adalah “bukan apa pun” (nothing). 26 “Bukan apa pun” di sini jangan ditafsirkan “semata-mata ketiadaan” (mere nothing) karena dalam kenyataannya “nothing” di sini memiliki peran konstituif dalam pengetahuan empiris. Karena sifat murninya dan karena fungsi konstitutifnya terhadap pengetahuan empiris, Kant menyebut 25 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 184 26 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 137, 267-268 25 representasi jenis ini sebagai pengetahuan murni—kadang-kadang disebut juga pengetahuan a priori atau pengetahuan transendental. Menarik memperhatikan gagasan Kant tentang skema. Setidaknya ada dua hal yang bisa ditekankan di sini. Pertama, representasi skema, sebagai representasi yang memediasi penerapan konsep pada pengalaman, memiliki sifat intelektual (nalar/rasional), di satu sisi, dan sensibel di sisi lain (intuitif). Kedua, sebagai representasi yang memiliki karakter ambivalen, representasi skema adalah representasi orisinal; ia bukan hasil dari penggabungan antara intuisi dan rasio. Karena itu, walaupun Kant memperkenalkan konsep sintesis dan bahwa skema adalah produk sintesis, dia tidak memaksudkan dengan kata “sintesis” itu sebagai produk kombinasi intuisi dan rasio. Sejak dalam pengantar “Critique”, Kant sudah mengantisipasi kemungkinan salah penafsiran atas konsep sintesis yang diperkenalkannya ini: “Sebagai pengantar atau antisipasi kita hanya perlu mengatakan bahwa ada dua sumber pengetahuan manusia, yaitu, sensibilitas ∗ dan pemahaman, yang mungkin keduanya berasal dari sumber yang sama (common root) yang kita tidak mengetahuinya”. 27 Kant memang tidak mengatakan apakah “sumber yang sama” tersebut. Namun maksudnya cukup jelas, Kant hendak mengatakan bahwa ada kemungkinan sintesis itu tidak terbentuk sebagai hasil penggabungan intuisi-rasio; sebaliknya, rasio dan intuisi justru adalah produk atau momen ganda dari sintesis. ∗ Sensibilitas (dari kata inggris “sensible” yang berarti “dapat terindra”) adalah kapasitas penerimaan objek secara langsung oleh subjek. Bagi Kant kapasitas ini menunjukkan bahwa subjek memiliki intuisi untuk menerima afeksi-afeksi dari objek. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 65 27 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 61 26 Menurut hemat saya, hal ini juga menjadi alasan mengapa dalam salah satu subbab “Critique”-nya, Transcendental Doctrin of Schematisme, dia mengisyaratkan keterbatasan analisanya terhadap fenomena skema sebagai representasi sintetis, sebagai berikut: “skematisme pemahaman kita, dalam penerapannya terhadap penampakanpenampakan (appearances) dan bentuk-bentuknya, adalah seni yang tersembunyi di kedalaman jiwa manusia, yang modus-modus nyata dari aktivitasnya tidak mengizinkan kita untuk mengungkapnya, dan membiarkan kita mengamatinya dengan seksama”. 28 Bersamaan dengan analisisnya atas skema (skematisme), Kant juga menunjukkan adanya fakultas lain, yang sebagaimana skema, memiliki karakter ambivalen. Kant menyebutnya “imajinasi” dan menurutnya fakultas (kekuatan mental) inilah yang memungkinkan terbentuknya skema, dan, karenanya sintesis. Fakultas ini niscaya terandaikan karena setiap jenis representasi selalu mengandaikan fakultasnya tersendiri. Sebagaimana representasi data-data partikular mengandaikan fakultas intuisi atau representasi konsep mengandaikan fakultas rasio, demikian halnya dengan representasi skematik yang mengandaikan fakultas imajinasi. Selanjutnya, pada level pengetahuan murni, di mana sintesis yang terbentuk adalah sintesis murni dan skema yang direpresentasikan adalah skema transendental, Kant mengasumsikan adanya fakultas imajinasi transendental, lawan dari imajinasi empiris, yang memungkinkan pembentukan skema transendental, dan karena itu, sintesis murni. 29 28 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 183 29 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 142-143 27 Dengan demikian, sejauh ini kita dapat membuat kesimpulan bahwa konsep transendensi Kant melibatkan tiga jenis fakultas pengetahuan: rasio murni, intuisi murni (waktu), dan imajinasi transendental. Tiga fakultas ini secara bersamaan membentuk apa yang oleh Kant disebut sintesis murni yang tidak lain adalah transendensi atau pengetahuan murni, suatu tahap pengetahuan di mana skema transendental direpresentasikan. Konsep transendensi ini rupanya masih menyisakan banyak persoalan. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan hubungan antara rasio, intuisi dan imajinasi, dan hakikat imajinasi itu sendiri sebagai faktor pembentuk sintesis melalui skema, yang sebagaimaan akan kita lihat, menjadi perhatian utama dalam pembacaan destruktif Heidegger. B. MARTIN HEIDEGGER: TRANSENDENSI SEBAGAI PEMAHAMAN ADA 1. Sekilas Biografi Hidup dan Karya Martin Heidegger (1889-1976) dikenal sebagai filsuf paling orisinal dan berpengaruh abad 20. Lahir di Messkirch, Baden, Jerman, dia belajar teologi Katolik Roma dan kemudian filsafat di Universitas Freiburg, di mana dia menjadi asisten Edmund Husserl, seorang pendiri fenomenologi. Heidegger memulai karir mengajarnya di Freiburg pada tahun 1915. Sejak 1923 sampai 1928 dia mengajar di Universitas Marburg. Dia kemudian kembali ke Freiburg pada tahun 1928, menggantikan posisi Husserl sebagai profesor filsafat. Karena dukungan publiknya atas Adolf Hitler dan Partai Nazi pada tahun 1933 dan 1934, aktivitas profesional Heidegger terbatas hingga tahun 1945, dan kontroversi menyangkut pendirian universitasnya terus berlanjut hingga pensiunnya pada tahun 1959. 28 Di antara Karya-karya Heidegger adalah sebagai berikut: Basic Problems of Phenomenology; Being and Time; Early Greek Thinking; Existence and Being; History of the Concept of Time; Kant and the Problem of Metaphysics; The Essence of Truth. 2. Transendensi atau Eksistensi dan Gagasan Destruksi Seperti Critique of Pure Reason bagi Kant, Being and Time adalah karya utama Heidegger yang menandai puncak karir pemikirannya. Di dalamnya Heidegger mengemukakan analisis transendensinya dengan bertolak dari fenomena pemahaman atas Ada (pemahaman ontologis), yang dia bedakan dari pemahaman atas pengada (pemahaman ontis)—Heidegger menegaskan perbedaan antara Ada dan pengada yang selanjutnya dia sebut “perbedaan ontologis” (ontologische differenz). 30 Jika saya memahami bahwa benda yang saya pegang ini adalah palu maka itu berarti saya memahami palu tersebut secara ontis sekaligus ontologis. Pemahaman ontis atas palu adalah pemahaman terhadap ciriciri fisik atau material pada palu tersebut: warna, bobot, bentuk, kehalusan atau ukuran. Sementara pemahaman ontologis atas palu berarti saya memahami modus Ada (mode of Being) palu tersebut; memahami Ada-nya. Modus-Ada palu yang saya pahami ini, dalam perspektif Heidegger, didefinisikan berdasarkan keberfungsian palu dalam suatu konteks referensial; yakni dalam hubungannya dengan gergaji, kayu, paku yang semua itu memiliki referensi terakhir, yaitu, pembuatan rumah saya dan pemenuhan diri saya sebagai si pembuat rumah. Totalitas referensial inilah yang menjadikan palu Ada sebagai palu; hanya dalam 30 Heidegger, Martin, Basic Problems of Phenomenology, pen. Alfred Hofstadter (Bloomington: Indiana University Press, 1982), dalam “Translator Introduction” oleh Alfred Hofstadter, h. xviii 29 konteks referensial, sebuah palu dapat meng-Ada (to-be) sebagai palu. Tanpa totalitas tersebut palu tidak dapat dipahami sebagai palu melainkan sebagai entitas homogen (tak terbedakan) yang sekadar memiliki bentuk, warna, atau ukuran sebagaimana entitas-entitas lain. Contoh yang serupa dapat dibuat, misalnya: kapur, penghapus, papan tulis, dan seorang guru yang sedang menerangkan pelajaran. 31 Gagasan terpenting dari Heidegger tentang fenomena pemahaman Ada adalah adanya entitas yang memahami Ada, yaitu, manusia. Pemahaman Ada oleh manusia menunjukkan bahwa Ada itu tersingkap pada manusia, atau, manusia tersingkap pada Ada--terkadang Heidegger mengilustrasikan ketersingkapan Ada ini sebagai peristiwa penyinaran (lichtung) di mana Ada menyinari manusia dan dengan sinar itu manusia menyinari entitas-entitas lain. Dalam ketersingkapan Ada inilah manusia dapat memahami Ada-dirinya dan Ada-nya entitas-entitas lain. 32 Dalam Being and Time, Heidegger menggunakan istilah Dasein untuk menyebut manusia, yang berarti Ada-Di sana (Da-Sein / There-Being). Dengan memakai istilah ini, Heidegger hendak menekankan dinamika pemahaman Ada manusia, bukan struktur biologisnya (warna kulit, organ-organ tubuh, postur dan sebagainya). Selain itu, dengan istilah ini pula, Heidegger hendak menekankan aspek ke-di-sana-an (The There/Da) Da-sein yang berarti bahwa pemahaman Ada Dasein (atau ketersingkapan Ada) itu selalu terjadi atau terikat dalam konteks dunia (um welt gebunden). 31 Ilustrasi-ilustrasi yang lengkap dan mudah tentang ini dapat ditemukan dalam Hubert L Dreyfus, Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I (Cambridge: The MIT Press), h. 89-107 32 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 125 30 Ini terjadi karena pemahaman Ada selalu berarti pemahaman akan cara atau modus Ada-nya sesuatu (mode of Being of beings). Ketika Dasein mengatakan “palu ini Ada”, Dasein mengerti “arti” Ada sekaligus modus Ada palu tersebut. Demikian halnya, ketika Dasein mengatakan “saya Ada” menunjukkan bahwa dia mengerti “arti” Ada sekaligus cara Ada dirinya (to be itself). Selanjutnya, karena setiap modus Ada itu selalu terbangun dalam totalitas referensial modus-modus Ada—lihat kembali contoh di atas—yang sudah selalu tersedia dalam dunia (mis, palu, gergaji, paku, rumah, guru, dokter, dan sebagainya), maka pemahaman Ada tersebut hanya dapat terwujud dalam dunia. Tanpa dunia, pemahaman Ada hanya akan menjadi sejenis dorongan-dorongan hampa. Dengan demikian, konsep Da-sein mencakup dua gagasan sekaligus: pemahaman Ada dan kebertempatan pemahaman tersebut dalam dunia. 33 Dalam Being and Time, Heidegger menyebut pemahaman Ada sebagai transendensi atau eksistensi yang keduanya memiliki arti sama atau setidaknya berdekatan, yaitu, “melampaui”. 34 Pemahaman Ada atau ketersingkapan Ada adalah momen transendensi karena dalam pemahaman Ada, Dasein seolah seolaholah “melampaui” dimensi ontis dari pengada-pengada untuk memahami Adanya. Sebagaimana sudah dikatakan, Ada selalu berarti Ada-nya sesuatu (Being of beings) atau cara Ada sesuatu (way of Being of beings) sehingga kenyataan Dasein memahami Ada berarti dia pada saat yang sama memahami cara Ada entitasentitas, termasuk cara Ada dirinya sebagai entitas yang memahami Ada. 33 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 54 34 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 10, 110. Lihat juga William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 39, 114 31 Pemahaman Ada tentu saja bukan pemahaman eksplisit atas Ada karena jika kita (Dasein) ditanya apa itu Ada tentu kita tidak dapat menjawabnya secara memuaskan, atau lebih buruk lagi, tidak dapat mengungkapkan gagasan apa pun dari kata tersebut. Namun demikian, pemahaman Ada adalah fakta yang jelas. Fakta ini dapat ditemukan dalam semua modus pemahaman sehari-hari manusia. Kita terbiasa mengatakan “batu ini ada”, “palu ini [adalah] berat”, “saya adalah Ki Joko”, dan sebagainya, yang semua itu menunjukkan bahwa kita telah mengerti arti Ada walaupun secara tidak eksplisit. Heidegger menyebut pemahaman Ada yang tidak eksplisit ini “pemahaman pra-ontologis”, suatu tahap pemahaman di mana Ada belum dibicarakan atau ditafsirkan secara diskurif yang di sepanjang sejarah pemikiran disebut ontologi (on: Ada, logos: diskursus atau pembicaraan). 35 Dalam Being and Time, Heidegger berusaha mendiskursuskan Ada, karenanya, melakukan semacam penyelidikan ontologis. Namun demikian, ontologi Heidegger bukan semacam pendefinisian secara lengkap arti Ada, sebagaimana dalam ontologi tradisional di mana Ada sering ditafsirkan dengan berbagai cara: monad, res cogitans, roh absolut, kehendak untuk berkuasa, ego transendental dan sebagainya. Sejak awal dalam Being and Time, Heidegger menegaskan secara terbatas bahwa: 1) Ada itu adalah konsep yang paling universal. Semua pengada atau entitas, apa pun itu, selalu dapat dilekatkan kata Ada padanya (mis, batu ada, manusia ada, Tuhan ada, jin ada, payung ada, dan sebagainya). 2) Ada itu adalah konsep yang jelas dengan sendirinya (self-evident concept); setiap orang sudah begitu saja menggunakan kata “ada” dalam 35 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 10-11 32 pembicaraannya tanpa dia tahu secara tegas arti dari kata tersebut. 3) Ada adalah konsep yang tidak dapat didefinisikan (undefinable concept) berdasarkan jenis (genus) dan cirinya (differentia) seolah-olah Ada itu semacam entitas yang memiliki perilaku tertentu, bentuk tertentu atau warna tertentu. 36 Lalu bagaimana Ada itu diselidiki jika ia bukanlah pengada sama sekali? Heidegger memahami ontologinya sebagai fenomenologi, yaitu, diskursus tentang fenomena pemahaman Ada dan, menurutnya, setiap pembicaraan tentang Ada (ontologi) harus dimulai dari fenomena pemahaman Ada (fenomenologi). Fenomena pemahaman Ada adalah satu-satunya petunjuk untuk memulai pembicaraan tentang Ada. Dia mengatakan: “Hanya sebagai fenomenologi, ontologi itu mungkin”. 37 Analisis pemahaman Ada, atau disebut juga analisis eksistensial, adalah gagasan orisinal Heidegger. Dia sendiri mengakui bahwa titik tolak analisisnya belum pernah dilakukan oleh para filsuf di sepanjang sejarah filsafat Barat, dan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, luputnya fenomena pemahaman Ada dari perhatian para filsuf adalah karena mereka telah melupakan pertanyaan tentang arti Ada (question of Being). Kelupaan ini adalah efek dari kelupaan yang lebih fundamental, yaitu, kelupaan akan perbedaan antara Ada dan pengada (perbedaan ontologis). Benarkah demikian? Dalam skripsi ini saya tidak akan mengulas tahap-tahap kelupaan tersebut. Apa yang terpenting dalam pandangan Heidegger ini adalah bahwa, walaupun Ada itu terlupakan, pemahaman Ada selalu terandaikan dalam penyelidikan para filsuf. Bahkan, pemahaman Ada sang filsuf sendiri selalu terikat oleh konsep-konsep tradisi di mana dia hidup, yang dengan 36 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 2-3 37 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 31 33 itu dia membangun sistem pemikirannya. 38 Karena itu, menurut Heidegger, kita dapat membaca ulang suatu teks pemikiran untuk memeriksa fenomena pemahaman Ada yang terimplikasi dalam teks tersebut, dan melihat seberapa kuat jejaring konseptual tradisi yang menghambat seorang filsuf untuk melihat fenomena tersebut secara jelas dan mempertimbangkannya sebagai potensi pemikiran. Heidegger menyebut pembacaan semacam ini “destruksi” yang secara harfiah berarti “merusak”. 39 Namun demikian, kenyataannya, destruksi Heidegger justru memiliki nilai korektif terhadap teks yang didestruksi walaupun benar juga bahwa dalam cara pembacaannya Heidegger kerap membahasakan ulang cara argumentasi dari teks yang didestruksi, yang pada taraf tertentu terkesan merusak. Terlebih dengan destruksinya, Heidegger tidak bermaksud menemukan intensi sesungguhnya dari sang pengarang melainkan elemen utama persoalan yang memberi orientasi pada sang pengarang, betapapun sang pengarang tidak menyadarinya. Destruksi berusaha mengangkat unsur vital dari suatu pemikiran yang seringkali tersamarkan oleh konsep-konsep tradisi yang sudah mengakar kuat. Dalam konteks destruksi, unsur vital tersebut tidak lain adalah fenomena pemahaman Ada, atau, ketakterhindaran persoalan tentang arti Ada. Dalam Being and Time, Heidegger merencanakan destruksinya atas tiga filsuf: Aristoteles, Descartes dan Immanuel Kant, yang sebagaimana kita tahu urung diwujudkan. 40 Rencana pembacaan destruktif tersebut baru terealisasi 38 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 17-18 39 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 20-21 40 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 35 34 kemudian dalam karya yang berbeda, salah satunya adalah Kant and the Problem of Metaphysics (selanjutnya ditulis “Kant and the Problem”) yang terdiri dari empat bab pembacaan Heidgger atas pemikiran Kant dalam “Critique”. Dalam “Kant and the problem”, Heidegger menjelaskan motif pemikiran Kant sebagai ontologi fundamental, atau, penyelidikan terhadap kapasitas transendental subjek yang dengannya metafisika sebagai ilmu atau pun kecenderungan alamiah dapat dikemukakan batas-batasnya (bab I). Penyelidikan ini tentu saja memiliki nilai epistemologis pada akhirnya, karena kapasitas transendental tersebut bukan hanya memungkinkan metafisika tetapi juga pengetahuan secara umum, tidak terkecuali sains-sains positif. Dalam tiga bab terakhir, Heidegger menjelaskan tahap-tahap penyelidikan Kant tentang keniscayaan terbentuknya skema oleh imajinasi transendental (bab II); imajinasi sebagai esensi transendensi dalam kaitannya dengan waktu (bab III); konsekuensi pemikiran Kant tentang imajinasi terhadap ide keterbatasan (bab IV). 3. Destruksi Heidegger atas “Critique” Kant: Sebuah Tinjauan Umum Destruksi Heidegger atas “Critique” terutama menekankan pembacaannya pada doktrin skematisme; doktrin tentang penerapan konsep dalam pengalaman atau doktrin tentang pembentukan skema. Dalam doktrin inilah menurut Heidegger gagasan transendensi sebagai pemahaman Ada dapat diungkapkan, terlepas apakah Kant menyadarinya atau tidak. Dengan kata lain, Kant mungkin tidak menyebut-nyebut istilah “pemahaman Ada” dalam kaitannya dengan skema transendental. Kant hanya mengatakan bahwa apa yang diketahui dalam skema transendental sebagai produk sintesis murni adalah “bukan apa pun” (nothing), karena itu Kant menyebutnya pengetahuan transendental atau pengetahuan 35 murni. 41 Dalam pembacaan Heidegger, gagasan ini sebenarnya merujuk pada fenomena pemahaman Ada atau pengetahuan ontologis karena sebagaimana dalam pengetahuan murni, apa yang diketahui dalam pengetahuan ontologis juga “bukanlah apa pun” (nothing). Ada itu sendiri adalah bukan apa pun. Dengan titik tolak pemahaman Ada, terdapat beberapa tesis dasar dalam destruksi Heidegger atas skematisme yang perlu dikemukakan di sini. Pertama, menurut Heidegger esensi transendensi terletak pada imajinasi transendental, bukan pada rasio murni. Itu berarti bahwa pemahaman Ada sebagai momen transendensi subjek tidak terbentuk melalui rasio murni melainkan imajinasi transendental. Pembacaan ini sebenarnya didasarkan pada argumen Kant sendiri ketika dia mengatakan dalam doktrin skematismenya bahwa penerapan konsepkonsep murni ke dalam pengalaman (sintesis murni) hanya mungkin oleh adanya mediasi skema transendental yang dibentuk oleh imajinasi transendental. Dengan demikian, Kant sendiri sebenarnya mengakui bahwa imajinasi memiliki peran sentral dalam membentuk pengetahuan transendental (pengetahuan murni/sintesis murni), walaupun dalam kenyataannya, Kant tidak banyak membicarakan imajinasi transendental dalam “Critique”-nya melainkan justru cenderung menekankan aspek rasio sebagai faktor esensial dalam pembentukan sintesis murni (transendensi). Kedua, menurut Heidegger, karena Kant cenderung menekankan rasio murni sebagai faktor esensial dalam pembentukan sintesis murni atau skema transendental (pengetahuan murni), Kant menurut Heidegger telah mereduksi konsep pemahaman Ada ke dalam salah satu modus pemahaman Ada, yaitu 41 Pengetahuan murni berarti pengetahuan yang tidak diperoleh dari pengalaman akan objek-objek. Itu berarti dalam pengetahuan murni tidak ada pengetahuan apa pun tentang ciri fisik suatu objek. Apa yang diketahui dalam pengetahuan murni “bukanlah apa pun” (nothing). 36 modus pemahaman kategorial, di mana pemahaman atau pengetahuan ditafsirkan sebagai proses determinasi konseptual atas waktu (time-determination) berdasarkan aturan-aturan konsep murni (substansi, kausalitas, kualitas dan seterusnya); sesuatu dianggap terpahami karena sesuatu tersebut tercakup dalam konsep atau kategori. Dalam destruksi Heidegger sementara itu, karena skema transendental adalah momen sintesis orisinal sebagaimana Kant sendiri secara implisit mengakuinya, maka pemahaman Ada tidak terbatas pada pemahaman kategorial. Orisinalitas skema transendental bagi Heidegger menunjukkan bahwa apa yang direpresentasikan dalam skema tersebut mestilah lebih luas dari sekadar determinasi rasio. Dengan demikian, dalam destruksi Heidegger, gagasan Kant tentang rasio sebagai dasar pengetahuan transendental, dipersoalkan. Ketiga, destruksi Heidegger juga berusaha meradikalkan gagasan Kant tentang waktu dalam kaitannya dengan imajinasi transendental. Kaitan ini sudah dapat dilihat dalam “Critique” ketika Kant mengatakan bahwa skema transendental tidak lain adalah determinasi waktu dan bahwa imajinasi transendental merupakan faktor esensial dalam proses determinasi tersebut. Atas dasar pandangan ini, Heidegger meradikalkan gagasan waktu Kant dengan menegaskan bahwa waktu sebenarnya adalah momen temporal dari imajinasi transendental. Berbeda dari Kant, Heidegger tidak mendefinisikan waktu sebagai rangkaian “sekarang” (sequence of nows) yang bergantian, melainkan proses mewaktu (temporalitas) yang mencirikan imajinasi transendental dalam aktivitas sintetisnya. Perlu diketahui bahwa dengan pembacaan ini, Heidegger sebenarnya hendak memperlihatkan bagaimana konsep waktu berkaitan dengan pemahaman 37 Ada, sebuah tema yang menjadi motif pemikiran Heidegger dalam “Being and Time” (Ada dan Waktu). Keempat, imajinasi transendental adalah konsekuensi keterbatasan, yaitu, keterbatasan intuisi, dan sebagai konsekuensi keterbatasan, imajinasi transendental itu sendiri bersifat terbatas. Konsekuensinya, transendensi sebagai pemahaman Ada juga terbatas dan merupakan konsekuensi keterbatasan. Sekadar untuk diketahui, Heidegger mengungkapkan konsep transendensi terbatas ini dalam “Kant and the Problem” dan “Being and Time”. Dalam “Kant and the Problem”, Heidegger memperlihatkan keterbatasan transendensi sebagai keterbatasan imajinasi transendental dalam kaitannya dengan intuisi terbatas manusia; imajinasi terandaikan karena intuisi manusia tidak menciptakan objek yang diintuisinya. Dalam “Being and Time”, sementara itu, ide keterbatasan berkaitan dengan sifat temporal pemahaman Ada, yaitu karakter proyektif yang terarah pada masa depan yang tidak pernah terpenuhi dan selalu ditandai oleh kebeluman (not yet). Dalam bab berikutnya, saya akan menjelaskan poin-poin destruksi Heidegger atas doktrin skematisme sebagaimana disebutkan di atas. Perlu diingat bahwa apa yang terpenting dalam pemikiran Heidegger adalah gagasan tentang Ada, modus-modusnya, bentuk-bentuk dan karakter pemahamannya. Gagasan ini selalu menjadi motif utama pemikiran Heidegger, dalam “Being and Time” atau pun dalam pembacaan destruktifnya atas doktrin skematisme Kant. Dalam “Critique”, sebagaimana telah dikatakan, Heidegger menemukan gagasan pemahaman Ada dalam analisis skematisme Kant, sebuah analisis dimana konsep-konsep seperti skema transendental, imajinasi transendental, rasio murni, 38 dan intuisi waktu dijelaskan hubungan-hubungannya. Heidegger menekankan faktor imajinasi transendental dalam hal ini dan berusaha melihat konsep-konsep lain dalam hubungannya dengan imajinasi transendetal. Pembacaan ini beralasan bagi Heidegger karena imajinasi transendental adalah fakultas sentral yang memungkinkan terbentuknya sintesis murni; terbentuknya pemahaman Ada. Hasilnya adalah suatu pemikiran Kant dalam terang yang lain. Jika pemikiran Kant dalam “Critique” adalah pemikiran tentang hakikat rasio murni dan batasbatasnya, maka pemikiran Kant yang didestruksi dalam “Kant and the Problem” adalah pemikiran tentang esensi imajinasi transendental dan batas-batasnya. 39 BAB III DESTRUKSI SKEMATISME: MEMBACA ULANG RELASI ESENSIAL ANTARA IMAJINASI, INTUISI WAKTU DAN RASIO MURNI Sebagaimana telah diulas sebelumnya, transendensi dalam pemikiran Kant dinyatakan dalam gagasan sintesis murni, di mana konsep-konsep murni dapat diterapkan pada objek-objek pengalaman melalui representasi skema transendental. Kant menyebut doktrin penerapan konsep-konsep ini “skematisme” dan pada doktrin inilah Kant mengemukakan kaitan antara imajinasi, waktu dan rasio murni. Dari titik tolak doktrin skema (skematisme) ini, Heidegger menemukan bahwa intuisi murni—dalam hal ini waktu—dan konsep-konsep murni yang dibentuk oleh rasio murni, tidak dapat dilepaskan dari peran imajinasi transendental dalam pembentukannya. Kenyataannya, dalam destruksi Heidegger, waktu dan rasio murni itu sendiri bersumber dari imajinasi transendental (Einbildung-Kraft). Penafsiran ini tentu saja amat radikal dan melampaui tesis pemikiran Kant sendiri. Namun menurut Heidegger gagasan ini sebenarnya sudah implisit dalam pandangan Kant ketika dia mengatakan bahwa imajinasi transendental, sebagai fakultas yang terandaikan dalam proses sintesis, berciri intelektual (rasional) sekaligus sensibel (intuitif). Bab ini akan menguraikan bagaimana Heidegger, dengan minat pemikirannya pada fenomena pemahaman Ada, membaca ulang secara destruktif hubungan antara rasio murni dan intuisi murni dengan imajinasi transendental. Dalam bagian pertama bab ini, saya akan mengulas hubungan imajinasi transendetal dengan waktu yang diawali dengan klarifikasi konsep waktu Kant. 40 Bagian kedua mengulas hubungan antara imajinasi transendental dengan rasio murni. Bagian ketiga berisikan pembacaan Heidegger atas konsep imajinasi transendental sebagai konsekuensi keterbatasan. Pembacaan ini saya sisipkan dalam bab ini karena gagasan keterbatasan Heidegger berkaitan langsung dengan karakter intuitif dan intelektual dari imajinasi. Selanjutnya, pada bagian terakhir saya akan memberikan ulasan ringkas tentang implikasi pemikiran transendental Heidegger dalam pemikiran etika dan keagamaan; tinjauan singkat tentang keunggulan dan kelemahan analisis Heidegger dan pembacaannya atas Kant. Penting untuk terus diingat bahwa pembacaan Heidegger bagaimanapun dilatarbelakangi oleh minatnya pada fenomena pemahaman Ada. Sebagaimana telah dikatakan, motif destruksi Heidegger adalah mengeksplisitkan fenomena pemahaman Ada dalam teks yang didestruksi. Karena itu, pembacaannya atas imajinasi transendental dan hubungannya dengan intuisi murni dan rasio murni, harus juga dilihat sebagai ikhtiar menegaskan fenomena transendensi sebagai pemahaman Ada, karakternya dan kedudukannya dalam struktur pemahaman atau struktur eksistensi manusia. A. WAKTU DAN IMAJINASI TRANSENDENTAL: PEMBACAAN KE ARAH TEMPORALITAS TRANSENDENSI Kant memahami waktu sebagai sejenis intuisi murni. Kant menyebutnya intuisi karena menurutnya waktu dihadirkan secara langsung atau terberi begitu saja dalam bentuk afeksi ∗ . Waktu juga disebut “murni” karena waktu tidak lain ∗ Afeksi berasal dari bahasa Latin “afficere” yang berarti pengaruh atau dorongan yang biasanya diasosiasikan dengan timbulnya perasaan. Intuisi adalah fakultas pengetahuan yang dengannya objek-objek atau hal-hal lain mengafeksi subjek secara langsung. Waktu adalah sejenis afeksi yang bersifat murni. Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 19 41 adalah bentuk dari proses intuisi subjektif.1 Ketika subjek merepresentasikan datadata pengalaman melalui intuisinya, intuisi subjek tidak hanya terarah pada apa yang diintuisi melainkan juga pada proses mengintuisi itu sendiri, dengan kata lain, pada dirinya sendiri (self-intuiting). Intuisi subjek, karenanya, tidak hanya terafeksi oleh objek-objek pengalaman melainkan juga oleh aktivitasnya sendiri sebagai proses mengintuisi. Pada titik inilah, menurut Kant, intuisi waktu terandaikan (presupposed). Ketika intuisi mengintuisi aktivitas intuitifnya (selfintuiting), intuisi merepresentasikan atau “merasakan” perubahan-perubahan dalam proses mengintuisi. 2 Perubahan-perubahan tersebut bukanlah semacam perpindahan posisi dalam ruang, melainkan pergantian-pergantian (succession) kehadiran dalam waktu. Dalam proses itu, intuisi waktu menjadi niscaya karena tanpanya, pergantian-pergantian tersebut tidak akan dapat direpresentasikan sebagai pergantian-pergantian dalam waktu. Waktu memungkinkan setiap proses mengintuisi direpresentasikan sebagai “yang telah berlalu”, “yang sedang terjadi”, atau “mungkin terjadi” dan itu, menurutnya, menunjukkan bahwa waktu terintuisi “lebih dulu” (a priori). 3 Namun demikian, waktu bukanlah sesuatu yang terintuisi dari luar subjek. Kant menolak eksistensi absolut waktu. Intuisi waktu hanya 1 Selain waktu, Kant juga sebenarnya mengenal jenis intuisi murni lainnya, yaitu, ruang. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 68. Namun, karena pembacaan Heidegger terbatas pada konsep waktu Kant, maka demikian pula skripsi ini. Tentang hal ini, lihat Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 31-34 2 Dalam Critique Kant menyebut fenomena intuisi atas intuisi (self-intuition) sebagai sejenis penginderaan yang mengarah ke dalam yang karenanya disebut indera-dalam (inner-sense). Lawan dari indera-dalam adalah indera-luar (outer-sense), yaitu ketika intuisi mengintuisi objekobjek pengalaman; mengarah keluar. Bentuk dari intuisi-luar adalah ruang; bentuk dari intuisidalam adalah waktu. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 67 3 Tentang karakter “a priori” waktu, lihat Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 76-79 42 dapat muncul bersamaan dengan dinamika suksesif intuisi subjek. Karena itu, waktu sepenuhnya berciri subjektif dan karena itu pula ia disebut murni. Waktu, lanjut Kant, direpresentasikan secara “tak terbatas” (unlimited) seperti sebuah garis yang memanjang terus ke depan dan ke belakang, tanpa tepi (unlimited). Tentu saja kita dapat mengatakan “dulu”, “sekarang”, dan “nanti” yang menunjukkan bahwa waktu itu terbagi-bagi ke dalam bentuk waktu yang berbeda-beda yang masing-masing memiliki batas (limit). Tetapi menurut Kant, “bagian-bagian (parts) waktu yang berbeda tidak lain hanyalah pembatasan (limitation) atas waktu sebagai efek dari proses intuisi subjek yang terjadi secara suksesif. 4 Dengan kata lain, waktu yang berbeda sebenarnya merujuk pada waktu yang satu dan sama (one and the same time)”. 5 Di sini kita melihat bagaimana waktu dalam konsepsi Kant dipahami sebagai keseluruhan tak terbatas yang direpresentasikan (represented whole) yang walaupun terbagi ke dalam batasbatas atau bagian-bagian (dulu, sekarang, nanti), ia tetap dihadirkan atau direpresentasikan sebagai keseluruhan. 6 Dalam pembacaan Heidegger, waktu yang direpresentasikan sebagai “keseluruhan tak terbatas” yang memungkinkan setiap bagian-bagian waktu selalu terpahami sebagai keseluruhan menunjukkan bahwa waktu memiliki karakter sintetisnya sendiri yang terbedakan dari sintesis konseptual. “Representasi keseluruhan [waktu] tidak terberi melalui konsep, karena konsep hanya berisi 4 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 100 5 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 75 6 Sebagaimana waktu, Kant juga menggambarkan ruang sebagai garis memanjang (satu dimensi) yang bagian-bagiannya tidak lain adalah ruang yang satu dan sama; ruang, sebagaimana waktu, direpresentasikan sebagai “tak terbatas”. Perbedaannya, jika bagian-bagian ruang (samping, depan, atas) diintuisi secara serentak (simultaneous) maka bagian-bagian waktu diintuisi secara bergantian (successive). Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 75 43 representasi parsial”. 7 Konsep hanya merepresentasikan ciri-ciri umum suatu objek (common properties) yang sebenarnya hanyalah sebagian saja dari ciri objek. Konsep buku, misalnya, hanya merepresentasikan ciri-ciri umum buku (mis, tumpukan kertas tulis berbentuk segi empat) yang tidak sepenuhnya menggambarkan buku yang direpresentasikan (mis, tumpukan kertas tulis berbentuk segi empat + berwarna kuning dan bergambar Ronaldinho). Berbeda dari representasi konseptual, representasi intuitif waktu merangkum seluruh bagian-bagian waktu secara penuh. Hal ini karena waktu bukanlah hasil abstraksi atas waktu-waktu yang berbeda, melainkan “sesuatu” yang terintuisi secara langsung dan a priori sebagai keseluruhan tak terbatas (unlimited whole); waktuwaktu yang berbeda adalah wujud terbatas dari waktu yang sama. Pada titik pembacaan ini, Heidegger dalam “Kant and the Problem” sampai pada kesimpulan bahwa apa yang memungkinkan terjadinya sintesis waktu adalah waktu itu sendiri. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan imajinasi transendental? Tentang hal ini, Heidegger mengatakan bahwa imajinasi transendental memiliki dasarnya pada waktu; waktu adalah asal mula imajinasi. Bagaimanakah itu dijelaskan? Dan apakah arti destruksi Heidegger ketika dia mengatakan bahwa waktu adalah dasar atau sumber bagi imajinasi transendental? 1. Representasi Waktu dalam Tiga Horizon Waktu: Imajinasi Transendental sebagai Asal Mula Waktu Untuk menunjukkan bahwa waktu adalah asal mula imajinasi transendental, Heidegger pertama-tama menunjukkan sebaliknya, bahwa imajinasi transendental adalah asal mula waktu (origin of time). Dasarnya adalah pandangan 7 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 75 44 Kant sendiri dalam “Critique” ketika dia mengatakan bahwa dalam setiap momen suksesif waktu, selalu terjadi sintesis di dalamnya. Dengan suksesi waktu Kant memahaminya sebagai suksesi waktu “sekarang”, yaitu sekarang yang sedang berlangsung, sekarang yang telah berlalu, dan sekarang yang mungkin terjadi. 8 Dengan kata lain, Kant menggambarkan waktu sebagai titik-titik waktu “sekarang” yang muncul bergantian (sequence of nows). Selanjutnya, menurut Kant, masing-masing waktu “sekarang” adalah horizon waktu bagi tiga jenis sintesis empiris: sintesis aprehensi, sintesis reproduksi dan sintesis rekognisi. Sebagai sintesis empiris, modus-modus sintesis ini adalah “penghadiran” dengan cara “menyatukan”. Apa yang disatukan adalah sesuatu yang berasal dari objek berupa data-data inderawi partikular yang senantiasa “berada dalam waktu” (within time)—berada dalam horizon waktu sekarang yang berbeda-beda. Sintesis aprehensi, misalnya, mensintesiskan data-data objek di waktu sekarang yang sedang berlangsung; sintesis reproduksi mensintesiskan partikularitas data-data inderawi yang hadir di waktu sekarang yang telah berlalu; sintesis rekognisi mensintesiskan partikularitas data-data inderawi yang hadir di waktu sekarang yang akan datang (belum terealisasi namun mungkin terealisasi). 9 Sintesis aprehensi adalah sintesis penghadiran (presenting). Sintesis reproduksi adalah sintesis ingatan (recollecting). Sintesis rekognisi adalah sintesis harapan atau antisipasi (anticipating). Ketiga sintesis ini menurut Heidegger saling mengandaikan satu sama lain karena terbentuknya pengetahuan adalah terbentuknya sintesis tiga jenis representasi sintetis ini. Sintesis aprehensi tidak 8 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 124-131 9 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 125-128 45 mungkin terjadi tanpa adanya sintesis reproduksi; menghadirkan objek yang hadir di waktu sekarang selalu mengandaikan penghadiran objek tersebut sebagai objek yang pernah ada di waktu lalu (sekarang yang telah berlalu). 10 Tanpa menghadirkan kembali (baca: mengingat) masa “lalu” objek, sintesis aprehensi akan selalu gagal karena objek “sekarang” tidak dapat dibandingkan dengan masa lalunya sehingga tidak dapat dikenali (identified) sebagai objek yang hadir “sekarang”. 11 Namun demikian, sintesis ingatan (recollection) hanya mungkin jika dalam sintesis terjadi antisipasi (anticipating). Dengan kata lain, ketika subjek mensintesiskan data-data pengalaman, dalam peristiwa itu mesti terjadi antisipasi dalam hal manakah dari data-data yang disintesiskan tersebut memiliki kemungkinan untuk hadir kembali. Data-data yang memiliki kemungkinan untuk hadir kembali itu selanjutnya dipertahankan atau diingat (recollected) dalam proses antisipasi yang dengan demikian memungkinkan data-data yang diingat itu dibandingkan dengan objek “sekarang”. Antisipasi memungkinkankan adanya ingatan, yang dengannya penghadiran juga menjadi mungkin. Karena itu, menurut Heidegger, masa depan sebagai antisipasi memiliki kedudukan primer karena ia merupakan kondisi ultim bagi pembentukan dua modus waktu lainnya (dulu dan sekarang). 12 Dalam pembacaan Heidegger, pengandaian tentang keniscayaan imajinasi transendental dalam tiga modus sintesis ini bertolak dari kenyataan bahwa sintesis empiris selalu terkondisikan dalam sintesis murni dan bahwa setiap sintesis selalu 10 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 125-128 11 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 128-132 12 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 131 46 meniscayakan adanya kerja imajinasi. Menurut Heidegger, bertolak dari argumentasi Kant, sintesis empiris terbentuk oleh imajinasi empiris, sementara sintesis murni terbentuk oleh imajinasi transendental. Karena itu, sebagaimana sintesis empiris selalu mengandaikan sintesis murni, demikian halnya imajnasi empiris selalu mengandaikan imajinasi transendental. Ketiga jenis sintesis empiris di atas sebagai produk imajinasi empiris dengan demikian mengandaikan tiga jenis sintesis murni yang dibentuk oleh imajinasi transendental. Tetapi apakah yang direpresentasikan dalam tiga jenis sintesis murni tersebut? Pada level murninya, masing-masing sintesis tidak menghadirkan objek menurut ciri waktunya, melainkan waktu itu sendiri. Demikian misalnya, sintesis aprehensi pada level “murni”-nya tidak menghadirkan objek yang hadir di waktu “sekarang”, tetapi menghadirkan waktu “sekarang” itu sendiri. Sintesis “murni” reproduksi tidak menghadirkan objek yang pernah hadir di waktu “lalu”, tetapi waktu “lalu” itu sendiri dalam kaitannya dengan waktu “sekarang”. Demikian halnya, sintesis “murni” rekognisi bukan menghadirkan kemungkinan objek di masa “depan”, tetapi masa “depan” itu sendiri sebagai antisipasi kemungkinankemungkinan. Ketiga sintesis murni di atas, yang menghadirkan tiga horizon waktu, adalah produk imajinasi transendental dan dalam arti inilah menurut Heidegger imajinasi transendental dipahami sebagai “asal mula” waktu. 13 2. Representasi Waktu sebagai Keseluruhan: Waktu sebagai Dasar bagi Imajinasi Transendental (Temporalitas) Berdasarkan uraian di atas, imajinasi transendental menghadirkan waktu melalui pembentukan tiga jenis sintesis murni (aprehensi murni, reproduksi 13 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 123-125 47 murni, dan rekognisi murni) yang masing-masing menghadirkan tiga horizon waktu yang berbeda (“sekarang”, “masa lalu”, dan “masa depan”). Tetapi pengetahuan adalah tersintesiskannya tiga horizon waktu sehingga pertanyaan Heidegger adalah “apakah yang memungkinkan sintesis tiga horizon waktu tersebut? 14 Heidegger dalam Kant and the Problem memperlihatkan bahwa tiga horizon waktu di atas sebenarnya merujuk pada horizon waktu yang satu dan sama (one and same). “Sekarang”, “masa lalu”, atau “masa depan” adalah tiga ekspresi dari waktu yang sama. Pandangan ini didasarkan pada tesis Kant sendiri bahwa waktu selalu direpresentasikan sebagai keseluruhan. Perbedaan waktu tidak lain adalah pembatasan (limitation) atas keseluruhan waktu sebagai efek dari proses representasi yang berciri suksesif. 15 Dengan demikian, menurut Heidegger, apa yang memungkinkan imajinasi transendental dapat membentuk tiga horizon waktu dan mensintesiskannya adalah waktu itu sendiri dan atas dasar inilah, menurut Heidegger, waktu dipahami sebagai asal mula imajinasi transendental. 16 Pandangan Heidegger tentang hubungan waktu dan imajinasi transendental ini sepintas tampak tidak konsisten. Namun demikian, uraian Heidegger tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: jika waktu dilihat dalam perbedaannya (dulu, sekarang, nanti), maka imajinasi transendental adalah asal mula bagi waktu. Namun, jika waktu dilihat dalam keseluruhannya (sebagai representasi keseluruhan), maka waktu adalah asal mula imajinasi transendental. 14 William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 142 15 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 139-140 16 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 137 48 Namun demikian, menurut saya, dengan mengatakan bahwa imajinasi transendental sebagai asal mula waktu, atau, waktu sebagai asal mula transendental, Heidegger sebenarnya tidak sedang mengubah pandangannya. Dia hanya ingin mengatakan bahwa imajinasi transendental itu mewaktu (temporal). Dengan pembacaan ini Heidegger sebenarnya hendak memperkenalkan konsep waktu “Being and Time” ke dalam Critique of Pure Reason, yaitu, waktu dalam arti mewaktu (time-ing). Heidegger memperkenalkan konsep waktu sebagai gerak dinamis yang menandai proses pemahaman Ada atau pengetahuan murni, yang dalam Kant, diasumsikan sebagai “produk” imajinasi transendental. Karena itu, mengatakan bahwa imajinasi transendental itu mewaktu (temporal) sama dengan mengatakan bahwa transendensi sebagai pemahaman Ada itu terbentuk dalam horizon waktu; memiliki karakter waktu. Pandangan ini tak diragukan lagi merupakan pandangan yang khas “Being and Time” di mana Heidegger memperlihatkan kaitan antara Ada (Being) dengan waktu (Time). 17 B. IMAJINASI TRANSENDENTAL DAN KEDUDUKAN RASIO DALAM DESTRUKSI HEIDEGGER Kita telah mendiskusikan bagaimana sifat intuitif imajinasi (determinasi waktu oleh imajinasi) diradikalkan oleh Heidegger sebagai sifat temporal (sifat mewaktu) imajinasi, yang karenanya juga merekonstruksi konsep waktu Kant. Masalah selanjutnya adalah: Bagaimanakah Heidegger meradikalkan karakter intelektual dari imajinasi? Dan konsekuensi apakah yang lahir dari pembacaan ulang atas rasio dalam kaitannya dengan imajinasi transendental? 17 Martin Heidegger, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996), h. 15 49 Pemikiran Heidegger dalam “Kant and the Problem” adalah pemikiran Kant yang dibaca dari perspektif terbalik. Dalam “Critique” Kant mengemukakan gagasan imajinasi melalui pendekatan rasio dan intuisi; sebaliknya, dalam “Kant and the Problem” Heidegger justru berusaha melihat rasio murni dan intuisi murni dari titik tolak imajinasi transendental. Pembacaan ini dilakukan karena menurut Heidegger, imajinasi transendental itu adalah pusat transendensi (centre for transcendence); fakultas yang memungkinkan sintesis murni melalui pembentukan skema transendental (esensi sintesis murni). Menganalisis rasio murni dan intuisi murni dari titik tolak imajinasi transendental, karenanya, berarti melihat bagaimana dua fakultas pengetahuan tersebut (rasio dan intuisi) terpusat pada imajinasi transendental. 18 Dalam pembacaan Heidegger, imajinasi sebagai esensi sintesis murni atau sebagai pusat transendensi menunjukkan bahwa konsep-konsep murni yang dihasilkan rasio murni memiliki dasarnya pada imajinasi transendental, sebagaimana waktu memiliki dasarnya pada imajinasi transendental. Alasannya terletak dalam pembacaan Heidegger atas konsep skema Kant: Heidegger sepakat dengan Kant bahwa skema merupakan bentuk representasi sintetis intuisi-rasio. Heidegger bahkan mempertegas bahwa apa yang direpresentasikan dalam skema bukanlah sesuatu yang dapat dianalisa atau digambarkan dengan pendekatan rasio-intuisi. Terandaikannya skema bagi Heidegger menunjukkan bahwa representasi yang tampil dalam kesadaran subjek bukanlah representasi rasio (konsep-konsep) atau pun representasi intuisi. Kant sendiri mengakui bahwa kita tidak pernah dapat mengetahui bagaimana skema itu 18 William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 137 50 ditampilkan dalam kesadaran (kesadaran subjek) atau bagaimana ia terbentuk. Kita mungkin bisa menganalisis bentuk-bentuk dari representasi intuisi sebagai berciri partikular sebagaimana kita juga dapat menganalisis representasi konsep sebagai sesuatu yang berciri umum. Tetapi representasi skema tidak dapat dianalisis dengan cara demikian karena ia bukan konsep dan juga bukan data-data intuisi, melainkan sintesis keduanya. Sebagai sintesis keduanya, skema itu melampaui keduanya. Heidegger tidak menjelaskan dalam Kant and the Problem apakah yang dimaksud dengan “melampaui” tersebut. Namun demikian, bagi Heidegger jelas bahwa jika representasi skema mesti terandaikan mendahului (a priori) representasi intuisi dan rasio untuk memungkinkan sintesis keduanya, maka itu berarti skema menjadi dasar (origin) bagi representasi intuisi dan rasio. 19 Hal ini berlaku juga bagi skema transendental yang didefinisikan oleh Kant sebagai determinasi waktu (time determination); sebagai momen sintesis murni yang memungkinkan konsep-konsep murni dapat diterapkan pada objek-objek pengalaman. Karena itu, jika rasio murni adalah fakultas pengetahuan yang merepresentasikan konsep-konsep murni dan intuisi murni adalah fakultas yang merepresentasikan waktu, maka baik konsep-konsep murni atau pun waktu memiliki dasarnya pada skema transendental. Tetapi skema transendental adalah produk imajinasi transendental sehingga, menurut Heidegger, kita juga bisa mengatakan bahwa rasio murni dan intuisi murni (waktu) tidak lain adalah dua momen imajinasi transendental.20 19 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 76, 79 20 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 87-93,99 51 Dalam kaitannya dengan konsep-konsep murni, pandangan Heidegger di atas dapat dinyatakan secara ringkas sebagai berikut: bukan konsep-konsep murni yang memberikan kontribusi bagi pembentukan skema transendental melainkan skema transendental itulah yang memberikan kontribusi bagi pembentukan konsep-konsep murni. Selanjutnya, dengan mengatakan bahwa rasio memiliki dasarnya pada imajinasi transendental atau bahwa konsep-konsep murni bersumber dari skema transendental, pembacaan Heidegger juga mengarah pada pandangan bahwa pemahaman-pemahaman konseptual (produk rasio) tidak lain adalah derivasi dari pemahaman pada level skema (transendensi). Tesis ini memang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam “Kant and the Problem”, tetapi indikasinya sangat gamblang terutama jika kita membandingkannya dengan konsep transendensi yang dikembangkan Heidegger dalam “Being and Time”, di mana transendensi yang terbentuk melalui skema transendental dipahami sebagai fenomena pemahaman Ada atau ketersingkapan Ada. Fenomena pemahaman Ada, sebagaimana dapat kita temukan dalam “Being and Time” atau pun dalam “Kant and the Problem”, dicirikan setidaknya oleh tiga hal: Ada terpahami secara pra-ontologis, bersifat temporal (mewaktu), dan ditandai oleh keterlibatan dengan dunia. 21 Ketika Kant mengatakan bahwa pemahaman terbentuk melalui proses sintesis di mana rasio dengan konsepkonsep murninya memiliki peran esensial, bagi Heidegger Kant telah mereduksi pemahaman Ada (transendensi) menjadi semata-mata pemahaman kategorial (substansi, kausalitas, dan sebagainya). 21 Karakter pemahaman Ada ini hanya secara jelas dan lengkap dijelaskan dalam “Being and Time”. 52 Suatu entitas menurut Heidegger tidak terpahami cara meng-Ada nya (its mode of Being) semata-mata berdasarkan konsep-konsep seperti substansi, esensi, kausalitas, posibilitas, dan seterusnya, melainkan berdasarkan totalitas referensial entitas tersebut dalam merealisikan dorongan manusia (Dasein) untuk meng-Ada (drive-to-Be/Seinkonnen). Misalnya, sebuah kapur, dalam perspektif Kant, dipahami karena substansinya yang berwarna putih, sementara dalam perspektif Heidegger, kapur tersebut dipahami dalam totalitas referensialnya dengan papan tulis, penghapus, penggaris yang semuanya terungkap (disclosed) karena dorongan Dasein untuk meng-Ada (mis, meng-Ada sebagai dosen). Bentuk pemahaman yang terakhir ini bagi Heidegger bersifat pra-ontologis, terikat dengan dunia (kontekstual), dan mewaktu. Sementara dalam Kant, pemahaman berdasarkan konsep-konsep murni itu bersifat sadar (reflektif), lepas dari “dunia” ∗ , dan berada dalam rangkaian waktu “sekarang”. 22 Titik tolak penting yang perlu terus diingat dalam pemikiran Heidegger, baik dalam “Being and Time” atau pun dalam Kant and the Problem adalah fenomena pemahaman Ada. Dalam pembacaannya terhadap Kant, Heidegger menemukan fenomena pemahaman tersebut pada doktrin penerapan konsep (skematisme), yaitu, momen terbentuknya skema transendental oleh imajinasi transendental—ini tentu saja terlepas dari apakah Kant sendiri memaksudkannya demikian atau tidak. Secara konseptual, Heidegger menyejajarkan pemahaman Ada dengan skema transendental karena pada titik itulah transendensi terbentuk; ∗ Maksudnya: lepas dari konteks referensialitas cara meng-Ada entitas-entitas lain. Bedakan dengan konsep “mewaktu” Heidegger. 22 53 dan Dasein sebagai entitas yang terbuka pada Ada disejajarkan dengan imajinasi transendental. 23 Apa yang membedakan Heidegger dari Kant adalah gagasan bahwa skema transendental (atau pemahaman Ada) itu adalah fakta terjelas dalam kehidupan sehari-hari manusia (Dasein) dibandingkan fakta rasio yang ditafsirkan sebagai dasar pemahaman oleh Kant. Rasio yang ditafsirkan sebagai fakultas aturan bagi pemahaman dan karenanya menjadi dasar pemahaman, menurut Heidegger, bisa “ya” bisa juga “tidak” (perhaps ultimate intelligibility). 24 Kenyataannya, fenomena pemahaman Ada bagi Heidegger adalah fenomena yang jauh lebih kompleks dari sekadar pembentukan konsep-konsep. Seorang jawa yang memahami dirinya sebagai jawa mengandaikan pemahaman akan keterkaitan seluruh modus Ada entitas (aksesoris, gestur, busana, bahasa dan sebagainya) yang semua itu terungkap (discovered) dalam rangka realisasi-diri seorang jawa (meng-Ada sebagai jawa). Fenomena ini tentu tidak dapat dijelaskan dengan perspektif pembentukan konsep-konsep dan penerapannya ke dalam pengalaman sebagaimana dalam paradigma Kant. C. IMAJINASI TRANSENDENTAL DAN GAGASAN TENTANG TRANSENDENSI TERBATAS Heidegger tidak sekadar menunjukkan bahwa imajinasi transendental itu adalah fakultas pemahaman Ada yang bersifat temporal, pra-ontologis, dan terlibat dengan dunia. Sebagai fakultas transendental, imajinasi transendental juga mengeksplisitkan aspek lain dari pemikiran Kant, yaitu ide keterbatasan. Gagasan 23 William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 153-154 24 Hubert L Dreyfus, Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I (Cambridge: The MIT Press), h. 155-161 54 keterbatasan dalam pemikiran Kant sudah sejak awal ditegaskan oleh Heidegger dalam bab pertama Kant and the Problem. Dia menafsirkan bahwa salah satu “motif” dari upaya filsofis Kant dalam “Critique” tidak lain adalah menentukan batas-batas pengetahuan metafisis-dogmatis. 25 Upaya tersebut, menurut Heidegger, ditempuh dalam bentuk penyelidikan terhadap struktur rasio karena menurut Kant rasio adalah fakultas pengetahuan yang mensuplai konsep-konsep murni pemahaman, sebagai faktor esensial dalam pembentukan pengetahuan. 26 Sebagai faktor esensial pengetahuan, Kant menunjukkan pada saat yang sama bahwa rasio itu terbatas. Keterbatasan rasio itu terletak pada kenyataan bahwa konsep-konsep murni yang dihasilkan rasio bukanlah konsep-konsep yang memberikan informasi tentang kenyataan eksternal, melainkan semata-mata aturan pemahaman yang hanya berfungsi sebagai aturan jika mereka diterapkan ke dalam pengalaman. Karena itulah, menurut Kant, suatu pemikiran yang sematamata mendasarkan dirinya pada rasio (mere reason) semisal metafisika tidaklah memberikan pengetahuan apa pun tentang kenyataan, kecuali sebagai spekulasispekulasi yang diselubungi antinomi-antinomi. 27 Dalam destruksi Heidegger, sementara itu, ketergantungan rasio pada intuisi yang ditegaskan oleh Kant menunjukkan bahwa esensi keterbatasan itu terletak pada intuisi. 28 Pada level intuisi lah menurut Heidegger pengetahuan manusia mula-mula terbentuk, suatu pandangan yang Kant sendiri menyetujuinya 25 Penafsiran ini kenyataannya sudah mulai umum bahkan di kalangan komentatorkomentator pemikiran Kant sendiri. Lihat misalnya salah satu komentar Paul Guyer dalam pengantarnya untuk The Cambridge Companion to Kant (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), h. 1-25 26 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 9 27 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 6 28 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 14-16 55 dalam beberapa paragraf “Critique”-nya. Karena itu, menurut Heidegger, penyelidikan terhadap esensi keterbatasan pengetahuan manusia harus bertolak dari keterbatasan intuisi sebagai aspek fundamental pengetahuan: Intuisi manusia itu terbatas karena intuisi manusia tidak menciptakan objek yang diintuisinya. Intuisi manusia sekadar bersifat reseptif (menerima). Ia adalah sejenis fakultas pemahaman yang memungkinkan manusia (Kant: subjek) terafeksi oleh objek-objek di sekitarnya yang memang sudah ada. Lawan dari intuisi terbatas manusia (finite intuition) adalah intuisi ilahi yang tak terbatas (Divine Intuition). Intuisi ilahi, Heidegger mengutip Kant, bersifat kreatif, yaitu, menciptakan objek yang diintuisinya. Karena itu, intuisi ilahi tidak memerlukan fakultas lain semisal rasio yang berfungsi menyatukan data-data atau objek-objek intuisi dalam rangka membentuk pemahaman. Rasio adalah konsekuensi langsung dari intuisi terbatas (finite intuition). 29 Bagi intuisi ilahi, proses “pemahaman” atau pengetahuan adalah efek dari keterbatasan. Intuisinya sudah lebih dari memadai dibandingkan pemahaman rasional (berdasarkan nalar/rasio), karena itu intusi ilahi tidak membutuhkan pemahaman demikian. Jika kita mengikuti alur logis dari pengandaian ini, maka apa yang terintuisi dalam intuisi ilahi adalah keseluruhan kenyataan-pada-dirinya (numena/thing in itself). Sementara apa yang terintuisi dalam intuisi terbatas adalah kenyataan parsial yang berjarak terhadap subjek, yang kompleksitasnya tidak terkuasai oleh intuisi terbatas subjek. Karena itu kenyataan yang tampak pada intuisi terbatas hanyalah kenyataan sebagaimana ia ditampakan 29 (fenomena/appearance), bukan kenyataan pada dirinya Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 17 56 (numena/the thing-in-itself). Intuisi terbatas hanya menerima “pantulan” dari kenyataan yang sesungguhnya. 30 Dalam Kant and the Problem, pembacaan Heidegger menyangkut tema keterbatasan diarahkan pada ciri terbatas imajinasi transendental. Sebagaimana rasio adalah konsekuensi lebih jauh dari keterbatasan intuisi, demikian halnya dengan imajinasi transendental. Imajinasi transendental bersifat terbatas karena imajinasi tidak menciptakan objek apa pun. Walaupun imajinasi transendental sebagai fakultas yang mengkonstitusi transendensi memiliki fungsi pengetahuan, dalam transendensi itu sendiri tidak ada “sesuatu” pun yang diketahui. Dalam bahasa Kant, apa yang diketahui dalam transendensi (sintesis murni/skema transendental) adalah ketiadaan, nothing. Heidegger menafsirkan “ketiadaan” tersebut sebagai Ada (non-beings/bukan-sesuatu) dan transendensi karenanya adalah pemahaman Ada. Tetapi itu tidak mengubah arti “ketiadaan” sebagaimana yang dipahami oleh Kant. Ada, bagi Heidegger, juga bukanlah apa pun (nothing). Perbedaannya, dengan menggunakan kata “Ada” Heidegger menjadi lebih mudah untuk menunjukkan bagaimana “ketiadaan” tersebut mengkonstitusi pemahaman atau pengetahuan empiris Dasein. Demikian misalnya, Heidegger akan selalu mengatakan bahwa pemahaman terhadap suatu entitas adalah karena entitas itu Ada; karena entitas tersebut terpahami cara-Adanya dan bahwa cara Ada suatu entitas selalu terkait secara referensial dengan cara Ada entitas-entitas lain. Tentu saja transendensi adalah sejenis kemampuan. Namun kemampuan di sini bukanlah kemampuan untuk membuat objek, melainkan kemampuan 30 Namun demikian, bagi Heidegger, “kenyataan pantulan” atau pun “kenyataan yang sesungguhnya” adalah kenyataan yang sama. Istilah penampakan (pantulan) dan kenyataan sesungguhnya bagi Heidegger sebenarnya adalah perbedaan intuisi ilahi dan intuisi terbatas. Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 22-23. 57 memahami objek, memahami cara meng-Ada nya. Ada hanya memiliki fungsi pemahaman, bukan fungsi penciptaan. Menjadi paham bagi Heidegger tidaklah membuat intuisi terbatas subjek menjadi tidak terbatas. Karena itu, alih-alih mengatakan bahwa transendensi adalah keistimewaan yang dimiliki subjek, bagi Heidegger lebih tepat mengatakan bahwa transendensi adalah ciri keterbatasan. Transendensi adalah konsekuensi keterbatasan. 31 Pada level ini, kita tentu dapat membuat pertanyaan spekulatif: apakah transendensi itu diperlukan jika manusia menciptakan objeknya sendiri? Ide tentang transendensi terbatas (finite transcenedence) tampak juga dalam sifat temporal imajinasi transendental. Sebagaimana telah sedikit disinggung, temporalitas imajinasi transendental berbeda dari konsep waktu Kant yang dipahami sebagai urutan “sekarang” (sequence of nows). Temporalitas atau kemewaktuan bagi Heidegger adalah gagasan keterarahan imajinasi transendental pada kemungkinan; sejenis antisipasi atau ekspektasi yang terarah pada masa depan—dalam terminologi Kantian disebut sintesis rekognisi murni. Kemewaktuan semacam ini harus dipahami sebagai ciri keterbatasan menurut Heidegger, karena “keterarahan pada kemungkinan” yang dimaksud di sini bukanlah semacam perencanaan yang dengan rencana tersebut manusia memegang kendali atas dirinya atau entitas-entitas selainnya. Antisipasi itu lebih tepat digambarkan sebagai semata-mata dorongan atau impuls untuk meng-Ada (drive-to-be/seinkonnen). Dalam “Being and Time”, Heidegger menerapkan konsep ini secara lebih jelas, di mana Dasein (sinonim dari imajinasi transendental) yang selalu terarah pada kemungkinan menunjukkan bahwa Dasein 31 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 53 58 tidak pernah mengalami sudah; dorongan untuk meng-Ada bukanlah semacam dorongan yang dapat dipenuhi seperti halnya dorongan rasa lapar atau haus. 32 Dalam Heidegger, dorongan untuk meng-Ada adalah dorongan primordial yang selalu hadir dalam setiap aktivitias pemahaman manusia. Dorongan tersebut tidak hilang disebabkan seseorang telah mencapai cita-citanya. 33 Ketika seorang guru sedang mengajar, dia selalu berada dalam dorongan tersebut dan hanya jika dorongan itu tetap ada, dia dapat mempraktikkan (memahami) perannya sebagai guru. Dengan demikian, Dasein tidak pernah mengalami sudah; Dasein selalu mengalami kebeluman yang dengan kebeluman tersebut Dasein selalu berada dalam kondisi realisasi-diri terus menerus, sebuah kenyataan yang bagi Heidegger menunjukkan bahwa Dasein selalu berada dalam keterbatasan. Tapi tidakkah dengan mengatakan itu menunjukkan bahwa transendensi bukan semata-mata konsekuensi keterbatasan, melainkan keterbatasan itu sendiri? Kenyataannya Heidegger berpendapat demikian. Bagi Heidegger, transendensi adalah keterbatasan itu sendiri. 34 D. IMPLIKASI KONSEP TRANSENDENSI HEIDEGGER TERHADAP PEMIKIRAN ETIKA DAN KEAGAMAAN Di luar konteks pemikiran Heidegger, kita dapat menemukan beberapa konsekuensi pemikirannya yang signifikan dalam berbagai tradisi pemikiran. Terkait dengan model pembacaan yang diperkenalkannya, pemikiran Heidegger memiliki kontribusi besar terhadap munculnya tradisi tafsir baru yang dikenal 32 William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 38-39 33 Hubert L Dreyfus, Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I (Cambridge: The MIT Press), h. 187 34 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 61. Lihat juga William J Richardson, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963), h. 135. 59 sebagai hermeneutika filosofis, suatu model pembacaan yang motif utamanya tidak diarahkan pada intensi pengarang melainkan pada tegangan persoalan yang terkandung dalam teks. Eksponen utama dari tradisi tafsir ini adalah Hans Georg Gadamer, seorang murid langsung Heidegger. Selain itu, tidak bisa dihindarkan juga kontribusi model pembacaan destruktif Heidegger terhadap dekonstruksi Derrida, sebuah strategi pembacaan yang mengusut jalinan oposisi biner dalam sebuah teks dan proses diseminasi makna yang terjadi di dalamnya. Pemikiran Heidegger memang memiliki potensi pemikiran yang sangat besar. Pengaruhnya cukup sepadan dengan pemikir-pemikir lain seperti Kant, Hegel, Nietzsche atau pun Husserl. Tidak heran, jika pemikirannya sering diklaim memberikan titik tolak penting bagi upaya-upaya baru dalam pemikiran filsafat, terutama yang dewasa ini sering disebut-sebut sebagai posmodernisme. Namun demikian, terkait dengan konsep transendensi dan praktik destruksi atas pemikiran Kant, saya hanya akan menggarisbawahi beberapa implikasi penting pemikiran Heidegger, yaitu dalam wilayah pemikiran etika dan keagamaan. Bersamaan dengan pembahasan ini, saya juga hendak mengemukakan keterbatasan konsep transendensi Heidegger, di samping potensi pemikirannya yang terbuka untuk ditafsirkan ulang. 1. Destruksi atas “Critique” sebagai Ontologisasi Pemikiran Kant: Konsekuensi Penting dalam Pemikiran Etika Dalam “Kant and the Problem”, Heidegger tidak banyak berbicara tentang etika. Heidegger hanya membicarakan etika tidak lebih dari lima halaman dalam 60 “Kant and the Problem”. 35 Itu pun sekadar untuk menunjukkan bahwa rasio, yang teoritis (theoretical reason) atau pun praktis (practical reason), hanya memiliki dasarnya pada imajinasi transendental. Dengan kata lain, fokus pembacaan Heidegger adalah semata-mata pada imajinasi transendental dan proses terbentuknya transendensi sebagai pemahaman Ada, sementara tema rasio dianggap sekunder dalam pembacaannya. Perlakuan Heidegger dalam pembacaannya terhadap konsep rasio Kant semacam ini menurut beberapa komentator menjadi sejenis ontologisasi; Heidegger mereduksi gagasan epistemologis dan etis Kantian menjadi sepenuhnya bersifat ontologis (ontologisasi), yaitu, menjadi diskursus tentang Ada. Heidegger merangkum semua pandangan epistemologis dan etis Kant kedalam satu kata, “Ada”. Menurut hemat penulis, pada level “epistemologis” destruksi Heidegger memang memperlihatkan keunggulan konsep transendensi yang dibangunnya, yakni transendensi sebagai pemahaman Ada. Dia berhasil menunjukkan, bahkan dalam argumen Kantian, keniscayaan transendensi sebagai pemahaman Ada dalam teks “Critique”, yaitu dalam gagasan sintesis murni atau representasi skema transendental yang dibentuk oleh imajinasi transendental. Sebagaimana diperlihatkan dalam “Being and Time”, konsep pemahaman Ada Heidegger lebih mampu menangkap fenomena pemahaman yang terbentuk dalam dunia sehari-hari yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan perspektif pemahaman kategorial Kant (pemahaman berdasarkan kategori-kategori). Hubungan-hubungan yang terjadi antara manusia dengan dunianya (entitas-entitas dalam dunia) bagi Heidegger tidak tampak seperti hubungan representatif subjek-objek sebagaimana dipahami 35 Lihat misalnya, Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 109-112 61 Kant; bukan regulasi rasio murni atas ciri-ciri partikular suatu objek hasil representasi intuisi. Hubungan manusia dengan dunianya adalah hubungan terlibat (involved) yang dibentuk oleh peristiwa ketersingkapan Ada yang merupakan kondisi primordial bagi manusia yang memungkinkannya memahami cara Ada setiap entitas dalam dunia, termasuk cara Ada dirinya (its Being). Tentang hal ini, di atas telah disinggung bagaimana Ada tersebut tersingkap atau terpahami secara referensial (terikat dalam dunia), mewaktu, dan pra-ontologis. Sementara itu, pada level etis, ontologisasi dalam pembacaan Heidegger membawanya pada sejenis pandangan moral yang indifferent; dia menjadi abai dalam soal prinsip moral-normatif suatu tindakan. Karena itu, bagi beberapa pemikir, terutama yang tergabung dalam mazhab Frankfurt (teori kritis) misalnya, pemikiran ontologis Heidegger adalah pemikiran yang mandul ketika dihadapkan pada problem-problem etis. Ini pernah diperlihatkan oleh Heidegger sendiri ketika dia terlibat dengan partai Nazi dan secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Hitler pada tahun 1933 dan 1934. Dukungan ini bagi mereka memiliki kaitan yang sangat jelas dengan pemikirannya. Pemikiran ontologis Heidegger yang memusat pada Ada membuatnya hanya peduli pada cara bagaimana Ada itu tersingkap dalam fenomena pemahaman sehari-hari Dasein atau bagaimana Dasein memahami Ada dirinya (its Being) dan Ada-nya entitas-entitas (Being of beings) dalam dunia. Dalam lingkup kekuasaan, pandangan semacam itu dapat ditransformasi ke dalam bentuk penegasan-diri (realisasi-diri) suatu bangsa, terlepas apakah penegasan diri tersebut ditandai dengan pemusnahan terhadap suatu ras tertentu atau tidak, bermoral atau tidak. 36 36 Terry Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1990), h. 310 62 Tentu saja kita masih bisa menemukan sisi normatif dalam pemikiran Heidegger, tetapi yang normatif tersebut bukan semacam prinsip etis. Semua hal yang normatif bagi Heidegger adalah produk keduniaan Dasein (faktisitas) yang dari satu budaya ke budaya lain memiliki arti yang berbeda. Hara kiri di Jepang adalah suatu praktik yang masuk akal sebagai simbol harga diri dan kehormatan, namun tidak demikian halnya di Indonesia di mana bunuh diri diartikan sebagai sikap frustasi dan putus asa. Yang normatif dalam pemikiran Heidegger itu tidak lebih dari cara bagaimana Dasein hidup dalam dunianya, meng-Ada atau merealisasikan dirinya sebagai ini atau itu. Apakah cara meng-Ada dibenarkan atau tidak, masing-masing kebudayaan (dunia di mana Dasein hidup) memiliki kode-kodenya sendiri. Karena itu, Heidegger tidak mengenal prinsip etika universal sebagaimana Kant. Heidegger hanya mengenal yang normatif sebagai produk faktisitas yang bersifat lokal; sementara yang universal adalah pemahaman Ada itu sendiri. Faktisitas menurut Heideger mendefinisikan Dasein tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak, mana yang tepat dan mana yang tidak. Tentu saja menurut Heidegger individu dalam kebudayaan dapat memberikan perlawanan terhadap aturan-aturan normatif kebudayaannya dan dengan dalih HAM misalnya berusaha mengubah praktik-praktik sosial yang berlaku (misalnya, hara kiri ditentang). Namun masalahnya bagi Heidegger, tidak ada patokan universal tentang yang baik dan yang buruk. Dalam perspektif Heideggerian, HAM itu hanyalah modus tafsir dari cara meng-Ada Dasein yang lahir dari situasi kacau— dan memang temuan-temuan baru dalam pemikiran moral selalu dilatarbelakangi oleh setting sosial yang hancur. Apa yang kita sebut sebagai “kemajuan moral” itu 63 mungkin saja terjadi. Tetapi, dalam perspektif Heideggerian, kemajuan moral itu hanya dapat dikatakan sebagai transformasi modus Ada dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dan kita tidak dapat menyebutnya “kemajuan”. Pergeseran dari rasio ke imajinasi transendental dalam pembacaan Heidegger memandulkan kekuatan etis dalam pemikiran Kant. Tidak heran, mengapa dalam lingkup etika, pandangan orisinal Kant tentang etika masih lebih bergema dibandingkan Heidegger. Namun demikian, walaupun pandangan ontologis Heidegger tidak begitu memberikan sumbangan positif bagi tercegahanya kekerasan, bahkan rentan ditransformasi menjadi kekerasan, pemikirannya memiliki fungsi etis dalam bentuk lain, yakni dalam hal sikap terhadap alam (nature)--karenanya pemikiran dia sering menjadi rujukan populer dalam kritik ekologi. 37 Dalam esai The Question Concerning Technology misalnya, Heidegger menyinggung tema-tema lingkungan dalam kaitannya dengan esensi teknologi. Namun demikian, dalam esai ini pun Heidegger sebenarnya tidak sedang merumuskan suatu konsep etis. Dalam esai ini, dia hendak mengungkapkan esensi teknologi sebagai modus pemahaman Ada tertentu yang secara khusus menandai zaman modern. Dia menjelaskan esensi teknologi adalah sejenis modus penyingkapan (mode of revealing); bukan sekadar seni manipulasi alam sebagaimana umum dalam pemikiran pada masanya. Sebagai modus penyingkapan, teknologi memiliki karakter tak terkontrol. Teknologi menjadi semacam imperatif yang menentukan cara Dasein mengambil sikap terhadap alam. Heidegger menyebutnya “pembingkaian” (enframing); suatu disposisi 37 Terry Eagleton, The Ideology of the Aesthetic, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1990), hlm 310 64 (Gemut) di mana Dasein selalu berhadapan dengan alamnya sebagai sumber daya (energi) yang dapat diolah, disimpan, dan didistribusikan.38 Dengan teknologi, alam tidak tampil (revealed) sebagai alam melainkan sebagai sumber energi yang berguna untuk melayani seluruh kebutuhan manusia setiap saat (available); entah kebutuhan konsumsi atau kebutuhan peperangan. 39 Dalam esai ini, Heidegger melihat sisi yang riskan dalam teknologi. 40 Namun demikian, dia tidak memberikan semacam formula etis untuk mencegah laju destruktif dari teknologi, yang bagi Heidegger jelas tidak mungkin. Dalam esai tersebut, dia hanya merumuskan sejenis cara melihat terhadap teknologi sebagai modus penyingkapan yang di dalamnya terdapat “bahaya”, dan menurutnya, cara melihat semacam itu dengan sendirinya dapat menjadi kekuatan yang menyelamatkan (saving power). 41 2. Transendensi dan Kecenderungan Religius: Pemahaman Ada sebagai Efek Ketidakhadiran Dalam pembacaan Heidegger, filsafat transendental Kant (analisis sitnesis murni), selain dilihat sebagai analisis yang berusaha menunjukkan bagaimana pengetahuan atau pemahaman itu mungkin, juga hendak menunjukkan bagaimana metafisika sebagai kecenderungan alamiah (natural disposition) itu mungkin. Kant sendiri mengindikasikan dalam “Critique”-nya bahwa metafisika sebagai kecenderungan untuk menemukan fondasi-fondasi transendental di luar yang 38 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, pen.&ed. William Levitt (New York: Harper & Row Publishers, 1977), h. 19, 24-25 39 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, pen.&ed. William Levitt (New York: Harper & Row Publishers, 1977), h. 14-15, 40 Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, pen.&ed. William Levitt (New York: Harper & Row Publishers, 1977), h. 33 41 Menurut Heidegger, refleksi dan konfrontasi terhadap teknologi hanya dapat dilakukan dalam bentuk seni. Martin Heidegger, The Question Concerning Technology and Other Essays, pen.&ed. William Levitt (New York: Harper & Row Publishers, 1977), h. 35 65 empiris (kecenderungan metafisis) adalah sesuatu yang sah. Menurut Kant, kecenderungan semacam ini memiliki dasarnya pada struktur transendental yang sama dengan sains-sains positif, yaitu pada struktur sintesis murni. 42 Namun demikian, menurut Kant, struktur sintesis murni hanya dapat melahirkan pengetahuan jika konsep-konsep murni yang merupakan komponen dalam sintesis tersebut dapat diterapkan pada pengalaman. Konsekuensinya, bagi Kant, metafisika hanya mungkin sebagai kecenderungan alamiah, tetapi tidak sebagai penyelidikan ilmiah. Pasalnya, konsep-konsep dalam metafisika bukanlah konsepkonsep yang dapat diterapkan dalam pengalaman, melainkan sekadar terkaanterkaan pikiran yang satu sama lain mungkin bertentangan namun tetap samasama rasional (antinomi). 43 Menurut hemat saya, filsafat transendental Kant (analisis sintesis murni) semacam ini pada akhirnya bukan hanya relevan bagi pertanyaan tentang bagaimana metafisika itu mungkin sebagai kecenderungan alamiah, tetapi juga bagaimana agama itu mungkin sebagai kecenderungan alamiah—selanjutnya, saya menyebutnya “kecenderungan religius”. Sebagaimana kecenderungan metafisis, dengan kecenderungan religius saya memaksudkan kecenderungan pada sesuatu yang absolut sebagai fondasi transendental. Karena itu, saya menyejajarkan keduanya walaupun mungkin terdapat perbedaan yang prinsipil. Dalam kaitannya dengan fenomena kecenderungan religius, filsafat transendental Kant yang didestruksi menurut saya memberikan perspektif yang lebih memadai. Sebagaimana telah disinggung, filsafat transendental Kant yang 42 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 56-57 43 Martin Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997), h. 6 atau Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964), h. 385 66 didestruksi adalah filsafat tentang pemahaman Ada. Perspektif pemahaman Ada ini memperjelas beberapa tesis Kant yang sebelumnya tidak begitu tampak dalam “Critique”, seperti tesis tentang temporalitas imajinasi atau transendensi sebagai konsekuensi keterbatasan. Tema-tema ini dapat menjelaskan mengapa kecenderungan religius itu mungkin—walaupun kebanyakan istilah dalam “Critique” sendiri tidak begitu fleksibel untuk digunakan di luar lingkup penyelidikan epistemologis dan metafisis—karena tema-tema tersebut berhubungan secara formal dengan apa yang terjadi dalam setiap kecenderungan religius. Kecenderungan religius adalah kecenderungan manusia pada sesuatu yang tersembunyi di balik penampakan; sesuatu yang sejati yang menjadi dasar terwujudnya kenyataan, sesuatu yang diharapkan, tujuan dari kehidupan dan kematian. Suatu perspektif Heideggerian atau pun “Filsafat transendental Kant hasil destruksi” tentu akan berpandangan bahwa kebutuhan akan fondasi itu adalah wujud dari karakter temporal transendensi; fenomena yang sudah selalu jelas dalam praktik kehidupan sehari-hari manusia yang, bahkan pada tataran sangat praktis, selalu ditandai oleh dorongan untuk meng-Ada. Dorongan ini bersifat temporal karena meng-Ada selalu berarti “berada dalam kemungkinan”; semacam keadaan terhempas terus menerus dalam jurang tanpa dasar. Karakter temporal inilah yang membentuk kecemasan, harapan, ketakutan dan segala hal yang mencirikan kondisi eksistensial manusia, yang karenanya agama lahir untuk menjawabnya. Dengan kata lain, dimensi transendental manusia yang selalu terarah pada kemungkinan itulah yang membentuk kecenderungan religius sehingga agama menjadi sesuatu yang dapat diterima (acceptable). 67 Tetapi apakah yang dimaksud Heidegger dengan dorongan untuk mengAda atau pemahaman Ada? Apakah itu satu-satunya penafsiran atas fenomena transendental? Adakah titik tolak lain untuk menafsirkan kecenderungan religius yang dari titik tolak itu kita bisa menafsirkan ulang konsep transendensi Heidegger (transendensi sebagai pemahaman Ada)? Berbeda dari perspektif Heideggerian, saya ingin menafsirkan fenomena kecenderungan religius di atas sebagai fenomena keterarahan pada “yang tidak hadir”. Sesuatu dikatakan tidak hadir karena ia di luar panca indera kita; melampaui kadar kemampuan nalar kita untuk memahaminya; sepenuhnya lain dari yang dapat kita pahami. Namun demikian, “tidak hadir” tidak berarti “tidak terpahami”. Ada upaya untuk menjelaskan bahwa “ketidakhadiran” tersebut juga sebenarnya hadir, yaitu, dalam selubung tanda-tanda yang terpahami. Dalam ajaran agama (Islam misalnya), di mana kecenderungan religius menemukan bentuknya, Allah sebagai “yang tidak hadir” sebenarnya hadir dalam wujud tandatanda: tatanan harmonis dan seimbang alam semesta, proses penciptaan manusia yang meliputi wujud dan daya hidupnya, dan sebagainya, yang semua itu merupakan tanda dari kehadiran Allah. Dalam ajaran agama, kita mendapat gambaran tentang kecenderungan religius sebagai suasana diliputi oleh ketidakhadiran dan “ketidakhadiran yang meliputi tersebut” adalah tanda-tanda dari kehadiran. Tentu saja orang dapat berdebat tentang apakah tanda-tanda itu secara niscaya merujuk pada suatu entitas ilahiah. Tetapi poinnya tidak terletak pada soal apakah yang tidak hadir tersebut; poinnya terletak pada afeksi ketidakhadiran itu sendiri sebagai disposisi alamiah, dan sebagai disposisi alamiah ia bersifat 68 konsitutif terhadap kecenderungan religius; disposisi alamiah ketidakhadiran membuat manusia seolah tidak bisa menghindar dari pertanyaan tentang apa yang tersembunyi di balik segala sesuatu yang tampak atau hadir. Kita bisa mengatakan bahwa afeksi ketidakhadiran itu adalah efek dari transendensi atau pemahaman Ada, suatu penafsiran yang mungkin lahir dari perspektif Heideggerian. Tetapi, menurut saya, kita juga sebenarnya bisa mengatakan sebaliknya; transendensi sebagai pemahaman Ada adalah efek dari ketidakhadiran. Kenyataannya, Heidegger dalam Kant and the Problem pernah menyejajarkan konsep Ada dengan Ketiadaan (no-thing) dan dia berkali-kali dalam karya yang berbeda menegaskan bahwa Ada itu adalah bukan-pengada atau bukan-entitas (non-beings). Apakah yang dimaksud Heidegger dengan “ketiadaan” (no-thing) atau “bukan-pengada” (non-beings)? Apakah yang dimaksud oleh Heidegger dengan “dorongan untuk meng-Ada” (drive-to-Be) yang merupakan ciri temporal transendensi? Bukankah Heidegger sebetulnya sedang membicarakan tentang sesuatu yang tidak hadir? Menurut saya, pemikiran Heidegger tentang transendensi sebagai pemahaman Ada atau ketersingkapan Ada pada kenyataannya merupakan proyeksi dari “afeksi ketidakhadiran” dan karenanya kita bisa menjelaskan ulang seluruh tesis pemikiran Heidegger berdasarkan konsep ketidakhadiran tersebut. Apa yang saya jelaskan di atas, tentang transendensi dan kecenderungan religius, hanyalah salah satu kemungkinan penerapan perspektif transendental Heidegger untuk menjelaskan fenomena transendensi, dalam hal ini fenomena kecenderungan religius. Namun, sebagaimana telah kita lihat, perspektif transendental Heidegger tidak menutup kemungkinan bagi penafsiran lain atas 69 gejala eksistensi yang sama. Kita dapat menafsirkan kecenderungan religius sebagai afeksi ketidakhadiran--bahkan, kita juga dapat menafsirkan bahwa konsepsi transendensi Heidegger sendiri (transendensi sebagai pemahaman Ada) adalah efek dari ketidakhadiran. Sekadar tambahan, saya ingin mengatakan bahwa penafsiran ini sebenarnya sudah terantisipasi oleh Heidegger. Dalam “Being and Time” Heidegger pernah mengatakan bahwa pemikirannya adalah sejenis penafsiran yang selalu mungkin untuk ditafsirkan ulang. Sebagai penafsiran, ia dibentuk oleh: 1) pengandaian-pengandaian yang sudah ada sebelumnya (fore-having); 2) pemilihan sudut pandang atau titik tolak yang digunakan (fore-sight), dan; 3) konsepsi tertentu tentang materi yang ditafsirkan (fore-conception). 44 Tiga aspek ini menurut Heidegger selalu menyertai setiap aktivitas penafsiran, termasuk penafsirannya dalam “Being and Time” atau pun dalam pembacaan destruktifnya atas doktrin skematisme Kant. Karena itu, terbuka kemungkinan bahwa pembacaan Heidegger atas doktrin skematisme atau pun analisis eksistensialnya dalam “Being and Time”, juga dapat ditafsirkan ulang, terutama jika kita bertolak dari pengandaian yang berbeda. Jika dalam destruksinya atau pun dalam analisis eksistensialnya Heidegger menggunakan paradigma pemahaman Ada untuk menjelaskan fenomena transendensi, maka kita dapat memulai dari paradigma lain, paradigma “ketidakhadiran” misalnya. Namun, ada satu hal yang selalu jelas, yaitu bahwa selalu terdapat dikotomi yang menandai setiap kerja rohani manusia: dikotomi antara entitas dan non-entitas (beings dan non-beings). 44 Dreyfus, Hubert L, Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I (Cambridge: The MIT Press), h. 199. 70 BAB IV PENUTUP: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dari bab I hingga bab III tentang fenomena transendensi dan konsepsinya dalam Kant dan Heidegger, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Fenomena transendensi adalah fenomena “purba”. Sejak manusia memulai kehidupan berbudayanya, fenomena transendensi telah berusaha ditafsirkan dengan berbagai cara. Usaha penafsiran ini tidak pernah tuntas. Ia terus berlangsung bahkan hingga manusia memasuki fase kehidupannya yang modern. 2. Kant dan Heidegger adalah dua di antara banyak filsuf yang hendak menafsirkan fenomena transendensi. Kant memahami transendensi sebagai dimensi normatif pengetahuan murni sementara Heidegger memahaminya sebagai pemahaman Ada. Dua gagasan ini tampak berbeda, namun sebagaimana ditunjukkan dalam destruksi Heidegger, gagasan transendensi Kant sebenarnya adalah gagasan keterarahan pada “yang bukan-objek” atau non-entitas (non-beings/no-thing) dan itu sama dengan pemahaman-Ada bagi Heidegger--karena Ada adalah bukan-pengada (non-beings). 3. Sebagai keterarahan pada non-entitas, transendensi itu berciri temporal, dengan kata lain, memiliki karakter waktu (mewaktu). Kenyataannya, apa yang kita sebut sebagai “waktu” justru memiliki dasarnya pada temporalitas transendensi. Temporalitas transendensi adalah asal mula pemahaman kita 71 tentang waktu. Tesis ini adalah tesis Heidegger yang dapat ditemukan baik dalam “Being and Time” atau pun dalam “Kant and the Problem”. Dalam “Kant and the Problem”, Heidegger menunjukkan sifat temporal transendensi melalui destruksinya atas doktrin skematisme Kant. Dalam konteks destruksi ini, gagasan transendensi dan sifat temporalnya berkaitan dengan konsep Kant tentang imajinasi transendental, semacam fakultas pengetahuan yang memediasi penerapan konsep-konsep murni ke dalam pengalaman melalui determinasi waktu (sintesis murni dan pembentukan skema transendental). 4. Transendensi sebagai momen pemahaman Ada tidak dapat dilihat secara utuh jika didekati dari perspektif hubungan representatif subjek-objek yang bersifat “rasional” (ditentukan oleh kriteria-kriteria rasio). Mendekati fenomena transendensi dari perspektif semacam ini dapat mereduksi pengertian transendensi (pemahaman Ada) ke dalam pemahaman kategorial. 5. Transendensi adalah konsekuensi keterbatasan, yaitu keterbatasan intuisi manusia. Intuisi manusia itu terbatas karena intuisi tersebut tidak menciptakan objek apa pun. Selain dalam hubungannya dengan intuisi, transendensi dan ide keterbatasan juga terkait dengan karakter temporal transendensi (dalam konteks destruksi: temporalitas imajiansi transendental), di mana transendensi selalu dicirikan oleh kebeluman. 6. Walaupun destruksi Heidgger memiliki keunggulan dalam perspektif transendensinya, transendensi yang ditafsirkan sebagai pemahaman Ada rupanya tidak dapat dijadikan titik tolak pemikiran etika. Pandangan salahbenar tentang suatu perbuatan dan benar (etika), dalam perspektif ini, hanya akan dianggap sebagai produk lokalitas yang tidak dapat berlaku universal. 72 Karena itu, di sini kita melihat kelemahan dari pembacaan destruktif Heidegger atas Kant; walaupun secara epistemologis pembacaannya memberikan wawasan baru dalam pemahaman filsafat transendental Kant, destruksinya justru mempersempit pandangan etika Kant. 7. Kapasitas transendental atau transendensi merupakan syarat kemungkinan bagi pengetahuan, metafisika, bahkan kecenderungan religius. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas transendental merupakan struktur yang mendasari setiap segi eksistensi manusia; harapannya, kecemasannya, ketakutannya; semua aktivitasnya, baik yang teoritis maupun praktis. Dalam Heidegger, kita menemukan bahwa kapasitas transendental ini sebagai pemahaman Ada. Namun demikian, konsep “pemahaman Ada” Heidegger sendiri adalah suatu penafsiran yang selalu terbuka untuk ditafsirkan ulang. Kita misalnya dapat mengajukan paradigma lain di mana fenomena transendensi (kapasitas transendental) dipahami sebagai efek ketidakhadiran. B. REKOMENDASI UNTUK PENELITIAN LEBIH LANJUT Apa yang telah saya kemukakan dalam skripsi ini menyangkut tema transendensi dalam pemikiran Heidegger atau pun Kant sangat jauh dari cukup. Penelaahan lebih dalam tentang konsep ini dan penerapannya dalam studi-studi lain masih perlu terus dilakukan. Karena itu, saya merekomendasikan beberapa kemungkinan penelaahan lebih jauh sebagai berikut: 1. Studi atas pembacaan Heidegger terhadap konsep waktu Aristoteles dan konsep Cogito Descartes sebagaimana yang direncanakan Heidegger sendiri dalam “Being and Time”. Rujukan utama untuk studi ini dapat ditemukan dalam beberapa karya Heidegger yang lain, salah satunya adalah “Basic 73 Problems of Phenomenology”. Ini penting dilakukan untuk melihat lebih jauh pembacaan destruktif Heidegger dan membuktikan bahwa problem tentang “arti” Ada selalu implisit dalam teks-teks filsafat. 2. Studi atas konsep estetika Heidegger. Heidegger memang tidak merumuskan suatu konsep estetika tertentu. Namun demikian, perlu diketahui bahwa pemikiran Heidegger sebenarnya sangat kental dengan nuansa estetis, terutama dalam tahap pemikirannya paska “Being and Time” yang sering dikenal dengan “Heidegger II”. Untuk studi ini, kita dapat merujuk pada sejumlah esai yang ditulis Heidegger, misalnya dalam “Origin of the Work of Art” atau dalam esai “The Question Concerning Technology”. Dalam studi ini kita akan melihat titik tolak yang berbeda dari analisis Heidegger atas fenomena pemahaman Ada. Jika dalam “Being and Time” Heidegger bertolak dari entitas Dasein, dalam esai-esai ini, dalam “Origin of the Work of Art” misalnya, dia bertolak dari definisi tentang apa itu “sesuatu” (thing/Sage). 3. Tinjauan kritis pemikiran Heidegger dari perspektif teori kritis, dengan eksponen-eksponen utamanya seperti Horkheimer, Adrono, dan Habermas di samping beberapa pemikir lainnya. Ini tampaknya penting dikaji karena kita dapat melihat kelemahan-kelemahan pemikiran Heidegger dari sudut berbedabeda, misalnya, dari sudut etika, estetika, atau sosiologi. 4. Terkait dengan studi-studi keislaman, pemikiran Heidegger tampaknya perlu ditransformasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan sebagai pisau analisis. Untuk tujuan ini, pemikiran Heidegger dapat ditransformasi misalnya ke dalam suatu pandangan teologis atau ke dalam sejenis hermeneutika kitab suci. Dalam bagian terakhir bab III, saya menyinggung kaitan antara konsep 74 transendensi Heidegger dengan fenomena kecenderungan religius. Tinjauan ringkas yang tidak memadai ini barangkali dapat dipakai sebagai gambaran awal tentang bagaimana perspektif Heidegger diterapkan dalam lingkup kajian agama. Wallahu A’lam 75 Daftar Pustaka: Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996) Bertens, K, ETIKA, Seri Filsafat Atmajaya: 15 (Jakarta: Gramedia, 2001) _________, Filsafat Barat Kontemporer, Perancis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) Cassirer, Ernst, Kant’s Life and Thought, pen. James Haden (Yale University Press, 1981) Dreyfus, Hubert L, Being-in-the-World, A Commentary on Heidegger’s Being and Time Division I (Cambridge: The MIT Press) Eagleton, Terry, The Ideology of the Aesthetic, (Massachusetts: Blackwell Publishers, 1990) Guyer, Paul (ed.), The Cambridge Companion to Kant (Cambridge: Cambridge University Press, 1996 Heidegger, Martin, Basic Problems of Phenomenology, pen. Alfred Hofstadter (Bloomington: Indiana University Press, 1982) __________, Basic Writings, from Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964), ed. David Farrel Krell (San Francisco: Harper Collins Publishers, 1993) ____________, Being and Time, pen. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York, 1996) __________, Existence and Being, pen. Werner Brock (Chicago: Henry Regnery Company, 1949) __________, History of the concept of time, pen. Theodore Kisiel (Bloomington: Indiana University Press, 1985) 76 __________, Kant and the Problem of Metaphysics, pen. Richard Taft (Bloomington: Indiana University Press, 1997) __________, The Question Concerning Technology and Other Essays, pen.&ed. William Levitt (New York: Harper & Row Publishers, 1977) Inwood, Michael, A Heidegger Dictionary (Oxford: Blackwell Publisher, 1999) Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, pen. Norman Kemp Smith (New York: St Martin Press, 1964) Kaufmann, Walter & Forrest E. Baird (ed.), Modern Philosophy, Pilosophic Classics, 2nd Edition, Volume III, (New Jersey: Prentice Hall, 1997) Muller-Volmer, Kurt (ed.), The Hermeneutics Reader, Texts of the German Tradition from the Enlightenment to the Present (New York: Continuum, 1985) Richardson, William J, Heidegger, Through Phenomenology to Thought (The Hague: Martinus Nijhoff, 1963) Ricoeur, Paul, Hermeneutics and the Human Sciences, Essays on language, Action and Interpretation, (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) Suseno, Franz Magnis, Pijar-Pijar Filsafat, Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernisme, (Jakarta: Kanisius, 2005) Taminiaux, Jacques, Heidegger and the Project of Fundamental Ontology, pen. & ed., Michael Gendre (Albany: State University of New York Press, 1991) West, David, An Introduction to Continental Philosophy, (Cambridge: Polity Press, 1996)