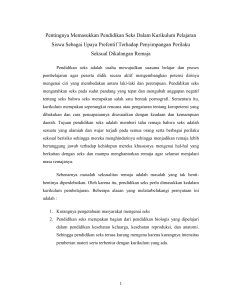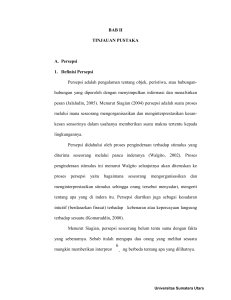SEKSUALISASI MEDIA DAN PERILAKU SEKSUAL ANAK DAN
advertisement
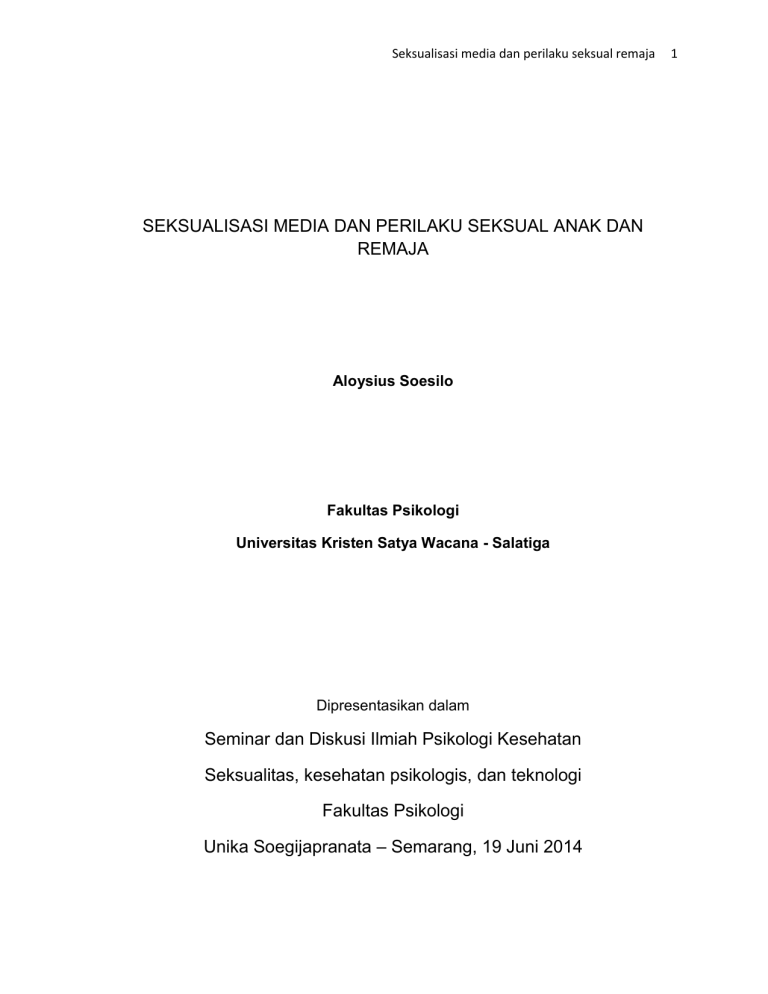
Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja SEKSUALISASI MEDIA DAN PERILAKU SEKSUAL ANAK DAN REMAJA Aloysius Soesilo Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana - Salatiga Dipresentasikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah Psikologi Kesehatan Seksualitas, kesehatan psikologis, dan teknologi Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata – Semarang, 19 Juni 2014 1 Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 2 Abstract The focus of this article is on the presentation of sex and sexualized media and its impact on young people. Discussions on sex or sexuality in the media are difficult to be realized and complicated by conflicts of interest from a variety of perspective, cultural, ideological, religious, and moral. Meanwhile, the increasing exposure of young people to sexually explicit material has been cited as a significant influence on their sexuality, sexual identity and health. This article presents some research findings that highlight the intersection of these issues with the context of sexualized media and culture. Our understanding of these studies would help us understand how young people construct their sexuality, sexual identity , their engagement with, and experiences, of sexualized culture from their own perspectives. Much can be investigated in these topics, and some examples of research areas are presented also in this article for future research. Key words: teenagers, sexuality, sexualized media and culture Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 3 SEXUALISASI MEDIA DAN PERILAKU SEKSUAL ANAK DAN REMAJA Ranah privat yang menyangkut seksualitas menjadi terbuka untuk publik melalui media. Perdebatan mengenai sensor, moralitas sosial dan perlindungan anak dan remaja dan sexual abuse dipicu oleh munculnya gambar dan tayangan seksual lewat televisi, film, dan media cetak serta digital. Menurut suvei oleh Time/CNN pada tahun 1998 (dalam Harris & Scott, 2002), 29% remaja di Amerika Serikat menyatakan TV sebagai sumber informasi yang paling penting tentang seks. Dan angka ini melonjak dari 11% pada 1986. Sumber yang paling banyak disebut adalah teman (45%), orangtua hanya 7% dan pendidikan seks menduduki porsi yang lebih kecil, yaitu 3%. Barangkali keadaan yang lebiih kurang sama juga terjadi Indonesia. Lalu menjadi kesempulan yang berlaku umum bahwa dari masa kanak-kanak, lewat remaja dan menuju dewasa awal, orang lebih belajar tentang seks dari media sebagai sumber informasi utama. KARAKTERISTIK KONTEKS SEKSUAL DALAM MEDIA Literatur membedakan antara materi seksual dengan kekerasan (violent sexual material) dan materi seksual tanpa kekerasan (npnviolent sexual material). Walaupun materi seksual tanpa kekerasan tidak mempertontonkan penyiksaan, sadomasokisme, pukulan, dsb., jenis ini bisa saja mempresentasikan konten yang menempatkan manusia pada posisi dikuasai, dihina, direndahkan, sekedar obyek bagi yang lain. Pelaku (umumnya wanita) ditampilkan sebagai pihak yang menerima perlakukan ini dan reseptif serta responsif terhadap tuntutan seksual si pria (Harris & Scott, 2002). Seks dalam media tidak terbatas pada penggambaran eksplsit tentang persetubuhan atau pose telanjang, tetapi juga sembarang representasi yang mencitrakan perilaku, minat, atau motivasi seksual. Pencitraan seperti ini tersebar luas dalam iklan dan berbagai jenis produk dari sabun mandi hingga ban mobil. Media dan budaya popular di Amerika Serikat dituduh telah ikut bertanggungjawab atas apa yang disebut dengan ‘over-sexualizing girls’, di mana Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 4 anak perempuan belia dan seksi, atau remaja putri, ditampilkan dengan perilaku seksual, tanpa takut dan malu dan ‘fun’ (American Psychological Association, 2007). Media menyebarkan dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan mitos mengenai seksualitas perempuan muda yang mengidealkan tubuh dan ‘ke-muda-an’ sebagai hal yang ‘cool’ dan seksi. Sejumlah ahli berpendapat kultivikasi mitos semacam inilah yang menguatkan gagasan mengenai eksibisionisme, manipulasi atensi pihak lawan jenis, dan kemudahan terjadinya kekerasan seksual. Penggambaran demikian ini kemudian berujung pada merongrong perkembangan seksual yang sehat pada remaja putri dan menempatkan mereka pada ruang terbatas yang ditentukan oleh ideologi tentang feminitas yang berfokus pada penampilan tubuh yang indah, muda dan menawan. Selanjutnya pencitraan seperti ini menjadi bahan konsumsi yang laku bagi media. Romansa percintaan diangkat sebagai sesuatu yang selayaknya diraih oleh perempuan, dominasi kaum pria menjadi ternormalisasi, sementara itu perasaan perempuan sendiri dikesampingkan. SEKSUALISASI OBYEK DAN OBYEK SEKSUALISASI Sebenarnya cukup problematik untuk mengartikan istilah “seksualisasi” atau terseksualisasi”, karena sifat subektif dan ambigu yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita melihat lebih lanjut tentang seksualisasi, kita meluangkan waktu sejenak untuk mengawali dengan pembahasan singkat tentang seksualitas. Ini tidaklah mengherankan karena konsep seksualitas sendiri erat terjalin dengan setiap disiplin apapun yang bisa kita bayangkan, sehingga seksualitas merupakan contoh bahan studi yang paling interdisipliner (Noonan, 2007). Bagi Noonan, seksualitas lebih dari sekedar aktivitas seksual. Dia bergerak dari hal yang paling remeh-sepele ke hal yang paling mendalam, mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia, baik yang fisk (biomedis) maupun yang psikososial dan kultural. Kendati istilah seksualisasi problematik untuk dirumuskan, tetapi, paling tidak apa yang diupayakan oleh Bragg, Buckingham, Russell dan Willett (2011) untuk mendeskripsikan makna istilah ini yang dikenakan pada berbagai benda atau produk Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 5 bisa membantu kita. Mereka membuat kategori yang luas dan inklusif mengenai barang-barang secara potensial mempunyai makna atau dimaknai secara seksual. (1) Barang/produk yang mempunyai rujukan pada praktek-praktek seksual melalui gambar, kata-kata, or humor. (2) Barang/benda yang nampaknya merujuk pada konteks seksual melalui gambar, kata-kata, warna,dan corak; di mana familiaritas dengan suatu benda bertolak dari konteks yang terseksualisasi. (3) Barang-produk yang menekankan bagian-bagian tubuh dan bentuk-bentuk tubuh yang secara kultural diasosiasikan dengan seksualitas dewasa. (4) Barang/benda yang menjiplak mode atau style yang pada masanya dipandang high fashion untuk orang dewasa. Produk ini mencakup barangbarang yang dipasarkan sedemikian rupa yang mengkombinasikan item-item dari seksualitas dewasa yang diasosiakan dengan masa anak-anak, sedemikian rupa sehingga menormalkan mereka sebagai barang untuk anak. (5) Barang/produk yang merujuk pada stereotipe gender; misalnya dengan berlebihan menekankan daya tarik fisik, mengasosiasikan perempuan dengan cinta dan intimitas, atau mengasosiasikan pria dengan agresivitas dan dominasi, lewat kata-kata, gambar, symbol atau aktivitas. Riset mengenai mengindikasikan bahwa berkembangnya perempuan seksualitas kaum menginternalisasikan perempuan obyektifikasi-diri, mengembangkan harga-diri (self-esteem) yang rendah, mereka meyakini bahwa tubuh adalah situs feminitas dan daya tarik ketimbang kepribadian ataupun capaian edukasional dan karier. Keindahan tubuh adalah jalan mudah menuju penerimaan sosial, romansa dan status. Keyakinan demikian termanisfestasi dalam relasi sosial kaum muda perempuan yang menuntut konformitas pada mitos tentang kecantikan, kompetisi untuk meraup perhatian dari lawan jenis melalui seksualisasi-diri (Lemish, 2011). Dan apabila kemudian terjadi sexual harassment dan sexual abuse, sikap masyarakat yang telah dibentuk oleh pencitraan semacam ini adalah mempersalahkan korban (APA, 2007). Persoalan ini menjadi semakin mendesak untuk memperoleh perhatian karena berkembangnya begitu banyak cara dan corak teknologi komunikasi yang tersedia dengan relatif mudah dilakukan oleh anak dan remaja. Konten seksual macam pornografi menumpang dengan mudah dan tersebar dengan cepat. Sangsi sosial tradisional tidak berdaya ketika berhadapan dengan konsumsi seperti ini. Eksposur Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 6 berulang-ulang terhadap kekerasn seksual bisa berakibat kehilangan kepekaan (desensitisasi) terhadap kekerasan terhadap wanita pada umumnya dan penerimaan/sikap reseptif yang lebih besar terhadap peristiwa dan kisah perkosaan. Ini tidaklah berarti bahwa kombinasi kekerasan dan seks akan membuat keadaan lebih buruk daripada hanya satu saja yang terjadi, karena harus diperhitungkan bagaimana peristiwa itu dilukiskan. Apabila wanita yang diserang dilukiskan sebagai juga terangsang dan ikut menikmati, reaksi pemirsa akan berbeda bila sebaliknya wanita tersebut digambarkan sebagai korban terror dan kebrutalan. Di samping itu, ada fenomenon menarik yang dikemukakan oleh Harris dan Scott (2002), yakni thirdperson effect, artinya, kita percaya bahwa apa yang kita lihat lebih berpengaruh pada diri orang lain ketimbang pada diri kita sendiri. Kendati terdengar keluhan dari sekalangan masyarakat mengenai meningkatnya seksualisasi konten media, namun banyak orang masih bungkam dan enggan untuk berdiskusi mengenai seks dan seksualitas sebagai aspek yang sehat dan positif dalam pertumbuihan dan perkembangan manusia. Banyak orangtua merasa enggan dan jengah untuk terlibat dalam pendidikan seksualitas dengan anak-anak mereka dan mereka berharap bahwa hal ini menjadi tugas pada pihak lain. Sementara itu, program pendidikan seksualitas minim dilakukan oleh lembaga pendidikan. Kalaupun dilakukan, program edukasi semacam ini kurang memberi ruang bagi diskusi mengenai relasi dan intimitas antarpribadi, identitas dan hasrat atau nafsu seksual, serta ‘pleasure.’ Sebagai konsekuensinya, anak-anak menerima pesan ganda: sebagaimana mereka tumbuh dan berkembangn secara fisik menjadi mahluk yang aktif secara seksual dan dikelilingi oleh stimulasi seksual, mereka tidak menyadari rasa takut dan malu yang mengkarakterisasikan diskusi orang dewasa mengenai seks dan seksualitas. Kepada anak sering dikatakan bahwa mereka sebaiknya tidak menjadi seksual dan mereka diharapkan untuk tidak berbuat apapun yang berhubungan dengan tubuh dan hasrat mereka. Anak-anak, khususnya, perempuan, diberi peran untuk mempertahankan reputasi yang baik dengan menekan dorongan dan hasrat seksual, mengendalikan Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 7 pelepasan hasrat dari pihak lawannya, dan diajarkan untuk merasa bersalah apabila pelanggaran ini terjadi. Secara keseluruhan yang menjadi persoalan adalah bahwa pendidikan formal atau informal tidak menawarkan pendidikan seks yang efektif, dengan memperhatikan kebutuhan anak dan remaja sebagaimana mereka bertumbuh, dan mediapun tidak mengisi kekosongan ini, untuk menjadi kekuatan sosialisasi. Jadi, seks menjadi realm kehidupan yang dikenal oleh anak melalui media, namun media tidak menjadi sarana untuk membawa pada realitas. Apa yang dikenal oleh anak tentang seks berkembang seiring dengan lamanya mengonsumsi isi media di tengah-tengah kekurangan akan tersedianya sumber-sumber informasi dan model alternatif, jauh sebelum mereka terlibat dalam pengalaman seksual pertama. PERSILANGAN SEKSUALITAS DAN PERILAKU SEKSUAL DAN KESEHATAN Banyak penyakit sosial seperti aktivitas seksual prematur, promiskuitas, kehamilan remaja, dan penyebaran penyakit menular sering dikaitkan dengan representasi seksual dalam berbagai media yang begitu mudah diakses oleh anak hingga remaja. Aneka penyakit sosial ini dianggap ikut andil bagi terjadinya erosi moralitas dan nilai-niali normatif keluarga dan masyarakat. Dalam media yang telah terseksualisasikan, sosok anak ditampilkan sebagai obyek seksual yang merangsang dan kemudian menjadi stimulus bagi fantasi dan aktivitas pedofilik (orang dewasa). Kalangan pendidikan, orangtua, dan masyarakat pada umumnya telah mengekspresikan keprihatinan mereka mengenai perilaku seksual remaja, berdasar pada isu-isu kesehatan seperti meningkatnya penyakit yang ditularkan karena hubungan seksual, serta keterlibatan remaja dalam pronografi. Pendidikan seksualitas dan media literacy semakin dipandang sebagai faktor yang penting dalam bagaimana kaum muda memperoleh pengetahuan mengenai seks dan membentuk identitas seksual yang dewasa. Walau penggambaran peilaku seksual anak dan remaja semacam ini adalah hal yang sudah lama berlangsung, tetapi kini media semakin menempati posisi yang Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 8 penting dalam penyajian informasi tentang seks kepada kelompok usia bawah dan memainkan peranan dalam pembentukan budaya seksual. Oleh karenanya sorotan tajam semakin banyak diarahkan ke media. Pembicaraan atau bahkan perdebatan mengenai seksualisasi media sebenarnya bisa dipahami bak dua sisi dari satu mata uang. Satu sisi, ini mencerminkan kecurigaan dari pihak tradisi terhadap erosi nilainilai dan otoritas oleh teknologi media, seks, dan kaum muda. Pada sisi yang lain, ini mencerminkan respons terhadap perubahan-perubahan nyata mengenai signifikansi seks dalam kehidupanan masyarakat modern, di mana seks dipresentasikan sebagai persoaaln kesenangan, kenikmatan, selera dan rekreasi personal. Situasi semacam ini yang dilihat oleh Berstein (2007) ikut membawa pengaruh atas bagaimana kehidupan kerja dan keluarga dikelola, dan bagaimana corak dan konten media telah merasuki ranah kehidupan personal. Studi yang dilakukan dari pendekatan Cultural Studies, yang melibatkan proses mendengarkan anak-anak dan remaja, mendapati bahwa kelompok ini berhubungan dengan media sebagai preferensi untuk sumber informasi dan bimbingan tentang seks. Mereka menggunakan panayangan televise dan internet mengenai seks dan seksualitas sebagai dasar untuk percakapanan mengenai relevansinya dengan kehidupan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka seringkali mendapati materi seksual dalam media dan menghargai informasi yang diterima dari sumber ini dan menggunakannya sebagai sumber belajar. Mereka sudah memperlihatkan ketrampilan kritis dalam mengomentari dan mengkritisi konten seksual dan mengevaluasinya lewat apa yang mereka persepsikan sebagai moralitas sesual (Lemish, 2011). Sebagai perbandingan dari pendekatan Cultural Studies, riset yang dilakukan melalui efek media mengandaikan bahwa masa muda adalah periode yang polos dan lugu dan pengetahuan seksual dapat berbahaya bagi remaja. Kewajaran dan pentingnya perkembangan seksualitas pada anak dan remaja sekaligus juga dibingkai sebagai problem sosial, khususnya bagi remaja putri. Resiko sebagai akibat dari paparan berat terhadap seks media lebih ditekankan daripada peluang dan potensi belajar atau pleasure yang bisa dicapai lewat penggambaran seksual. Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja Riset mengenai efek kumulatif menunjukkan bahwa anak dan 9 remajja menginternalisasikan sikap dan perilaku seksual dari penayangan yang telah terdistorsi pada media komersial (Lemish, 2011). Maraknya pornografi yang tersedia dalam berbagai corak media mempunyai implikasi yang serius bagi perkembangan mahluk seksual yang sehat. Bagi Zillman, Bryant, dan Huston (1994), material pornografis menyuguhkan model untuk berbagai praktek seksual, memberi jalan bagi sikap untuk promiskuitas dan keyakinan yang menyimpang mengenai peran seks dalam relasi manusia, menegakkan ekspektasi mengenai capaian diri, mengobyektifkan wanita dan menyebarkan sikap negative tentang wanita, serta meremehkan seriusnya kejahatan seksual serta konsekuensinya. Lepas dari tradisi dan hampiran riset yang dianut, mayoritas pengamat dan peneliti sepakat bahwa penggambaran oleh media mengenai seks mempunyai peran yang sentral dalam perkembangan seksualitas remaja, dan dengan demikian selayaknya dicermati dengan seksama. Di samping itu, telah nampak jelas bahwa ada inter-relasi anatra seks dan sejumlah isu penting seperti kekerasan , emosi, momitmen, keluarga, kehamilan dan pengasuhan anak, orientasi dan identitas seksual. Semua isu ini membutuhkan atensi serius dari mereka yang berkepentingan dengan peran media dalam mendukung perkembangan yang sehat bagi anak dan remaja. Ada keragaman opini mengenai corak dan praktek relasi seksual yang tepat untuk dilihat oleh anak dan remaja. Keragaman ini bukan hanya bisa dijumpai pada orangtua dan kaum dalam lingkup pendidikan, namun juga pada produser film dan tv anak-anak yang diwawancara oleh Lemish (2011) dari sejumlah negara. Pandangan mereka tidak hanya bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, tetapi juga antar berbgaai kelompok dalam suatu budaya, seperti halnya ras, etnisitas, kelas , tradisi, dan sejarah memempengaruhi keyakinan dan prakteks seputar seksualitas. Sebagai satu contoh, apa yang relevan untuk budaya-budaya dalam masyarakat maju yang kapitalis tidak perlu dirasakan relevan untuk masyarakatmasyarakat lainnya di bagian lain di dunia. Ada pendekatan yang lebih longgar dan Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 10 permisif di negara-negara Eropa (misalnya kelompok Nordik) mengenai apa yang bisa ditayangkan dalam program-rpogram untuk pemirsa muda usia. Apabila tayangan ini, di mana perilaku erotis, buka-bukaan, humor jorok dan percakapan bebas tentang seks, ditonton oleh remaja di belahan dunia lain tentu akan menimbulkan ketegangan dan pertentangan. Televisi di Amerika Serikat lebih konservatif dan kurang permisif dibandingkan dengan kelompok negara-negara disebut di atas. Sedangkan konten yang serupa akan dinilai terlalu vulgar dan tidak senonoh oleh masyarakat di Afrika dan Asia. Dalam kultur yang konservatif, pendidikan seks dan pembagian kondom untuk pencegahan penyakit bahkan bisa diartikan sebagai bentuk legitimasi dan dorongan bagi perilaku seksual oleh remaja. Maka diskursus mengenai seksualitas sebenarnya minim pada kultur yang menentang segala intervensi semacam ini dalam kehidupanan anak dan remaja. Sejajar dengan ini, keengganan kuat lainnya yang muncul dalam diskurus mengenai homoseksualitas. Isu ini bukan hanya diperhadapkan dengan tabu tetapi juga dengan sangsi-sangsi religius. Oleh karena itu seks dan seksualitas tetap harus dijaga sebagai rahasia yang tidak selayaknya dipaparkan dan dibicarakan secara terbuka. Seks dan seksualitas diposisikan sebagai ruang privat, sarat dengan perasaan cemas, takut dan malu – oleh karena itu sebaiknya tetap diperlakukan demikian. Orangtua tiba-tiba menjadi gagap ketika diperhadapkan pertanyaan seksual oleh anak, dan sebagai ganti jawaban yang mencerahkan orangtua menekan rasa ingin tahu anak untuk tidak bertanya macam-macam. Edukasi seksual terkesan hanya terjadi dalam keluarga yang lebih terdidik dalam kelas sosial yang lebih tinggi. Pesan yang ditanggap oleh umum dari kultur semacam ini adalah anak dan remaja memiliki peluang terbatas untuk masuk dalam dialog terbuka dan santai mengenai tubuh, dorongan, dan hasrat seksual mereka. Apa yang mereka ketahui, alami dan rasakan pada giliran bukan datangnya dari orang dewasa, tetapi dari pencarian dan penjelajahan sendiri. EKSPOSUR TERHADAP KONTEN SEKSUAL DAN DAMPAKNYA ATAS PERILAKU Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 11 Meningkatnya paparan terhadap materi yang eksplisit seksual menjadi satu faktor yang berpengaruh atas seksualitas remaja dan kesehatan mereka. Dalam konteks ini, amat menarik untuk diamati bagaimana perspektik remaja sendiri mengenai seksualitas, identitas seksual, media dan budaya yang telah terseksualisasi bersinggungan dengan kesehatan. Sayangnya, belum banyak riset dilakukan seputar isu ini (Bale, 2011). Diskusi dan perbedaan bukan lagi pada terjadi atau tidak terjadinya seksualisasi kultur dan media, karena eksistensi sudah amat jelas. Pertanyaan lebih mengarah pada bagaimana eksistensi media dan kultur yang telah mengalami seksualisasi ini dimaknai oleh masyarakat, khususnya remaja, dan apa signifikansinya bagi mereka. Inilah yang dicoba diamati oleh Clare Bale, khususnya mengenai relasi antara media dan kesehatan seksual remaja sebagaimana diartikulasikan dalam kebijakan kesehatan masyarakat di Inggris. Bale (2011) menyesalkan bahwa relasi antar kedua aspek ini lebih banyak dibingkai dalam moralisme tersembunyi dibaliknya dan dengan fokus yang menitik-beratkan pada eksposur dan efeknya, serta resiko seksual dan kerugiannya. Pembingkaian cara pandang demikian ini menurut Bale justru membatasi dan mengerdilkan remaja sebagai sexual agency, dan ini pada gilirannya berimplikasi pada ekspresi seksual dan kesehatan mereka. Peran dan dampak media di dalam membentuk seksualitas dan perilaku seksual remaja telah menjadi fokus perdebatan dan konsultasi serta program edukasi di banyak negara. Namun riset yang mendukung pandangan bahwa dampak media atas kesehatan seksual adalah negati masih belum benar-benar konklusif. Kebanyakan riset dalam area ini dilakukan dari pendekatan kuantitati yang bisa diperdebatkan dari segi cocok, tepat dan layaknya. Menurut Bragg dan Buckingham (2002), pendekatan ini mengandalkan model behavioristik untuk mengkaji efek, di mana subyek dipersepsikan sebagai konsumen pasif. Kelemahan lainnya dalam pendekatan ini adalah kurangnya presisi dalam mendefinisikan apa sebenarnya representasi yang terseksualisasikan dan apa representasi seksual serta kecenderungan untuk mengabaikan konteks, makna, representasi, dan bagaimana merumuskan persoalan riset. Riset oleh Bragg dan Buckingham menyimpulkan Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 12 bahwa anak-anak muda menggunakan pengalaman mereja sendiri dan identitas mereka yang sedang terkembang untuk mnenginterpretasikan media. Partisipan muda ini juga menggunakan nilai-nilai yang lebih luas seperti trust dan mutual respect untuk memformulasikan sikap, keyakian dan nilai-nilai mereka sendiri dalam membaca media. Masih sedikit perhatian diarahkan pada konteks kultural dan sosial pada seksualitas, bagaimana makna seksual dibangun dan dinegosiasikan, dan bagaimana remaja menginterpretsikan dan menggunakan konten seksual (Bragg, Buckingham, Russell, & Willett, 2011). Selain bahwa banyak riset tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai dampak seksualisais kultur, hasil riset ini dianggap sebagai suara autoritatif yang berpengaruh atas kebijakan sosial dan kesehatan. Bale (2011) berpendapat bahwa hasil sering dipresentasikan dalam bentuk yang umum dan berlaku untuk semua hal, dan bahkan kontradiktif. Begitu pula konklusi dan rekomendasi yang dibuat. Kepustakaan yang persuasif dan komprehensif dalam jumlah besar mencoba menunjukkan dampak negatif dari materi seksual yang eksplisit atas fisiologi remaja serta berfungsinya kognitif-emosional dan sosial mereka. Namun Atwood (2002) melihat bahwa hasil riset ini lebih mencerminkan sikap dan nilai produsennya ketimbang relasi antara kaum muda dan media. Oleh karena itu, Bale (2011) berupaya menempatkan risetnya pada persilangan antara kesehatan masyarakat, sosiologi, media dan cultural studies. Risetnya bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kultur yang telah terseksualisasikan dan kesehatan remaja melalui metodologi kualitatif, yang secara eksplisit bertolak dari pengalaman dan kisah/narasi mereka sendiri sebagai tema untuk analisis. Dari sini Bale melihat bahwa daripada sekedar pasif terpapar (exposure) pada seksualisasi kultur, remaja sebenarnya secara aktif mencermati teks seksual, termasuk pornografi, dalam cara-cara dan alas an-alasan yang berbeda-beda. Penggunaan istilah terpapar (eksposed atau exposure) di dalam konteks kesehatan dan evidence-based medicine tidak mampu menangkap kompleksitas cara dan alasan remaja dan dengan begitu mudah disalah-interpresikan. Remaja mencari materi seksual bisa untuk sekedar memuaskan rasa ingin tahu mereka, atau Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 13 untuk membantu melakukan masturbasi, atau untuk menghilangkan kejenuhan. Ada remaja yang mengakses materi seksual untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kepercayaan diri dalam hubungan dengan praktek dan pengalaman seksual mereka. Namun ada pula yang ingin memperoleh dukungan sehubungan dengan munculnya seksualitas mereka yang mereka rasakan tidak bisa dieksplorasi dalam “kehidupan nyata.” Dalam hal ini Bale mengatakan bahwa reaks-reaksi emosional yang negatif seperti cemas, takut, jijik, terhadap paparan materi seksual muncul karena “reductive fallacy of exposure” (p. 308), yakni orang sudah kadung berkeyakinan bahwa paparan akan berakibat buruk. Temuan lain dari riset Bale adalah bagaimana remaja telah belajar dan mengembangkan opini dan kapabilitas mereka dengan menggunakan pengalaman dengan media dan dengan praktek seksual, bahwa kalaupun pengalaman ini menyimpang dari apa yang mereka deskripsikan sebagai ideal mereka. Misalnya, salah seorang partisipan putri mengungkapkan tentang pengalaman seksual pertamanya yang dia sebenarnya nilai bukan sesuatu yang dia inginkan terjadi. Sementara dia menyesali perbuatan ini, dia melihatnya sebagai bagian dari jalan menuju perkembangan (rite of passage) yang harus dilalui yang memberikan kontribusi bagi dirinya sebagai mahluk seksual (sense of sexual self); ia merasa lebih jernih dan percaya diri dalam melihat relasi-relasi yang akan dibina di masa depan. “Peer pressure” merupakan konsep kunci karena melalui pengalaman ini tumbuh-kembang remaja dan apa yang mereka konsumsi harus dimengerti. Terkadang keprihatinan mengenai ini dipresentasikan lebih besar dan lebih berbahaya daripada pengaruh komersial atau pengaruh media (Bragg, Buckingham, Russel, & Willet, 2011). Misalnya, seorang partisipan dalam riset Bragg dkk., membeli celana dalam yang sebenarnya dia rasakan tidak nyaman untuk dipakai. Dia menjelaskan bahwa dia tetap membelinya karena banyak teman yang memakainya, maka celana itu dianggap mode yang ngetren dan sekaligus tanda dari meningkatnya usia ke jenjang lebih dewasa. Remaja pria sebenarnya juga menghadapi isu yang serupa seperti remaja putri, namun pilihan-pilihan bagi pria biasanya lebih terbatas, sehingga terkesan bahwa hanya remaja putrid yang “rewel” Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 14 dan jlemet soal pilihan pakaian atau aesori lainnya. Namun riset juga menemukan pola konsumsi oleh remaja pria dipandang oleh orangtua sebagai kurang “liar” dibandingkan dengan remaja aputri. Jadi ada dimensi gender dalam isu-isu semacam ini. Bertolak belakang dengan kesan promiskuitas yang diungkap dari media, partisipan dalam riset Bale menunjukkan derajat yang tinggi menyangkut kecemasan dan “kepolosan” (naivety) mereka tentang seks. Perasaan-perasaan semacam ini tidak memperoleh porsi dalam pendidikan seksualitas, tidak pernah menjadi bagian dalam diskusi dan representasi media, dan dengan demikian tidak mebantu remaja mengembangkan rasa percaya-diri untuk sanggup mengambil keputusan ketika mereka diperhadapkan dengan aktivitas seksual mereka pertama. Misalnya, seorang partisipan mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki ketrampilan untuk mengatakan tidak kepada pacarnya pada hubungan seks pertama kali. Dia mendeskripsikan dirinya sebagai terangsang dan membiarkan rangsangan itu ke tahap lebih lanjut, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengharapkan itu terjadi di situ dan saat itu. Ia mengalami kesulitan untuk menegosiasilan perasaan dan kehendaknya, dan dia merasa kalau sekiranya dia sebelumnya dibekali dengan cara-cara menghadapi situasi seperti ini, dia akan merasa lebih siap. Dalam mengisahkan seksualisasi kultur mereka, remaja, khususnya putrid, juga mengungkapkan pengalaman mereka yang mengilutrasikan kekuatan normanorma etis-sosial, dan pertimbangan ini yang perlu bagi mereka untuk mencegah kemungkinan konsekuensi yang harus ditanggungnya, misalnya kehilangan nama baik dan dicap sebagai ‘perempuan nakal’. Satu partisipan mengungkapkan keinginannya yang besar untuk menjadi model seksi, tetapi dia takut akan konsekuensi mengenai bagaimana orang memandang dirinya. Sedangkan partisipan lain mengartikulasikan rasa frustasi atas kekangan-kekangan sosial atas kebebasan untuk berekspreasi secara seksual.. Menurut Bale, yang menarik dari risetnya adalah bahwa tak seorang pun dari 21 partisipan ini (rentang usia : 16 – 19) mengangkat isu mengenai perasaan tertekan untuk mejadi seksi, yang sesungguhnya menjadi fokus utama dalam Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 15 kebanyakan diskusi mengenai seksualisasi. Sebaliknya, kebanyakan dari partisipan merasa ambivalen. Di satu pihak mereka mengatakan bahwa ingin lebih percaya-diri mengenai tubuh dan penampilan mereka; pada sisi lain mereka tetap mendefinisikan diri mereka sebagai berbeda dari wanita yang percaya diri dengan tubuh dan seksualitasnya. Bale beranggapan bahwa perilaku remaja ini nampaknya menunjukkan regulasi-diri yang kuat dalam membuat pilihan antara romans dan sekedar seks bebas dan dalam mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi negati apabila memilih yang terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas dan diskursus resiko masih dominan diperhadapkan dengan pendekatan yang sekedar mengutamakan kenikmatan (pleasure) dan hak terhadap seksualitas dan kesehatan seksual. Berbicara mengenai kesehatan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari peran dan tanggungjawab pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan penting anak dan remaja, baik secara individual dan kolektif. Kebijakan dan riset mengenai kesehatan publik dirumuskan dalam kerangka-kerja seksualitas dan kesehatan seksual yang normatif dengan pesan-pesan moral yang kental (moralizing). Dalam kerangka ini definisi kesehatan seksual difokuskan pada fungsi-fungsi reproduktuf dan patologinya. Apakah kerangka-kerja dan definisi semacam ini konsisten atau cocok dengan rumusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), barangkali masih bisa didiskusikan dan diperdebatkan. Rumusan WHO sendiri mengenai kesehatan seksual member tempat pada hak individu untuk bertindak dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sexual health is a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasure and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual rights of all persons must be respected, protected and fulfilled (WHO, 2002, 5) Temuan dari riset oleh Clare Bale mengajak kita untuk memposisikan seksualitas remaja pada sexual health economy yang multidimensional, bukan sekedar diskursus moralistik dan berbasis resiko. Artinya, pendekatan riset sebaiknya Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 16 menempatkan remaja sebagai subyek yang bertindak, berfungsi, mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Sudah banyak kecemasan dan ketakutan menyangkut konsekuensi dan dampak msyarakat dan kultur yang telah terseksualisasi atas remaja, khsususnya perempuan, dan berbagai kemungkinan hal ini berkaitan erat dengan ketidaksetaraan gender, eksploitasi dan kekerasan seksual. Pada kenyataannya kita menyaksikan bahwa banyak aspek dalam kehidupanan telah terseksualisasi dan gaya hidup seksual telah menjadi komoditas. Pencitraan dan diskursus mengenai tubuh yang seksi dan segalam yang membangkitkan nafsu seksual lewat tubuh wanita ditawarkan kembali dalam bentuk pornografi, operasi plastic, produk-produk kecantikan dan gaya-hidup muda dan urban, musik dan berbagai asesoris untuk menopang citra ini. Inilah yang menjadi keprihatinan dari Bale dan pengamat lain bahwa seksualisasis kultur ini kemudian digunakan untuk menjual kesehatan seksual melalui presentasi seksual yang termuat dalam setiap produk sebagai sarana untuk mencapai pemenuhan dan pemberdayaan seksual. Bale mengutip ahli lain, Gill (2009), yang mengidentifikasikan bahwa portofolio estetik perempuan yang dipresentasikan oleh media ini menjadi terbatas/sempit dan mengenyampingkan siapa saja yang tidak memenuhi ukuran estetika yang telah terseksualisasikan. Pada akhirnya, pemodelan dan pencitraan tubuh wanita secara narsistik dalam praktek-praktek kultur masa kini bergerak menekan, membatasi dan bahkan memojokkan dan merendahkan perempuan sendiri dalam banyak hal. Fenomena semacam ini bukan hanya pengalaman eksklusif kaum hawa, tetapi juga semua jenis kelamin. Kendati keprihatian mengenai kultur seksual remaja sudah lantang diekspresikan, namun studi mengenai isu-isu ini sebenarnya masih amat terbatas di Indonesia. Banyak area-area penting yang masih belum diselami oleh riset. Kesulitan yang kelihatan jelas adalah tebalnya tabu dalam kultur kita untuk berbicara tentang seks, di samping rasa cemas dan takut yang ada di balik tabu tersebut. Apa saja area yang sebenarnya kita bisa kaji lebih dalam baik dalam disiplin psikologi maupun lintas disiplin? Di bawah ini dikemukakan beberapa area penelitian berdasarkan apa Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 17 yang kemukakan oleh Attwood dan Smith (2011), dalam introduksi yang mereka tulis untuk edisi khusus jurnal Sex Education. Prevalensi mengenai asumsi-asumsi yang dipegang oleh masyarakat majemuk mengenai perilaku seksual remaja, karakterisasi mengenai kelompok usia muda ini (khususnya, perempuan) sebagai rusak dan bejat, serta apa yang dewasa ini yang menjadi pembicaraan umum mengenai seksualitas. Kekawatiran, bahkan ketakutan, pada peneliti berhadapan dengan isu-isu seputar seks yang dikarakterisasikan secara negatif; publikasi riset tentang seks dipandang oleh publik sebagai publikasi yang tidak layak atau tidak patut. Pengetahuan actual anak dan remaja mengenai perilaku dan kultur seksual, orientasi seksual, mengenai tubuh, hasrat, nafsu, dan cinta, serta relasi antar jenis dan sesame jenis. Ambivalensi dalam sikap remaja sendiri terhadap seks, pemahaman tentang remaja sebagai penyumbang dan partisipan dalam kultur seksual, pengalaman dalam seks yang dinilai baik dan yang beresiko, merugikan dan menimbulkan penyesalan. Norma, etika, representasi, dan praktek seksual yang berubah seiring dengan perubahan ide dan perilaku seksual berdasarkan usia. Pengembangan dan perumusan riset, kebijakan dan pedoman untuk bekerja dengan anak-anak dan remaja, untuk kepentingan pendidikan dan konseling/terapi. Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 18 KESIMPULAN Satu sisi kebanyakan orang mengakui bahwa kultur dan media dewasa ini sudah sarat dengan seks dan segala sesuatu yang berkonotasi seks. Namun, pada sisi yang lain, tidaklah mudah mendefinisikan apa yang sesungguhnya makna ‘seksualisasi’ sendiri (atau bahkan ‘seksi’). Dalam semangat yang sama, makna dari model peran yang baik dan seksualitas yang sehat masih menjadi bahan perdebatan yang hangat. Hanya apabila konsep-konsep semacam ini mempunyai cukup kejelasan bagi masyarakat umum, khususnya bagi anak dan remaja, maka edukasi dalam konsumerisme dan media literacy bisa menjadi strategi yang secara potensial bermanfaat. Seksualitas dan pengeathuan seksual merupakan aspek yang penting aspek dalam mengartikan apa itu menjadi dewasa, tetapi juga apa itu menjadi anak/remaja. Batas antara keduanya bukan berhimpitan, tetapi terdapat ruang yang longgar dan justru transisi dari fase yang satu ke fase berikutnya menjadi krusial. Nampaknya transisi dari anak/remaja ke status dewasa menjadi semakin ambigu dan sekaligus lebih “ribet” dewasa ini dibandingkan dekade-dekade yang sudah lewat. Anak-anak jaman ini sudah relatif menguasai teknologi media yang mereka pergunakan sehari-hari dalam dunia interaksi sosial, sementara itu orangtua mereka masih belum paham bagaimana menggunakan internet atau HP. Sumber-sumber informasi yang bisa diakses oleh anak-anak ini jauh lebih cepat dan luas daripada apa yang bisa dituturkan dan dinasehatkan oleh orangtua. Sebagai konsekuensinya, seksualitas dan perilaku seksual mereka bisa sangat kontras dengan apa yang dianut oleh generasi orangtua. Oleh karena itu, riset mengenai dampak atau efek teknologi media tidak bisa berangkat dari sekedar asumsi bahwa apa yang marak dilihat dan didengar akan tentang seks akan berakibat negatif pada diri mereka. Asumsi seperti ini seringkali tidak terlepas dari kecemasan dan ketakutan orangtua/pendidik sendiri yang diproyeksikan pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, riset dan diskursus mengenai hal ini perlu berfokus pada isu-isu yang lebih luas sebagaimana telah dibahas dalam tulisan ini. Seksualisasi media dan seksualisasi masa muda barangkali tidak akan pernah sirna, begitu pula kebutuhan Seksualisasi media dan perilaku seksual remaja 19 untuk terus menerus terlibat dalam respons dan dialog tentang isu-isu ini pada pihak orangtua, pendidik, dan pembuat kebijakan. DAFTAR PUSTAKA American Psychological Association (2007). Report of the APA on the sexualization of girls. http//www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html. Atwood, F. (2002). Reading porn: The paradigm shift in pornography research. Sexualities, 1, 91-105. Attwood, F., & Smith, C. (2011). Investigating young people’s sexual cultures: an introduction. Sex Education, 3, 235-242. Bale, C. (2011). Raunch or romance? Framing and interpreting the relationship between sexualized culture and young people’s sexual health. Sex Education, 3,303-313. Berstein, E. (2007). Temporary yours: Sexual commerce in post-industrial culture. Chicago, IL: University of Chicago Press. Bragg, S., & Buckingham, D. (2002). Young people and sexual content on television: A review of the research. London: Broadcasting Standards Commission. Bragg, S., Buckingham, D., Russel, R., & Willett, R. (2011). Too much, too soon? Children, ‘sexualization’ and consumer culture. Sex Education, 3, 279-292. Harris, R.J., & Scott, C.L. (2002). Effects of sex in the media. Di dalam J. Bryant & D. Zillmann (Eds.), Media effects : Advances in theory and research (pp. 307331) . Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Lemish, D. (2011). ‘Can’t talk about sex’:Producers of children’s television around the world speak out. Sex Education, 3, 267-277. Noonan, R.J. (2007). The psychology of sex: A mirror from the internet. Di dalam J. Gackenbach (Ed.), psychology and the internet (2nd ed.) Academic Press. World Health Organization (2002). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002. Geneva: WHO. http://www.who.int/reproductivehealth/publication.