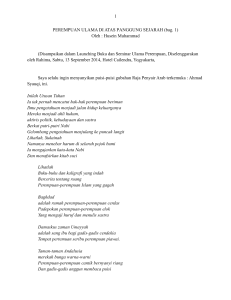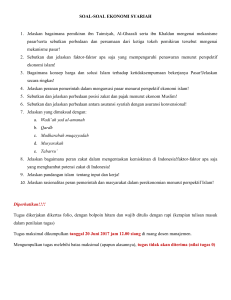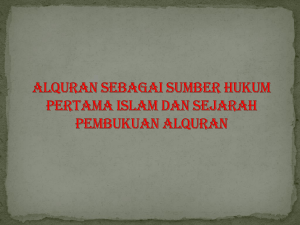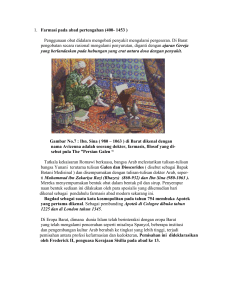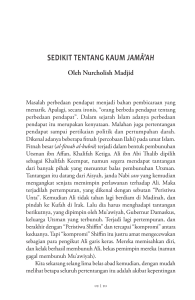kehidupan para ilmuan muslim dalam bidang ilmu
advertisement

Kehidupan Para Ilmuan Muslim KEHIDUPAN PARA ILMUAN MUSLIM DALAM BIDANG ILMU AGAMA ISLAM Agus Salim Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi Abstrak Kehidupan para ilmu muslim dalam bidang ilmu agama Islam sangat menarik dikaji dikaitkan dengan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mempengaruhinya. Perjalanan panjang sejarah pemikiran Islam telah melahirkan berbagai disiplin ilmu yang terbentuk seperti; ‘Ulum al-Qur’an, ‘Ulum al-Hadits, Fiqh, Kalam, Filsafat dan Tashawwuf. Artikel ini bermaksud mengungkap seluruh kompleksitas yang menaungi dan mengiringi kehidupan ilmuan muslim hingga terbentuknya suatu disiplin ilmu dan madzhab-madzhab pemikiran dalam Islam menjadi sangat menarik untuk dapat memahami elan vital pemikiran-pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah peradaban Islam. Kata Kunci: Madzhab, Ilmu Kalam, Hadits, Tasawuf A. Pendahuluan Sejarah para ilmuan muslim sangat menarik dikaji sebagai layar proyeksi untuk meneropong kegiatan keilmuan Islam pada masa kejayaannya. Hal itu sekaligus juga dapat memberikan gambaran tentang proses pembentukan ilmu-ilmu keislaman yang terpusat pada ilmu Kalam, Filsafat, Fiqh, Tasawuf, Akhlak dan Hadits, serta Ulumul Qur’an. Namun dalam konteksnya yang historis, kegiatan keilmuan tersebut tidak tumbuh dan berkembang tanpa pengaruh-pengaruh lingkungan sejarahnya. Karena produk ilmu pada dasarnya adalah hasil pemikiran yang lahir sebagai hasil interaksi dialogis antara pemikiran dan realitas-realitas yang dihadapinya. Dunia ilmu dan pemikiran TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 87 Agus Salim mutlak mempertimbangkan hal tersebut sebagai variabel yang dapat memberi jaminan bagi diterimanya suatu produk ilmu dan pemikiran, sekaligus juga sebagai landasan kontekstual bagi historisitas suatu pemikiran. Maka tidak salah jika dinyatakan bahwa ilmu dan produk-produk pemikirannya dalam Islam sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik yang berkembang pada saat produksi pemikiran itu terjadi. Malah lebih jauh dapat dikatakan bahwa kelahiran pemikiranpemikiran Islam itu memang didorong oleh dinamika kehidupan sosial dan politik Islam masanya, di samping karena dorongan utama dari intelektualisme keagamaan. Setiap disiplin keilmuan inipun membentuk mazhabmazhab disipliner. Sehingga dapat dimengerti jika di dalam Islam muncul banyak mazhab, sesuai dengan tokoh-tokoh ilmuan dengan corak pemikiran dan disiplin ilmu yang digelutinya. Dalam hal ini, bidang ilmu fiqh dan kalam merupakan dua disiplin ilmu yang mendominasi pembentukan mazhab dalam Islam, seperti Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali dalam keilmuan fiqh, serta lebih banyak lagi mazhab dalam ilmu kalam, mulai dari Murjiah, Khawarij, Syi’ah, Mu’tazilah hingga Sunni, yang dalam setiap madzhab pun muncul sub-sub madzhab yang memiliki karakteristik pemikirannya sendiri-sendiri. Semua madzhab tersebut tidak terbentuk dalam ruang hampa sejarah. Semua dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, seperti faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi. B. Pembahasan 1. Gambaran Umum tentang Disiplin-Disiplin Ilmu Islam Berbagai disiplin ilmu Islam tidak lahir bersamaan dengan datangnya Islam, melainkan lahir sebagai hasil kegiatan keilmuan yang dilakukan para ilmuan muslim (ulama) setelah berlalunya generasi Sahabat. Hal tersebut muncul sebagai hasil jerih payah mereka dalam upaya memahami ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an. Oleh karena itu, disiplin ilmu pertama yang muncul dalam Islam adalah Ulumul Qur’an beserta Ulum 88 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim al-Tafsir dengan berbagai perangkat pendukungnya, terutama terkait dengan ilmu Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan sebagainya). Disiplin ilmu ini muncul karena adanya upaya ulama melakukan sistematisasi kajian al-Qur’an hingga terjadilah akumulasi berbagai rumusan teoritis hingga membentuk berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam kategori Ulumul Qur’an, seperti Ilmu Tafsir, Qawa’id al-Tafsir, Qawa’id al-Lughah, Asbab al-Nuzul, Muhkamat Mutasyabihat, I’jaz al-Qur’an, Nasikh Mansukh, dan sebagainya. Sebagai pendukung upaya pemahaman al-Qur’an, maka lahir pula disiplin ilmu hadits yang juga merupakan akumulasi dari berbagai teori mengenai hadits, seperti ilmu dirayah, ilmu riwayah, ilmu asbab al-wurud, hingga munculnya di masa yang lebih belakangan ilmu al-jarh wa al-ta’dil, naqd al-hadits, takhrij al-hadits, dan sebagainya. Pada masa yang hampir bersamaan, muncul ulama-ulama yang memfokuskan diri pada upaya memahami hukum-hukum Islam, sehingga muncullah disiplin ilmu fiqh yang didukung oleh ilmu ushul al-fiqh. Sejatinya, tiga ilmu inilah yang menjadi representasi keilmuan Islam klasik, yang jika dikaitkan dengan teori Abid Jabiri, maka inilah yang menjadi basis paradigma Bayani, yaitu paradigma keilmuan yang bertumpu pada nash. 1 Hal tersebut tidak bertahan lama, hingga Islam tersebar ke berbagai wilayah budaya di luar Jazirah Arab, dengan berbagai dinamika sosial, politik dan ekonominya. Umat Islam pun tumbuh menjadi masyarakat yang kosmopolitan yang terbentuk dari gabungan berbagai latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi. Islam pun menjelma menjadi sebuah peradaban global yang selalu dihadapkan pada tantangan untuk berkembang secara terus menerus, dalam sebuah proses melakukan asimilasi dan akomodasi terhadap berbagai hal baru secara tak terelakkan, termasuk dengan kehadiran berbagai 1 Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique (Austin: The Center for Middle Eastern Studies, 1999) 47-62. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 89 Agus Salim corak dan kecenderungan pemikiran di luar mainstream tiga keilmuan Islam yang menjadi basis paradigma Bayani di atas. Didorong oleh berbagai dinamika yang terjadi, Islam pun mulai mendapatkan sentuhan baru melalui Tasawuf, Ilmu Kalam dan Filsafat. Pada perkembangannya, Tiga disiplin ilmu inilah dibakukan menjadi disiplin ilmu inti dalam Islam melengkapi tiga disiplin yang terbentuk pada masa yang lebih awal. Ditinjau dari teori Abid Jabiri, Tasawwuf mewakili paradigma Irfani, sedangkan Kalam dan Filsafat mewakili paradigma Burhani, sehingga lengkaplah Islam dengan tiga paradigma ilmu: Bayani, Irfani dan Burhani. Upaya pemahaman proses pembentukan disiplin-disiplin ilmu tersebut, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan makalah ini, tidak akan utuh tanpa melihat dinamika sosial, budaya, politik dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu aspek-aspek tersebut sebagai konteks historis tempat terbentuknya berbagai disiplin ilmu keislaman tersebut. 2. Latar Belakang Sosial, Budaya, Politik dan Ekonomi a. Masa Banu Umayyah Meskipun kegiatan keilmuan Islam telah tumbuh sejak masa paling awal dari kedatangan Islam, dan terus berkembang pada masa Sahabat, namun upaya-upaya sistematis untuk terbentuknya disiplin ilmu Islam baru muncul setelah generasi Sahabat. Secara periodik hal tersebut dapat ditandai dengan berakhirnya masa Khulafa’ Rasyidun dan dimulainya kekuasaan dinastik dalam Islam, yaitu sejak berdirinya Dinasti Umawiyah (Banu Umayyah) tahun 656 M. Berkuasanya Banu Umayyah setelah mengakhiri masa kekuasaan Ali bin Thalib meninggalkan luka sosial yang mendalam dalam tubuh Islam. Sejak kekuasaan Umayyah, masyarakat Islam terkotak-kotak dalam tiga kutub politik yang tak terdamaikan, yaitu Syiah, Khawarij dan Murjiah. Masingmasing faksi politik tersebut memiliki basis sosial dan budayanya masing-masing. Syiah yang berbasis di Kufah (Ibukota Islam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib) berhasil 90 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim menarik solidaritas kesukuan dari bangsa Persia. Maka Syiah memiliki basis sosial Persia dengan budaya pemikirannya yang cenderung irfani (mengandalkan intuisi batin). Visi perjuangannya adalah mengembalikan kekuasaan Islam ke tangan para imam keturunan Ali bin Abi Thalib.2 Sementara Khawarij berhasil menarik solidaritas kesukuan dari bangsabangsa minoritas (utamanya Afrika dan sebagian TurkiMongol), dengan corak pemikiran cenderung tegas dan simplistik. Visi politiknya adalah menentang setiap kekuasaan yang hegemonik dan mengembalikan prinsip khilafah Islamiyah. Adapun Murjiah merupakan faksi mayoritas umat yang sejatinya menarik diri dari pertikaian antara Syiah dan Khawarij, namun dalam kadar tertentu berhasil dimanfaatkan penguasa Umayyah untuk meraih simpati politik dan akhirnya untuk membentuk solidaritas kesukuan Arab. Visi politiknya adalah menjaga perdamaian meskipun harus membela penguasa yang zalim demi menghindari kekacauan sosial dan anarkisme hukum. Massa murjiah inilah yang akhirnya menjadi basis terbentuknya jamaah Sunni. Berdasarkan pemetaan tersebut, maka hampir di sepanjang pemerintahan Banu Umayyah, peta sosial umat Islam dapat dipilah menjadi tiga kubu: (1) Kubu penguasa mendapat dukungan kaum Murjiah yang berbasis bangsa Arab (2) Gerakan oposisi Syiah yang didukung bangsa Persia, (3) Gerakan pemberontak Khawarij yang didukung oleh bangsa-bangsa minoritas. Terkait dengan peta sosial tersebut, penguasa Banu Umayyah menetapkan kebijakan politik yang represif terhadap para penantangnya, sehingga terciptalah kelas ekonomi berbasis peta sosial tersebut. Diungkapkan bahwa hanya bangsa Arab saja yang dapat bekerja di lingkungan istana dan mendapat proteksi perdagangan yang istimewa dari pemerintah. Sementara 2 C. E. Bosworth, “Al-Maqrizī’s Exposition of the Formative Periode in Islamic History and It’s Cosmic Significance: The Kitāb al-Nizā’ wa-ttakhāshum”, dalam Alfred T. Welch and Pierce Cachia (ed.), Islam: Past Influence and Present Challenge, Edinburgh: The University of Edinburgh Press, 1979), 93-102. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 91 Agus Salim yang terpetakan dalam kelompok Khawarij dan Syiah/Persia betul-betul mendapatkan tekanan ekonomi, dengan akses pekerjaan yang terbatas pada lapangan-lapangan kasar saja. Hanya beberapa kelompok bangsa saja yang tidak terpetakan dalam kelompok tersebut yang mendapatkan akses ke istana sebagai prajurit dan pegawai non strategis. Pada masa ini juga, bangsa non Arab mendapatkan sebutan umum sebagai mawali (identik dengan budak). Setelah satu abad berkuasa, kekuatan Banu Umayyah melemah karena oposisi Syiah dan pemberontak Khawarij yang terus menerus. Dalam situasi seperti itu, muncul gerakan Hasyimiyyah yang dipelopori oleh keturunan Muhammad ibn ‘Ali ibn ‘Abdillah ibn al-‘Abbās ibn Abdul Muththalib.3 Dengan menggunakan nama Hasyim (kakek Nabi SAW), gerakan ini berhasil meraih simpati bangsa Persia untuk meruntuhkan kekuasaan Umayyah, dengan iming-iming akan mengembalikan kekuasaan Islam di tangan imam Syiah (Ahl al-Bayt) dengan mendirikan kerajaan berbasis Imamah Syiah. Pada tahun 750 M, gerakan tersebut berhasil menjatuhkan kekuasaan Umayyah. 4 b. Masa Abbasiyah Sejarah Dawlah ‘Abbāsiyyah, demikian nama resminya,5 akhirnya dimulai dengan klaim kekuasaan di tangan Abū al-‘Abbās al-Shaffah, dengan mengingkari janjinya untuk mengangkat Ahl alBayt sebagai khalifah. Reaksi atas pengingkaran tersebut segera bermunculan. Terlebih karena al-Shaffāh menggunakan gelar Imam sebagai simbol kekuasaan tertinggi Kerajaan Abbasiyah, yang dalam paham Syiah merupakan hak eksklusif Ahl al-Bayt. 6 Zaid ibn ‘Alī 3 Heinz Halm, Shiism (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), 21-24. 4 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1974), jilid 2, 272-279. 5 Philip K. Hitti, History of Arabs (London: The MacMillan Press, 1967), cet. ke-10, 286. 6 Abū al-Hasan al-Asy’arī mencatat ada 55 aliran dalam Syī’ah, dengan jalur imām yang beragam. Al-Asy’arī, Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al- 92 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim ibn al-Husain ibn ‘Alī ibn Abī Thālib memimpin langsung pemberontakan Syiah terhadap Abbasiyah. 7 Hanya karena al-Shaffāh dapat melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap setiap pemberontakan Syiah, sehingga ia dapat bertahan dalam kekuasaannya. Misi selanjutnya adalah menyatukan kembali umat Islam dalam satu solidaritas. Hal ini dilakukan pertama-tama dengan menumpas seluruh keturunan Umayyah yang dipandang berpotensi bangkit dengan segala basis sosial yang dimilikinya, sehingga berhasil memaksa sisasisa kekuatan Umayyah menyeberang ke Afrika hingga menetap di Andalusia. Selanjutnya penumpasan terhadap basis-basis Khawarij, sehingga berhasil mereka terpojok di wilayah-wilayah perbatasan kekuasaan Islam. Karena itu juga, ia mendapat sebutan al-shaffah, karena pemerintahannya yang penuh dengan darah.8 Ketika Abū Ja’far al-Mansūr bertahta (754-775), regulasi pemerintahan mulai berjalan stabil, berkat perhatian yang besar pada upaya-upaya restrukturisasi sosial dan politik. Namun visi keagamaannya belum bergeser dari Syī’ah. Mula-mula, ia merancang sebuah sistem yang dapat meneguhkan patrimonialisme kekuasannya. Maka dibuatlah upaya-upaya penggalangan kekuatan di dalam istana, dengan merekrut personil-personil baru yang berintikan kaum intelek Persia, bekas orang-orang penting dalam pemerintahan Dinasti Sasania. Tahun 762, kota Baghdad mulai dibangun menjadi pusat pemerintahan yang berorientasi pada sistem administrasi Sasania. Lembaga-lembaga birokrasi profesional ala Persia pun diadopsi. Maka terbentuklah lembaga kementerian (wazārah) yang dijabat oleh ahli tata negara (wazīr); jabatan sekretaris (kātib) diserahkan kepada kaum intelek; pejabat hukum (qādli) diserahkan kepada kaum `ulamā’; dan jabatan panglima perang (amīr) diserahkan Mushallīn (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Misriyyah, 1954), cet. ke-1, 66137. 7 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge: The university Press, 1988), 65. 8 Philip K. Hitti, History of Arabs, 288. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 93 Agus Salim kepada kaum militer.9 Sistem itu mempertegas identitas kepersiaan ‘Abbāsiyyah. Bangsa Arab memberikan perlawanan, baik karena sentimen kebangsaan, maupun karena kesenjangan sosial ekonomi yang tercipta akibat stratifikasi tersebut. Pemberotakan Arab pun pecah di Syria (basis utama loyalis Umawiyyah),10 diikuti oleh sukusuku Badui di berbagai wilayah dengan mengusung paham Khawārij. Kaum `ulamā’ pun mengadakan perlawanan dengan membangun basis solidaritas jamā’ah, yang menjadi dasar bagi terbentuknya jamā’ah Sunni kemudian. Pemberontakan kaum Syī’ah terus bergolak, dan semakin sengit sejak terbunuhnya al-Nafs al-Zakiyyah (762 M) di Mekkah. Saat itu pula al-Manshūr mendemostrasikan ancamannya terhadap kaum `ulamā’ di Mekkah, agar bersikap akomodatif terhadap pemerintahannya.11 Sementara di Kufah, aliran-aliran baru dalam Syī’ah bermunculan, mengadopsi paham-paham Persia Kuno yang bervisi messianik, untuk mengobarkan semangat perlawanan terhadap rejim Arab yang memanfaatkan bekas-bekas elit Persia.12 Buruknya hubungan ‘Abbāsiyyah dengan kaum Syī’ah, akhirnya mendorong Muhammad al-Mahdi (775-785) untuk secara tegas melepas dasar lejitimasi kekuasaan mereka pada konsep kepemimpinan Syī’ah. Maka disandanglah gelar baru sebagai Khalifah menggantikan gelar imam. Pemilihan gelar itu sendiri dapat dilihat sebagai upaya baru al-Mahdī untuk melakukan rekonsiliasi dengan Sunni yang selama dua pemerintahan sebelumnya nyaris terabaikan sama sekali. Hal ini terkait dengan semakin meluasnya massa Sunni, melebihi perkembangan Syī’ah, hingga telah menembus batas-batas kebangsaan Persia, dan menjadi alternatif utama bagi corak keagamaan bangsa Turki dan Afrika yang terislamkan. Dukungan massa yang lebih besar itu diperlukan alMahdi untuk mendapatkan pembenaran yang lebih luas bagi upaya 9 Tentang administrasi pemerintahan ‘Abbāsiyyah, History of Arabs, 317. 10 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 78. Philip K. Hitti, History of Arabs, 284. 12 Philip K. Hitti, History of Arabs, 284. 11 94 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim penegakan kekuasaan yang lebih absolut dan tak dapat diganggu gugat, dan bersifat absolut.13 Namun demikian, struktur pemerintahan tetap bertahan dengan pola dan unsur Persia. Tiga posisi penting dalam pemeritahan ‘Abbasiyyah: wazir, kātib, dan amīr, secara tetap diduduki oleh bangsa Persia, bahkan diwarisi secara turun-temurun oleh keluarga tertentu. Jabatan wazīr sendiri telah tampak sebagai semacam dinasti dalam dinasti. Jabatan kātib telah menjadi kelas sosial tertentu, yang lebih tampak sebagai tandingan dari kelas `ulamā’. Sedangkan qādī yang semestinya diduduki kaum `ulamā’, cenderung dihindari oleh figur-figur penting dari kalangan Arab. Dominasi unsur Persia dalam pemerintahan ‘Abbāsiyyah akhirnya menciptakan pola budaya berpikir baru, menyerap unsurunsur rasional dalam kebudayaan Persia. Kelas kātib menjadi pelopor bagi gerakan berpikir rasional, yang bermuara pada paham Mu’tazilah. Sementara kaum `ulamā’ kukuh pada wataknya yang tradisional, mengacu pada tradisi-tradisi awal pemikiran Islam yang bertumpu pada teks-teks agama (nas al-Qur’ān dan Sunnah). Perbedaan ini akhirnya menciptakan perpecahan di kalangan elit pemikir: kaum kātib versus `ulamā’, yang bermuara pada perseteruan antara Mutazilah vs. Sunni.14 Perseteruan itu meruncing dengan munculnya pemikiran Ibn Muqaffa’ (w. 759), seorang kātib yang paling berpengaruh, yang mengusulkan kepada al-Mansūr untuk membuat formulasi hukum fiqh berdasarkan ijtihadnya sendiri, dan dijadikan sebagai standar hukum Islam yang harus dipatuhi oleh semua mazhab.15 Penggalakan budaya berpikir rasional itu semakin mendapat tempat pada masa Harun Al-Rasyid melalui lembaga-lembaga simposium yang didirikannya, untuk menghadirkan para ilmuan dalam forum debat-debat ilmiah, sekaligus menandai awal persentuhan Islam dengan pemikiran filsafat Helenisme. Tradisi ini semakin menguat 13 Bernard Lewis, Bernard, The Political Language of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), 43-47. 14 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: The Clarendon Press, 1971), 55. 15 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 55. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 95 Agus Salim pada masa al-Ma’mun yang mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat kajian dan pusat transfer ilmu dan filsafat dari Yunani, Aleksenderia, dan India. Sementara itu, ketegangan politik terus terjadi akibat tarik menarik kepentingan antara kaum Sunni dan Syiah. Dalam kondisi inilah, Al-Ma’mun melancarkan proyek Mihnah pada tahun 833 M, yang memaksakan paham Mu’tazilah (bahwa al-Qur’an sebagai makhluk) kepada para ulama (Sunni). Sebagai akumulasi dari kekecawaan politik, sosial, budaya dan ekonomi, kaum Sunni pun bereaksi dengan membangkitkan pemberontakan besar-besaran dari bangsa Arab hingga terjadilah perang kesukuan yang tercatat terbesar sepanjang sejarah Islam. Pemberontakan itu berkepanjangan hingga masa kekuasaan Al-Mutawakkil, hingga memaksa Al-Mutawakkil untuk menggugurkan Mu’tazilah sebagai paham resmi kerajaan, dan beralih kepada paham Sunni. Sejak masa itulah, kaum Sunni mendapatkan ruang ekspresi keilmuan yang lebih luas. Namun demikian, perkembangan politik Abbasiyah mengalami penurunan karena melemahnya kekuasaan para khalifah setelah Al-Mutawakkil. Wilayah kekuasaan Abbasiyah pun menciut dengan munculnya berbagai kerajaan kecil yang memerdekakan diri di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Kondisi itu memecah umat Islam ke dalam berbagai kekuasaan politik yang menurut Hitti mencapai jumlah ratusan hingga tak terbilang. Dalam kondisi menurunnya kekuasaan sentralisitik Abbasiyah itu, kontrol terhadap ekspresiekspresi budaya pun terlokalisasi berdasarkan kecenderungankecenderungan penguasa lokal. Pada tahap perkembangan itulah, berbagai aliran pemikiran (mazhab) muncul dengan membangun afiliasi dengan kerajaankerajaan yang ada, baik besar maupun kecil. Meskipun pusat pemerintahan Abbasiyah sejak Al-Mutawakkil memunculkan larangan terhadap Mu’tazilah dan kajian-kajian filsafat, namun paham-paham rasionalistik tersebut terus tumbuh subur di bawah patronase kerajaan-kerajaan tertentu. Kegiatan keilmuan 96 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim itu pun terus tumbuh, karena posisi istimewa yang ditempati oleh para ilmuan di dalam istana, meskipun perubahan haluan politik memaksa ilmuan-ilmuan tertentu untuk berpindah-pindah tempat mencari kerajaan yang paling kondusif untuk corak dan warna pemikirannya. Kondisi inilah yang terjadi di sepanjang sisa kekuasaan Abbasiyah, yang dipenuhi dengan intrik-intrik politik, mulai dari penggelapan pajak, kudeta kekuasaan dan separatisme, hingga runtuhnya Baghdad oleh pasukan animis Mongol pada tahun 1258 M. 3. Pembentukan Berbagai Disiplin Ilmu Keislaman a. Ilmu Hadits Fenomena keilmuan yang muncul setelah berlalunya masa Sahabat adalah perang pendapat (ijtihad) antar ulama. Oleh karena itu, proyek keilmuan terbesar yang dicanangkan Bani Umayyah adalah melakukan standardisasi ajaran Islam. Hal itu dilakukan melalui standardisasi rujukan terhadap Sunnah Nabi SAW, sebagai sumber Islam kedua setelah al-Qur’an, dengan mengumpulkan hadits-hadits Nabi SAW dan menerbitkannya menjadi standar rujukan satu-satunya terhadap Sunnah Nabi SAW. Hal ini terkait dengan fenomena umum pemalsuan hadits untuk memperkuat suatu pendapat. Atas latar belakang itulah, muncul tokoh hadits sekaliber Ibnu Syihab al-Zuhri. Ulama hadits ini yang paling dipercayai riwayatriwayatnya, sehingga diyakini bahwa jika tidak melalui keduanya, maka suatu riwayat hadits diragukan kesahihannya. Karena pamornya yang demikian itulah, Ibn Syihab al-Zuhri pernah didatangi oleh Ibrahim ibn al-Walid untuk menuliskan hadits-hadtis yang akan dijadikan standar bagi seluruh umat Islam. Akan tetapi, al-Zuhri menolak karena kekhawatirannya akan dijadikan alat oleh pemerintah untuk mengontrol ijtihad para ulama yang tidak disertai dengan suatu riwayat hadits, atau didasarkan pada hadits yang tidak diketahui oleh al-Zuhri, karena tidak semua hadits melalui alZuhri.16 Abū Bakr ibn Hazm juga pernah disurati oleh Khalifah 16 Fazlur Rahman, Islam 1984), 60-61. (terjemah Ahsin Mohammad) (Bandung: TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 97 Agus Salim ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz untuk menuliskan setiap riwayat hadits yang ditemukannya untuk dijadikan standar. Hal serupa juga diperintahkan oleh ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz kepada `ulamā’ hadits yang lain, tapi semuanya menolak.17 Hasan Basri bahkan pernah menghadap ‘Umar ibn ‘Abd al‘Azīz dan menyatakan pandangannya bahwa suatu pendapat ijtihādī tidak harus bersandar kepada riwayat-riwayat hadits, jika memang tidak ada riwayat yang ditemukan pada masalah tertentu. Karena jika diharuskan demikian, sementara tidak semua masalah dipecahkan secara detail dalam Sunnah, maka justru akan mendorong terjadinya pemalsuan hadits.18 Meskipun para ulama hadits menolak dibukukannya kitab hadits standar pada masa itu, namun mereka terus bergiat melakukan kajian-kajian hadits, dan merumuskan perangkat keilmuan hadits untuk kepentingan mendeteksi hadits shahih, dha’if, dan maudhu’ (palsu). Gerakan ulama-ulama hadits inilah yang menjadi cikal bakal gerakan Ahl al-Sunnah dalam rangka menjaga kemurnian hadits Nabi SAW. Gerakan Ahl al-Sunnah itu berkembang menjadi lebih sistematis pada peralihan abad pertama menuju abad kedua Hijriyah. Hal ini ditandai dengan munculnya sistem isnad (transmisi berantai) sebagai salah satu komponen inti dalam meriwayatkan Sunnah Nabi SAW. Sistem itu juga yang memicu pertumbuhan kegiatan verbalisasi Sunnah secara massif menjadi riwayat-riwayat hadits.19 Pada abad kedua Hijriyyah, muncullah ulama-ulama yang membukukan hadits -hadits yang mereka riwayatkan sendiri.20 17 Ahmad Amin, Fajr al-Islām (Kairo: Maktabat al-Nahdah alMisriyyah, 1965), cet. ke-10, 221-222. 18 Lihat Fazlur Rahman, Islam, 70-71. 19 Fazlur Rahman, Islam, 68. 20 Kegiatan penulisan hadits sesungguhnya telah berlangsung pada masa Rasulullah SAW, namun lebih diperuntukan sebagai koleksi pribadi para Sahabat, bukan untuk dibukukan dan dipublikasikan secara luas. ‘Abdullah ibn ‘Amr ibn al-Ās , umpamanya, mengaku menulis setiap apa yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Salah satu riwayat yang paling terkenal menyangkut masalah adalah adalah riwayat tentang seseorang dari penduduk 98 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim Tokoh pertama di bidang ini adalah: al-Rabī’ ibn Syubaih (w. 160 H.) dan Sa’īd ibn Abī ‘Arūbah (w. 156 H.). Selanjutnya diikuti oleh Mālik ibn Anas (179 H/795 M), ‘Abd al-Malik ibn Juraij, al-Awza’ī, Sufyān al-Śawrī, Hammād ibn Salamah, dan banyak lagi. Menurut Ahmad Amin, hampir setiap `ulamā’ hadits masa itu menulis setiap koleksi haditsnya masing-masing.21 Pada masa Abbasiyah, Khalifah Al-Mahdi dan Harun AlRasyid juga pernah meminta Imam Malik untuk membuat kitab hadits standar, akan tetapi Imam Malik menolak permintaan tersebut. Kepada Harun al-Rasyīd, Imam Mālik memberi jawaban: " تفعل ال، "مصيب وكل البلدان في وتفرقوا الفروع في اختلفوا هللا رسول أصحاب فإن “Jangan engkau lakukan, karena sesungguhnya Sahabat Rasulullah pun berbeda pendapat pada masalah-masalah furū’ī, dan menyebar di berbagai negeri, dan masing-masing adalah benar bagi dirinya masing-masing.”22 Dasar pandangan Imam Mālik di atas adalah bahwa hadits Nabi SAW tersebar di berbagai negeri melalui penyebaran para Sahabat, yang sulit sekali ada seorang ahli yang menerima semua riwayat hadits tersebut. Sehingga hampir mustahil mengadakan kitab hadits standar yang memuat seluruh riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW. Kehati-hatian ulama dalam masalah hadits Nabi mendorong Imam Abu Hanifah menolak hadits yang diriwayatkan perorangan. Argumen umum yang sering digunakan adalah bahwa di Madinah saja terdapat tiga puluh ribu Sahabat atau lebih, yang merupakan saksi hidup dipraktekkannya Sunnah Nabi SAW. Maka sulit sekali untuk mempercayai adanya Sunnah yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua saja. Oleh karena itu, Abu Hanifah hanya meyakini hadits yang diriwayatkan secara mutawatir sebagai dasar hukum.23 Yaman yang meminta kepada Rasulullah untuk dituliskan apa yang didengarnya dari khutbah Nabi pada saat Fathu Makkah. Nabi SAW bersabda: “Tuliskanlah untuk si Fulan”. ()فالن ألبي أكتبوا. Diriwayatkan juga dari. Ahmad Amin, Fajr al-Islām, 209. 21 Ahmad Amin, Fajr al-Islām, 222. 22 Ahmad Amin, Fajr al-Islām, 222. 23 Fazlur Rahman, Islam, 79. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 99 Agus Salim Pandangan tersebut ditolak oleh Imam Syāfi’ī dengan menyatakan bahwa riwayat perorangan (ahad) harus diterima sebagai dasar hukum, sepanjang rawinya shahih (‘adil dan dlabith). Oleh karena itu, Imam Syafi’i merumuskan suatu standar kritik hadits. Sejak itu pula, upaya formalisasi keilmuan hadits sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dilakukan. Sejumlah perangkat keilmuan hadits yang telah berkembang pada masa-masa yang lebih awal, dirumuskan ulang dalam sistem yang lebih ketat. Pada tahap inilah, prinsip al-jarh wa al-ta’dīl sebagai perangkat kritik sanad hadits berkembang luas, sekaligus sebagai senjata utama menghadapi praktek pemalsuan hadits yang juga semakin luas di masa-masa awal pemerintahan Abbāsiyyah.24 Upaya Imam Syafi’i itu diteruskan oleh muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal yang memimpin sebuah gerakan yang ia sebut sebagai gerakan Ahl al-Hadits. Ia pun menulis kitab hadits “al-Musnad”. Atas upaya-upaya itulah, kaum Sunni menetapkan enam kitab hadits yang paling terpercaya, yang dikenal dengan “al-Kutub al-Sittah”, yaitu: 1. Shahih al-Bukhārī, karya Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī (w. 256 H/870 M); 2. Shahih Muslim, karya Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj alQusyairī (w. 261 H/875 M); 3. Sunan Abī Dāwūd, karya Abū Dāwūd Sulaimān al-Sījistānī (w. 275 H/888 M); 4. Sunan al-Turmudzi, karya Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā alSulmī al-Turmudzī (279 H/892 M); 5. Sunan al-Nasā’ī, karya Abū ‘Abd al-Rah mān Ahmad ibn Syu’aib al-Nasā’ī (303 H/916 M); 6. Sunan Ibn Mājah, karya Abū ‘Abdillah Muh ammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, dikenal dengan Ibn Mājah (273 H/886 M). 25 24 Fazlur Rahman, Islam, 68-85. Suyūtī, Jalâl al-Dīn al-, Tadrîb al-Râwî fî Syarh al-Taqrîb li al-Imām al-Nawawî (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 57, 107. 25 100 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim b. Ilmu Fiqh Setelah menjadi pihak yang tertekan di sepanjang masa pemerintahan al-Shaffāh dan al-Manshūr, kaum `ulamā’ akhirnya mendapat ruang ekspresi yang lebih luas pada masa pemeritahan alMahdī. Hal ini terkait dengan menguatnya posisi `ulamā’ sebagai sandaran rujukan keberagamaan bagi mayoritas umat Islam yang kelak menjadi basis komunitas Sunni. Penguatan itu terjadi karena posisi politiknya yang ideal, dengan menampilkan sikap-sikap moderat, di tengah pertikaian yang nyaris terpusat pada pendukung Banū al-‘Abbās di satu pihak, dan pendukung Ahl al-Bayt di pihak lain. Al-Mahdi akhirnya mulai memperhitungkan kekuatan sosial yang dimiliki kaum `ulamā’, dengan mencitrakan diri dalam citra kekuasaan yang universal. Maka digunakanlah gelar Khalīfah yang lebih netral dibandingkan dengan gelar Imām yang sudah menjadi prinsip tetap dalam ideologi politik Syī’ah.26 Sejak itu, terjadilah konsolidasi pemikiran di kalangan `ulamā’, yang diawali dengan pemikiran di bidang hukum. Hal ini sesungguhnya telah dimulai sejak era Imam Abū Hanīfah (w. 204/767), ketika ia mengembangkan metode kritis terhadap kajian hukum Islam. Metode inilah yang digunakan untuk membendung praktek-praktek klaim keagamaan yang meluas dalam pertikaian politik. Mālik ibn Anas (w. 179/795) melanjutkannya dengan membukukan pandangan-pandangan hukumnya dalam al-Muwaththa’.27 Namun formulasi pemikiran hukum menjadi sistem hukum yang koheren, baru muncul pada masa Imam Syāfi’ī (150-204/767819), terkait dengan upayanya merumuskan ushūl al-fiqh sebagai landasan metodologis bagi pemikiran hukum Islam. Inilah yang memperkuat posisi `ulamā’ pada masa al-Mahdī, yang dapat diduga kuat sebagai salah satu faktor penting yang mendorong al-Mahdī untuk melakukan konsiliasi dengan kaum `ulamā’. Mula-mula al-Syāfi’ī mengkampanyekan kritik sanad hadits secara besar-besaran. Selanjutnya ia menekan otoritas ijmā’ yang dalam konsepsi para pendahulunya mempunyai jangkauan terlalu luas, dan cenderung mengintervensi wilayah kewenangan Sunnah. 26 27 Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam, 288, 291. Fazlur Rahman, Islam, 112. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 101 Agus Salim Maka dibuatlah batasan ijmā’ dengan kewenangan yang terbatas, dan hanya berlaku dalam pengertian ijmā’ al-ummah ‘āmmatan (melibatkan seluruh lapisan masyarakat muslim), bukan sekadar ijmā’ al-‘`ulamā’ (konsensus `ulamā’ secara terbatas). Dua proyek inti al-Syāfi’ī ini secara efektif dapat menekan praktek pemalsuan hadits, dan pelembagaan hukum yang hanya didasarkan pada konsensus `ulamā’ secara terbatas. Konsensus yang terbatas, menurut al-Syāfi’ī tidak dapat mempunyai kewenangan hukum yang bersifat tetap dan mengikat, dan karenanya tidak dapat dilembagakan secara baku. Hal ini dapat juga dilihat sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah ‘Abbāsiyyah untuk melakukan sentralisasi hukum Islam di bawah kontrol politik pusat, yang memuncak pada masa Hārūn alRasyīd (170-193/786-809). Khalīfah yang melegenda di kalangan Sunni inilah yang mewujudkan gagasan yang pernah diusulkan oleh Ibn al-Muqaffa’, dengan membuat lembaga qādlī al-qudlāt sebagai pihak yang mempunyai kewenangan resmi untuk memutuskan perkara-perkara hukum di seluruh wilayah ‘Abbāsiyyah. Pejabat pertama lembaga tersebut adalah Abū Yūsuf (w. 182/798) yang merupakan pengembang madzhab Hanafi.28 Dengan metodologi hukum yang dikembangkannya, Imam Syafi’i telah memberi contoh tentang kompromi ilmiah terhadap dua kecenderungan pemikiran yang berkembang secara berseberangan, antara yang menekankan konservatisme tradisional dan rasionalisme yang inovatif. Upaya-upaya inovasi rasional lazimnya dengan cepat dikecam sebagai gerakan bid’ah, yang melanggar Sunnah. Sebaliknya, langkah-langkah konservatif menjadi kontraproduktif bagi upaya penyebaran Islam ke wilayah-wilayah budaya yang baru, yang mensyaratkan adanya inovasi-inovasi. Cara pandang pertama mewakili cara pandang yang tipikal ahl al-hadīts, yang dipelopori oleh Mālik ibn Anas, yang berasal dari bangsa Arab. Sedangkan 28 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: The Clarendon Press, 1971), 51. 102 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim yang kedua mewakili ahl al-ra’y yang dimotori oleh Abū Hanīfah yang mencirikan asal Persianya.29 Kedua cara pandang ini dikompromikan oleh al-Syāfi’ī berbekal pengalaman pendidikan di kedua pusat aliran hukum tersebut,30 sehingga dapat menghasilkan sintesa ushul al-fiqh yang lengkap. Pengaruh konservativisme ahl al-hadīts tampak jelas dari penekanannya terhadap otoritas riwayat hadits, sekalipun ahad. Sementara pengaruh ahl al-ra’y terekspresikan melalui prinsip Qiyas yang dimasukkannya sebagai sumber hukum Islam yang sah, di samping proses formulasi hukumnya yang rasional, sehingga menghasilkan sistem yang koheren.31 Al-Syāfi’ī juga memberi contoh tentang posisi ideal `ulamā’ di hadapan pemerintah, untuk tidak terlibat dalam hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah. Terkait dengan ini, al-Syāfi’ī pernah menolak untuk menduduki jabatan qādlī al-qudlāt yang ditawarkan oleh al-Ma’mūn pada awal kekuasaannya (813). Akibat kondisi politik yang semakin memburuk, al-Syāfi’ī keluar dari Baghdad menuju Mesir, tempat berdirinya dinasti Arab yang memecah diri dari ‘Abbasiyyah, yaitu Aghlabiyyah. Pada perkembanganya, empat tokoh fuqaha’ inilah yang menjadi imam empat madzhab fiqh Sunni yang mu’tabar. c. Ilmu Kalam Cikal bakal ilmu kalam pertama kali muncul pada masa perpecahan umat Islam menjadi Syi’ah, Khawarij dan Murjiah. Ketiganya terlibat dalam perdebatan tentang hak kepemimpinan dalam Islam. Syiah memandang bahwa hak tersebut berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Khawarij memandang bahwa hak tersebut berada di tangan orang yang bukan pelaku dosa besar, termasuk membunuh sesama muslim, karena dosa besar merusak keimanan, dan karenanya pelaku dosa besar tidak boleh menjadi pemimpin umat. Sedangkan Murjiah berpandangan bahwa 29 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 57-63. Lihat Muhammad Sayyid Kaylānī, “Al-Imām al-Syāfi’ī Radiyallāh ‘anhu”, dalam Muhammad ibn idrîs al-Syāfi’ī, al-Risālah (Jakarta: Dinamika Berkat utama, t.t.), 3. 31 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, 47-48. 30 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 103 Agus Salim dosa tidak merusak iman, karena iman tidak terkait dengan amal. Namun perbedaan pendapat tersebut lebih banyak diwarnai dengan pertikaian politik. 32 Kalam sebagai sebuah disiplin ilmu, mulai muncul pada masa Mu’tazilah dengan memberi ciri kepada ilmu kalam sebagai sebuah kajian rasional terhadap struktur dasar ajaran Islam. Paham ini sendiri muncul dari Washil bin ‘Atha’ (w. 131 H) terkait dengan perdebatannya dengan Hasan Basri di masjid Basrah. Pada suatu hari datang seorang yang bertanya mengenai pendapat Hasan Basri tentang orang yang berdosa besar. Sebagaimana diketahui, kaum Khawarij memandang mereka itu kafir. Sedangkan kaum Murjiah memandang pelaku dosa besar itu tetap mukmin. Ketika Hasan Basri masih menimbang-nimbang jawaban, Wasil mengeluarkan pendapatnya dan berkata: “Saya berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak juga mukmin, tapi berada pada posisi antara keduanya.” Kemudian ia berdiri dan menjauhkan diri dari Hasan Basri, dan duduk di tempat lain dalam masjid. Atas peristiwa itu, Hasan Basri mengatakan: “Ia telah memisahkan diri dari kita (i’tazala ‘anna).” Pernyataan Hasan Basri itu akhirnya digunakan untuk menyebut kelompok Wasil dan yang sepaham dengannya, yaitu Mu’tazilah.33 Paham Mu’tazilah ini mendapat rumusan yang baku melalui Qadli Abd al-Jabbar (w. 415/1025), melalui rumusan lima prinsip Mu’tazilah (al-Ushul Khamsah) yang dikemukakan oleh Qadli Abd al-Jabbar (w. 415/1025). Kajian rasional yang memasuki wilayah ketuhanan tersebut (teologi) mendapat serangan dari kaum Hanbalī (Ahl al-Hadīts), yang memandang cara berpikir kalam merupakan impor rasionalisme asing yang bersifat spekulatif, dan karenanya tidak dapat diterima dalam konteks Islam. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, satu-satunya pemikiran yang dibolehkan tentang Tuhan 32 Syahrastānī, Abū al-Fath al-, al-Milal Wa al-Nihal (Kairo: Mustafa alBabi al-Halabi, 1961), Juz 1, 28-29. 33 Harun Nasution, Teologi Islam (Jakarta: UI-Press, 1986), 38. 104 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim adalah “bi lā kayf”. Pembicaraan kalām yang lebih jauh dari itu adalah bid’ah yang menyesatkan. Serangan Imam Ahmad bin Hanbal tersebut dipertajam oleh kekuasaan Mu’tazilah pada masa Al-Ma’mun yang melalui proyek Mihnahnya menjerumuskan Imam Ahmad bin Hanbal ke dalam penjara yang penuh deraan fisik selama 6 tahun. Namun demikian, ilmu kalam terus berkembang, meskipun Mu’tazilah telah dinyatakan sebagai paham terlarang oleh AlMutawakkil. Pada tahap inilah muncul dua tokoh dari kalangan Sunni yang berupaya melakukan counter terhadap serangan Mu’tazilah, dengan merumuskan ilmu kalam versi Sunni. Kedua tokoh tersebut adalah Abu al-Hasan al-Asy’arī dan Abū Manshūr alMātūrīdī. Kedua tokoh ini menawarkan suatu formula pemikiran yang mengompromikan tradisionalisme ekstrem Ahl al-Hadits di satu pihak; dengan rasionalisme ekstrem Mu’tazilah di pihak lain. Maka dihasilkanlah paham-paham bersama yang moderat, yang belakangan menjadi lambang pandangan teologi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah.34 Namun demikian, pada awal kemunculannya, baik al-Asy’arī maupun al-Mātūrīdī, belum dipandang sebagai bagian dari paham Sunni, yang saat itu dinisbatkan pada kaum Hanbali. Kaum Hanbali pun tidak menerima pengakuan al-Asy’arī bahwa ia berpegang pada mazhab Hanbali. Ibn al-Subkī menyatakan dalam “Thabaqāt alSyāfi’iyyah” bahwa kaum Hanbali melarang al-Khathīb al-Baghdādī (w. 463 H.) untuk memasuki masjid Jāmi’ di Baghdad, karena mengembangkan paham Asy’ariyyah. Para pengembang paham Asy’ariyyah pada masa itu bahkan diusir dan disirnakan. AlQusyairī (tokoh Asy’ari abad ke-6 Hijriyah, w. 514 H.) mengalami hal itu ketika terusir dari Baghdad, setelah sebelumnya terjadi perkelahian antara massa kedua paham. Karena peristiwa inilah, 34 Tentang titik temu pandangan Asy’ari dan Mātūrīdī: Fathullāh Khulaif, “Muqaddimah”, dalam al-Mātūrīdī, Kitāb al-Tawhīd, Istanbul: alMaktabah al-Islāmiyyah Mohammed Ozdmir, 1979, h. 10-26; Sa’d al-Dīn alTaftazānī, Syarh al-`Aqā’id al-Nasafiyyah, (tahqīq: Ahmad Hijāzī al-Saqqā), (Kairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1988). TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 105 Agus Salim menurut Ibn ‘Asākir, terjadi perselisihan berkepanjangan antara kaum Hanbali dan Asy’ari.35 Padahal, Abu al-Hasan al-Asy’arī sendiri, ketika menyatakan paham teologinya, ia mencetuskan ikrar sebagai berikut: “Pendapat dan agama yang kami pegang adalah berdasarkan pada Kitab Allah, Sunnah Nabi SAW, dan apa yang diriwayatkan dari Sahabah, Tābi’īn, dan para imām hadīts. Kami berpegang pada itu, dan apa yang dipegang oleh Ahmad ibn Hanbal —[semoga] Allah telah memuliakannya, mengangkat derajatnya, dan memperbanyak pahalanya. Dan kami menjauh dari siapa yang pendapatnya bertentangan dengan pendapat Ahmad ibn Hanbal, karena dialah imām utama, pemimpin yang sempurna, dan Allah telah menetapkan kebenaran pada dirinya ketika muncul kesesatan.”36 Hal ini terkait dengan kedudukan Hanbali pada masa itu sebagai mazhab resmi Abbasiyah yang diteguhkan oleh khalīfah al-Qādir, melalui sebuah manifesto yang terbit pada tahun 433 H/1041 M.37 Manifesto tersebut mencantumkan pasal larangan terhadap madzhab-madzhab kalam sebagai “ahl al-bid’ah”, yaitu: Karrāmiyyah, Imāmiyyah, Ismā’īliyyah, Mu’tazilah, dan Asy’ariyyah.38 Inilah yang menjelaskan munculnya persekusi terhadap tokoh-tokoh Asy’ariyyah di Baghdad hingga pada pertengahan abad kesebelas Masehi.39 Kenyataannya, maka meskipun sesungguhnya mayoritas wilayah ‘Abbāsiyyah telah tersunnikan, namun realitas Sunni sendiri belum solid, dan karenanya belum mempunyai solidaritas kolektif yang menyatukan mereka. Madzhab-madzhab proto-Sunni 35 Hamīd, Muhammad Muhy al-Dīn ‘Abd al-, Muqadimmat al-Maqalat (Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1954), cet. ke-1, 66-137. 36 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqih min al-Dhalāl (Beirut: alMaktabah al-Sya’biyyah, t.t.), 24. 37 Syahrastānī, Abū al-Fath al-, al-Milal Wa al-Nihal (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961), 27. 38 Watt, William Montgomery, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1992), cet. ke-2, 80-82. 39 Syahrastānī, Abū al-Fath al-, al-Milal Wa al-Nihal, 26. 106 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim berkembang secara terpisah-pisah dan terkotak-kotak ke dalam wilayah-wilayah yang otonom, mengikuti otonomi dinasti-dinasti satelit. Pada masa kekuasaan Bani Buwaih di Baghdad, situasi berpihak kepada paham Maturidi, karena dukungan pemerintah. Kondisi sebaliknya dialami para pengikut Ahmad bin Hanbal dan Asy’ari, karena paham fiqh mereka berbeda. Pemerintah Bani Buwaih saat itu berpaham Hanafi yang berafiliasi pada paham kalam Maturidi, sedangkan Asy’ari berafiliasi pada paham fiqh Syafi’i. Namun pada saat Banū Saljūq berkuasa, situasi beralih kepada pengikut paham Asy’ari dan Syafi’i. Pada masa inilah muncul Imam Syafi’i yang menggagas sebuah proyek penyatuan madzhabmadzhab fiqh, kalam dan tasawuf. Maka lahirlah paham Sunni sebagaimana bentuknya seperti sekarang ini. d. Tasawuf dan Filsafat Tasawwuf dan filsafat menjadi wacana pemikiran yang paling polemis dalam Islam, terkait dengan corak pemikirannya yang asing bagi budaya Arab. Hal ini juga menjelaskan mengapa kecenderungan berpikir sufistik dan filosofik pada umumnya datang dari kaum muslim non-Arab. Atas dasar ini, maka tasawwuf dan filsafat dapat dilihat sebagai disiplin alternatif terhadap main stream pemikiran Islam yang didominasi oleh bidang fiqh dan kalām. Tradisi tasawwuf telah muncul lebih awal dari filsafat, dan mengambil bentuk dalam keberagamaan para zuhhād, qurrā’, bukkā’ūn, qushsāsh, nussāk, dan bentuk-bentuk praktek keislaman asketik lainnya. Namun pada masa ‘Abbāsiyyah, ia tampak lebih sebagai respons terhadap rumusan-rumusan pemikiran Islam yang legal dan formal-oriented. Terlebih ketika pemerintah ‘Abbāsiyyah terus mengupayakan terbentuknya legislasi hukum Islam untuk dibakukan menjadi representasi syarī’ah. Namun berdasarkan interaksinya dengan paham Sunni, tasawwuf terpecah ke dalam dua arah perkembangan. Pertama, tasawwuf yang terkompromikan dengan paham Sunni. Kedua, tasawwuf yang mengambil bentuk perkembangan yang terpisah dari paham Sunni.40 40 ‘Abd al-Razzāq al-Kāsyānī, Ishthilāhāt al-Sūfiyyah (t.tt.: Dār alM’ārif, t.t.), 10. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 107 Agus Salim Tokoh awal dari mazhab tasawwuf pertama, dapat disebut sebagai tasawwuf Sunni, adalah al-Hārits al-Muhāsibī (w. 243/857) dan alJunayd al-Baghdādī (w. 298/911). Sementara tokoh awal dari mazhab kedua adalah Źū al-Nūn al-Misrī (w. 245/859), Abū Yazīd al-Bistāmī (w. 260/874), dan al-Husain ibn Mansūr al-Hallāj (w. 310/923). Perpecahan dua corak tasawwuf ini ditandai oleh konflik antara al-Junayd al-Baghdādī dengan muridnya, al-Hallāj, yang berakhir dengan eksekusi mati al-Hallāj. Pokok pertentangan keduanya berkenaan dengan polemik tentang haqīqah dan syarī’ah. Tasawwuf Sunni, atau apa yang disebut oleh Fazlur Rahman sebagai sufisme ortodoks, mengharuskan keselarasan keduanya. Sementara al-Hallāj lebih menekankan pada haqīqah, karena hanya dengan itulah, seorang hamba dapat mengalami puncak pengalaman spiritual tertinggi (hāl al-haqq), yang diistilahkan al-Hallaj sebagai hulūl. Bersamaan dengan masa itu, filsafat juga muncul menawarkan alternatif lain dalam memahami Islam. Meskipun filsafat — bersama-sama dengan paham Mu’tazilah, telah dinyatakan ilegal sejak digugurkannya Mihnah, namun ia berkembang pesat menjadi kegiatan-kegiatan individual di negeri-negeri yang menawarkan swaka politik. Muncullah nama-nama seperti Ibn Sīnā dan al-Fārābī, yang pemikirannya banyak memberi sumbangan bagi perkembangan doktrin tasawwuf (teosofi) Syī’ah, dan teologi rasional pada umumnya. Pada kenyataannya, gerakan-gerakan filsafat lebih banyak bersembunyi di balik tiga bentuk pemikiran tersebut, karena pemerintah ‘Abbāsiyyah sendiri secara resmi melarang perkembangan filsafat. Maka selain Ibn Sīnā dan al-Fārābī, sulit untuk menemukan gerakan filsafat secara mandiri, tanpa berafiliasi (bersembunyi) pada lembaga pemikiran tertentu. Misteri Ikhwān al-Safā dengan jelas menggambarkan hal tersebut.41 Pada perkembangannya, penolakan terhadap filsafat yang berlangsung secara konstan sejak kehilangan patron politiknya bersamaan dengan kemenangan Ahl al-Hadīts pada masa al41 Mohammed ‘Abed al-Jabiri, Contemporary Critique, 47-62. Arab-Islamic 108 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Philosophy: A Kehidupan Para Ilmuan Muslim Mutawakkil, terlembagakan menjadi penolakan resmi dalam ortodoksi Sunni.42 3. Rekonsiliasi Ilmu-Ilmu Islam Hingga masa kekuasaan Saljuk di Baghdad, kondisi sosial, budaya, politik dan inteletual umat Islam sedemikian terpecah. Dalam situasi itulah muncul Imam Ghazali (450-505/1058-1111) yang tumbuh sebagai anak yatim dan menenggelamkan diri dalam kegiatan studi terhadap berbagai macam ilmu dan aliran pemikiran. Al-Ghazali pun merasakan kekhawatiran akan bahaya perpecahan umat, lebih dari siapa pun pada masanya. Hal ini dengan tegas ia nyatakan dalam otobiografi intelektualnya, sebagai berikut: إعلموا... األديان يف اخللق اختالف أن، وتباين الفرق كثرة على املذاهب يف األئمة اختالف مث وامللل،حبر الطرق الناجي أنه يزعم فريق وكل األقلون إال منه جنا وما األكثرون فيه غرق عميق43 “Ketahuilah bahwa perbedaan dalam hal agama dan aliran kepercayaan, kemudian berlanjut ke dalam perbedaan madzhab dalam berbagai kelompok yang semuanya mengklaim diri benar dan akan selamat, merupakan lautan yang amat dalam yang menenggelamkan hampir semua umat kecuali sangat sedikit yang tidak.” Berdasarkan kekhawatiran atas kondisi itu, al-Ghazālī dengan sungguh-sungguh berupaya membuat formula sintesa untuk seluas mungkin dapat mengakomodir segala bentuk pemikiran dalam Islam, yang ia rangkum dalam kerangka ‘ulūm al-dīn. Hasil studinya atas empat kelompok besar dalam pemikiran Islam: Muakallimun, Bāthiniyyah, Falāsifah, dan Sufiyyah, membawanya pada kesimpulan bahwa masing-masing kelompok itu adalah jalan menuju kebenaran yang berbeda-beda, yang benar menurut porsinya masing-masing. Kebenaran yang utuh hanya dapat diperoleh jika empat cara pandang itu diletakkan dalam porsinya.44 42 Lebih jauh tentang dua wacana ini, Rahman, Islam, 167-216; Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, 208-218; Karen Armstrong, A History of God (New york: A Mandarin Paperback, 1996), 200-212, 261-265 43 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqizh min al-Dlalāl (Beirut: alMaktabah al-Sya’biyyah, t.t.), 24. 44 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqizh min al-Dlalāl, 33-35. TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 109 Agus Salim Kekacauan pemikiran terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap proporsi yang semestinya. Filsafat, umpamanya, hanya berwenang pada wilayah-wilayah aqlī (al-ma’rifah al-manthiqiyyah wa al-riyādliyyah) dan hissī (al-ma’rifah al-tajrībiyyah), dan tidak dapat memasuki wilayah kewenangan agama atau wahyu (alma’rifah al-ghaibiyyah). Kesesatan dan kekufuran terjadi karena pelanggaran terhadap wilayah kewenangan tersebut.45 Lebih jauh, al-Ghazālī dengan tegas menyatakan bahwa sebab kekacauan dan kelemahan iman adalah karena sikap penganut empat kelompok pemikiran yang tidak proporsional, yaitu: 1. Fanatisme berlebihan pada ilmu filsafat. 2. Fanatisme berlebihan pada jalan-jalan (tharīqah) Sufi. 3. Sektarianisme kaum Bāthiniyyah (yaitu: Ismā’iliyyah). 4. Masuknya kaum awam dalam wilayah ilmu yang pelik.46 Inilah yang memberi bentuk bagi pembahasan teologi yang sarat dengan pesan-pesan sufistik; memberi bentuk syar’ī bagi tasawwuf yang hanya mengedepankan haqīqah (esoterik); memberi kerangka rasional filosofis bagi doktrin-doktrin hukum fiqh; memberi acuan teologis (doktrin kalām) bagi filsafat; dan akhirnya memberi ransangan berpikir kritis terhadap pendapat-pendapat doktriner yang hanya akan memperluas populasi muslim awam yang jauh dari ilmu. C. Penutup Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bidang-bidang ilmu agama Islam lahir sebagai hasil dari dinamika sosial, budaya, dan politik umat Islam sepanjang masa pembentukan, pertumbuhan dan pengembangnnya, yaitu sepanjang masa Banu Umayyah dan Banu Abbas. 45 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqizh min al-Dlalāl, 46-54; Badawī Tabānah, Muqaddimat al-Ihya’, 19; Sulaiman Dunia, “Muqaddimah”, dalam al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, (Mesir: Dar al-Ma’ārid, t.t.), cet. ke-4, h. 44-45 46 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqizh min al-Dlalāl, 88. 110 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 Kehidupan Para Ilmuan Muslim 2. 3. Ilmuan-ilmuan muslim dalam bidang ilmu Hadits, Fiqh, Tasawuf, Kalam dan Filsafat merupakan aktor-aktor sejarah yang tumbuh konteks-konteks sejarah sosial, budaya, politik dan ekonomi pada zamannya. Faktor sosial, budaya, dan politik adalah faktor yang paling berpengaruh bagi corak, warna dan aliran keilmuan dalam Islam. Sementara faktor ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya dinamika ilmu tersebut dalam proses sejarahnya. Daftar Pustaka Jabiri, Mohammed ‘Abed al-, Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, Austin: The Center for Middle Eastern Studies, 1999 Alfred T. Welch and Pierce Cachia (ed.), Islam: Past Influence and Present Challenge, Edinburgh: The University of Edinburgh Press, 1979 Halm, Heinz, Shiism, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991 Hodgson, Marshall G. S., The Venture of Islam, jilid 1, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1974 Hitti, Philip K., History of Arabs, London: The MacMillan Press, 1967, cet. ke-10 Asy’arī, Abū al-Hasan al-, Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf alMushallīn, juz 1, , Kairo: Maktabat al-Nahdlah alMisriyyah, 1954, cet. ke-1 Lapidus, Ira M., A History of Islamic Societies, Cambridge: The university Press, 1988 Lewis, Bernard, The Political Language of Islam, Chicago: The University of Chicago Press, 1988 Schacht, Joseph, An Introduction to Islamic Law, Oxford: The Clarendon Press, 1971 Rahman, Fazlur, Islam (terjemah Ahsin Mohammad), Bandung: 1984 Amin, Ahmad, Fajr al-Islām, Kairo: Maktabat al-Nahdah alMisriyyah, 1965, cet. ke-10 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014 111 Agus Salim Suyūtī, Jalâl al-Dīn al-, Tadrîb al-Râwî fî Syarh al-Taqrîb li alImām al-Nawawî, Beirut: Dar al-Fikr, 1993 Kaylānī, Muhammad Sayyid, “Al-Imām al-Syāfi’ī Radiyallāh ‘anhu”, dalam Muhammad ibn idrîs al-Syāfi’ī, , al-Risālah, Jakarta: Dinamika Berkat utama, t.t. Syahrastānī, Abū al-Fath al-, al-Milal Wa al-Nihal, juz 1, Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1961 Harun Nasution, Teologi Islam, Jakarta: UI-Press, 1986 Mātūrīdī, Abu Mashur, Kitāb al-Tawhīd, Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah Mohammed Ozdmir, 1979 Taftazānī, Sa’d al-Dīn al-, Syarh al-`Aqā’id al-Nasafiyyah, (tahqīq: Ahmad Hijāzī al-Saqqā), Kairo: Maktabat alKulliyyāt al-Azhariyyah, 1988 Hamīd, Muhammad Muhy al-Dīn ‘Abd al-, Muqadimmat alMaqalat, Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah, 1954, cet. ke-1, h. 66-137 Ghazālī, Abū Hāmid al-, Al-Munqiz min al-Dalāl, Beirut: alMaktabah al-Sya’biyyah, t.t., Watt, William Montgomery, Islamic Philosophy and Theology: An Extended Survey, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1992, cet. ke-2, h. 80-82 Kāsyānī, ‘Abd al-Razzāq al-, Ishthilāhāt al-Sūfiyyah, t.tt.: Dār al-M’ārif, t.t. Armstrong, Karen, A History of God, New york: A Mandarin Paperback, 1996 Dunia, Sulaiman, “Muqaddimah”, dalam al-Ghazālī, Tahāfut al-Falāsifah, (Mesir: Dar al-Ma’ārid, t.t.), cet. ke-4 112 TAJDID Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2014