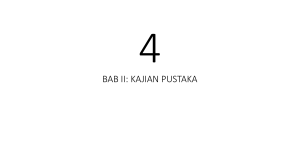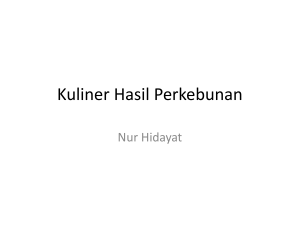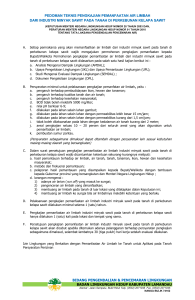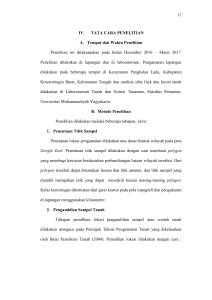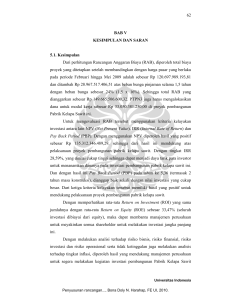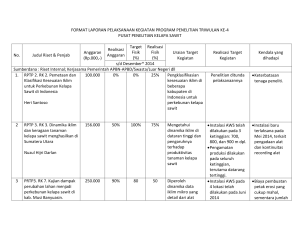BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1
advertisement

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 1. Permasalahan Lingkungan merupakan komponen utama bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Khalayak umum masa kini mulai sering membicarakan tentang akibat yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan hidup yang semakin mengancam kelangsungan kehidupan di bumi (Kristanto, 2004:8). Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di bumi memiliki kadar yang berbeda. Penyebab utama kerusakan lingkungan hidup hanya satu, yaitu paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi (Borong, 2000: 50). Kerusakan lingkungan juga terjadi dalam kaitan dengan meningkatnya jumlah lahan krisis akibat rusaknya permukaan tanah. Hal ini terjadi bukan saja karena kerusakan hutan, tetapi juga akibat tidak langsung dari pola pertanian dan perkebunan intensif dengan menggunakan berbagai pupuk kimia yang merusak lapisan tanah. Kerusakan lingkungan juga akan semakin parah apabila proses degradasi hutan yang terjadi dengan tingkat yang masif seperti sekarang diiringi dengan pola intensifikasi perkebunan yang mengandalkan pupuk kimia yang berbahaya maka akan menimbulkan proses penggurunan yang serius (Keraf, 2010: 34). Pola keinginan yang kurang terkendali sering terjadi disebabkan oleh faktor yang selalu mementingkan diri sendiri. Kepentingan yang berhubungan 1 2 dengan masalah bersama seringkali terabaikan dari perhatian manusia. Faktor egoisme dapat dikatakan sebagai hal yang cukup dominan dalam hubungannya dengan masalah lingkungan. Faktor egoisme ini muncul karena sifat egoisme seseorang demikian dominan, sehingga faktor-faktor norma, etika atau kewajaran/ kepatutan tidaklah menjadi halangan baginya (Siahaan, 2004: 66). Manusia sebagai bagian dari alam seharusnya sangat peduli dan sadar terhadap kelestarian alam. Kepedulian terhadap lingkungan sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh manusia yang merupakan bagian integral dari alam. Manusia sebagai makhluk hidup yang dominan telah banyak menentukan corak kehidupan ekosistem. Manusia dengan berbagai tingkah laku, kepentingan, keinginan, ideologi, pandangan terhadap nilai telah banyak mempengaruhi dan mengubah wajah bumi yang mencerminkan ketidakseimbangan (Siahaan, 2004: 13). Perkebunan sebagai salah satu wujud pemanfaatan alam memiliki banyak pengaruh terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Perkebunan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia saat ini. Demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dari usaha perkebunan, banyak dampak baik maupun buruk yang diterima lingkungan. Teh merupakan komoditi perkebunan yang cukup mempunyai arti penting bagi Indonesia karena dapat menghasilkan devisa bagi negara. Pembukaan lahan perkebunan teh juga dapat berfungsi sosial karena menampung banyak tenaga kerja, serta dapat memelihara kelestarian sumber daya alam yang berupa tanah, air, dan lingkungannya. Tanaman teh yang dimiliki semua perkebunan teh di 3 Indonesia pada saat ini hampir semuanya merupakan tanaman tua. Sebagian besar tanaman teh yang ditanam di Indonesia berasal dari biji, sehingga apabila dicermati akan menunjukkan keragaman meskipun berada dalam satu populasi pertanaman (Mangoendijojo, 2000: 2). Tanaman Kelapa Sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien dibandingkan beberapa tanaman sumber minyak nabati yang memiliki nilai ekonomi tinggi lainnya, seperti kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari. Kelapa Sawit dapat menghasilkan minyak paling banyak dengan rendemen mencapai 21%, kelapa sawit dapat menghasilkan minyak sebanyak 6-8 ton/ hektare (Sunarko, 2010). Masa depan agrobisnis kelapa sawit memiliki peran yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Perkembangan luas dan produksi kelapa sawit di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 1.592.000 hektare pada tahun 1997 menjadi 6.513.000 hektare pada tahun 2007 atau meningkat 7,5% per tahun. Produksi juga meningkat dari 5.448.000 ton (1997) menjadi 17.300.000 ton (2007). Hal ini menjadikan Indonesia mampu melampaui produksi minyak sawit Malaysia, tetapi ekspor Malaysia masih lebih besar. Proses ini mendasari konversi tanaman pada PT. Perkebunan Nusantara IV di Kabupaten Simalungun menjadi tanaman kelapa sawit di samping prospek komoditi teh yang semakin menurun. Keberhasilan dalam pengembangan kelapa sawit sangat ditentukan oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah faktor lahan (tanah dan iklim) faktor tanah khususnya, sebagai medium tumbuhnya tanaman kelapa sawit memiliki sifat-sifat yang kompleks. 4 Kelapa sawit membutuhkan persyaratan iklim tertentu agar dapat tumbuh optimal. Faktor iklim meliputi curah hujan, hari hujan, temperatur, evapotranspirasi, lama penyinaran, dan angin. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh baik di wilayah dengan curah hujan 1.500-3.500 mm/tahun dan optimumnya 2.500 mm/tahun. Lama penyinaran matahari yang dibutuhkan kelapa sawit minimum sekitar 1.600 jam/tahun atau 4,3 jam/hari dan optimalnya 6-7 jam/hari dengan temperatur udara 24-28o Celcius, serta kelembaban udara nisbi sekitar 80%. Tanaman kelapa sawit relatif tahan angin, tetapi kecepatan angin rata-rata tidak lebih dari 40 km/jam.Angin yang kencang dapat merusak daun dan pertumbuhan kelapa sawit (Sunarko, 2014: 38). Tanaman teh hampir sama sekali tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, berbeda dengan kelapa sawit, sebagai tumbuhan yang rakus air dapat membuat kekeringan. Persawahan dan perladangan masyarakat setempat akan hancur apabila sumber air dari tanah habis diserap oleh tanaman kelapa sawit. Pembukaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Simalungun telah dilakukan dengan mengkonversi tanaman teh. Konversi yang sudah terlanjur dilakukan di Kebun Marjandi dan Bah Birung Ulu ke tanaman sawit, sudah beberapa kali mengakibatkan bencana longsor pada waktu musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kebun teh merupakan peninggalan sejarah yang digagas oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920, yang berarti sudah ada 92 tahun lamanya. Petani dan masyarakat Simalungun khususnya sudah sangat akrab dengan kebun teh (http://dpchimapsisimalungun.blogspot.com/ diunduh 27 April 2014). 5 Undang-undang yang mengatur perkebunan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-undang No 18 tahun 2004 tentang perkebunan dan Undangundang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pihak perkebunan sebaiknya membatasi jumlah lahan yang hendak dikonversi jika memang tindakan tersebut harus dilakukan. Pengalaman yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, lingkungannya menjadi rusak akibat konversi kelapa sawit yang telah dilakukan. Pengelolaan perkebunan haruslah memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya agar tidak terjadi bencana yang tidak diharapkan dikemudian hari akibat konversi kelapa sawit. Lingkungan hidup tidak sekedar permasalahan teknis, begitu pula krisis lingkungan global yang saat ini dihadapi manusia adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Etika dan moralitas diperlukan untuk mengatasinya (Keraf, 2010: 1). Teori etika lingkungan Ekosentrisme memusatkan perhatiannya pada seluruh lapisan komunitas ekologis. Makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain secara ekologis. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga berlaku bagi semua realitas ekologis (Keraf; 2010: 92). Deep Ecology merupakan salah satu teori Ekosentrisme menuntut adanya sebuah etika baru yang tidak berpusat pada manusia. Deep Ecology menginginkan etika yang berlaku bagi makhluk hidup seluruhnya dalam hubungan dengan usaha mengatasi persoalan lingkungan hidup. Deep Ecology memusatkan perhatianpada seluruh komunitas ekologis. 6 Tindakan konversi tanaman teh ke kelapa sawit sudah terlanjur dilakukan oleh PTPN IV di Perkebunan Marjandi, Kabupaten Simalungun. Segala macam dampak baik positif dan negatif telah diterima pihak PTPN IV dan masyarakat Simalungun. Konversi tanaman teh ke kelapa sawit bukan hanya masalah teknis saja, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran manusia terhadap lingkungannya dari dampak konversi tersebut. Refleksi etika lingkungan Ekosentrisme yang menginginkan adanaya etika baru yang berpusat pada seluruh komunitas ekologis dianggap dapat digunakan sebagai analisis di pihak PTPN IV dan masyarakat Simalungun penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. 2. Rumusan Masalah Beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: a. Mengapa terjadi konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di PTPN IV Marjandi? b. Apa dampak yang ditimbulkan dari praktek konversi tanaman perkebunan teh menjadi kelapa sawit di PTPN IV Marjandi? c. Apa peran etika lingkungan Ekosentrisme terhadap konversi tanaman perkebunan teh menjadi kelapa sawit di PTPN IV Marjandi? 3. Keaslian Penelitian Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang pernah menulis tentang dampak konversi tanaman teh ke kelapa sawit dikaji dari sudut pandang etika lingkungan Ekosentrisme. Adapun penelitian maupun tulisan yang sejenis dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut. 7 Tesis karya Jan Ericson Chandara Purba, 2009, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Tanaman Perkebunan Teh Menjadi Kelapa Sawit di Kabupaten Simalungun yang berisi harga teh dan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan harga Tandan Buah Segar (TBS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap alih fungsi (konversi) tanaman Perkebunan Teh menjadi Perkebunan Kelapa Sawit. Skripsi karya Choirul Syahmora Hasibuan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2013, Analisis Konversi Lahan Karet ke Kelapa Sawit di Desa Sabungan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berisi hasil produksi kelapa sawit lebih besar dibandingkan dengan hasil produksi karet. Pemasaran kelapa sawit juga lebih mudah dilakukan daripada pemasaran getah karet karena pabrik kelapa sawit lebih banyak jumlahnya dan relatif dekat jaraknya. Skripsi karya R. Nice Marpaung, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2012, Dampak Konversi Hutan Mangrove Menjadi Kebun Kelapa Sawit terhadap Lingkungan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat yang berisi konversi hutan mangrove menjadi kelapa sawit di Kecamatan Brandan Barat telah membawa dampak terhadap lingkungan fisik yaitu penyusutan luasan hutan mangrove, frekuensi banjir semakin sering terjadi setiap air pasang dan menghilangkan habitat binatang yang berada di sekitar hutan mangrove Kecamatan Brandan Barat. 8 Penelitian ini difokuskan pada konversi tanaman perkebunan teh menjadi kelapa sawit ditinjau dari etika lingkungan, maka penulis menyatakan bahwa penelitian ini benar-benar asli dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Bagi ilmu pengetahuan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam perihal pelestarian lingkungan terutama kelestarian ekosistem perkebunan. Kontribusi positif diupayakan mampu menarik minat dari berbagai ilmu tentang lingkungan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit sehingga menambah pengetahuan di bidang pelestarian ekosistem perkebunan. b. Bagi filsafat Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur dan kajian filsafat di bidang lingkungan khususnya etika lingkungan. Etika bukan hanya kajian teoritis, tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan. c. Bagi bangsa Indonesia Penelitian ini diharapkan berguna bagi bangsa Indonesia dalam pengkajian kelestarian alam dan lingkungan, terutama pada perkebunan serta sebagai salah satu acuan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pelestarian alam dan lingkungan. 9 B. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Merumuskan secara deskriptif alasan dilakukannya konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di PTPN IV Marjandi. 2. Merumuskan dampak yang ditimbulkan dari konversi tanaman perkebunan ke kelapa sawit di PTPN IV Marjandi. 3. Merumuskan secara analitis relevansi pemikiran etika lingkungan Ekosentrisme terhadap konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit. C. Tinjauan Pustaka Tanaman teh berasal dari iklim sub tropis, maka cocok ditanam di daerah pegunungan. Garis besar syarat tumbuh untuk tanaman teh adalah kecocokan iklim dan tanah. Faktor iklim yang harus diperhatikan seperti suhu udara yang baik antara 13 – 15oC, kelembaban relatif pada siang hari > 70%, curah hujan tahunan tidak kurang dari 2.000 mm, dengan bulan penanaman curah hujan tidak kurang dari 60 mm tidak lebih 2 bulan. Penyinaran sinar matahari juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh, makin banyak sinar matahari makin tinggi suhu, bila suhu mencapai 30oC pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Pada ketinggian 400 – 800 m tanaman teh memerlukan pohon pelindung tetap atau sementara, disamping itu perlu mulsa sekitar 20 ton/ha untuk menurunkan suhu tanah. Hal ini dikarenakan suhu tanah yang tinggi dapat merusak perakaran tanaman, terutama akar di bagian atas.(Syakir, 2000: 1) 10 Tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman teh adalah tanah yang serasi. Tanah yang serasi adalah tanah yang subur, banyak mengandung bahan organik dan tanah memiliki derajat keasaman 4,5 – 5,6. Tanah yang baik untuk pertanaman teh terletak di lereng-lereng gunung berapi, yang dinamakan tanah Andisol. Tanah andisol adalah tanah yang berasal dari abu gunung api (Syakir, 2000: 2). Elevasi (ketinggian suatu tempat di atas permukaan laut) tidak menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan tanaman teh jika iklim dan tanah serasi bagi pertanaman teh. Elevasi dan unsur iklim (suhu udara) memiliki kaitan, semakin rendah elevasi pertanaman, suhu udara akan semakin tinggi. Mengantisipasi suhu udara yang semakin tinggi pada daerah renda diperlukan pohon pelindung untuk mempengaruhi suhu udara agar menjadi lebih rendah sehingga tanaman teh tumbuh baik. Keserasian elevasi di Indonesia terbagi atas 3 daerah, yaitu : daerah rendah (<800 mdpl), daerah sedang (800-1.200 mdpl), daerah tinggi (>1.200 mdpl). Perkebunan teh di Indonesia terdapat pada keserasian elevasi cukup luas, berkisar 400-2000 mdpl. Pengaruh suhu udara berpengaruh bagi pertumbuhan teh sehingga mutu yang dihasilkan tergantung dari tempat teh di tanam. Aroma yang dihasilkan teh di dataran tinggi lebih baik daripada teh yang ditanam di dataran rendah (Syakir, 2000: 2-3). Konversi adalah adanya perubahan, pengubahan, penukaran penggunaan lahan. Wahyunto dalam Purba (Jan Purba, 2009: 37), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan 11 penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan lebih disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Mc Neill dalam Purba (Jan Purba, 2009: 37) menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Selain itu teknologi juga berperan dalam menggeser fungsi lahan. Jenis-jenis tanah yang dapat dijadikan lahan perkebunan dan cocok untuk budidaya kelapa sawit adalah yang berlokasi pada ketinggian sampai 500 m di atas permukaan laut. Lahan yang tingginya lebih dari 500 m dari permukaan laut akan mengakibatkan gejala-gejala permulaan dari pengaruh iklim yang dingin daripada yang letaknya lebih rendah. Tanaman sawit akan lambat tumbuhnya, seperti halnya dengan tanaman karet atau tanaman industri lainnya. Pohon-pohon akan berproduksi setahun lebih lambat, meskipun seterusnya pertumbuhannya akan cukup memuaskan. Produksi yang berasal dari tanaman muda pada dasarnya setiap tahun akan bertambah. Apabila dibandingkan dengan pertanaman yang ditanam pada saat yang bersamaan, tetapi ketinggiannya lebih rendah, maka akan menderita kerugian produksi yang kurang lebih sesuai dengan tambahan luas setiap tahun. Kerugian ini dapat menyebabkan kurang baiknya rentabilitas 12 perusahaan. Jadi sedapat mungkin disarankan agar jangan menanam kelapa sawit pada ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut (Heurn, 1985: 25-27). Areal perkebunan sawit di Sumatera pada tahun 2005 mencapai 4.280.094 ha atau 76,46% dari total areal perkebunan kelapa sawit nasional. Provinsi Riau tercatat memiliki areal terbesar yaitu 1.383.477 ha diikuti provinsi Sumatera Utara seluas 964.257 ha (ICN, 2009a). Data dari PTPN IV (2009) menyebutkan luas lahan sawit di Sumatera Utara adalah 1,9 juta ha dengan rincian satu juta ha perkebunan rakyat, 500 ribu ha PBN dan 400 ribu ha dikelola oleh PTPN, sementara luas areal di propinsi Riau adalah 1.611.361 ha (BPS Provinsi Riau, 2008). Sumatera Utara sendiri meski memiliki perkebunan sawit cukup luas, namun hanya bisa menghasilkan CPO, sehingga yang mendapatkan nilai tambah justru daerah lain, sementara propinsi ini sendiri sering kekurangan minyak sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat setiap hari (ICN, 2009b). Bisnis atau usaha yang bergerak di bidang apapun pastinya mengusahakan profit/keuntungan yang berkesinambungan. Mengacu pada dasar tersebut dan melemahnya harga teh di pasaran PTPN IV mentransformasi komoditi teh menjadi komoditi kelapa sawit di dataran tinggi. Tindakan ini didukung dengan kenaikan suhu global yang terjadi dengan peningkatan temperatur udara minimum tahunan menjadi ≥ 18 ºC setelah tahun 1990 pada ketinggian 850 m dpl. Marjandi dan Bah Birung Ulu (sebagai pilot Project) merupakan dua Unit Usaha yang mengalami transformsi bisnis dari komoditi teh menjadi kelapa sawit secara menyeluruh dengan tahapan-tahapan. (Makalah Transformasi Bisnis Teh Menjadi Kelapa Sawit, 2011: 1). 13 D. Landasan Teori Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat istiadat atau kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke genarasi berikutnya. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan menjadi kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan kepada masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Kaidah inilah yang menentukan apa yang baik yang harus dilakukan dalam kehidupan, dan hal yang buruk harus dihindari. Etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baikburuknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari (Keraf, 2002: 2-3). Etika bila dilihat secara historisnya merupakan usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Hal ini dikarenakan pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak dipercayai lagi (Suseno, 1987: 15). Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berpikir. Apabila pikiran-pikirannya berjalan begitu saja karena asosiasi tanpa pengarahan dan pengontrolan yang sadar, maka pikiran-pikiran manusia itu hanyalah menjadi perbuatan manusia bukannya perbuatan manusiawi, meskipun perbuatan-perbuatan ini perbuatan-perbuatan dari tata susunan rasional 14 (Poespoporodjo, 1999: 85). Manusia akan kekurangan panduan dan arahan dalam menangani masalah-masalah tanpa adanya suatu jenis etika dan teori-nilai, baik itu masalah yang bersifat global, lingkungan maupun sebaliknya (Attfield, 2010:29). Etika dapat digolongkan atas 3: etika deontologi, etika teleologi, etika keutamaan. Etika deontologi yang berasal dari kata Yunani deon, yang berarti kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Etika deontologi menilai baik atau buruk suatu tindakan berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban etika. Etika teleologi berasal dari kata Yunani telos, yang berarti tujuan, dan logos berarti ilmu atau teori. Etika teleologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Etika teleologi melihat baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Etika keutamaan (virtue ethics) tidak mempermasalahkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang (Keraf, 2010: 36-37). Etika lingkungan hidup menginginkan adanya perluasan cara pandang dan perilaku moral manusia dengan memasukkan keseluruhan alam semesta ke dalam komunitas moral. Etika lingkungan hidup menuntut etika dan moralitas diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau ekologis. Etika lingkungan hidup dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan nilai-nilai moral yang selama ini hanya untuk komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas bagi 15 komunitas biotis atau komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup berkaitan dengan pola perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup berkaitan dengan semua relasi antara kehidupan alam semesta, yaitu relasi antara manusia dengan manusia yang berdampak pada alam dan relasi antara manusia dengan makhluk hidup lain maupun dengan alam secara keseluruhan. Etika lingkungan hidup juga berkaitan dengan berbagai kebijakan politik dan ekonomi yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap alam (Keraf, 2010: 41). Etika lingkungan merupakan landasan rasional bagi tuntutan akan perlindungan lingkungan akan masalah ekologis. Etika lingkungan menetapkan dan menjelaskan norma-norma atau kaidah-kaidah bagi sikap maupun pola perilaku manusia yang tepat berhadapan dengan lingkungannya. Etika lingkungan juga menginginkan ketetapan-ketetapan norma-norma material konkret terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh ilmu alam dan ilmu sosial bagaimana cara ekosistem berfungsi, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam ekosistem akibat dari proses-proses sosial dan ekonomi (Glaeser, 1989:135-137). Etika lingkungan sangat diperlukan manusia dalam menghadapi persoalan lingkungan atau alam, terutama yang berkaitan dengan penataan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan makhluk hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha yang dilakukan manusia secara sadar untuk memelihara dan memperbaiki mutu lingkungan hidup agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaikbaiknya. Mutu lingkungan hidup yang baik diperoleh dengan cara memperbesar 16 manfaat lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan hidup (Soemarwoto, 2004: 76-77). Ekosentrisme sebagai bagian dari teori-teori etika lingkungan hidup mencoba mendobrak cara pandang antroposentrisme yang memusatkan etika hanya pada manusia. Ekosentrisme memusatkan perhatiannya pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Makhluk hidup dan bendabenda abiotis lainnya saling berkaitan satu sama lain. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis (Keraf, 2010: 92-93). Deep Ecology sebagai salah satu versi teori Ekosentrisme menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Deep Ecology tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kepentingan jangka pendek, tetapi jangka panjang. Prinsip moral yang dikembangkan oleh Deep Ecology menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis (Keraf, 2010: 93). Deep Ecology dirancang sebagai etika praktis yang berupa sebuah gerakan. Gerakan oleh Deep Ecology berlandaskan prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Deep Ecology dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan diantara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama, mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam, dan sama-sama memperjuangkan isu lingkungan hidup dan politik (Keraf, 2010: 94). 17 E. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana penelitian dilakukan dengan mengandalkan berbagai literatur yang ada, baik itu berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan laporan penelitian. 1. Bahan atau Materi Penelitian a. Pustaka Primer 1) Buku Kelapa Sawit karya J. D. Heurn tahun 1985 2) Buku Pembudidayaan dan Pengolahan Teh karya Nazaruddin Paimin dan Farry. B tahun 1993 3) Buku Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan karya Sunarko tahun 2010 4) Buku Budi Daya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan karya Sunarko tahun 2014 5) Jurnal Standar Prosedur Operasi (SPO) Bidang Tanaman/Pabrik Kelapa Sawit, Tanaman/Pabrik Teh, PPIS dan Pabrik Kompos Organik RKAP Tahun 2008 tahun 2007 6) Jurnal Transformasi Bisnis Teh Menjadi Kelapa Sawit Oleh PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) tahun 2011 b. Pustaka Sekunder 1) Buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat karya Dr. Sunyoto Usman tahun 1998 2) Buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan karya N. H. T. Siahaan tahun 2004 18 3) Buku Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem, Komunitas, dan Lingkungan karya Zoer’aini tahun 2007 4) Buku Etika Lingkungan Hidup karya A. Sonny Keraf tahun 2010 5) Buku Etika Lingkungan Global karya Robin Attfield tahun 2010 Selain buku-buku yang dicantumkan tersebut, pustaka sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui naskah akademik yang diterbitkan dalam buku, artikel maupun jurnal, yang aksesnya diperoleh melalui internet. Data tersebut kemudian dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan kajian konversi lahan perkebunan teh ke kelapa sawit dalam perspektif etika lingkungan. 2. Jalan Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. Mengumpulkan data yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa buku, artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji, yaitu konversi lahan perkebunan teh ke kelapa sawit di Kabupaten Simalungun. b. Klasifikasi data yang telah diperoleh untuk dikelompokkan sebagai data primer dan data sekunder. c. Melakukan analisis data primer dan data sekunder serta data penunjang lainnya. d. Melakukan analisis hasil dalam bentuk evaluasi kritis. 19 3. Analisis Hasil a. Deskripsi, penulis mencoba mengungkapkan dan memaparkan data yang diperoleh, yang ditulis secara menyeluruh dari berbagai aspek sehingga memberikan jawaban atas sebuah masalah. b. Verstehen, penulis berupaya untuk memahami konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit Marjandi. c. Interpretasi, penulismengungkapkan fakta yang berasal dari konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di Marjandi. d. Hermeneutika, penulis berusaha menangkap makna esensial dengan melakukan penafsiran terhadap konversitanaman perkebunan teh kelapa sawit di Marjandi. e. Heuristik, penulis berusaha menemukan pemahaman baru atau cara pandang baru, kemudian memberikan evaluasi kritis pada konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di Marjandi. F. Hasil yang Telah Dicapai Penelitian ini telah mencapai beberapa hasil sebagai berikut: 1. Memperoleh penjelasan deskriptif tentang alasan konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di PTPN IV Marjandi. 2. Memperoleh penjelasan deskriptif dari pokok pemikiran etika lingkungan Ekosentrisme. 3. Memperoleh penjelasan deskriptif mengenai dampak konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit menurut etika lingkungan Ekosentrisme. 20 4. Mendapat penjelasan mengenai relevansi pemikiran etika lingkungan Ekosentrisme terhadap upaya berkelanjutan menanggapi dampak dari konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit. G. Sistematika Penulisan Bab I: berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, manfaat, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil yang akan dicapai, dan sistematika penulisan. Bab II: berisi tentang pembahasan mengenai sejarah perkebunan teh, sejarah perkebunan kelapa sawit, dan pengertian konversi lahan. Bab ini mendeskripsikan sejarah perkebunan teh hingga dikonversi ke kelapa sawit serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar PTPN IV Marjandi di Kabupaten Simalungun. Bab III: berisi tentang uraian tentang ruang lingkup etika, pengertian lingkungan hidup, pengertian etika lingkungan hidup, teori-teori etika lingkungan, dan prinsip-prinsip etika lingkungan. Bab IV: berisi tentang analisis mengenai konversi tanaman perkebunan teh ke kelapa sawit di PTPN IV Marjandi ditinjau dari segi etika lingkungan Ekosentrisme. Bab V: berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.