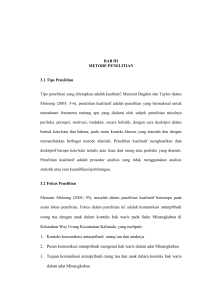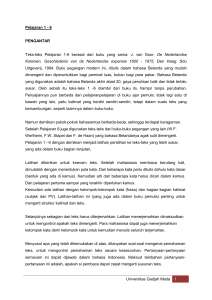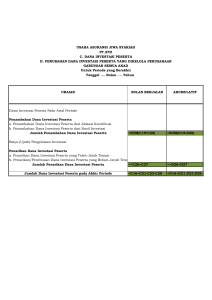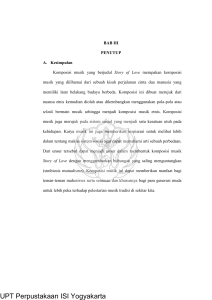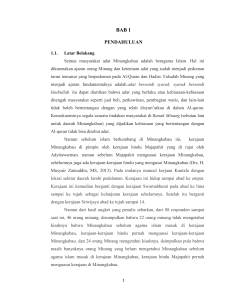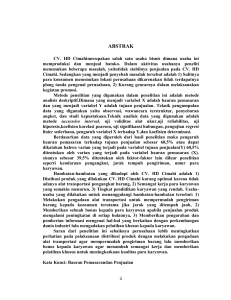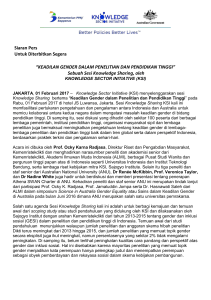TRADISI LISAN DALAM PERSPEKTIF KAJIAN
advertisement

TRADISI LISAN DALAM PERSPEKTIF KAJIAN AGAMA1 Suryadi Leiden University, Belanda Bapak Rektor Insitut Hindu Dharma Negeri Denpasar, Prof. Dr. I Made Titib, Bapak-bapak dan Ibu-Ibu para dosen, serta Saudara-saudara mahasiswa sekalian yang saya hormati, Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapat undangan untuk menyampaikan kuliah umum di hadapan hadirin sekalian pada hari ini. Dalam kesempatan pertemuan di Leiden pada akhir Juni lalu, Prof. Dr. I Nengah Duija, teman akrab saya sejak kami sama-sama mengabdi di Universitas Indonesia tahun 1990-an sampai kini, meminta kesediaan saya untuk memberikan kuliah umum ini, setelah beliau mengetahui bahwa saya dan keluarga akan berlibur ke Indonesia selama enam minggu, dari 29 Juni sampai 11 Agustus 2011. Rasanya sulit untuk menolak permintaan seorang sahabat baik yang telah sama-sama merasakan kerasnya rimba metropolitan Jakarta pada tahun 1990-an, meskipun kepulangan saya ke Indonesia kali ini direncanakan untuk membawa keluarga berlibur dan mengunjungi sanak famili di Sumatra Barat. Sesuai dengan arahan Prof. Dr. I Nengah Duija, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang TRADISI LISAN DALAM PERSPEKTIF KAJIAN AGAMA. Topik ini cukup penting mengingat bahwa tradisi lisan–termasuk bagian darinya yaitu sastra lisan: verbal art yang fungsi utamanya adalah untuk menghibur–dan agama memang merupakan dua aspek yang kerap bersinggungan dalam berbagai kebudayaan lokal di Indonesia. Dalam pembicaraan ini saya mungkin akan banyak mengambil contoh tradisi lisan dari lingkup budaya Minangkabau, bidang yang memang lebih menjadi fokus penelitian saya selama ini. Namun demikian, kita tentu dapat mencari contoh-contoh yang sepadan yang hidup dalam budaya-budaya lainnya di Indonesia, termasuk budaya Bali sendiri. Sesungguhnya tidak sulit untuk mengidentifikasi dimensi agama dalam tradisi lisan yang hidup dalam berbagai suku bangsa di Indonesia. Bahkan aspek religiositas, baik yang menyangkut agama-agama tradisional maupun agama-gama samawi, adalah sesuatu yang 1 Ceramah yang disampaikan dalam Stadium General (Kuliah Umum) di Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Bali, 13 Juli 2011. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor IHDN, Prof. Dr. I Made Titib, yang telah memfasilitasi saya selama saya berada di Bali. inheren dalam pertunjukan berbagai genre tradisi lisan. Dalam tataran yang lebih sederhana, nuansa magis sering merupakan bagian dari pertunjukan tradisi lisan. Dalam pertunjukanpertunjukan tradisi lisan di berbagai daerah di Indonesia para penampil (performer) membakar kemenyan atau dupa serta merapalkan mantera-mantera tertentu sebelum memulai suatu pertunjukan. Di Minangkabau, sebagaimana dicatat oleh Nigel Philips, tukang suara tukang sijobang dianggap mempunyai daya magis yang dapat menarik hati wanita.2 Di Bali sering terjadi diskusi apakah pertunjukan-pertunjukan budaya tertentu yang terkait erat dengan agama, dan oleh karenanya mengandung nilai sakral, boleh dipertunjukkan untuk turis atau untuk tujuan komersil atau tidak. Bila kita melihat tradisi sarafal anam dan barzanji dalam acara Mawlid3 di wilayah Indonesia yang penduduknya beragama Islam, manakiban dan pangaosan Layang Seh4 di Sunda, selawat dulang5 di Minangkabau, pembacaan lontar Yusup6 di Banyuwangi – untuk menyebut sekedar contoh – semuanya adalah representasi dari aktifitas tradisi lisan yang berkait kelindan dengan agama. Kiranya tidak berlebihan jika saya katakan bahwa hampir setiap etnis yang hidup di Indonesia mempunyai aktifitas verbal art (taal kunst kata orang Belanda), baik yang murni lisan maupun yang didasarkan atas teks tertulis, yang fungsinya terkait dengan agama. Barangkali di antara kita ada yang pernah mendengar tentang Hikayat Perang Sabil yang terkenal di Aceh.7 Di zaman kolonial konon Hikayat Perang Sabil telah berfungsi sebagai pembakar semangat perang orang Aceh melawan Kompeni Belanda karena di dalamnya diyakini terkandung aspek religius yang berkaitan dengan jihad. Hikayat itu didendangkan oleh para pejuang Aceh sebelum mereka terjun ke medan pertempuran. Semangat mereka terbakar mendengarkan dendangan hikayat itu yang dilantunkan oleh para pedendang yang bersuara merdu, yang membuat para pejuang Aceh memperoleh suntikan semangat perang, 2 Nigel Phillips. Sijobang: Sung narrative poetry of West Sumatra. Cambridge: Cambridge University Press (1981). 3 Lihat misalnya: Nico Kaptein, ‘The berdiri Mawlid issue among the Indonesian Muslims in the period from circa 1875-1930’, Bijdragen to de Taal-, Land- en Volkenkunde 49.1 (1993), hlm. 124-53. 4 Lihat: Julian Millie, Splashed by the saint: ritual reading and Islamic sanctity in West Java. Leiden: KITLV Press, 2009. 5 Lihat misalnya: Adriyetti Amir, “Salawat Dulang: sastra berangka yang dihapalkan”, Warta ATL no.2 (Juli 1996), hlm. 5-24; Bahar, Mahdi Bahar, “Pertunjukan Salawat Talam untuk membangun mesjid”, Seni v/02-03 (1997), hlm. 225-34. 6 Lihat misalnya: Bernard Arps, ‘Singing the life of Joseph: an all-night reading of the Lontar Yusup in Banyuwangi, East Java’, Indonesia Circle 53 (1990), hlm. 34-58. 7 Lihat misalnya, Tengku Pante Kulu, Hikajat Perang Sabil di Atjeh. Djakarta: Balai Pustaka (1958); Ibrahim Alfian, Satra perang: sebuah pembicaraan mengenai Hikayat Perang Sabil. Jakarta: Balai Pustaka (1992). suatu ‘efek candu’ dari teks sastra yang telah sering dibicarakan dalam teori-teori mengenai psikologi sastra. Entah karena suara magis tukang hikayat, entah karena aspek estetika teks Hikayat Perang Sabil sendiri, para pejuang Aceh maju tak gentar pergi ke medan perang melawan ‘kape” Belanda (kafir Belanda) dengan semangat berani mati setelah mendengarkan hikayat itu. Dalam catatan sejarah mengenai Perang Aceh seorang Belanda bernama Henri Carel Zentgraaff menggambarkan keberanian orang Aceh di medan perang. 8 Dia mengatakan apabila orang Aceh sudah menyerang, lebih-lebih setelah mendapat semangat dari para penyair lisannya, maka mereka, termasuk para perempuannya, akan malu pulang dengan kelewang dan rencong tanpa mencicipi darah musuh. Satu tetakan kelewang dan tusukan rencong para pejuang Aceh di tubuh musuh cukup untuk membuat mereka meregang nyawa. Studi Julian Millie, Splashed by the saint: ritual reading and Islamic sanctity in West Java (2009) dengan menarik menggambarkan kegiatan manakiban dan pangaosan Layang Seh dalam masyarakat Sunda. Kegiatan ini adalah resitasi beberapa teks yang berhubungan dengan pemujaan kepada arwah ulama sufi Syekh Abdul Kadir al-Jaelani di kalangan para pengikut tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di daerah Bandung dan sekitarnya. Orang Sunda menyebut kegiatan yang bernuansa keagamaan ini sebagai membaca karamat. Pertanyaan kunci yang diajukan Millie adalah: “What can the ritual reading and recitation of saintly narratives [based on written texts] tell us about Islamic sanctity and the place it occupies in the wider Islamic society?”9 Millie membahas teks, konteks, serta pelaku aktifitas ritual ini dalam komunitas penutur Bahasa Sunda. Apa yang hendak saya katakan adalah bahwa tradisi lisan sudah inheren dalam praktek keagamaan dari agama apapun di Indonesia. Malah sering ditemukan para tukang cerita (storyteller) memegang peran religius tertentu dalam masyarakatnya. Sejak zaman kolonial para sarjana Eropa, khususnya Belanda, sudah tertarik melihat fenomena ini. Di daerahdaerah yang beragama Islam, misalnya, tradisi ratib atau pendendangan kisah-kisah Nabi membuat para penguasa kolonial was-was karena dianggap bisa meletuskan radikalisme. Jika kira menengok ke Pulau Bali, tidaklah sulit benar mencari contoh aktifitas-aktifitas seni lisan (verbal art) yang merepresentasikan kait kelindan antara tradisi lisan dan agama (religi), lantaran masyarakat Bali sendiri memang terkenal sebagai masyarakat yang religius dan 8 9 H.C. Zentgraaff, Atjeh. Batavia: De Unie [1938]. Julian Millie, Splashed by the saint, hlm. 16. mempunyai kosmologi khas (inimitable) yang mempengaruhi tindak laku sosial mereka sehari-hari. Salah satu contoh yang sangat jelas adalah kegiatan mesanti. Pun dalam tradisi mabebasan kelihatan bahwa unsur-unsur keagamaan itu tetap ada karena religiositas masyarakat Bali bersandar pada kitab-kitab sastra lokalnya, seperti kakawin dan naskahnaskah klasik lainnya, di mana mabebasan menduduki peran sentral dalam pewarisan nilai dan spiritualitas sebagaimana yang terekam dan terwariskan dalam kakawin dan geguritan.10 Apabila dalam konteks pembicaraan ini kita coba meluaskan pengertian agama dari tidak hanya sekedar agama samawi (Islam, Hindu, Budha, Kristen), maka kita akan menemukan bahwa unsur religiositas selalu dapat dijumpai dalam pertunjukan tradisi lisan. Dalam agama apa saja dapat dikesan bahwa suara, baik dalam rupa resitasi, pendendangan, dan lain sebagainya, adalah unsur yang penting. Dalam berbagai komunitas tribes sering kita jumpai nyanyian-nyanyian dan dendangan-dendangan lisan yang berfungsi magis. Para bomoh di kalangan masyarakat asli Melayu atau sikerei di Mentawai menguasai mantera-mantera tertentu untuk mengobati penyakit, yang membuat mereka menduduki posisi sosial yang tinggi dalam komunitasnya. Dalam konteks agam Islam, contoh yang paling jelas mengenai hubungan suara dan agama adalah panggilan adzan. Studi-studi antropologis menunjukkan bahwa banyak pertunjukan tradisi lisan terkait dengan pemujaan kepada para leluhur dan dewa-dewa di mana suara magis sering memainkan peranan yang tak tampak. Salah satu contoh adalah upacara Kwangkay dalam masyarakat Dayak Benuaq di pedalaman Kalimantan Timur.11 Dalam upacara itu, yang berlangsung sampai 20 hari, teks-teks lisan yang panjang didendangkan oleh para tukang cerita untuk mengiringi arwah-arwah anggota keluarga yang meninggal agar mereka berbahagia di sorga abadi di Gunung Lumut. Begitu juga dengan Syair Lawe’ dalam masyarakat Dayak Kayan di Kalimantan. 12 Lihat misalnya, Nengah Madera, Kakawin dan mabebasan di Bali. Denpasar: Upada Sastra (1997); I Made Tjendra, Geguritan: sebuah bentuk sastra yang mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat Bali. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional (1973). 11 Lihat: Suryadi, “Tradisi lisan dalam upacara Kwangkay: puncak upacara kematian suku Dayak Benuaq”, Kalimantan Review, 5 (1996), hlm. 3-6. 12 Lihat: S. Lii’Long (tukang cerita). Syair Lawe’ (disunting dan diterjemahkan oleh A.J. Ding Ngo). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984. 10 Demikian pula umpamanya, dalam berbagai komunitas etnis di Indonesia dikenal mantera, suatu bentuk ekspresi lisan yang terkait dengan berbagai bentuk kepercayaan lokal (bijgeloof).13 Kepercayaan adalah unsur kebudayaan manusia yang sama pentingnya dengan unsur-unsur kebudayaan lain yang berwujud kebendaan (fisik). Kepercayaan sekaligus menyangkut aspek psikologis (pribadi) dan sosiologis (masyarakat): satu kelompok etnis dicirikan bukan oleh penampilan fisik saja, tetapi juga karena unsur kepercayaan yang mereka anut, di mana aktifitas tradisi lisan sering memainkan peran penting. Kepercayaan sebagai unsur kebudayaan manusia sudah lama menarik perhatian dunia ilmu, khsususnya antropologi atau cabangnya: etnografi. Para pakar di bidang ini selalu tertarik kepada eksepresi-ekpresi kultural yang bersifat lisan dalam pelbagai kebudayaan lokal karena ekspresi-ekspresi tersebut adalah suatu laman (site) atau teks budaya (cultural text) yang dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep kosmologis dan religiositas masyarakat pendukungnya. Dalam perspektif ini kepercayaan memiliki makna yang agak khusus, yaitu semacam local beliefs, yang bisa dibedakan dengan agama samawi (seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha). Berbeda dengan agama yang lebih bersifat lintas etnis, lintas bangsa, dan lintas ras, kepercayaan lebih bersifat lokal saja, yang bervariasi atau malah berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Kepercayaan itu termanifestasi dalam berbagai hal, misalnya percaya kepada kekuatan gaib (zielestof), takhyul (bijgeloof), percaya pada benda atau binatang yang dianggap bertuah atau yang menimbulkan celaka, percaya kepada, tempat-tempat keramat, percaya kepada dukun, praktek guna-guna, dan lain sebagainya. Ada dua unsur yang terkait dengan kepercayaan tradisional: 1) benda (medium) tertentu seperti jimat, batu, dll.; 2) mantera (teks lisan). Kepercayaan adalah unsur yang membentuk sistem religi suatu kelompok masyarakat. Menurut Kuntjaraningrat sistem religi ini merupakan salah satu dari tujuh unsur yang selalu ada dalam suatu kebudayaan; enam unsur lainnya adalah: bahasa, sistem pengetahuan, 13 Untuk konteks dunia Melayu di bagian barat Nusantara, lihat misalnya M.T. Soetan Lémbang ‘Alam, Berbagai-bagai kepertjajaan orang Melajoe [4 Jilid]. Weltevreden: Balai Poestaka (1920); Haron Daud, Mantera Melayu: analisis pemikiran. Pulau Piang: Universiti Sains Malaysia Press (2001). organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, dan kesenian.14 Dalam Bahasa Indonesia ada istilah kebudayaan tradisional atau kebudayaan daerah yang menjadi isu penting di tengah maraknya wacana globalisasi di masa sekarang. Dalam kebudayaan tradisional sebenarnya tercakup juga unsur kepercayaan tadi, yang disebut kepercayaan tradisional. Istilah “tradisional” memberi indikasi bahwa ia warisan masa lalu yang agak berada di luar lingkup agama-agama resmi negara, yang mungkin masih diamalkan pada masa sekarang. Walaupun banyak etnis di Indonesia sudah menganut agama-agama samawi, namun kadangkala praktek keagamaan masyarakat masih tetap diwarnai oleh kepercayaankepercayaan lokal. Seorang sarjana Belanda yang bernama G.A. Wilken15 menunjukkan bahwa tiap-tiap kelompok masyarakat di kepulauan Nusantara memiliki nama-nama tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap makhluk halus dan kekuatan supranatural. Orang Melayu, misalnya, sangat percaya pada keefektifan mantera untuk mengobati penyakit dan untuk ilmu guna-guna atau, sebaliknya, untuk menangkal setan agar jangan masuk ke dalam tubuh manusia. Kepercayaan tradisional adalah unsur kebudayaan yang bisa berubah dan aus. Penyebabnya adalah bahwa kepercayaan tradisional terikat dengan basis materialnya, yaitu lingkungan alam tempat tinggal: jika basis material itu berubah atau hilang, maka kepercayaan tradisional ikut berubah. Banyak jenis kepercayaan tradisional hilang begitu saja seiring dengan perputaran zaman tanpa sempat terdokumentasikan. Jika satu generasi hilang, maka itu berarti sejumlah kepercayaan tradisional mungkin juga ikut lenyap. Untunglah di zaman kolonial beberapa administrator Belanda yang bekerja di daerah-daerah tertentu di Hindia Belanda mencatat beberapa kepercayaan tradisonal masyarakat setempat. Terdapat juga banyak salinan genregenre tradisi lisan yang dibuat oleh para sarjana Belanda di zaman kolonial. Bahan-bahan itu saya kira amat penting untuk melihat transformasi religiositas satu kelompok masyarakat. 14 Koentjaraningrat, Pengantar ilmu Antropologi. Jakarta: PT. Rineka Cipta (1990), hlm. 204-305. Lihat: G.A. Wilken, “Het animisme bij de volken van den Indische Archipel”, De Indische Gids 6(I) (1888), hlm. 925-1000; G.A. Wilken, “Het animisme bij de volken van den Indische Archipel”, De Indische Gids, 7(I) (1889), hlm. 13-58, 191-242. 15 Banyak genre tradisi lisan yang dapat ditemukan dalam bahasa lokal yang berbeda-beda di Indonesia, merepresentasikan apa yang disebut sebagai fetisisme dan spiritisme yang jelas berkaitan dengan kepercayaan tradisional. Demikianlah umpamanya, dalam konteks kebudayaan Minangkabau, J.L. van der Toorn menyebutkan bahwa orang Minang menyebut kedua unsur ini sebagai nyao (nyawa) dan sumangaik (semangat). Kedua unsur itu dipercayai ada dalam masing-masing tubuh manusia, tapi sumangaik bisa dikeluar-masukkan dari tubuh manusia dengan bantuan kekuatan supranatural. Ini dipraktekkan secara luas dalam banyak aktifitas magis (ilmu hitam dan putih) seperti dalam tradisi manggasiang, manggayuang orang, dan aktifitas pedukunan lainnya. Demikianlah umpamanya, dalam tradisi “manggasieng”, Van der Toorn mencatat: Dat de soemangat het lichaam kan verlaten en daarin terugkeeren, is een opvatting, waarop het zoogenaamde manggasieng berust, en tooverij, die vaak wordt toepast door wraakzuchtige minnars. Deze namelijk hebben de overtuiging, dat zij door die tooverij de hulp kunnen erlangen van booze geesten, om de soemangat weg te voeren van de vrouw, die hen afwees, en haar zoodoende in een toestand van razernij te brengen, die bekend is onder de naam van Si Djoendai en veelvuldig onder de vrouwen in de Padangsche Bovenlanden wordt aangetroffen. Voor dat doel zoekt hij in ’t bezit tekomen van het voorhoofsbeen, tangkoera’, van een gestroven oerang barani of oerang barélémoe, en van eenige hoofdharen zijns slachtoffers. Aan dat been geeft hij den vorm van een schijf; hij windt er de haren om heen en boort er een paar gaten in, zoodat het werktuigje door het heen en weer trekken aan een koord, dat door de openingen gebracht is, een snorred geluid voortbrengt. Met deze gasieng, waarover een tooverspreuk wordt uitgesproken, begeeft hij zich, gewoonlijk des avonds, naar de eene of andere heilige plaats in het bosch, waar hij, aan het koord trekkende, voor zijn doel de hulp de geesten inroept. Is zijn toeleg gelukt, dan begint de vrouw te lijden aan vlagen van kranzinnigheid, die zich in zulk eene woestheid openbaren, dat zij gillend overal tegen opklimt en de kleederen zich van het lichaam rukt of stuk scheurt, daarbij onophoudelijk den naam van haren minnar uitroepende. Het eenige middel om dezen toestand te doen ophouden, is dan een der bloedverwanten van de betooverde, insgelijks door toedoen van het manggasieng, de booze geesten terugdrijft of hen overhaalt, de soemangat van den belager eveneens te kwellen. De Si Djoendai Paka’ is en dergelijke ziekte, die echter niet door het manggasieng ontstaat, maar door het eten van allerlei vuiligheid, die de algewezen minnar de vrouw heeft weten te bereiden (Van der Toorn 1890:55-6). Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut: Kemampuan soemangat untuk keluar masuk tubuh merupakan dasar kepercayaan manggasieng, semacam guna-guna yang sering diterapkan orang yang jatuh cinta yang ingin membalas dendam. Orang ini percaya bahwa dengan guna-guna tersebut, mereka bisa mendapat bantuan dari roh-roh jahat untuk mengambil soemangat itu dari badan si wanita yang menolak cintanya sehingga wanita itu menjadi gila. Keadaan gila itu dikenal dengan nama Si Jundai dan sering ditemukan di antara wanita di daerah Padang darat. Untuk tujuan tersebut, si laki-laki coba memperoleh tengkorak dari mayat orang berani [pendekar] dan orang berilmu [hitam] dan beberapa rambut kepala korban [wanita] yang menjadi sasarannya. Tengkorak itu dibentuk menjadi bundar; rambut-rambut diikat pada tulangnya dan kemudian dilubangi beberapa buah sehingga alat itu menghasilkan bunyi mendengung ketika tali yang dimasukkan ke dalam lobang-lobang itu ditarik. Dengan gasieng ini, yang juga disihirkan dengan mantera-mantera tertentu, si laki-laki pergi ke suatu tempat yang angker dalam hutan, biasanya pada malam hari. Di tempat itu diminta bantuan dari roh-roh jahat dengan cara menarik tali gasieng. Apabila berhasil, si wanita mulai gila dan memanjati barang apa saja dan merobek pakaiannya sambil berteriak dan tidak berhenti memanggil nama si laki-laki itu. Keadaan gila ini hanya bisa diakhiri kalau seorang saudara korban mengusir roh-roh jahat itu atau menyuruh mereka balik mengganggu soemangat si laki-laki itu, juga dengan cara manggasieng. Si Jundai Pakak adalah semacam penyakit yang tidak disebabkan oleh manggasieng, tapi merupakan akibat makan kotor-kotoran yang dihidangkan untuk si wanita oleh si laki-laki yang cintanya ditolak. Walaupun Van der Toorn kurang jelas menyebutkan tempatnya, besar kemungkinan tradisi “manggasieng” yang dimaksud terkait dengan kegiatan basirompak di Luhak 50 Kota (sekarang masuk wilayah administratif Kabuparen 50 Kota, Provinsi Sumatra Barat). Tetapi basirompak juga menggunakan instrumen musik saluang.16 Bunyi saluang dipercayai dapat mempengaruhi “soemangat” seorang wanita (oleh karenanya, kata Phillips, tukang sijobang banyak istrinya). Itulah mungkin yang menyebabkan mengapa alat musik tiup dilarang dalam Islam. Bunyi suara dari alat musik tiup dianggap dapat melenakan orang dan membawa ke kegairahan duniawi (ibarat ular kobra yang mendengar tiupan suara suling) dan oleh karenanya dapat menjauhkan dirinya dari kekhusyukan beragama. Van der Toorn juga mencatat beberapa mantera yang merefleksikan kepercayaan terhadap sumangaik itu, seperti mantera berikut ini: Babuah-buah si lakuik, babuah duo puluah, sumangaik lah kami japuik, badiri ka batang tubuah. Berbuah-buah si lakuik17, berbuah dua puluh, sumangaik sudah kami jemput, berdiri ke batang tubuh. Babuah-buah si lakuik, babuah sakampia baih, sumangaik lah kami japuik, badiri ka jari manih. Berbuah-buah si lakuik, berbuah sekampil baih18, sumangaik sudah kami jemput berdiri ke jari manis. Babuah-buah si lakuik, babuah sakampia pandan, sumangaik lah kami japuik, badiri ka induak tangan. Berbuah-buah si lakuik, berbuah sekampil pandan, sumangaik sudah kami jemput, berdiri ke empu jari tangan. Babuah-buah si lakuik, babuah sakampia padi, sumangaik lah kami japuik, Berbuah-buah si lakuik, berbuah sekampil padi, sumangaik sudah kami jemput, Lihat Marzam, Basirompak: sebuah transformasi aktivitas ritual magis menuju seni pertunjukan. Yogyakarta: Kepel Press (2002). 17 M. Thaib gl. St. Pamoentjak, Kamoes Bahasa Minangkabau – Bahasa Melajoe-Riau. Batavia: Balai Poestaka (1935), hlm. 129 menulisnya silakoei’, yang menurutnya adalah sejenis pohon. 18 ‘Baih’ yaitu “sebangsa kertjoet, dapat dibuat tikar dan soempit” (Pamoentjak, Kamoes Bahasa Minangkabau, hlm. 27). 16 badiri ka induak kaki. berdiri ke ibu jari kaki. Babuah-buah si lakuik, babuah duopuluah aso, Sumangaik lah kami japuik, badiri ka urang-urang mato.19 Berbuah-buah si lakuik, berbuah dua puluh satu, sumangaik sudah kami jemput, berdiri ke kornea mata. Kepercayaan kepada sumangaik juga dapat dikesan pada pengobatan penyakit tatagua (di tempat lain di Minangkabau disebut tasapo), yaitu penyakit yang diderita seseorang yang diyakini akibat ditegur atau disapa oleh makhluk halus ketika ia berada di sebuah tempat yang diangap angker. Dalam kasus seperti ini diyakini bahwa sumangaik si pasien (orang yang tatagua) dibawa oleh kekuatan supernatural yang menegurnya itu. Untuk memasukkannya kembali ke tubuh si pasien, diperlukan pertolongan dukun. Dalam proses pengobatan terhadap penderita tatagua, dukun mengucapkan mantera tertentu, seperti berikut ini. Sigulambai manggulambai, Tasangkuik di gulang-gulang, Antu setan antu manggemai, Anta sumangaik si Anu pulang.20 Sigulambai menggulambai, Tersangkut di gulang-gulang, Hantu setan hantu menggemai, Antarkan semangat si anu pulang. Pada akhir abad ke-19 Islam makin berkembang di Minangkabau, begitu juga dengan sekolah sekuler. Sebagian masyarakat Minangkabau mulai meninggalkan takhyul-takhyul akibat pencerahan yang dibawa oleh agama dan pendidikan Barat. Namun di desa-desa terjadi sinkretisme: unsur-unsur Islam ikut digunakan dalam praktek-praktek magis, sihir, dan pedukunan. Nama-nama makhluk halus dalam praktek-praktek magis, seperti hantu dan mambang, digantikan oleh nama-nama yang berbau Islam seperti jin, iblis, dan setan. Dalam mantera pekasih di bawah ini, misalnya, unsur Islam itu dapat dikesan: Iyo Allah, bukan aku marandang jajak si Anu, malainkan aku marandang hati jantuang si Anu, limpo si Anu, utak banak, urang-urang mato si Anu. Supayo nak bacinto kasiah sayang si Anu kapado aku. [Ya 19 J.L. van der Toorn, “Het Animisme bij de Minangkabauer der Padangsche Bovenlanden”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 39.1 (1890), hlm. 52-3. Ejaan disesuaikan. Dari mantera itu dapat dikesan bahwa sumangaik (semangat) diyakini dapat dikeluar-masukkan melalui bagian-bagian tubuh tertentu, seperti jari manis, ibu jari tangan, ibu jari kaki, dan kornea mata di mana yang terakhir ini sekarang sering menjadi sasaran para tukang pukau. 20 Lihat: “Een Wachtgelder” [alias J.L. van der Toorn]. 1892. “Over het Bijgeloof in Agam (Soematra)”, Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 7e deel, Nos. 1-6 (1892), hlm. 153. Ejaan disesuaikan. Van der Toorn menulis “Sigolameij” yang saya kira maksudnya sigulambai, sejenis hantu atau setan api yang bisa membakar rumah (lihat: Gérard Moussay. 1995. Dictionnaire Minangkabau--Indonesien--Français, (2 vols.). Paris: L’harmattan & Association Archipel, 1995, Vol 1:429). Ini mungkin berhubungan dengan kepercayaan dalam Islam yang menyebutkan bahwa setan terbuat dari api. Api yang terbang dari sebuah rumah ke rumah lain ketika terjadinya kebakaran besar disebut api sigulambai (M. Thaib gl. St. Pamoentjak, Kamoes Bahasa Minangkabau, hlm. 81). Kata “si Anu”pada baris keempat biasanya diisi dengan nama orang yang sakit (pasien). Allah, bukan aku merendang jejak si Anu, melainkan aku merendang hati jantung si Anu, limpa si Anu, otak benak, kornea mata si Anu. Supaya hendak bercinta kasih sayang si Anu kepada aku]. Dirandang Allah, Dirandang Muhammad, Dirandang Bagindo Rasulullah, 21 Berkat Laillaha illallah. Direndang Allah, Direndang Muhammad, Direndang Baginda Rasulullah, Berkat Lailah illallah. Demikian pula halnya seorang yang memakai ilmu pemanis, yang biasanya disertai dengan memakaikan minyak (parfum) tertentu ke tubuh. Mantera yang diucapkan juga berciri Islamis, seperti di bawah ini; Minyakku satabuang gayuang, Minyakku setabung gayung, Talatak di ateh pinggan, Terletak di atas pinggan, Duduakku seperti payuang, Dudukku seperti payung, Tagakku seperti bulan, Tegakku seperti bulan, Berkat aku mamakaikan minyak pamanih, maka manjilah aku dipandang si Anu. Berkat aku memakaikan minyak pemanis, maka menjadi bersih aku dipandang si Anu. Berkat Laillaha illallah.22 Berkat Laillaha illallah. Atau versi lainnya, seperti berikut ini: Paku tunduak paku banuah, Tamiang aku sorang mangalahkan, Anak si Anu lagi tak kan tunduak, Sadang gajah putiah di subarang lauiktan lagi tunduak lagi manyambah di bawah tapak ayangkih kaki aku, Aku malakatkan pamanih, Pamanih Allah pamanih Nabi Muhammad, Pamanih Bagindo Rasulullah, Berkat Laillaha illallah.23 Paku tunduk paku banuah, Temiang aku seorang yang mengalahkan, Anak si Anu lagi tak akan tunduk, Sedangkan gajah putih di seberang lautan lagi tunduk lagi menyembah di bawah telapak amang kaki aku, Aku melekatkan pemanis, Pemanis Allah pemanis Nabi Muhammad, Pemanis Baginda Rasulullah, Berkat Laillaha illallah. Di masa sekarang aktifitas-aktifitas magis yang menggunakan mantera-mantera jauh berkurang dalam masyarakat Indonesia. Modernisasi dan globalisasi yang juga melanda 21 “Een Wachtgelder” [alias J.L. van der Toorn], “Over her bijgeloof in Agam (Soematra)”, hlm. 160. Ejaan disesuaikan. Kata “si Anu” mengacu pada nama orang (perempuan/gadis) yang dimanterai. 22 “Een Wachtgelder” [alias J.L. van der Toorn], “Over her bijgeloof in Agam (Soematra)”, hlm. 161. Ejaan disesuaikan. Kata “si Anu” mengacu pada nama orang – bisa saja laki-laki, tapi biasanya sering ditujukan kepada perempuan – yang dimanterai. 23 “Een Wachtgelder” [alias J.L. van der Toorn], “Over her bijgeloof in Agam (Soematra)”, hlm. 161. Ejaan disesuaikan. Kata banuah pada baris pertama kurang jelas artinya. Sedangkan ayangkih (ajangkih) pada baris keenam tampaknya derivasi dari kata ajang yang menurut Pamoentjak, Kamoes Bahasa Minangkabau, hlm. 9 berarti “atjoe, amang; djan diajang-ajang andjieng tu – djangan diamang-amang andjing itoe, oemp.: dengan tongkat”. Kata-kata yang arkhais dan esoteris biasa ditemukan dalam teks mantera, yang sepertinya menguatkan sifat magis suatu mantera ketika diucapkan oleh pemakai yang meyakini kemangkusannya (lihat: Umar Junus, Junus, “Puisi yang mantra di Indonesia: suatu interpretasi”, dalam: Pemusuk Eneste (ed.), Dari peristiwa ke imajinasi: wajah sastra dan budaya Indonesia (kumpulan tulisan Umar Junus; Pengantar: Taufik Abdullah), hlm. 131-47. Jakarta: PT. Gramedia. (1983). Indonesia juga telah jauh mengurangi kepercayaan orang terhadap takhyul. Pergolakan dan reformasi agama serta penyebaran Islam dan pendidikan sekuler yang sudah berlangsung sejak abad ke-19 dan makin intensif pada masa-masa sesudahnya juga telah mengurangi kepercayaan masyarakat kepada magis dan takhyul. Makin banyak anggota masyarakat yang menilainya tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama, karena dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat. Akan tetapi kemudian muncul pula kepercayaan-kepercayaan tradisional yang bernuansa agama. Contohnya, dalam Islam lokal di banyak tempat di Indonesia muncul cerita-cerita lisan yang diwariskan turun temurun tentang kelebihan beberapa ulama setempat. Cerita mengenai orang saleh yang memiliki mukjizat dan kesaktian ditemukan di banyak di dunia Melayu, lebih-lebih semenjak seperempat terakhir abak ke-19, setelah Islam semakin terintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sinkretisme antara kepercayaankepercayaan lama dengan agama-agama baru, dalam hal ini Islam, dapat dilihat misalnya dalam “Tjoerito Nobi Kaidie” (Cerita Nabi Khaidir) yang dicatat oleh Walther Achiele di daerah Payakumbuh, Sumatra Barat.24 Nabi Khaidir dipercayai oleh orang Islam tetap hidup abadi. Dalam cerita itu dikisahkan bahwa Nabi Khaidir sering mendatangi mesjid ketika shalat Jumat, dan bila sempat bersalaman dengan beliau, permintaan bisa dikabulkan Tuhan. Bila ketahuan, Nabi Khaidir berusaha berubah wujud menjadi harimau, setan, dan lain-lain. Cerita di atas menunjukkan sinkretisme Islam dengan kepercayaan asli dalam masyarakat Minangkabau: motif perubahan bentuk–dimana disebutkan Nabi Khaidir bisa berubah menjadi harimau, setan, atau hantu jika ketahuan–menunjukkan motif kepercayaan asli setempat yang diadopsi ke dalam Islam (kurang logis juga bahwa seorang nabi mengubah dirinya menjadi setan, musuh umat Islam, terutama rasul-rasulnya sendiri). Fenomena seperti ini biasa terjadi dalam tahap awal pengislaman masyarakat di Nusantara: unsur kepercayaan lama/asli diintegrasikan ke dalam agama Islam sendiri supaya masyarakat yang dialihimankan tidak mengalami gegar budaya. Boleh jadi juga Cerita Nabi Khaidir ini sengaja diciptakan oleh ulama-ulama Islam di zaman dulu untuk mengajak masyarakat secara persuasif agar rajin shalat Jumat: orang yang pergi shalat Jumat berpeluang besar bertemu dengan Nabi Khaidir yang dapat menjadi perantara bagi pemenuhan permintaan-permintaan mereka kepada Tuhan. 24 Lihat: Walther Aichele, “Swei legenden der Menangkabau-Malaien im dialekt von Pajakomboeh, von Oesman Idris”, Zeitschrift Eingeborenen-Sprachen Jrg. 12 (1921/2922), hlm. 275-91. Kedatangan agama samawi memang tidak otomatis dapat menghilangkan kepercayaankepercayaan tradisional dalam masyarakat etnis di berbabagai daerah di Indonesia. Malah muncul kepercayaan-kepercayaan yang merupakan sinkretisme antara keduanya, seperti dapat dikesan dari Tjoerito Nobi Kaidie di atas. Di zaman sekarang pun sisa-sisa kepercayaan tradisional itu masih saja dapat dikesan dalam masyakarat Minangkabau: demikianlah umpamanya, kalau ada suatu gejala alam yang aneh–misalnya nenas yang banyak buahnya, kelapa yang bercabang dua, pisang yang tandan empat, dll.–hal itu cepat ditanggapi oleh masyarakat dengan pikiran irasional mereka; hal itu tidak dilihat sebagai suatu gejala penyimpangan genetik yang biasa terjadi pada makhluk hidup, seperti kasus bayi kembar siam pada manusia. Di banyak tempat lainnya di Indonesia, dalam lingkungan budaya etnis yang berbeda-beda, fenomena keterkaitan tradisi lisan dengan media modern makin kelihatan kentara. Berbagai program televisi, misalnya, merefleksikan tradisi lisan kita. Di banyak daerah di Indonesia kita menemukan genre-genre tradisi lisan kita dalam bentuk rekaman kaset dan VCD yang diperjualbelikan. Kita dengan mudah menemukan kaset-kaset dan VCD komersial wayang kulit, kaba Minangkabau, kabanti Buton, dan berbagai macam genre lisan lainnya dari berbagai etnis di Indonesia. Di Bali kita melihat fenomena yang sama: banyak stasiun radio menyiarkan kidung interaktif, acara mamebasan dan mesanti.25 Acara-acara tersebut digemari pula oleh anak muda. Fenomena ini menunjukkan adaptasi tradisi lisan Bali terhadap teknologi modern, bukan sebagaimana sering dipikirkan orang bahwa masyarakat lokal hanya pasif menerima teknologi modern tersebut. Banyak genre tradisi lisan yang mengandung unsur religiositas juga dimediatisasi dengan menggunakan media modern. Salah satu contohnya adalah selawat dulang di Minangkabau yang sudah disebut di atas. Sekarang banyak kaset dan VCD komersial selawat dulang diproduksi oleh studio-studio rekaman di Sumatra Barat.26 Komodifikasi reportoar-repertoar tradisional dari berbagai etnis yang kebanyakan bersifat anonim seperti selawat dulang terus berlangsung sampai sekarang dan malah makin masif. Efek-efeknya terhadap teks genre25 Lihat misalnya, I Nyoman Darma Putra, “Kidung interaktif: vocalizing and interpreting traditional literature trough electronic mass media in Bali”, Indonesia and The Malay World 37. 109 (Nov. 2009), hlm. 249-276; Helen Creese, “Singing the text: on-air textual interpretation in Bali”, in: Jan van der Putten and Mary Kilcline Cody (eds.), Lost times and untold tales from the Malay world, pp. 210-226. Singapore: NUS Press (2009). 26 Mengenai impak teknologi kaset dan VCD terhadap sastra lisan Minangkabau, lihat : Suryadi, “The impact of the West Sumatran regional recording industry on Minangkabau oral literature”, Wacana. Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, 12. 1 (2010), hlm. 35-69. genre itu sendiri, para penampilnya (performers) dan khalayak (audience) perlu diteliti secara lebih seksama dan mendalam. Sampul kaset-kaset dan VCD selawat dulang, suatu genre sastra lisan yang bernuansa agama (Islam ) dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. Perspektif penelitian tradisi lisan Indonesia yang cenderung melihat objeknya sebagai sesuatu yang identik dengan orang desa dan tidak terkait dengan dunia modern harus diubah. Selama ini, berbagai penelitian tradisi lisan di Indonesia cenderung melihat objeknya seperti steril dari sentuhan teknologi komunikasi modern. Padahal kenyataannya hampir tak ada wilayah Indonesia dewasa ini yang tak terjangkau dan terpengaruh oleh teknologi radio, televisi, kaset, VCD dan jenis-jenis media lainnya. Pengaruh nation-state terhadap masyarakat etnis antara lain terlihat dari bagaimana negara lakukan indoktrinasi ideologi kebangsaan, termasuk di dalamnya agama yang resmi diakui oleh negara, kepada masyarakat-masyarakat lokal dengan menggunakan berbagai macam media, baik cetak maupun elektronik. Dalam bukunya tentang media dan pembangunan kebangsaan, John Postil membahas dengan sangat menarik dari sudut pandang antropologi media (media anthropology) bagaimana Pemerintah Malaysia me- malaysia-kan masyarakat dayak Iban di Kalimantan Utara dengan menggunakan berbagai macam media yang dioperasikan di bawah panduan blue print ideologi negara Malaysia. 27 *** Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara-saudara sekalian, Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, izinkan saya menyimpulkan beberapa hal dari pembicaraan saya tadi. Pertama, bahwa tradisi lisan adalah salah satu cultural site yang penting yang dapat digunakan sebagai ‘pintu gerbang’ untuk memahami dinamika agama masyarakat lokal Indonesia. Melaluinya kita dapat memahami praktek-praktek agama dengan karakter lokalnya dan perbedaan konsep kosmologi antara masyarakat suatu etnis dengan etnis lainnya. Tradisi lisan adalah bagian yang integral dalam praktek-praktek agama dalam masyarakat lokal Indonesia. Para sarjana yang ingin meneliti dinamika agama di Indonesia dalam perspektif mikro mestilah memberi perhatian pada pertunjukan-pertunjukan tradisi lisan dalam masyarakat setempat, karena itu merupakan salah satu jenis data yang penting untuk dikoleksi dan ditelaah dalam rangka memahami konsep-konsep kepercayaan dan kosmologi masyarakat setempat. Kedua, banyak tradisi lisan yang mengandung unsur religiositas didasarkan pada teks tertulis. Artinya, bahwa pelisanannya berupa resitasi terbuka dengan berpedoman pada sebuah naskah atau bahan tertulis lainnya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dalam masyarakat lokal Indonesia antara yang lisan dan yang tertulis saling mempengaruhi secara bolak balik: yang lisan didasarkan atas yang tertulis atau, sebaliknya, yang tertulis didasarkan atas yang lisan. Namun, pesan yang lebih penting lagi di balik fenomena ini adalah bahwa seorang peneliti agama perlu juga mengetahui dunia tradisi lisan dengan segala teori dan pendekatannya di satu sisi dan dunia pernaskahan dengan segala teori dan pendekatannya pula di sisi lain. Dengan demikian berarti pula bahwa penguasaan bahasa lokal setempat, lisan maupun tulisan (kalau ada) juga amat diperlukan. 27 John Postill, Media and nation building: how the Iban became Malaysian. New York and Oxford: Berghahn Books (2006). Ketiga, adalah sangat mungkin untuk meneliti transformasi religiositas dari perspektif local dan bersifat diakronis mengingat bahwa cukup banyak tersedia dokumen-dokumen klasik yang mencatat praktek-praktek religius dan cerita-cerita yang terkait dengan kepercayaan lokal di Indonesia pada zaman kolonial, suatu tema penelitian yang sangat menarik dan sangat relevan dengan mahasiswa kita di sini. Keempat, untuk meneliti dimensi religiositas dalam pertunjukan-pertunjukan tradisi lisan, diperlukan pula pengetahuan, setidaknya tingkat dasar, mengenai antropologi dan etnologi. Dengan demikian dalam penelitian lapangan, para peneliti akan diberikan kesadaran akan pentingnya konteks, masyarakat pendukung, dan teks tradisi lisan itu sendiri. Selain itu, dengan berbekal pengetahuan antropologi dan etnologi tersebut, peneliti akan dapat pula memahami secara teoretis konsep-konsep fetisisme dan spiritisme yang mempengaruhi kepercayaan suatu kelompok etnis yang sering diekspresikan dalam berbagai pertunjukan tradisi lisan. Kelima, mediasi tradisi lisan melalui media modern seperti kaset, VCD, radio, televisi dan sebagainya, telah memunculkan bentuk-bentuk pertunjukan tradisi lisan berciri elektronik. Hal ini sudah merupakan keniscayaan di Indonesia yang masyarakatnya makin menuju ke masyarakat elektronik (electronic society). Baik unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik genre-genre lisan yang mengalami mediasi itu menyesuaikan diri dengan medianya. Namun yang tak kalah pentingnya untuk diamati adalah bagaimana genre-genre lisan yang bernuansa agama memperoleh citra baru dalam media modern. Fenomena ini kiranya penting diamati oleh para peneliti agama yang ingin menggunakan data-data tradisi lisan untuk penelitian mereka. Demikianlah ceramah saya, semoga ada manfaatnya bagi hadirin sekalian. Wassalam, Om shanti Om