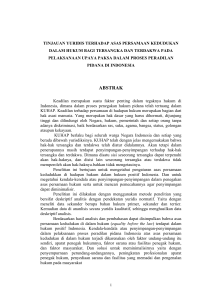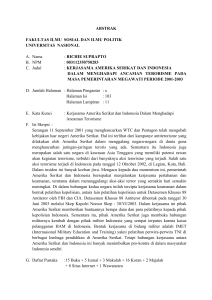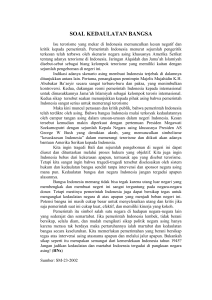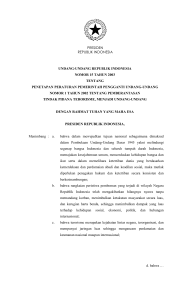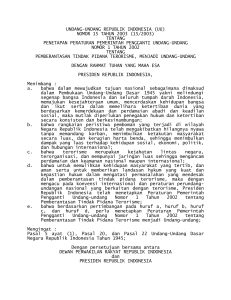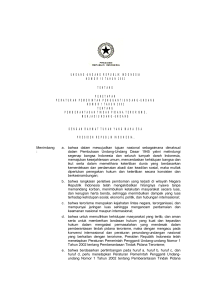tinjauan yuridis hak memperoleh rehabilitasi terhadap tersangka
advertisement

TINJAUAN YURIDIS HAK MEMPEROLEH REHABILITASI TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo OLEH NOPAN H1 A1 12 029 PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HALUOLEO KENDARI 2016 ii iii ABSTRAK Nopan, NIM: H1 A1 12 029, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, Agustus 2016, Tinjauan Yuridis Hak Memperoleh Rehabilitasi Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana, Oheo K. Haris, sebagai pembimbing I dan Ramadan Tabiu, sebagai pembimbing II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak terdakwa teroris dalam memperoleh rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan, rumusan Pasal 37 mengenai hak memperoleh rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki beberapa perbedaan dengan rumusan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Utamanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai kewenangan memeriksa rehabilitasi, pengajuan rehabilitasi, tenggang waktu mengajukan, sampai pada aturan mengenai cara memperoleh rehabilitasi yang dilalaikan oleh pengadilan. . iv KATA PENGANTAR Assalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan hidayah-Nya, limpahan rezeki, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu ’alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan kita umat muslim sampai akhir hayat. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Hak Memperoleh Rehabilitasi Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana” Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan tantangan yang penulis dapatkan, namun atas bantuan dan bimbingan serta motivasi yang tiada henti, disertai harapan yang optimis dan tekad yang kuat sehingga penulis dapat mengatasi semua itu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih, penghormatan, dan penghargaan yang setinggitingginya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Hadimin, S.Pd. dan Ibunda tercinta Mina, S.Pd. yang telah susah payah melahirkan, membesarkan dengan seluruh cinta dan kasih sayang, juga memberikan bantuan, serta dorongan kepada v penulis dalam menyelesaikan studi. Juga kepada saudara-saudaraku, Devin, Heriawan dan Alfian Saputra dan semua keluarga yang telah memberikan ketenangan hati dan kesabaran kepada penulis. Ucapan terima kasih pula yang tidak terhingga, penghargaan dan penghormatan kepada Bapak Dr. Oheo K. Haris, SH, M.SC, LL.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Ramadan Tabiu, SH, LL.M. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS sebagai Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Jufri, SH., MS sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. 3. Ibu Heryanti, SH., MH sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan selama mengikuti pendidikan. 5. Ibu Dr. Hj. Sabrina Hidayat, S.H, M.H, Bapak Lade Sirjon, S.H, LL.M, serta Bapak Ali Rizky, S.H.M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan isi skripsi ini. 6. Kepada rekan-rekan Kelas A Reguler 2012 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Abu Annas, Zahren Zukri Alyafie, Dicky Rafliyanto, Firman Sam, Limit Hadrianus, Syaiful, Muh. Iryansah Nasir, Andi Dangkang Marifatullah Joenoes, Dzulkifli Jumardi, Fandy Achmad Tawakal, Herman Saputra, Tri Hermawan, Galih Chandra Kirana, Afriani Roesman, Helisa Setiawati, Kartini, Arizka Damayanti, Nur Afni, Salniati, Wa Ode Isra Mirad, Wa Ode Nur Fitriyana, Zherly Amalia Ningzih, serta teman-teman yang tidak sempat penulis tuliskan namanya satu persatu terima kasih atas semua bantuannya, motivasi, dukungan moril, kekompakan, dan kenangannya. 7. Kakak-kakak senior angkatan 2010, 2011 dan adik-adik junior angkatan 2013, 2014 dan 2015 Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. 8. Kepala Desa Puunangga, Mamanya Rey, Ibu aji beserta keluarga, serta masyarakat Desa Puunangga, yang telah menerima kami, membantu kami, serta memberi kami semangat dalam kegiatan KKN T.A. 2015/2016. Juga untuk rekan-rekan KKN dari berbagai Fakultas, Universitas HaluOleo, Kak Husni, Fatrah, Sansan, Ai, Ida, Ifa, Nova, dan Niar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya penulis berdoa semoga Allah, SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan. Wasalammualaikumwarahmatullahi wabarakatuh Kendari, Oktober 2016 Penulis DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………..…..i HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………………………ii HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………………iii ABSTRAK………………………………………………………………………..iv KATA PENGANTAR………………………………………………………….....v DAFTAR ISI……………………………………………………………………..vi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang…………………………………………………………1 B. Rumusan Masalah……………………………………………………...8 C. Tujuan Penelitian……………………………………………………….8 D. Manfaat Penelitian……………………………………………………..8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Terorisme……………………………….…………...9 1. Terorisme di Indonesia………………………………….…………17 2. Terorisme sebagai Kejahatan Luar Biasa……………...…………..22 B. Hak-Hak Tersangka dalam Hukum Nasional......................................25 1. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....................................................................25 2. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.........................30 3. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.......................................32 vi 4. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman...............35 5. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....36 C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana............................................39 BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian......................................................................................48 B. Jenis Pendekatan...................................................................................48 C. Bahan Penelitian Hukum......................................................................50 D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum..................................................52 E. Teknik Analisis Bahan Hukum.............................................................52 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Rehabilitasi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Rumusan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Rumusan Pasal 97 jo. Pasal 1 Butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana……………..........................................................................53 A. Rehabilitasi Dalam Rumusan Pasal 97 jo. Pasal 1 Butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana………….…………………..53 1. Kewenangan Memeriksa…………………………………………54 2. Pengajuan Rehabilitasi…………………………………………...56 3. Tenggang Waktu Mengajukan…………………………………...59 4. Redaksi Amar Putusan…………………………………………...62 B. Rehabilitasi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Rumusan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme……..64 1. Kewenangan Memeriksa…………………………………………66 2. Pengajuan Rehabilitasi…………………………………………...68 3. Tenggang Waktu Mengajukan…………………………………...70 4. Redaksi Amar Putusan…………………………………………..72 5. Kelalaian Pemberian Rehabilitasi………………………………..72 C. Usulan Rekomendasi Atas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016………………………………………………………………….76 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………………..80 B. Saran…………………………………………………….…………...80 DAFTAR PUSTAKA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara hukum dan pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup setiap warga negara indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila juga merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku dinegara kita yang mana didalamnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan/atau hak-hak asasi manusia, maka penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dua hal yang secara simultan harus diperhatikan dan dipatuhi bagi setiap proses penegakkan hukum di Indonesia1. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang melekat dan menyatu pada diri hukum. Namun dilihat dari sudut hukum, hak dan kewajiban secara individual selalu berkonotasi dengan hak dan kewajiban individu anggota masyarakat lainnya. Disamping itu, karena hukum tidak hanya mengatur hubungan antar individu didalam pergaulan masyarakat, tetapi juga hubungan individu dengan lingkungan dan masyarakat sebagai salah satu kesatuan komunitas, maka hak asasi manusia (HAM) secara individual berkonotasi pula dengan HAM sebagai kesatuan komunitas. Jadi HAM pada hakikatnya mengandung dua wajah, yaitu HAM dalam arti “Hak Asasi Manusia” dan HAM dalam arti “Hak Asasi 1 M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 8. 1 2 Masyarakat”. inilah dua aspek yang merupakan karakteristik dan sekaligus identitas hukum, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan 2. Hak untuk hidup merupakan hak asasi paling dasar bagi seluruh manusia yang memiliki sifat non derogable rights yang artinya bahwa hak ini mutlak harus dimiliki oleh setiap orang. Pengecualian terhadap penghilangan hak hidup tidak mencakup pada penghilangan hak hidup seseorang oleh orang lain tanpa ada alasan hak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh penghilangan hak hidup tanpa alasan hak adalah pembunuhan melalui aksi terorisme. Aksi terorisme jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat, dan norma agama. Terror juga telah menunjukan gerakannya sebagai tragedi atas hak asasi manusia3 Terorisme adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat transnasional (Transnational Crime) yang menimbulkan bahaya keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…” 2 3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 57. Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Agama), PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 2 3 Persoalan terorisme di Indonesia menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan indonesia menjadi sorotan publik internasional, dimana teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang pernah terjadi 4. Mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya kembali berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda, dan instalasi-instalasi vital yang ada di Negara kita, maka pemerintah berpendapat bahwa syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 telah terpenuhi. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu), menunjukan pemerintah ingin menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dirumuskan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang mana penjelasan pemerintah tersebut diatas secara mendalam dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, 5 bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip yakni: 1. Prinsip National Security, yaitu untuk mewujudkan prinsip teritorialitas sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan NKRI. 2. Prinsip Balance of Justice, yaitu untuk menegakan prinsip equality before the law baik terhadap tersangka/terdakwa maupun korban sehingga due proses harus digandengkan dengan crime control model dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. 4 5 Ibid, hlm. 59. Romli Atmasasmita, Pemberantasan Terorisme Dari Aspek Hukum Internasional; Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme tgl 21-21 Maret 2003, hlm. 13. 4 3. Prinsip Safe Guarding Rules, yaitu prinsip untuk mencegah terjadinya abuse of power. 4. Prinsip Save Harbor Rules, yaitu prinsip perlindungan kepada tersangka, dan prinsip ini telah diperkuat oleh ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. 5. Prinsip Sunshine Principle, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. 6. Prinsip Sanset Principle, yaitu prinsip pembatasan waktu (time limits) terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa terorisme dalam perjalanannya masih sering kali terabaikan, tidak hanya dari segi hukum materiil, tetapi juga dari segi hukum formil suatu produk perundang-undangan. Pengabaian hak-hak tersangka/terdakwa terorisme merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak individu warga Negara (individual freedom of the citizen) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Padahal, jaminan konstitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UndangUndang Dasar dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undangundang pula. Pelanggaran yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak 5 individu warga Negara ini terlihat dalam pasal 3 Universal Declaration Of Human Rights, yaitu the right to life, liberty and security. Hak-hak warga negara ini tidak akan berarti bilamana secara sewenang-wenang negara (melalui aparatnya) dapat membunuh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga Negara. Hal ini jelas bukanlah perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum. Hukum selalu menyatakan, bahwa apabila ada hak yang dilanggar, maka selalu harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperolehnya (ubi jus ibi remidium). Kelanjutan dari asas ini adalah penafsiran, bahwa hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya, dapat dikatakan adanya hak bersangkutan (ubi remidium ibi jus).6 Yang menjadi masalah adalah, apabila peraturan yang seharusnya digunakan untuk menuntut dan memperoleh hak-hak itu, malah justru tidak mengatur secara explicit, dan atau menimbulkan kontradiktif dalam penafsiran dan pengimplementasiannya. Jelas saja, hal ini akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak itu, dan membuka peluang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam setiap proses peradilan (Ciminal Justice Process) dalam sistem peradilan pidana. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorime yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dibentuk dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, sedangkan paradigma pembentukan undang-undang ini merupakan paradigma tritunggal, yaitu melindungi Wilayah Kesatuan Republik 6 Paul Sieghart, The Lawful Right of Mankind (An Introduction to The International Legal Code of Human Rights), (Oxford University Press, 1986), hlm. 107-110. 6 Indonesia, Hak Asasi Manusia, dan Perlindungan Hak Asasi Tersangka. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak tersangka terorisme, dan berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam undang-undang ini, seringkali memunculkan pertentangan, baik dikalangan aparat penegak hukum, para pihak yang berperkara, maupun dikalangan pakar hukum pidana. Pertentangan ini seringkali berkaitan dengan pemenuhan hak-hak baik itu korban terorisme, maupun tersangka/terdakwa terorisme. Faktanya, undang-undang ini memang memiliki kelemahan-kelemahan substantif yang perlu membutuhkan perbaikan. Diantara kelemahan itu, kaitannya dengan hak-hak tersangka teroris, seperti; berlakunya asas retroaktif penerapan ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 terhadap kasus bom bali tanggal 12 Oktober 2002 yang ditetapkan melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2002 yang disahkan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2003 yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 013/PUU-I/2003 menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal lain berkaitan dengan perihal penangkapan dan proses penyidikan mengenai tidak terdapatnya kejelasan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 maupun KUHAP mengenai pada saat kapan tersangka akan diperiksa, selain itu, ada pula yang berkaitan dengan masalah substantif seperti dalam pasal 25 ayat (2) mengenai kepentingan penyidikan dan penuntutan, dan sampai pada persoalan yang berkaitan dengan masalah hak memperoleh rehabilitasi bagi terdakwa yang 7 sampai saat ini, masih menjadi isu hangat dalam persoalan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka terorisme. Melihat fenomena diatas, maka menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas kaitannya dengan perlindungan hak tersangka demi terlaksananya prinsip “due process of law” dan prinsip “fair trial” serta “equality before the law” yang seimbang antara pihak korban dan pihak tersangka. Untuk itu, mengingat pentingnya hal ini, berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam penelitian saya yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS HAK MEMPEROLEH REHABILITASI TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”. 8 B. Perumusan Masalah Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah hak terdakwa teroris dalam memperoleh rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ? C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui hak terdakwa teroris dalam memperoleh rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat teoritis penelitian ini yakni menambah wawasan pengetahuan dalam lingkup HAM yang akan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan menjadi acuan literatur seputar hak asasi tersangka. 2. Manfaat praktis penelitian ini dalam prakteknya akan dapat digunakan sebagai acuan mengenai bagaimana bertindak dan menyikapi berbagai masalah seputar pemenuhan hak asasi tersangka pidana. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Terorisme Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari kata latin ”terrere” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa berarti menimbulkan kengerian. Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam defenisi, yaitu defenisi tindakan teroris (terrorism act) dan pelaku terorisme (terrorism actor). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong ke dalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik dan terror/intended audience. Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, Crimes against Humanity termasuk kategori gross violation of human rights yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (public by innocent). 9 10 Memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji telebih dahulu pengertian atau defenisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/pakar atau ahli, yaitu : 1. US Central Inteligence Agency (CIA) Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing 7. 2. US Federal Bureau of Investigation (FBI) Teorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta, untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik8. 3. US Departments of State and Defense Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara9. 4. TNI AD Terorisme adalah cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan10. 7 8 9 10 Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op. cit., hal. 71. Muladi, Demokrasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia, Op. cit., hal. 72. Loc.cit. Berdasarkan Bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang Anti Teror Tahun 2000. 11 5. Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999 Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk : a. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum; b. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain; c. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau tejadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat; d. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut; e. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional; f. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris di bawah perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme. 12 6. Konvensi PBB Tahun 1937 Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas11. 7. The Arab Convention on the Suppresion of Terrorism (1998) Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut, dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional12. 8. State of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism a. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak Sah atas Keselamatan Penerbangan Sipil”, ditandatangani di Hague pada 16 Desember 1970; b. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak Sah atas Penerbangan Sipil”, ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971; 11 12 Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, http://buletinlitbang.dephan.go.id, diakses pada 20 Mei 2016. Loudewijk F. Paulus, Op. cit. 13 c. Kejahatan dalam lingkup “Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman atas Tindak Pidana terhadap Orang-Orang yang Secara Internasional dilindungi, Termasuk Agen-Agen Diplomatik”, ditandatangi di New York, 14 desember 1973; d. Kejahatan dalam lingkup konvensi apapun di mana negaranegara anggota SAARC adalah pihak-pihak yang mengharuskan anggotanya untuk menuntut atau melakukan ekstradisi; e. Pembunuhan, pembantaian, serangan yang mencelakakan badan, penculikan, kejahatan yang berhubungan dengan senjata api, senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang jika digunakan untuk melakukan kejahatan dapat berakibat kematian atau luka yang serius atau kerusakan berat pada harta milik; f. Usaha untuk melakukan kejahatan, atau turut sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan kejahatan tersebut; g. Usaha atau konspirasi untuk melakukan kejahatan, membantu, memudahkan atau menganjurkan kejahatan tersebut atau berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang digambarkan. 9. Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terorism, 1999 Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan 14 rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya tau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas terirotial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka. 10. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik. 11. Black’s Law Dictionary Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan. 12. Terrorism Act 2000, UK Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri : i. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, 15 membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik; ii. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik; iii. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi; iv. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. Dari beberapa hal tersebut ada catatan yang perlu diperhatikan bahwasanya di UK mereka yang dalam aktivitas organisasi terlarang dapat dipidana, keterlibatan bisa dalam bentuk keanggotaan, membantu dalam bentuk uang atau kekayaan atau mempersiapkan rapat organisasi terlarang, memakai seragam organisasi terlarang di muka umum dan membantu pengumpulan dana. Suatu organisasi dianggap terlibat apabila berpartisipasi dalam terorisme, mempersiapkan terorisme, menggalakkan dan mempromosikan terorisme. 13. Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang 16 dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III, Pasal 6 dan 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika : Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional; Seseorang juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang ini. 14. Menurut Laqueur (1999) Setelah mengkaji lebih dari seratus defenisi terorisme adanya unsur yang paling menonjol dari defenisi-defenisi tersebut yaitu bahwa ciri utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama13. 15. Menurut Muladi Dalam catatan Muladi bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 13 Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III (Desember 2002), hlm. 33. 17 berkarakter politik, dengan berbagai bentuk perbuatan, seperti berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku terorisme dapat merupakan individu, kelompok, atau negara, yang melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan menimbulkan munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain. Menyimpulkan dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas, dapat diketahui bahwasanya terorisme adalah kejahatan yang direncanakan, terorganisasi, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama. 1. Terorisme di Indonesia Peristiwa terorisme di Indonesia sudah sering kali terjadi dalam sejarah Indonesia. yang pertama pernah terjadi pada tahun 1981 yaitu teroris yang menyamar sebagai penumpang dan membajak pesawat DC-9 Woyla14. Dan peristiwa yang baru-baru ini terjadi adalah Bom di Sarinah. Berikut ini adalah serangkaian aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia : Pada tahun 1981 Garuda Indonesia di serang oleh teroris yang menyamar sebagai penumpang dan membajak pesawat DC-9 Woyla pada tanggal 28 Maret 1981. 14 http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2016/01/kumpulan-aksi-terorisme-di-indonesia.html, diakses pada 20 Mei 2016. 18 Dalam perjalanan menuju Medan setelah transit di Palembang dari penerbangan di Jakarta. Pesawat ini dibajak oleh 5 orang bersenjata yang mengaku sebagai Komando Jihad, 3 dari 5 teroris tersebut mengaku sebagai bagian dari penumpang pesawat Garuda Indonesia. Peristiwa tersebut merenggut 1 orang kru pesawat tewas, 1 orang penumpang tewas, dan 3 orang teroris tewas. Pada tahun 1985 5 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 21 Januari 1985. Aksi terorisme dengan motif "jihad" kembali terjadi. Kali ini terjadi pada salah satu keajaiban dunia yaitu Candi Borobudur. Pada tahun 2000 1. Bulan Agustus, sebuah bom meledak di Kedubes Filipina. Akibat dari kejadian ini 2 orang tewas dan 21 orang luka-luka termasuk didalamnya Duta Besar Filipina untuk Indonesia yaitu Leonides T. Canay dan kerusakan mobil-mobil yang terparkir di lokasi sekitar terjadi ledakan. 2. Tanggal 27 Agustus, peledakan bom kembali terjadi pada kedutaan. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah Malaysia. Beruntung, dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. 3. Tanggal 23 September, peledakan bom kembali terjadi, sasarannya adalah di Gedung Bursa Efek Jakarta tepatnya di lantai parkir P2. Dalam peristiwa tersebut 10 orang tewas, 90 orang luka-luka dan sebanyak 104 mobil rusak berat. 4. Tanggal 24 Desember, serangkaian peledakan bom yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Dalam peristiwa ini 16 orang tewas. 19 Pada tahun 2001 1. Tanggal 22 Juli, bom yang diledakkan di Gereja Santa Anna dan HKBP kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Pada kejadian ini sebanyak 5 orang tewas. 2. Tanggal 23 September, bom yang meledakkan kawasan Plaza Atrium Senen. Beruntung pada aksi terorisme ini tidak ada korban jiwa. 3. Tanggal 12 Oktober, bom pada restoran cepat saji KFC Makassar. Pada aksi terorisme ini tidak ada korban jiwa. 4. Tanggal 6 November, peledakan bom yang terjadi di halaman sekolah AIS (Australian International School). Dalam peristiwa ini tidak ada memakan korban jiwa15. Pada tahun 200216 1. Tanggal 1 Januari, peledakan bom yang terjadi pada malam tahun baru, bom ini meledak pada kawasan Bulungan, Jakarta tepatnya di salah satu rumah makan 2. Tanggal 12 Oktober, bom Bali ada tiga ledakan yang terjadi dan mengakibatkan korban meninggal sebanyak 202 orang dan 300 orang luka-luka. Sebagian besar yang menjadi korban adalah warga Australia dan sempat menjadi headlines news di berbagai negara. 3. Tanggal 5 Desember, bom yang meledakkan sebuah restoran sepat saji McDonald's Makassar. Dalam kejadian ini sebanyak 3 tewas dan 11 lainnya luka-luka. 15 16 https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia, diakses pada 20 Mei 2016. Loc.cit. 20 Pada tahun 2003 1. Tanggal 3 Februari, bom yang pertama terjadi di lobi Bhayangkari Mabes Polri Jakarta. 2. Tanggal 27 April, peledakan bom yang terjadi di terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. Pada peristiwa ini memakan 10 korban, 2 luka berat dan yang lain hanya mengalami luka ringan. 3. Tanggal 5 Agustus, peledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriot. Pada peristiwa tersebut puluhan korban tewas dan ratusan lainnya menderita luka-luka. Pada tahun 2004 1. Tanggal 10 Januari, bom pertama ini dikenal dengan nama Bom Palopo. Dalam peristiwa ini 4 orang tewas. 2. Tanggal 9 September, pemboman yang kedua dikenal dengan nama Bom Kedubes Australia. Pada kejadian ini sebanyak 5 orang tewas, ratusan orang luka-luka, dan beberapa gedung disekitar terkena dampaknya. 3. Tanggal 12 Desember, pemboman yang ketiga dikenal dengan Bom Gereja Immanuel di Palu, Sulawesi Tengah. Pada tahun 2005 1. Tanggal 21 Maret, ada dua bom yang meledak di Kota Ambon dan beruntung pada kejadian ini tidak ada korban jiwa. 2. Tanggal 28 Mei, pemboman ini dikenal dengan nama Bom Tentena. Dalam kejadian ini sebanyak 22 orang tewas. 21 3. Tanggal 8 Juni, bom meledak di Pamulang. Yang menjadi sasarannya adalah kediaman Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. 4. Tanggal 1 Oktober, bom kembali meledak di Bali, pada peristiwa ini sebanyak 22 orang tewas dan 102 orang luka-luka. 5. Tanggal 31 Desember, peledakan bom di Palu, Sulawesi Tengah yang menjadi sasarannya adalah sebuah pasar dan mengakibatkan 8 orang tewas dan 45 orang luka-luka17. Pada tahun 2009 Empat tahun kemudian, dua bom diledakkan secara bersamaan di Jakarta tepatnya di JW Marriot dan Ritz-Carlton. Pada tahun 2011-2012 Tanggal 15 April 2011, tiga bom meledak di tiga kota di Indonesia. Kota pertama adalah Cirebon dimana sebuah bom bunuh diri diledakkan di Masjid Malporesta. Peristiwa ini menewaskan pelaku pemboman dan melukai 25 orang. Kota kedua adalah Tangerang dimana polisi berhasil menggagalkan aksi pemboman terhadap Gereja Christ Cathedral. Kota ketiga adalah Solo, Jawa Tengah. Sebuah bom bunuh diri diledakkan di GBIS Kepunten, Solo, Jawa Tengah. Dalam peristiwa ini 1 orang pelaku tewas sedangkan 28 orang lainnya luka-luka. Tanggal 19 Agustus 2012, pemboman yang terjadi di Pospam Gladak, Solo Jawa Tengah, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 17 (Sumber: Harian KOMPAS edisi 8 Oktober 2005). 22 Pada tahun 2013 Bom Polres Poso 2013, 9 Juni 2013 dengan target personel polisi yang sedang apel pagi. Bom meledak di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. 1 orang petugas bangunan terluka di tangan sebelah kiri, sementara pelaku bom bunuh diri tewas di tempat. Pada tahun 2016 Tanggal 14 Januari, terjadi ledakan bom di pos polisi di depan gedung Sarinah dan Starbucks di jalan M.H Thamrin. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 10.30 WIB. Bom yang lebih dikenal dengan nama Bom Sarinah ini menyebabkan 7 orang tewas dan melukai 17 orang. 2. Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa Terorisme merupakan kejahatan lintas Negara (Transnational crime), terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional18. Banyak pihak menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah extra ordinary crime. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuaannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali. 18 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 23 Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai extra ordinary crime adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi crime against humanity, genocide, war crimes dan Agressions19. Menentukan kejahatan mana yang termasuk dalam kategori extra ordinary crime, harus ditentukan dulu karakteristiknya. Namun saat ini karakteristik extra ordinary crime masih kabur. Penentuan pelanggaran HAM berat sebagai extra ordinary crime didasarkan pada dokumen hukum internasional yaitu Statuta Roma. Apabila kita bersandar kepada teori hirarki Hans Kelsen, maka penentuan tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime pun harus di dasarkan pada dokumen hukum yang lebih tinggi dari sebuah undang-undang, dengan mengingat bahwa penentuan suatu kejahatan sebagai extra ordinary crime akan menyimpangi bahkan bertentangan dengan beberapa prinsip hukum, misalnya asas legalitas20. Berdasarkan konvensi dan praktik hukum internasional, kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) diatur dan dikualifikasikan kepada pelaku negara. Misalnya Resolusi PBB tentang pelanggaran HAM zionisme Israel kepada bangsa Palestina; sidang Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap penguasa Serbia, Slobodan Milosevic, atas tindakan pemusnahan etnis Bosnia. Terorisme negara ini menurut Statuta Roma yang dimaksudkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Sedangkan terorisme oleh warga hanyalah kejahatan bersifat sporadis. Sebab kejahatan perang, agresi, kejahatan terhadap 19 20 Trimoelja Darmasetia Soerjadi. Terorisme, perang global, dan masa depan demokrasi, Matapena, Jakarta, 2004, hlm. 32. Loc.cit. 24 kemanusiaan dan genosida adalah kejahatan sistemik. Negara yang mampu dan mempunyai “keabsahan” tindakan itu dalam arti sebenarnya21. Pelanggaran HAM berat masuk kategori sebagai extra ordinary crime berdasarkan dua alasan, yaitu pola tindak pidana yang sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh, dan alasan bahwa kejahatan tersebut sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan. Tindak pidana terorisme dimasukkan dalam “extra ordinary crime “ dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan “transnational“dan melibatkan jaringan internasional. Fakta menunjukkan bahwa memang tindak pidana terorisme lebih banyak merupakan tindak pidana yang melibatkan jaringan internasional, namun kesulitan pengungkapan bukan karena perbuatannya ataupun sifat internasionalnya. Kemampuan pengungkapan suatu tindak pidana lebih ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme aparat kepolisian yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban. Kejahatan lintas batas tentu bukan merupakan alasan yang valid untuk menentukannya sebagai “extra ordinary crime”, karena di jaman ini banyak tindak pidana yang memiliki jaringan internasional (misalnya pencucian uang, perdagangan orang, dan penyelundupan)22. Menurut Indriyanto Seno Aji, terorisme sudah menjadi bagian dari “extra ordinary crime“ yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi 21 22 Aulia Rosa Nasution, Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 128. Loc.cit. 25 khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era keberadaban karena kejahatan itu mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa. Sesuai dengan karakteristik kejahatan terorisme yang mana menggunakan kekerasan dalam operandinya. Dan akibat dari kejahatannya dapat merusak sistem perekonomian, integritas negara, penduduk sipil yang tidak berdosa, serta fasilitas umum lain dalam konteks melawan hukum yang signifikan sekali. Karena itu, pelaku teror yang berlindung sebagai pelaku delik politik atau “political purpose“ yang dilakukan dengan “purpose of violence“ di mana tindakan dimaksudkan untuk membuat shock atau intimidasi kepada “governmental authority“ atau yang berakibat pada ”public by innocent“, berlakulah prinsip ekstradibilitas. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ECST bahwa delik yang dikategorikan sebagai ”acts of terror“ bukanlah sebagai pelaku delik politik, dan karenanya dapat dilakukan tindakan ekstradisi. B. Hak-Hak Tersangka Dalam Hukum Nasional23 1. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sering disebut KUHAP, diberlakukan mulai tahun 1981 untuk menggantikan hukum acara pidana yang terdapat dalam HIR 1941 (het Herziene Inlandsh Reglement diterjemahkan sebagai Reglemen Indonesia yang diperbaharui, disingkat RIB). 23 Munir Fuadi, Sylvia Laura L, Hak Asasi Tersangka Pidana, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 15 26 Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu : Asas-asas umum : a. b. c. d. e. f. g. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; Praduga tidak bersalah; Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; Hak untuk mendapatkan bantuan hukum; Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan; Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum. Asas-asas khusus : h. i. j. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya. Asas pertama tentang “perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi”, tidak saja terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga tercantum dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan Pasal 16 ICCPR. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan 27 keadilan. Setiap orang, apakah ia tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Asas kedua tentang “praduga tak bersalah”, Unsur-unsur dalam asas ini adalah prinsip utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup : a. Bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang jujur atau fair trail , berimbang dan tidak memihak (impartiality); b. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum; d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya, tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun. Asas ketiga, adalah tentang “hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi”. Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu : a. Hak waga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya). b. Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi. Prinsip yang terkandung pula dalam asas ini adalah bahwa negara dapat pula meminta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya. 28 Asas keempat adalah tentang “hak untuk mendapat bantuan hukum”. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan para pejabat hukum harus memberlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin “equality of arms” juga harus ditaati. Asas kelima, merupakan “hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan”, yang harus diperhatikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi “sudut pandang” tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar “hak untuk membela diri” dan “praduga tidak bersalah” seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan “in absentia” tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal (misalnya pasal-pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205). Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas (Pasal 214 (1)). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk “mempermalukan” terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi 29 kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Asas keenam menegaskan adanya “peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana”. Di sini kita lihat ada dua asas, yaitu : i. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun; ii. Bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dengan sederhana. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum (Pasal 50 KUHAP). Asas ketujuh adalah tentang “peradilan yang terbuka untuk umum” disini adalah adanya “public hearing” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “secret hearing”, dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara seksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu “show case” atau dimaksudkan sebagai “instrument of deterrence”, baik dengan cara mempermalukan terdakwa (prevensi khusus) ataupun menakut-nakuti masyarakat atau “potential offenders” (prevensi umum). Asas kedelapan tentang “dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara”. Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak-hak individu warga negara” adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (individual freedom of the citizen) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan kontitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 UDHR, yaitu “the right to life, liberty and security”. Asas kesembilan tentang “hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya”, asas ini merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas “liberty and security”. Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purna-ajudikasi (postadjudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat hanyalah dilihat sejauh kewajiban pengawasan. 2. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Perlindungan HAM agar warga negara terhindar dari segala bentuk penyiksaan dan kekerasan baik berupa fisik maupun psikis adalah dengan melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Merendahkan Martabat Manusia dengan secara serius dan konsekuen. Beberapa pasal dalam kaitannya untuk melindungi hak asasi tersangka/terdakwa antara lain : a. Kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan dengan langkahlangkah legislatif,administrasi, hukum,atau langkah-langkah efektif lainnya (Pasal 2 31 b. Kewajiban negara untuk menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara (Pasal 10 ayat (1)); c. Kewajiban negara untuk senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaankebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan (Pasal 11); d. Kewajiban negara untuk menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya (Pasal 12); e. Kewajiban negara untuk menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkahlangkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu 32 dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan (Pasal 13); f. Kewajiban negara untuk menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan kompesasi (Pasal 14). 3. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia24 Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan aparat maupun pejabat pemerintah. Beberapa ketentuan dalam undang-undang terkait perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa antara lain : a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat 2); b. Hak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi (Pasal 3 ayat 3); 24 Ibid, hlm. 21 33 c. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, persamaan di muka hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 4); d. Hak untuk menuntut dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 ayat 1) e. Hak untuk mendapat bantuan hukum dan proses pengadilan yang adil, objektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2)25; f. Hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin (Pasal 9 ayat 2); g. Hak mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik perkara perdata, pidana, maupun administrasi melalui proses peradilan yang bebas, tidak memihak dan objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17)26; h. Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dapat dibuktikan kesalahannya melalui sidang pengadilan yang sah dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya (Pasal 18 ayat 1)27; i. Hak tidak dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya (Pasal 18 ayat 2); 25 26 27 Ibid, hlm. 22. Loc.cit. Loc.cit. 34 j. Hak setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka (Pasal 18 (2)); k. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4); l. Hak tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5)28; m. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya (Pasal 29 ayat 1); n. Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (Pasal 29 ayat 2); o. Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30); p. Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat 1); q. Hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa (Pasal 33 ayat 2); 28 Ibid, hlm. 23. 35 r. Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM (Pasal 90); 4. Hak Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan. Undang-Undang ini mengatur pula perihal perlindungan HAM tersangka/terdakwa, antara lain : a. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 (2)); b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 5 ayat 1); c. Hak setiap orang untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 7); d. Hak untuk dianggap tidak bersalah bagi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8) e. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi bagi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan 36 undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di terapkannya (Pasal 9 ayat 1); f. Hak untuk memperoleh bantuan hukum terhadap setiap orang yang tersangkut perkara (Pasal 37); g. Hak tersangka menghubungi dan meminta bantuan advokat sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan (Pasal 38). 5. Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah extraordinary crime. Derajat ”keluar-biasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Anti Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom bali. Selama ini yang telah diakui sebagai extraordinary crime adalah pelanggaran hak asasi manusia berat yang meliputi crime against humanity dan genocide (sesuai dengan Statuta Roma). Untuk menentukan kejahatan yang termasuk dalam kategori extraordinary crime harus ditentukan karakteristik extraordinary crime. Penentuan pelanggaran hak asasi manusia berat sebagai extraordinary crime didasarkan pada kaidah hukum internasional yaitu statuta roma29. 29 Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia meliputi: - Kejahatan Genosida - Kejahatan terhadap kemanusiaan. 37 Setelah terjadi serangkaian peledakan bom di Bali dengan puncaknya pada tanggal 12 Oktober 2002 berupa ledakan dahsyat yang terjadi di Sari Cafe, Jalan Legian, Kuta, untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya kembali berbagai serangan terhadap jiwa, harta benda, dan instalasi-instalasi vital lainnya, Pemerintah berpendapat bahwa syarat ”hal ikhwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah terpenuhi. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu), Pemerintah menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dirumuskan dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan pemerintah tersebut diatas secara mendalam dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip, yaitu: 1. Prinsip National Security; adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Prinsip Balance of Justice; adalah untuk menegakan prinsip equality before the law, baik tehadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban sehingga due process harus digandengkan dengan crime control model dalam mencegan dan memberantas tindak pidana terorisme. 38 3. Prinsip Save Guarding Rules; adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini. 4. Prinsip Save Harbor Rules; adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana terorisme dan prinsip ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diperkuat oleh ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (accessories after the fact) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. 5. Prinsip Sunshine Principle; adalah prinsip yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme. 6. Prinsip Sunset Principle; adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu terhadap kebijakan pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme. Bila mencermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka, terdakwa dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme hanya dalam pasal 19, yaitu hak tersangka yang umurnya di bawah 18 tahun untuk tidak 39 di jatuhi hukuman mati dan seumur hidup, pasal 24 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 yaitu hak tersangka yang umurnya di bawah 18 untuk tidak dijatuhi pidana minimum. Khusus pasal 20, 21, 22, dan pasal 25 ayat (2) yaitu hak tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 6 bulan30. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, juga mengatur tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas, dan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasihat hukumnya setiap saat, berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 37 (1)), dan Pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 mengenai pengajuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi31. C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. 30 31 Soeharto. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme. PT Refika Aditama. Bandung. 2007, hlm. 134. Ibid, hlm. 138. 40 Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial. 1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim penegakan hukum semata-mata. 2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi. 3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistim dalam peradilan pidana, ialah : 1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). 41 2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. 3. Efektifitas sistim penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. 4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan “The administration of justice” Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana adalah : 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 3. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu “due process of law” yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang 42 adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Sistem hukum yang baik, berusaha untuk membatasi tindakan yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat merasa tidak aman, terjadilah tindakan-tindakan main hakim sendiri atau take the law into their own hands. Tindakan main hakim sendiri adalah perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik terhadap keamanan jiwa maupun harta bendanya. Kondisi ini diakibatkan oleh : 1. Pengabaian hukum (disregarding the laws); 2. Ketidakhormatan pada hukum (disrespecting the law); 3. Ketidakpercayaan pada hukum (distrusting the law); 4. Penyalahgunaan hukum (misuse of the law). Oleh karena itu, untuk mencegah tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat, tugas menciptakan keamanan masyarakat itu diserahkan kepada negara melalui Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana Mempunyai tujuan jangka pendek untuk resosialisasi, tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana dapat dilihat dari bentuk-bentuk hukuman, tambahan jenis hak untuk 43 pelaku dan korban, dan reformasi penegakan hukum. Perkembangan ini dapat dilihat dari berubahnya kebiasaan, ide politik dan kondisi ekonomi32. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro,S.H.,M.A., Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. Sedangkan Sistem Peradilan Pidana menurut Andi Hamzah, bukan hanya meliputi hukum, tetapi termasuk juga berbagai unsur non-hukum. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari pembentukan undang-undang hukum pidana di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sampai kepada pembinaan narapidana hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi Sistem Peradilan Pidana adalah teori yang berkenaan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum, yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu. Seperti kepolisian dalam penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan, Mahkamah Agung (pengadilan) dalam peradilan, Lembaga Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM) dalam pemasyarakatan, dan Advokat dalam pemberian bantuan hukum. Namun, koordinasi antara lembaga penegak hukum sering terjadi tidak 32 Barda Nawawi Arief, Op.cit, 2011., hlm. 45. 44 sebagaimana yang diharapkan. Kita mengetahui bahwa lembaga-lembaga tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran HAM. Pemerintah, yang berdasarkan undang-undang wajib memenuhi HAM tersebut, seringkali tidak mampu melakukan perlindungan apapun ketika dituntut untuk memenuhi kewajibannya 33 Hukum acara pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam hukum acara pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka melindungi HAM. Melalui sejumlah prosedur hukum itulah, hakim dapat tiba pada kesimpulan apakah seseorang secara faktual dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana yang telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang hukum pidana materil34. Sementara itu, hak untuk menuntut tanggung jawab terhadap pelanggaran atas hak asasi seorang tersangka, terdakwa maupun terpidana, dijamin melalui lembaga seperti Habeas Corpus di Australia dan Inggris, lembaga Praperadilan di Indonesia, atau lembaga Rechter-Commisaris di Belanda. Merujuk pada pengertian Sistem Peradilan Pidana, dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana erat kaitannya dengan hak tersangka dan terdakwa 33 34 Barda Nawawi Arief, Op.cit, 2011., hlm. 58. Loc.cit. 45 yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana harus memiliki struktur yang berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal35. Sebagaimana pendapat Muladi, Sistem Peradilan Pidana terpadu adalah sinkronisasi atau keselarasan struktural, substansial dan kultural. Ketiga hal tersebut di atas saling berkait dan mempengaruhi. Berfungsinya Sistem Peradilan Pidana terpadu dengan baik dan benar ditentukan sejauh mana ketiga sinkronisasi (keselarasan) tersebut bekerja. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu. Dengan demikian, kegagalan pada salah satu sub-sistem saja, akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan. Tujuan pokok gabungan fungsi Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan memutuskan hukum pidana. Dengan demikian, kegiatan Sistem Peradilan Pidana didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama : 1. 35 Fungsi pembuatan undang-undang (law making function). Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat), Refika Aditama,Bandung,2009, hlm. 55. 46 Fungsi ini dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah atau badan lain berdasarkan delegated legislation. Sedapat mungkin, hukum yang diatur dalam undang-undang, tidak kaku (not rigid), fleksibel, dan akomodatif terhadap kondisi-kondisi perubahan sosial (enough to accomodate changing social conditions). 2. Fungsi penegakan hukum (law enforcement function). Tujuan objektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (social order): a. Penegakan hukum secara aktual (the actual law enforcement) meliputi tindakan : 1) Penyelidikan-penyidikan (investigation); 2) Penangkapan (arrest)-penahanan (detention); 3) Persidangan pengadilan (trial); 4) Pemidanaan (punishment) guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (correcting the behavior of individual offender). b. Efek preventif (preventive effect) Fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Kehadiran dan eksistensi polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan. Dengan demikan, kehadiran dan keberadaan polisi dianggap mengandung preventive effect yang memiliki daya cegah (detterent effort) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal. 3. Fungsi pemeriksaan persidangan pengadilan (Function of Adjudication). 47 Fungsi ini merupakan subfungsi dari kerangka penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi inilah ditentukan : a. Kesalahan terdakwa (the determination of guilty); b. Penjatuhan hukuman (the imposition of punishment). 4. Fungsi memperbaiki terpidana (The Function of Punishment). Fungsi ini meliputi aktivitas Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Sosial terkait, dan Lembaga Kesehatan Mental. Tujuan umum semua lembagalembaga yang berhubungan dengan penghukuman dan pemenjaraan terpidana : merehabilitasi pelaku pidana (to rehabilitate the offender) agar dapat menjalani kehidupan normal dan produktif (return to a normal and productive life)36. Selain adanya kebutuhan akan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, suatu sistem berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini sejalan dengan tujuan akhir dari politik kriminal yaitu perlindungan masyarakat dalam kerangka kebijaksanaan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau politik sosial. Manfaat lain yang terutama dari kebutuhan akan keterpaduan Sistem Peradilan Pidana adalah terciptanya perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia dalam proses pidana. 36 Ibid, hlm. 57. BAB III METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kejahatan terorisme, serta pandangan hukum nasional terhadap perlindungan hakhak tersangka terorisme. B. Jenis Pendekatan Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki37 pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undangundang dasar atau antara regulasi dan undang-undang, dimana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan maka pengambilan konklusi dapat dilakukan dengan tepat sehingga proposisi yang diajukan dapat terjawab dengan baik38. 2. Pendekatan Konseptual 37 38 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 137. Ibid, hlm. 141. 48 49 Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi 39. Dalam membangun konsep, hal pertama yang harus dilakukan adalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, yang mana prinsipprinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak eksplisit, konsep hukum dapat juga di ketemukan didalam Undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada40. 3. Pendekatan Perbandingan Pendekatan komparatif (Comparative Approach) dilakukan dengan membandingkan undang-undang terkait mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Dalam pendekatan perbandingan, dikenal beberapa bentuk pendekatan yaitu Comparative Law, Comparative Jurisprudence, dan Comparative Foreign Law. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut, dalam rangka memecahkan suatu isu hukum. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan 39 40 Ibid, hlm.177. Ibid, hlm.178. 50 undang-undang itu. Dengan demikian perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undangundang yang ada. Hal ini sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa41. 4. Pendekatan Kasus Pendekatan kasus (Case Aproach) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum42. C. Bahan Penelitian Hukum 41 42 Ibid, hlm. 172. Ibid, hlm. 158. 51 Bahan penelitian adalah bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research), bahan hukum yang dimaksud terdiri atas : 1. Bahan Hukum Primer Berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi tersangka menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Universal Declaration Of Human Rights 1948. 2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri atas hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, seminar, atau forum sejenis, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media yang relevan dengan objek penelitian. 3. Bahan Hukum Tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder dalam hal ini kamus hukum dan ensiklopedia hukum. 52 D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum Metode yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap dalam penelitian ini, penulis tempuh dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research) guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli dan pihak-pihak (instansi) yang berwenang dengan masalah yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk ketentuan formal, maupun data melalui naskah-naskah resmi yang ada. E. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis Normatif Kualitatif yaitu peneliti akan mendeskripsikan secara lengkap berdasarkan fakta-fakta yang terungkap sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari objek penelitian lalu di korelasikan dengan undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan hak-hak asasi tersangka terorisme khususnya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Universal Declaration Of Human Rights 1948. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Rehabilitasi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Rumusan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Rumusan Pasal 97 jo. Pasal 1 Butir 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana A. Rehabilitasi Dalam Rumusan Pasal 97 jo. Pasal 1 butir 23 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana Rehabilitasi dalam KUHAP diatur dalam Bab XII, Bagian Kedua, sebagai lanjutan ketentuan ganti kerugian. Rehabilitasi diatur hanya dalam satu pasal saja, yakni Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian, masih diharapkan peraturan pelaksana, terutama yang berhubungan dengan : - Bentuk rehabilitasi yang dapat diberikan pengadilan, dan - Cara pemberitahuan rehabilitasi Pengertian rehabilitasi merujuk pada Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang berbunyi : “Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. 53 54 Dari pengertian singkat diatas, tampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi yang Menurut M. Yahya Harahap, tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang43. Misalnya seorang tersangka yang telah dikenakan pemeriksaan penyidikan, ditangkap atau ditahan. Ternyata kemudian penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya kesidang pengadilan. Dalam kejadian yang seperti ini, tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi pemulihan nama baik serta kedudukan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula sebelum kepada dirinya dilakukan pemeriksaan penyidikan. Demikian juga halnya terhadap seorang terdakwa yang dituntut dan diperiksa disidang pengadilan. Ternyata putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadapnya berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan yang demikian, memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan yang bersangkutan. 1. Kewenangan Memeriksa Dalam rehabilitasi, terdapat dua instansi yang berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 97 KUHAP. Kewenangan pemeriksaan pada salah satu instansi ditentukan berdasar tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Jika perkaranya dihentikan sampai 43 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta, 2006, hlm. 69. 55 tingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, yang berwenang memeriksanya adalah Praperadilan. Jika pemeriksaan perkara sampai pada tingkat pengadilan, yang berwenang pemeriksanya adalah pengadilan Apabila pemeriksaan perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan, dan dari hasil pemeriksaan pengadilan menjatuhkan: - Putusan pembebasan, dan - Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, maka dalam hal ini, rehabilitasi diberikan pengadilan yang memutusnya. Bertitik tolak dari bunyi ketentuan Pasal 97 ayat (2), rehabilitasi berdasar putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Jadi, menurut ketentuan Pasal 97 ayat (2), jika pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi tersebut diberikan dan “dicantumkan” sekaligus dalam amar atau diktum putusan pengadilan yang bersangkutan. Di samping rehabilitasi diberikan langsung oleh pengadilan dalam putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, Praperadilan berwenang memeriksa rehabilitasi. Jenis rehabilitasi yang termasuk dalam kewenangan Praperadilan meliputi permintaan rehabilitasi atas tindakan penegakan hukum yang tidak sah yang perkaranya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 97 ayat (3). Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, apabila proses tingkat pemeriksaan perkara masih dalam taraf 56 penyidikan atau penuntutan, lantas pemeriksaan dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sehingga perkara yang bersangkutan tidak diajukan ke pengadilan, dalam peristiwa yang semacam ini, yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi adalah Praperadilan. 2. Pengajuan Rehabilitasi Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam KUHAP hanya mencantumkan satu pasal tentang rehabilitasi yakni Pasal 97. Oleh karena itu, masih dibutuhkan peraturan pelaksana baik yang berhubungan dengan orang yang berhak mengajukan rehabilitasi, tenggang waktu pengajuan, maupun bunyi amar putusan rehabilitasi. Baru setelah KUHAP berumur dua tahun, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana pada tanggal 1 Agustus 1983, sebagaimana yang diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yang terdiri dari Pasal 12 sampai Pasal 15. Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi tidak begitu jelas diatur dalam Pasal 97. Hanya dalam Pasal 97 ayat (3) ada disinggung sepintas lalu orang yang berhak mengajukan permintaan. Berdasar ayat (3) tersebut, hanya tersangka saja yang disebut yang berhak mengajukan. Untung Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983, memperjelas masalah ini. Berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (3) KUHAP dan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983, orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi : - Tersangka, - Keluarga tersangka, atau - Kuasanya. 57 Memperhatikan tentang orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi yang diatur dalam ketentuan diatas, “terdakwa” tidak termasuk kedalam kelompok orang yang berhak mengajukannya. Undang-undang dan peraturan hanya menyebut tersangka saja, dan menyampingkan terdakwa untuk mengajukan permintaan rehabilitasi. Padahal Pasal 97 ayat (1) KUHAP sudah menegaskan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan dijatuhkan kepadanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Bukankah yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ini, tiada lain daripada terdakwa yang kepadanya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jadi orang yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ialah orang yang didakwa atau diperiksa dalam sidang pengadilan, oleh pengadilan dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Berarti Pasal 97 ayat (1) telah membenarkan sendiri adanya hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi, apabila pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepadanya. Kalau begitu, kenapa Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 tidak mencantumkan terdakwa sebagai orang yang berhak mengajukan rehabilitasi. Menutut M. Yahya Harahap hal ini disebabkan, bagi terdakwa yang kepadanya dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, tanpa mengajukan permintaan kepadanya “mesti diberikan secara langsung” rehabilitasi pada saat putusan dijatuhkan. Jika pengadilan negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, harus memberikan sekaligus rehabilitasi kepada terdakwa dengan jalan mencantunkan dalam amar putusan. Demikian juga Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, 58 harus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi jika terhadap terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum44. Hak mengajukan rehabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi, sekalipun tersangka masih hidup dan sehat. Tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya. Masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan permintaan rehabilitasi. Tentang diberikan kemungkinan kepada kuasa mengajukan permintaan rehabilitasi, memperlihatkan sifat rehabilitasi agak cenderung kearah keperdataan. Memang rehabilitasi secara murni adalah hak keperdataan yang seharusnya dimintakan atau digugat didepan peradilan perdata. Akan tetapi lain halnya dengan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Permintaan rehabilitasi atas tindakan pejabat penegak hukum yang dikenakan kepada seseorang, tidak perlu melalui gugat perdata. Apabila pejabat penegak hukum melakukan tindakan pidana penangkapan, penahanan yang tidak berdasar alasan yang dibenarkan undang-undang atau apabila terhadap terdakwa dijatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi atas tindakan dan peristiwa tersebut tidak perlu melalui proses perdata. Yang bersangkutan atau keluarganya dapat mengajukan permintaan rehabilitasi melalui proses yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP jo. Bab V PP No. 27 Tahun 1983. 44 Ibid, hlm. 72. 59 Beda proses permintaan dan pemeriksaan rehabilitasi melalui pengadilan perdata dengan apa yang diatur dalam KUHAP, terletak pada subjek yang menjadi pihak. Rehabilitasi melalui gugatan perdata, mesti ada pihak yang digugat sebagai pihak yang dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berkewajiban untuk merehabiliter nama baik orang yang dirugikan atas fitnah atau pencemaran nama baiknya. Sedang proses rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 KUHAP, tidak menempatkan seseorang sebagai pihak tergugat. Malahan pihak pemohon sendiri, bukan merupakan pihak secara murni. Atau walaupun disebut ada pihak yakni pemohon pada satu sisi dan pejabat penegak hukum yang bersangkutan pada pihak lain, sifat keberadaan mereka sebagai pihak adalah semu. Pemohon secara semu bertindak sebagai penggugat, dan pejabat atau instansi yang terlibat atau Negara berada dalam kedudukan sebagai tergugat semu. 3. Tenggang Waktu Mengajukan Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi ditentukan dalam Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 yang berbunyi : “Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon”. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut, tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi adalah 14 hari terhitung sejak putusan 60 mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan diberitahukan. Jika pasal 12 diteliti lebih lanjut, tenggang waktu yang diatur didalamnya hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi yang disebut dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yakni tenggang waktu mengenai rehabilitasi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan kesidang pengadilan. Sedang tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, tidak ada disinggung dalam Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983. Alasannya, setiap putusan pengadilan yang berupa pembebsaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantukan rehabilitasi. Itu sebabnya tidak ada tenggang waktu untuk itu. Pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak yang wajib diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak perlu diminta dan diajukan terdakwa. Berarti tidak ada tenggang waktunya. Kemudian rehabilitasi yang diberikan dan dicantumkan dalam putusan tersebut, baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. Umpamanya, Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa, Maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan. Sekiranya terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri itu dimintakan kasasi oleh jaksa, dengan sendirinya pemberian rehabilitasi belum 61 berlaku. Pemberian rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut baru sah dan mengikat, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, yang terjadi dalam kenyataan praktek peradilan, sering putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, tidak mencantumkan amar pemberian rehabilitasi. Banyak putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi, tidak konsekuen mengikuti ketentuan Pasal 97 ayat (2). Sebagai bukti beberapa putusan Mahkamah Agung yang berisi putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, tidak dicantumkan pemberian rehabilitasi dalam amar putusan. Akibatnya, kalau terdakwa berkehendak memperoleh rehabilitasi, terpaksa harus mengajukannya lagi kepengadilan. Misalnya putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1983 Reg. No. 597 K/Pid/1982. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada terdakwa atas kesalahan membantu melakukan kejahatan pemalsuan surat dan mempergunakan surat palsu. Dalam tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan Mahkamah Agung atas alasan apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena mengenai cap dan pembuatan stempel palsu adalah perbuatan orang lain, bukan atas suruhan terdakwa. Oleh karena itu, apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah, dan meyakinkan. Namun dalam amar putusan pembebasan tidak dicantumkan rehabilitasi kepada terdakwa. Demikian pula putusan Mahkamah Agung tanggal 6 juni 1983, Reg. No. 298 K/Pid/1982. Dalam perkara ini Pengadilan Negeri 62 Gunung Sitoli menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa-terdakwa atas kesalahan melakukan perkosaan. Pada tingkat banding, putusan dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dengan perbaikan sepanjang mengenai beratnya hukuman seperti yang dapat dilihat dalam putusannya tanggal 19 Desember 1981, Reg. No. 158/1981. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membetalkan putusan dimaksud berdasar pertimbangan, tidak ada seorang saksi pun atau alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan para terdakwa, karena itu para terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Disini pun Mahkamah Agung tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi kepada para terdakwa, sehingga jelas pembebasan ini tidak konsekuen mengikuti ketentuan Pasal 97 ayat (2) KUHAP. Demikian seterusnya dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Agustus 1983, Reg. No. 1982 K/Pid/1982 dan putusan tanggal 15 Agustus 1983 Reg. No. 932 K/Pid/1982. Dalam putusan-putusan pembebasan ini ternyata Mahkamah Agung tidak mencantumkan amar pemberian rehabilitasi kepada terdakwa. 4. Redaksi Amar Putusan Bunyi redaksi pemberian Rehabilitasi, diatur dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983. Perumusan redaksi ini dalam peraturan, memperlancar pelayanan pemberian rehabilitasi. Sebab dengan ditentukan rumusan standar, dalam pemberian rehabilitasi, baik pemohon maupun pengadilan tidak memperdebatkan rumusan redaksi. Pengadilan dan pemohon terikat, dan harus tunduk menerima rumusan yang ditentukan dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, tujuan utama pemberian rehabilitasi sebagai upaya hukum yang sah untuk memulihkan nama baik serta 63 harkat martabat seseorang kedalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan ditangkap atau ditahan atau sebelum yang bersangkutan di periksa di pengadilan. Pemberian rehabilitasi didasarkan atas putusan pengadilan atau Praperadilan, yang rumusan redaksinya telah ditentukan dalam Pasal 14. Pasal ini memuat dua jenis redaksi, namun isi yang terkandung adalah sama. Dasar pembedaan rumusan itu dalam dua redaksi, semata-mata didasarkan atas alasan perbedaan status pemohon serta instansi yang memeriksa permintaan rehabilitasi yang diajukan : - Yang memeriksanya pengadilan, Apabila yang berwenang memberikan adalah pengadilan atas alasan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP, amar putusan pemberian rehabilitasi berbunyi : “Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya”. - Yang memeriksa Praperadilan, Apabila permintaan rehabilitasi didasarkan atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang berwenang memeriksa permintaan rehabilitasi adalah praperadilan, berdasar Pasal 97 ayat (3), bunyi amar penetapan Praperadilan dalam pemberian rehabilitasi: “Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya”. Dari kedua bunyi redaksi yang tertera diatas, pada hakikatnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, hanya terdapat perbedaan satu kata saja, yakni 64 perkataan “terdakwa” pada redaksi yang pertama, diubah dengan perkataan “pemohon” pada redaksi yang kedua. B. Rehabilitasi Tersangka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Rumusan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam hukum terdapat suatu asas penting yang dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generali, yang mana secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali), maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam suatu tindak pidana khusus secara jelas dirumuskan dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang berbunyi : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Menurut Bagir Manan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis, yaitu: 65 1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; 2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuanketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang); 3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis45. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sama-sama termasuk lingkungan hukum pidana. Sebagaimana pemaparan mengenai hak rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa dalam rumusan Pasal 1 Butir 23 jo. Pasal 97 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang merupakan suatu produk lex specialis, juga mengatur tentang pemberian hak rehabilitasi bagi tersangka/terdakwa. Berbeda dengan pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dirumuskan dalam Pasal 37 Ayat 1, sebagai berikut : “Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan di putus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. 45 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, hal. 56. 66 Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa rehabilitasi dalam pasal ini adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain termasuk penyembuhan dan pemulihan fisik atau psikis serta perbaikan harta benda. Menurut H. Soeharto, dari ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena yang dapat diberikan hak rehabilitasi menurut undang-undang ini hanya ditujukan terhadap seseorang yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, artinya terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum atau tidak ada upaya hukum lagi. Sedangkan terhadap seseorang yang ditangkap atau ditahan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang mana perkaranya tidak lanjut ke pengadilan, tidak diatur dalam undang-undang ini, sehingga pengaturannya kembali pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP. 1. Kewenangan Memeriksa Dalam pengaturan rehabilitasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hanya terdapat satu instansi yang berwenang memutus permintaan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang berbunyi: ”Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”. Rumusan ini sejalan dengan bunyi Pasal 97 ayat (2) KUHAP. Sedang untuk perkara yang dihentikan ditingkat pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dalam undang-undang ini tidak 67 diatur lebih lanjut, sehingga pengaturannya kembali pada rumusan Pasal 97 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 14 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 yakni dimintakan dan diputus oleh hakim Praperadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa keberlakuan lex specialis derogat legi generali, harus memenuhi kriteria: 1. bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang. 2. bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut46. Apabila pemeriksaan perkara sudah sampai ke tingkat pengadilan, dan dari hasil pemeriksaan pengadilan menjatuhkan: - Putusan pembebasan, dan - Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, maka dalam hal ini, rehabilitasi diberikan pengadilan yang memutusnya. Bertitik tolak dari bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, rehabilitasi berdasar putusan pengadilan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. 46 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 1996. hlm. 16 68 Jadi, menurut ketentuan Pasal 37 ayat (2), jika pengadilan menjatuhkan putusan bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, rehabilitasi tersebut diberikan dan “dicantumkan” sekaligus dalam amar atau diktum putusan pengadilan yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan rumusan dalam Pasal 97 ayat (2) KUHAP. 2. Pengajuan Rehabilitasi Jika kita merujuk pada Pasal 38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, proses pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Menurut H. Soeharto, Ketentuan pasal ini membingungkan dan memberikan ketidakpastian hukum, karena merujuk pada rumusan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, jelas mengatakan bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Hal ini jelas menimbulkan tanda tanya perihal kata “korban” yang dimaksud dalam rumusan Pasal 38 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini. Apakah yang dimaksud adalah tersangka yang mengajukannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang perkaranya belum sampai pada tahap pengadilan, ataukah terdakwa yang mengajukannya kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas dasar putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun bisa jadi korban yang dimaksud dalam pasal ini adalah rehabilitasi fisik dan psikis korban dari tindak pidana terorisme. Sayangnya, Undang-Undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait korban yang dimaksud dalam rumusan Pasal 38 ayat (3) tersebut. Adapun dalam PP No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, 69 Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, hanya mengatur perihal perlindungan korban terorisme yang berstatus saksi, dan tidak membahas pengajuan rehabilitasi sebagaimana yang dirumuskan Pasal 38 ayat (3) tersebut. Praktis, tidak adanya peraturan pelaksana undang-undang ini mengakibatkan perlunya penjelasan lebih lanjut terkait pengertian korban yang dimaksud dalam undang-undang ini. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan perlunya penambahan pengertian korban dalam rancangan undang-undang terorisme yang baru. Lebih lanjut di katakan bahwa “undang-undang pemberantasan terorisme tahun 2003 dan RUU Pemberantasan terorisme 2016, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi pun tidak berupaya diperjelas (pasal 36-42). Padahal dalam perkembangan terbaru, respon Negara atas Korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendasi pelapor khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi UU pemberantasan Terorisme tersebut”. Makna korban sejatinya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam konteks terorisme, menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam jurnal yang diterbitkannya terkait usulan rekomendasi RUU Pemberantasan Terorisme, memaparkan bahwa korban dalam undang-undang 70 terorisme ada 2 jenis, yaitu korban akibat tindak pidana, dan korban kesalahan prosedural. Korban akibat tindak pidana memiliki hak memperoleh kompensasi dan restitusi. Sedangkan korban kesalahan prosedural, memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi. Jika korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah terdakwa yang di kategorikan sebagai korban kesalahan prosedural sehingga perlu mengajukan permintaan rehabilitasi kepada menteri Kehakiman dan HAM, maka jelaslah pendapat H. Soeharto yang mengatakan Pasal ini membingungkan, karena disisi lain, Pasal 37 jelas mengatakan bahwa rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Selain itu, akan berimplikasi pada tenggang waktu mengajukan rehabilitasi yang baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, samasama tidak mengatur perihal tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 3. Tenggang Waktu Mengajukan Oleh karena tenggang waktu pengajuan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, maka pengaturannya merujuk kepada Pasal 97 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983. Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi dalam Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983 berbunyi : “Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada pengadilan 71 yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon”. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal tersebut, tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi adalah 14 hari terhitung sejak putusan mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan diberitahukan. Jika pasal 12 diteliti lebih lanjut, tenggang waktu yang diatur didalamnya hanya berkenaan dengan permintaan rehabilitasi yang disebut dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yakni tenggang waktu mengenai rehabilitasi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, yang perkaranya tidak diajukan kesidang pengadilan. Sedang tenggang waktu atas alasan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP, tidak ada disinggung dalam Pasal 12 PP No. 27 Tahun 1983. Alasannya, setiap putusan pengadilan yang berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus sekaligus memberikan dan mencantumkan rehabilitasi. Itu sebabnya tidak ada tenggang waktu untuk itu. Sejalan dengan alasan itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap bahwa Pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, merupakan hak yang wajib diberikan dan dicantumkan sekaligus secara langsung dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian, rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak perlu diminta dan diajukan terdakwa. Berarti tidak ada tenggang waktunya. Kemudian rehabilitasi yang diberikan dan 72 dicantumkan dalam putusan tersebut, baru dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat terhitung sejak putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Redaksi Amar Putusan Bunyi redaksi pemberian Rehabilitasi, mengikuti rumusan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 1983. Hal ini dikarenakan tidak diaturnya secara khusus dalam peraturan pelaksananya tersendiri. Perumusan redaksi ini dalam peraturan, memperlancar pelayanan pemberian rehabilitasi. Sebab dengan ditentukan rumusan standar, dalam pemberian rehabilitasi, baik pemohon maupun pengadilan tidak memperdebatkan rumusan redaksi. Pengadilan dan pemohon terikat, dan harus tunduk menerima rumusan yang ditentukan dalam Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983. 5. Kelalaian Pemberian Rehabilitasi Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dalam prakteknya, sering terjadi kelalaian mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pun dalam kasus terorisme. Padahal pemberian rehabilitasi dalam putusan yang demikian merupakan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa. Hal ini sesuai dengan salah satu asas yang menjadi tujuan KUHAP yakni disamping KUHAP bertujuan melindungi kepentingan umum, sekaligus harus melindungi hak asasi terdakwa. Dengan demikian pemberian dan pencantuman amar rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum merupakan “kewajiban” bagi pengadilan dalam semua tingkat, mulai dari tingkat pertama, banding, dan kasasi. 73 Oleh karena pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntuan hukum merupakan perlindungan terhadap hak asasi terdakwa, pencantuman dalam putusan yang demikian adalah bersifat “imperatif”. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 37 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 bersifat memaksa bagi semua tingkat pemeriksaan untuk mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sesuai dengan redaksi rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983. Oleh karena itu, putusan yang lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum memperkosa hak asasi terdakwa serta sekaligus pula mengandung kesalahan penerapan hukum, selayaknya perkosaan dan kekeliruan itu dapat diperbaiki apabila putusan yang bersangkutan sudah sempat memperoleh kekuatan hukum tetap. Sekiranya putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan terhadap putusan diminta lagi upaya kasasi, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki kelalaian dalam tingkat kasasi. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Umpamanya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tanpa mencantumkan pemberian rehabilitasi kepada terdakwa. Jaksa tidak mengajukan kasasi, berarti putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal putusan jelas mengandung perkosaan dan kesalahan penerapan hukum karena lalai mencantumkan pemberian rehabilitasi. 74 Hal yang seperti ini bisa juga terjadi pada tingkat banding. Misalnya, Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atas putusan tersebut terdakwa atau jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tanpa mencantumkan pemberian rehabilitasi kepada terdakwa. Terhadap putusan itu jaksa tidak mengajukan kasasi, sehingga putusan yang mengandung perkosaan dan kekeliruan penerapan hukum itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian pula misalnya hal ini terjadi pada tingkat kasasi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dalam kasus yang demikian masih ada upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi. Menurut M. Yahya Harahap, jika “bertitik tolak dari ketentuan undangundang dan peraturan, sama sekali tidak ada diatur tata cara memperoleh rehabilitasi dalam kasus- kasus tersebut. Akibatnya, jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan “tertutup” hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi”. Berarti atas kelalaian pengadilan menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 97 ayat (2) KUHAP, hilang dan lenyaplah hak terdakwa memperoleh rehabilitasi. Tentu hal ini tidak patut dan tidak adil. Sebab keteledoran dan kelalaian pengadilan dijadikan alasan untuk pembenaran perkosaan terhadap hak asasi terdakwa. Hal ini tidak adil, dan sangat merugikan kepentingan terdakwa. Oleh karena itu praktek hukum mesti menciptakan upaya hukum yang praktis dan memadai demi untuk memulihkan hak dan perlindungan kepentingan terdakwa. 75 Praktek hukum mesti membuka jalan yang memberi hak bagi terdakwa untuk memperbaiki kelalaian pengadilan, pemberian hukum ini sangat prinsipil sebagai sarana memperbaiki kesalahan yang dilakukan pengadilan sendiri. Sehubungan dengan banyaknya putusan bebas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi tidak mencantumkan pemberian rehabilitasi, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA No. 11 Tahun 1985”). Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan. Meneliti bunyi SEMA No. 11 Tahun 1985, terdapat kata “dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri”, kemudian dilanjutkan dengan kalimat “memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan”, yang notabennya jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983 seharusnya ditujukan kepada tersangka dalam Praperadilan, yang mana akan terasa rancu jika di gunakan kepada terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Sejalan dengan SEMA No. 11 Tahun 1985, menurut M. Yahya Harahap, memang jika bertitik tolak dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan, 76 “tertutup” hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi. Akan tetapi, lebih lanjut ia katakan bahwa akan lebih logis jika ditempuh upaya hukum yang praktis dan sederhana, dengan cara pendekatan “konsistensi” terhadap ketentuan dan tata cara dan proses pemeriksaan rehabilitasi yang diatur bagi Praperadilan yakni tata cara permintaan rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 97 ayat (3) jo. Pasal 77 huruf b, jo. Pasal 82, dan jo. Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Artinya, tata cara untuk mengajukan rehabilitasi yang dilalaikan dapat menggunakan tata cara permintaan rehabiitasi tersangka dalam Praperadilan dengan dasar upaya hukum praktis dan sederhana dan pendekatan konsistensi. C. Usulan Rekomendasi Atas Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2016 Pada akhir Januari 2016, Pemerintah kemudian memfinalkan RUU Pemberantasan Terorisme, yang mana pada bulan Februari 2016 pemerintah menyerahkan naskah rancangan tersebut kepada DPR secara terbatas. Meskipun revisi Undang-Undang Antiteror tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 (Prolegnas), Dalam naskah tersebut beberapa muatan baru dalam RUU dirumuskan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muatan Perluasan tindak pidana terorisme Terorisme anak Penahanan Penangkapan Penelitian berkas perkara Alat bukti Pemeriksaan saksi Perlindungan aparat penegak hukum Penanggulangan dan deradikalisasi Ketentuan Peralihan Pasal 6, 10 A, 12 A, 12 B, 13 A, 14, 15 16A 25 28 28A 31 32 33 43A 43B 43 C, 46 A 77 Sumber: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berdasarkan RUU versi 29 Januari 2016 Menurut lembaga Aliansi Indonesia Damai (AIDA), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, seluruh muatan dalam revisi tersebut ternyata tidak menyentuh dan tidak menyinggung secara detail dan konkret baik mengenai hak korban terorisme, maupun hak tersangka atau hak terdakwa terorisme yang berkaitan dengan hak memperoleh rehabilitasi, sehingga tertangkap kesan jika RUU ini lebih menyoroti soal pelaku terorisme, baik dari segi hukum materil, hukum acara bahkan soal pemidanaan sampai dengan program deradikalisasi. Hal ini menjadi keprihatinan karena dalam praktiknya hak tersangka terorisme yang berkaitan dengan pemenuhan hak rehabilitasi di Indonesia dalam situasi yang minim perhatian, yang dikarenakan singkatnya pengaturan mengenai hak rehabilitasi, dan juga dikerenakan tidak adanya peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini, hingga saat ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa mengenai akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum sendiri dalam pemberantasan terorisme, RUU versi 2016 ini masih belum membahas secara spesifik bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam melakukan operasi pemberantasan terorisme. Tidak adanya mekanisme akuntabilitas tercermin pada saat dilakukan pencegahan, penangkapan, dan penahanan terhadap terduga teroris. Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak hanya satu dua kali terjadi. Penyiksaan selama proses pemeriksaan bahkan berakibat pada kematian 78 seperti kasus Siyono kepada yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, juga bukan hal baru. Data yang dimiliki Komnas HAM, disebutkan bahwa sebanyak 112 orang yang diduga melakukan terorisme, dari periode 2004 – 2015, tewas tanpa menjalani proses peradilan terlebih dahulu, dan tidak adanya data perihal pemberian rehabilitasi bagi tersangka, keluarganya, maupun kuasanya. Sedangkan kasus-kasus terorisme yang telah masuk dalam proses peradilan pidana dan telah diputus bebas maupun lepas di Pengadilan Negeri, dalam Amar Putusan pengadilan tersebut tidak pernah dicantumkan baik mengenai kompensasi, restitusi, dan juga rehabilitasi yang menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Hanya dalam kasus JW Marriot saja, hakim mengamanatkan pemberian kompensasi bagi korban, sisanya kompensasi kepada korban di kasus terorisme lain, sama sekali tidak ada, termasuk juga masalah pemberian hak rehabilitasi. Seperti dalam kasus Ruqayyah Binti Husen Luceno Alias Fatimah Zahra Anis yang tidak terbukti kasus terorisme, akan tetapi dalam kasus imigrasi, juga seperti dalam kasus Al Khelaiw Ali Abdullah alias Ali yang juga tidak terbukti dalam kasus terorisme, Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 37 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo. Pasal 97 ayat (2) KUHAP, jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 yang mengharuskan rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Untuk itu, sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dan SEMA No. 11 Tahun 1985, ada baiknya jika terdakwa yang menginginkan pemberian 79 rehabilitasi atas dirinya, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama, yang mana Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan, sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan rehabilitasi tersangka dalam Praperadilan. Akan tetapi, menurut hemat penulis, akan lebih baik jika segera dibuatkan suatu aturan yang lebih memadai, agar lebih memiliki kepastian hukum, dan terpenuhinya hak asasi terdakwa. BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dari rumusan masalah yang dibahas dapat ditarik simpulan bahwa : Rumusan Pasal 37 mengenai hak memperoleh rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki beberapa perbedaan dengan rumusan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Utamanya terkait hal-hal yang berkaitan dengan aturan mengenai kewenangan memeriksa rehabilitasi, pengajuan rehabilitasi, tenggang waktu mengajukan, sampai pada aturan mengenai cara memperoleh rehabilitasi yang dilalaikan oleh pengadilan. B. Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah : 1. Agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat dijadikan landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan baik secara substansial maupun secara operasional. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyangkut masalah kompensasi, restitusi, dan utamanya hak rehabilitasi, harus ada hukum acaranya sendiri. 80 81 DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku Arief, Barda Nawawi. 2011. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana. Bagir Manan. 2007. Hukum Positif Indonesia. Jakarta: Kencana. Bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang Anti Teror Tahun 2000. Darmasetia Soerjadi, Trimoelja. 2004. Terorisme, perang global, dan masa depan demokrasi. Jakarta: Matapena. Fuady, Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern(Rechtstaat). Bandung: Refika Aditama. __________, Laura L, Sylvia. 2015. Hak Asasi Tersangka Pidana. Jakarta: Kencana. Lubis, M.Sofyan. 2010. Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Mahmud Marzuki, Peter. 2015. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Mertokusumo, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty. Muhammad Mustofa, Muhammad.2002. Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III. Rosa Nasution, Aulia. 2012. Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. Jakarta: Kencana. Soeharto, H. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme. Bandung: PT. Refika Aditama. Sieghart, Paul. 1986. The Lawful Right of Mankind (An Introduction to The International Legal Code of Human Rights). Oxford University Press. 82 Wahid, Abdul, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama (HAM dan Agama). Bandung: PT. Refika Aditama. Yahya Harahap, M. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Grafika. B. Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Universal Declaration Of Human Rights 1948. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Sumber Internet Buckeye State Blog, A History Of The Right to Counsel, Posted : 26 September 2007. Loudewijk F. Paulus, “Terorisme”, http://buletinlitbang.dephan.go.id. Https://www.komnasham.go.id/siaran-pers/pers-rilis-terkait-tanah-runtuh. Https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia, diakses pad 20 Mei 2016 Http://ensiklopediasli.blogspot.co.id/2016/01/aksi-terorisme-di-indonesia. html Sumber: Harian KOMPAS edisi 8 Oktober 2005.