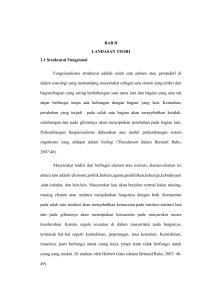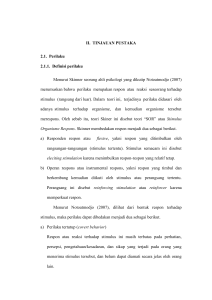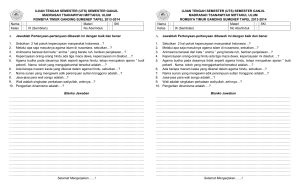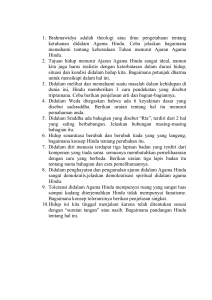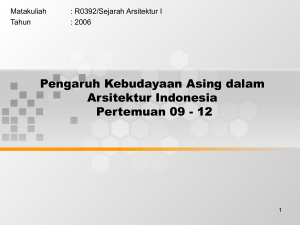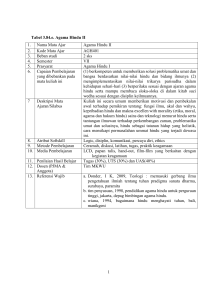Sistem dan Jenis Upacara Keagamaan Terkait dengan Aktivitas
advertisement

Sistem dan Jenis Upacara Keagamaan Terkait dengan Aktivitas Subak di Bali Oleh I Ketut Suda Fakultas Pendidikan Agama dan Seni, Universitas Hindu Indonesia, Denpasar e-mail: [email protected] Dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, berkembang unit-unit kesatuan sosial yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun unit-unit kesatuan sosial tersebut meliputi, desa, banjar, sekehe, dan organisasi subak. Berbicara soal subak dapat mengacu pada ketentuan Perda Bali No.02/PD/DPRD/1972 yang mengatakan ‘’subak merupakan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari satu sumber air dalam suatu daerah’’. Batasan ini dikritisi Pitana (1997) dengan mengatakan bahwa subak sebagaimana dimuat pada Perda Bali tersebut, belum sepenuhnya tepat, sebab pada kenyataannya satu sumber air bisa dimanfaatkan oleh beberapa subak, dan sebaliknya bisa jadi satu subak mendapatkan air dari beberapa sumber. Ada lagi sumber lainnya mengatakan bahwa ‘’subak adalah organisasi petani di Bali yang didasarkan pada hukum atau aturan tradisional, seperti aturan sosio-agraris, agama, ekonomi, dan dinamika alam (Anon,2002). Apapun batasan tentang subak yang telah dikemukan di atas, tidak akan dibahas secara lebih rinci dalam kajian ini, sebab tulisan ini akan mencoba menajamkan perhatian pada persoalan sistem dan jenis upacara keagamaan yang berkaitan dengan aktivitas subak di Bali. Dari hasil studi yang dilakukan Tim peneliti FFI (Fauna & Flora Internasional) tentang Jasa Lingkungan Budaya Sistem Subak di Bali (2015) dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Subak Jati Luih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, ditemukan setidaknya ada 13 jenis upacara yang dilakukan oleh para petani di lingkungan subak, baik yang berada di kawasan Warirsan Budaya Dunia (WBD) maupun yang berada di luar kawasan WBD. Adapun ketiga belas jenis upacara tersebut antara lain : (1) upacara magpag toya; (2) nuasain (ngerastiti pangwiwit nandur); (3) ngerasakin (mecaru di carik); (4) nyepi di carik I (selama 3 hari setelah padi berumur 1 bulan); (5) nyepi di carik II (selama 2 hari setelah padi berumur 2 bulan); (6) nyepi di carik III (selama 1 hari setelah padi berumur 3 bulan); (7) upacara mohon air suci ke pekendungan; (8) upacara mohon air suci ke pura bedugul; (9) upacara ngusaba; (10) upacara nganyarin; (11) mantenin padi di lumbung; (12) upacara nuunang tegteg; dan (13) upacara ngutang tain asep. Hal menarik dari semua jenis dan sistem upacara yang dilakukan oleh para petani subak di Bali terkait dengan aktivitas pertanian yang digelutinya adalah, hampir semua informan yang diwawancarai menyatakan tidak memahami makna, baik simbolik maupun filosofis dari pelaksanaan upacara tersebut. Namun, mereka tetap melaksanakannya dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh rasa bhakti. Kondisi ini bisa terjadi, salah satunya disebabkan oleh sistem pengetahuan masyarakat Bali terkait dengan pelaksanaan upacara keagamaan cenderung lebih bersandar pada tradisi mule keto (memang begitu) dibandingkan dengan tradisi nyastra (melaksanakan tradisi tertentu atas dasar teks-teks sastra). Akibatnya, banyak tradisi, baik dalam bentuk sistem ideel, seperti: gagasan, nilai, dan norma-norma, yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Bali; sistem sosial, seperti berbagai bentuk perilaku manusia berpola, termasuk sistem pelaksanaan upacara keagamaan; maupun dalam bentuk berbagai artepak yang dihasilkan manusia Bali, kurang dipahami maknanya oleh masyarakat Bali sendiri. Padahal berdasarkan ajaran Tatwa (filsafat agama) secara umum dapat dipahami makna persembahan yang digunakan dalam proses upacara keagamaan Hindu dengan mengacu pada filsafat Ketuhanan yang mengatakan bahwa Tuhan itu bersifat Acintya (tak terpikirkan); Tuhan bersifat impersonal god (tak berwujud); Tuhan bersifat transendent (sangat luhur); dan Tuhan bersifat Wyapi Wyapaka (Tuhan memenuhi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini (Suja, 1999:67). Berangkat dari berbagai kemuliaan Tuhan tersebut, dan keterbatasan manusia biasa dalam berkomunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa, inilah kemudian masyarakat Hindu di Bali, mempersonifikasikan perwujudan Tuhan itu melalui berbagai bentuk sesajen dan berbagai macam upacara keagamaan yang pada hakikatnya bermakna sebagai upaya untuk memudahan manusia berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Hal ini didasarkan atas wahyu Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Bhagavadgita, Bhg. IX.26 yang berbunyi: ‘’ptram puspam phalam toyam Yo me bhaktya praycchati Tad aham bhaktyupahrtam Asnami prayatat manah’’ Bhg.IX.26 Artinya: Siapa yang sujud kepada-Ku, dengan persembahan setangkai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, atau seteguk air, Aku terima sebagai bhakti pesembahan dari orang yang berhati suci. Berangkat dari isi sloka di atas, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa sarana persembahan yang digunakan oleh umat Hindu untuk berkomunikasi dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa dalam berbagai manifestasinya, secara garis besar hanya terdiri atas empat unsur, yakni daun-daunan, bunga-bungaan, biji-bijian, dan air. Akan tetapi mengingat dalam praktiknya, agama Hindu di Bali banyak dipengaruhi oleh faktor adat dan budaya, maka penggunaan sarana persembahan yang dalam istilah Balinya sering disebut upakara ini, kadang-kadang dikembangkan sesuai dengan prinsip desa, kala, dan patra (tempat, waktu, dan keadaan), sehingga keberadaannya, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainya. Jadi, apapun bentuk sesajen yang dipersembahkan oleh masyarakat Bali kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, pada hakikatnya merupakan perwujudan rasa bhaktinya kepada Tuha Yang Maha Esa dan Betara-Betari junjungannya, dan sekaligus sebagai simbolisasi dari cara masyarakat Bali untuk berkomunikasi dengan Tuhannya.