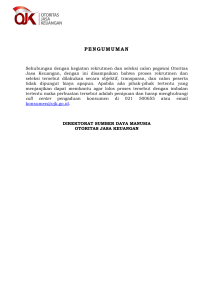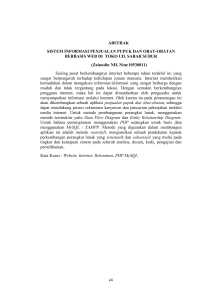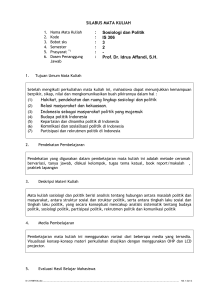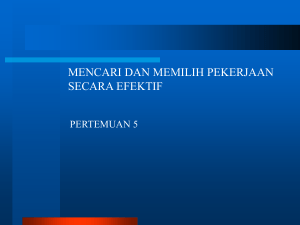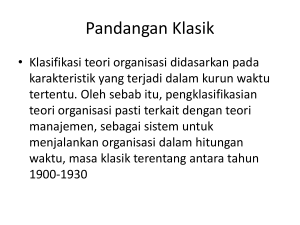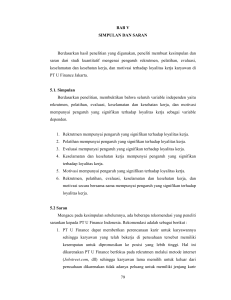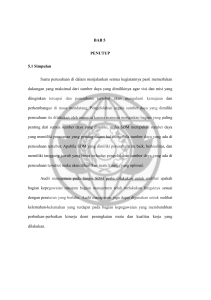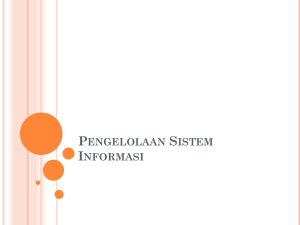Draf `Final` TESIS
advertisement

BAB I PENDAHULUAN "The successes of modern democratic government have to be considered the successes of government bureaucracies as well."(Douglas J. Amy) A. Problematika Birokrasi dan Tuntutan Agenda Reformasi Penelitian ini membahas mengenai bekerjanya faktor internal dan eksternal dalam mekanisme pengisian jabatan struktural berbasis kompetensi di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Pengisian jabatan struktural di dunia birokrasi bukanlah sebuah proses yang bekerja di ruang vakum dan imun dari berbagai pengaruhinstitusional normatif, sosio-politik, sosio-kultural dan sosio-ekonomibaik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal.Sulit untuk dipungkiri bahwa terdapat banyak kemungkinan faktor yang berpotensi mempengaruhi terciptanya kondisi ideal birokrasi berbasis merit system, di antaranya adalah faktor legal- formal, faktor politis, faktor nepotisme, faktor primordialisme dan budaya patrimonial.Menempatkan birokrasi pada wilayah steril yang sepenuhnya terbebas dari pengaruh beragam faktor tersebut boleh dikatakan mustahil. Birokrasi adalah sebuah sistem terstruktur dari bangun kekuasaan berisi aktor-aktor yang terbagi menurut area dan jenjang hirarkis. Bangun kekuasaan tersebut, puncaknya ditempati oleh aktor penguasa tunggal (executive ascendancy) yang memposisikan diri sebagai super ordinat terhadap aktor lainnya, yakni para eksekutif karir. Penguasa tunggal dengan klaim “hak prerogatifnya” adalah satu-satunya aktor paling berkuasa dalam menentukan nasib jabatan birokrasi para eksekutif. Penguasa tunggal ini tentunya 1 merupakan pribadi humanistik dengan segala motif dan kepentingan individualnya, pun ia adalah pribadi politik (homo politicus). Birokrasi secara natural memang berwajah ganda, di satu sisi ia dituntut untuk menjadi entitas netral mengatasi semua kepentingan partikular, namun pada saat yang bersamaan ia dituntut pula untuk mampu menerjemahkan visimisi dan agenda dari sang penguasa tunggal. Birokrasi adalah tempat berkumpulnya para eksekutor peraturan perundang- undangan yang notabene merupakan produk dari sebuah proses politik. Persoalan klasik birokrasi hingga saat ini adalah kebutuhan birokrasi untuk berjuang keluar dari zona stigmatisasi negatif yang dialamatkan kepadanya. Masyarakat menganggap bahwa birokrasi Indonesia pada umumnya dan birokrasi daerah khususnya masih terkungkung dalam kondisi patologis (bureau-pathology) seperti kecenderungan adanya inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Bila kita menengok ke belakang dan sekedar mengambil potongan fragmentasi sejarah dengan memulai titik berangkat pengamatan dari birokrasi orde baru, maka keburukan birokrasi itu pun sudah jelas terlihat. Bagaimana tidak, birokrasi secara struktural dipakai untuk mendukung pemenangan partai politik pemerintah melalui praktek diskriminasi dan penyalahgunaan fasilitas, program maupun dana negara. Birokrasi adalah alat rejim status quo untuk melakukan kooptasi kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan dan memperluas kekuasaan monolitik. Jati diri birokrasi sebagai lembaga publik yang netral dan adil hanyalah sekedar harapan. Sejumlah kenyataan tersebut, 2 sekali lagi memperlihatkan wajah buram birokrasi sebagai salah satu bagian dari sistem yang turut menghambat berkembangnya keadilan dan demokrasi. Kondisi kepegawaian yang ada di birokrasi sekarang memiliki pertalian sejarah dengan kebijakan kepegawaian di masa lalu. Proses penataan kepegawaian mulai dari rekrutmen, pembinaan, dan pensiun banyak diwarnai aroma politik. Pemerintah saat itu membutuhkan pegawai karena didorong oleh keinginan memperbanyak jumlah sehingga semakin banyak pegawai yang bisa dibina untuk mendukung kekuatan golongan politik yang berkuasa. Menurut Eko Prasojo, yang menjadi akar permasalahan buruknya kondisi birokrasi di Indonesia hingga saat ini, di samping karena adanya pengaruh perkembangan lingkungan eksternal juga disebabkan oleh persoalan sistem internal kepegawaian terkait dengan fungsi dan profesionalismenya. Persoalan itu meliputi: (a) rekrutmen pegawai, (b) penggajian dan reward, (c) pengukuran kinerja, (d) promosi jabatan, (e) pengawasan. Kegagalan pemerintah melakukan reformasi terhadap subsistem tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kemampuan birokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta melahirkan para birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral. (Prasojo, 2009 : 7) Pendapat tentang adanya kerusakan moral para birokrat sebagaimana tersebut di atas, dikuatkan dengan hasil survei PERC yang berbasis di Hongkong tentang persepsi ekspatriat terhadap kinerja birokrasi publik di Indonesia. Hasil survei PERC yang diterbitkan dalam jurnal Transparency Internasional Indonesia (2010), menyatakan bahwa kondisi birokrasi Indonesia termasuk salah satu yang terburuk di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 3 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat terendah setelah Kamboja, dengan skor 9.27 (0: terbersih; 10: terkorup). Bahkan di antara negara ASEAN, Indonesia hampir selalu mendapatkan peringkat terkorup sejak 1997 hingga 2010. (Dwiyanto, 2011 : 309) Oleh karenanya, maka reformasi birokrasi menjadi kata kunci guna mengatasi persoalan tersebut. Ada banyak hal yang perlu disikapi oleh birokrasi terkait perubahan lingkungan eksternal dengan melaksanakan agenda pembenahan internal. Setidaknya terdapat tiga area pembenahan internal birokrasi yang diamanatkan melalui agenda reformasi birokrasi, yakni pembenahan pada aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Gagasan utama dalam rangka mengelola reformasi birokrasi adalah terjadinya perbaikan yang sistematis, komprehensif dan cepat atas pelayanan yang diberikan kepada publik sehingga publik merasa sangat puas terhadap apa yang telah dan sedang birokrat berikan kepada mereka. Ini berarti, harus terdapat perubahan (change) di tubuh birokrasi berkaitan dengan organisasi maupun sumber daya manusia (Masdar, 2009 : 46-47). Walaupun rencana perubahan sudah matang dan siap dengan prioritas kerja yang jelas, reformasi birokrasi tetap tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh tersedianya SDM yang profesional dan handal. SDM Aparatur yang berkualitas, terutama di level pejabat eselon sangat diperlukan untuk memastikan bahwa mesin birokrasi bisa bekerja secara optimal dalam rangka menjalankan misi utamanya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. 4 Ketersediaaan SDM pejabat yang kompeten dan profesional tentu tidak terlepas dari bagaimana kehandalan mekanisme rekrutmen jabatan yang diberlakukan dalam internal birokrasi untuk memastikan penempatan pegawai yang tepat pada posisi yang tepat. Penyebaran pegawai untuk memenuhi tugas dari masing- masing organisasi tidak memiliki Kejelasan. Berapa jumlah pegawai yang sebenarnya dibutuhkan oleh masing- masing unit organisasi dalam departemen pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak jelas ukuran dan kriterianya. Upaya untuk melakukan penataan kembali (rightsizing) merupakan kebutuhan yang amat mendesak guna melihat seberapa jauh kepegawaian pemerintah ini bisa berperan dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik. (Thoha, 2005:99) Penempatan pegawai yang tepat berarti ada kesesuaian kompetensi pegawai terhadap jabatan sebagai suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak- haknya dalam satuan organisasi negara (Jeddawi, 2010 : 71). Jabatan yang dimaksud adalah jabatan karir pada struktur organisasi birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh para pegawai yang sudah berstatus PNS.Kenyataan hingga saat ini, penempatan PNS dalam jabatan struktural birokrasi, meskipun telah dijalankan menurut prosedur normatif yang dirancang seideal mungkin, namun belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan akan ketersediaan sosok-sosok pejabat yang dapat membawa birokrasi bergerak ke luar dari zona stigmatisasi negatif. Sejalan dengan itu, dalam salah satu karya tulisannya, Cornelis Lay mengatakan bahwa : “secara normatif birokrasi Indonesia didesain menurut model merit system dengan mengandaikan proses pengangkatan birokrasi 5 dilakukan menurut standar-standar profesional dan non politis. Akan tetapi dalam praktiknya, kriteria pengangkatan birokrat terutama pada tingkat elite birokrasi lebih dekat dengan praktek perkoncoan (patrimonialisme) dan kental dengan pertimbangan politis.” (Lay, 2003 : 59). Untuk menghindari terjadinya tendensi politis terus- menerus dalam mekanisme pengisian jabatan, maka perlu adanya kajian ulang mengenai pola serta sistem rekrutmen pejabat yang ada saat ini sehingga terdapat jaminan bahwa unsur kompetensi dan prestasi kerja merupakan inti utama dari kebijakan rekrutmen tersebut sembari memastikan bahwa setiap PNS yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, bisa memperoleh kesempatan sama dalam hal pengangkatan sebagai pejabat struktural di birokrasi. Gambaran riil mengenai kondisi dari mekanisme pengisian pos jabatan struktural di lingkungan sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah, bisa ditelusuri dari proses yang telah dijalankan selama ini, apakah sudah memberikan ruang kondusif bagi terciptanya struktur peluang dan akses yang sama kepada setiap PNS untuk bisa diangkat dalam jabatan struktural pada level eselon tertentu. Struktur peluang dan kesamaan akses tersebut, diharapkan dapat terlahir dari suatu mekanisme seleksi yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan dan obyektivitas, bukan karena adanya alasan-alasan yang subyektif yang bias kepentingan (interest), seperti faktor nepotisme, primordialisme, patrimonialisme atau beragam motif politis lainnya. Sepengetahuan penulis, sebenarnya telah banyak karya tulis dan hasil penelitian sebelumnya yang mengulas seputar permasalahan pengisian jabatan 6 struktural di birokrasi daerah, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Didimus D. (2004) yang meneliti pengaruh etnisitas dalam penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota Kupang, temuan penelitian menyebutkan bahwa birokrasi daerah yang tidak memiliki sikap netral dengan menjadikan kesamaan etnik sebagai dasar bagi rekrutmen pegawai maupun penempatan para pejabat, merupakan pemicu terjadinya konflik lokal. Selanjutnya adalah penelitian oleh Belo (2008) yang membahas mengenai Strategi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di Sekretariat Dewan Menteri Negara Republik Demokratik Timor-Leste. Hasil studinya berhasil mengungkapkan kondisi di lokus penelitian bahwa kompetensi dan profesionalisme para pejabat yang ada masih rendah, tatakelola administrasi yang buruk serta belum diterapkannya sistem manajemen data administrasi berbasis elektronik. Berikutnya penelitian yang lebih spesifik mengenai rekrutmen pejabat pernah dilakukan oleh Rustam (2011) tentang pelaksanaan prosedur pengangkatan pejabat struktural di lingkungan sekretariat daerah propinsi Sumatera Barat di tinjau dari peran instansi dan Individu terkait. Hasil penelitiannya menemukan fakta bahwa pengangkatan pejabat struktural dilaksanakan secara tertutup di setiap instansi tanpa adanya analisa jabatan yang ideal. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada usaha memberikan pandangan sistematis dan menyeluruh, mengenai mekanisme pengisian jabatan struktural di birokrasi sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah dan analisa terhadap bekerjanya faktor 7 internal dan faktor eksternal yang bersumber dari klaim “hak prerogatif” pejabat politik, dimana kedua faktor ini mempengaruhi hasil dan pelaksanaan mekanisme tersebut. Dengan demikian, menurut hemat kami, kajian ini memiliki signifikansi untuk diteliti lebih jauh. B. Rumusan Masalah Berdasarkan deskripsi singkat pada latar belakang di atas, kami merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai rekrutmen jabatan tersebut dengan mengajukan pertanyaan: Bagaimana bekerjanya faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi mekanisme pengisian jabatan struktural di lingkungan sekretariat daerah propinsi (setdaprop) Kalimantan Tengah? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah : 1. Menganalisa bagaimana mekanisme pengisian jabatan struktural yang dilaksanakan di sekretariat daerah propinsi (setdaprop) Kalimantan Tengah. 2. Memetakan sejumlah faktor baik internalmaupun eksternalsekaligus menjelaskan bagaimana faktor- faktor tersebut bekerja dan potensial mempengaruhi mekanisme pengisian jabatan struktural di sekretariat daerah propinsi (setdaprop) Kalimantan Tengah. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 1. Manfaat Teoritis, yakni memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terkait implikasi nilai- nilai good governancedi 8 level birokrasi daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada publik. 2. Manfaat Praktis, yakni menjadi bahan masukan atau rekomendasi bagi pemerintah guna perbaikan sistem rekrutmen jabatan karir birokrat daerah, termasuk memperkaya perspektif sejumlah stakeholders lainnya untuk dapat ambil bagian dalam mendorong terciptanya kualitas SDM pejabat yang profesional dan kompeten. E. Kerangka Dasar Teori Penelitian ini didasarkan pada sejumlah pilihan teori yang masingmasing kedudukannya berusaha diletakan secara konsisten dalam masalah yang diteliti. Kerangka teori disusun sedemikian rupa yang memuat pokokpokok pemikiran terdahulu dari para ahli untuk menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian disoroti termasuk bagaimana membangun asumsiasumsi. (Nawawi, 1995 : 39-40). Adapun teori-teori yang dipilih sebagai landasan berfikir peneliti dalam menjelaskan dan membingkai argumen mengenai mekanisme pengisian jabatan struktural beserta faktor- faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagaimana paparan berikut ini: 1. Konsepsi Birokrasi Konsep birokrasi lahir sekitar abad 19 yang dicetuskan oleh Max Weber. Definisi birokrasi, menurut bapak birokrasi ini, a clearly defined hierarchy where office holders have very specific functions and apply universalistic rules in a spirit of formalistic impersonality (Frinces, 2008 : 32). Pengertian birokrasi sebagaimana tersebut, mengandung arti yang rasional 9 dimana birokrasi merupakan struktur hirarkis bagi sejumlah pejabat yang melaksanakan tugas serta fungsi khusus berdasarkan aturan-aturan formal yang bersifat impersonalitas. Dari berbagai konsep birokrasi yang banyak ditulis oleh para ahli, setidaknya terminologi birokrasi dapat dikontraskan ke dalam dua kategori: pertama, birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (bureau rationality) seperti terkandung dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy; Kedua, birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau pathology) seperti terkandung dalam pengertian Marxian Bureaucracy. Birokrasi dalam pengertian bureau rationality terungkap dari pemikiran Max Weber tentang konsep tipe ideal birokrasi. Tetapi kritikan tentang seberapa jauh peran birokrasi terhadap kehidupan politik, atau sebaliknya pengaruh politik terhadap birokrasi, kurang dikenal dalam konsep birokrasi Weberian yang hanya menekankan bagaimana seharusnya mesin birokrasi itu secara rasional dijalankan. Namun demikian, David Beetham melihatnya secara berbeda, birokrasi Weberian dalam praktek masih memiliki titik persinggungan dengan persoalan politis. (Ma’arif, 2013:109-111) Tipe ideal birokrasi Weber sebagaimana dirangkum oleh Martin Albrow, memiliki empat ciri utama, yaitu: (1) adanya suatu struktur hirarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi, (2) adanya serangkaian posisi-posisi jabatan, dimana masing- masing memiliki tugas dan tanggungjawab yang tegas, (3) adanya aturan-aturan, regulasiregulasi, serta standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan 10 tingkah laku para anggotanya, (4) adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat dan dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi berdasarkan pada kualifikasi dan penampilan. (Santoso, 1997:18). Konsep Weber tentang tipe ideal birokrasi dapat ditelusuri akarnya dari pandangan filsafat Hegel yang melihat negara sebagai suatu elemen netral yang seolah-olah terpisah dari kehidupan masing- masing individu warga masyarakat. Menurut Hegel, kalau warga sebuah negara dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka akan terjadi kekacauan karena masing- masing warga akan memperjuangkan kepentingan subyektifnya melawan kepentingan subyektif warga lainnya (homo homini lupus). Ini adalah tesa dan antitesa yang sintesanya ditemui dalam perwujudan lembaga negara. Negara bagi Hegel merupakan penjelmaan kepentingan umum masyarakat. Kepentingan umum ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing di luar individu tiap-tiap warga negara, melainkan juga adalah kepentingan “obyektif” warga itu sendiri. Dengan mengikuti kepentingan umum, berarti warga patuh pada negara, meskipun sebenarnya warga ini sedang melawan kepentingan personalnya yang subyektif. Hegel mengatakan: “negara merupakan penjelmaan dari kebebasan rasional yang menyatakan dan mengenali dirinya dalam bentuk yang kongkrit dan obyektif”. Dengan demikian negara merupakan sebuah lembaga yang mengatasi dan lebih sempurna dari masyarakat. Kesempurnaan dan kekuatan negara terletak di dalam kesatuan dari tujuannya yang universal daripada kepentingan khusus dari masing- masing warga. Di dalam kenyataan bahwa 11 para warga punya kewajiban-kewajiban terhadap negara dengan hak- hak yang mereka peroleh sebagai warga dari negara tersebut. (ibid :15) Berdasarkan uraian di atas, nampaknya Hegel beranggapan bahwa negara secara apriori melayani kepentingan umum, karena ia merupakan sintesis dari pertentangan-pertentangan individu yang subyektif dan tidak rasional. Pada tataran realitas, berbagai kebijaksanaan negara yang ada seringkali hanya menguntungkan sekelompok orang dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya struktur yang menjembatani antara the state yang merefleksikan kepentingan umum dan civil society yang terdiri dari pelbagai kepentingan khusus dalam masyarakat. Inilah inti dari konsep Hegelian Bureaucracy. Pendapat Hegel tersebut dibantah oleh Karl Marx. Bagi Marx, negara hanyalah alat dari kelas yang berkuasa yakni kalangan bangsawan di negara feodal dan kaum pemilik modal di negara kapitalis. Marx melontarkan kritik terhadap pemikiran Hegel yang dianggap abstrak dan hanya bermain dengan logika, namun kemudian ingin memaksakan kesimpulan-kesimpulan dari logika-abstrak tersebut masuk ke dalam kenyataan empiris. Marx beranggapan ada kesalahan metodologis yang dilakukan Hegel. Seharusnya ide diperoleh dan diangkat dari kenyataan empiris, bukan sebaliknya. Karena itu bagi dia, Hegel bukan melahirkan sebuah analisa tentang lembaga-lembaga tersebut. Marx berpendapat, birokrasi adalah alat bagi kaum borjuis dan kapitalis selaku kelas yang berkuasa untuk mengeksploitir kelas proletar. Birokrasi adalah parasit yang eksistensinya menempel pada kelas yang berkuasa dan dipergunakan untuk menghisap kelas proletar tadi. Karena eksistensi birokrasi 12 terkait dengan “kelas”, maka setelah terjadi revolusi sosial yang memporakporandakan kelas-kelas sosial dan terciptanya classes society, bersamaan dengan itu akan lenyaplah birokrasi. Pandangan Marx tentang birokrasi ini melahirkan model birokrasi Marxian yang memandang birokrasi sebagai bureau pathology. Birokrasi dalam pengertian bureau pathology selalu dikaitkan dengan kelambanan kerja dan beragam prosedur yang begitu berbelit-belit. Seringkali birokrasi dianggap sebagai organisasi yang kejam dengan peraturan anehaneh, sewenang-wenang dan menindas. Sejalan dengan Marx, setidaknya Laski juga mencatat bahwa birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada pada pejabat-pejabat negara yang diselenggarakan sedemikian rupa sehingga merugikan atau membahayakan warga negara. Sementara itu Robert Michels melihat birokrasi sebagai suatu struktur yang mesti mengambil bentuk oligarki. Oleh karenanya, pandangan ini sering disebut sebagai the iron law of oligarkhi. Pengertian lainnya tentang birokrasi juga dicatat oleh Crocier dalam penelitiannya di Perancis, yakni birokrasi sebagai organisasi birokratik merupakan suatu organisasi yang tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan-kesalahannya. (op. cit :18-19) 2. Model Birokrasi Dalam terminologi ilmu politik, setidaknya dikenal empat model birokrasi yang umum ditemui dalam praktik pembangunan di beberapa negara di dunia. Model- model tersebut, yakni model Weberian, Parkinsonian, 13 Jacksonian, dan Orwellian. (Fatah, 1998: 192-195) yang secara lebih rinci keempat model birokrasi tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini: Pertama, Model Weberian digagas oleh Max Weber, seorang tokoh penting yang menjelaskan konsep birokrasi klasik. Model ini menunjuk pada birokrasi sebagai sebuah organisasi yang ber-tipe ideal, yakni : 1) adanya pembagian kerja yang jelas; 2) hierarki kewenangan yang jelas; 3) formalisasi yang tinggi; 4) bersifat tidak pribadi (impersonal); 5) pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan; 6) jejak karir bagi para pegawai; dan 7) kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi. Kedua, Model Parkinsonian merupakan model birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatif birokrasi melalui kebijakan penambahan jumlah anggota (PNS) dan atau mengembangkan struktur organisasi birokrasi untuk meningkatkan kapabilitasnya sebagai alat pembangunan. Di satu sisi, model Parkinsonian dibutuhkan untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan kebutuhan mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang makin bertumpuk, namun di sisi lain juga dipakai sekedar alat bagi kepentingan fragmatis penguasa untuk menampung para pejabat yang dijadikan klien dalam pola hubungan patronase. Ketiga, Model Jacksonian merupakan suatu model dengan menjadikan birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara yang menyingkirkan masyarakat di luar birokrasi dari ruang politik dan pemerintahan. Dalam prakteknya, model ini menggambarkan pergantian rejim penguasa akan diikuti dengan penggantian komposisi pejabat di lingkungan birokrasi yang 14 dipimpinnya dengan cara memasukan para pendukungnya dan menyingkirkan orang –orang dari kubu lawan politiknya. Keempat, Model Orwellian ini merupakan model yang menempatkan birokrasi sebagai alat perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol terhadap masyarakat. Ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, segenap aspek kehidupan masyarakat berada pada wilayah kontrol birokrasi. Sebagaimana fakta yang terjadi selama ini bahwa dalam berbagai masalah di banyak aspek, masyarakat harus meminta ijin kepada birokrasi. 3. Patologi Birokrasi dan Penyebabnya Penyempurnaan birokrasi dalam pemerintahan memerlukan perubahan sikap mendasar dari birokrasi itu sendiri. Sampai saat ini birokrasi mengalami apa yang disebut dengan patologi birokrasi, terutama ditunjukan dengan adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan menghalangi adanya perubahan. Namun, di dalam praktek transformasi birokrasi itu sendiri juga tidak mudah untuk dilaksanakan. Pendekatan yang dipakai dalam pelaksanaan transformasi itu seringkali terlalu bersifat struktural, yaitu sekedar menyasar kepada penataan organisasi dan fungsi- fungsinya saja. Sebenarnya, satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana pembaharuan pada sisi nilai- nilai yang membentuk manusia birokrat. Birokrasi pemerintah dibentuk untuk menjalankan peran pada penyelenggaraan tata pemerintahaan. Dalam mewujudkan fungsinya, birokrasi menghadapi hadangan dan gangguan yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Ibarat sebuah organisme hidup, birokrasi tumbuh dan 15 berkembang untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan jamannya. Dalam berproses itulah, birokrasi seringkali menemui pengganggu yang berpotensi menghambat kinerjanya yaitu penyakit birokrasi, atau yang sering diistilahkan oleh para ahli sebagai patologi birokrasi. Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan lagi hal baru bagi kita, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk sehingga dipersepsikan suatu penyakit (bureau patology) ketimbang citra yang baik atau rasional (bureau rationality), seperti terkandung misalnya, dalam birokrasi Weberian dan Hegelian. Citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dalam aneka-ragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan karena prosedur berbelit-belit atau yang lebih dikenal sebagai efek pita merah (red-tape). Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi Hegelian dan Weberian yang memfungsikan birokasi untuk mengkoordinasikan unsur- unsur dalam proses pemerintahan secara ideal. Apabila ditelusuri lebih jauh, bisa dipahami bahwa gejala patologi dalam birokrasi bersumber dari masalah-masalah pokok, diantaranya: Pertama, persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi dan mewujud dalam tindakan penyalahgunaan jabatan. Kedua, manifestasi perilaku birokrasi yang bersifat disfungsional, seperti perilaku sewenang-wenang dan diskriminatif. 16 Dwiyanto menyatakan bahwa patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabelvariabel lingkungan yang salah” (Dwiyanto, 2011: 63). Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear. Menurut Peter M. Blau dan Marshal W Meyer (2000) maupun Taliziduhu Ndraha (2003), mereka menyebutkan bahwa penyebab patologi birokrasi adalah lemahnya faktor moral, gaji rendah, sistem rekrutmen dan promosi tidak baik, aturan dan mekanisme kerja belum jelas, lemahnya pengawasan dan birokrasi berpotensi politis. Sedangkan menurut JW. Schoorl (1984), patologi birokrasi disebabkan faktor kekurangan administrator yang cakap, besarnya jumlah aparat birokrasi, luasnya tugas pemerintahan, sentralisasi, besarnya kekuasaan birokrasi serta adanya anasir tradisional seperti nepotisme, primordialisme dan patrimonialisme. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor politis dan anasir tradisional sebagai salah satu penyebab terjadinya patologi birokrasi yang dianggap potensial mempengaruhi mekanisme pengisian jabatan struktural di birokrasi daerah, yakni: a. Faktor Politis Birokrasi publik tidak pernah beroperasi dalam ruang hampa, melainkan selalu beroperasi dalam suatu lingkungan sosial, budaya, politik, dan pemerintahan yang kompleks (Dwiyanto, 2011 : 7). Lebih lanjut, menurut Azhari bahwa Marx mengemukakan birokrasi merupakan instrumen yang 17 dipergunakan oleh kelas-kelas dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. (Azhari, 2010 : 83) Birokrasi dan politik ibarat dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan (ibid : 1). Di satu sisi birokrasi dipimpin oleh pejabat politik sebagai pemegang tampuk tertinggi kekuasaan yang selalu berganti secara periodik melalui mekanisme pemilihan umum, sementara di lain sisi, birokrasi dalam strukturnya terdapat pejabat birokrasi karir. Kondisi seperti ini rentan memunculkan hubungan emosional dan personal antara pejabat karir dengan pejabat politik dalam hal pertukaran atau transaksi politik demi kekuasaan. Alhasil, seringkali nuansa politis begitu kental terjadi dalam proses pengisian jabatan struktural di lingkup birokrasi. Keterkaitan ini dapat terlihat jelas pada saat momen pemilukada dalam perebutan jabatan politik di tingkat daerah yang melibatkan kontestasi calon incumbent. Kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaan dengan memenangi kontestasi, mendorong calon incumbent selaku pejabat yang sedang berkuasa melirik birokrasi untuk dijadikan mesin politiknya atau tim sukses yang mendukung pemenangannya. Kesadaran penguasa akan pentingnya dukungan dari berbagai pihak merupakan sesuatu yang saling terkait (mutual interest) dengan adanya kenyataan bahwa para birokrat pemburu jabatan (job seeker) sangat menyadari bahwa skenario peraturan perundang- undangan meletakan nasib dari karir jabatan mereka berada pada genggaman pejabat politik yang memiliki kontrol terhadap sumberdaya organisasi, termasuk lingkup hegemoni atas kewenangan luas dan kuat dari pejabat politik melalui klaim “hak prerogatif”. Azhari menyebut fenomena ini sebagai personal executive acendency (op.cit. : viii), 18 yakni suatu kondisi di mana karir birokrasi hanya diatur oleh satu orang pejabat politik. b. Faktor Nepotisme Secara etimologis, istilah nepotisme berasal dari kata latin ‘nepos’ yang berarti "keponakan" atau "cucu". Pengertian lengkapnya bisa merujuk pada kata ‘nepotism’ dalam kamus Inggris, yang diartikan sebagai mendahulukan sanak saudara sendiri. (Echols dan Sadily Hasan, 1985 : 21 ). Dalam dunia birokrasi, nepotisme merupakan produk dari personalisasi kekuasaan oleh pejabat politik yang menganggap bahwa kewenangan yang dimilikinya bisa dipergunakan secara relatif bebas menurut kehendak diri pribadi. Pola nepotisme biasanya teridentifikasi melalui praktek perlakuan khusus, pemberian prioritas maupun fasilitas lebih berupa akses informasi penting, properti, jabatan maupun proyek oleh penguasa kepada para kerabatnya. Nepotisme merupakan tindakan subyektif penguasa yang mengabaikan aspek“fairness” dengan tanpa mempertimbangan kualitas dan kemampuan dari pihak penerima perlakuan khusus tersebut. Dalam sistem nepotis tidak ada istilah kesamaan peluang dan iklim kompetisi sehat. Nepotisme merupakan tindakan yang semata- mata berdasarkan pada naluri dan ikatan emosional karena alasan pertalian darah atau hubungan kekerabatan. c. Faktor Primordialisme Primordialisme adalah suatu sikap sangat cintanya terhadap sesuatu, atau dapat juga dimaknai sebagai suatu faham yang menunjukkan sikap berpegang teguh kepada karakteristik individu yang dibawanya sejak lahir, seperti agama, etnis, maupun golongan dan kebudayaan (bahasa, adat istiadat). 19 Faktor primordial merupakan suatu hubungan keterikatan berdasarkan pada kesamaan unsur-unsur komunal yang dimiliki secara bersama oleh sejumlah individu dalam suatu komunitas. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama tetapi melahirkan pula persepsi yang sama tentang masyarakat yang dicita-citakan. (Surbakti, 1992:44). Perspektif primordialisme umumnya melihat bahwa kelompokkelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran seperti kewilayahan, kebudayaan, bahasa, organisasi sosial dan agama yang memang disadari sebagai hal yang ‘given’ dari sananya. Pendekatan ini terbukti mempunyai pengaruh terhadap gambaran sosial masyarakat. Primordialisme muncul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) Adanya sesuatu yang dianggap istimewa oleh individu dalam suatu kelompok atau perkumpulan sosial. 2) Adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan kelompok atau kesatuan sosial terhadap ancaman dari luar. 3) Adanya nilai- nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan, misal agama. (Abdilah S., 2002 : 76) Clifford Geertz beranggapan bahwa primordialisme menyangkut hubungan kesetiaan komunal yang adalah percampuran faktor politis, psikologis, kultural dan demografis (Geertz, 1992 : 77). Dalam politik, menguatnya primordialisme dapat mengakibatkan munculnya tindakan diskriminasi sebagai upaya untuk membedakan golongan-golongan yang berkaitan dengan kepentingan tertentu yang dilakukan dengan sengaja. Primordialisme sekarang ini menjadi aspek penting dalam hubungan antar kelompok yang menyangkut gagasan tentang pembedaan, dikotomi antara “kami” dan “mereka.” Dikotomi ini menegaskan batas-batas komunal 20 yang melingkupi anggota yang terikat di dalamnya dan non anggota di luarnya. d. Faktor Patrimonialisme Salah satu budaya yang menonjol di dalam tubuh birokrasi Indonesia adalah kecenderungan pembentukan pola hubungan patronage. Hubungan ini oleh James Scott (1972) disebut sebagai hubungan patron-client. Pola hubungan dalam konteks ini terjadi antar dua individu, si patron dan si client yang bersifat resiprokal atau timbal-balik dengan saling mempertukarkan sumber daya (exchange of resources) oleh masing- masing pihak. Si Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, harta kekayaan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang. Sementara, klien memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing- masing pihak tetap memiliki sumber daya tersebut. Kalau tidak demikian, maka masing- masing pihak akan kembali mencari orang lain sebagai patron atau klien yang baru. Menarik untuk diperhatikan, bahwa tidak jarang pula pola hubungan yang bersifat clientilistic ini tumbuh dan berkembang, karena ada orang ketiga yang menjadi perantara yang disebut sebagai brooker atau middleman. (Gaffar, 2006:109-110) Pola hirarki yang bertemu dengan budaya paternalistik dalam birokrasi telah menumbuhkan ketergantungan kuat para pejabat karir terhadap pejabat politik sebagai atasan maupun pejabat karir lainnya dengan kedudukan eselon lebih tinggi. Ketergantungan itu kemudian mendorong mereka untuk memperlakukan atasan secara berlebihan, dengan menunjukkan loyalitas dan 21 pengabdian yang sangat tinggi kepada pimpinan dan mengabaikan perhatiannya kepada para pengguna layanan yang seharusnya menjadi perhatian utama. (Mulder dalam Dwiyanto, 2011: 65) Selanjutnya, ketergantungan ini lebih diperkuat dengan posisi tawar pejabat atasan selaku pemegang otoritas tunggal yang akan menentukan nasib para pejabat karir bawahannya. Menyadari akan hal yang demikian seringkali pejabat karir sedapat mungkin mencari citra baik dan simpati atasan dengan menjual loyalitas dan dedikasi guna dipertukarkan dengan peluang memperoleh kemudahan dari sang pejabat politik dalam memuluskan karir birokrasinya. Prinsif loyalitas yang dipahami secara keliru oleh aparat pelayanan turut pula memberikan implikasi pada rendahnya kemampuan melakukan tindakan diskresi. Prinsip loyalitas yang dipahami dalam konteks struktur piramidal kekuasaan birokrasi menyebabkan persepsi yang berkembang dalam birokrasi adalah loyal kepada pimpinan karena jabatannya, bukan loyalitas yang dipahami sebagai ketaatan secara institusional dan profesional atas dasar visi dan misi organisasi serta tujuan pelayanan. (Kausar, 2008 : 9) Hubungan emosional yang terbangun dari pola paternalistik yang mementingkan loyalitas, cenderung membuat pejabat politik mengabaikan sejumlah unsur obyektifitas seperti prestasi kerja, kompetensi dan profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan utama penilaian kinerja dan keputusan promosi jabatan. Dengan demikian ada perbedaan karakteristik tentang konsep jabatan, dimana birokrasi paternalistik melihat 22 jabatan sebagai fungsi dari kepercayaan atasan, sedangkan dalam birokrasi rasional, jabatan merupakan fungsi dari kemampuan dan prestasi kerja. F. Alur Pikir Penelitian Untuk memberikan kejelasan mengenai mekanisme pengisian jabatan struktural yang akan dijadikan obyek sekaligus fokus penelitian, maka dibuat alur pikir yang mengkerangkai proses dan kerja riset di lapangan sebagaimana berikut: Skema I.1 Alur Pikir Penelitian Internal Internal Internal Internal BAPERJAKAT GUBERNUR ( Proses Birokrasi ) (Proses Politik) Tahap Tahap Pengusulan Tahap Verifikasi Tahap Rekomendasi Penetapan Eksternal Eksternal Eksternal Eksternal Pejabat Terpilih Proses rekrutmen pejabat struktural, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal yang terjadi di setiap tahapan. Secara skematik mekanisme pengisian jabatan struktural berlangsung dalam beberapa tahapan sebagai sebuah sistem normatif, meliputi: tahap pengusulan, tahap verifikasi, tahap rekomendasi dan tahap penetapan yang ditandai dengan adanya keputusan gubernur. Proses yang bekerja dalam mekanisme ini mengalir mulai dari satuan kerja/ instansi menuju institusi BAPERJAKAT sebagai tempat dimana proses birokrasi berlangsung, dan selanjutnya berakhir dalam proses 23 politik di tangan gubernur sebagai pejabat tertinggi yang berhak membuat penetapan final melalui penerbitan surat keputusan pengangkatan sekaligus melantik pejabat terpilih. Faktor internal merupakan seperangkat aturan normatif di dalam birokrasi yang menjadi dasar acuan pada tahap pengusulan oleh pimpinan instansionalmaupun dalam tahap verifikasi dan rekomendasi di BAPERJAKAT untuk membuat daftar nominasi para calon pejabat yang layak diusulkan pengangkatannya, sedangkan faktor eksternal adalahsejumlah faktor dari luar birokrasi yang berpotensi “menyusup” melalui pertimbangan personalistik gubernur dengan klaim “hak prerogatifnya”. Peran strategis gubernur sebagai pimpinan tertinggi eksekutif yang dianggap sangat menentukan arah perkembangan karir para PNS, sebenarnya berangkat dari perspektif klasik yang memaknai konsep jabatan lebih kepada fungsi kepercayaan atasan ketimbang hak pegawai yang bisa dituntut berdasarkan kinerja dan prestasi. Kondisi seperti ini diperparah lagi dengan fakta bahwa karir birokrasi terpusat pada pejabat politik selaku pemimpin tertinggi eksekutif. G. Definisi Konsepsional Untuk memudahkan pemahaman sekaligus memberikan kepastian arah dalam ruang lingkup studi, maka dilakukan penegasan definisi terhadap sejumlah konsep yang dipakai. Definisi konsep sesuai permasalahan yang terangkum pada pertanyaan penelitian, adalah sebagai berikut: 1. Mekanisme adalah totalitas alur kerja berisi tahapan-tahapan yang terdiri dari : tahap pengusulan, tahap verifikasi, tahap rekomendasi, dan tahap 24 penetapan. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan satu rangkaian proses yang ditempuh dalam mekanisme pengisian pos jabatan struktural di birokrasi daerah yang secara ideal dirancang untuk mampu menghasilkan SDM Aparatur yang profesional dan kompeten dalam mengisi posisi jabatan struktural di birokrasi daerah. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengisian jabatan struktural di kelompokkan ke dalam kategori faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam birokrasi itu sendiri terkait sejumlah pertimbangan formal yang diatur secara normatif berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan di luar birokrasi. Faktor eksternal ini erat kaitannya dengan penggunaan klaim “Hak Prerogatif” yang keberadaannya meskipun tidak diatur secara resmi dan tertulis, namun dalam praktek kesehariannya tetap ikut andil dalam mempengaruhi hasil keputusan pengangkatan para PNS dalam berbagai posisi jabatan struktural di birokrasi daerah. Pertimbangan personalistik gubernur atas dasar klaim “Hak Prerogatif” ini selanjutnya berpotensi menjadi pintu masuk bagi sejumlah faktor eksternal, diantaranya faktor politis, nepotisme, primordialisme dan paternalisme. H. Definisi Operasional Berdasarkan definisi konsepsional yang disebutkan di atas, maka operasionalisasi terhadap konsep-konsep dalam penelitian mengenai mekanisme pengisian jabatan struktural di sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah, dapat dilihat dengan menggunakan indikator- indikator: 25 1. Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural Mekanisme ini diketahui dari pelaksanaan setiap tahapan dalam proses pengisian pos jabatan struktural yang berlangsung di sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah mulai dari tahap pengusulan, tahap verifikasi, tahap rekomendasi dan tahap penetapan. Setiap tahapan dipaparkan masingmasing untuk memberi gambaran apa adanya mengenai proses yang berlangsung di dalamnya. 2. Faktor Inte rnal dan Eksternal yang me mpengaruhi mekanis me pengisian Jabatan Struktural a. Faktor Internal Berlandaskan pada pertimbangan legal rasional yang berlaku secara formal di internal birokrasi terkait unsur-unsur obyektif yang mewakili kemampuan personal masing- masing PNS yang akan diusulkan menjadi pejabat struktural, yakni: a.1. Unsur Kecakapan Kerja (merit system) − pengalaman rotasi jabatan dan prestasi kedinasan yang pernah diraih selama ini; − sertifikasi tertinggi dari diklat jabatan yang dimiliki; − pendidikan tertinggi yang dimiliki; − nilai rata-rata penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir. a.2. Unsur Senioritas (seniority system) − pangkat terakhir pada saat pelantikan; 26 − masa kerja pada saat pengangkatan dibandingkan dengan para pegawai lain dalam satu unit kerja atau instansi di sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah; − pengalaman jabatan atau catatan mutasi yang dimiliki oleh pegawai dari satu unit ke unit kerja yang lain. Hal ini menggambarkan berapa luas lingkup tugas dan tanggung jawab yang pernah ditangani. b. Faktor Eksternal Faktor ini bertalian dengan keberadaan klaim “Hak Prerogatif” gubernur yang meskipun tidak dirancang secara resmi dan juga tidak tercantum secara tertulis di dalam ketentuan perundang-undangan, namun dalam realitasnya ia memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan dan ikut menentukan hasil dari mekanisme pengisian jabatan struktural di birokrasi daerah. Faktor eksternal ini berkesempatan masuk melalui adanya personalisasi kekuasaan pejabat politik dengan klaim “Hak Prerogatif” yang dianggap melekat dalam jabatannya selaku pembina kepegawaian daerah. Adapun faktor informal ini berupa anasir tradisional, meliputi faktor politis, faktor nepotisme, faktor primordialisme dan faktor patrimonialisme, sebagaimana berikut ini: b.1. Faktor Politis − Proses pengisian jabatan yang memiliki indikasi dan tendensi mewakili kepentingan pragmatis penguasa dan lingkarannya. 27 b.2. Faktor Nepotisme − Ada tidaknya pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan gubernur yang saat diangkat tidak memenuhi syarat legalformal. b.3. Faktor Primordialisme − Ada tidaknya pejabat struktural dengan ikatan primordialistik terhadap gubernur yang diangkat namun tidak memenuhi syarat legal-formal. b.4. Faktor Patrimonialisme − Intensitas dan akses komunikasi non formal terhadap pejabat politik; − Ketaatan terhadap instruksi atasan langsung dan pejabat politik mengenai suatu kebijakan yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab jabatan. I. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Studi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yakni menggunakan kata-kata tertulis (Moleong, 2013:4) untuk memberikan gambaran secara sistematik, terperinci dan menyeluruh mengenai mekanisme pengisian jabatan struktural di sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah dan bekerjanya faktor internal dan eksternal yang keberadaannya potensial mempengaruhi pelaksanaan dan hasil dari mekanisme rekrutmen jabatan di birokrasi sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah. 28 2. Fokus Penelitian Pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan agar pembahasan tidak terlalu meluas, sehingga penelitian ini hanya fokus pada mekanisme pengisian pos jabatan struktural yang telah dilaksanakan di lingkungan sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah, sekaligus pula melihat bagaimana bekerjanya faktor- faktor, baik internal maupun eksternal dalam mempengaruhi pelaksanaan dan hasil dari mekanisme tersebut. 3. Unit Analisa Data Adalah unit darimana informasi dikumpulkan sekaligus sebagai basis untuk melakukan analisis, yaitu para pejabat eselon yang tergabung dalam tim BAPERJAKAT propinsi, termasuk jajaran birokrat yang ada di sejumlah biro/ bagian di sekretariat daerah propinsi (setdaprop) Kalimantan Tengah dan para ‘outsider’ terpilih, yakni anggota LSM, wartawan, akademisi, dan pengurus partai politik yang dianggap memiliki wawasan cukup mengenai kondisi birokrasi daerah dan peta perpolitikan lokal. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Lapangan, dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara (interview) kepada para narasumber yang terdiri dari para pejabat terkait dan sejumlah stake-holders seperti tersebut di unit analisa data. b. Penelitian Kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan literatur fisik maupun informasi digital. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, karya akademik, artikel, jurnal.(Soekanto, 1998 : 12) 29 5. Metode Analisis Data Data penelitian diolah menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan dan membuat analisis argumentatif terhadap data primer hasil observasi dan wawancara maupun data sekunder dari penelusuran pustaka dan dokumen relevan. Hasil analisis merupakan jawaban atas rumusan masalah, sekaligus sebagai bahan dalam menyusun kesimpulan dan saran. Gambar I. 2 Skema Analisis Data Data Hasil Observasi Data Hasil Wawancara Data Hasil Studi Pustaka Hasil Analisis Kesimpulan dan Saran J. Sistematika Bab Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis dan terstruktur yang dituangkan ke dalam satuan bab. Secara keseluruhan terdapat total lima bab, berisikan pokok bahasan berbeda yang saling terkait sebagai suatu kesatuan gugus pemikiran. Tulisan dimulai dengan sekilas latar untuk mengantarkan kita memasuki bab-bab berikutnya. Bab kedua, memaparkan gambaran umum tentang struktur organisasi birokrasi sekretariat daerah propinsi Kalimantan Tengah beserta jalur hirarkis kewenangan dan pola koordinasi yang saling terkoneksi antar bagian. Setting 30 birokrasi dilihat dalam hubungannya dengan konstelasi perpolitikan lokal yang diwarnai oleh dominasi PDI-P yang berkiprah sekaligus di dua domain kekuasaan pada level daerah, baik di ranah legislatif maupun di ranah eksekutif dengan berposisi sebagai partai yang menjadi patron dari gubernur. Bab ketiga, menampilkan mekanisme pengisian pos jabatan struktural melalui empat tahapan, yakni tahap pengusulan, verifikasi, rekomendasi dan penetapan yang diselenggarakan oleh BAPERJAKAT sebagai instrumen normatif yang memberikan pertimbangan kepada pejabat politik dalam rangka menetapkan keterpilihan pejabat karir di dalam struktur birokrasi daerah. Bab keempat, mengulas tentang faktor internal dan eksternal yang potensial mempengaruhi mekanisme dan hasil rekrutmen para pejabat di lingkungan birokrasi daerah Kalimantan Tengah. Faktor internal adalah kriteria legal-rasional pada pegawai terkait kelayakan normatif untuk diangkat sebagai pejabat, . Adapun faktor eksternal meliputi pertimbangan politis, nepotisme, primordialisme dan patrimonialisme yang merupakan unsur dari lingkungan luar birokrasi yang dalam prakteknya seringkali menjadi dasar pertimbangan pejabat politik dalam membuat keputusan sehingga turut mempengaruhi hasil dari mekanisme rekrutmen tersebut. Bab kelima, merupakan bagian akhir tulisan berisi ulasan singkat mengenai intisari bahasan di tiap bab sebagai satu kesatuan penjelasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian. Bagian ini juga menampilkan refleksi dari teori yang dipakai dalam menganalisa sejumlah fenomena dan data temuan lapangan, sekaligus beberapa ide dan saran perbaikan yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan wilayah garap bagi riset selanjutnya. 31