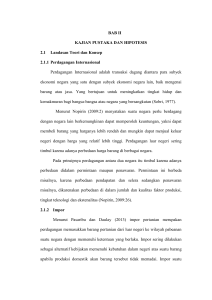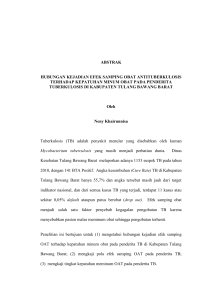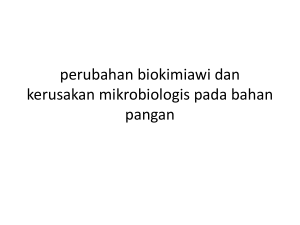196 BAB VI PENUTUP 6. 1. Kesimpulan Sejak
advertisement
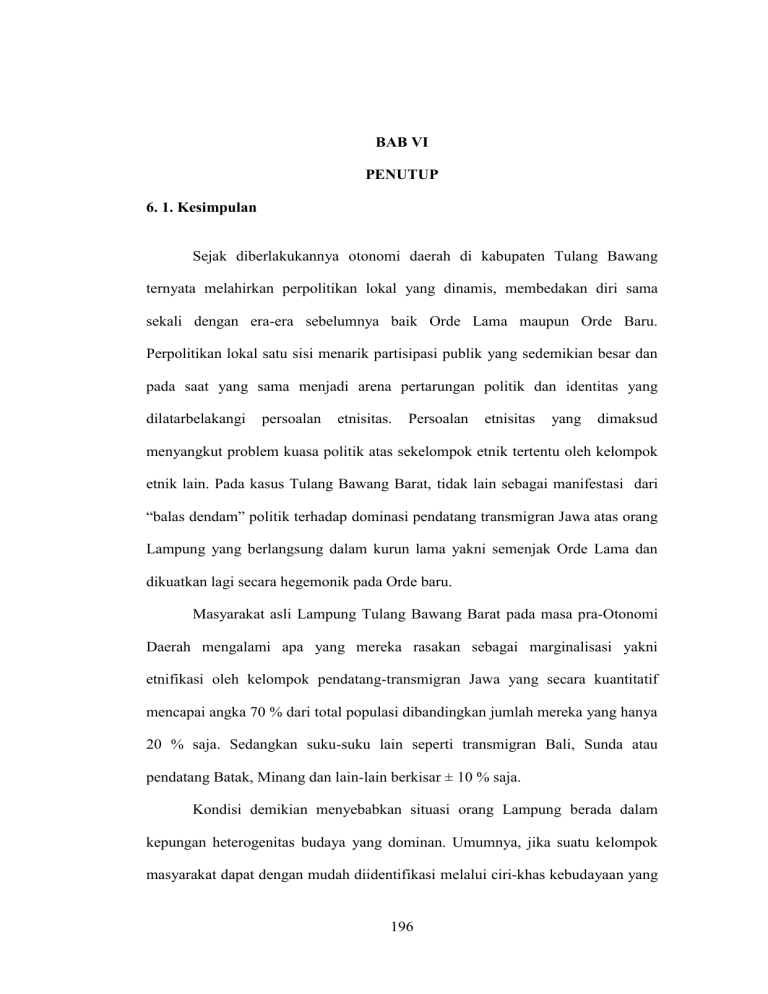
BAB VI PENUTUP 6. 1. Kesimpulan Sejak diberlakukannya otonomi daerah di kabupaten Tulang Bawang ternyata melahirkan perpolitikan lokal yang dinamis, membedakan diri sama sekali dengan era-era sebelumnya baik Orde Lama maupun Orde Baru. Perpolitikan lokal satu sisi menarik partisipasi publik yang sedemikian besar dan pada saat yang sama menjadi arena pertarungan politik dan identitas yang dilatarbelakangi persoalan etnisitas. Persoalan etnisitas yang dimaksud menyangkut problem kuasa politik atas sekelompok etnik tertentu oleh kelompok etnik lain. Pada kasus Tulang Bawang Barat, tidak lain sebagai manifestasi dari “balas dendam” politik terhadap dominasi pendatang transmigran Jawa atas orang Lampung yang berlangsung dalam kurun lama yakni semenjak Orde Lama dan dikuatkan lagi secara hegemonik pada Orde baru. Masyarakat asli Lampung Tulang Bawang Barat pada masa pra-Otonomi Daerah mengalami apa yang mereka rasakan sebagai marginalisasi yakni etnifikasi oleh kelompok pendatang-transmigran Jawa yang secara kuantitatif mencapai angka 70 % dari total populasi dibandingkan jumlah mereka yang hanya 20 % saja. Sedangkan suku-suku lain seperti transmigran Bali, Sunda atau pendatang Batak, Minang dan lain-lain berkisar ± 10 % saja. Kondisi demikian menyebabkan situasi orang Lampung berada dalam kepungan heterogenitas budaya yang dominan. Umumnya, jika suatu kelompok masyarakat dapat dengan mudah diidentifikasi melalui ciri-khas kebudayaan yang 196 197 merujuk pada nilai-nilai maupun bahasanya serta pada kesempatan yang sama dijadikan sebagai aturan main sehingga Tulang Bawang Barat dikenal dengan “kelampungannya” maka hal tersebut tidak terjadi pada masa itu. Yang terjadi adalah bahwa Tulang Bawang kental dengan ciri-khas Jawa baik dari sisi budaya, bahasa maupun tampilan postur birokrasi baik sipil maupun militer, dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten maupun gubernuran, mulai dari struktur POLSEK, POLRES, KORAMIL hingga KODIM maupun KODAM. Situasi tersebut memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah kontak masyarakat lampung dengan pendatang-transmigran Jawa sejak era kolonial Belanda ditambah lagi dengan gaya kepemimpinan sentralistik otoritarianisme Orde Baru. Transmigrasi dengan para transmigrannya menjadikan mereka mengalami marginalisasi di tanahnya sendiri dan membuat mereka tidak berkuasa atas wilayahnya atau sebagaimana diisitilahkan Sokefeld sebagai etnifikasi. Sedangkan Avtar Brah menggambarkan sebagai pribumi diasporian yang mengalami keterasingan. Dalam konteks ruang diaspora ini, baik masyarakat asli Lampung maupun pendatang-transmigran Jawa mengalami ketegangan- ketegangan identitas dan psikologis yang senantiasa hadir dan menghilang. Semenjak otonomi daerah, terdapat pergeseran sikap orang asli Lampung menghadapi marginalisasi yang mereka alami. Resistensi yang dilakukan pertamatama bukanlah perlawanan politik dengan merebut posisi-posisi strategis jabatan partai politik yang akan dipergunakan untuk kendaraan politik. Melainkan strategi budaya dengan modal budaya yang mereka miliki yakni filsafat Piil Pesenggiri sebagai modal pembentukan identitas kolektif mereka demi 198 menghadapi dominasi pendatang transmigran Jawa yang mayoritas. Piil Pesenggiri dikontekstualisasikan menurut tafsiran akan kebutuhan jaman yakni otonomi daerah. Dalam hal ini Comaroff menyebutnya sebagai alat perjuangan melawan marginalisasi. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan terdapat 3 pokok temuan yakni : Pertama. Gerakan sosial budaya dengan konstruksi identitas diri orangorang Lampung dan identitas pendatang berdasarkan tafsir kontesktual Piil Pesenggiri. Filsafat Piil Pesenggiri yang pada mulanya bersifat etis-normatif dan berfungsi sebagai ajaran nilai-nilai moralitas mengalami ideologisasi. Pada modus pertama ini, mereka berusaha mendefinisikan siapa mereka dan siapa pendatang Jawa melalui pemaknaan ulang akan doktrin Nemui Nyimah; siapa kami dan siapa pendatang; tuan rumah berhadap-hadapan dengan tamu. Konstruksi identitas bersifat bipolar. Vis a vis : orang Lampung berhadap-hadapan dengan orang Jawa (atau pendatang lain). Identitas tidak bersifat cair dan justru menggumpal saling berhadap-hadapan. Mengikuti alur gerakan tersebut pada gilirannya menjadi pintu masuk pada arena perpolitikan lokal sebagai implikasi gerakan pertama yakni hak kepemimpinan kekuasaan birokrasi Tulang Bawang Barat. Siapa yang harus menjadi Bupati, Ketua DPRD, Anggota DPRD, Camat, Kepala Dinas dan seterusnya. Hak kekuasaan ini secara langsung merupakan implementasi dari modus pertama dan terjemahan kongkrit dari Piil Pesenggiri yang mereka yakini. Pada pokok kedua ini pula nepotisme patron client semakin menyubur. 199 Disamping modus tersebut, terjadi pula resistensi orang Lampung yang berbentuk aksi sosial lapangan yang bersifat tidak terstruktur dan terorganisir. Pada pola ini, aksi massa atas nama putra daerah sering terjadi dan bersifat sporadis. Biasanya dipicu masalah konflik tanah. Mereka dengan menggerakkan orang-orang lokal dan “LSM” bentukan mereka sendiri biasanya menduduki rumah atau tanah yang diklaim miliki mereka. Bagi kelompok pendatang trasnmigran, meskipun pola jenis ini tidak termasuk sebagai gerakan sistematis kekuasaan akan tetapi implikasi psikologisnya, sesungguhnya jauh lebih terasa dibanding pergerakan politik terutama bagi kalangan masyarakat bawah yang hirau terhadap hingar-bingar politik. Bagi mereka keamanan sosial dan ketenangan hidup jauh lebih berarti dibandingkan dengan pertarungan politik. Bersamaan dengan perebutan basis-basis kekuasaan, produk-produk kebijakan publik seperti pengajaran bahasa Lampung diwajibkan di sekolahansekolahan, simbol-simbol daerah, kegiatan seni tradisi orang Lampung secara masif dihidupkan. Terdapat keinginan utama untuk membumikan lagi simbol dan adat budaya Lampung yang telah lama hilang dan tergantikan oleh dominasi budaya Jawa. Konteks ini, sesungguhnya masyarakat asli Lampung menginginkan pengakuan dari komunitas lain yang tinggal di sana. Belajar dari yang mereka alami nampaknya orang Lampung belajar dari pengetahuan para pendatang. Mereka mempelajari pengetahuan pendatang dengan membentuk organisasi-organisasi adat dan berstrategi untuk kemudian bagaimana mengalahkan mereka. Dengan mengambil pengetahuan para pendatang mereka 200 meningkatkan kapasitas diri bagaimana berkompetisi dalam internal masyarakatnya maupun ketika berhadapan dengan orang lain. Kedua, bahwa kelompok masyarakat transmigran (tidak hanya yang berasal dari Jawa) secara historis terstreototipkan sebagai kelompok kelas rendahan dalam struktur sosial masyarakat Lampung. Sejak mula kedatangan mereka di tanah asal sampai dengan di tanah tujuan tetap dianggap sebagai warga kelas dua. Barangkali sama dengan cara pandang sebagaian dari kita terhadap label transmigran. Konstruksi label transmigran memuat anggapan negatif tentang kelas sosial yang berasal dari golongan rendahan atau kelompok marginal miskin, pengangguran atau secara keseluruhan kelas ekonomi lemah. Demikianlah sejarah sendiri telah secara lama melakukan marginalisasi identitas mereka. Di masyarakat Tulang Bawang Barat, kelompok lokal (pribumi) pun melakukan cara pandang yang sama. Masyarakat asli Lampung Tulang Bawang mennggolongkan kelompok transmigran menjadi dua jenis kelompok : a). Kelompok mereka yang dianggap kelas satu, sehingga layak untuk dijadikan sebagai “orang Lampung” atau “dilampungkan” dengan cara pemberianpemberian gelar. Pada kelompok ini, meliputi orang-orang Jawa (maupun non Jawa) yang dianggap memiliki derajat ketokohan tertentu, berhasil secara ekonomi dan biasanya adalah mereka-mereka yang menjabat jabatan publik seperti birokrat desa, PEMDA, instansi militer, pengusaha dan sejenisnya. b). Kelompok transmigran yang tetap dianggap sebagai warga kelas dua, yakni kelompok sosial baik Jawa maupun non Jawa yang tidak memiliki jabatan publik tertentu. Tidak terdapat kriterium khusus untuk menentukan sebagai kelompok a 201 atau b. Akan tetapi dapat dilihat bahwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang dianggap tidak memiliki derajat ketokohan tertentu meskipun secara finansial cukup Ketiga, orang Jawa dengan etika Jawanya menanggapi perlawanan balik masyarakat asli Lampung dengan sikap khas Jawa yakni mengedepankan keselarasan, pragmatis dan pada titik tekan tertentu masuk ke dalam situasi apatisme politik. Mayoritas responden memberi pernyataan bahwa mereka lebih baik “mengalah” demi keluarga dan apa yang telah mereka perjuangkan selama puluhan tahun dari pada melakukan perlawanan tetapi akan kehilangan properti yang telah dimiliki. 6.2. Saran Memaparkan catatan dinamika perpolitikan lokal Kabupaten Tulang Bawang menggiring pada kesimpulan bahwa identitas keindonesiaan sebagai syarat terwujudnya “kemauan politik bersama” sebagaimana gagasan yang biasa berkembang dalam diskursus nasionalisme belum terbentuk. Merujuk pada pendapat Furnivall dan Miller sebuah “kemauan bersama” di Tulang Bawang Barat hanya dirasakan pada level ekonomi yang berlangsung di pasar-pasar dimana transaksi perniagaan berlangsung. Keluar dari arena pasar, yang tersisa hanya kehidupan sosial dengan dua polarisasi identitas kolektif yang satu mencurigai yang lain, merasa dirinya lebih besar, memiliki hak utama karena klaim kepemilikan sedangkan kelompok lain pasrah, nrimo, tidak terlalu peduli/pasif demi menjaga keselamatan diri dan keselarasan jagad gedenya. 202 Untuk itu terdapat saran yang barangkali relevan dan patut untuk direnungkan bersama : Pertama, pembentukan identitas keindonesiaan sebagai antitesis dari identitas kelokalan. Bagaimanapun juga Pemerintah kolonial Belanda, Soekarno (Orde Lama) maupun Soeharto (Orde Baru) memiliki andil terbentuknya polarisasi bipolar pendatang transmigran Jawa vis a vis masyarakat lokal Lampung dengan pembangunan pemukiman yang bersifat enclave, membentuk kantong-kantong etnik sehingga setelah sekian puluh bahkan ratusan tahun tidak terjadi pembauran sosial dan akulturasi budaya secara alamiah. Orang Jawa tumbuh dengan kejawaannya, orang Bali tumbuh dengan kebalianya dan orang Lampung meredup dengan sendirinya karena keterdesakan populasi maupun etnifikasi. Gelora ide kebangsaan sejak Soekarno melalui demagogi dan retorika berapi-api yang disiarkan lewat radio nampaknya hanya sekilas menyentuh kesadaran diri transmigran sebagai orang Indonesia (baca : Wong Jowo Indonesia) yang hidup di tengah-tengah masyarakat “bukan seperti mereka” di tanah air Indonesia dan tidak sempat mengguratkan identitas diri sebagai orang Indonesia akibat pemukiman enclave, kesibukannya menaklukan alam dan memperbaiki derajat kualitas hidup yang keras. Ide kebangsaan/nasionalisme dan identitas keindonesiaan hanya lirih terdengar dari seberang pulau Jawa dan tidak membekas banyak dalam memori kolektifnya. Mereka tetap merasa sebagai orang Jawa di tanah bukan pulau Jawa. Era Orde Baru Soeharto, ide kebangsaan dan identitas keindonesiaan nampaknya “lebih berhasil” karena dilakukan secara koersif-sentralistik ala 203 militer dan birokrasi otoritarianistik. Disini KORAMIL, KODIM, kantor-kantor aparat pemerintahan menjadi agen langsung penerjemah, penafsir dan penopang dari ide identitas keindonesiaan. Tidak ketinggalan, partai-partai politik semisal GOLKAR, PPP maupun PDI melakukan hal yang sama meskipun hasilnya jauh berbeda dengan hasil yang dilakukan dari lembaga-lembaga pertama. Penataranpenataran P4, propaganda keberhasilan ekonomi melalui siaran-siaran RRI, KELOMPENCAPIR menjadi salah satu medium pemerintahan Soeharto memperkenalkan gagasan keindonesiaan. Akan tetapi masyarakat lokal Lampung menanggapi cara Orde Baru dengan berbeda. Bagi mereka identitas keindonesiaan yang diperkenalkan dan dipromosikan Orde Baru bertolak belakang dengan praktik di lapangan dimana menurutnya, telah terjadi ide dan gerakan Jawanisasi. Camat, wedana, bupati hingga gubernur dipilih dari orang Jawa. Polisi-polisi dan BABINSA dan KORAMIL, KODIM juga kebanyakan berasal dari Jawa. Belum lagi seragam batik yang wajib dipergunakan tiap hari Jumat oleh birokrat-birokrat juga guru-guru dan murid sekolah. Yang mereka rasakan jauh dari rasa “keindonesiaan” tetapi “jawanisasi”. Merujuk pada Benedict Anderson, definisi bangsa/nation adalah komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena anggota bangsa sekecil apapun tidak akan tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lainnya dan tidak akan bertatap muka dengan mereka. Tetapi masingmasing membayangkan dalam sebuah arena imajiner yang disatukan oleh bayangan akan kebersamaan mereka. Kebangsaan bersifat terbatas karena anggota 204 suku-suku bangsa baik yang jumlah populasinya besar maupun kecil memiliki garis demarkasi yang jelas tetapi elastis. Orang Lampung adalah orang Lampung, dan Jawa tetaplah Jawa tetapi mereka dalam figura keindonesiaan. Oleh sebab itu, pembangunan proyek identitas keindonesiaan adalah suatu proses budaya yang terus menerus. Ia harus dikerjakan, diolah, didisain sedemikian rupa sehingga sampai pada arah dan tujuan yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Ketiga, otonomi daerah, identitas keindonesiaan, nasionalisme adalah produk modernitas berlawanan dengan identitas kelokalan, kepemimpinan adat /kesukuan yang adalah produk tradisional. Jika modernitas mengandalkan rasionalitas yang identik dengan produk pencerahan maka kebalikannya, tradisionalitas lebih pada dogma kesukuan maupun agama yang terkadang bersifat jumud dan anti-kritik dan cocok diberlakukan pada masyarakat tradisional homogen. Sebagai produk modernitas yang mengandalkan rasionalitas maka proyek pembangunan identitas kebangsaan/keindonesiaan sebagai instrumen untuk melawan tumbuhnya politik identitas sempit ala otonomi daerah adalah pendidikan. Proyek identitas adalah proyek yang tidak pernah berhenti selama negara yang bersangkutan masih berdiri tegak. Oleh sebab itu, mengajar dan mendidik dan membentuk “orang Indonesia” merupakan proses yang bersifat long life education. Di sekolahan, pasar-pasar, lingkungan kantor, pusat-pusat perniagaan keindonesiaan hendaknya diutamakan daripada kesukuan. Orangorang Jawa sudah harus mulai menghargai masyarakat Lampung dengan meninggalkan kejawaanya ketika beranjak dari pintu rumah mereka dengan berbahasa Indonesia. Demikianpun orang Lampung hendaknya mulai menyadari 205 bahwa mereka bukanlah tuan rumah abadi yang berkuasa absolut atas kontrol pemerintahan daerah dan klaim kepemilikan tanah. Otonomi daerah hendaknya tidak menjadi pintu masuk tirani politik yang menampilkan diri dengan wajah kearifan lokal Piil Pesenggiri kepada para pendatang. Piil Pesenggiripun hendaknya jangan dijadikan instrumen intimidasi sosial demi menekan, menakutnakuti dan merebut tanah yang sudah menjadi milik orang lain. Piil Pesenggeri bukanlah ideologi yang beralih rupa menjadi “senjata tajam” yang lantas kemudian dipergunakan untuk menikam orang lain. Piil Pesenggiri bukan pula ideologi komunitas tetapi hanya sebatas filsafat, etika dan nilai-nilai tradisi yang memungkinkan dalam dirinya alpa, salah atau sudah tidak up to date. Selanjutnya, otonomi daerah seyogyanya dijadikan arena fair play layaknya pertandingan sepakbola dimana mereka yang terbaiklah yang dapat menjadi juara, bukan karena dasar pertimbangan klub yang bertanding pemilik stadion atau banyaknya suporter di sudut-sudut tribun. Suksesnya jalur pendidikan akan kesadaran identitas keindonesiaan ditunjukkan oleh narasumber-narasumber asal Lampung maupun Jawa yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Bagi mereka, Piil Pesenggiri menjadi salah kaprah jika dijadikan modal sosial untuk melakukan penetrasi dan marginalisasi terhadap suku-suku lain di tanah Tulang Bawang. Pun pada saat yang sama, anak-anak transmigran/PUJAKESUMA merasa bahwa identitasnya sudah mencair bukan lagi sebagai orang Jawa dan orang Lampung tetapi sebagai orang Indonesia. Mereka dengan modal pendidikannya telah berhasil keluar dari selubung 206 kepompong lokalitas kesukuan dan bermetamorfosa menjadi kupu-kupu Indonesia. Keempat, Dalam era multikultural, globalisasi menggiring hampir semua negara ke dalam situasi multikultur. Hampir tidak terdapat sebuah negara dengan penduduk homogen yang terdiri dari satu jenis etnik saja. Tiap-tiap negara memiliki ragam penduduk dan ragam budaya dengan nilai-nilai yang berbeda. Tentu saja, pertanyaannya tidak berhenti pada “sejauh mana masyarakat memenuhi norma-norma keadilan, kebebasan individu dan demokrasi permusyawaratan ?”. Tetapi pada bagaimana prinsip demokrasi dijunjung dengan tetap mengijinkan kearifan lokal hidup berkembang. Multikulturalisme memberikan jawaban tepat akan problematika politik sosial Tulang Bawang Barat. Secara garis besar, multikulturalisme melompati definisi lama pluralisme yakni sekedar pengakuan terhadap keanekaragaman, kemajemukan dan kebinekaan yang sudah terkonstruksi jauh-jauh hari sebelum Indonesia merdeka. Kerajaan-kerajaan kuno Indonesia bahkan Orde Baru mengakui hal tersebut, bahwa di sana terdapat berbagai macam ras, suku agama, golongan dan kelompok-kelompok budaya tertentu. Fakta Tulang Bawang era Soeharto menyisakan persoalan etnifikasi orang Lampung dan memberikan ruang bagi timbulnya “Jawanisasi”. Multikulturalisme disamping mengakui potensi keragaman, ia juga memberikan peluang berekspresi menurut jati diri masingmasing dengan saling berkomunikasi satu sama lain dengan meniadakan dominasi maupun mematikan oleh satu kepada yang lain. Identitas kultural 207 sebagai orang Jawa dan orang Lampung diakui dan tetap memperoleh hak-hak yang sama untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial-politik. Antara komunitas Lampung dan Jawa serta suku-suku lainnya yang hidup di sana, bersifat egaliter, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Tidak terdapat hak istimewa/previledge sebagai tuan rumah/pribumi dan pendatang/tamu. Arena kontestasi bersifat terbuka dan hanya merupakan pertarungan kualitas kepemimpinan.