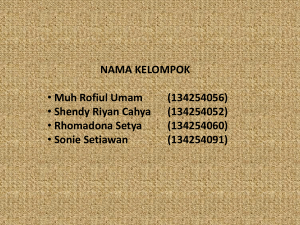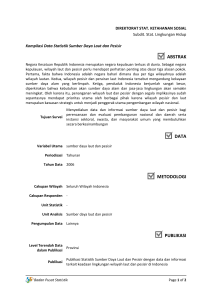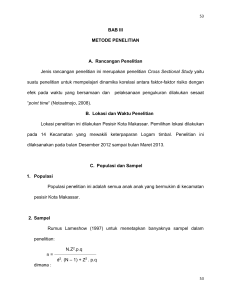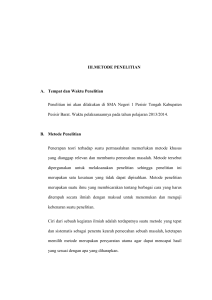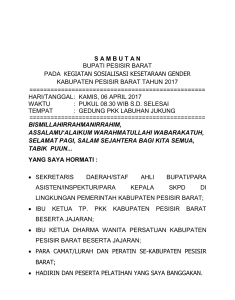Marine Cadastre - IPB Repository
advertisement

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut ICOZM (Integrated Coastal and Ocean Zone Management) atau sering disingkat ICZM merupakan cabang ilmu baru di Indonesia, bahkan menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) tahun 1994, juga merupakan cabang ilmu baru di dunia. ICZM adalah: “pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir; dengan cara melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatnya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan” (Dahuri et al., 2001). Senada dengan pengertian di atas dinyatakan bahwa ICM: “can be defined as a continuous and dynamic process by which decisions are made for the sustainable use, development, and protection of coastal and marine areas and resources. Integrated coastal management is a process that recognizes the distinctive character of the coastal area - itself a valuable resource - and the importance of conserving it for current and future generations” Cicin-Sain dan Knecht (1998). Selanjutnya dinyatakan pula bahwa: “The major functions of integrated coastal management are: (1) area planning; (2) promotion of economic development; (3) stewardship of resources; (4) conflict resolution; (5) protection of public safety; dan (6) proprietorship of public submerged lands and waters”. (Cicin-Sain and Knecht, ibid.) Wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan dan interaksi antara daratan dan lautan, sehingga menjadikan wilayah ini dalam posisi yang sangat rentan, unik, bernilai, dan tertekan. Mengingat posisi alam dan topografi wilayah pesisir sebagai “penampung” limpahan kegiatan di darat, maka respons sistem pesisir terhadap aktifitas manusia di darat tersebut sangat sensitif. Kegiatan di daratan seperti pertanian, pembangunan perkotaan dan industri, kehutanan dan 9 pertambangan, perumahan dan lain sebagainya menyumbang lebih dari 70 % dari seluruh polusi wilayah pantai dan lautan, mulai dari transpor erosi dan sedimen, material dan bahan-bahan kimia serta bahan beracun lainnya (Collier, 2002). Mengingat demikian besarnya pengaruh daratan terhadap pesisir, maka konsep pembangunan pesisir tidak hanya bersifat sektoral (melainkan multisektor dan interdisiplin) dan berbasis lautan, namun harus pula berbasis daratan, sehingga merupakan suatu konsep pembangunan wilayah yang integral (Clark, 1995). Hal inilah yang belum banyak (kalau tidak dapat dikatakan belum ada) dilakukan di Indonesia, di mana perencanaan tata ruang dan pembangunan wilayah masih bersifat parsial. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta sumberdaya buatan merupakan obyek-obyek yang dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan lautan. Sumberdaya non-hayati dan sumberdaya hayati yang menjadi obyek utama penelitian ini adalah: pasir laut, ekosistem mangrove dan terumbu karang, karena sumberdaya inilah yang mendominasi keberadaannya pada lokasi studi. 1) Ekosistem laut: sebuah contoh kegagalan kebijakan publik panambangan pasir laut Penambangan pasir laut telah mengakibatkan meningkatnya kekeruhan air laut, perubahan sirkulasi air laut akibat pengerukan dasar laut, rusaknya bagan-bagan ikan dan keramba budidaya ikan nelayan akibat gelombang arus kapal pengangkut pasir, serta bermigrasinya ikan tangkap yang mengakibatkan kerugian nelayan setempat. Kegiatan penambangan pasir laut telah berlangsung selama lebih kurang tiga puluh tahun sejak tahun 1970. Kegiatan ini dihentikan sementara dengan terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut. Namun, aktifitas tersebut dibuka kembali melalui Keppres Nomor 33 Tahun 2003, dan kemudian karena menimbulkan kontroversi lagi maka kegiatan ini ditutup kembali dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 117/MPP/KEP/II/ 2003. 10 2) Ekosistem mangrove: sebuah contoh kegagalan kebijakan publik, khususnya karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum Kegagalan pengawasan dan penegakan hukum merupakan suatu kegagalan kebijakan publik dalam pengelolaan sumberdaya dan wilayah. Berdasarkan hasil penelitian Global Environment Facility/ United Nations Development Program/International Maritime Organization (GEF/UNDP/IMO) Regional Programme for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas di Selat Malaka, termasuk wilayah pesisir dan laut pulau Bintan (Chua, 1999), maka kerusakan wilayah dan sumberdaya mangrove telah mengakibatkan kehilangan (dan dampak lebih besar lagi apabila diukur dampak berganda dari kerusakan dimaksud), yaitu: a. Nilai fungsi pemijahan dan pembesaran ikan pada mangrove, b. Nilai fungsi penyaringan karbon pada mangrove, c. Nilai fungsi pencegahan erosi pada mangrove, d. Nilai persepsi keberadaan sumberdaya dan ekosistem mangrove, dan e. Nilai manfaat pelestarian sumberdaya dan ekosistem untuk mangrove. 3) Ekosistem terumbu karang: sebuah contoh kegagalan kebijakan publik, khususnya karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum Demikian pula kegagalan pengawasan dan penegakan hukum merupakan suatu kegagalan kebijakan publik dalam pengelolaan sumberdaya dan wilayah pada ekosistem terumbu karang telah mengakibatkan kehilangan (dan dampak lebih besar lagi apabila diukur dampak berganda dari kerusakan dimaksud), yaitu: a. Nilai fungsi produksi organik dan penyaringan karbon pada terumbu karang, b. Nilai fungsi perlindungan garis pantai oleh terumbu karang, c. Nilai keanekaragaman terumbu karang, d. nilai persepsi keberadaan sumberdaya dan ekosistem pada terumbu karang e. Nilai eko-turisme terumbu karang, dan f. Nilai manfaat pelestarian sumberdaya dan ekosistem terumbu karang. 11 2.2. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut Dalam perspektif (definisi) konsepsional, pemanfaatan ruang dalam teori ICOZM adalah merupakan bagian atau sebagai implementasi dari perencanaan tata ruang. Perencanaan adalah seni dalam pengambilan keputusan di bidang sosial secara rasional, suatu aplikasi formulasi dan implementasi program dan kebijakan ke depan, suatu proses di mana masyarakat mengontrol dan mengarahkan diri mereka sendiri, suatu proses rasionalisasi kepentingan publik, atau suatu upaya untuk mengaitkan pengetahuan ilmiah dan teknis kepada proses arahan sosial atau transformasi sosial. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis (kepentingan) masyarakat. Apabila tujuan utama dari sistem perencanaan atas tanah adalah untuk mengatur perkembangan dan penggunaan tanah untuk kepentingan publik, maka definisi formal atas perencanaan tata ruang laut sejauh ini belum banyak dikembangkan (Canning and Gilliland, 2003). Dalam bahasa sederhana perencanaan tata ruang laut adalah suatu perencanaan stratejis untuk mengatur, mengelola dan melindungi lingkungan laut dari kompleksnya, kumulatifnya dan sangat potensialnya konflik penggunaan sumberdaya dan ruang laut. Perencanaan tata ruang laut harus dapat memasukkan mekanisme untuk mencapai integrasi dari beberapa sektor yang berbeda. Isu utama dari definisi tersebut adalah elemenelemen yang dibutuhkan dalam perencanaan tata ruang laut, yaitu yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Data dan informasi lingkungan laut; Skala perencaraan ruang; Sektor-sektor kelautan yang disertakan; Penilaian lingkungan stratejis terhadap lingkungan laut secara keseluruhan; Pendapatan dari ijin-ijin kelautan; Pengaturan praktis dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan kelautan; Tanggungjawab dalam pembangunan, implementasi, monitoring, dan penegakan hukum dari rencana tata ruang laut; 8) Meyakinkan keterlibatan para lintas pemangku kepentingan. Adapun prinsip-prinsip dalam arahan dan pengembangan perencanaan tata ruang laut yang harus dipegang, adalah: 1) Konservasi dan pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari prinsip-prinsip: a. Pembangunan berkelanjutan, b. Manajemen terpadu, c. Konservasi keanekaragaman biologi; 12 d. e. f. g. Ilmu pengetahuan yang kuat, Prinsip keselamatan, Keterlibatan pemangku kepentingan, dan Prinsip-prinsip “pencemar membayar” dan “pengguna membayar”. 2) Pendekatan ekosistem, yang terdiri dari prinsip-prinsip: a. Menyediakan dan berkerja di dalam suatu rangkaian tujuan ekosistem yang jelas, b. Pemanfaatan lebih besar dari penilaian lingkungan dan sosial-ekonomi, c. Penggunaan manajemen strategis yang lebih baik dari aktifitas manusia di lingkungan laut, d. Pengambilan keputusan dan aksi manajemen yang mempertimbangkan keanekaragaman biologi dan memperteguh arah pembangunan yang berkelanjutan, e. Memanfaatkan pengetahuan ilmiah dalam proses pengambilan keputusan, f. Mengembangkan penelitian dan monitoring yang lebih terfokus, dan g. Melibatkan para lintas pemangku kepentingan secara penuh. 3) Integrasi: diperlukan pemaduan seluruh program dan kepentingan yang ada di sektor kelautan berkelanjutan. untuk dapat menangulangi masalah-masalah yang Langkah-langkah menuju integrasi dalam perancanaan tata ruang laut diawali dari komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan kerjasama, koordinasi, harmonisasi dan barulah kemudian integrasi. Kebijakan penataan ruang laut pada umumnya, dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan khususnya dewasa ini masih bersifat parsial, baik ditinjau dari sisi cara pandang sektoralisme parsial: baik sektor kegiatan maupun sektor wilayah (keruangan), pembangunan daratan terpisah dengan pembangunan kelautan (Kusumastanto 2002a), maupun dari sudut pandang pengutamaan strategi tertentu saja (Nikijuluw, 2002). Konsep kebijakan penataan ruang pesisir dan lautan yang berkeadilan mengandung implikasi yang luas. Pertama, berkeadilan di sini dapat diukur dari aspek keadilan di antara para lintas pemangku kepentingan, yaitu tripartit “good ocean governance”: negara, sektor privat, dan masyarakat. Negara sebagai pemegang hak penguasaan tertinggi atas bumi, air, dan ruang angkasa berikut seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dapat merencanakan pengelolaan sumberdaya ini secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip desentraliasi kewenangan dan pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan indikator utama kepemerintahan yang baik 13 tersebut, termasuk pula penghargaan atas kearifan lokal dan pengakuan atas hakhak masyarakat hukum adat atas ruang dan sumberdaya pesisir dan lautan. Kedua, berkeadilan di sini mempunyai konotasi pula menurut aspek keruangan. Perencanaan ruang dan pembangunan di sektor daratan tidak boleh merugikan atau berdampak merusak ruang dan ekosistem pesisir dan lautan. Ketiga, berkeadilan di sini harus pula dapat dipandang dari sisi resolusi konflik, yaitu bagaimana perencanaan tata ruang pesisir dan lautan dapat menghindari serta menyelesaikan konflik atas ruang dan penggunaan ruang pesisir dan lautan. Pengembangkan konsep pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkeadilan harus menggunakan perspektif tata ruang dan ekologi sebagai arus utamanya bersama-sama dengan prinsip keadilan dalam aspek tripartit lintas pemangku kepentingan, aspek keadilan dan kesetaraan kewilayahan, serta aspek keadilan dalam menghindari dan menyelesaikan konflik. Artinya bahwa, konsep perencanaan tata ruang daratan, pesisir, dan lautan harus menjadi satu kesatuan perencanaan dengan memaksimalkan saling menguntungkan serta meminimalkan kerugian dan kerusakan. Untuk itu maka prinsip utama yang harus dipedomani adalah, lakukan sinergi perencanaan dan pembangunan wilayah daratan dan pesisir, melalui prinsip kesetaraan dan kesesuaian tata ruang dan ekologi, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sumberdaya alamnya, dan diselenggarakan dalam rangka untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep “milik bersama” dalam doktrin “mare liberum” (kebebasan di laut) Grotius mengakibatkan “dilema kepemilikan bersama” dan “tragedi kepemilikan bersama” karena menganggap sumberdaya sebagai “res nullius” (tidak dimiliki dan oleh karenanya “akses bebas”). Doktrin ini awalnya lahir dari masalah di wilayah luar landas kontinen (200 mil laut), namun sungguh tidak dapat dibenarkan adanya doktrin “akses bebas” dan terjadinya “tragedi tragedi kepemilikan bersama” di wilayah pesisir, maka doktrin ini berlaku pula di wilayah ini. Namun, sejak terbitnya artikel yang ditulis oleh Garret Hardin pada tahun 1968 yang berjudul “Tragedy of the Commons”, konsep tersebut terus dikritik dan akhirnya UNCLOS 1982 mematahkan doktrin “mare liberum”, sumberdaya lautan disepakati sebagai “res communes” atau “properti bersama” dalam konsep laut sebagai “warisan umat manusia”. 14 Faham Grotius yang masih mengilhami banyak orang dewasa ini, yang tidak menyetujui adanya partisi (boundary) atau persil laut, karena menganggap setiap orang berhak dan bebas mengakses, memanfaatkan, dan mengeksploitasi laut sebagai milik bersama. Sedangkan di pihak lain, sebagaimana telah banyak dilakukan dewasa ini, penerapan konsep tentang perlunya partisi atau persil laut justru dilakukan sebagai langkah awal menuju pentadbiran lautan (ocean governance). Kepemerintahan di lautan dimulai dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ruang dan sumberdaya laut secara terpadu dan berkelanjutan, melindungi hak-hak bersama, hak privat dan hak masyarakat tertentu, serta melindungi ekosistem, taman-taman laut dan kawasan lindung lainnya. Praktek masa lalu atas kasus-kasus pengkaplingan laut tertentu yang melanggar azas “akses publik” dan kelestarian alam dan ekosistemnya, telah menyebabkan pemahaman yang kurang tepat mengenai konsep persil-persil laut. Warisan umat manusia itu seharusnya dijaga (agar tidak terjadi konflik dan tidak melampaui batas daya dukungnya) dan dimanfaatkan bersama untuk dapat memberikan kesejahteraan manusia baik sekarang maupun yang akan datang. Namun sering terlihat adanya praktek-praktek ‘konsep’ pemilikan oleh negara, perseorangan dan badan hukum atas persil laut dan pesisirnya secara eksklusif berupa real estat pantai, bangunan dan jasa kelautan, hotel dan resort. Termasuk dalam hal ini adalah berbagai kegiatan pengurukan pantai berbasis legitimasi perijinan (ijin lokasi) atau hak kepemilikan (hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah) yang mengejar keuntungan dengan mengabaikan bahkan merusak ekosistem di lokasi pengurukan maupun daerah di sekitarnya. Pengurukan pantai terlanjur diartikan sebagai reklamasi, suatu penggunaan terminologi yang menyesatkan, karena reklamasi (dari bahasa Inggeris: “reclamation”) berarti: (1) pemulihan kembali tanah tandus (waste land) atau kering melalui irigasi dan pemupukan, atau menghasilkan barang yang berguna (useful) dari (2) suatu proses untuk sisa-sisa produksi (waste products) (Webster’s New World College Dictionary, 1997). Paradigma laut sejak awal abad ke 17, tepatnya tahun 1609, melalui gagasan Grotius (Hugo de Groot, yaitu yang pada waktu itu adalah seorang pelajar 15 berkebangsaan Belanda) tentang “mare liberum” yaitu kebebasan laut, masih membayangi pola pikir saat ini. Padahal konsep ini telah mengakibatkan “common property dilemmas” serta melahirkan “tragedy of the commons” di mana-mana. Menimbulkan konflik-konflik maritim, overfishing, kerusakan ekosistem pesisir dan lautan, polusi, dan pembuangan limbah-limbah berbahaya di lautan. Sesungguhnya ide dasar kebebasan laut ini adalah untuk memberikan legitimasi negara-negara kolonial Eropa untuk menguasai samudera, yang pada akhirnya menguasai dunia mengembangkan wilayah-wilayah jajahannya. Motto mereka: “who command the sea, control the world”. “Mare liberum” inilah awal dari kolonialisme di negara-negara Asia, Afrika, danAmerika Selatan oleh negaranegara barat dengan teknologi perkapalan jarak jauh. Doktrin “freedom of the seas” ini sesungguhnya merupakan reaksi atas doktrin “mare clausum” (laut tertutup), yang terkait dengan pernyataan Paus Alexander VI, Inter Caertera 1493, Treaty Tordessillas 1494, dan klaim Portugal serta Spanyol yang memiliki hegemoni atas wilayah lautan di dunia. Hugo Grotius, sebagaimana kebanyakan orang Belanda pada masa itu, perlu menentang doktrin yang memberikan hegemoni wilayah laut dunia kepada Portugal dan Spanyol karena Belanda mempunyai kepentingan yang sangat besar, khususnya bagi perusahaan VOC (Dutch East India Company) atas wilayah lautan Hindia (East Indies). Setelah itu, khususnya sejak akhir Perang Dunia II, muncul doktrin bahwa lautan dan sumberdaya lautan adalah warisan umat manusia, sehingga semua bangsa di dunia ini mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan yang berada di lautan, tidak terkecuali, kendatipun negara tersebut tidak memiliki laut. Doktrin “the sea is a common heritage of mankind ” ini semakin menguat sejak “Pacem in Maribus”, sebuah Konferensi Institut Kelautan Internasional yang didirikan pada tahun 1972 (Rais et al., 2004, Cicin-Sain and Knecht, 1998). Perdebatan lain terus berlangsung antara konsep imperium atau souvereignity (kedaulatan) dan konsep dominium (kepemilikan). Demikian pula tentang bentuk kedaulatan dan kepemilikan, apakah mutlak, atau bersifat stewardship atau trusteeship. Pada tahun 1982 dunia internasional sepakat atas Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) di mana Indonesia telah meratifikasinya melalui UU No. 17 Tahun 1985. Dalam konvensi ini dengan 16 tegas telah diatur mengenai laut wilayah teritorial, wilayah tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara berikut hak-hak, batasan-batasan serta kewajibannya. Dengan adanya UNCLOS 1982 maka doktrin “ocean space as a common” tidak berfungsi lagi, karena telah ada perangkat hukum pentadbiran lautan yang telah disepakati tersebut, antara lain tentang penetapan Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen suatu negara. Sejak berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 ini, maka mulailah berkembang konsep “marine cadastre”. Konsep ini mengarah kepada obyek wilayah laut teritorial, tidak dapat diterapkan azas “marine cadastre” di ZEE, karena tidak ada “tenure system” pada zona ini dan bukan merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Selanjutnya dalam konferensi Pacem in Maribus (PIM) ke XIX di Lisbon pada tanggal 18-21 November 1991 ditetapkan sebuah tema: “Ocean Governance: National, Regional, Global Institutional Mechanisms for Sustainable Development in the Oceans” atau “Pentadbiran Lautan: Mekanisme Kelembagaan Nasional, Regional, dan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Lautan” (Rais et al., 2004). Pertentangan serta kesesuaian kepentingan dan pemanfaatan secara ekonomi, ekologi, dan sosial-politik atas ruang pesisir dan lautan merupakan isu pokok yang telah berkembang selama beberapa abad ini. Meskipun Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 telah banyak diratifikasi dan dipedomani oleh sebagian besar negara-negara di dunia, dan bahkan telah dikeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan untuk wilayah pesisir dan laut teritorial nasional, namun pandangan berdasarkan doktrin-doktrin kelautan di masa lalu (mare liberum dan mare clausum) masih tetap mewarnai cara pandang dan pola pikir serta tindakan para lintas pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah ini. Berkenaan dengan itu diperlukan suatu pemahaman yang benar, agar lautan sebagai warisan seluruh umat manusia dapat dijaga kelestariannya, sehingga pembangunan pesisir dan lautan dapat terus berlangsung dalam siklus berkelanjutan untuk kesejahteraan umat manusia. Konflik kepentingan di wilayah pesisir (daratan pesisir dan perairan laut) terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan intensitas 17 kegiatan manusia di wilayah tersebut. Berdasarkan publikasi Vallega pada tahun 1990 dan dari hasil penelitian Couper pada tahun 1993 di Laut Mediterania, maka dari 29 kegiatan dan pemanfaatan perairan pesisir dan apabila masing-masing kegiatan diurutkan dalam suatu matriks kegiatan, maka ditemukan 100 pasang kegiatan yang saling bertentangan bertentangan (konflik) dan 60 pasang kegiatan yang saling membahayakan satu dengan lainnya (Cicin-Sain and Knecht, 1998) (Gambar 2). Gambar 2. Interaksi antara penggunaan dan aktifitas ruang pesisir dan laut di Laut Mediterania menurut Couper, 1993 dan Vallega, 1990 sebagaimana gambar dan teks aslinya (Cicin-Sain and Knecht, 1998) Relasi: ▲ Saling bertentangan x Saling membahayakan ■ Membahayakan terhadap kegiatan I □ Membahayakan terhadap kegiatan J √ Saling menguntungkan ● Menguntungkan terhadap kegiatan I ○ Menguntungkan terhadap kegiatan J 18 Telah dikemukakan di atas bahwa penyebab utama dari konflik-konflik tersebut adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Pada sisi lain terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi pemanfaatan rencana tata ruang yang juga merupakan masalah utama, yaitu: 1) Belum merupakan satu kesatuan dengan produk rencana pembangunan daerah lainnya, seperti Propeda; 2) Sering terlambat terhadap proses pembangunan daerah; 3) Kualitas rencana tata ruang yang masih rendah; 4) Sering kali tidak diperkuat oleh aturan perundangan atau belum ada penegakan hukumnya; 5) Belum tersosialisasi dengan baik terhadap seluruh pelaku pembangunan; dan 6) Kualitas sumberdaya pelaku pembangunan di daerah masih perlu peningkatan (Kusumastanto, 2001). Dua tipe utama konflik atas sumberdaya pesisir dan lautan adalah: (1) konflik di antara para pengguna perihal penggunaan atau ketidak-penggunaan wilayah pesisir dan lautan tertentu, dan (2) konflik di antara instansi pemerintah yang menjalankan program pesisir dan lautan (Cicin-Sain and Knecht 1998). “Pengguna” yang dimaksudkan di sini adalah baik pengguna langsung (seperti: operator penambangan dan transportasi minyak dan nelayan), maupun pengguna tak langsung atau pengguna potensial (misalnya kelompok-kelompok lingkungan yang mempromosikan nilai-nilai non-komersil pesisir dan lautan, angota-anggota masyarakat yang tinggal di tempat lain, serta generasi mendatang). Karena sebagian besar sumberdaya kelautan merupakan kekayaan publik, dan terdapat pula kepentingan-kepentingan strategis dari publik dan sosial dalam pengelolaan bagian daratan dari wilayah pesisir, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan para pengguna tak langsung tersebut harus pula diperhitungkan. “ Konflik antar instansi pemerintah” ini dapat berupa konflik di antara lembaga pemerintah pada level yang sama baik di tingkat nasional, provinsi, dan lokal; maupun konflik antar tingkatan lembaga pemerintah yang berbeda. Konflik ini berawal dari berbagai sebab, yaitu karena perbedaan misi dan mandat, perbedaan persepsi dan keterampilan personel, perbedaan partner eksternal instansi pemerintah, dan kurangnya komunikasi dan informasi. Ada beberapa 19 tipikal manifestasi konflik di antara para pengguna, yaitu: (1) kompetisi pada ruang pesisir dan lautan; (2) efek bertentangan dari suatu kegiatan (seperti pengeboran minyak), dengan kegiatan lainnya (seperti perikanan); (3) pengaruh yang bertentangan dalam ekosistem; dan (4) pengaruh pada ekosistem pesisir, seperti kompetisi dalam wilayah pelabuhan. Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir dan lautan di Indonesia, Kusumastanto (2001) berpendapat bahwa penyebab utama dari konflik-konflik tersebut adalah karena tidak adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Contoh-contoh “kecil” konflik dimaksud adalah: konflik penggunaan ruang di Pantai Indah Kapuk Jakarta, konflik nelayan tradisional dan nelayan trawl, konflik antara kepentingan konservasi dengan pariwisata di taman laut Kepulauan Seribu, serta kontroversi “pengurukan” pantai Manado. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diperlukan perencanaan dan pengelolan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu, agar pemanfaatn ruang dan sumberdaya pesisir dan lautan dapat berlangsung secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Khusus berkaitan dengan resolusi konflik, maka pada intinya perencanaan dan pengelolaan pesisir dan lautan secara terpadu ini tipikal berfungsi sentral untuk mengatasi konflik di antara pengguna dan instansi di pesisir dan lautan (Cicin-Sain and Knecht, 1998). Senada pula dinyatakan bahwa masalah pengelolaan pesisir sesungguhnya pertama-tama harus terpusat kepada isu-isu konflik (Kay and Alder 1999). Dalam sejarah sistem politik di Indonesia, periodisasi kebijakan umumnya dibagi ke dalam tiga era, yaitu era orde lama, era orde baru dan era reformasi. Namun dalam konteks pembangunan kelautan, dikhotomi tersebut tidak banyak berpengaruh, karena kebijakan kelautan di masa lalu dan masa yang sedang berlangsung saat ini masih berorientasi kepada paradigma lama. Pada masa lalu orientasi pembangunan mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Sistem kebijakan bersifat social exclusion (sentralistik otoriter) yang menyebabkan timbulnya masyarakat marginal yang miskin dan mempunyai posisi tawar yang lemah. Pelayanan birokrasi bersifat normatif, fungsi pemerintah 20 sebagai provider, dan pengambilan keputusan bersifat top-down (Budiharsono 2001). Konsep mengejar pertumbuhan ekonomi banyak mengabaikan aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan dengan cara mengekploitasi secara besarbesaran sumberdaya pesisir dan lautan yang ada. Konsep pembangunan ini pula telah mengabaikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, hak-hak masyarakat atas sumberdaya di wilayahnya, serta mengembangkan rezim open access yang mengakibatkan terjadinya moral hazard (Kusumastanto 2003a). Strategi masa depan perencanaan dan pengelolaan pesisir memerlukan pergeseran landasan epistemologi pembangunan dari konsep pembangunan berkelanjutan Michael Redclif kepada konsep penguatan pengetahuan lokal Feyereban serta Friberg dan Hettne. Kegagalan doktrin pembangunan berkelanjutan dapat menghancurkan sumberdaya alam pulih di negara dunia ketiga, seperti hutan dan sumberdaya perikanan, karena beban biaya yang ditimbulkan ditanggung sendiri oleh negara berkembang, sementara negara maju tetap meningkatkan aktifitas ekonomi dengan merusak lingkungan hidup. Melalui landasasan epistemologi pembangunan yang bercirikan kearifan lokal ini, maka (communal) property rights atas sumberdaya kelautan diakui, sehingga berkembangnya moral hazard akibat rezim open access atas sumberdaya kelautan seperti pada era Orde Baru dapat dihindari (Kusumastanto, 2003a); Sejalan dengan itu, strategi masa depan perencanaan dan pengelolaan pesisir memerlukan pula pergeseran dari paradigma eksklusi sosial (sentralisitik otoriter) kepada paradigma inklusi sosial (masyarakat sebagai main stakeholder serta diakuinya indegenous knowledge) dalam pembangunan sumberdaya pesisir dan laut. Dalam konsep ini diperhatikan hak-hak kepemilikan (property right) masyarakat, hak ulayat masyarakat hukum adat, hak-hak perolehan rakyat (entitlement), dan manfaat sosial (social benefit) terbesar diberikan kepada masyarakat (Budiharsono, 2001). Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa strategi masa depan perencanaan dan pengelolaan pesisir harus bersifat holistik; dari sisi keruangan harus meliputi perencanaan dan pengelolaan mulai wilayah hulu dan hilir (daratan) hingga lautan secara terpadu, dari sisi kewenangan harus dimulai dari 21 kewenangan daerah dan kearifan lokal; melibatkan semua lintas pemangku kepentingan; berwawasan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam melalui pendekatan konsep carrying capacity; dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui penyelenggaraan good ocean governance. Banyak keberhasilan kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikemukakan. Misalnya di bidang kelembagaan, kebijakan nasional sektor kelautan dan perikanan dapat ditangani oleh suatu lembaga, yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Namun demikian sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1, tidak semua kebijakan publik tersebut membuahkan keberhasilan, masih tersisa pula kegagalan yang memerlukan solusi untuk mengatasinya. Tabel 1. Kegagalan kebijakan publik di sektor kelautan dan perikanan (disarikan dari Kusumastanto, 2003a) No Isu Pokok Kegagalan Kebijakan Baik Yang Ada Mapun Yang Berpotensi Terjadi (Kebijakan Tidak Memuaskan) 1 Pasir laut dan penambangan laut Kerusakan lingkungan, eksploitasi ilegal, berkurangnya mata pencaharian nelayan, konflik kepentingan pusat dan daerah, indikasi KKN 2 Perikanan tangkap Pencurian ikan oleh kapal asing, pengawasan yang lemah, konflik nelayan tradisional dengan nelayan modern dan nelayan asing 3 Pulau kecil Rusaknya ekosistem pulau kecil, indikasi terancam tenggelamnya sebanyak 4.000 pulau pada tahun 2012 4 Pariwisata bahari Kerusakan habitat terumbu karang (sekitar 70% dengan estimasi kerugian sekitar US$ 45 juta), rusaknya sebagian besar hutan mangrove 5 Perikanan budidaya Matinya udang, ikan mas, ikan koi di pulau Jawa akibat virus dengan kerugian sekitar Rp. 90 milyar 6 Pelabuhan umum dan perikanan serta lemahnya Armada Laut Nasional Pendangkalan beberapa pelabuhan tradisional, belum terdesentralisasinya perijinan pelabuhan, daya saing angkutan laut nasional yang rendah 7 Embargo hasil perikanan Adanya ancaman embargo ikan budidaya khususnya dari Singapura dan Jerman, belum dicabutnya embargo udang dari Amerika Serikat, ancaman embargo ikan tuna 8 Sumberdaya manusia kelautan Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya laut, rendahnya daya saing pelaut Indonesia 9 Degradasi lingkungan pesisir dan laut Terjadinya pencemaran sumberdaya hayati laut oleh logam berat dan buang limbah yang menghancurkan industri pertambakan, terjadinya abrasi pantai di beberapa daerah 10 Keamanan laut Nelayan merasa tidak aman melakukan penangkapan ikan di laut, perusahaan merasa tidak aman melakukan pengangkutan barang di laut 11 Kelembagaan (retribusi hasil perikanan) Ketidakjelasan kewenangan untuk memungut retribusi hasil perikanan dalam era otonomi daerah 12 Pelanggaran HAM Penggunaan tenaga anak-anak dalam bisnis kelautan 22 Masalah kebijakan publik timbul apabila kondisi sumberdaya alam dan lingkungan tidak sama dengan yang diharapkan, atau dengan kata lain ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Pentingnya peranan analisis kebijakan nampak jelas di sini serta merupakan kebutuhan untuk menuju pencapaian suatu “good ocean governance”. 2.3. Konsep “Marine Cadastre” Aspek hukum konsep “Marine Cadastre” ke dalam merupakan bagian dari konstitusi dan sistem hukum negara yang bersangkutan, sedangkan keluar merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan internasional yang tertuang di dalam United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS). Demikian pula, ditinjau dari aspek keilmuan studi “Marine Cadastre”, konsep ini merupakan bagian integral dari dasar teori dan konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, atau sering pula disebut Integrated Coastal and Ocean Zone Management (ICOZM), atau Integrated Coastal and Ocean Management (ICOM). “Marine cadastre” belum lama dikenal karena memang masih merupakan konsepsi baru. Demikian pula belum banyak peneliti yang tertarik atau mendalami topik ini. Sudah banyak penelitian yang mendalami bidang pengelolaan dan penataan ruang pesisir dan laut dari berbagai aspek atau pendekatan, namun masih sulit sekali didapatkan penelitian yang mengaitkan bidang ini dengan konsep kadaster, yaitu: hak, batasan, dan kewajiban dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang. Sistem penguasaaan lahan mengenal adanya konsep batas lahan. Demikian pula dalam sistem pesisir dan laut, konsepsi batas-batas (boundary system) penguasaan dan pemanfaaatan lahan pesisir dan lautan mengenal pula sistem batas, zonasi, atau persil. Sesungguhnya sistem batas-batas perencanaan, penguasaan, pemanfaatan dan pemantauan atau pengawasan ini telah dikenal sejak lama. Pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran persil atau zonasi laut bukanlah merupakan hal yang baru. 23 Misalnya di Jepang, dokumen tentang hak penguasaan dan hak ulayat laut telah dikenal sejak Era Feodal (1603 – 1867). Formalisasi keberadaan hak ulayat laut pada masa kekaisaran Edo dipercaya didasarkan oleh tradisi yang berlaku sebelumnya. Setelah restorasi Meiji pada tahun 1868, maka pada tahun 1876 pemerintah Jepang mengambil alih seluruh kepemilikan atas perusahaan perikanan, kemudian menerbitkan lisensi dan perijinan perikanan perorangan dengan disertai pajak (Ruddle, 1992). Filosofi kadaster adalah “the boundary of use” atau “the boundary of tenure”, yaitu batas atau zonasi penguasaan, penggunaan, serta pemilikan lahan. Sejarah dan filosofi kadaster dapat ditarik kembali jauh ke masa sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi di tepi Sungai Nil, Mesir, di mana terhampar luas daerah- daerah pertanian yang subur. Penduduk di sekitar sungai ini telah menikmati hidup yang cukup makmur dari hasil pertanian serta perdagangan melalui transportasi sungai. Namun suatu ketika terjadilah banjir besar akibat meluapnya air sungai yang cukup deras arusnya sehingga merusak tanah pertanian, rumah dan bangunan lainnya (permukiman penduduk) di sekitar sungai termasuk merusak batas-batas tanahnya. Pasca kerusakan akibat bencana alam tersebut, penduduk setempat membentuk tim untuk melakukan pengukuran pengembalian (rekonstruksi) batas-batas tanah yang telah hilang. Rekonstruksi batas-batas lahan ini tidak hanya untuk pengembalian batas penggunaan dan pemilikan lahan saja, namun juga dimaksudkan untuk memungut kembali pajak-pajak tanahnya. Sejak itu dikenallah kadaster sebagai suatu kegiatan bahkan institusi yang melakukan pengukuran, pemetaan dan pendaftaran tanah. Bentuk-bentuk persil laut dimaksud selama ini dikenal sebagai: pemintakat (zonasi) laut, batas budidaya ikan–kerang–rumput (biota) laut (aquaculture), batas penambangan pasir laut, batas alur pelayaran, batas laut lindung, batas wilayah hak ulayat laut dan sebagainya. Lebih jauh lagi dalam konteks penetapan batas administrasi pemerintahan dan batas kedaulatan negara, yaitu batas- batas wilayah laut Kabupaten dan Kota, Propinsi, batas wilayah laut Negara (territorial sea), batas wilayah tambahan (contiguous zone), dan batas ZEE, semuanya adalah merupakan penerapan dari konsep persil-persil laut. 24 Gambar 3. Persil-persil laut: ijin-ijin penambangan pasir laut di Riau (kanan) dan blok-blok penambangan minyak dasar laut (blok Ambalat) di wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sarawak, Malaysia (Rais, 2002a; dan KOMPAS, 1 November 2004) Isu-isu “mengkapling” laut acapkali dilempar sebagai isu yang berkonotasi negatif tanpa mengindahkan substansi atau pokok masalahnya. Kapling atau zonasi atau persil laut justru sangat diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, baik sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengelolanya, arahan, evaluasi, pemantauan, maupun perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang dan sumberdaya pesisir dan laut. Gambar 3 di atas menunjukkan beberapa “fakta” pengkaplingan laut dewasa ini di Indonesia, yaitu kapling ijin-ijin penambangan pasir laut di Riau dan “claim” Pemerintah Indonesia atas “kapling laut” yang diberi nama Blok Ambalat, yang di pihak lain oleh Pemerintah Malaysia diklaim pula sebagai Blok YZ. Konsep “marine cadastre” merupakan pengembangan dari Kadaster Darat atau “land cadastre”. Federasi Surveyor Internasional (FIG: Federation Internationale des Geometres) memberikan definisi dan ilustarsi kadaster sebagai berikut (Gambar 4): “A Cadastre is normally a parcel based and up-to-date land information system containing a record of interests in land (i.e. rights, restrictions, and responsibilities). It usually includes a geometric description of land parcels linked to other records describing the nature of the interests, and ownership or control of those interests, and often the value of the parcel and its improvements. It may be established for fiscal purposes (e.g. valuation and equitable taxation), legal purposes (conveyance), to assist in the management of land and land use (e.g. for planning and other administrative purposes), and enables sustainable development and environmental protection” (FIG, 1995). 25 Gambar 4. Ilustrasi konsep kadaster (FIG, 1995) Cukup banyak definisi tentang “marine cadastre”, namun beberapa pengertian berikut ini cukup mewakili konsep-konsep dimaksud, yaitu antara lain adalah: a. U.S. DOC: United States Department of Communication–NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration (2002): “The U.S. Marine Cadastre is an information system, encompassing both nature and spatial extent of interests in property, value and use of marine areas. Marine or maritime boundaries share a common element with their land-based counterparts in that, in order to map a boundary, one must adequately interpret the relevant law and its spatial context. Marine boundaries are delimited, not demarcated, and generally there is no physical evidence of the boundary”. b. Rais (2002a): “Marine Cadastre atau Kadaster Laut adalah penerapan prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut, yaitu mencatat: penggunaan ruang laut oleh aktifitas masyarakat dan pemerintah; ruang laut yang dilindungi, dikonservasi, taman nasional, taman suaka margasatwa, dan sebagainya; dan penggunaan ruang laut oleh komunitas adat.” 26 c. Binns (2004): “A Marine Cadastre is a spatial boundary management tool, which describes, visualises, and realises legally defined boundaries and associated rights, restrictions, and responsibilities in marine environment, allowing them to be more effectively assessed, administered and managed”. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, serta ditambah dengan beberapa referensi konsep dari Universitas Melbourne Australia, Universitas New Brunswick, Canada, dan FIG: International Federation of Surveyors, maka dapatlah dirumuskan suatu definisi operasional “marine cadastre” sehubungan dengan penelitian ini, yaitu: “Marine Cadastre” adalah sistem penyelenggaraan administrasi publik yang mengelola dokumen legal dan administratif, baik yang bersifat spasial maupun tekstual, mengenai kepentingan berupa: hak, kewajiban, dan batasannya, termasuk catatan mengenai nilai, pajak, serta hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada dan berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut. “Marine Cadastre” diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tertib hukum, tertib administrasi, tertib penggunaan dan tertib pemeliharaan ekosistem laut serta mendukung tertib perencanaan, penataan, dan pengelolaan wilayah laut secara spasial terpadu. Sebagai suatu bagian dari sistem hukum (“legal cadastre”), maka “marine cadastre” ditujukan untuk mengelola dan menyediakan data, informasi, dan dokumen jaminan kepastian hukum atas pemanfaatan ruang pesisir dan laut. “Marine Cadastre” merupakan pengembangan dari “land cadastre”, namun tidak semua aspek “land cadastre” dapat diterapkan ke dalam konsep “marine cadastre”. Berikut adalah perbedaan dan kesamaan di antara keduanya (Tabel 2). Beberapa konsep dasar “marine cadastre” melengkapi pengertian tersebut misalnya dapat dikemukakan tentang sistem batas. Dalam beberapa hal batas persil laut dapat ditandai dengan benda fisik di permukaan maupun di dasar laut dangkal, namun dalam banyak hal batas persil laut hanya ditetapkan dalam sistem koordinat geografis namun tidak dibangun tanda-tanda fisik batas di laut. 27 Tabel 2. Perbedaan dan persamaan antara kadaster pertanahan (Land Cadastre) dengan kadaster kelautan (Marine Cadastre) (dari berbagai sumber serta modifikasi dari BPN – LPPM ITB, 2003) No Unsur & Aspek “Land Cadastre” “Marine Cadastre” 1 Kepemilikan Dikenal adanya Hak Milik atas (persil) tanah (Pasal 16 UUPA); Tidak dikenal hak milik pribadi atas bidang atau persil laut, yang ada adalah pembagian kewenangan pengelolaan wilayah laut, baik diberikan kepada Negara, publik, masyarakat hukum Adat, badan usaha, maupun perseorangan (Rais, 2002.a); 2 Penguasaan & pemanfaatan Dikenal hak-hak sementara yaitu: HGB, HGU, HP (Pasal 28, 35, dan 41 UUPA); Dikenal Hak Guna Air, Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan (Pasal 47 UUPA); Hak Atas Ruang (UU No.24/1992 jo. PP 69/1996) Lisensi, konsesi dan perijinan eksploitasi sumberdaya laut (undang-undang sektoral); Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan (Pasal 46 UUPA); 3 Administrasi Mencatat batas administratif (desa, kabupaten/kota, provinsi) dan batas setiap bidang tanah baik yang ada haknya maupun tidak; Dikenalnya NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah, Daftar Tanah, dan Sistem Buku Tanah; Merupakan produk hukum (sertipikat hak atas tanah) dan produk fiskal (PBB & BPHTB); 4 Kelembagaan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai “Legal Land Cadastre” Direktorat PBB & BPHTB Ditjen. Pajak Departemen Keuangan sebagai “Fiscal Land Cadastre” Mencatat persil pesisir dan laut serta batas-batas terkait, hak atas persil termasuk hak adat atau ulayat; Batas-batasnya adalah batas yuridiksi (laut teritorial); batas administratif (provinsi, kabupaten, dan lainnya); batas laut, selat dan teluk; batas estat laut (pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan ekonomi masyarakat, perseorangan, dan badan hukum); Merupakan ruang laut 3-dimensi yang menggambarkan stratifikasi hak pada permukaan laut, kolom air (laut), dasar laut dan tanah di bawahnya (Rais, 2002.a) Belum ada UU yang secara spesifik mengatur perihal “Marine Cadastre” UU terkait: UUPA 1960, UU No. 11 Tahun 1967 (Pertambangan), UU No. 5 Tahun 1990 (Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya), UU No. 24 Tahun 1992 (Penataan Ruang), UU No. 23 Tahun 1997 (Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan UU No. 32 Tahun 2004 (Pemerintahan Daerah); Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur perihal kelembagaan “Marine Cadastre”: Opsi: BPN sepanjang menyangkut administrasi (manajemen) hak-hak (property rights) atas ruang pesisir dan laut; DKP menyangkut perihal administrasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut (coastal and sea resources); 5 Teknis Skala peta 1:1.000 dan 1: 500 untuk perkotaan dan 1:2.000 atau 1:2.500 untuk perdesaan, serta 1:5.000 atau 1:10.000 untuk lokasi perkebunan besar; Skala peta 1:1.000 atau 1:2.500 untuk wilayah “tidal interface”; Warna dan legenda peta minimalis; Warna dan legenda peta: berwarna dan banyak legenda maritim “Maritime boundary system” (sistem batas): • Batas yuridiksi nasional sampai batas laut territorial; “Fixed boundary system” untuk batasbatas persil tanah dan batas administarsi (lihat butir 2 di atas) Skala 1:50.000 – 1:100.000 untuk wilayah laut kabupaten/kota dan provinsi serta laut teritorial; skala 1:100.000 – 1:1.000.000 untuk landas kontinen dan ZEE; 28 No Unsur & Aspek “Land Cadastre” “Marine Cadastre” • • • Peta Kadaster Darat: menggambarkan batas-batas zonasi lahan yang diukur dan berbagai jenis hak dan penggunaannya Sistem koordinat menggunakan proyeksi TM 3o (Transverse Mercator dengan lebar zone 3o) dengan referensi datum WGS1984 (a = 6.378.137 m dan f = 1/298,26); Ruang tanah (lahan) dalam referensi 2dimensi (ukuran luas, panjang dan lebar); 6 Terminologi Dikenal adanya Tanah Negara dan Tanah Hak Batas adminsitratif dan batas zona khusus (laut lindung, kawasan konservasi, zona perikanan, dan sebagainya); Batas estat laut (batas pemanfaatan dan penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi oleh masyarakat, perseorangan, dan badan hukum); Batas kewenangan Negara sesuai UNCLOS (Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif); Peta Kadaster laut: memuat informasi persil-persil pesisir dan laut serta batas-batasnya yang terkait, hak dan ketentuan hukum lainnya atas persil tersebut termasuk hak adat dan hak ulayat, serta kewenangan yuridiksi yang menyangkut sumberdayanya (Rais, 2002.a) Rais (2003: hal.27-28) mengusulkan agar semua peta di Indonesia kompatibel, maka sistem yang digunakan sebaiknya sistem koordinat geosentris dengan Datum Geodesi Nasional Indonesia (DGNI) 1995 yang mengacu kepada WGS 1984 (a = 6,378,137 m and f = 1/298,26); Ruang laut dalam referensi 3-dimensi yang menggambarkan stratifikasi hak (rights) pada permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya (Rais, 2002.a); Dikenal pula adanya Tanah Negara, yaitu tanah yang tertutup oleh air laut dan dasar laut (sea bed) dan tanah di bawahnya, serta Laut Negara (untuk menghindari istilah Laut Provinsi, Laut Kabupaten, atau Laut Kota berkaitan dengan UU No. 32 Tahun 2004) (a.l. Rais, 2002.a); Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juncto UUPA, UNCLOS juncto UU No. 17/1985, laut dapat dipartisi dalam persil-persil untuk penguasaan dan pemanfaatannya. Contoh, untuk ruang usaha ekonomis seperti bididaya ikan, rumput laut, kerang, penambangan dasar laut dan di bawah dasar laut; sebagai ruang laut konservasi seperti laut lindung dan taman nasional; sebagai ruang laut wisata dan rekreasi seperti arena selam, surfing, sailing dan fishing-sport; serta sebagai ruang laut publik seperti alur pelayaran, pelabuhan dan sebagainya (Rais, 2002). Konsep “marine cadastre” di Australia melingkupi pengggunaan dasar laut (sea floor), misalnya untuk jalur pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dalam (Binns, 2004). Bahkan di Kanada penyelenggaraan “marine cadastre” merupakan barometer keberhasilan dari sebagian indikator ‘good governance’ (Nichols et al., 2001). 29 Konsep diagram “marine cadastre” yang banyak dijadikan referensi adalah gambaran yang dikemukakan Melbourne University, Australia (Gambar 5). Model ini banyak digunakan oleh berbagai pihak dan peneliti sebagai referensi. Konsepsi ini memberikan pendekatan holistik dalam gagasannya, yaitu dengan menghubungkan keterkaitan tiga pintakat kegiatan: 1) Kegiatan terestrial (aktifitas urban dan kegiatan industri serta pertanian), 2) Kegiatan pesisir (pertanian, turisme dan rekreasi, serta hak-hak masyarakat adat), dan Gambar 5. Diagram Konsepsi “Marine cadastre”: hak cipta © The University of Melbourne sebagaimana gambar dan teks aslinya (Collier, 2002) 30 3) Kegiatan kelautan (kawasan lindung laut, budidaya laut, eksploitasi mineral dan energi, pelayaran, wilayah tangkapan ikan, kabel dan pipa dasar laut, harta karun, serta tempat pembuangan limbah di lautan). 2.4. Relevansi Konsep “Marine Cadastre” Dengan Teori ICZOM Clark (1992) mengemukakan bahwa: “ICZM is a planning and coordinating process which deals with development management coastal reasources”. Lewat definisi-definisi teori dasar ICZM tersebut di atas, dapat ditarik benang merah yang tajam antara konsep dan teori dasar ICZM dimaksud dengan konsep “marine cadastre”, teristimewa pada aspek-aspek: penataaan ruang dan sumberdaya secara komprehensif, perencanaan pemanfaatan sumberdaya dan kawasan, media penyelesaian konflik, dan pengakuan hak-hak penguasaan dan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Relevansi ini kemudian lebih menonjol lagi pada tataran praktik ICZM, khususnya pada aspek penataan ruang pesisir dan lautan, serta aspek penguasaan dan pemanfaatan (tenurial) (Gambar 6). Melalui gambaran di atas maka nampak setidaknya terdapat 8 (delapan) komponen grand theory ICZOM yang terkait erat dengan konsep “marine cadastre”, yaitu: 1) ICZOM adalah pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara: a. Melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir beserta sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalamnya; menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian; b. Merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Dahuri et al. 2001); 2) ICOZM menurut Clark, adalah: c. A planning and coordinating process which deals with development management and coastal resources and which is focused on the land/water interface; 31 d. ICM menurut Cicin-Sain and Knecht: “can be defined as a continuous and dynamic process by which decisions are made for sustainable use, development, and protection of coastal and marine areas and resources; ... is a process that recognizes the distinctive character of the coastal area - itself a valuable resource - and the importance of conserving it for current and future generations; … has major functions as: • Tata Ruang dan proses koordinasi • Orientasi Kebijakan dan Pengembangan Manajemen Strategis untuk Isu-isu Konflik Pemanfaatan Sumberdaya (Clark, 1992) • Penilaian Spasial Komprehensif • Penentuan Tujuan, Sasaran & Perencanaan Pemanfaatan Kawasan (Dahuri et al., 2001) • • • • Tata Ruang Arahan Pemanfaatan Resolusi Konflik Arahan Kesesuaian (Cicin Sain and Knecht, 1998) Teori Dasar ICOZM Hak “Marine Cadastre” Philosofi: Batas Pemilikan Batasan Kewajiban Gambar 6. Relevansi Konsep “Marine Cadastre” Dengan Teori Dasar dan Praksis ICOZM e. Area planning: plan for present and future uses of coastal and marine areas; provide a long-term vision; Promotion of economic development: promote appropriate uses of coastal and marine areas (e.g., marine aquaculture, ecotourism); 32 f. Stewardship of resources: protect the ecological base of coastal and marine areas, preserve biological diversity, and ensure sustainability of uses; g. Conflict resolution: harmonize and balance existing and potential uses, address conflicts among coastal and marine uses; Protection of public safety: protect public safety in coastal and marine areas typically prone to significant natural, as well as human-made, hazards; h. Proprietorship of public submerged lands and waters: as governments are often outright owners of specific coastal and marine areas, manage government-held areas and resources wisely and with good economic returns to public (Cicin-Sain and Knecht, 1998). 2.5. Sejarah “Marine Cadastre”: Munculnya Filosofi “The Boundary of Tenure” Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kadaster adalah kantor tempat pendaftaran hak milik (Badudu dan Zain, 2001). Selanjutnya dalam pengertian modern, kadaster dikenal sebagai suatu sistem informasi pertanahan publik. Bab Pendahuluan telah menguraikan perihal asal mula dikenalnya kadaster, yaitu kembali ke tahun 2.000 S.M. di tepian sungai Nil, Mesir, di mana dalam sejarah tercatat pernah dilaksanakan kegiatan rekonstruksi batas-batas kepemilikan tanah akibat banjir besar yang melanda tempat permukiman dan daerah pertanian penduduk. Sejak peristiwa di sekitar sungai Nil inilah, yaitu diselenggarakannya pengukuran, pemetan dan pencatatan serta pendaftaran kembali tanah-tanah pertanian yang kemudian dikenal dengan nama “kadaster”. Demikian pula selanjutnya dikenal konsep “the boundary of tenure” atau “the boundary of use” sebagai dasar filosofi kadaster. Sejarah kadaster kemudian berkembang seiring dengan perkembangan ilmu, khususnya matematika. Dalam sejarah dicatat pula bahwa pada tahun 1.500 SM di Mesir mulai dikenal pengukuran sudut secara matematis dengan cara 33 mengamati lintasan sinar matahari pada permukaan batu ukur (stone tablet) dengan menggunakan mistar vertikal (Gnomon) di atasnya. Namun alat ukur sudut yang pertama dikenal adalah instrumen yang mereka kembangkan kemudian yang disebut Groma, yaitu empat butir batu yang tergantung oleh tali pada keempat ujung batang kayu yang terikat saling tegak lurus. Alat ini dipakai selama ribuan tahun termasuk untuk pembangunan piramid dan bangunan-bangunan kekaisaran Romawi. Sejak itu pula dikenal seorang yang bernama Lucius Aebutius Faustus sebagai “Agremèntor” atau juru ukur tanah yang pertama (Wallis, 2005). Periode berikutnya, Eratosthenes (275-195 SM) dikenal sebagai “bapak” konsep geometri (Lelgemann, 2005), yang kemudian digunakan pula sebagai dasar pemodelan (pengukuran dan pemetaan) batas tanah. Sedangkan alat ukur sudut pertama yang merupakan cikal bakal theodolite yang dikenal sekarang adalah Dioptra, yang dalam bahawa Yunani artinya instrumen untuk melihat dengan jelas, dibuat sekitar tahun 150 SM (Wallis, 2005). “The mile stone” sejarah kadaster berikutnya adalah program Napoleon Bonaparte (1789–1821) untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Perancis guna mengatur perekonomian dan membiayai perangnya melalui pungutan pajak tanah dan hasil bumi serta kekayaan penduduk. Napoleon berhasil membangun kadaster di Perancis dalam masa pemerintahannya, bahkan ia sempat mengeluarkan “fatwa” yang cukup terkenal, yaitu: “Barang siapa dapat membangun suatu kadaster yang baik, sungguh layak dibuatkan patung baginya”. Pengenalan istilah kadaster di Indonesia pertama kali dilakukan oleh pemerintah jajahan Belanda ketika membentuk Kadastrale Dienst (Dinas Kadaster) pada tahun 1823, yaitu sebuah dinas di bawah Departemen Kehakiman. Pemerintah pendudukan Jepang merubah nama dinas ini menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan Kantor Pendaftaran Tanah. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Agraria berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1955, namun baru dua tahun kemudian, yaitu melalui Keppres Nomor 190 Tahun 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah yang semula di bawah Departemen Kehakiman dialihkan dalam lingkungan tugas Kementerian Agraria. 34 Sedikitnya ada delapan tonggak sejarah batas laut dan delapan periode konsep awal sejarah batas laut dan konsep awal “marine cadastre” sebagaimana disarikan dalam Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Sejarah Batas Laut dan Konsep Awal “Marine Cadastre” (dari berbagai sumber utamanya Soebroto et al., 1983 dan BPN-LPPM ITB, 2003) Sejarah Batas Laut Konsep Awal “Marine Cadastre” Tahun Peristiwa Tahun 1945 Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan yuridiksinya atas kekayaan sumberdaya alam yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya di sepanjang landas kontinen yang mengelilingi pantainya. Pengumuman ini menggugah negara-negara pantai lainnya untuk berbuat yang sama. 1982 Lahirnya UNCLOS 1982 merupakan “tonggak sejarah” yang melahirkan konsep “Marine Cadastre” berangkat dari filsofi dan isu “the boundary of use”. 1989 Sue Nichols, Kandidat Ph.D. di Universitas New Brunswick, Kanada menulis tentang “Water Boundaries – Coastal” dan ide awal konsep “Marine Cadastre”. 1991 Konferensi Pacem in Maribus di Lisbon menetapkan tema “Ocean Governance” yang merupakan ‘cikal bakal’ pula dari berkembangnya konsep “Marine Cadastre”. 1999 Konsep ini mulai ramai dibicarakan dalam seminar, workshop, dan juga dalam proyekproyek penelitian, antara lain: 1957 Deklarasi Djuanda: Pengumunan Pemerintah tentang Perairan Indonesia dalam suatu Konsep Wawasan Nusantara sebagai konsekuensi logis dan geografis bagi sebuah negara kepulauan (archipelagic state). Deklarasi yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957 ini sekaligus merupakan “kontra” undang-undang pemerintah kolonial Belanda: “Territoriale Zee- en Maritiem Kringen Ordonantie 1939” (Ordonansi Laut Wilayah dan Lingkungan Maritim). 1958 Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke I digelar di Geneva. 1960 Digelar Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke II di Geneva; Pada tahun yang sama, terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang sekaligus merupakan “pengukuhan” Deklarasi Djuanda 1957. Peristiwa • Canadian Center for Marine Communication menerbitkan Draft MGDI: Marine Geospatial Data Infrastructure; • Sue Nichols dan David Monahan menulis tentang: Fuzzy Boundaries of the Sea; • Sue Nichols, David Monahan, dan Michel Sutherland menulis tentang menawarkan konsep Good Ocean Governance; • Terminologi “Marine Cadastre” mulai dikenalkan, antara lain Sue Nichols, Hoogsteden dan Robertson, serta Grant; 2000 Sebuah proyek “Marine Cadastre” dilaksanakan di Kanada oleh beberapa peneliti, yaitu Sam Ng’ang’a, Sue Nichols, Michel Sutherland, dan Sarah Cockburn; 35 Sejarah Batas Laut Tahun 1969 1973 1980 Peristiwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969 menerbitkan Pernyataan atau Pengumuman tentang Landas Kontinen dalam perairan laut Indonesia. Konsep Awal “Marine Cadastre” Tahun Peristiwa 2001 Kelompok Kerja 2 PCGIAP – FIG mengeluarkan Resolusi No. 6 tentang “Marine Cadastre” diawali dari PCGIAP Meeting 7th di Tsukuba, Jepang (24 – 27 April 2001) dan pertemuan lanjutan di Penang, Malaysia (11 – 12 September 2001). Dalam kedua pertemuan ini Williamson dan Widodo menyampaikan pula presentasi perihal konsep “Marine Cadastre”. Terbit UU Nomor 1 Tahun 1973 Tanggal 6 Januari 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; Dalam tahun yang sama mulai digelar Konferensi PBB tentang Hukum Laut ke III digelar di New York; Sidang ini berlangsung bertahap selama 9 (sembilan) tahun hingga sidang yang ke 12 pada tahun 1982. 2002 Tercatat banyak seminar, workshop maupun penelitian mendalami konsep “Marine Cadastre”, bahkan US DOC-NOAA telah menetapkan kebijakan tentang “US Marine Cadastre”; Beberapa penulis telah pula secara intensif membahas konsep ini, misalnya: • Collier, Leahly, dan Williamson mengusulkan konsep “Australian Marine Cadastre”; • Jacub Rais menawarkan konsep “Marine Cadastre” untuk Indonesia; • Beberapa “statement” dalam surat khabar juga menyoroti perihal “Marine Cadastre”, antara lain: Budi Sulistyo dan Sarwono Kusumaatmadja dalam harian KOMPAS; 2003 LPPM ITB Bandung berkerjasama dengan BPN menghasilkan dokumen “Studi Pengembangan Kadaster Kelautan di Indonesia”; Sementara itu Widodo menyampaikan makalah tentang “Spatial Data Infrastructure and Marine Cadastre” dalam sebuah FIG Weekly Meeting di Paris; • Secara berurutan Tamtomo dan Widodo menyampaikan makalah tentang “Marine Cadastre” dalam 3rd FIG Regional Conference di Jakarta; • Telah terbit buku “Menata Ruang Laut” terbitan Pradnya Paramita ditulis oleh Rais et al. termasuk perihal “Marine Cadastre”; • Telah diselenggarakan sebuah seminar oleh FT UGM “Kadaster Laut dan Peran Geodesi-Geomatika Untuk Masyarakat” di Yogyakarta; • Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat mencanang-kan “Implementation Plan for a Multipurpose Marine Cadastre” (US DOI – MMS, 2004) Pengumuman Pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif 1982 Ditandatanganinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) oleh 119 negara di dunia pada tanggal 7 Oktober 1982. 1983 Terbit UU Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. 1985 1996 Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985. Terbit UU Nomor 16 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti dan penyempurnaan PERPU Nomor 4 Tahun 1960. 1999 Terbit UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur batas wilayah laut provinsi dan kabupaten/kota. 2004 Terbit UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999. 2004 2005 Jacub Rais dan J.P.Tamtomo menulis tentang kasus Blok Ambalat: “Make Marine Cadastre Not War” (KOMPAS, 11-04-2005) 36 2.6. Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan “Marine Cadastre” Tujuan penyelenggaraan “marine cadastre” oleh suatu negara, adalah untuk: 1) Mengadministrasikan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut berikut sumberdaya alam dan buatan serta termasuk pula semua kepentingan, hak, batasan dan kewajiban yang ada di wilayah itu; 2) Mewujudkan ketertiban wilayah, yaitu tertib administrasi, tertib hukum, tertib tata ruang wilayah, tertib pemanfaatan dan penggunaan ruang dan sumberdaya wilayah, serta tertib pemeliharaan wilayah dan ekosistem wilayah; 3) Memberikan perspektif manajemen sumberdaya alam kepada pemerintah dan mengembangkannya agar manfaat dan kegunaan “marine cadastre” menjadi lebih nyata bagi para pemangku kepentingan, seperti: pemerintah dan daerah, sektor industri, serta masyarakat akademis (US DOI–MMS, 2004) dan masyarakat disektor pesisir dan kelautan khususnya; 4) Menyediakan infrastruktur data spasial yang komprehensif di mana hak, batasan, dan kewajiban di lingkungan pesisir dan kelautan dapat dinilai, diadministrasikan, dan dikelola (US DOI–MMS, 2004); 5) Menyediakan informasi wilayah laut yang berguna untuk: (1) mengidentifikasi masalah dan prioritas; (2) merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pembangunan kelautan yang sesuai dan tepat sasaran; (3) membantu perencanaan tata guna ruang dalam aktifitas pembangunan kelautan; (4) menyediakan suatu proses perijinan yang proporsional dalam mendukung pembangunan perekonomian sektor kelautan; (5) dapat menerapkan suatu sistem pengelolaan pajak yang tepat dan efisien; dan (6) mengawasi tata guna ruang untuk dapat mengidentifikasi permasalahan baru dan mengevaluasi pengaruh dari suatu kebijakan kelautan (BPN – LPPM ITB, 2003). Direktorat Jenderal Pajak telah memungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas bangunan-bangunan kelautan seperti penambangan minyak “offshore”, rumpon dan bagan-bagan ikan, dan bangunan kelautan, jasa kelautan serta akuakultur lainnya. Manfaat dari penyelenggaraan “marine cadastre” bagi suatu negara, adalah: 1) Tersedianya mekanisme untuk mendefinisikan, menggambarkan, menganalisis, dan menghitung, serta menyatakan hak kedaulatan dari setiap 37 jengkal lahan di wilayah pesisir dan lepas pantai berikut kekayaan alam atau sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya; 2) Tersedianya mekanisme untuk mengidentifikasi tumpang tindih dan konflik hak, kepentingan, dan tanggungjawab di wilayah pesisir dan lautan serta untuk mendorong dan menyelenggarakan kepemerintahan yang baik di bidang kelautan (good ocean governance) (US DOI – MMS, 2004); 3) Tersedianya serta meningkatnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan efisiensi penggunaan sumberdaya dan ruang laut sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap terjadinya degradasi lingkungan akibat kegiatan pembangunan kelautan (BPN – LPPM ITB, 2003); Sementara itu, dalam pengembangan konsep “Multi-Purpose Marine Cadastre”, maka Tamtomo (2006) telah mengenalkan konsep Total Asset Value (TAV), yaitu agregat nilai Total Real Property Value (TRPV) ditambah dengan Total Economic Value (TEV) dari suatu “persil laut”, khususnya persil pada perairan pesisir (near shore parcel). 2.7. Aspek Yuridis Dalam Penyelenggaraan “Marine Cadastre” Kadaster, ditinjau dari definisi dan pengertiannya sendiri, adalah sebuah institusi hukum. Pertama, karena di dalam sistem kadaster dikandung tiga pilar utama, yaitu 3R (FIG, 1995, Dale and McLaughlin, 1988), yang terdiri dari: rights: hak-hak, restrictions: batasan atas penguasaan dan penggunaan hak-hak tersebut, dan responsibilities: tanggungjawab terhadap penguasaan dan penggunaan hak-hak tersebut. Oleh karena itu maka kadaster memenuhi syarat sebagai sebuah struktur hukum. Kedua, karena tujuan kadaster adalah mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi dan praktik hukum atas penggunaan hak, pemenuhan kewajiban, dan implementasi batasan tersebut (Larsson, 1991); maka dengan sendirinya kadaster merupakan dan menjalankan fungsi-fungsi hukum. Sehubungan dengan itu, maka “marine cadastre”, meskipun tidak dengan serta merta dapat langsung dipersamakan dengan kadaster daratan karena adanya perbedaan sifat dan karakteristik obyek dan subyek hukumnya, merupakan institusi hukum pula, karena “marine cadastre” memenuhi kedua syarat tersebut 38 di atas. Apabila “marine cadastre” telah mempunyai dasar hukum bagi legitimasi penyelenggaraannya, maka dengan sendirinya ia akan mempunyai implikasi hukum dalam pelaksanaannya. Cockburn dan Nichols (2002) menyatakan bahwa setidaknya ada 4 (empat) hal yang akan berimplikasi dan oleh karena itu harus dipertimbangkan. Pertama, jenis-jenis hak apakah yang ada dalam konteks kelautan. Kedua, rezim hukum apa yang mengatur atau menentukan hak-hak tersebut. Ketiga, apakah dapat ditentukan atau diletakkan hirarki atas hak-hak tersebut, dan Ke-empat, adalah bagaimana dapat diletakkan hubungan di antara hak-hak tersebut satu dengan lainnya (Gambar 7). Kerangka Hukum “Marine Cadastre” KewenanganNegara Wilayah Hak Administrasi Berpengaruh pada: Hak Privat • Hak Guna Usaha • Hak Penambangan • Hak Kabel Laut Hak Publik • Hak Akses • Hak Penangkapan Ikan • Navigasi, dsb. Gambar 7. Kerangka Hukum Pelaksanaan “Marine Cadastre” (Cockburn dan Nichols, 2002: p.3) Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu kiranya dapat dipahami beberapa karakteristik serta doktrin yang membedakan “land cadastre” dengan “marine cadastre”. Untuk itu perlu merujuk kembali pada Tabel 3 tentang perbedaan dan persamaan antara kadaster pertanahan dengan kadaster kelautan (marine cadastre). Selebihnya, Cockburn, Nichols dan Monahan (2003) mengajak untuk memahami tentang konsepsi persil laut dibandingkan dengan persil tanah. 39 Di laut di mana sumberdaya dan kegiatan, dan oleh karena itu hak, batasan, dan kewajiban, dapat ada atau timbul seiring dengan waktu dan ruang, serta dapat bergerak atau berpindah sesuai perubahan waktu dan ruang, maka konsepsi persil laut menjadi kompleks. Pertama, kepemilikan individual secara penuh, sebagaimana dikenal dalam persil tanah, tidaklah dikenal dalam konteks ruang lautan (sama dengan pendapat Rais, 2002: “ ... the ocean is an heritage of human kind, available to anyone but owned by none ...”, tidak ada hak milik pribadi di lautan, yang ada adalah kewenangan pengelolaan saja). Hak penguasaan dari negara, hak-hak publik, dan hukum internasional adalah faktor-faktor yang akan banyak mempengaruhi hakhak privat, dan dapat dipastikan pula bahwa kepemilikan pribadi yang eksklusif atas atas kolom (persil) laut tidak mendapat pengakuan. Kedua, dapat dikatakan hanya sedikit sekali aktifitas di sektor kelautan yang hanya menggunakan permukaan air laut saja sebagai ruang kegiatan utamanya. Hampir semua kegiatan kelautan sesungguhnya berada pada volume atau kolom laut, sehingga dengan demikian hampir semua hak-hak kelautan, seperti akuakultur, penambangan laut, perikanan laut, dan hak-hak berlabuh dan bahkan navigasi laut secara inheren memiliki sifat-sifat tiga dimensi (bandingkan dengan persil tanah yang bersifat dua dimensi). Demikian pula kemungkinan berlapis-lapisnya beberapa hak yang mungkin ada pada ruang laut sangat terbuka, mengingat banyak kemungkinan sesuatu hak pada kolom permukaan air laut bagian atas berlapis dengan sesuatu hak lainnya pada kolom air di bawahnya, dan bahkan sesuatu hak pada dasar laut (seabed). Untuk mengawasi dan mengatur aktifitas kelautan, gambaran mengenai hak-hak yang ada dalam ruang atau kolom laut yang lebih akurat sangatlah diperlukan. Ketiga, adanya suatu kenyataan bahwa tidak semua atau bahkan pada umumnya batas persil atau kolom laut tidak dapat ditandai dengan batas fisik, khususnya persil laut yang terletak dilepas pantai. Batas-batas tersebut hanya dapat ditandai dalam peta atau publikasi lainnya. Nichols dan Monahan (1999) menamakan sistem penetapan batas persil laut dengan “fuzzy boundary system”, sedangkan Hoogsteden and Robertson. (1999) justru mengatakannya sebagai “seamless boundary system” (tegas). 40 Dalam konteks sistem penguasaan dan pemilikan properti (property tenureships) di Indonesia, maka “state of the arts” konsep “marine cadastre” harus pula mencerminkan kekhasan sistem dimaksud. Dengan kata lain harus ada keberanian untuk meletakkan konsep ini secara aktual, agar dapat menampung kebutuhan masyarakat dan pembangunan, dengan pertimbangan bahwa: 1) Ruang perairan laut teritorial adalah ruang perairan yang dihitung dari ratarata air laut surut terendah sejauh 12 nautical miles ke arah laut; 2) Adanya sistem penguasaan atau pemilikan dalam wilayah perairan pantai dangkal (shallow shore-water), misalnya: rumah-rumah nelayan di atas air laut, bagan-bagan dan keramba ikan, pelantar (“jalan” di atas air laut sebagai akses publik yang dikenal di Kepulauan Riau), dan sebagainya; 3) Adanya kekosongan hukum dalam pengaturan hak-hak kepemilikan di wilayah ini, padahal sistem kepemilikan lahan telah berlaku di masyarakat. Sejalan dengan itu, maka obyek “Marine Cadsatre” dalam perspektif hukum agraria Indonesia harus dapat membedakan antara ruang perairan pantai dan ruang laut. Perlunya pemilahan kedua wilayah ini secara spesifik karena adanya perbedaan substansial di antara keduanya, meskipun keduanya merupakan satu wilayah yang tidak terpisahkan. Perbedaan dimaksud adalah: 1) Ruang perairan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan (fragile), baik ditinjau dari aspek fisik dan ekosistem (merupakan wilayah “tumpahan” seluruh dampak aktifitas di daratan yang terbuang atau mengalir ke laut), maupun ditinjau dari aspek hukum dan sosial-ekonomi, yaitu sangat berhubungan erat dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (land tenureships) daratan pesisir; 2) Ruang perairan pantai merupakan wilayah perairan laut dangkal, termasuk wilayah yang pada saat air laut surut nampak sebagai ruang daratan, dan oleh karena itu tenureship system lahan ini dapat dicirikan oleh tipologi atau karakteristik tenureships daratan (land-based tenure) maupun ruang laut (seabased tenure) secara seimbang; Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka jenis-jenis hak yang dapat dipunyai oleh perseorangan serta badan hukum publik dan privat, adalah hak-hak menurut UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya. 41 3) Ruang laut, yaitu ruang laut teritorial di luar perairan pantai, di lain pihak, umumnya tidak berkaitan langsung dengan tenureship system di daratan; Hak-hak yang sesuai di wilayah ini adalah Hak Guna Perairan, kecuali untuk konstruksi pengeboran minyak lepas pantai (rigs) dan bagan-bagan ikan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan. Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan akan ditelaah mengenai hakhak di wilayah perairan pantai dan laut dalam konteks lokus penelitian khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. 2.8. Pemetaan dan Penetapan Hak-Hak di Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Kerangka “Marine Cadastre” Beberapa negara di dunia telah melaksanakan “marine cadastre” dalam pengelolaan sumberdaya dan wilayah pesisir dan lautan. Negara-negara dimaksud antara lain: Canada, Amerika Serikat, dan Australia. Di Negara Belanda, meskipun tidak menggunakan nomenklatur “marine cadastre”, namun batas laut teritorial negara ini telah diukur dan dipetakan serta didaftar dalam Kantor Kadaster Belanda, semacam Badan Pertanahan Nasional di Indonesia. Dalam Gambar 8 berikut ini adalah contoh pelaksanaan “marine cadastre” pada pilot proyek di Negara Bagian Victoria, Australia. Peta ini menggambarkan berbagai representasi hak yang cukup lengkap, yaitu hak-hak publik, privat, dan kolektif (adat), serta hak-hak atas pengelolaan sumberdaya dan lingkungan hidup. Hak-Hak Guna Dasar Laut (sea-bed rights) untuk jalur pipa dan kabel bawah laut dipetakan dalam bentuk garis-garis warna hijau. Hak-Hak Ulayat Laut dan hak-hak masyarakat tradisional (native title claims) di wilayah pesisir dan laut dipetakan dalam bentuk persil-persil pesisir dan laut. Hak Pengelolaan untuk National Marine Parks dipetakan dalam bentuk persil-persil laut berwarna merah muda. Hak atas wilayah laut teritorial negara dipetakan dalam zona-zona berwarna coklat muda (cream), sedangkan wilayah laut tambahan (contiguous zone) dipetakan dalam zona-zona berwarna tekstur hijau muda, dan keduanya dipetakan dengan garis batas zona berwarna hitam. Gambar 8. Peta “Marine Cadastre” di Negara Bagian Victoria, Australia (Binns, 2005) (Tanpa Skala) Skala ۞ U 42 Gambar 9. Peta “Marine Cadastre” di Florida Sanctuary, USA (US-DOC NOAA, 2002) 43 44 Demikian pula, sebagaimana tersaji dalam Gambar 9 adalah contoh pelaksanaan “marine cadastre”. Peta ini menggambarkan secara lebih khusus kepada pengadministrasian sumberdaya dan lingkungan pesisir dan laut di Negara Bagian Florida, Amerika Serikat. Hak atas wilayah laut teritorial (Florida State Waters) dipetakan dalam zona-zona dengan garis berwarna biru muda. Hak Negara atas Taman Nasional (National Park Boundaries) dipetakan dalam persil atau zona yang dibatasi oleh garis berwarna merah, yang meliputi batas di darat dan di laut dalam satu kesatuan zona (tidak dipisahkan). Pengadministrasian wilayah taman nasional ini merupakan “state of the art” dari suatu pelaksanaan “marine cadastre”, di mana dalam hal-hal tertentu, antara “land cadastre” dan “marine cadastre” dapat diintegrasikan ke dalam satu peta. Hak-hak pengelolaan negara untuk taman-taman suaka marga satwa laut (National Wildlife Refuge) dipetakan dalam zona-zona atau persil-persil berwarna hijau. Sementara itu, zona-zona lindung laut (Ecological Reserves) dipetakan dengan zona warna ungu muda, dan zona-zona pengelolaan laut (Existing Management Areas) dipetakan dalam warna hijau muda. Penerapan konsep “marine cadastre” di Amerika Serikat dan Australia ini harus dapat menjadi teladan bagi Indonesia, terlebih karena negara ini merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan.