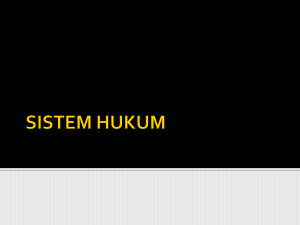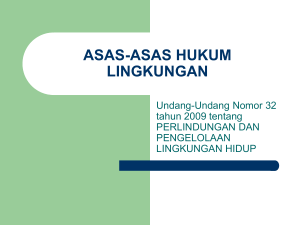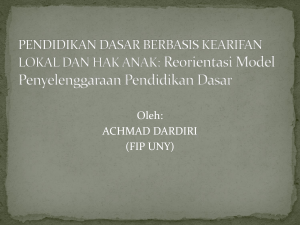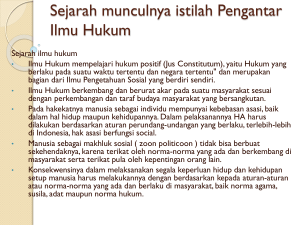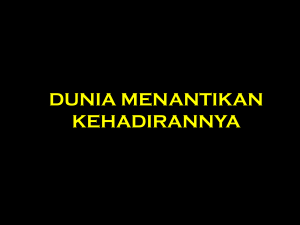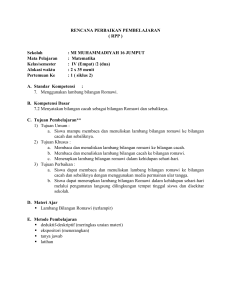Dalam mesdiskusikan local wisdom, tentu kita tidak berhenti pada
advertisement

ade saptomo BUDAYA HUKUM & Kearifan lokal Sebuah Perspektif Perbandingan Jakarta, 2014 i Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT) Budaya Hukum vii, 207 halaman budaya, hukum, budaya hukum, perbandingan, sengketa, kearifan lokal ISBN: 978-602-19984-0-3 diterbitkan FHUP Press dicetak & lay out Lintangades email: [email protected] Jakarta, 2014 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip atau memperbanyak dengan cara apapun seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa seizin penulis dan penerbit. ade saptomo ii KATA PENGANTAR Buku yang diberi judul Budaya Hukum & Kearifan Lokal Sebuah Perspektif Perbandingan ini ditujukan untuk mengisi kekurangan literatur dan buku-buku terkait budaya hukum, sekaligus untuk mengantarkan pembaca dalam memahami Budaya Hukum Indonesia. Budaya hukum dimaksud berisikan keseluruhan kekuatan budaya, social, dan hukum (social forces dan legal forces) dalam menjadikan serta menghasilkan hukum itu sendiri. Lantas, apakah pengertian budaya hukum itu adalah budaya ditambah hukum? Untuk menjelaskan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum, dalam tulisan ini dikemukakan lebih dahulu tentang pengertian budaya dan hukum pada umumnya. Penjelasan mengenai hal itu perlu dengan tujuan agar peminat budaya hukum dapat membedakan tidak saja antara budaya dan hukum tetapi juga dimana letak budaya hukum diantara pengertian budaya dan hukum tersebut. Untuk itu, keseluruhan penjelasan yang ada dalam buku ini diurai menjadi serangkaian bab. Diawali Bab I tentang Budaya dan Hukum, diikuti dengan varian pendefinisiannya aspek-aspek budaya, dan definisi hukum, seperti definisi Idealis, definisi Positivistis, definisi Sosiologis. Bab II tentang Budaya Hukum. Dalam bab ini upaya memahami pengertian Budaya Hukum diawali dengan iii pertanyaan: selain apa budaya dan hukum itu sebagaimana dijelaskan pada Bab I, juga dibicarakan apa perbedaan antara Budaya Hukum (legal culture) dengan Kesadaran Hukum (legal consciousness). Pertanyaan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menekankan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum. Untuk mempermudah dua hal itu, penjelasannya diawali dengan pertanyaan apakah tertib hukum merupakan hasil budaya hukum atau kesadaran hukum. Kemudian disusul Bab III tentang Budaya Hukum Perspektif Perbandingan. Uraian dalam Bab III ini ditujukan untuk menjelaskan bahwa Budaya Hukum yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, kearifan-kearifan lokal perlu diisikan pada proses membuat dan memproduksi hukum sehingga isi dan kualitas hukum sesuai dengan harapan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan rasa keadilan masyarakat luas. Selain itu, dalam bab ini secara perbandingan pula diperlihatkan isi Budaya Hukum Indonesia, Budaya Hukum Asian, Budaya Hukum Modern, Budaya Hukum Individual dan Komunal. Setelah itu, dilanjutkan pada Bab IV tentang Resepsi Budaya Hukum Barat Perspektif Sejarah. Resepsi budaya hukum demikian dimaksudkan agar dipahami bahwa seperangkat struktur hukum, kultur hukum, substansi hukum sebagaimana diperkenalkan sarjana Lawrence M. Friedman dapat juga dikemas kedalam suatu sistem hukum Indonesia meskipun dalam perspektif sejarah sebenarnya Indonesia mengadopsi negeri Kontinental, terutama negeri iv Belanda. Uraian resepsi dalam bab ini diharapkan dapat digunakan untuk memetakan hukum manakah yang sesuai dengan kondisi budaya, sosial dan politik negeri Indonesia. Untuk itu, dalam bab ini berturut-turut diuraikan Awal Resepsi Budaya Hukum Barat, Resepsi Budaya Hukum Barat kedalam Masyarakat Indonesia (Nusantara), Resepsi Budaya Hukum Barat Pra-Kemerdekaan, dan Resepsi Budaya Hukum Barat Pasca Kemerdekaan. Bab V Sengketa dan Budaya Hukum. Dalam Bab V ini dikemukakan konsep konflik atau sengketa berikut tahaptahapannya. Kemudian dilanjutkan dengan konsep Budaya Penyelesaian Sengketa dan Perdamaian sebagai ujung tujuan penyelesaian setiap konflik atau sengketa. Sejumlah kearifan-kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan lama yang telah mapan dan dijadikan isi sebuah proses membuat dan menghasilkan hukum setempat untuk menyelesaikan sengketa. Kemudian disusul Bab VI dengan tema Penegakan Hukum Dengan Kearifan Lokal. Disampaikan pula bahwa konstitusionalitas Indonesia sebenarnya telah memberi ruang gerak bagi hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan menggali nilai budaya hukum dimana peristiwa hukum konkrit terjadi agar putusan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan sosial budaya hukum masyarakat setempat. Selain itu, institusi kepolisian sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban masyarakat memiliki kewenangan memberdayakan potensi masyarakat untuk membantu tugas-tugas polisionil secara terbatas. v Untuk itu, kearifan-kearifan lokal dalam hukum positif sengaja diangkat untuk memperkaya kembali pengetahuan. Last but not least, keseluruhan isi yang terkandung dalam buku ini dikemas dari gagasan, pikiran, pandangan, dan pengalaman intelektual penulis, di satu sisi, serta hasil penelusuran literatur terkait. Melalui buku ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Umar Kayam, Prof. Dr. PM. Laksono, Prof. Dr. Shri Heddy Ahimsa Putra, dan Prof. Dr. Amri Marzali yang telah banyak membuka dan mempengaruhi pikiran penulis tentang bagaimana mengerti, mengetahui, dan memahami budaya.Terima kasih juga disampaikan kepada teman sejawat diskusi penulis Prof. Dr. Herman Slaats dari Universiteit te Nijmegen Nederland. Selain itu, diucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji yang mempercayakan kepada penulis menjadi penyanggah utama dalam Seminar PPRA XLVI bertema Budaya Hukum 7 Desember 2011. Kepercayaan dimaksud dirasakan melegitimasi intelektual penulis untuk segera menyelesaikan buku ini. Penulis buku yang dirujuk namun namanya belum sempat disebut dalam buku ini semata disebabkan kekurangtelitian, penulis memohon maaf. Terakhir, saran konstruktif pembaca amat diharapkan demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat. Jakarta, 2014 ade saptomo vi DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................ i DAFTAR ISI...................................................................... v BAB I BUDAYA DAN HUKUM ................................... 1 I.1 Pengertian Budaya ................................................ 1 I.2 Jenis Budaya ......................................................... 5 I.3 Aspek-Aspek Budaya ........................................... 8 I.4 Pengertian Hukum .............................................. 11 I.5 Definisi Hukum .................................................. 18 I.5.a Definisi Idealis ................................................. 19 I.5.b Definisi Positivistis .......................................... 25 I.5.c Definisi Sosiologis ........................................... 29 BAB II BUDAYA HUKUM ........................................... 33 II.1 Pengertian ......................................................... 33 II.2 Budaya Hukum .................................................. 36 II.3 Kesadaran Hukum ............................................. 44 II.4 Perilaku Hukum................................................ 52 II.5 Penyuluhan Hukum .......................................... 55 BAB III BUDAYA DAN SISTEM HUKUM PERSPEKTIF PERBANDINGAN ....................... 61 III.1 Budaya Hukum Indonesia ............................... 61 III.2 Budaya Hukum Asian ...................................... 65 III.3 Budaya Hukum Modern ................................... 68 III.4 Budaya Hukum Individual dan Komunal ........ 69 III.4.a Budaya Hukum Individual ............................ 69 III.4.b Budaya Hukum Komunal ............................. 74 1 III.5 Sistem Hukum .................................................. 76 III.5.a Sistem Peradilan Common Law .................... 79 III.5.b Sistem Peradilan Eropa Kontinental ............. 83 III.5.c Sistem Peradilan di Indonesia ....................... 88 BAB IV RESEPSI BUDAYA HUKUM BARAT. ......... 96 IV.1 Awal Resepsi Budaya Hukum Barat ................ 96 IV.2 Resepsi Budaya Hukum kedalam Masyarakat Indonesia .................................... 101 IV.3 Resepsi Budaya Hukum Pra-Kemerdekaan .. 105 IV.4 Resepsi Budaya Hukum Pasca Kemerdekaan 111 IV.5 Resepsi Budaya Hukum Pertanahan .............. 119 BAB V SENGKETA DAN BUDAYA HUKUM ......... 135 V.1 Pengertian Sengketa ........................................ 135 V.2 Budaya Penyelesaian Sengketa ....................... 138 V.3 Penyelesaian Sengketa Dalam Budaya Indonesia ......................................................... 143 V.4 Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa ..... 150 BAB VI PENEGAKAN HUKUM DENGAN KEARIFAN LOKAL .......................................... 154 VI.1 Penegakan Hukum ........................................ 154 VI.2 Menggali Nilai dan Budaya Hukum ............. 160 VI.3 Penegakan Hukum Polisi Sipil ..................... 167 VI.4 Penegakan Hukum Commuity Policing ........ 169 VI.5 Penegakan Hukum Polisi Budaya................. 171 VI.6 Penegakan Hukum Kearifan Lokal............... 175 VI.7 Konstitusionalitas Kearifan Lokal ................ 192 DAFTAR PUSTAKA .................................................... 201 2 BAB I BUDAYA DAN HUKUM I.1. Pengertian Budaya Setidak-tidaknya ada dua kelompok pandangan utama yang membahas makna kata budaya. Kelompok pertama, misalnya M.M. Djojodigoeno (1958) dalam bukunya AzasAzas Sosiologi sebagaimana dikutip Koentjaraningrat1, yang membedakan antara budaya dan kebudayaan. Alasannya, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, ke-budaya-an dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Kelompok kedua, misalnya saja P.J. Zoetmulder (1951) dalam bukunya Cultuur, Oost en West mengupas kata budaya sebagai perkembangan dari kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi. Dengan demikian, budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, karsa itu sendiri. Namun ada juga sarjana yang tidak membedakan antara makna kebudayaan dan budaya, terutama sarjana Antropologi, dengan alasan bahwa budaya merupakan kata dasar dari kebudayaan. Sementara kebudayaan yang hal-hal yang terkait dengan budaya. 11 Koentjaraningrat, 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru, hal. 181. 3 Dalam perspektif “Indonesia” kata budaya sendiri berasal dari dua suku kata budhi dan daya. Budhi diartikan sebagai akal baik, halus, indah, edi, halus, dan santun. Sementara daya diartikan sebagai kuat, kekuatan. Dengan demikian, budaya dimaknai sebagai kekuatan berakal baik, halus, indah, santun atau positif. Pada titik ini, budaya dapat diartikan sebagai pemikiran, gagasan, seperangkat gagasan, ide baik. Dalam konteks kemasyarakatan atau secara sosiologis, budaya diartikan sebagai seperangkat nilai, kaidah, norma masyarakat yang menjadi pedoman berfikir, berperilaku, bertindak dalam kehidupan seharihari. Pertanyaannya, kapan hal itu dimulai. Orang berfikir, menggagas, dan sejenisnya diawali ketika ia berkontak dan berkelanjutan dengan segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Segala sesuatu yang berada di luar dirinya dimaksud dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, manusia atau bukan manusia, singkatnya apa saja yang dapat tertangkap oleh panca indera manusia. Berfikir atau menggagas dimaksud dapat digambarkan ketika dalam satu wilayah kosong, misalnya yang datang kemudian adalah seorang manusia dan manusia pertama dimaksud memandang segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Misalnya saja yang berada di luar dirinya adalah sosok manusia, maka pada saat memandang, melihat manusia lain tersebut, mulailah akal masing-masing manusia tergerak untuk berpikir (ngulir budhi). 4 Jika yang ada di luar dirinya adalah manusia, dan manusia selain dirinya itu juga merespon, maka pada saat itu yang terjadi adalah saling kontak. Dalam saling kontak tersebut masing-masing manusia dimaksud menggerakkan fikiran untuk mengidentifikasi apa saja yang ada dan melekat pada manusia di luar dirinya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dalam proses pengidentifikasian, akan menghasilkan pengetahuan yang kemungkinan berbeda antara dirinya dengan yang lain, apa yang ada dalam dirinya dan apa yang tidak ada dalam diri yang lain, apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki yang lain. Ketika mereka memahami bahwa masing-masing memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut tidak dimiliki yang lain atau ada kelebihan dalam dirinya di satu pihak sementara yang disebut kelebihan itu merupakan kekurangan bagi yang lain, maka pada saat itulah mereka mulai muncul keinginan untuk tahu satu sama lain dan bahkan tergerak untuk saling memenuhi kekurangan yang ada dalam dirinya dan memberikan kelebihan yang ada dalam dirinya masing-masing kepada pihak lain. Gerakan saling mengisi dan memenuhi masingmasing pihak tersebut disebut interaksi. Interaksi yang semakin meluas dalam arti jumlah orang yang terlibat banyak, maka pada titik itu disebut sebagai interaksi sosial. Interaksi sosial meluas dan dalam jangka waktu lama lambat laun menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mapan dan tidak tertulis yang akhirnya menjadi pedoman berfikir, 5 bertindak, berbicara, bertingkah laku, dan bahkan hasil berfikir, bertindak tersebut telah menghasilkan suatu karya atau benda-benda tertentu. Keseluruhannya itu dipandang oleh sebagian sarjana sebagai budaya, sebuah budaya yang mencakup budaya immaterial dan materiil. Bertitik tolak dari uraian sederhana tersebut, secara konsepsi menjadi mudah memaknai apa yang disebut budaya. Misalnya menurut Clifford Geertz budaya itu hanya berhenti pada tataran idea atau gagasan, demikian pula pandangan Roger Keesing.2 Ini berarti budaya diartikan sebagai fikiran, olah fikir (ngulir budhi). Namun tidak demikian menurut pandangan Koentjaraningrat, budaya atau kebudayaan diartikan sebagai sebuah sistem yang mencakup gagasan, ide; tindakan; dan hasil tindakan. Satu kesatuan dari ketiganya saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain itu merupakan kebudayaan. Pandangan yang memberi makna hampir sama dikemukakan oleh kalangan sosiolog, misalnya Kathy S. Stolley seperti yang disebutkan oleh Seta bahwa budaya merupakan sebuah konsep yang luas, budaya terbangun dari seluruh gagasan (ide), keyakinan, perilaku, tindakan, dan produk-produk yang dihasilkan secara bersama, dan menentukan cara hidup suatu kelompok.3 Artinya, budaya 2 Lihat Ade Saptomo, 1995. Berjenjang Naik Bertangga Turun: Sebuah Proses Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PPS UI 3 http://setabasri01.blogspot.com/2009/05/teori-budaya.html 6 meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia tatkala mereka saling berinteraksi, kemudian hal itu membentuk cara bagaimana orang melihat dunia sehingga berpengaruh atas bagaimana manusia berpikir, berbicara, berperilaku, dan bertindak. Tentu, hasil berfikir dan bertindak dimaksud menghasilkan sesuatu karya yang nyata. Sesuatu karya yang nyata dimaksud juga merupakan dan bagian dari hasil atau perwujudan dari kebudayaan. I.2 Jenis Budaya Konsep budaya sebagai sebuah konsep kehidupan sosial telah diupayakan dengan sejumlah cara untuk memberikan makna yang tepat. Terutama jika merujuk pada perilaku yang dipelajari sebagai hal yang berbeda dengan yang diberikan oleh alam, atau biologi. Budaya telah digunakan untuk mendesain setiap hal yang dihasilkan (kebiasaan, keyakinan, seni, dan artefak) dan melalui penurunan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dalam formulasi demikian ini, budaya dapat dibedakan dari alam, dan budaya dimaksud berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Dalam konteks ruang lingkup, definisi pertama lebih luas, yang mencakup semua kehidupan sosial manusia, sementara yang kedua lebih spesifik yaitu mencakup makna-makna yang dihasilkan. Artinya, ada sebuah konsep budaya dalam pengertian yang lebih sempit dari yang disebut di atas, yaitu pemahaman budaya merujuk pada seperangkat pranata sosial tertentu, terutama pada produksi tanda dan makna. Dalam pemahaman demikian ini, pranata 7 budaya mencakup, misalnya, seni, musik, teater, mode, sastra, agama, media dan pendidikan. Dengan memperhatikan pemahaman terhadap makna kata budaya tersebut di atas berarti budaya dapat mewujud kedalam bentuk nyata, kasad inderawi yang satu sama lain berbeda. Pemahaman demikian ini, oleh sebagian sarjana menyebutnya sebagai budaya material. Dengan demikian, dalam konteks abstrak atau tidak abstrak, kebudayaan dapat dikategorikan kedalam dua jenis budaya, yaitu budaya material (nyata, kasad inderawi) dan budaya immaterial sebagaimana disebut di atas. Yang termasuk kedalam kategori komponen material adalah seluruh produk nyata, riil, kasad inderawi yang terbentuk lewat serangkaian tindakan. Produk nyata dimaksud, seperti yang disebut Seta, termasuk pakaian, buku, seni, bangunan, software komputer, penemuan, makanan, kendaraan bermotor, alat kerja, dan sejenisnya. Sementara itu, yang termasuk ke dalam kategori komponen immaterial adalah semua kreasi manusia yang tidak kasat mata, seperti bahasa, nilai-nilai, keyakinan, perilaku, ataupun lembaga sosial. Penggunaan kata budaya dalam percakapan seharihari memang masih membingungkan dan tumpang tindih. Misalnya saja, seseorang dapat dikatakan “berbudaya” jika gagasan, tindakan, atau hasil tindakan dipandang sesuai dengan nilai-nilai mapan yang diyakini benar oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai pendukungnya atau “tak berbudaya” jika sebaliknya. Namun, dalam kehidupan 8 sehari-hari pemakaian kata “budaya” juga kerap dirujukan pada apa yang dinamakan budaya tinggi (high culture). Budaya tinggi sendiri biasanya terdiri atas hal-hal yang seringkali dihubungkan dengan kelas sosial ekonomi, bahkan kelompok penghuni wilayah tertentu, misalnya saja kaum elit tertentu di Jakarta. Lebih-lebih kaum elit sosial ekonomi masyarakat ini menonton pameran mobil terbaru, menonton opera asal luar negeri, melihat galeri lukisan abstrak, menonton konser musik klasik, mengunjungi counter butik mahal, dan sejenisnya yang tidak dapat atau tidak biasa dilakukan rakyat umumnya. Apa yang difikir dan dilakukan oleh kelompok sosial ekonomi tersebut dapat dianggap sebagai budaya tinggi. Hal ini berbeda dengan budaya rakyat atau budaya popular (popular culture). Budaya populer memiliki daya tarik bagi aneka manusia dari beragam kelas sosial ekonomi. Misalnya saja dalam masyarakat Jawa, ada pagelaran seni wayang kulit. Di mana saja ada hal.laran seni wayang kulit, di situ ratusan hingga ribuan orang dari berbagai kelas sosial dan ekonomi berbondong-bondong, berkumpul, dan menonton hal.laran wayang kulit. Bahkan tidak saja penonton pagelaran seni wayang kulit mampu menggugah, menghidupkan, dan meningkatkan peredaran ekonomi mikro rakyat bawah. Dalam konteks nasional, masyarakat Nusantara dari Sabang sampai Merauke juga telah memiliki budaya membatik kain dengan corak masyarakat yang berbeda-beda sehingga kain batik juga merupakan sebuah budaya populer. 9 I.3 Aspek-Aspek Budaya Dalam kalangan sarjana budaya, kajian seputar budaya biasanya lebih difokus pada beberapa aspek budaya immaterial, seperti nilai-nilai, norma-norma, simbol, dan bahasa. Sebab itu, tinjauan atas tiap aspek ini lebih membuat orang lebih dapat memahmi soal apa itu budaya. Bagaimana budaya itu terbentuk dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan seberapa penting budaya yang pernah ada dan dipedomani itu. Berikut penjelasan dari aspek-aspek budaya tersebut4: 1. Nilai (Values) Nilai diartikan sebagai apa yang dipandang baik oleh sebagian besar warga masyarakat untuk dilakukan. Nilai dimaksud terbangun oleh serangkaian interaksi antarmanusia dalam jangka waktu lama dan melalui proses panjang sampai pada “kesepakatan” bahwa itulah yang seharusnya (sollen). Itulah yang seharusnya atau yang seharusnya dilakukan dimaksud merupakan suatu hal yang bermanfaat, menentukan, amat berarti. Dengan demikian, nilai sebenarnya menggambarkan pengetahuan yang sudah ada, mapan, diyakini, dimiliki sebagian besar warga masyarakat yang seharusnya dipilih, dilakukan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang seharusnya dilakukan dalam dunia kerja adalah disiplin, tepat waktu, kerja keras, tertib kerja, tertib hukum, dan seterusnya. 4 Seta Basri, 2009. Op Cit. 10 Meskipun nilai telah diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh sebagian besar warga masyarakat bahwa yang seharusnya tersebut amat bermanfaat, amat menentukan, dan amat berarti, namun adakalanya nilai baik dimaksud tidak menjadi pilihan utama sebagai rujukan bertindak. Justru yang terjadi malah memilih nilai yang lain. Praktik demikian ini dalam wacana disebutkan bahwa ada nilai ideal dan tidak ideal, atau dipandang sementara sebagai nilai masa lampau atau masa silam yang telah usang dan pada saat bersamaan lebih memilih nilai yang dipandang sesuai dengan kepentingannya dan kondisikondisi kekinian. Dengan demikian, selalu ada pemahaman yang disandingkan antara budaya ideal dan budaya riil. Budaya disebut pertama masih bebas ruang dan waktu, sementara yang kedua tidak bebas ruang waktu. 2. Norma Norma merupakan turunan dari nilai dan lebih mudah ditangkap karena norma merupakan harapan warga masyarakat yang seharusnya dilakukan. Harapan dimaksud diwujudkan kedalam suatu pedoman tidak tertulis bagi warga untuk bertindak ketika menghadapi situasi tertentu. Norma dibutuhkan untuk menjamin keteraturan sosial. Norma sekaligus menginstruksikan ataupun melarang suatu perilaku. Norma memberitahu apa yang seharusnya dilakukan (menunggu giliran, hadir tepat waktu, menghormati yang tua, dan sejenisnya). Norma juga memberi tahu apa yang seharusnya dilakukan dan tidak lakukan (berteriak di dalam 11 ruangan, berpakaian tidak sopan, berhenti tatkala lampu lalu-lintas berwarna hijau, dan sejenisnya). Norma dimaksud ditanamkan melalui proses internalisasi melalui agen-agen sosial seperti keluarga, sekolah, ataupun pemerintah. Setelah terinternalisasi, norma kemudian menjadi bagian dari sisi kehidupan diri si individu dan sebagai sebuah bagian dari budaya masyarakatnya. 3. Mores Mores juga merupakan turunan norma karena dalam mores dimaksud mencakup penilian baik-buruk, benarsalah sehingga apa yang baik merupakan norma yang ditegakkan. Mores biasanya diwujudkan secara kategoris kedalam standar baku tentang apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang dilarang dan tidak dilarang, apa yang benar dan tidak benar. Larangan-larangan membunuh, merampok, memperkosa, merupakan contoh-contoh mores yang diterapkan di aneka negara. Mores dianggap signifikan secara moral dan kerap diformalisasi menjadi pernyataan-pernyataan formal seperti hukum. Karena signifikansi ini, hukuman bagi pelanggaran mores kerapkali diterapkan. Ini juga melibatkan pemberian sanksi berupa penangkapan dan pemenjaraan. Bahkan di beberapa negara, diterapkan hukuman mati bagi pelanggaran mores. 4. Simbol Simbol adalah sesuatu yang melambangkan, mewakili atau menyatakan hal yang lain. Simbol dapat mewakili gagasan, emosi, nilai, keyakinan, sikap, atau 12 peristiwa. Simbol itu pula dapat berupa apa saja, misalnya saja berupa gerakan tubuh, kata-kata, obyek atau bahkan peristiwa. Simbol memiliki makna berbeda tergantung pada budaya yang dianut individu yang menafsirkannya. Kini, meskipun tidak seluruhnya, simbol-simbol dimaksud mulai kehilangan makna. Namun, ada kalanya simbol tidak akan kehilangan makna, tetapi justru memperoleh makna baru. 5. Bahasa Bahasa adalah sistem simbol yang memungkinkan terjadi proses komunikasi antaranggota penganut suatu budaya. Simbol dimaksud dapat berupa lisan maupun tulisan. Dengan demikian, bahasa merupakan aspek sentral seputar cara orang memahami dunia dan bahasa juga menyatakan apa yang dipikir mengenai dunia dan bagaimana orang bertindak. I.4 Pengertian Hukum Tampaknya, menjelaskan tentang sesuatu lebih mudah daripada memberi definisi tentang sesuatu dimaksud. Namun, tidak lazim untuk menjelaskan sesuatu atau mengkaji sesuatu subyek tertentu jika definisinya tentang sesuatu dimaksud itu sendiri belum jelas. Ini berarti bahwa pada awal mengkaji sesuatu subyek dengan tanpa pembatasan (definisi) akan beresiko belakangan karena diskusinyapun tidak akan terarah dengan baik. Untuk itu, definisi tentang sesuatu yang menjadi subyek kajian menjadi sangat perlu mengingat selain sebagai pembatasan, pengarahan, juga sebagai awal dan akhir dari kajian sebuah subyek. Dengan demikian, definisi 13 tetap perlu dan penting untuk dirumuskan. Namun, dalam konteks hukum, untuk memberikan definisi hukum secara pasti memang sulit karena banyak alasan. Pertama, dalam semua jenjang/tataran perkembangan masyarakat baik dari masyarakat dengan peradaban rendah hingga peradaban tinggi, masing-masing masyarakat dimaksud memiliki hukum. Perbedaan terletak antara hukum dari dua masyarakat tidak hanya dalam satu bentuk saja tetapi ada tahapan perkembangan yang masing-masing memiliki karekteristik berbeda sehingga terminologi hukum memiliki arti dan mencakup hal-hal yang berbeda dalam setiap masyarakat. Law merupakan kosa kata dalam bahasa Inggris, dalam sistem Hindu disebut dharma, dalam sistem Islam disebut hukum, dalam bahasa Romawi disebut Jus, dalam bahasa Perancis disebut Droit, dan dalam bahasa Jerman disebut Richt. Makna dan gagasan yang ada dalam katakata tersebut berbeda satu sama lain sehingga suatu definisi hukum yang gagal mencakup semua makna dimaksud tidak akan menjadi definisi baik. Kedua, defnisi berbeda padahal yang didefinisikan dari hal yang sama mungkin ini terjadi karena definisi diberikan dari sudut pandang berbeda dan satu sudut tidak mengambil pertimbangan dari sudut pandang yang lain. Dengan demikian definisi yang diberikan oleh advokat, filosof, dan theologian semakin menjadi besar perbedaan. Aliran beragam yang dianut penekun hukum juga 14 mempengaruhi alam fikirannya sehingga mereka telah mendefinisikan hukum dari sudut berbeda-beda pula. Beberapa ahli hukum telah mendefinisikan dengan mendasarkan pada siapa, dan beberapa ahli hukum juga ada yang menekankan pada sumbernya, sementara beberapa ahli hukum yang lain berkenaan dengan pengaruh masyarakat, atau berkaitan dengan akhir atau tujuan. Sehubungan dengan itu, seolah ada tuntutan bahwa sebuah definisi yang tidak mencakup semua unsur tersebut akan menjadi definisi yang tidak sempurna. Ketiga, demikian juga dalam tataran ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu sosial. Ilmu sosial yang dimaksud adalah sebuah ilmu yang tumbuh dan berkembang bersama dinamika masyarakat. Perkembangan masyarakat dimaksud dimulai dari masyarakat sederhana hingga modern, terutama era modern yang penuh kemajuan ilmu dan teknologi tinggi, telah menciptakan problem baru tentang definisi hukum. Hukum dituntut mencakup bidangbidang baru dan bergerak ke arah baru agar mampu menjaga ruangan, fungsi, dan lingkup hukum yang selalu berubah. Oleh sebab itu, sulit untuk memberikan sebuah definisi hukum dalam pengertian tertentu untuk tetap berlaku untuk sepanjang waktu. Sebuah definisi yang tetap dan baku tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi mengingat definisi yang paling memuaskan saat ini bisa mempersempit dan tidak lengkap untuk masa yang akan datang. Oleh karena kesulitan itu, Hart pernah mengatakan 15 bahwa sejak zaman kuno kebutuhan akan definisi apa hukum itu telah dibuat dan jawaban berbeda antara satu dan yang lain telah diberikan, diantaranya “Few questions concerning human society have been asked with such persistence and answered by serious thinkers in so many diverse, strange, and even paradoxical ways as the question What Law is.5 Artinya, jawaban atas pertanyaan “apa hukum itu” tidak gampang sehingga jawaban sementara yang paling memungkinkan mendekati persoalan itu adalah sebatas upaya mengemukakan sejumlah ciri dan sifat dari hukum secara singkat dan mencoba menjelaskan sampai pada suatu pengertian utuh dari hukum itu sendiri. Ketidakgampangan dimaksud karena suatu analisis hingga pada perumusan jawaban tidak bebas nilai dan netral, tetapi ia terkait pada orientasi kefilsafatan hukum yang melandasi. Pada umumnya, setiap kali “hukum” dibicarakan, yang dimaksud adalah hukum yang berlaku atau biasa disebut hukum positif. Jadi, hukum yang berlaku diartikan sebagai undang-undang atau keputusan-keputusan hakim dan tidak tentang salah satu hukum kodrat atau sistemsistem hukum ideal lain yang memang juga berlaku. Hukum yang dibicarakan di sini adalah hukum pada umumnya yang setiap hari banyak orang berurusan 5 Hart, H.L.A.,1961. The Concept of Law. Oxford: Clarendom Press.. 16 dengannya. Ada beberapa ciri objektif untuk sampai pada apa yang disebut hukum:6 a. Hukum itu, pada umumnya, ditetapkan oleh kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang. Ini hampir selalu berupa perlengkapan penguasa (overheads-orgaan) dari suatu tatanan hukum dan tatanan negara yang konkret. b. Hukum memiliki suatu sifat lugas dan objektif. Itu berarti bahwa ia secara jelas dapat dikenali dan tidak tergantung pada kehendak bebas yang subjektif. Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa hukum positif modern itu rasional. Dengan itu hukum tidak timbul dari pewartaan religius (wahyu), juga tidak lagi memiliki suatu bobot mistik atau yang irasional, tetapi ia hampir selalu merupakan ujung dari suatu prosedur yang diatur secara cermat. Bila suatu undang-undang dibentuk atau apabila suatu proses hukum di hadapan hakim dijalankan, maka berbagai argumentasi yang satu dihadapkan pada argumen yang lain dan pada saat sama dipertimbangkan dengan cara membandingbandingkan yang satu terhadap yang lain. “Rasionalitas dari hukum” terutama mengandung arti bahwa antarorang saling meyakinkan 6 Meuwissen, D.H.M., 1982. Recht en Vrijheid. Utrecht: Aula. 17 berdasarkan argumentasi-argumentasi yang masuk akal. Selain itu, dalam menetapkan hukum adalah bukan suatu keputusan dari otoritas yang lahir begitu saja, tetapi membutuhkan suatu motivasi jauh ke depan. c. Hukum itu berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang dapat diamati. Dalam segi ini, hukum itu dibedakan dari etika. Untuk etika, suatu pertimbangan pribadi yang murni dan intensi (niat) atau sikap memang menjadi unsur penting. Untuk hukum hal ini menjadi penting, apabila disposisi yang demikian itu diwujudkan kedalam suatu perilaku (pola perilaku) konkrit. Jadi hukum itu mengatur hubungan-hubungan konkrit dan lahiriyah antarmanusia. Ia tidak berkaitan dengan hubungan-hubungan atau kontak-kontak pribadi yang murni. d. Hukum itu memiliki suatu keberadaan dalam masa tertentu, yang biasa disebut keberlakuan (berlaku, gelding). Keberlakuan ini memiliki tiga aspek, yakni aspek moral, sosial, dan yuridik. e. Hukum itu memiliki suatu bentuk tertentu, suatu struktur formal. Ada pembedaan kaidah-kaidah hukum, figure-figur hukum, dan lembaga-lembaga hukum (pranata hukum). Termasuk ke dalam kaidah-kaidah hukum dimaksud adalah aturanaturan umum (misalnya undang-undang) keputusan-keputusan konkret (misalnya vonis18 vonis, keputusan-keputusan pemerintah atau ketetapan) dan asas-asas hukum (misalnya itikad baik, tuntutan kecermatan, pasca sunt servanda, asas persamaan). Sementara itu, perbedaan asasi antara aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum tidak ada. Asas itu seperti aturan memiliki suatu sifat umum, dengan catatan bahwa isinya kadang-kadang dirumuskan kurang tajam ketimbang yang terjadi pada aturan. Selanjutnya misalnya dalam pengertian “aturan” masih dapat dibedakan berbagai struktur, misal keharusan-keharusan (perintah-perintah), laranglarangan, pemberian kewenangan-kewenangan. Struktur-struktur demikian oleh banyak filsuf hukum analitik dijadikan objek penelitian. Figur-figur hukum memiliki suatu sifat yang lebih majemuk. Mereka merupakan perangkat-perangkat aturan dan keputusan-keputusan atas dasar suatu substrat ideal atau kemasyarakatan spesifik (misalnya hak milik, kontrak, perbuatan melanggar hukum, hak-hak dasar). Lembaga hukum jauh lebih majemuk lagi dan dalam banyak hal ia mengenal suatu pengaturan kewenangan-kewenangan yang terjabar dengan organ-organ. Misal saja, perkumpulan, perusahaan, perseroan, dan lembaga hukum yang terpenting adalah negara. f. Ciri yang terakhir dan terpenting dari hukum menyangkut objek dan isi hukum. Hukum itu 19 memiliki pretensi untuk mewujudkan atau mengabdi pada tujuan tertentu. Dalam arti yang sangat formal, menunjuk tujuan ini sebagai ideahukum (cita-hukum). Tentang isi dari idea hukum itu di dalam filsafat hukum terdapat perbedaan pemahaman yang besar. Tujuan dari hukum sering disampaikan, misalnya tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban, perdamaian, harmoni, keteraturan, keajegan, sesuatu yang dapat diperhitungkan secara pasti, kepastian hukum. Setelah masuk pada kajian ciri-ciri hukum, kembali ke belakang sejenak untuk mengingatkan betapa penting definisi hukum yang telah berkembang hingga saat ini. Definisi hukum dimaksud dapat ditemui dalam beberapa literatur yang terkait dengan Ilmu Hukum, di sana akan ditemukan beberapa definisi tentang “hukum”. Definisi hukum dapat pula ditemukan dalam kamus, ensiklopedi ataupun dari suatu aturan perundang-undangan. Untuk melihat apa yang dimaksud dengan hukum, berikut akan diurai definisi “hukum” dari beberapa aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Timbulnya perbedaan tentang definisi hukum di bawah ini akibat dari sudut pandang orang tentang apa itu “hukum”. Hal ini terjadi salah satunya sangat dipengaruhi oleh aliran yang melatarbelakangi pemikiran pemberi definisi. I.5 Definisi Hukum Mengerti definisi menjadi penting dan perlu karena mengawali dan mengakhiri kajian suatu bidang ilmu lazim 20 dengan pengertian definisi bidang ilmu dimaksud. Memberikan definisi hukum secara perbandingan memang merupakan perkerjaan sulit karena banyak alasan, pertama, dalam semua masyarakat dari bentuk sederhana hingga masyarakat yang telah memiliki peradaban tinggi, maju, dan modern masing-masing memiliki apa yang disebut hukum. Itu satu hal, hal lain hampir setiap penekun hukum baik itu akademisi, praktisi, dan pengamat hukum sekalipun telah berusaha untuk mendefinisikan hukum dengan sudut pandang berbeda. Bahkan telah banyak definisi dengan beragam sudut telah mereka berikan sehingga banyak pilihan definisi untuk didiskusikan. Oleh karena terdapat banyak definisi, maka dengan tujuan mengklarifikasi definisi-definisi hukum tersebut, di bawah ini diklasifikasikan definisi-definisi dimaksud kedalam tiga kelompok definisi, yaitu definisi idealis (idealisitic definition), definisi positivistis (positivistical definition), dan juga definisi sosiologis (sociological definition). Sudut pandang inilah yang membedakan pandangan satu dengan yang lain. I.5.a Definisi Idealis Definisi idiealis dimaksud pada umumnya diberikan pada zaman Romawi dan ahli-ahli hukum masa silam. Diantaranya definisi yang diberikan oleh Justinian’s Digest bahwa hukum didefinisikan sebagai the standard of what is just and unjust. Ulpian mendefinisikan hukum sebagai the art or science of what is equitable and good. 21 Cicero mengatakan bahwa law I the highest reason implanted in nature. Pendek kata keadilan sebagai elemen utama hukum, merupakan satu hal yang harus ditekankan dalam semua upaya pengungkapan semua definisi hukum. Namun demikian, satu hal yang perlu dicatat bahwa apa saja pandangan teoretis ahli hukum Romawi yang saat itu mereka miliki, dalam praktik tidak pernah kebingungan dalam memisahkan antara hukum dan keadilan. Pada era Hindu Kuno juga memiliki pandangan bahwa hukum adalah perintah Tuhan dan bukan perintah dari kekuatan politik. Pembuatan peraturan itu sendiri juga terikat dan patuh pada hukum, bahkan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum tersebut. Jadi hukum dipandang sebagai dharma. Ini merupakan pandangan tentang hukum bahwa didalam hukum itu ditemukan moral, bahkan perintah agama, diadonkan dengan ajaranajaran hukum. Artinya, ide keadilan selalu dihadirkan dalam konsep hukum dalam masyarakat Hindu. Hukum alam (natural law atau lex naturalis) pun merupakan idealis karena pada dasarnya merupakan hukum yang tidak dibuat oleh manusia dan oleh karenanya berlaku universal (International Encyclopedia of the Sosial Sciences). Pemahaman hukum alam ini sering diasosiasikan bertentangan atau merupakan lawan dari pemahaman hukum positif, masyarakat, dan pemerintahan negara. Pemahaman tentang teori hukum alam tidak terlepas dari pemikiran Aristotle (384 sM-322 sM) yang menggali 22 filsafat Yunani dengan membedakan antara “hukum” dan “alam.” Hukum bisa berbeda dari satu tempat dengan lainnya, sedangkan alam bersifat universal yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kebutuhan, perilaku, dan hak-hak manusia, pada prinsipnya bersifat alami atau sesuai dengan hukum alam. Oleh karena itu, Aristoteles mengemukakan faktor terpenting, yaitu aspek keadilan yang bersifat alami atau universal (ius naturalis). Atas dasar pemikiran dan kontribusinya dalam perkembangan ilmu hukum, Aristotle dinobatkan sebagai “bapak hukum alam.” Pandangan Aristoteles tersebut sering dikaitkan dengan sebuah ungkapan “an unjust law is not a true law” (hukum yang tidak berkeadilan bukan hukum sebenarnya). Prinsipprinsip dari pemikiran Aristoteles tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam pengembangan ilmu hukum oleh Thomas Aquinas (1225-1274) dalam bukunya Treaties on law7, sehingga menjadi dasar-dasar pengembangan ilmu hukum pada abad-abad berikutnya. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dalam konteks hukum, aturan-aturan moralitas pada hakikatnya bersifat alami dan mengikat bagi seluruh umat manusia. Oleh karena sifatnya yang universal, pemikiran Thomas Aquinas banyak mempengaruhi pengembangan sistem hukum di dunia, terutama di Inggris dan negara-negara Anglo-Saxon 7 Lihat McInerny, R., 1996. Thomas Aquinas: Treatise on law (Summa Theologica, Quesions 90-97). Washington, D.C. Regnery Publishing Inc. 23 yang menganut sistem Common Law. Untuk itu, Thomas Aquinas mengembangkan teori hukum alam yang didasari oleh 3 doktrin yaitu:8 (1) Semua hukum yang berkeadilan dapat ditemukan secara alami; (2) Aturan-aturan yang bersifat aturan dasar harus dijadikan pedoman untuk menyelesaikan berbagai konflik; dan (3) Hukum hanya dapat difahami dan dimengerti apabila didasari oleh prinsip-prinsip moralitas yang telah ada dan bersifat alami. Definisi tersebut diatas diberikan pada saat ketika belum ada pembedaan secara jelas antara hukum, moral, dan agama sehingga seolah ketiganya menyatu kedalam satu definisi. Sementara pada saat zaman sudah modern seperti sekarang, hukum berkembang dan pada umumnya telah disekulerisasi dan telah tumbuh kedalam satu cabang yang independen dalam ilmu sosial. Untuk itu, definisi hukum yang diberikan dari sudut teologis tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Namun unsur keadilan masih menjadi elemen penting dalam beberapa definisi yang diberikan oleh ahli-ahli hukum modern. Mereka telah mendefinisikan hukum berkaitan dengan keadilan tetapi konsep keadilan tidak sama persis seperti keadilan pada zaman kuno. Keadilan, 8 Ibid 24 dalam definisi modern berarti keadilan hukum dan bukan sebuah keadilan abstrak. Keadilan dapat diperoleh melalui proses hukum formal, yatu melalui praktik peradilan. Pandangan demikian telah diklasifikasikan oleh ahli hukum masih sebagai idealistis meskipun mereka sebenarnya positivistik. Definisi yang demikian ini adalah definisi yang dikemukakan oleh Salmond, bahwa hukum merupakan prinsip-prinsip yang diakui dan diterapkan oleh negara sebagaimana tampak dalam administrasi peradilan. Dengan kata lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui, dijalankan oleh pengadilan. Ada dua implikasi penting berkenaan dengan definisi yang demikian ini. Pertama, bahwa untuk memahami hukum orang harus mengetahui tujuannya; kedua, bahwa untuk mengetahui ciri utama hukum orang harus masuk ke pengadilan dan tidak ke lembaga legislasi. Definisi Salmond demikian ini menuai kritik dari ahli hukum lain. Diantaranya, Vinogradoff menyampaikan kritik terhadap definisi Salmond, bahwa definisi tersebut didasarkan pada sebuah pemahaman bahwa hukum berlangsung dari tindakan hakim. Kritik utama terhadap definisi Salmond adalah bahwa ia merancukan antara keadilan dengan hukum sementara hukum dan keadilan bukan satu hal sama karena hukum diterapkan hingga memperoleh kesimpulan apakah baik atau buruk. Sementara, keadilan merupakan idealisme yang ditemukan dalam moral manusia. Salmond itu sebenarnya dianggap tidak pernah membicarakan keadilan, tetapi ia 25 mengatakan bahwa dengan hukum keadilan itu dapat diperoleh. Dengan demikian, hukum telah didefinisikan oleh Salmond berkenaan dengan tujuan. Memang mendefinisikan hukum yang dikaitkan dengan tujuan mungkin membantu namun ketika hukum dimaknai untuk melayani banyak tujuan, tentu definisi demikian itu akan memperoleh kesulitan sendiri. Misalnya saja, jika tujuan hukum adalah keadilan maka Salmond dianggap telah mempersempit wilayah kajian hukum. Konsekuensi logisnya, untuk mengerti hukum orang harus pergi ke pengadilan dan bukan ke lembaga legislasi. Pandangan demikian ini telah dikritik dengan alasanalasan sebagai berikut: Pertama, menurut definisi ini berarti konvensi-konvensi sudah seharusnya dikeluarkan dari hukum karena konvensi tidak dijalankan pengadilan. Kedua, definisi Salmond demikian itu telah memunculkan kontroversi tentang makna pengadilan. Misalnya, apakah peradilan administrasi yang dalam beberapa kasus telah menetapkan hak dan kewajiban serta tanggungjawab hendak dipertimbangkan sebagai pengadilan atau bukan. Pada titik ini, jelas definisi Salmond dipandang kurang memadai sehingga hal itu merupakan kesulitan tersendiri bagi Salmond untuk menjawabnya. Ketiga, pranata-pranata hukum tidak dipertimbangkan sebagai hukum menurut definisi Salmond karena pranata-pranata itu tidak lahir di depan pangadilan. Demikian pula hukum internasional, hukum adat, hukum tata negara dan seterusnya yang kesemuanya tidak lahir dan tidak 26 dijalankan oleh pengadilan adalah bukan hukum, padahal keseluruhannya menjadi rujukan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aliran Sejarah, Frederich Karl von Savigny mengatakan bahwa: All law is originally formed by custom and popular feeling, that is, by silently operating forces. Law is rooted in a people’s history: the roots are fed by the consciousness, the faith and the customs of the people (Keseluruhan hukum sesungguhnya terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar kedalam sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga negara. Selain itu, masih terdapat lagi aliran hukum lain, yaitu aliran hukum alam yang diteorikan oleh Aristoteles. Menurut aliran hukum alam, hukum didefinisikan sebagai sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspressikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Selain Aristoteles, Jhon Locke juga berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka, untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan jujur dan mana yang merupakan perbuatan curang. 27 I.5.b Definisi Positivistis Selain itu, masih ada di dalam hukum terdapat pandangan dari aliran Positivistis. Definisi positivistis sebenarnya juga telah lama muncul, misalnya saja ahli filsafat hukum yang mengembangkan teori positivisme hukum (legal positivist theory),9 terutama Jeremy Bentham, John Austin, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Joseph Raz. Teori ini didasari oleh 3 prinsip pokok yaitu: (1) Tidak ada kaitan langsung antara hukum dan etika atau moralitas; (2) Hukum adalah aturan yang dibuat oleh manusia, disengaja atau tidak; (3) Hukum harus memberikan kepastian dan menggunakan ukuran-ukuran pasti, yaitu sangat ditentukan oleh aturan-aturan dan praktik dalam kehidupan sosial masyarakat yang memberlakukan norma sebagai hukum. Perdebatan antara penganut faham hukum alam (natural-made) dan positivisme hukum (man-made) selalu menarik perhatian diantara para ahli filsafat hukum. Para penganut faham positivisme berpendapat bahwa hukum didasarkan oleh suatu tindakan, praktik, atau permasalahan yang di masa lampau tidak bisa dipecahkan; masa yang 9 Jeremy Bentham (1748-1832) dikenal sebagai tokoh individualis, utilitarian, John Austin (1790-1859) dikenal sebagai tokoh aliran analistis dan bapak Jurisprudence Inggris, Hans Kelsen (1881-1973) dikenal sebagai tokoh positivis, Demikian pula H.L.A. Hart (19071992), dan Joseph Raz (1939-sekarang). 28 akan datang ditentukan oleh suatu tindakan dan keputusan masa lampau dan masa kini. Teori Bentham yang dielaborasi lebih tegas oleh salah seorang muridnya yakni John Austin dalam bukunya The province of jurisprudence determined yang terbit tahun 1832, mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah penguasa (kedaulatan) yang dilengkapi dengan ancaman dan harus dipatuhi oleh banyak orang atau masyarakat umum. Menurut John Austin bahwa hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi. Dengan kata lain, hukum merupakan komando, perintah dari yang berdaulat. Hukum mewajibkan serangkaian tindakan atau mendorong suatu kewajiban dan diikuti sebuah sanksi. Dengan demikian, perintah, kewajiban, dan sanksi merupaka tiga unsur penting dalam mendefinisikan hukum. Artinya, hukum yang mencirikan atau meliputi tiga elemen penting ini disebut hukum positif. Sehubungan dengan itu, definisi John Austin setidaknya menggambarkan faham positivisme dimaksud. John Austin membedakan antara hukum positif, moralitas positif dan jenis-jenis lain aturan yang disebut hukum. Memang definisi Austin demikian juga tidak luput dari kritikan dengan alasan-alasan sebagai berikut: pertama, tidak semua hukum adalah perintah; kedua, kebanyakan hukum memberikan kesempatan daripada 29 pembatasan (ini berarti bukan sebuah kewajiban); ketiga, hukum bukan sanksi semata yang membuat patuh hukum tetapi juga ada faktor lain. Kelemahan lainnya bahwa definisi John Austin demikian ini tidak mencakup kebiasaan dan hukum internasional karena keduanya ini tidak mempunyai esensi hukum sebagaimana dimaksud definisi John Austin. Secara lengkap, Austin mengabaikan aspek sosial dan faktor psikologis yang memang menjamin ketaatan seseorang terhadap hukum. Kemudian sarjana Hans Kelsen yang menggunakan pendekatan the pure theory of law, dapat juga dikategorikan sebagai positivis. Meskipun ia menganut aliran positivisme hukum yang demikian ini, namun agak berbeda pendapat dengan sarjana sebelumnya karena ingin memberikan jalan tengah antara hukum alam dan positivisme hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral seperti yang dianut dalam mazhab hukum alam.10 Menurut A.P. d’Entreves,11 teori positivisme hukum dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu: (i) imperativisme yaitu hukum merupakan perintah kekuasaan yang didukung oleh suatu kebiasaan; (ii) normativisme yaitu hukum merupakan kumpulan norma-norma; dan (iii) 10 Asshiddiqie, J. Dan Safa’at, 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi Ri, Jakarta 11 A.P. d’Entreves, 1951. Natural law: An introduction of Legal Philosophy. 30 realisme (realism) yaitu hukum merupakan produk manusia yang selalu berkaitan dengan dunia nyata. Dari ketiga jenis teori tersebut, yang paling mendapat perhatian besar adalah realisme hukum. Jika dalam teori hukum positif, pengertian positif bersifat “tekstual,” maka dalam teori realisme hukum, pengertian positif bersifat “kontekstual.” Lain lagi menurut Oliver Wendell Holmes, Jr. (1881) yang dalam bukunya The common law, dikatakan hukum bukan semata teks dan kontekstual tetapi lebih hukum mudah dimengerti dalam praktik sebagaimana yang dijalankan oleh institusi peradilan, kantor pengacara, dan kantor polisi daripada mempelajari rangkaian aturan yang tertera dalam dokumen. I.5.c Definisi Sosiologis Sarjana yang pandangannya dapat diklasifikasikan kedalam definisi sosiologis adalah Nathan Roscoe Pound (18701964). Ia berpandangan bahwa hukum berasal dari negara atau pemerintah sebagai penguasa mengingat negara atau pemerintah perlu mengatur berbagai kepentingan, baik kepentingan publik maupun kepentingan privat. Meskipun demikian, Pound (sebutan Nathan Roscoe Pound) yang merupakan pioner dalam gerakan pembangunan hukum untuk tujuan-tujuan sosial (sociological jurisprudence), mengemukakan teorinya bahwa hukum mencerminkan kemauan negara dan/atau pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam rangka melakukan perubahan sosial (social engineering) dan pengendalian sosial (social control). Lebih jauh dikatakan 31 Pound bahwa berbagai perubahan sosial masyarakat harus dikendalikan agar perubahan tersebut membawa manfaat yang lebih baik. Dikaitkan dengan perkembangan hukum, pemikiran Pound mempengaruhi praktik ketatanegaraan, misalnya saja dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi hukum asli masyarakat setempat atau biasa dikenal dengan terminologi adat. Selain itu, dalam praktik ketatanegaraan, pemikiran Pound juga berpengaruh kuat mengingat hanya sedikit saja inisiatif pembentukan rancangan undang-undang yang berasal dari lembaga legislatif. Pandangan Pound tersebut dapat dikategorikan juga sebagai penganut faham realisme hukum. Faham demikian ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem hukum dan sistem peradilan di berbagai negara, bahkan termasuk di Indonesia. Salah satu bentuk penerapan dari pemikiran Pound di Amerika Serikat, misalnya, muncul pengembangan Criminal Justice System (CJS) yang mutlak berasal dari keinginan pemerintah untuk menciptakan keadilan dengan mengintegrasikan sistem peradilan. Menurut aliran sosiologis, Nathan Roscoe Pound, memaknai hukum dari dua sudut pandang, yakni:12 1. Hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah 12 Ilmu hukum76.wordpress.com/2008/04/14/beberapa-definisi-hukum/ 32 laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi). 2. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompokkelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka). Hukum bagi Rouscoe Pound adalah “Realitas Sosial” dan negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum sebagai sarana utamanya. Sedangkan menurut Jhering: Law is the sum of the condition of sosial life in the widest sense of the term, as secured by the power of the states through the means of external compulsion (Hukum adalah sejumlah kondisi kehidupan sosial dalam arti luas, yang dijamin oleh kekuasaan negara melalui sarana paksaan yang bersifat eksternal). Sedangkan Bellefroid berpendapat bahwa: “Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu”. Dalam aliran Realis, Holmes berpendapat bahwa the prophecies of what the court will do are what I mean by the law (apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang penulis artikan sebagai hukum). Sedangkan menurut Salmond: Hukum dimungkinkan untuk didefinisikan sebagai kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan. Dengan 33 perkataan lain, hukum terdiri dari aturan-aturan yang diakui dan dilaksanakan pada pengadilan. Selain aliran sosiologis dan Realis, dari segi Antropologis, melalui Schapera: Law is any rule of conduct likely to be enforced by the courts (hukum adalah setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan). Sedangkan menurut Gluckman: Law is the whole reservoir of rules on which judges draw for their decisions (hukum adalah keseluruhan gudang-aturan dimana para hakim mendasarkan putusannya). Setelah mengurai pengertian dan mencoba untuk memahami konsep budaya di satu pihak dan hukum di pihak lain, maka dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa budaya itu bukan hukum, baik hukum secara idealis, sosiologis, maupun positivistis. Selanjutnya, dalam bab berikut ini akan diurai konsep budaya hukum dan sekaligus menegaskan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum. 34 BAB II BUDAYA HUKUM II.1 Pengertian Dalam upaya memahami pengertian Budaya Hukum, akan lebih mudah jika upaya memahami itu diawali dengan pertanyaan: selain apa budaya dan hukum itu sebagaimana dijelaskan pada bab I, juga pertanyaan apa perbedaan antara Budaya Hukum dengan Kesadaran Hukum. Pertanyaan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menekankan sebuah awal model penjelasan bahwa budaya hukum itu bukan budaya ditambah hukum, dan berbeda pula dengan kesadaran hukum. Untuk itu, penjelasannya dapat diawali dengan, misalnya, apakah tujuan hukum itu? Misalnya saja tujuan hukum dimaksud adalah tertib hukum, apakah tertib hukum dimaksud merupakan hasil budaya hukum atau kesadaran hukum. Jawabannya, membutuhkan perenungan bahkan beberapa sarjana yang membedakan antara budaya hukum dengan kesadaran hukum, hampir selalu saja jawaban yang dikemukakan tidak jelas pilahannya. Hal ini diduga karena penjelasan kedua konsep tersebut masih tumpang tindih sehingga, kadangkala, terkesan membingungkan. Kebingungan itu mungkin terletak pada tidak terpilahnya antara gagasan hukum, perilaku atau tindakan hukum, dan tertib hukum sebagai hasilnya, yang keseluruhannya merupakan budaya hukum atau kesadaran hukum. Jika tertib hukum merupakan 35 produk dari kesadaran hukum, maka apakah secara otomatis tertib hukum itu juga dapat dikatakan sebagai produk budaya hukum. Oleh sebab itu, pertanyaan mendasarnya, apa perbedaan antara budaya hukum dengan kesadaran hukum tersebut di atas menjadi penting dikemukakan. Budaya hukum dan kesadaran hukum sebenarnya merepresentasikan dua pendekatan metodologi yang berbeda terhadap kajian realitas hukum. Semula, kedua konsep tersebut mampu memberikan kesan bahwa keduanya sejajar namun analisis yang lebih rinci mengungkapkan bahwa masing-masing konsep memiliki disiplin yang berbeda, yaitu sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kesadaran hukum yang disebut terakhir merepresentasikan pendekatan antropologi hukum dibanding konsep sosiologi budaya hukum yang disebut pertama. Perbedaannya muncul tidak hanya dalam tataran disiplin teori tetapi juga dalam perspektif metodologi. Bahkan, dapat diasumsikan bahwa kedua konsep merepresentasikan pengkayaan metodologis dimana sosiologi hukum telah meneliti untuk mencapai pemahaman komprehensif apa yang dimaksud hukum, apabila fokus penelitian utamanya adalah reprentasi sosial tentang hukum. Ada suatu studi berpretensi bahwa untuk memahami representasi sosial hukum yang dikemukakan sosiologi hukum, maka langkah pertama yang dilakukan adalah harus dimulai dari perpektif etnografi sosial (socio36 ethnograpy perspektif) sebagaimana yang biasa dilakukan dalam kajian antropologi hukum.. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum itu lebih menekankan respon seseorang atau kelompok orang yang tampak dari serangkaian perilaku atau tindakan hukum setelah dihadapkan pada faktor ekternal, misal aturan hukum. Respon tersebut bisa saja menolak, menyimpang, berlawanan atau menerima, atau sesuai. Respon positif menghasilkan harapan diberlakukan hukum itu sendiri tercapai, yaitu tertib hukum (order), tentu sebaliknya (disorder). Lantas, bagaimana dengan Budaya Hukum ? Kemudian, untuk mengawali pengertian secara spesifik tentang Budaya Hukum, terlebih dahulu dijelaskan terminologi Budaya Hukum. Budaya Hukum terdiri atas dua kata Budaya dan Hukum, namun bukan berarti pengertiannya budaya ditambah hukum. Budaya sendiri berasal dari dua suku kata budhi dan daya, dimana budhi diartikan sebagai akal baik dan daya diartikan kekuatan positif. Dengan demikian, budaya dimaknai sebagai kekuatan fikiran berakal baik atau positif. Kemudian, hukum umumnya dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengkategorikan tentang perilaku benar atau salah, kewajiban dan hak. Namun bukan berarti jika budaya dikaitkan dengan hukum, lantas otomatis pemahaman terhadap budaya hukum menjadi gagasan untuk bertindak berdasarkan hukum yang berisikan bobot 37 kategoristik seperti benar - salah, baik - buruk, hak kewajiban. II.2 Budaya Hukum Di berbagai tempat dan kesempatan penulis sering ditanya mahasiswa program doktor ilmu hukum terutama yang berkenaan dengan pengertian konsep budaya hukum. Penulis katakan secara sederhana bahwa sejak awal Lawrence M Friedman (1975) memperkenalkan konsep legal culture dalam buku The Legal System: A Sosial Sciences Perspective, konsep itu sering menjadi perdebatan antara penekun hukum tradisi Americanis dengan Europis, terutama negeri Jerman. Sarjana Lawrence M. Friedman memperkenalkan konsep budaya hukum yang diartikan sebagai sebuah alat untuk mempertegas fakta bahwa hukum paling baik dipahami dan digambarkan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur struktur, substansi, dan budaya hukum. Artinya, hukum (misalnya putusan hakim) dipahami sebagai sebuah hasil dari proses menyatunya antara unsur kekuatan-kekuatan sosial (social forces) dan kekuatankekuatan hukum (legal forces) sebagai input, yang kemudian menghasilkan hukum. Dengan sendirinya produk hukum yang disebut terakhir merupakan saluran dari kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan hukum dimaksud yang akan memiliki dampak ketertiban hukum masyarakat sebagai outcome. Umumnya, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis yang 38 mengkategorikan suatu perilaku benar atau salah, kewajiban dan hak, namun menurut Friedman pemahaman demikian ini merupakan gagasan konvensional yang memberikan atribusi-atribusi terlalu jauh pada tidak ada keterkaitannya antara hukum dalam buku dengan hukum dalam praktik. Dalam kajian sosial, sebuah hukum dalam praktik, Friedman mengadopsi model sebuah sistem, dimana didalam sistem itu terdapat seperangkat struktur yang memproses input yang berasal dari sebuah lingkungan, masuk kedalam proses dan sampai kemana proses itu mengirimkan input menjadi output. Artinya, ada input, process, output, yang kemudian akan membentuk dan mewujudukan tujuan hukum itu sendiri. Friedman mengidenfikasi tiga sentral komponen sistem hukum, pertama, kekuatan-kekuatan sosial dan hukum yang ada sebagai input, dalam beberapa cara, menekan dan membuat hukum; kedua, hukum itu sendiri, yaitu struktur dan aturan-aturan sebagai output; dan ketiga, pengaruh dari hukum pada perilaku di dunia luar (outcome). Dengan kata lain, dari mana hukum berasal dan apa saja yang menyertai merupakan kajian sosial terhadap hukum. Artinya, istilah pertama dan ketiga merupakan komponen penting dalam kajian sosial tentang hukum. Pandangan Friedman demikian dijadikan diskusi panjang mengingat kajian-kajian sosial terhadap hukum di negeri Amerika Serikat memang kurang mendapat perhatian cukup dan bahkan terpinggirkan di beberapa sekolah tinggi hukum dan universitas. Hal ini terjadi karena 39 Friedman telah melakukan kajian dalam sebuah tradisi yang berakar kuat di negeri-negeri Kontinental Eropa terutama Jerman. Misalnya saja, Friederich Karl von Savigny (1831), pada abad ke-19 telah menggambarkan bahwa hukum dipahami sebagai salah satu perwujudan suatu jiwa rakyat (volksgeist) yang paling penting dan ia bergulir terus bersama dalam sebuah budaya rakyat. Pandangan von Savigny demikian ini merupakan pandangan yang dianggap menentang adanya kodifikasi hukum Jerman saat itu. Menurutnya, kodifikasi bukan merupakan sebuah instrumen yang cocok untuk pembangunan hukum Jerman pada saat itu mengingat hukum merupakan produk dari kehidupan rakyat dan hukum merupakan manifestasi jiwa rakyat. Artinya, hukum memiliki sumber yang berasal dari kesadaran umum rakyat masyarakat setempat. Dengan makna yang sama namun dengan cara yang berbeda Oliver Wendell Holmes, sebagai seorang juris dan hakim, pun memiliki pandangan tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum paling baik dipahami sebagai dokumen antropologis. Artinya, hukum itu lahir, tumbuh, dan berkembang melekat pada komunitas-komunitas masyarakat setempat. Bahkan, dalam karya-karya klasik sosiologi, seperti Emile Durkheim dan Max Weber juga menempatkan hukum pada pusat kehidupan sosial daripada menempatkan ke pinggiran sebagaimana umum terjadi di Amerika. 40 Kedua sarjana tersebut menganalisa hukum sebagai sebuah ekspresi kekuatan sosial dalam transformasi masyarakat modern dan sebagai perangkat saluran untuk mengembangkan kepekaan sosial. Tentu, gagasan-gagasan tersebut mendapat tentangan kuat dari kaum positivis yang memiliki pandangan bahwa hukum paling baik dipahami sebagai sistem yang otonom, yang secara resmi diberi sanksi dan secara logika terdiri dari aturan dan prosedur. Dalam konteks budaya, pengertian budaya hukum dimaksud dapat diperhalus menjadi seperangkat gagasan, norma yang menjadi pedoman berucap, berperilaku, bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Dengan demikian, bisa saja gagasan yang diharapkan masyarakat dimaksud berupa norma yang terkandung dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Itu berarti budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budhi dan daya warga masyarakat setempat dan telah terinternalisasi kedalam alam kesadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori di satu pihak dan perilaku, tindakan nyata pada tataran praksis di lain pihak yang diharapkan warga masyarakat. Dengan demikian, pada titik ini, kesadaran pada tataran individu, kelompok, bahkan masyarakat, atau biasa disebut kesadaran hukum masyarakat dapat dibedakan dengan Budaya Hukum. 41 Pemahaman konsep disebut terakhir lebih berakar kedalam nilai-nilai normatif bersama yang terlahir dan terbangun selama proses masyarakat itu sendiri terbentuk dan terinternalisasi kedalam kehidupan masyarakat sepanjang perkembangan masyarakat itu sendiri berlangsung. Artinya, kelahiran suatu budaya hukum dimaksud berasal dari proses internal selama perkembangan masyarakat berlangsung, dan selama itu pula interaksi baik antarwarga maupun antara warga dengan warga dari luar berlangsung membentuk perilaku yang semakin mempola dan akhirnya pola tindakan dimaksud dianggap sebagai yang benar dan dijadikan pedoman bertindak oleh sebagian besar warga masyarakat. Dengan demikian, budaya hukum dapat dimaknai sebagai nilai bersama. Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal nusantara yang kini disebut bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia seharusnya merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila. Tentu tidak saja aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila berhenti pada konstitusi dalam pengertian sempit seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, tetapi seperangkat peraturan perundangundangan yang berada di bawahnya mulai dari undang42 undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden hingga peraturan yang paling bawah di tingkat desa. Kesemuanya, baik secara vertikal maupun horisontal merupakan norma yang menindaklanjuti pasal-pasal konstitusi dan terkontrol oleh nilai Pancasila atau budaya bangsa sehingga nilai itu dapat kembali atau dikembalikan ke masing-masing budaya masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk itu, ketika produk hukum itu diberlakukan akan diterima seluruh warga nusantara, dan jika tidak diterima berarti ada kemungkinan ada garis yang terpotong (disconnection). Oleh sebab itu, dalam konteks politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundangundangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian pula, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujukkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Lebih-lebih era globalisasi dewasa ini yang membuka ruang terbuka untuk berinteraksi dengan negara lain, diskusi budaya hukum Asian, terutama Indonesia dewasa menjadi penting. Pembahasan hal ini amat relevan dengan gerakan globalisasi mengingat di negara-negara kulturalis seperti Jepang sendiri yang mendasarkan nilai-nilai harmonipun tidak sedikit persoalan-persoalan hukum justru diarahkan ke proses penyelesaian formal yang menghujung pada hasil kalah dan menang. Pada saat bersamaan, muncul diskusi lain yang menyatakan bahwa praktik Hukum Barat 43 dikatakan sebagai tak berakar budaya (acultural), “tak asli” (unnative). Kemunculan pandangan tak berbudaya atau tak asli tersebut sebenarnya semakin menampak ketika globalisasi itu sendiri mulai merambah ke negeri-negeri sedang berkembang. Bahkan, sejumlah praktisi di negeri berkembang juga sering mengatakan bahwa menggunakan budayanya sendiri akan lebih baik dan pas (match) daripada yang lain untuk menyelesaikan suatu persoalan karena hukumnya original. Landasan berfikir mereka adalah lebih baik mendasarkan pada budaya daerah tempatan dimana persoalan hukum itu terjadi daripada budaya negara masing-masing individu yang terlibat. Artinya, Eropa itu bukan Asian, dan sebaliknya Asian bukan Eropa karena memang ada batas-batas norma jelas. Friedman menyebutkan bahwa ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum, pertama, struktur; kedua, substansi; dan ketiga, kultur (budaya). Pertama, struktur dimaksud adalah seperangkat kelembagaan yang diciptakan untuk mendorong bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Kedua, substansi dimaksud adalah produk (output) dari bekerja struktur hukum tadi, dan ketiga, kultur (budaya) dimaksud adalah seperangkat nilai-nilai yang terdiri dari kekuatan sosial dan hukum yang dijadikan sebagai pengikat bekerjanya struktur. Bekerjanya ketiga unsur tadi merupakan sistem hukum sebagaimana dimaksud Friedman. Dalam konteks Indonesia, Pancasila lah yang dimaksud oleh Lawrence M. 44 Friedman13 sebagai inti legal cultural (budaya hukum). Berdasarkan teori ini, maka Pancasila merupakan nilai-nilai ke-Indonesia-an yang harus dijadikan input pada bekerjanya struktur hukum di Indonesia. Lebih-lebih ketika atribut globalisasi seperti individualistik, kapitalistik, dan hedonistik semakin menjalar ke tengah masyarakat Indonesia, maka kita sebagai bagian masyarakat Indonesia semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya budaya lokal, baik lokal kita maupun lokal mereka. Kemunculan keinginan kuat kembali ke budaya lokal tidak mungkin dihindari sebagai paradoksiasi dari globalisasi yang kita terima sendiri, lebihlebih secara politik hukum, nuansa otonomi daerah semakin bergerak merambah ke lapisan masyarakat bawah. Tentu, di bawah sana, yaitu masyarakat lokal sebenarnya telah penuh dengan budaya lokal (micro cultural) mendesak untuk digunakan sebagai pedoman bertindak. Misalnya, dalam Budaya Jawa, semangat kebersamaan (holo bis kuntul baris, gotong royong), budaya penyelesaian sengketa/konflik (menang tanpa ngasorake), dan konsensus (berembug). Kemudian pertanyaannya, apakah isi budaya lokal itu. Ada tiga tingkatan budaya untuk menjawab isi budaya lokal dimaksud, yaitu tingkat budaya individual, komunal, 13 Lawrence M. Friedman, 1975. The Legal System. New York: Russell Sage. Lihat juga Lawrence M. Friedman, 1986. “Legal Culture and Welfare State”, dalam Gunther Teubner (Ed), Dilemas of Law in the Welfare State. New York: Walter de Gruyter, hal. 13-27. 45 dan budaya bangsa. Pada tataran pertama, budaya diartikan sebagai keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai individu dalam masyarakat. Pada tataran kedua, biasa dijumpai di Negara Asia, termasuk Indonesia, di mana dalam negara-negara di lingkungan Asia merupakan negara yang memiliki masyarakat pluralistik, multikultural yang biasanya mengakui nilai-nilai mayoritas dan nilai-nilai minoritas serta seringkali yang terakhir justru diterima sebagai budaya ideal nasional. Contoh, selain Indonesia juga negeri Jepang yang menekankan harmoni dalam hubungan interpersonal, Ahimsa (anti kekerasan) dalam masyarakat Hindia, dan konsensus di Indonesia. Pada tataran ketiga, hukum sebagai budaya suatu bangsa. Pada tingkat ini budaya bangsa lebih disukai secara resmi dalam bentuk kelembagaan. Namun dalam praktik politik hukum Indonesia, ada “keterpaksaan sementara” untuk menggunakan atau meminjam budaya hukum negeri lain karena negeri itu sendiri belum membangun hukumnya secara formal. Dalam keadaan kekosongan hukum demikian itu, dijembatani secara politis dengan dasar asas hukum bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang belum diatur oleh yang baru. Dengan demikian, kekosongan tidak terjadi. II.3 Kesadaran Hukum Konsep lain yang amat berdekatan dengan budaya hukum adalah kesadaran hukum. Kedua konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi pemahaman dan makna hukum yang menyelimuti dalam hubungan sosial. Prefix legal 46 dalam legal culture dan legal consciouness mencirikan suatu aspek yang diasosisiasikan dengan hukum, lembagalembaga hukum, pelaku-pelaku hukum, dan perilaku hukum. Perbedaannya, budaya hukum merujuk pada suatu fenomena derajad besaran (makro atau group) sementara kesadaran hukum biasanya merujuk pada hubungan sosial dalam derajad mikro, terutama cara-cara individu menginterpretasi dan memobolisasi makna hukum dan tanda-tanda hukum. Dengan kata lain, konsep kesadaran hukum ini digunakan untuk menyebut secara analitis terhadap pemahaman dan makna hukum dalam hubungan sosial. Kesadaran hukum mengacu pada apa yang dilakukan orang tentang hukum. Hal ini dipahami sebagai bagian dari proses timbal balik dimana makna yang diberikan oleh individu untuk dunia mereka menjadi bermotif, stabil, dan ada unsur objektifikasi. Makna-makna dimaksud sekali dilembagakan menjadi bagian dari sistem wacana yang membatasi dan sekaligus akan dapat menghambat makna-makna yang ada berikutnya. Kesadaran bukanlah semata-mata sifat tunggal atau ideasional; kesadaran hukum merupakan jenis praktik sosial yang mencerminkan dan membentuk struktur sosial. Ada pemahaman terhadap pengertian kesadaran hukum. Pertama, kesadaran hukum sebagai sikap, dan kedua, sebagai epiphenomena sebagaimana disebutkan Silbey (2001). Pertama, kesadaran sebagai sikap. Sejumlah akademisi memang mengkonseptualisasikan kesadaran 47 sebagai gagasan dan sikap individu yang menentukan tentang bentuk dan tekstur kehidupan sosial. Sebagai ekspresi dari sebuah tradisi liberal dalam teori hukum dan politik, konsepsi kesadaran menghendaki bahwa semua kelompok sosial dari berbagai ukuran dan tipe (keluarga, sejawat, korporasi, komunitas, masyarakat, dan bangsa) memunculkan kesadaran pada rangkaian tindakan-tindakan individu. Dalam konsepsi individualis, kesadaran itu sendiri terdiri dari baik kesadaran yang dibangun atas dasar alasan maupun keinginan. Menurut ideologi liberal, variasi manusia yang tak tampak akan selalu menjamin bahwa manusia akan selalu berkeinginan terhadap hal-hal berbeda, sekalipun mereka beralasan sama. Beberapa sarjana yang meletakkan konsepsi kesadaran hukum sebagai suatu sikap dimaksud, diantaranya beberapa peneliti yang berupaya untuk mendokumentasikan variasi-variasi tersebut kedalam keyakinan, sikap, dan tindakan-tindakan individu sebagai alat untuk menjelaskan bentuk pranata hukum dan serangkaian praktiknya. Beberapa peneliti memang menilai derajad suatu aturan hukum merupakan bagian dari sosialisasi dan kebiasaan penduduk. Misalnya saja, penelitian yang pernah dilakukan oleh Stalans dan Kinsey (1994). Lainnya, misalnya saja penelitian yang dilakukan Lind dan Tyler (1998) yang hasilnya menggambarkan sebuah konsensus normatif mendalam tentang apa yang 48 mereka sebut sebagai keadilan prosedural (procedural justice). Kedua, kesadaran hukum sebagai Epiphenomena. Dalam formulasi lain, sejumlah akademisi menganggap kesadaran sebagai sebuah produk bekerjanya sebuah struktur sosial daripada agen-agen formatif dalam membentuk pranata-pranata. Dalam kajian antropologi struktural misalnya, menggambarkan pelaku-pelaku sosial ditempatkan pada jaringan hubungan sosial yang kompleks yang menentukan persepsi dan tindakan mereka. Senada dengan hal itu juga, Strukturalis Marxist mengungkapkan bahwa ide, gagasan, yang mencakup simbol-simbol budaya dan beragam narasinya itu dipandang sebagai residu suprastruktural terhadap kondisi-kondisi material yang melayani kepentingan para elit. Jika mengikuti perspektif demikian ini, kesadaran hukum merupakan sebuah epiphenomena mengingat struktur sosial dan ekonomi tertentu dipahami sebagai instrumen untuk memproduksi tatanan hukum yang saling merespon dengan membentuk subyek hukum. Kesadaran hukum dalam tradisi demikian ini seringkali menggambarkan bagaimana suatu keutuhan produksi kapitalis dan memproduksi kembali perilaku dan kesadaran hukum. Kajian-kajian paham strukturalis demikian ini menekankan pada produksi dan praktik hukum, dan mengakomodasi kepentingan kelas. Penelitian-penelitian yang menggunakan perspektif strukturalis demikian ini umumnya melengkapi dengan 49 tema hubungan antara hukum dan struktur kelembagaan dengan memberikan rekomendasi bahwa tatanan hukum yang ada sebenarnya untuk merespon konflik-konflik dan ketidakkonsistensian yang dilakukan oleh kapitalis dengan mode of production daripada sebagai instrumen kepentingan langsung kelas tertentu. “To legitimize the inconsistencies and irrationalities born of the contradicitions of the economy. The legal order constitutes myths, creates institutions of repression, and tries to harmonize exploitation with freedom, expropriation with choize, inherently unequal contractual agreements with an ideology of free will”14 Artinya, paham di atas menunjukkan perhatiannya dengan memfokuskan pada legitimasi fungsi hukum. Penelitiannya menguraikan cara-cara hukum membantu orang dalam melihat dunianya, urusan pribadi dan publiknya baik sebagai hak maupun sebagai sifatnya. Memang ada penganut paham strukturalis dan Marxist yang berbeda dibanding pengertian terdahulu, misalnya saja pandangan yang mengatakan bahwa budaya dan kesadaran merupakan dua unsur yang saling berpatisipasi aktif dalam memproduksi praktik-praktik material dan realitas sosial. 14 Chambliss W and Seidman R, 1982. Law, Order, and Power. Addison-Wesley: Reading Mass, hal. 70. 50 Ada cara lain untuk memahami pengertian kesadaran hukum, misalnya saja pandangan sarjana bernama van Schmid yang membedakan pengertian antara “perasaan hukum” dan “kesadaran hukum”15. Untuk menunjukkan letak perbedaan antara kedua istilah itu, Sunaryati Hartono mencoba menjelaskan dengan menggunakan contoh berikut. Di Sulawesi Selatan misalnya, kasus pembunuhan akibat pemutusan pertunangan yang menimbulkan malu keluarga bakal pengantin wanita. Demikian pula di Bali, seorang ahli waris membunuh orang yang membagibagikan warisan karena ia tidak diberi bagian warisan. Tindakan membunuh tersebut merupakan reaksi spontan dan dianggap sebagai instrumen untuk mengembalikan keseimbangan. Tindakan demikian ini merupakan representasi “perasaan hukum”. Namun, apabila hal tersebut dirumuskan dalam pengertian-pengertian hukum, maka rumusannya menjadi “penghinaan berat harus ditebus dengan nyawa”. Secara lebih abstrak lagi dapat dirumuskan, bahwa kesalahan dan hukuman harus seimbang”16. Menurutnya, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. 15 Sunaryati Hartono, 1975. “Peranan Kesadaran Hukum Rakyat Dalam Pembaharuan Hukum” Kertas kerja pada Symposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi. Jakarta: BPHN – Bina Cipta, hal. 89-90. 16 Ibid. 51 Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan suatu pengertian atau konsep sebagai hasil dari cipta para sarjana hukum. Konsep itu disimpulkan dari pengalaman hidup sosial atau dikonsepsikan dengan cara penafsiran tertentu17. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk, disuluh secara sadar agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat.18 Serangkaian uraian di atas telah menjelaskan tentang berbagai pendapat tentang terminologi kesadaran hukum. Dari uraian itu pula dapat dipahami bahwa konsep kesadaran hukum itu sendiri juga mengandung unsur nilai yang sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak lama dan sudah melembaga. Produk dari proses pelembagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan kembali melalui proses sosialisasi dalam masa-masa berikutnya. Apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma, yaitu norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakatnya dalam bertingkah laku. Jadi, sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya, dan 17 Ibid. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, ist und wird dem volke. Uraian yang relatif lengkap tentang pendapat Von Savigny ini dapat ditemukan dalam Lawrence M. Friedman, Op Cit 52 18 ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum negara di dalam masyarakat. Jadi, jelas bahwa kesadaran hukum ini timbul apabila apa yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum itu sama dengan nilai-nilai yang yang telah tertanam lama kedalam alam pikiran warga masyarakat. Tentu sebaliknya, tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap aturan formal dari Negara amat mungkin disebabkan hukum negara (modern) tidak merekam kembali norma tingkah laku yang sudah ada di dalam masyarakat. Pada titik ini, ia justru menjadi sarana penyalur kebijakan-kebijakan pemerintah atau kelompok-kelompok kepentingan sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada sehingga muncul ketidakpatuhan tersebut19. Dalam konteks keilmuan, budaya hukum dan kesadaran hukum sebenarnya merepresentasikan dua pendekatan metodologi yang berbeda terhadap kajian realitas hukum. Semula, kedua konsep tersebut memunculkan kesan kuat bahwa keduanya sejajar namun hasil analisis yang lebih rinci mengungkapkan bahwa masing-masing konsep memiliki disipilin ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi hukum dan antropologi hukum. Kesadaran hukum yang disebut terakhir merepresentasikan 19 Satjipto Rahardjo, 1979. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni, hal. 144. 53 pendekatan antropologi hukum dibanding konsep budaya hukum yang disebut pertama. Perbedaannya terletak tidak hanya dalam tataran teori tetapi juga dalam perspektif metodologi. Bahkan, dapat diasumsikan bahwa kedua konsep merepresentasikan pengkayaan metodologis dimana sosiologi hukum telah meneliti untuk mencapai pemahaman komprehensif apa yang dimaksud hukum, apabila fokus penelitian utamanya adalah reprentasi sosial tentang hukum. Di sisi lain, ada suatu studi yang berpretensi bahwa untuk memahami representasi sosial tentang hukum sebagaimana dikemukakan sosiologi hukum, maka langkah pertama yang dilakukan adalah harus dimulai dari perpektif etnografi sosial (socio-ethnograpy perspective) sebagaimana yang biasa dilakukan dalam kajian antropologi hukum. Selain itu, jika fokus penekanan penelitian budaya hukum adalah pada cara-cara bagaimana hukum eksis dalam masyarakat pada umumnya, sementara kajian kesadaran hukum penekanannya untuk mengungkap cara-cara dimana hukum dialami dan diinterpretasikan oleh individu-individu. II.4 Perilaku Hukum Penulis menjelaskan dari sudut (angle) lain, yaitu teori Perilaku Hukum. Perilaku hukum dimaksud ini adalah tindakan-tindakan warga masyarakat yang sesuai dengan harapan aturan hukum. Asumsinya, jika tindakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki aturan hukum, maka baru disebut ada kesadaran hukum. Artinya, apakah 54 perilaku dan seterusnya itu memang merupakan kesadaran hukum yang lahir dari materi penyuluhan hukum atau kemauan warga sendiri dalam menterjemahkan hukum? Nah, disini yang membedakan kesadaran hukum dan budaya hukum dimana dalam konteks ini, kesadaran hukum diartikan sebagai bagaimana harapan hukum itu menjadi bagian cara hidup (perilaku) masyarakat. Pada kesempatan ini, untuk memperjelas perbedaan antara budaya hukum, kesadaran hukum, dan perilaku hukum, penulis memberi contoh apa yang dilakukan oleh warga masyarakat. Misalnya saja, masyarakat Minangkabau dalam memilih dua hukum yang hidup dalam masyarakat setempat, hukum Islam dan Hukum Adat. Jika mereka melakukan niat hajad perkawinan, maka perkawinan dimaksud merujuk pada hukum Islam, tetapi jika menyangkut warisan maka mereka akan merujuk pada Hukum Adat secara otomatis, meskipun dalam Hukum Islam sendiri mengenal warisan. Ini artinya, dalam konteks warisan, tindakan (kesadaran hukum)nya merujuk pada Hukum Adat. Dalam Hukum Adat dimaksud terdapat pedomanpedoman pembagian warisan yang diyakini benar dan dipedomani oleh warga masyarakat sebagai hal yang benar yang merujuk misalnya saja pada pepatah-pepatah. Sementara dalam kesadaran hukum tidak ditemukan pepatah-pepatah dimaksud tetapi suatu respon berupa tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar. Artinya, penyebutan kesadaran hukum itu, setelah secara kasad 55 inderawi apa yang dilakukan, diucapkan, tindakan atau perilaku yang ditunjukkan warga sesuai harapan hukum (Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Negara). Contoh lain, seorang warga masyarakat akan melangsungkan akad pernikahan. Tentu, ia diharapkan memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu, antara lain berupa persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian pula, seorang warga masyarakat yang akan membeli tanah, ia pun diharapkan memenuhi tindakan-tindakan (baca: ketentuan-ketentuan) administratif dan yuridis tertentu sebagaimana tercantum dalam peraturan-teraturan hukum dalam bidang agraria. Sementara dalam merespon Hukum Negara tersebut, apakah seseorang akan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, sangat tergantung pada tiga variabel utama. Variabel-variabel itu antara lain20 (1) apakah normanya telah disampaikan; (2) apakah normanya serasi dengan tujuan-tujuan yang diterapkan bagi masyarakat; (3) apakah warga masyarakat digerakkan oleh motivasi. Suatu aturan hukum memuat pasal-pasal yang tidak mengakomodasi ketiga hal tersebut di atas kadangkala menimbulkan kesulitan sendiri bagi warga masyarakat yang akan dijadikan sasaran. Memang yang baik, aturan hukum itu sendiri selain jelas maknanya, juga susunan kalimat harus jelas. Tentu 20 William J Chambliss & Robert B. Seidman, Op Cit., 1982. Lihat juga Robert B Seidman, “Law and Development, A. General Model”, dalam Law and Society Review, Edisi VI Tahun 1972. 56 ketidakjelasan keduanya sering menyebabkan kesulitan tersendiri bagi petugas penyuluh untuk menterjemahkan ke bahasa masyarakat. Namun hal ini berbeda jika aturan hukum itu sendiri lahir dari kehendak hukum masyarakat atau biasa disebut kebutuhan hukum (legal needs) yang datang dari masyarakat. Artinya, aturan hukum itu sebenarnya berisikan harapan hukum sosial (socio-legal needs). Dengan telah ditangkapnya harapan hukum sosial itu oleh tenaga penyuluh, maka tiba gilirannya bagi penyuluh untuk memahami dan menstranfer kedalam bahasa masyarakat. Ini menjadi penting, karena bahasa masyarakat akan memudahkan pula kelompok sasaran mudah memahami dan menerima. II.5 Penyuluhan Hukum Teori penyimpangan mengajarkan bahwa para pemegang peran (warga masyarakat) itu dapat mempunyai motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan keharusan norma maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma. Sementara itu pemegang peran itu dapat juga mempunyai tingkah laku yang mungkin sesuai dan mungkin pula tidak sesuai. Artinya, sebelumnya telah ada upaya-upaya tertentu seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan ke tengah masyarakat. Misalnya saja dalam bentuk penyuluhan undang-undang perkawinan dengan tatap muka bersama warga masyarakat, siaran program-program kebijakan pemerintah melalui dialog interaktif di stasiun radio atau televisi. 57 Sosialisasi terus menerus dan berjalan dalam masa yang lama menjadikan apa yang dikehendaki hukum semakin terinternalisasi kedalam alam pikir warga masyarakat. Jika telah mengendap, maka apa yang terendap itu akan muncul sendiri dikemudian waktu sebagai alat merespon terhadap apa yang ada di luar dirinya. Dengan demikian, dilihat dari subyek, predikat dan obyeknya, maka pembahasan kesadaran hukum sebenarnya juga cukup kompleks mengingat isinya menyangkut beberapa komponen penting, yaitu tidak saja siapa penyuluh atau sumber daya manusia yang akan melakukan penyuluhan, isi materi aturan hukum, tetapi juga pilihan sasaran kelompok sosial yang dijadikan sasaran penyuluhan, dan adanya indikasi kesiapan budaya masyarakat yang akan menerima isi hukum. Satu hal yang akan membedakan dengan budaya hukum adalah satuan kesadarannya yang ada dalam orang perorang, kelompok orang, dan mungkin masyarakat. Tentu yang disebut terakhir ini harus dapat diukur dengan pendekatan kuantitatif. Di dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan misalnya, berusaha merubah tingkah laku masyarakat dengan memasukkan unsur-unsur baru seperti melarang perkawinan di bawah umur dan penerapan asas poligami. Norma yang terkandung dalam alam pikiran orang dimaksud terakhir ini bukan norma hukum negara tetapi norma hukum agama yang ia anut dan diyakini bahwa poligami dan perkawinan di bawah umur dibenarkan. 58 Penulis lebih condong menggunakan konsep kepatuhan hukum secara otomatis (legal obedience automatically) dari pada konsep kesadaran hukum mengingat sebenarnya dalam proses bekerjanya hukum, setiap warga masyarakat dipandang sebagai agregat hukum dan diharapkan mampu bertindak sebagai “pemegang peran” (role occupant). 21 Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapanharapan tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, warga masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis dalam serangkaian pasal-pasal (role expectation). Penyuluh (role enforcer). Ketrampilan penyampaian makna hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peran yang dimainkan oleh seorang komunikator kepada komunikan sebagaimana yang ada dalam kajian ilmu komunikasi. Untuk itu, penyuluh hukum itu adalah seorang komunikator yang bertugas menyampaikan pesan atau harapan hukum kepada komunikan atau kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang diduga belum kuat kesadaran hukumnya sehingga yang penting dalam penyuluhan adalah ketepatan memilih kelompok-kelompok sasaran itu. Penyuluh itu tidak lain adalah tenaga-tenaga manusia sehingga peningkatan kemampuan sumber daya manusia 21 Chambliss dan Seidman, 1971. Law, Order and Power. Adison Wesly: Reading Mass. 59 itu sendiri agar professional menjadi penting diperhatikan. Satu hal penting lagi, penyuluh professional harus lahir melalui proses pelatihan sehingga ia disebut sebagai trained legal enforcer. Dengan demikian, syarat kedua ini ada menyusul setelah dipahami dengan jelas harapan peran yang ada dalam aturan hukum itu sendiri. Tentu setelah itu, satu hal yang penting berikutnya adalah kelompokkelompok masyarakat yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Kelompok Sasaran (role occupant). Dalam tindakan penyuluhan hukum, tentu langkahnya harus bertahap dari mana dan kelompok mana yang harus dipilih untuk lebih didahulukan. Ini berkaitan dengan langkah sistematis dimana kelompok sasaran itu akan dijadikan pilot proyek selain untuk bertugas melakukan penyuluhan berikutnya baik formal maupun informal melalui contoh-contoh ucapan dan perilaku mereka yang sesuai dengan harapan aturan hukum. Dalam konteks masyarakat Minangkabau misalnya agak mudah memilih kelompok sasaran yang akan dijadikan role occupant mengingat disana ada kelompok tokoh adat, tokoh cerdik pandai, dan tokoh agama. Tentu kelompok inilah yang didahulukan mengingat mereka lebih dipercaya akan mampu menyuluh kepada warga masyarakat luas lewat perilaku dan ucapan yang konsisten. Satu hal yang penulis pikirkan adalah sasaran ini sebenarnya bukan hanya masyarakat bawah saja, tetapi 60 juga para pemegang otoritas karena kadangkala justru yang lapisan atas lupa diperhatikan. Oleh karena pengaruh berbagai faktor yang bekerja atas diri orang tersebut sebagai pemegang peran, maka dapat saja terjadi suatu penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Itu artinya telah terjadi ketidaksesuaian antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat. Di sini, ada kemungkinan besar bahwa warga masyarakat tersebut tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai budaya yang telah lama dikenal dan dihayatinya.22 Lain halnya, warga masyarakat berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri dan hukum Negara. Jika hal demikian yang terjadi, maka peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri sehingga sifatnya memperkukuh saja. Ini berarti peraturan hukum 22 Dalam konteks sosiologi modern yang berorientasi empirisme cenderung berpendapat bahwa kekuatan pokok kontrol sosial itu terletak pada adanya kaidah-kaidah kelompok yang telah diresapi masyarakat. Kekuatan kontrol sosial juga terletak pada adanya tekanantekanan psikologis antarsesama warga masyarakat. Itu berarti, kekuatan utama kontrol sosial bukan terletak pada adanya pasal-pasal peraturan hukum yang dibuat secara formal dan tertulis. Walaupun, tidak dapat dipungkiri bahwa bagaimanapun juga peraturan-peraturan hukum formal dan tertulis itu masih bisa memberikan pengarahan, pengaruh dan efek-efek kekuatan pada pelaksanaannya 61 itu hanya bersifat memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh warga masyarakatnya.23 Uraian di atas menggambarkan bahwa Budaya hukum merupakan seprangkat nilai normatif yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari hasil interaksi warga masyarakat itu sendiri, dianggap sebagai yang benar, dan dijadikan pedoman bertindak sebagian besar warga masyarakat. Sementara kesadaran hukum lebih merupakan sikap moral warga masyarakat dalam merespon hukum. Dalam konteks peningkatan kesadaran hukum, secara teoretik, kegiatan penyuluhan akan efektif, jika (1) rumusan aturan hukum mudah dipahami, (2) isi aturan hukum diketahui masyarakat luas, (3) mobilisasi aturan hukum, (4) pengakuan masyarakat luas atas aturan hukum, (5) contohcontoh mekanisme dan ketuntasan penyelesaian sengketa hukum. 23 . Perilaku yang bertentangan dengan hukum itu lebih disebabkan oleh sikap moral (mores) masyarakat yang tidak sejalan dengan isi peraturan hukum tersebut. Sikap moral masyarakat itu selalu berada dalam posisi mendahului dan menjadi penentu bekerjanya hukum. Pendapat Seidman tersebut menunjukkan bahwa selain sosialisasi dan sinkronisasi produk hukum, faktor motivasi juga ikut menentukan tingkah laku seseorang pemegang peran dalam mentaati isi produk hukum tersebut. Seidman membuat suatu model yang berkamar empat untuk menunjukkan hubungan antara bentuk tingkah laku dengan motivasi para memegang peran. Selanjutnya, lihat Robert B Seidman, “Law and Development, A. General Model”, dalam Law and Society Review, Edisi VI tahun 1972. 62 BAB III BUDAYA HUKUM DAN SISTEM HUKUM PERSPEKTIF PERBANDINGAN III.1 Budaya Hukum Indonesia Banyak negara yang sekarang ini diposisikan sebagai negara berkembang oleh peta kekuatan ekonomi dunia, misalnya, negara-negara di sepanjang Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Asian sendiri. Negara yang termasuk di negara-negara Asian itu, misalnya, Malaysia, Thailand, Brunei, Philipina, Vietnam, Kamboja, dan Indonesia sendiri. Negara-negara tersebut merupakan Negara Kolonisasi negara Eropa yang telah lama mencengkeramkan koloninya termasuk memaksakan hukumnya kedalam masyarakat yang kemudian ketika mencapai kemerdekaan belum mampu bangkit membentuk sistem hukumnya sendiri, bahkan hingga sekarang. Tentu, yang terjadi ketika warga masyarakat mulai bergerak membentuk negara sendiri yang dibutuhkan seperangat hukum yang digunakan sebagai perangkat hukum dan politik agar roda pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan hukum masyarakat itu sendiri. Setidak-tidaknya kitab undang-undang Hukum dari negera kolonial yang dipakai dengan cara meminjam, suatu peminjaman yang dilindungi oleh asas hukum bahwa selama hukum baru belum terbentuk hukum lama 63 digunakan. Peminjaman hukum asing ini secara akademis menjadi masalah mengingat hukum yang dipinjam itu lahir dari budaya masyarakat berbeda dan berbeda pula sejarah kelahirannya. Misalnya, masyarakat Prancis, Belanda yang kapitalis tentu yang dibutuhkan adalah hukum kapitalis, ekonomi kapitalis yang dibutuhkan hukum kapitalis, ekonomi sosialis yang dibutuhkan hukum sosialis, masyarakat modern yang dibutuhkan hukum modern. Untuk mengatasi hal ini memang cara yang paling mudah adalah meminjam dari negara yang pernah mengkolonisasi. Di Indonesia, seperangkat peraturan perundangundangan asal negara kolonial disesuaikan dengan prinsipprinsip Pancasila, diharapkan aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukumnya dirujukkan pada prinsipprinsip Pancasila yang diakui sebagai budaya bangsa dan merupakan kristalisasi dari keseluruhan budaya lokal dari seluruh nusantara yang kini disebut bangsa Indonesia. Dengan Pancasila itu, keseluruhan produk hukum merupakan turunan dari prinsip-prinsip Pancasila, tentu tidak saja berhenti pada konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945, tetapi seperangkat peraturan perundangundangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden hingga peraturan yang paling bawah di tingkat desa. Semua itu merupakan norma yang menindaklanjuti pasal-pasal konstitusi dan terkontrol oleh nilai Pancasila atau budaya bangsa sehingga nilai itu dapat kembali atau dikembalikan ke masing-masing budaya masyarakat 64 Indonesia itu sendiri dan diterima seluruh warga Nusantara. Dengan cara demikian, bentuk budaya hukum yang lebih disukai secara resmi adalah dalam bentuk kelembagaan dan memang selalu menunjukkan bahwa budaya bergerak antara dua tataran sedang dibentuk dan dibentuk kembali oleh individual maupun oleh negara. Satu hal yang perlu dicermati adalah tidak semua produk hukum negara yang disusun berdasarkan prosedur baku dapat dilaksanakan atau dapat diterapkan pada satu persoalan hukum kongkrit yang terjadi di daerah-daerah yang memang karakter budaya hukum lokalnya amat kental, seperti konflik sumber daya alam dan sengketa tanah yang sering terjadi di dalam Masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Demikian pula, produk hukum yang sumbernya dari negeri Eropa seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sebenarnya di negeri Belanda sendiri juga telah mengalami perubahan-perubahan sedemikian rupa untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat setempat. Hal lain yang juga lebih menggelikan lagi ketika kasus-kasus hukum kongkrit yang dilakukan oleh orang Indonesia, lokasi kejadiannya juga di wilayah Indonesia, namun prosedur penyelesaiannya dan dasar-dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menghukum atas dasar hukum yang bersumber dari negeri Kontinental. 65 Oleh sebab itu, beberapa kasus hukum kongkrit, misalnya penghinaan terhadap Presiden sudah tidak tepat lagi jika digunakan pasal-pasal KUHP yang sebenarnya substansi pasal-pasal dimaksud memiliki akar budaya yang sejak semula ditujukan untuk melindungi Sang Ratu dalam suatu kerajaan. Makna demikian dapat ditangkap dari asal usul KUHP sebagai terjemahan Strafsrecht itu berlaku berasal dari negeri Belanda. Artinya, Ratu berbeda dengan Presiden, negerinya pun berbeda di mana yang satu berupa Kerajaan-Monarchi dan yang lain Negara Kesatuan Republik. Demikian pula, pola pemilihan hingga yang dimaksud menjadi pucuk pimpinan, yang satu atas dasar keturunan menurut tatanan budaya, sementara yang lain menurut dasar-dasar demokratis menurut tatanan politis. Jika dalam kasus penghinaan termasuk misalnya, hakim berketetapan menerapkan pasal-pasal KUHP maka sebenarnya secara akademis hal itu tidak logis. Tentu, yang logis adalah sejumlah pasal-pasal dalam kitab-kitab tersebut diatas isinya disesuaikan dengan kondisi budaya bangsa Indonesia sehingga substansinya dapat diharapkan menyentuh dan akhirnya mendekati keadilan masyarakat Indonesia. Tentu sebaliknya, jika tidak dilakukan akan menambah deretan daftar panjang perkara hukum yang antri untuk diselesaikan baik dalam proses peradilan umum maupun diajukannya ke Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk dilakukan judicial review. 66 III.2 Budaya Hukum Asian Mengapa diskusi budaya hukum Asian dewasa ini menjadi penting. Ini merupakan pertanyaan yang amat relevan dengan gerakan globalisasi sekarang mengingat di negaranegara kulturalis seperti Jepang sendiri yang mendasarkan nilai harmoni namun tidak sedikit persoalan-persoalan hukum justru diarahkan ke proses penyelesaian formal. Sementara pada saat bersamaan, muncul diskusi lain yang menyatakan bahwa praktik hukum barat seperti dikatakan sebagai tak berakar budaya (acultural), “takasli” (unnative). Ketika atribut globalisasi seperti individualistik, kapitalistik, dan hedonistik semakin menjalar dan sebagian mengalami kegagalan, maka kita semakin menjadi sadar bahwa betapa pentingnya budaya lokal baik lokal kita maupun lokal mereka. Kemunculan keinginan kuat kembali ke budaya lokal tersebut tidak mungkin dihindari sebagai paradoksi dari globalisasi yang diterima sendiri, lebih-lebih secara politik hukum, nuansa otonomi daerah semakin bergerak merambah ke bawah, dimana di bawah sana, yaitu masyarakat lokal sebenarnya telah hidup dan penuh dengan budaya lokal (micro cultural). Kemudian pertanyaannya adalah apakah isi budaya lokal itu. Ada tiga tataran budaya untuk menjawabnya, yaitu tataran budaya individual, komunal, dan budaya bangsa. Pada tataran pertama, budaya diartikan sebagai keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai individu dalam masyarakat. Ini seringkali amat kontras dengan nilai-nilai Asia yang bermasyarakat multikulural seperti Brunei, 67 Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia sendiri. Tentu, budaya individual ini tidak sertamerta cocok ketika membicarakan penyelesaian konflik atau sengketa dengan budaya-budaya negara lain tersebut. Oleh sebab itu, hubungan dengan suatu negara yang memiliki budaya berbeda perlu pemahaman perbedaan budaya bangsa yang menjadi tuan rumah budaya (host cultural). Pada tataran kedua, biasa dijumpai di Negara Asia di mana dalam negara-negara di lingkungan Asia merupakan negara yang memiliki masyarakat pluralistik, multikultural yang biasanya mengakui nilai-nilai mayoritas di atas nilainilai minoritas dan seringkali diterima sebagai budaya ideal nasional, misalnya seperti disebut di atas, Jepang menekankan hubungan interpersonal yang harmoni, Konfusian di Korea, nilai Budhis di Thailand, dan konsensus di Indonesia. Seperti diatas, pertanyaannya adalah apakah pentingnya membicarakan budaya suatu bangsa, terutama budaya hukum Asian. Kemunculannya sebenarnya semakin menampak ketika globalisasi itu sendiri mulai merambah ke negeri-negeri sedang berkembang sehingga sejumlah praktisi sering mengatakan bahwa menggunakan budayanya sendiri akan lebih baik dan pas daripada yang lain untuk menyelesaikan suatu persoalan karena hukumnya original. Landasan berfikir mereka adalah lebih baik mendasarkan pada budaya daerah tempatan daripada budaya negara masing-masing individu yang terlibat. 68 Artinya, Eropa itu bukan Asian, dan sebaliknya Asian bukan Eropa karena memang ada batas-batas norma jelas. Sumber Budaya Hukum 3. No 1. Budaya Hukum Sistem Civil Law 2. Sistem Common Law Negara Indonesia Taiwan Korea Japan Pilipina Warisan Hukum Belanda Jepang Jerman Jerman Perancis Amerika Serikat Inggris India Pakistan Malaysia Brunei Singapura Pilipina Hongkong Australia New Zealand Pengaruh Hukum Pakistan Timur Tengah Islam Malaysia Indonesia Brunei 4. Sistem Hukum RR Cina Perancis Sosialis Vietnam Perancis Laos Perancis Cambojia Mongolia Sumber: Veronica Taylor and Michael Pryles, 1997 69 Namun dalam praktik politik hukum, ada keterpaksaan penggunaan atau peminjaman budaya hukum negeri lain sebagai akibat dari riwayat kolonialisasi negaranegara lain di negeri Asian, sementara negeri itu sendiri belum membangun hukumnya secara formal. Dalam keadaan kekosongan hukum demikian, dijembatani dengan dasar asas hukum bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang belum diatur oleh yang baru. III.3 Budaya Hukum Modern Perubahan-perubahan dalam teori dasar tentang legitimasi ternyata telah memiliki akibat luas dalam masyarakat. Sikap-sikap dan gagasan baru merupakan hal penting ketika mereka mengarah pada perilaku berbeda. Teori-teori legitimasi ternyata telah merubah pola-pola kepatuhan dan ketidakpatuhan. Dalam masyarakat tradisional misalnya, orang mengikuti aturan biasa disebabkan karena kebiasaan atau kepercayaan, sementara dalam masyarakat modern memunculkan budaya hukum modern pula, dimana kepercayaan dimaksud semakin menipis dan sanksi-sanksi diterapkan untuk menjamin telah dipenuhi suatu tuntutan. Pertanyaannya hampir sama dengan apa isi budaya lokal itu atau apa isi budaya hukum itu. Dengan demikian, jika kerangka pemikiran ini digunakan untuk menganalisis fenomena hukum seperti korupsi misalnya, maka sebenarnya perilaku korupsi amat berkaitan dengan budaya masyarakat di mana korupsi itu terjadi atau amat berkaitan dengan budaya hukum dari mana pelaku korupsi itu dilahirkan, tentu demikian pula penyelesaiannya. Korupsi 70 itu amat beragam cara penyelesainnya sesuai budaya dari masyarakat satu ke masyarakat lain, korupsi yang terjadi di Amerika berbeda dengan Indonesia. Dalam negeri Amerika sendiri korupsi yang terjadi antara Negara Bagian satu berbeda dengan Negara Bagian lain. Korupsi yang terjadi di Inggris juga di Negara Eropa lainnya namun amat sedikit jumlahnya dibanding di Amerika. Tentu ini berbeda pula dengan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kondisi negara-negara berkembang umumnya amat berbeda meskipun demikian ada kecenderungan sama, yaitu setidak-tidaknya pada saat ini masih cukup terbuka akan terjadi praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. III.4. Budaya Hukum Individual dan Komunal III.4.a Budaya Hukum Individual Untuk menjelaskan kelahiran budaya individualisme dimaksud, salah satu diantaranya adalah dapat dimulai dari sebuah asumsi hedonisme3, yang diartikan sebagai faham untuk mencapai kekayaan, kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Tentu, gambaran paling nyata yang perlu dikaitkan dengan itu adalah apa yang telah dilakukan oleh 3 Ini merupakan salah satu filasafat hidup yang dianut dalam kekuatan global dari 4 (empat) kekuatan lainnya, yaitu individualisme, sekularisme, dan tentu hedonisme itu sendiri. Filosofi pelaksanaannya pun berlainan, yatu rasional ekonomis (tepat guna), rasional teknis (terukur), sportif, bersaing, perhitungan logis kausal dalam menghadapi persoalan nyata. Selanjutnya lihat Koesnoe,1997, hal. 137-138 71 orang Barat yang memang selama ini membuktikan dan sejarah yang mereka bangun menampilkan fakta bahwa sejumlah negara di luar kawasan mereka dijadikan daerah koloni mereka. Keberadaan mereka di negeri luar itu dan kedatangan orang berbeda asal kelahiran, bahasa, dan seterusnya di daerah sama menjadikan diantara mereka dengan tidak disadari membentuk budaya kompetisi dengan tujuan untuk menyelamatkan pribadi orang masing-masing sehingga melahirkan karakter keindividualan. Sehubungan itu, pengertian individualsime dapat ditelusuri ke belakang dengan merujuk pada perspektif perantauan orang Barat. Sejarah perantauan orang Barat telah menjelaskan bahwa menyusul benua Amerika ditemukan oleh Columbus pada abad ke XV, orang Eropa Barat datang ke benua baru tersebut. Dengan temuan historis seperti itu, dapat dibayangkan surut ke belakang pada abad tersebut bahwa kedatangan mereka, orang Barat, sudah tentu dengan tanpa diiringi jiwa nekad untuk berpetualang dan keberanian untuk menanggung resiko tinggi dalam diri masing-masing, tentu tidak mungkin dan mustahil berhasil mengingat serangkaian resiko mengancam berada di depan mereka. Kemustahilan inilah menjadikan resiko tinggi ada di depan mata dan di pundak mereka yang saat itu tidak akan mudah berbagi resiko sepenuhnya dengan orang lain. Latar belakang petualangan beresiko tinggi yang ditanggung orang perseorangan ini melahirkan apa yang biasa disebut orang sebagai faham individual, atau individualisme 72 (individualism).4 Di sana, pengertiannya dikembalikan ke belakang bahwa individualisme memandang manusia sebagai individu bebas untuk hidup dan bertanggung jawab atas kehidupannya sehingga penekanannya adalah pemenuhan kebebasan individu ketimbang kebebasan sosial Saat itu, dengan faham demikian mereka berpetualang mengarungi laut dan menerabas batas-batas geografis benua dan negara seraya disertai harapan akan muncul perbaikan kehidupan mereka di dunia lain. Artinya, petualangan itu dilakukan secara sangat sengaja dengan tujuan menjadikan hidup mereka serba bergelimang atau setidak-tidaknya berkecukupan materi. Fanatisme perjuangan demikian melahirkan sebuah pandangan penting berikutnya, bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah mencari kehidupan bergelimang materi, kenikmatan, serta kebahagiaan. Faham yang menekankan pada bergelimang materi, kenikmatan, dan kebahagiaan ini biasa disebut materialisme (materialism). Faham ini memacu mereka untuk melakukan tindakan strategis dan langkah-langkah nyata dengan perjuangan keras dan matimatian untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Di Dunia Barat, alat untuk merealisasi isme-isme tadi adalah penguasaan teknologi desain (engineering) di 4 Pengertian yang memperlihatkan bahwa orang atau sekelompok orang ingin memperbaiki kehidupan di dunia dengan keberanian menanggung resiko ini berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Rafael Maran, 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 2-3 73 berbagai bidang. Apa yang kita lihat, ternyata penguasaan itu telah mewujud menjadi kenyataan, sebagaimana tampak pada bangsa Amerika dan Eropa saat ini. Dalam suasana keindividualismean ini, persaingan ketat menjadi unsur penentu dalam hedonisme sehingga siapa saja yang berhasil dalam persaingan baik secara orang perseorangan maupun kolektif, ia menjadi kaya, kekayaan menjadikan kuat, kekuatan membawa kekuasaan. Inilah sebagian yang dikehendaki hedonisme ala orang Barat. Namun, dibalik kesuksesan itu, ada suatu hal yang perlu dicatat bahwa itu semua telah memunculkan rasa khawatir, was-was, cemas, dan gelisah terhadap kekayaan materiil, kejayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ketenaran yang telah diperoleh akan terancam berkurang, hilang, bahkan punah baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Kerasaan was, khawatir menjadikan mereka tidak mudah begitu saja untk percaya orang lain meskipun orang lain dimaksud telah mempunyai sejarah panjang tentang bagaimana meyakinkan orang lain berdasarkan budayanya. Mereka amat berkeinginan untuk memastikan apa yang dikatakan dan apa yang orang lain katakana benar, ditaati, dipatuhi dengan disilin sehingga kepastian menjadikan unsur penting dalam berinteraksi, untuk mencapai kepastian sudah tentu bukti tertulis sehingga hukum tertulis (ipso jure), terkodifiksasi, dan seterusnya menjadi unsur penting berikutnya. 74 Berkaitan dengan ini, tampaknya tidak cukup sekedar invidual, kepastian, tertulis, masih ada keunggulan yang dikejar yaitu bagaimana mengamankan apa yang telah mereka peroleh. Untuk itu bagi orang Barat pilihan keamanan berteknologi tinggi (high-techno security) menjadi faktor penentu dalam upaya menjaga keutuhan apa yang telah diperoleh dan mengamankan praktik realisasi faham-faham yang dimaksud di kemudian hari. Artinya, faktor keamanan berteknologi tinggi menjadi fokus berikutnya. Untuk itu, upaya penciptaan alat mesin berteknologi canggih, modern, efektif, dan efisien untuk menjaga serta mengamankan apa yang telah digapai segera diwujudkan. Semua ini telah dihasilkan dan kini terus menerus dikembangmajukan, yang intinya untuk menggapai dan mengamankan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan, dan kebahagiaan secara berkesinambungan. Prinsip yang dibawa serta dalam filsafat yang dimaksud adalah menggerakkan masyarakat di seluruh dunia untuk menerima sebuah proses menuju kearah kemajuan materiil yang luar biasa. Ke seluruh dunia, memang, kita lihat saja sejarah globalisasi itu sendiri. Secara substansial, ada kekuatan yang mengglobalkan suatu ide beserta hasil-hasilnya dalam kehidupan materi untuk umat manusia yang hidup di muka bumi ini, yang pada dasarnya adalah ide materi tersebut harus ada dimanamana. Hanya saja dalam pelaksanaannya memang awalnya tidak begitu gigih. Pelaksanaan semakin gigih terjadi ketika 75 para petualang Eropa Barat berupaya mencari dan menemukan negeri-negeri di luar Eropa untuk dikuasi dan diambil kekayaannya. Petualangan itu sendiri diawali sejak abad Ke XIV dan di dalam perjalanan abad tersebut hingga sekarang, dan era kini mengalami bentuk-bentuk non fisik. Dengan demikian, petualangan awal yang sangat berkesan adalah ketika seorang Columbus abab Ke XV, tentu ia tidak sendirian, menemukan benua Amerika. Penemuan Benua Amerika oleh orang-orang Eropa pimpinan Columbus ini membawa gerakan besar orang Eropa ke Amerika. Amerika menjadi sesuatu yang sangat menarik mengingat pada saat itu hasil petualanagn di Amerika itu sendiri benar-benar dapat memenuhi harapan yang didambakan oleh orang banyak, terutama dari kalangan mereka sendiri. Para petualang dari Eropa yang berdatangan ke benua Amerika saat itu, bukan sembarang petualangan karena petualangannya itu keberanian dan tekad bulat. Tentu, jika tidak disertai keberanian total atau tekad yang bulat tentu tidak akan berhasil. Mereka berani menanggung resiko tinggi dan karena resiko terlalu tinggi itulah tidak mudah berbagi resiko dimaksud dengan orang lain. Inilah diduga awal mula lahir kejiwaan perseorangan sehingga seseorang menganut faham individualisme. III.4.b Budaya Hukum Komunal Budaya hukum individual tentu berbeda dengan budaya hukum komunal. Budaya yang disebut pertama memandang manusia sebagai individu bebas untuk hidup 76 dan bertanggung jawab atas kehidupan orang perorangan sehingga penekanannya adalah pemenuhan kebebasan individu, namun budaya yang disebut kedua menekankan sebaliknya pada kebersamaan. Kebersamaan dimaksud hidup dalam masyarakat komunal dan dalam masyarakat komunal, sebenarnya, sudah memiliki suatu tata kelola sosial atau masyarakat yang mampu merumuskan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi bersama dan sekaligus mampu mencari jalan keluar secara bersama pula. Dalam konteks Indonesia, budaya hukum komunal, misalnya budaya menjunjung tinggi kebersamaan, itu lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarakat yang memiliki struktur komunal sebagaimana tampak pada praktik gotongroyong yang masih hidup di seluruh pelosok pedesaan nusantara. Artinya, kebersamaan itu sejatinya merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong, kebersamaan, dan kekeluargaan, maka dibentuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara sosiologis, inti dari kebersamaan itu adalah partisipasi sosial. Namun partisipasi sosial tersebut tidak hanya dimaknai sebagai partisipasi aktif dalam pemilihan wakil rakyat atau sekedar partisipasi prosedural seperti dalam praktik politik, tetapi partisipasi sosial yang memiliki budaya atau kebersamaan berdasarkan kearifan-kearifan lokal masyarakat setempat sebagaimana yang akan diurai dalam Bab VI di bawah ini. 77 III.5 Sistem Hukum Dalam pengertian umum, kata "sistem" berarti suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur, dimana unsur satu dengan unsur lain saling berhubungan secara fungsional. Secara teoretik, masing-masing unsur itu terdiri dari subsistem-subsistem yang masing-masing subsistem terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain juga berhubungan secara fungsional. Dalam konteks hukum, Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa hukum paling baik dipahami sebagai suatu sistem hukum, yaitu sebuah sistem yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya24. Pertama, struktur dimaksud adalah seperangkat kelembagaan yang diciptakan dalam kerangka sistem yang ada untuk mendorong bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Kedua, substansi dimaksud adalah produk (output) dari bekerjanya sistem hukum dimaksud tadi, yaitu hukum itu sendiri; dan ketiga, budaya dimaksud adalah nilai-nilai, yang oleh Friedman disebut sebagai keseluruhan kekuatan sosial (social forces) dan keseluruhan kekuatan hukum (legal forces) yang dijadikan bahan masukan (input) ke sebuah proses bekerjanya struktur dan sebagai pengikat bekerjanya struktur itu sekaligus dapat digunakan sebagai pemetaan budaya hukum satu di antara budaya hukumbudaya hukum lain. Friedman sendiri menganggap bahwa 24 Friedman, M. Lawrence., 1975. The Legal System. New York: Russell Sage Foundation. 78 unsur-unsur dari suatu sistem hukum tersebut pada dasarnya menentukan bagaimana hukum dibentuk, dilaksanakan, dan difungsikan untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks hukum yang berlaku di seluruh dunia, ada dua sistem hukum utama. Secara umum, berbagai referensi menunjukkan bahwa sistem hukum utama (mainstream) yang ada di dunia ada dua jenis:25 (1) Sistem hukum Common Law atau Common Law System yang dianut oleh negara-negara Anglosakson, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan sebagian besar negara negara persemakmuran. (2) Sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law System yang dianut oleh negaranegara Eropa Daratan, seperti Belanda, Prancis. termasuk Indonesia. Keberlakuan sistem hukum Eropa Kontinental di Indonesia karena ketergantungan pada Asas Konkordansi, dimana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sehingga sistem hukum Belanda berdasarkan asas konkordansi tersebut dianut oleh Indonesia setelah merdeka. Namun demikian, menyusul dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik ketatanegaraan dan ketatapemerintahan Indonesia berkembang sedemikian rupa sehingga sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang tidak sepenuhnya terikat pada Sistem Eropa Kontinental, sebagaimana telah dijelaskan pada bab Resepsi Budaya 25 Bogdan, Michael., 2010. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan Derta Srie Widowatie). Bandung: Nusa Media. 79 Hukum Barat. Bahkan, beberapa komponen sistem hukum Common Law diresepsi ke dalam sistem hukum Indonesia, baik pada sub-sistem peraturan maupun pada sub-sistem peradilannya. Kedua sistem hukum dan sistem peradilan di atas, meskipun memiliki perbedaan-perbedaan, tetapi secara umum ada persamaannya, antara lain keduanya tetap mengenal adanya pemisahan kekuasaan dari semua lembaga-lembaga negara, sebagaimana dimaksud dalam teori pemisahan kekuasaan. Demikian pula, ada pemisahan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan tersendiri di luar kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Namun demikian, ada pula perbedaannya terutama pada sub-sistem peraturan sebagai berikut: (1) Pada sistem hukum Common Law, pada umumnya didominasi oleh hukum tidak tertulis (asas stare decisis) melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi). (2) Pada sistem hukum Common Law, tidak ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dengan hukum privat, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental, ada pemisahan yang jelas dan tegas antara hukum publik dengan hukum privat. Perbedaan sistem hukum dan peraturannya tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberadaan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena sistem hukum sebagai 80 rangkaian peraturan-peraturan hukum yang disusun secara sistemik berdasarkan asas-asas hukum terkait, memiliki perbedaan-perbedaan yang muncul akibat dari pemahaman hukum yang didasarkan pada budaya hukum bangsa dimana hukum itu dijalankan. Friedman sendiri seperti dikemukakan di atas mengemukakan salah satu unsur dari suatu sistem hukum, yaitu the legal culture atau budaya hukum sebagai salah satu penggerak bagaimana sistem hukum berfungsi. Budaya hukum dimaksud berupa seperangkat nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan yang memberikan isi sekaligus pengikat bekerjanya struktur. Berdasarkan pada dua jenis sistem hukum yang dominan di dunia seperti dikemukakan di atas, sistem peradilanpun terdiri pula atas dua jenis yang mengikuti sistem hukumnya, sebagai berikut: III.5a Sistem Peradilan Common Law Sistem peradilan Common Law menganut sistem peradilan juri, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan apa hukumnya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya kemudian menentukan bersalah-tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara. Di sini hakim diikat oleh suatu asas stare decisis atau the binding force of precedent. Artinya, putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sejenis. Sistem peradilan juri ini sebagai manifestasi dari pemikiran bahwa peradilan merupakan tugas dan tanggung jawab rakyat. 81 Hakim pada negara yang menganut sistem hukum Anglo Sakson atau Common Law menggunakan metode berpikir metode induktif, yaitu proses berpikir dari yang khusus berupa kasus-kasus riil ke yang tataran umum. Mereka mendasarkan putusannya pada kasus in-konkreto (kasus-kasus nyata, riil) yang berlaku khusus kemudian diangkat menjadi aturan umum yang akan berlaku sebagai preseden bagi hakim lain pada perkara sejenis berikutnya. Esensi dari asas the binding of precedent bagi hakim adalah kecermatan, ketelitian, kecepatan, ketepatan, dan ketrampilan hakim dalam mengambil suatu putusan dan menerapkan suatu aturan hukum atas kasus kongkrit. Asas ini merupakan kewajiban utama bagi seorang hakim, yaitu kewajiban tradisional hakim untuk memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara dengan mencarikan aturan hukum yang relevan melalui Binding Precedent. Kelihatan sekali bagaimana maksud penggunaan asas preseden, yaitu untuk mempercepat putusan hakim sebab dasar untuk memutus pada perkara yang sama telah ada sebelumnya. Metode yang digunakan dalam menilai fakta kasus, adalah analogi yang membandingkan antara peristiwa-peristiwa yang sejenis, atau mempersamakan suatu peristiwa yang sejenis. Preseden ini berbentuk sebagai suatu lembaga, yaitu terdiri atas sebagian besar hukum yang tidak tertulis (ius non scriptum) melalui putusan-putusan hakim. Namun, putusan ini hanya diakui apabila dihasilkan dari suatu proses peradilan. Artinya, hanya putusan pengadilan yang diakui sebagai hukum. 82 Kadangkala putusan hakim sudah disampaikan, namun masih ada pernyataan hakim yang disampaikan di luar putusan dimaksud. Pernyataan hakim yang tertuang di dalam putusannya biasa disebut ratio decidendi dan di luar putusan biasa disebut obiter dictum. Ratio decidendi adalah aturan hukum yang dipakai pengadilan dalam memutuskan kasus hukum kongkrit. sementara obiter dictum adalah keputusan ”in passing” yang tidak dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak mengikat untuk kasus-kasus sejenis yang kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang. Yang pertama aturan hukum mengikat karena telah teruji dengan bukti dalam serangkaian persidangan, sementara obiter dictum tidak mengikat karena fakta obiter dictum dibuat tanpa hakim harus mengujinya lebih terdahulu dan tanpa mempertimbangkan masing-masing konsekuensi aktualnya. Dengan demikian jelas, Michael Bogdan menganalogkan dengan contoh fiktif. Misalnya, ada tetangga memelihara anjing jenis tertentu untuk menjaga rumah pemiliknya. Suatu ketika, anjing lepas dari tali pengikat lehernya sehingga anjing tersebut dapat meloncat pagar mengejar dan menggigit seseorang yang kebetulan sedang lewat depan rumah yang dijaganya. Akibat bagian tubuhnya digigit anjing itu sehingga terluka dan berdarah, pengadilan memerintahkan pemilik anjing tersebut untuk memberi kompensasi sebagai akibat dari kelalaian merantai anjing yang menjadi tanggungjawabnya menyebabkan orang lain terluka. 83 Namun dalam menjelaskan putusannya itu, hakim membangun pernyataan obiter di luar argumentasi hukum yang digunakan, misalnya hakim menjelaskan penalarannya dengan menambahkan jika ada kasus-kasus sejenis dapat diputus serupa. Pernyataan itu dimaksudkan untuk memberi penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kasus sejenis, namun ketika terjadi hal yang mirip misalnya yang melukai bukan anjing tetapi binatang jenis lain, tentu ini menjadi masalah analog. Memang hakim pengadilan yang disebut pertama tidak menyebut binatang lain selain anjing tetapi makna pernyataan hakim dimaksud tidak dapat dihindarkan dari binatang-binatang lain sejenis sebagai akibat kelalaian dan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Keterikatan hakim pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, hanya pada bagian ratio decidendi, yaitu aturan hukum yan menjadi alasan penentu dalam memutus suatu kasus hukum kongkrit. Memang obiter dicta tidak berkaitan langsung berhubungan dengan kasus hukum kongkrit yang pertama tetapi menjadi problem kepastian hukum ketika terjadi kasus hukum sejenis. Di sinilah letak pentingnya kehadiran juri di dalam sistem peradilan Common Law untuk memberi pertimbangan putusan hakim. Juri-juri dimaksud dipilih dari komunitas warga masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan, cerdik pandai dan tokoh keagamaan setempat) dimana kasus hukum kongkrit terjadi, bukan ahli hukum atau sarjana hukum. 84 Sebagai prinsip penafsiran keputusan pengadilan, penafsiran atas preseden menjadi penting baik dalam Sistem Hukum Common Law maupun Sistem Hukum Kontinental. Kesamaan itu amat masuk di akal mengingat tujuan yang utama pelaksanaan asas preseden pada sistem peradilan dengan asas the binding force of precedent pada negara Anglo Sakson yang menggunakan juri ini maupun kontinental dengan tanpa juri adalah untuk mewujudkan asas kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum selain asas manfaat dan asas keadilan. Keterikatan hakim lain pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, hanya terbatas pada aturan hukum yang menjadi dasar putusan yang disebut ratio decidendi sebagaimana dijelaskan di atas. III.5.b Sistem Peradilan Eropa Kontinental Sistem peradilan Eropa Kontinental atau biasa juga disebut Civil Law System, dimana hakim diikat oleh undangundang (hukum tertulis). Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, kepastian hukumnya dijamin melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Hakim tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya, seperti yang berlaku pada sistem peradilan Common Law dengan asas preseden. Artinya, hakim-hakim lain boleh mengikuti putusan hakim sebelumnya pada perkara yang sejenis, tetapi bukan suatu keharusan yang mengikat. Di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1917 KUHPerdata bahwa putusan pengadilan hanya mengikat para pihak, dan tidak mengikat hakim lain. 85 Sistem peradilan Eropa Kontinental tidak mengenal Sistem Juri. Tugas dan tanggung jawab hakim di sini, adalah memeriksa langsung materi perkaranya, menentukan bersalah tidaknya terdakwa atau pihak yang berperkara, kemudian sekaligus menerapkan hukumnya. Metode berpikir hakim dilakukan "secara deduktif", yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Hakim berpikir dari ketentuan yang umum untuk diterapkan pada kasus inkonkreto yang sedang diadili. Contoh ketentuan umum dalam peraturan Indonesia adalah kata “barang siapa”, yang berarti siapa saja dan tentu saja berlaku secara umum bagi setiap subjek hukum. Dalam sistem peradilan Eropa Kontinental, menggunakan pula metode subsumptie dan metode sillogisme. Sumsumptie adalah suatu upaya memasukkan peristiwa ke dalam peraturannya yang banyak dilakukan dalam perkara pidana. Suatu peristiwa hukum dicarikan rumusan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, laksana mencocokkan sepatu dengan kaki pemakainya. Namun, metode sumsumptie agak sulit diterapkan oleh hakim di Indonesia pada perkara perdata, akibat masih banyak peraturan hukum perdata yang tidak tertulis. Melihat bagaimana sistem peradilan Eropa Kontinental seperti penulis uraikan di atas, terlihat jelas adanya perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil dengan sistem peradilan Common Law. Namun, melihat kenyataan kehidupan sosial masyarakat saat ini, terutama pengaruh globalisasi dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 86 teknologi di pelbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga setidaknya juga mempengaruhi kedua keberadaan sistem peradilan. Hal ini yang menjadikan hakim-hakim Indonesia yang sebetulnya berpedoman pada sistem peradilan Eropa Kontinental, sering mengikatkan diri pada asas preseden seperti pada sistem peradilan Common Law dengan menggunakan yurisprudensi. Sebaliknya, hakim di Inggris yang menganut sistem peradilan Common Law sering pula melepaskan diri dari keterikatan terhadap asas preseden pada perkara tertentu, jika kebutuhan masyarakat menghendaki lain. Menyimak uraian Sistem Hukum dan Sistem Peradilan Eropa Kontinental dengan Common Law (Anglo Sakson) di atas, maka untuk lebih memahami eksistensi kedua sistem peradilan tersebut, ada baiknya melihat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil antara keduanya, yaitu: a. Perbedaan pada Sistem Peraturannya: Pada sistem hukum Common Law didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental didominasi oleh hukum tertulis (kodifikasi). Pada sistem hukum Common Law tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat, sedangkan pada sistem hukum Eropa Kontinental ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat. b. Perbedaan pada Sistem Peradilannya: 87 Pada sistem peradilan Common Law menggunakan Juri yang memeriksa fakta kasusnya kemudian menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan, sedangkan pada sistem peradilan Eropa Kontinental tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan. Pada sistem peradilan Common Law hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis melalui asas the binding force of precedent, sedangkan pada sistem peradilan Eropa Kontinental hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya, meskipun perkara hukumnya sejenis. Pada sistem peradilan Common Law menganut pula asas "adversary system" yaitu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, sedangkan pada sistem peradilan Eropa Kontinental hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat) dan pada perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang. Selain ketiga perbedaan prinsipil yang penulis kemukakan di atas, masih ada perbedaan lainnya yaitu pada hukum acaranya (hukum formil) yang berbeda antara perkara perdata dengan perkara pidana. Ada tiga macam perbedaan dalam hukum acara pidana dengan hukum acara 88 perdata yang dapat dikaji pada sistem peradilan Eropa Kontinental, sebagai berikut: Perbedaan dari segi inisiatif penuntutan. Inisiatif penuntutan dalam hukum acara pidana ada pada Jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan publik, sedangkan dalam hukum acara perdata inisiatif terletak pada pihak penggugat yang mewakili kepentingan dirinya sendiri atau perseorangan. Termasuk dalam hal pembuktian, yaitu pada perkara pidana yang membuktikan kesalahan terdakwa penuntut umum, sedangkan pada perkara perdata kedua pihak yang membuktikan kebenaran dalil atau bantahannya terhadap dalil lawannya Perbedaan dari segi keterikatan hakim pada alat bukti yaitu pada hukum acara pidana, hakim selain terikat pada alat-alat bukti yang sah, juga harus yakin akan kesalahan terdakwa, atau dikenal dengan istilah "beyond reasonable doubt" yang berarti "alasan yang tidak diragukan lagi". Pada hukum acara perdata, hakim hanya terikat pada alatalat bukti sah yang biasa disebut dengan istilah preponderance of evidence yang berarti "pengaruh yang lebih besar dari alat bukti". Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin dicapai, pada hukum acara pidana ingin mencapai "kebenaran meteriil" yaitu kebenaran yang nyata atau betul-betul kebenaran dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, atau hubungan antara pihak yang terkait dalam perbuatan pidana tersebut. Pada hukum acara perdata, semata-mata ingin mencari "kebenaran formil", yaitu 89 kebenaran yang dinyatakan oleh para pihak di dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan bukti surat, kendati belum tentu secara nyata demikian. III.5.c Sistem Peradilan di Indonesia Mendiskusikan sistem hukum tidak dapat lepas dari diskusi sistem peradilan di Indonesia. Sistem Peradilan Indonesia (baca: peradilan litigasi) tentu diawali dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.26 Undang-undang dimaksud merupakan koreksi atas dan mengganti UndangUndang Nomor 19 Tahun 1964 tentang hal yang sama. Dalam undang-undang dimaksud ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya diatur dengan undang-undang. Ketika era reformasi bergulir sejak 1998, berbagai tuntutan reformasi hukum menjadi Condio Sine Quanon. Salah satu reformasinya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam lingkup 26 Sebagian isi disarikan dari Ahmad Fauzan , 2005. “Kata Pengantar” dalam Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Prenada Media, vii-xii 90 peradilan umum, pengadilan negeri dapat menangani perkara-perkara khusus misalnya pengadilan ekonomi, pengadilan anak, yang semuanya diatur dengan undangundang. Peradilan umum berwenang memeriksa atau menyidangkan baik kasus pidana maupun kasus perdata termasuk kasus yang menyangkut masalah hubungan keluarga, yaitu perceraian, kecuali para pihak yang akan bercerai itu beragama Islam sehingga harus disidangkan oleh peradilan agama. Peradilan anak yang merupakan anak peradilan dari peradilan umum bukan sebuah pengadilan yang menyidangkan semua persoalan yang berkaitan dengan anak tetapi hanya berwenang memeriksa dan mengadili masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berusia 8 tahun, namun belum berumur 18 tahun dan belum kawin. Berbeda dengan pengadilan negeri pada umumnya ketika lembaga ini menyidangkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka persidangan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, kecuali saat pembacaan putusan karena pembacaan harus digelar dengan sidang terbuka untuk umum. Di samping itu, para penegak hukum yang terlibat dalam kasus yang disidangkan tidak boleh mengenakan pakaian kebesaran toga atau pakaian dinas. Hal ini disesuakan dengan kondisi kejiwaan anak yang tidak sama dengan kondisi kejiwaan orang dewasa. 91 Pada saat pemeriksaan di persidangan, si anak sebagai terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh. Sedangkan pada pemeriksaan saksi, terdakwa dibawa keluar sidang. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan saksi yang terdakwanya orang dewasa,. Begitu pula saat ditahan dan/atau dalam masa hukuman, anak ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan yang terpisah dari tempat orang dewasa. Sebagai pengejawantahan ajaran legisme, semua peradilan dibentuk dengan undang-undang, tetapi tidak semua peradilan dibentuk dengan nama-nama undangundang khusus tentang peradilan yang dimaksud. Misalnya, Pengadilan Niaga yang dibawah undang-undang kepailitan, pengadilan tindak pidana korupsi di bawah undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Syari’ah di bawah undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mahkamah Pelayaran di bawah Peraturan Pemerintah tentang Pemeriksaan Kapal. Pengadilan Niaga tidak diatur dalam undang-undang tersendiri seperti pengadilan anak atau pengadilan hak asasi menusia tetapi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Perpu ini selanjutnya ditetapkan menjadi undang-undang dengan lahirnya undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. 92 Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus atau deferensiasi yang berbeda dalam lingkungan peradilan umum (pengadilan negeri). Dalam konteks putusan, putusan peradilan niaga berbeda dari putusan peradilan umum, putusan peradilan khusus pengadilan niaga ini merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir artinya, terhadap putusan pengadilan niaga ini tidak dapat diajukan banding. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan niaga, maka ia dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hakim Ad Hoc pada pengadilan niaga ini Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Niaga. Oleh karena pengadilan niaga tidak diatur dalam undang-undang tersendiri maka tidak semua ketentuan dalam semua pasal tertuang dalam himpunan undangundang ini. Yang tercantum dalam buku ini hanya pasalpasal secara langsung mengatur tentang pengadilan niaga. Badan peradilan khusus lain yang bernasib sama seperti pangadilan niaga adalah pengadilan pidana korupsi dan pengadilan perburuhan atau perselisihan industri. Pengadilan tindak pidana korupsi diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga dengan pengadilan perselisihan industrial hanya merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 2 93 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. Badan peradilan khusus lain adalah Mahkamah Syari’ah. Mahkamah Syari’ah hanya berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hanya berlaku khusus bagi mereka yang beragama Islam. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), inilah badan peradilan khusus yang ditunggu-tunggu oleh pendamba kebenaran dan keadilan terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan terbentuknya pengadilan HAM, korban dan atau keluarga korban Hak Asasi Manusia sekarang mempunyai akses untuk melaporkan mereka yang diduga sebagai pelanggar ke pihak yang berkompeten seperti Komnas HAM agar pelaku pelanggaran HAM dapat diadili di pengadilan HAM yang berada dalam lingkup Peradilan Umum. Untuk kasus pelanggaran hak asasi yang bertindak sebagai penyelidik adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan sebagai pihak penyidik adalah Jaksa Agung yang sekaligus juga berfungsi sebagai Jaksa Penuntut Umum. Adapun selaku (Majelis) Hakim, berbeda dalam majelis Haklim Peradilan Umum, Hakim pengadilan HAM berjumlah 5 (lima) orang dan 2 di antaranya adalah hakim Ad Hoc. Perbedaannya dengan pengadilan negeri adalah bahwa pengadilan HAM ini berwenang untuk memeriksa atau menyidangkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi 94 sebelum dikeluarkannya Undang-undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jika demikian halnya, maka pelaku pelanggaran HAM pada kasus Aceh, Timtim, dan Tanjung Priok akan dapat disidangkan. Saat ini sudah keluar Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kasus Tanjung Priok dan Timor Timur. Pengadilan khusus lain adalah Pengadilan Pajak, sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan ini melaksanakan kekuasaan kehakiman dibidang sengketa pajak. Dalam undang-undang tentang pengadilan pajak tidak terdapat ketentuan yang jelas mengenai apakah pengadilan pajak berada dalam lingkup peradilan yang sama atau tidak. Namun pada penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan pajak adalah “cabang” dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu juga penjelasan Pasal 9A. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa pengadilan pajak adalah bawahan Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat diajukan banding. Namun berbeda dari putusan pengadilan 95 niaga yang dapat diajukan kasasi oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga, pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan tata cara yang diatur PERMA Nomor 3 Tahun 2002. Mahkamah Pelayaran, tidak seperti peradilan khusus lain yang diatur dengan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, diatur dalam peraturan pemerintah dan itupun tidak secara khusus mengatur tentang mahkamah ini. Peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal. Mahkamah Pelayaran sebagaimana halnya pengadilan pajak berkedudukan di Ibu Kota Negara, yaitu Jakarta. Hanya saja ia tidak seperti badan peradilan lain, misalnya Mahkamah Pelayaran tidak berada dalam lingkup pengadilan negeri mengingat Mahkamah Pelayaran merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada menteri perhubungan. Pertanyaannya, apakah Mahkamah Pelayaran ini di bawah lingkungan Peradilan Umum atau yang lain. Walaupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa semua peradilan khusus harus berada dibawah salah satu di antara 4 lingkungan peradilan, memang undang-undang ini tidak menentukan secara spesifik apakah mahkamah pelayaran dimaksud berada dibawah peradilan tertentu. Namun mesti maklum bahwa mahkamah pelayaran ini bukan suatu peradilan khusus seperti yang dimaksudkan 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebab badan ini dibentuk dengan peraturan pemerintah, bukan dengan undang-undang sebagaimana diisyaratkan oleh UndangUndang Nomor 4 tahun 2004. Jika Mahkamah Pelayaran dikategorikan sebagai badan peradilan khusus, maka badan ini diatur dengan undang-undang. Kewenangan mahkamah pelayaran adalah memeriksa adanya kesengajaan atau kelalaian yang berhubungan dengan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh mualim, atau perwira/pemimpin kapal. Sedangkan keputusan yang dijatuhkan adalah berupa sangsi administrasi. Keputusan mahkamah pelayaran, seperti halnya pengadilan pajak atau pengadilan niaga, adalah bersifat final. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yang lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat (1) dan (2). Wewenang mahkamah ini adalah: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutuskan sengketa lembaga Negara; yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutuskan pembubaran partai politik; memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas dugaan bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran. 97 BAB IV RESEPSI BUDAYA HUKUM BARAT IV.1 Awal Resepsi Budaya Hukum Barat Dakam konteks sejarah, pada awalnya Hukum Barat merupakan hukum yang diambil dari hukum Romawi. Negeri Belanda sebagai salah satu negeri daratan Eropa memiliki hukum yang asalnya juga merupakan hasil resepsi budaya hukum dari luar Belanda. Meskipun demikian, resepsi Budaya Hukum Romawi oleh masyarakat Belanda tidak berlaku sekaligus akan tetapi mulai tahap-tahapan. Menurut seseorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Djokosoetono, resepsi Budaya Hukum Romawi oleh masyarakat daratan Eropa Barat, dilakukan secara bertahap, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut.27 Tahap pertama, suatu tahap di mana orang-orang terpelajar di Daratan Eropa Barat yang berminat memperlajari hukum pergi ke Romawi untuk belajar Hukum Romawi. Hal itu terjadi pada masa daratan Eropa Barat dikuasai oleh Kerajaan Romawi. Sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Romawi, penguasa-penguasa Romawi tentu memperlakukan Hukum Romawi di Negeri Belanda. Pada masa itu, kalangan orang-orang terpelajar dari Eropa Barat yang berminat ilmu hukum mempelajari seluk beluk 27 Sebagian uraian ini dikutip dari Mochammad Koesnoe, 1989. Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positip. Surabaya: Ubhara 98 dari Hukum Romawi, yaitu hukum Itali. Tahap resepsi budaya ini merupakan tahap resepsi Budaya Hukum Romawi yang disebut resepsi teoritis. Tahap kedua, suatu tahap di mana para yuris yang telah terdidik dalam teori tentang Hukum Romawi melaklukan praktik Hukum Romawi atas dasar kemampuan yuris yang bersangkutan dalam menyerap dan memahami asas-asas dan ketentuan-ketentuan, lembaga serta sistem Hukum Romawi dengan latar belakang budaya masingmasing, yaitu nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang hidup dan dihayati masyarakat dari mana yuris dimaksud berasal. Tahap resepsi ini merupakan tahap yang disebut sebagai tahap resepsi praktis Hukum Romawi yang dilakukan oleh masing-masing negeri yang ada di dataran Eropa Barat. Berikutnya, tahap ketiga, dalam tahap ketiga ini segala hasil praktik para yuris di daratan Eropa Barat tentang Hukum Romawi dipelajari dengan cara membandingkan secara ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa Hukum Romawi di dalam praktik di daratan Eropa Barat tidak sepenuhnya sama dengan aslinya Hukum Romawi yang dipraktikkan oleh para yuris Romawi di negerinya sendiri. Hasil dari upaya mempelajari Hukum Romawi dalam praktik demikian ini merupakan suatu bahan yang sangat berguna untuk menentukan Hukum Romawi yang bagaimanakah yang seharusnya diberlakukan untuk masing-masing negeri yang ada di daratan Eropa Barat. 99 Hasil kajian Hukum Romawi Barat yang dipraktikkan di Daratan Eropa Barat secara kritis menunjukkan bahwa Hukum Romawi yang diberlakukan di negeri-negeri yang bersangkutan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diberlakukan di Romawi. Hal itu disebabkan karena nilainilai, pandangan-pandangan, dan persamaan-persamaan hukum dan keadilan masyarakat yang bersangkutan ternyata dan terbukti ikut menentukan isi hukum. Tahap resepsi Budaya Hukum Romawi ini adalah suatu tahap yang disebut sebagai tahap resepsi Ilmu Hukum Romawi. Tahap keempat. Di dalam tahap keempat ini terlihat bahwa masyarakat di daratan Eropa Barat berusaha menuangkan hasil-hasil studi ilmiah resepsi Budaya Hukum Romawi kedalam bentuk hukum positif masyarakatnya masing-masing. Yang dimaksud Hukum Romawi yang diresepsi tersebut bukan Hukum Romawi Kuno yang benarbenar khas Romawi, akan tetapi Hukum Romawi sebagaimana telah disesuaikan dengan pikiran dan perasaan hukum masing-masing budaya masyarakat negeri daratan Eropa Barat. Tahap-tahapan resepsi Budaya Hukum Romawi oleh negeri-negeri yang ada di daratan Eropa Barat tersebut memunculkan suatu pikiran bahwa Hukum Romawi adalah hukum yang dapat diberlakukan di luar Romawi. Hal itu dapat terjadi karena Hukum Romawi adalah hukum yang mempunyai sifat universal. Mengapa demikian, menurut kalangan pemikir ini Hukum Romawi adalah ratio manusia yang ditulis (ratio scripta). Sebagai ratio scripta, Hukum 100 Romawi itu universal dan ada pada setiap manusia di manamana dan kapan saja manusia dimaksud ada di dunia ini. Pandangan yang berpendapat demikian terhadap Hukum Romawi menimbulkan pandangan berikutnya bahwa Hukum Romawi sebagai ratio manusia, maka ia dapat ditemukan dalam suatu Undang-Undang yang lengkap. Pandangan semacam ini akhirnya membawa paham kodifikasi, yaitu menulis sesuatu bidang hukum tertentu secara lengkap, tuntas, dan bersifat sistematis dalam bentuk rumusan pasal demi pasal kedalam suatu kitab Undang-Undang merupakan tuntutan. Resepsi Budaya Hukum Romawi yang melahirkan pikiran bahwa kodifikasi merupakan sebuah tuntutan menjadikan dasar yang diikuti oleh kalangan penguasa Perancis pada waktu diperintah oleh Napoleon Bona Parte. Pada waktu itu Napoleon memerintahkan untuk menyususn kodifikasi hukum Perancis dengan contoh dan model Hukum Romawi dengan memperhatikan hasil-hasil resepsi ilmiah Hukum Romawi. Hasilnya, dalam masa itu terbentuk kodifikasi dalam bidang Hukum Pidana, kodifikasi hukum sipil, serta kodifikasi hukum dagang masing-masing kedalam kitab-kitab Undang-Undang yang tersendiri. Kodifikasi hukum tersebut di daratan Eropa Barat terkenal dengan sebutan Kode Napoleon. Pada waktu pemerintah Perancis di bawah kaisar Napoleon, negeri Belanda berada pada pendudukan negara tentara Perancis. Selama pendudukan tersebut diberlakukan di negeri Belanda kode Napoleon tersebut. Setelah negeri 101 Belanda terlepas dari pendudukan tentara Perancis, kode Napoleon ternyata sangat mempengaruhi kehidupan Hukum Positif di negeri Belanda. Kode Napoleon tetap dipertahankan oleh pemerintah negeri Belanda sekalipun diadakan perubahan dan penyesuaian disana-sini atas dasar perasaan dan pikiran hukum yang bersumber pada apa yang di negeri Belanda disebut Oud vaderlandch recht. Kodifikasi negeri Belanda ini kemuduan, atas dasar asas konkordansi, diberlakukan pula oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sebagai daerah jajahannya. Sebagaimana disebutkan di atas, selain memberlakukan melalui tahap-tahapan, yang menjadi tugas mempraktikkan kode-kode Napoleon, demikian juga Hukum Belanda di Indonesia, ditentukan secara bertahap dan berkembang terus disesuaikan dengan perasaan budaya masyarakat setempat dimana kode itu diberlakukan. Dalam hubungannya dengan resepsi Budaya Hukum Romawi oleh masyarakat di daratan Eropa Barat, tidak semua pemikir hukum di sana pada abad ke XIX menyetujui aliran pemikiran tentang Hukum Romawi. Aliran lain ini disebut sebagai Mazhab Historis. Di antara tokoh yang sangat terkenal dalam mazhab ini bernama Von Savigny. Aliran ini menentang pikiran yang melihat Hukum Romawi sebagai ratio cripta yang berlaku universal. Aliran ini berpendirian bahwa hukum tidak dibuat dengan sengaja. Hukum itu ada dan berkembang sesuai dengan irama yang kehidupan rakyat dari masyarakat yang bersangkutan. 102 Aliran sejarah sebenarnya tidak menentang kodifikasi, akan tetapi persoalan utamanya yang ditentukan adalah soal memberlakukan hukum asing bagi masyarakat yang tidak menganut dan menghayati hukum yang bukan cita rasa budaya hukumnya sendiri. Untuk kodifikasi dikemukakan oleh aliran ini bahwa pertama-tama ilmu pengetahuan hukum dari masyarakat bersangkutan harus dikembangkan dan ditingkatkan terlebih dahulu. Dalam konteks Indonesia, Hukum Barat yang dengan lahap diresepsi pada waktu sekarang ini ternyata Hukum Romawi yang diresepsi oleh negara Belanda pada abad XIX melalui penyaringan, rekayasa, dan terus menerus berkesinambungan. Hukum Belanda yang kini diterima dan geluti dengan begitu akrab, di negeri Belanda sendiri dewasa ini sudah banyak dirubah sesuai dengan panggilan jiwa dan kebutuhan hukum dari rakyat negeri tersebut. Dengan lain perkataan resepsi Budaya Hukum Romawi sebagaimana direkayasa pada abad yang lalu, oleh masyarakat Belanda sendiri dewasa ini telah ditinggalkan, sementara yang tinggal tersisa hanya sekelumit dari ilmu maupun sistemnya. Sedangkan hal-hal yang menyangkut ketentuanketentuan substansi telah banyak dirubah. IV.2 Resepsi Budaya Hukum Barat kedalam Masyarakat Indonesia Secara umum, Hukum Positif di Indonesia pada waktu ini masih dapat dibedakan dalam dua golongan hukum, golongan Hukum Barat dan golongan Hukum Adat. Golongan Hukum Adat atas dasar tradisi yang diikuti dari 103 masa lalu dan menurut kalangan hukum Nusantara termasuk di dalamnya hukum yang berasal dari agamaagama besar seperti Hukum Hindu, Budha, Fiqih. Dengan dimasukkannya hukum-hukum yang dibawa oleh agamaagama besar kedalam Hukum Adat tersebut maka dalam wacana Hukum Adat pribumi, sebenarnya substansi Hukum Adat sudah termasuk hukum-hukum yang berasal dari agama-agama besar tersebut. Tentu pertanyaannya, sejak kapan kira-kira Hukum Barat diresepsi oleh masyarakat pribumi yang kini disebut masyarakat Indonesia. Semula Hukum Barat diperkenalkan kedalam masyarakat Indonesia sejak orang-orang Barat mulai bertempat tinggal di kota-kota tertentu di Indonesia. Berdasarkan penelusuran bahan-bahan hukum sejarah Indonesia, yang dengan jelas dapat dikemukakan bahwa Hukum Belanda diperkenalkan terutama di tempat-tempat konsentrasi kediaman orang-orang Barat, terutama orang Belanda, misalnya di Kota Batavia yang kini disebut Jakarta, diresepsi telah dimulai sejak zaman Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Tentang bentuk Hukum Barat yang pada awalnya diperkenalkan di Kota Batavia tersebut, ternyata Hukum Barat yang diberlakukan adalah Hukum Belanda Kuno. Hukum Belanda Kuno lain adalah Burgerlijk Wetboek (BW) yang hinggi kini masih digunakan. Di Kota Batavia tersebut Hukum Belanda Kuno itu tidak berlaku bagi orangorang pribumi sehingga tidak ada suatu peristiwa resepsi Budaya Hukum Belanda Kuno tersebut oleh orang-orang 104 pribumi yang kini disebut orang Indonesia. Masing-masing golongan penduduk yang ada di Kota Batavia tersebut pada prinsipnya hidup di bawah hukumnya sendiri-sendiri. Peristiwa resepsi Budaya Hukum Barat oleh masyarakat Indonesia dalam arti yang sesungguhnya baru dapat dicatat sekitar 1847 dan seterusnya. Sejak tahuntahun itu dapat dicatat adanya peristiwa Hukum Barat dipaksakan (enforced) berlaku untuk masyarakat adat. Tahap pertama, perlakuan secara paksa Hukum Barat di dalam masyarakat adat dalam bidang tertentu saja, yaitu bidang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Strafsrecht Wetboek. Diberlakukannya Hukum Pidana dengan paksa oleh pemerintah kolonial atas dasar kekuasaan. Hukum Pidana yang dipaksakan pemerintah kolonial Belanda diterima begitu saja oleh masyarakat adat dengan menyerah untuk menerimanya tanpa pengertian. Dengan perlakuan paksa tersebut tampak bahwa banyak ketentuan-ketentuan dari Hukum Pidana Barat yang dirasakan sebagai hukum ganjil terutama jika diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah diatur Hukum Adat pribumi. Ada perbuatan yang menurut hukum adat sudah sesuai dengan budaya pribumi namun apabila diikuti ketentuan Hukum Pidana Barat perbuatan itu ada yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan keadaan yang demikian, banyak diantara petugas hukum kolonial lambat laun menyadari tentang tidak adilnya ketentuan Hukum Pidana Barat tersebut 105 apabila diterapkan begitu saja terhadap orang-orang Indonesia. Memperlakukan dengan paksa akhirnya membawa tuntutan untuk memberlakukan dengan bijaksana. Memberlakukan Hukum Barat dengan bijaksana demikian ini merupakan permulaan adanya resepsi Budaya Hukum Barat oleh masyarakat adat. Ada satu resepsi Budaya Hukum Barat yang sampai pada waktu ini berlangsung tanpa paksaan, yaitu resepsi Budaya Hukum Perdata Barat sebagaimana termuat di dalam Burgerlijk Wetboek. Hukum Perdata Barat yang tercantum di dalam Burgelijk Wetboek (BW) adalah suatu Wetboek atau kitab Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif negeri Belanda pada pertengahan abad XIX. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk berlaku bagi orang-orang Belanda di negeri Belanda. Pada 1847 dengan mempergunakan asas konkordansi, BW negeri Belanda tersebut oleh Pemerintah Kolonial diberlakukan bagi orang Indonesia. Pada awalnya, undang-undang tersebut khusus bagi orang-orang Eropa termasuk golongan orang-orang Cina, yaitu hanya bagian-bagian tertentu saja dari ketentuan kitab undang-undang tersebut. Namun dalam perjalanan, lambat laun keberlakuan undang-undang tersebut diperluas dengan pengurangan dan penambahan pasal-pasalnya. Penambahan artinya ada tambahan sesuai keadaan dan pengurangan artinya adanya pasal-pasal yang tidak berlaku karena tidak sesuai lagi budaya masyarakat pribumi 106 Selanjutnya di dalam tahun-tahun berikutnya bagianbagian tertentu dari BW diberlakukan pula dengan paksa untuk golongan orang-orang timur asing bukan golongan Cina yang bertempat tinggal di Indonesia. Perkembangan berikutnya, diberlakukan BW (Bugerlijk Wetboek) dan WK (Wetboek Koophandel) untuk masyarakat Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat. Ini adalah tahap dimana masyarakat Indonesia yaitu golongan Bumi Putra mulai benar-benar melakukan resepsi Budaya Hukum Barat. IV.3 Budaya Hukum Barat Pra-Kemerdekaan Berbeda antara berlakunya Hukum Pidana Barat bagi orang-orang Indonesia dengan berlakunya Hukum Perdata Barat untuk orang-orang Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat. Pada mulanya tidak terjadi paksaan Pemerintah Kolonial terhadap orang-orang Indonesia golongan Bumi Putra agar tunduk pada Hukum Perdata Barat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari dasar perundang-undangan yang menyatakan di dalam Pasal 11 Algemeene Bepalingen (AB) bahwa orang-orang Indonesia tunduk kapada Hukum Adatnya sendiri. Hubungan sosial antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Barat, khususnya dengan orang Belanda yang tinggal di Indonesia, membawa kebutuhan-kebutuhan hukum baru di dalam memenuhi tuntutan hubungan sosial kemasyarakatan antarmereka. Ada diantara orang-orang Indonesia yang karena hubungan tersebut berpindah agama, yaitu dari agama yang dianut semula menjadi beragama Kristen. Kemudian, ada yang karena perubahan itu, mereka 107 memiliki jenis kedudukan dan pangkat yang sama dan sederajat dengan orang-orang Belanda sebagai koleganya yang sama-sama tunduk kepada Hukum Barat. Selain itu, adalagi di antara mereka yang mempunyai hubungan erat dalam bidang Hukum Perdagangan menuntut diberlakukannya hukum yang dapat diterima oleh kedua pihak. Semua perubahan tersebut menimbulkan kebutuhankebutuhan hukum baru yang belum diatur atau diatur tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan hubungan antara kedua golongan penduduk yang berbeda budaya hukumnya. Kebutuhan-kebutuhan hukum baru tersebut, yang dialami oleh kalangan orang-orang Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat, mendapat perhatian pula di dalam perundang-undangan pemerintah kolonial. Atas dasar ketentuan Undang-Undang yang demikian itu, maka orangorang Indonesia diberikan berbagai macam kesempatan dengan ruang lingkup pilihan yang bermacam-macam untuk menikmati Hukum Perdata Barat. Sehubungan dengan itu, menikmati Hukum Perdata Barat dapat dilakukan untuk keseluruhan yang meliputi perubahan statusnya sebagai orang adat. Bilamana ini terjadi, orang adat yang tunduk pada Hukum Adat berubah statusnya menjadi orang Eropa yang tunduk pada Hukum Barat. Jika demikian hanya yang terjadi, maka orang adat tersebut telah ’dipersamakan’ (Gelijkgesteld) dengan orang Eropa. Dengan dipersamakan sebagai orang Eropa, maka mereka tunduk pada Hukum Barat, baik Hukum Perdata 108 BW maupun WK. Segala macam bentuk-bentuk Hukum Perdata Barat yang diberlakukan bagi orang adat itu, yang penting untuk diperhatikan dalam sejarah hukum Indonesia adalah bentuk peraturan ke-empat yang biasa disebut Onderweping voor een bepaalde rechtsandeling. Bentuk yang ke-empat tersenut ialah bentuk yang sampai sekarang masih penting. Banyak orang-orang adat yang dalam usaha dagangnya memilih bentuk usaha dagang beserta lembaga-lembaga dari Hukum Barat. Misalnya, penggunaan CV, Perseroan Terbatas, Yayasan, pemakaian giro, chek, dan penggunaan jasa notaris dan sebagainya. Keseluruhannya tersebut merupakan gejala-gejala tentang bagaimana ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat tersebut digunakan, dmanfaatkan, dan dinikmati oleh orang-orang adat Indonesia. Sekalipun terjadi perkembangan resepsi Budaya Hukum Perdata Barat begitu pesat oleh masyarakat adat, namun yang perlu diperhatikan adalah penerimaan dan penggunaan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat tersebut oleh masyarakat adat. Penerimaan dan penggunaan Hukum Barat dimaksud menunjukkan bahwa adanya perkembangan menuju kepada pemahaman yang tidak lagi murni Barat. Apa yang tampak adalah adanya pemahaman Hukum Barat yang dijiwai oleh Budaya dan Hukum Adat orang Indonesia. Jadi, terjadi semacam meng-adat-kan Hukum Perdata Barat. Hukum Barat yang dimaksud disini dibatasi dalam arti Hukum Barat yang dikodifikasi kedalam ketiga 109 Wetboek di atas. Pada awalnya, ketiga Hukum Barat tersebut dikenal di Indonesia karena pemerintah kolonial memberlakukannya untuk orang-orang Eropa yang menjadi penduduk Indonesia. Kemudian ada kebijakan yang isinya mempersilahkan orang-orang Indonesia dari golongan Bumi Putra menundukkan diri untuk menikmati Hukum Barat secara sukarela. Dalam rangka resepsi Budaya Hukum Barat oleh masyarakat Indonesia peran petugas sebagai pelaksana Hukum Barat sangat menentukan. Di dalam tahap pertama, para pelaksana yang ditugaskan ialah orang-orang yang menguasai pengetahuan Hukum Belanda dan bahasa Belanda. Bidang hukum yang dipercayakan kepada orangorang di Indonesia saat itu masih terbatas pada bidang hukum pidana. Perkembangan selanjutnya mengenai soal tenaga petugas untuk melaksanakan Hukum Barat tersebut, secara bertahap diupayakan diambil dari kalangan putra Indonesia yang termasuk golongan Bumi Putra. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, golongan ini mula-mula diberikan latihan teoretis tentang bagaimana penerapan Hukum Barat, terutama Hukum Pidana Barat. Latihan ini diberikan di dalam suatu lembaga pendidikan hukum yang khusus diadakan untuk orang-orang Bumi Putra dengan instrukturnya yuris-yuris Belanda. Lembaga itu adalah sekolah hukum yang dinamakan Rechtschool. Sekolah hukum ini bertujuan membentuk tenaga terampil di dalam menerapkan Hukum Barat secara praktis, terutama dalam bidang Hukum Pidana Barat. Pendidikan ini 110 melahirkan ’Penerap Undang-Undang’ yang dalam bahasa Belanda disebut Wetstoepasser. Tahap pertama resepsi Budaya Hukum Barat oleh masyarakat Indonesia ini oleh Koesnoe disebut sebagai ’Resepsi Teoritis dari babak permulaan’. Dengan adanya tenaga Penerap Undang-Undang yang terdiri dari orang-orang dari golongan Bumi Putra tersebut, terbentuklah sejumlah kelompok ahli penerap undangundang (Hukum Barat) dari kalangan putra-putera Indonesia golongan Bumi Putra. Dengan ini masyarakat Indonnesia mulai memasuki tahap Resepsi Praktis terhadap Hukum Barat yang tertuang di dalam kitab UndangUndang. Di dalam tahap kedua resepsi ini baik teoretis maupun praktisnya, penguasaan pengetahuan tentang Hukum Barat oleh yuris Indonesia golongan Bumi Putra itu mencakup selain mengenai kualitas juga mengenai lingkup bidangnya yaitu hanya bidang Hukum Pidana Barat. Dalam bidang hukum perdata belum tampak ada kelompok yuris Indonesia golongan Bumi Putra yang dipercaya untuk menangani persoalan hukum itu. Perkembangan selanjutnya, ada desakan kuat untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang lebih banyak dan lebih murah untuk dapat memimpin bidang-bidang kegiatan pemerintah kolonial yang berhubungan atau yang ada hubungan dengan hukum. Selain itu, juga dirasakan oleh pemerintah kolonial adanya kebutuhan mendidik tenagatenaga yuris Indonesia dari kalangan Bumi Putra agar dapat 111 menguasai lebih dalam dan lebih luas pengetahuan teoritis yang bertarap akademis mengenai Hukum Barat. Dengan kebutuhan ini tahun 1924 dibentuk Sekolah Tinggi Hukum atau Rechtshogeschool di Batavia yang kini bernama Jakarta. Dari lembaga pendidikan hukum ini kemudian lahirlah yuris-yuris putera Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan tentang Hukum Barat secara lebih dalam dan lebih luas. Mereka diajarkan hukumhukum sebagaimana yang diajarkan di negeri Belanda sehingga pengetahuan mereka tidak saja mencakup Hukum Pidana Barat akan tetapi juga meliputi bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara. Dengan demikian, kualitas para yuris putera Indonesia saat itu ibaratnya sebagai agen yang siap melanjutkan proses resepsi teoritis hukum Barat ke agen-agen lain berikutnya. Sebagai yuris Indonesia yang menguasai dengan baik bahasa undang-undang barat beserta jiwa bangsa (volkgeist) yang melatar belakangi undang-undang Hukum Barat menjadikan mereka semakin handal. Melalui pendidikan tinggi hukum menjadikan mereka lebih mengerti dibanding dari pada hasil pendidikan Rechtsschool. Kemampuan memahami Hukum Barat mereka adalah mendekati pemahaman Hukum Barat seperti halnya oleh para yuris Barat. Dengan begitu konkordansi hukum tersebut menjadi tidak hanya meliputi berlakunya kitab Undang-Undang hukum di Indonesia, akan tetapi juga meliputi cara pemahamannya terhadap jiwa dan budaya yang terkandung dalam Hukum Barat. 112 Mereka mampu berperan yuris sebagaimana layaknya yuris Barat karena para yuris putra Indonesia tersebut dapat mengupayakan dirinya untuk hidup mengikuti, menghayati, dan menjalani semangat dan Budaya Barat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugastugasnya sebagai petugas Hukum Barat. Memang sebagian dari kalangan ini, ada yang benar-benar menjadi sekelompok putra Indonesia yang asing dari cita-cita dan penghayatan budaya hukum adatnya, terutama di dalam perasaan dan pikiran hukum dari golongan Bumi Putra. Dalam keadaan masyarakat golongan Bumi Putra mempunyai yuris-yuris Hukum Barat itu, saat itu pula mulai diperluas pula bidang-bidang berlakunya Hukum Barat yang tertuang di dalam kitab kodifikasi tersebut. Dalam keadaan demikian itu tampak sebagian golongan Bumi Putra sedikit demi sedikit ada yang menikmati Hukum Barat baik secara penuh maupun sebagian dengan secara sukarela, bahkan hingga berlangsung terus sampai hingga kini. IV.4 Resepsi Budaya Hukum Barat Pasca Kemerdekaan Tahun 1945, tepatnya sejak 17 agustus 1945, Indonesia secara politik mempunyai kedudukan yang lain daripada sebelumnya karena sejak itu Negara Republik Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan. Sebagai negara baru yang saja dideklarasikan berdiri belum mungkin untuk menyusun hukum nasionalnya sendiri secara lengkap sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasarnya. Bertitik 113 tolak dari itu, Pasal Peralihan Undang-Undang Dasar menetapkan bahwa hukum dan perundang-undangan yang lama tetap masih berlaku. Dengan catatan bahwa nyatanyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Dalam perkembangannya, terutama antara tahun 1945 sampai 1949 negara muda ini ternyata mengalami perkembangan dinamis. Sebagai negara Indonesia yang wilayahnya meliputi kepulauan seluruh Nusantara tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Hal ini terjadi mengingat sebagian besar daerah kepulauan Indonesia, bahkan pulau Jawa dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pasca Perang Dunia ke II yang disebut pemerintahan NICA (Nederlandsch Indië Civil Administratie).28 Daerah Indonesia yang dikuasai NICA, tata hukum yang diberlakukan berbeda dengan tata hukum yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tetapi satu hal yang sama yaitu tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang. Di daerah pendudukan NICA, ketiga kitab undang-undang tersebut dipertahankan oleh pemerintah pendudukan NICA dengan mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku pada masa Pemerintah Kolonial sebelum Perang Dunia ke II. 28 NICA adalah tentara sekutu yang ditugasi untuk mengkontrol daerah yang sekarang disebut Indonesia setelah Jepang menyerah kalah Perang Dunia II pada pertengahan 14 Agustus 1945 114 Dalam konteks keberlakuan hukum di wilayah Indonesia antara 1945 sampai 1949, keberlakuan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam wilayah dimana sifat berlakunya Hukum Barat berbeda. Pertama, di daerah yang dikuasai Republik Indonesia. Kedua, daerah yang dikuasai oleh pemerintah NICA. Di daerah yang dikuasai Republik Indonesia, ketiga kitab undang-undang tersebut sebagai Hukum Barat diberlakukan untuk sementara. Selain itu, memberlakukan bahasa Indonesia dan harus disesuaikan dengan jiwa hukum yang baru, yaitu disesuaikan dengan semangat dan prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Di daerah pendudukan NICA berlakunya ketiga kitab undang-undang tersebut sebagai Hukum Barat tetap penuh. Kedaan yang demikian membawa pengaruh kepada teori dan praktik tentang ketiga kitab Undang-Undang tersebut di Indonesia. Di daerah yang dikuasai Republik Indonesia, teori dan praktik ketiga kitab Undang-Undang tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia. Di daerah pendudukan NICA dalam bahasa Belanda yang sesuai dengan bahasa ketiga kitab undang-undang itu. Pada mulanya perbedaan itu tidak terlalu dirasakan dalam arti dan konsekuensinya. Hal itu dikarenakan para petugas hukum di kedua bagian daerah Indonesia tersebut umumnya mempunyai kualitas sama dalam penguasaan bahasa dari ketiga kitab undang-undang itu. Selain itu para teorotis dan para petugas hukum yang menerapkan ketiga kitab undang-undang tersebut kemampuan memahami dan menyerapkan nilai Budaya Barat satu sama lain tidak jauh 115 berbeda. Hal ini karena pendidikan yang mereka peroleh tentang Budaya Barat dan ilmu hukumnya pada dasarnya adalah sama. Perbedaan pemberlakuan ketiga kitab undang-undang sebagai Hukum Barat di Indonesia baru mulai dirasakan arti dan konsekuensinya ketika 1950. Pada waktu itu Indonesia yang dikuasai oleh kedua kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, yang membawa terbaginya daerah Indonesia kedalam dua daerah yang berbeda dalam menghadapi Hukum Barat, menjadi berubah. Perubahan dimaksud ketika Indonesia menjadi di bawah satu kekuasaan yaitu kekuasaan dari Republik Indonesia Serikat. Tidak lama kemudian, di dalam tahun itu juga, berubah lagi di bawah kekuasaan Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tahun 1959 kemudian berubah lagi di bawah kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar 1945. Selama kurang lebih sembilan Tahun Indonesia secara silih berganti mengalami perubahan bentuk negara dan Undang-Undang Dasarnya. Hal itu ternyata sangat berpengaruh kepada arti ketiga kitab undang-undang sebagai Hukum Barat yang masih ditolerir untuk diberlakukan. Selama Indonesia berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia Serikat 1950 dan kemudian di bawah Pemerintah Republik Indonesia kesatuan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sementara 1950, sikap terhadap ketiga kitab undang-undang dari masa kolonial tersebut masih kuat 116 dalam mengikuti, mempelajari, dan mempraktikannya seperti pada masa kolonial. Pada waktu itu, kitab undang-undang tersebut masih tetap berada di dalam keadaannya yang asli, yaitu sebagai Wet, dengan bahasa Belanda. Pemahamannya masih banyak tergantung pada dan masih memakai sumber-sumber bahan pengetahuan dan budaya tentang itu dari negeri Belanda. Keputusan-keputusan dari Hoogeraad Negeri Belanda dan sumber-sumber ilmu pengetahuan positif tulisan para pakar hukum di negeri Belanda masih sangat berpengaruh. Sehubungan dengan itu, bagi seorang sarjana hukum yang ingin melakukan praktik dalam bidang Hukum Barat tersebut dituntut harus dengan baik menguasai bahasa dan Budaya Belanda. Dari itu pada waktu itu tentang resepsi Budaya Hukum Barat, berlangsung sebagaimana masa kolonial. Satu catatan dalam hal ini yaitu bahwa hasil pemahamannya baik teoritis maupun praktis dituangkan kedalam bahasa Indonesia dan bukan dalam bahasa undang-undang itu. Dengan begitu sekalipun upaya memberlakukan Hukum Barat pada masa itu berlangsung sedikit banyak serupa dengan pada masa kolonial, tetapi dalam jiwa dan budayanya mulai ada hal-hal yang tidak sama. Perbedaan itu adalah kalau dahulu resepsi Budaya Hukum Barat berlangsung dalam bahasa dan dengan memperhatikan nilai-nilai Budaya Belanda namun kemudian dinyatakan hasilnya kedalam bahasa Indonesia. Hal semacam ini 117 terjadi tidak hanya di dalam kalangan praktik akan tetapi juga di dalam kalangan teori dan pendidikan hukum. Sehubungan itu, lanjut Koesnoe, bagi orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan hukumnya di Jakarta maupun di Yogyakarta sampai 1959, mereka masih tetap diberikan Meester in de Rechten. Dalam hal ini Rechten yang dimaksud adalah Hukum Belanda. Tahun 1959, Indonesia berada di bawah Pemerintahan Republik Indonesia yang melepaskan diri dari Undangundang Dasar Sementara 1945 karena jiwa Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya berbeda sama sekali dengan kedua Undang-Undang Dasar yang dibentuk 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 jiwa dan budayanya adalah Budaya liberal demokratis. UndangUndang Dasar 1945 jiwa dan budayanya adalah kebersamaan dan bersumber kepada semangat Budaya Indonesia sendiri, yaitu Pancasila. Hal yang demikian mempengaruhi penerimaan ketiga kitab Undang-Undang di atas, baik di dalam praktik, teori maupun di dalam bidang pendidikan hukum. Pengaruh itu diutamakan dalam pemahaman dan dalam memberlakukan ketiga kitab Undang-Undang tersebut sesuai dengan jiwa dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dengan lain perkataan, praktik, teori maupun pendidikan hukum yang menyangkut ketiga kitab Undang-Undang tersebut di atas adalah benarbenar sementara dan harus disesuaikan serta pemahamannya didasarkan pada semangat dan filsafat 118 bangsa Indonesia sendiri seperti tertera di dalam UndangUndang Dasar 1945. Dalam tahap permulaan, hal tersebut memang dilakukan dengan masih sedikit banyak meneruskan tradisi dari waktu sebelumnya. Pemahaman atas ketiga undangundang tersebut sedapat mungkin dilakukan menurut paham dan Budaya Barat, tetapi penyampaian hasilnya dilakukan dalam bahasa Indonesia. Lambat laun keadaan demikian ini menjadi berubah. Semakin lama semakin tampak perubahan dan perubahan itu semakin mendasar karena kurang atau tidak dikuasainya lagi bahasa dan Budaya Belanda oleh kalangan yuris generasi baru Indonesia. Dengan itu semakin berkurang ketergantungan kalangan yuris muda pada sumber-sumber pengetahuan dan budaya dari Belanda. Selanjutnya ketiga kitab undang-undang tersebut akhirnya sebagai Wet menjadikan semakin menjadi benar-benar asing dan pendekatannya dilakukan menurut kemampuan yang ada pada kalangan generasi yuris Indonesia. Dalam tahap itu, pada umumnya ketiga kitab undang-undang tersebut didasarkan pada terjemahan-terjemahan orang-perorangan sebagaimana yang dilakukan oleh penulis-penulis Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam soal mengetahui dan memahami isi ketiga kitab undang-undang tersebut, oleh generasi yuris muda tersebut dilakukan dengan perantaraan karya pribadi orang yang menterjemahkannya. Dari hasil pemahaman secara orang-perorangan demikian ini 119 kemudian penyajiannya dilakukan kedalam bahasa Indonesia. Dengan begitu tahap resepsi Budaya Hukum Barat mengalami titik peralihan yang prinsipil. Artinya, ketiga kitab undang-undang dari Barat tersebut sebagai Wet secara praktis tidak banyak lagi artinya. Dalam keadaan demikian ini apa yang dilakukan untuk meresepsi Budaya Hukum Barat adalah tentu menginterpretasikan lebih lanjut terhadap interpretasi pribadi pandapat penulis Indonesia tentang Hukum Barat. Dengan lain perkataan pemahaman Hukum Barat yang kini telah dikenal umum dan dan diresapi kalangan hukum dewasa ini pada dasarnya bukan lagi Hukum Barat murni, akan tetapi merupakan pemahaman dan penerapan pikiran prinadi penterjemah perorangan tentang apa yang disebut Hukum Barat. Tahun 1960 hal semacam ini dirasakan oleh kalangan pemerintah sebagai hal yang tidak tepat lagi kalau para lulusan fakultas hukum diberi gelar Meester in de Rechten sebagai mana dahulu. Pendidikan hukum di Indonesia pada waktu itu dianggap tidak lagi menghasilkan Meester in de Rechten dalam arti bahwa yang dihasilkan itu adalah sarjana tentang hukum Indonesia. Memang dari dulu pemerintah menghimbau agar lulusan fakultas hukum Indonesia tidak lagi menggunakan gelar Meester in de Rechten atau Mr, tetapi gelar sarjana hukum, disingkat S.H. Bagi lulusan sebelum perang dan dekat setelah itu diserahkan kepada pribadi masing-masing apabila ingin memanfaatkan gelar baru tersebut. 120 Tahap-tahap berikutnya dalam meresepsi Budaya Hukum Barat berlangsung sebagai berikut. Pertama, Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan murni yang meliputi keseluruhan, atau sebagian, atau suatu pasal atau lembaga tertentu. Kedua, Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan tidak begitu murni meliputi sebagian, atau suatu pasal atau lembaga tertentu saja. Ketiga, Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan tidak murni meliputi sebagian atau sesuatu pasal atau lembaga saja. Keempat, Hukum Barat yang semu dinikmati secara sukarela menurut selera rakyat Indonesia sendiri. IV.5 Resepsi Budaya Hukum Pertanahan Mendiskusikan persoalan tanah dan sertifikat hak atas tanah (agrarian aspect), tentu, satu hal yang harus dicoba untuk dibayangkan surut ke belakang adalah tentang keadaan alam pertanahan jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Imajinasi ke belakang yang tertangkap menggambarkan bahwa kala itu alam pertanahan, apakah lahan tanah itu sendiri, apa yang ada di atasnya seperti hutan, sungai, dan apa yang ada di dalamnya seperti tambang, apa yang ada disampingnya seperti laut, dan ikan, tidak atau belum diatur oleh manusia mengingat jumlah manusia masih amat terbatas sementara kekayaan alam melimpah ruah. Ketika manusia lahir, tumbuh, dan beranak pinak yang semakin banyak jumlahnya, maka mulai tumbuh hubungan erat antara manusia dengan alam sekitarnya, misalnya tanah untuk dimiliki baik secara perseorangan 121 maupun kelompok. Ini ditandai dengan upaya membuka lahan, hutan, dan menentukan luas-sempit tanah yang dikuasai dengan memberi tanda-tanda batas alam atau tanda buatan lainnya. Fenomena demikian memperlihatkan bahwa manusia mulai mengatur tanah dan kebiasaan manusia mengatur tanah semakin mapan, bahkan sering diikuti oleh yang lain. Kemapanan aturan satu dan yang lain menjadikan aturan yang diikuti, dan melembaga sehingga akhirnya menjadi hukum adat. Oleh sebab itu, zaman nenek moyang hubungan antarorang, antara orang dan alam, tanah, lahan serba diatur oleh apa yang disebut sebagai hukum adat. Pada masa kerajaanpun sedemikian rupa keadaannya sehingga hukum adat mewarnai semua arena bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lokal masyarakat tempatan atau kerajaan dimaksud. Dengan demikian, posisi hukum adat saat itu sangat kuat dan berakar tunjang jauh ke dalam budaya masyarakat tempatan, sehingga dapat dibayangkan lebih lanjut tentang suasana adat yang seolah tak bakal tersentuh oleh tangantangan administrasi kekuasaan dan kekuatan luar yang datang dari manapun asalnya. Ketidaktersentuhan demikian itu menjadikan lahan pertanahan terbentang luas, sekaligus merupakan aset tak bersubyek hukum sehingga siapapun yang berada di atas tanah dan lahan itu dianggap sebagai subyek hukum secara mutlak (common property). Anggapan demikian muncul menyusul sebuah pandangan religius bahwa tanah adalah 122 bagian dari alam semesta ciptaan Illahi untuk kepentingan makhluknya. Manusia sebagai salah satu dari makhluk lain berupaya mencari dan menggali terus sumber daya alam yang lebih baru dibanding kehidupan masa sebelumnya. Tanah, tentu dipandang sebagai salah satu sumber daya alam, namun mengingat lahan pertanahan saat itu tak terukur luasnya maka tanah hanya dapat dikuasai secara ipso facto.29 Artinya, tanah dipandang dikuasi apabila secara nyata dan kasad inderawi dimana tanah dimaksud ditempati, dimanfaatkan, diusahakan, dan dirawat oleh pemukim dan penggarapnya untuk kesejahteraan manusia. Semakin lahan pertanahan dimaksud ditempati, diolah dan dimanfaatkan secara nyata dan kasad inderawi, maka hak penguasaan atas tanah akan semakin menguat. Sebaliknya, semakin diterlantarkan, maka hak penguasaan dimaksud akan semakin mengabur. Jika demikian halnya, hak atas tanah berupa hak individual itu kembali tertransformasi menjadi tanah bebas. Jika imajinasi logis dilanjutkan ke arah zaman rajaraja pribumi beberapa abad lalu. Maka pada saat itu, konsep-konsep yang lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang berada dalam suasana peradatan atau adat kerajaan. Para raja pribumi berikut kelengkapan perangkatnya bukan penggarap-penggarap tanah sehingga tidak perlu secara ipso facto menjadi penguasa atas lahan pertanahan. Para 29 Dipinjam dari istilah yang biasa digunakan Wignyosoebroto, 1996. Tanah Negara: Tanah Adat yang dinasionalisasi. Jakarta: Elsam. 123 penguasa pribumi hanyalah penguasa atas suatu kawasan yuridiksi tertentu berikut penduduk yang berada dan bermukim di dalam lingkungan kawasan dimaksud. Dengan demikian, pada masa raja-raja pribumi tidak ada perubahan konsep penguasaan hak atas tanah. Keadaan ini dapat dirasakan keberadaannya, terutama di Jawa, sementara di luar Jawa tentu suasana hukum adat masih menyelimuti secara utuh. Pada masa pemerintahan kolonial, kedatangan pemerintah kolonial di Bumi Nusantara ini menjadikan suasana hukum adat mengalami perubahan. Perubahanperubahan tak mungkin terhindarkan lagi mengingat terjadi intensitas hubungan sosial antara masyarakat tempatan dan pemerintah kolonial. Perubahan dimaksud terjadi menyusul praktik-praktik hubungan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di bawah konsepsi-konsepsi Budaya Negeri Barat. Konsekuensinya, tentu, ia akan menafikkan konsep-konsep hukum adat yang dalam hal pertanahan telah dinyatakan secara ipso facto, sementara konsep Barat mendalilkan ipso jure. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Hindia Belanda yang memang sejak awal berkonsep Barat, hak gubernur (gubernemen) atas tanah pun didalilkan secara ipso jure dari penguasa pribumi lewat kontrak panjang (lange contracten) atau pernyataan pendek (korte verklaringen).30 30 Ini merupakan perjanjian-perjanjian politik antara raja-raja pribumi dengan Pemerintah Hindia Belanda, seperti (1) kontrak panjang Kesunanan Solo, Kesultanan Jogjakarta dan Deli, (2) pernyataan 124 Bertitik tolak dari premis tersebut, praktik-praktik penguasaan ipso jure dicarikan alat pembenar yuridis berupa Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) pada tahun 1870 (Ind. Stb. 1870 No. 55). Undang-Undang Agraria dimaksud berisi suatu keputusan bahwa tanahtanah di Jawa dan Madura, yang di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya hak eigendom merupakan domein negara. Pada perkembangan waktu kemudian, sebuah ordonansi yang dikenal dengan sebutan Algemene Domeinverklaring, yang dimuat dalam Agrarische Wet 1875 (Ind. Stb. 1875 No. 1991) diterbitkan. Di sana, dinyatakan undang-undang agraria sebelumnya berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Faktor yuridis ini menjadi faktor penentu peniadaan kemutlakan hak-hak adat masyarakat adat dan warganya atas tanahtanah lahan warisan nenek moyangnya secara ipso facto. Namun demikian, aspek penggabungan antara dua konsep di atas, juga dapat dibaca ketika hak-hak rakyat masih memperoleh pengakuan de facto sebagai bezitrech yang dapat dimohonkan pengakuan de jure sebagai eigendom. Namun warga masyarakat tempatan tetap saja beranggapan bahwa apabila keberadaannya di atas tanahtanah lahan yang mereka tempati telah berlangsung lama, pendek Kesultanan Goa, Bone, dan sebagainya. Selanjutnya lihat Muslimin, 1984. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung: Alumni, hal. 14 125 turun-temurun, sudah cukup kuat untuk membuktikan haknya atas tanah yang telah ditempati dan dimanfaatkan secara nyata itu. Kebijakan kolonial mengenai pengakuan hak atas rakyat yang dikonsepkan sebagai bezitrecht kian lama kian sulit diteruskan. Terutama, pada era pascakolonial tatkala pembangunan nasional menuntut pemanfaatan tanah-tanah lahan secara nasional untuk tujuan produktif. Sementara itu keberadaan lahan pertanahan kian langka dan tidak sebanding dengan akselerasi tingkat kepadatan penduduk. Perebutan tanah menjadi tak terelakkan lagi dan dalam proses perebutan itu pembenaran-pembenaran hak berdasarkan hukum sangat menentukan. Satu hal yang menjadi persoalan kemudian, menurut Wignyosoebroto, adalah hukum manakah yang harus dijadikan dasar? Hukum nasional (state law) baik yang dibangun berdasarkan atas sumber-sumber formil dan materiil nusantara tetap saja dipahami oleh jutaan orang yang bermukim di pedalaman sebagai hukum asing, yang tak mudah dikenali, dimengerti, dan dipahami, apalagi dihayati oleh warga masyarakat tempatan untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan tanah. Dalam persoalan hak atas tanah misalnya, saat itu sertifikat hak atas tanah tidak mudah dimengerti karena fakta penguasaan atas tanah yang telah berlangsung turun-temurun dari generasi satu ke generasi berikutnya tiba-tiba dikesampingkan begitu saja oleh titeltitel yang termuat dalam dokumen berupa sertifikat hak atas tanah. 126 Hasil penelitian tentang eksistensi dan pola penguasaan tanah adat di Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa tanah adat masyarakat tempatan masih ada dikuasai secara ipso facto, sekaligus menunjukkan dinamika penguasaan hak atas tanah beragam.31 Dua hal menarik yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah fenomena model sertifikasi hak atas tanah. Di Sumatera Barat misalnya, terdapat dua jenis model sertifikat, pertama, sertifikat hak atas tanah dengan model kepemilikan bersama. Model dimaksud berupa selembar sertifikat hak atas tanah dimana di atas lembaran dimaksud tertulis nama seorang kepala kaum atau suku sebagai penanggung jawab komunitasnya dan di balik lembaran sertifikat dimaksud tertulis sejumlah nama anggota kaum suku dimaksud. Kedua, terdapat pandangan bahwa setiap bidang tanah yang disertifikatkan dianggap sebagai sebagai tanah “liar”.32 Alasannya, tanah yang sudah disertifikatkan akan menjadi bebas bagi pemiliknya untuk dijual, disewa, digadai, dan sejenisnya, yang akhirnya tidak diketahui oleh kepala nagari, suku, bahkan kepala kaum sekalipun. 31 Hal ini dapat dilihat dalam Buku Laporan Hasil Penelitian Tanah Adat yang dilakukan oleh Puslitbang Unika Atmajaya, Jakarta bekerjasama dengan BPN Pusat. 32 “Liar” merupakan pandangan pimpinan masyakarat bahwa setiap bidang tanah yang disertifikatkan diartikan sebagai dapat diberlakukan sesuai kehendak penuh seseorang yang namanya tertera di atas lembaran sertifikat dimaksud. 127 Dalam konsep lokal, memang hubungan antara warga masyarakat tempatan dengan tanah tidak diukur dengan selembar kertas yang disebut sertifikat, tetapi riwayat penggarapan tanah secara turun temurun, pengakuan tokohtokoh adat, dan kesaksian orang lain menjadi faktor penentu. Oleh sebab itu, jumlah warga masyarakat yang tidak mengerti dan memahami fungsi sertifikat hak atas tanah mungkin tak terhitung jumlahnya mengingat pembuktian dan bukti ada ditangan yang secara budaya memang telah berjalan secara turun temurun. Apalagi bagi mereka yang tak pernah merasa berkepentingan untuk membebaskan diri dari alam pemikiran hukum adat, tentu dalam peta kognisinya akan berkukuh bulat untuk tetap merujuk kepada struktur normatif lama. Kini, permasalahannya adalah sebagian tanah ulayat telah menjadi tanah negara dan sebagian lain telah mejadi tanah perorangan. Ini berarti terjadi transformasi tanah ulayat menjadi tanah negara melalui interaksi antara hukum negara (Agrarian Law) dan hukum lokal (Adat Law) yang hubungannya dibuktikan dengan selembar sertifikat mulai dari sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah perorangan atau individual dengan sertifikat Hak Milik (HM). Sertifikat-sertifikat tersebut telah menjadi dokumen penting dalam realitas sosial sehari-hari yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi. Ini berarti ada kecenderungan kuat sebagian orang tidak mempercayai 128 kepemilikan hak atas suatu tanah tanpa dibuktikan dengan selembar dokumen tertulis.33 Dalam konteks tanah kepemilikan atas sebidang tanah dengan dokumen selembar sertifikat hak atas tanah. Jika sertifikat hak atas tanah tersebut dianggap sebagai bukan produk sosial budaya lokal dan dipandang sebagai liar atau asing sebagaimana pandangan di atas, maka kini muncul pertanyaan penting, mengapa harus sertifikat dan apa makna di balik sertifikasi hak atas tanah. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, di bawah ini disampaikan lebih dahulu konsep-konsep filosofis34 yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan makna apa yang terdapat di balik sertifikasi hak atas tanah. Pertama, globalisme. Globalisme sebagai suatu konsep filosofis dapat menunjuk kepada suatu proses penyebaran sesuatu ke seluruh penjuru dunia yang dikerjakan oleh suatu kekuatan tertentu. Kekuatan dimaksud mengerjakan suatu proses yang membawa serta warga masyarakat di seluruh penjuru dunia untuk menerima peradaban baru, tidak saja dalam bidang teknologi, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Dengan begitu ia 33 Sejajar dengan hal itu dalam kehidupan sehari-hari dapat dijumpai, misalnya, kepemilikan sepeda motor, mobil dengan dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibuktikan dengan selembar ijazah. 34 Konsep-konsep filosofis lebih ditekankan ketimbang konsep-konsep teknis atau operasional. Jika hal terakhir yang digunakan, tentu ketiga veriabel tersebut tidak akan memperlihatkan kesamaan, tetapi yang terlihat justru perbedaan-perbedaan teknis. 129 berisi suatu proses penggantian filsafat yang telah dianut oleh masyarakat tempatan dengan filsafat luar yang terbawa serta dalam arus globalisasi. Kedua, individualisme. Individualisme sebagai konsep filosofis menggerakkan masyarakat di seluruh dunia untuk menerima sebuah proses menuju kemajuan materiil dengan sebuah taruhan beresiko tinggi yang tak dapat terbagi kepada orang lain. Artinya, secara substansial, ada kekuatan yang mengglobalkan suatu ide beserta hasilhasilnya ke dalam kehidupan materi semua umat manusia.35 Ketiga, hedonisme36. Hedonisme dimaksud diartikan sebagai faham pencapaian kekayaan, kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Artinya, petualangan kearah perbaikan kehidupan manusia dilakukan dengan tujuan menjadikan hidup mereka serba berkecukupan materi. Fanatisme perjuangan demikian melahirkan sebuah pandangan bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah mencari kehidupan 35 Pada dasarnya, ide materi sudah ada di mana-mana. Hanya pelaksanaannya tampak semakin menguat ketika para petualang Eropa Barat berupaya mencari dan menemukan negeri-negeri di luar Eropa dengan maksud menguasai dan mengambil kekayaannya. Petualangan itu sendiri, secara historis, diawali sejak abad Ke XIV dan di dalam perjalanan petualangan ke benua Afrika, Asia, Australia, hingga ditemukannya benua Amerika oleh Columbus pada abad XV. 36 Ini merupakan salah satu filasafat hidup yang dianut dalam kekuatan global dari 4 (empat) kekuatan lainnya, yaitu individualisme, sekularisme, dan hedonisme itu sendiri. Filsafat pelaksanaanyapun berlainan, yatu rasional ekonomis (tepa guna), rasional teknis (engineering), sportif, bersaing, perhitungan logis kausal dalam menghadapi persoalan nyata. Selanjutnya lihat Koesnoe, 1997. Hukum Adat. Surabaya: Ubhara Press, hal. 137-138. 130 bergelimang materi. Faham yang menekankan materi demikian ini biasa disebut materialisme (materialism), suatu faham yang memacu mereka untuk berjuang keras untuk memperoleh harta kekayaan dalam jumlah sebanyakbanyaknya.37 Keempat, konsep interaksi antarhukum. Menurut pandangan Moores (1987), jika hukum negara dan hukum lokal berinteraksi di dalam lokal sosial sama (one sosial field) diduga akan melahirkan empat kemungkinan. Kemungkinan dimaksud diasumsikan sebagai integrasi (integrate) yaitu penggabungan sebagian hukum negara dan hukum lokal, inkoorporasi (incoorporate) yaitu penggabungan sebagian hukum negara ke dalam hukum adat atau sebaliknya, konflik (conflict) yang tidak terjadi penggabungan sama sekali mengingat hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan, dan menghindar (avoidance) yaitu salah satu hukum menghindari kebelakukan hukum yang lain. Dengan konsep-konsep filosofis dan perspektif pluralisme hukum tersebut diharapkan dapat menjelaskan apa makna yang ada di balik sertifikasi hak atas tanah. Ketika orang mencari kehidupan dunia lebih baik dari sebelumnya, upaya itu dibenarkan oleh sebuah faham hedonisme. Pemahaman ini dapat ditelusuri ke belakang dengan merujuk pada perspektif filosofi orang Barat yang 37 Istilah yang biasa digunakan Wignyosoebroto, 1996. Tanah Negara: Tanah Adat yang dinasionalisasi. Jakarta: Elsam. 131 menjelaskan bahwa menyusul benua Amerika ditemukan oleh Columbus pada abad ke XV, orang Eropa Barat datang ke benua baru tersebut untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya. Di dunia Barat, alat untuk mencapai maksud tersebut dengan rekayasa (engineering), penguasaan teknologi desain di berbagai bidang dan lini menjadi impian. Apa yang terlihat, ternyata sebagian impian mewujud menjadi kenyataan, sebagaimana tampak pada bangsa Amerika dan Eropa saat ini. Dalam pencapaian (achievement) impian-impian tadi memunculkan suasana keindividualismean, dalam suasana seperti ini persaingan ketat menjadi unsur penentu sehingga siapa saja yang berhasil dalam persaingan baik secara orang perseorangan maupun kolektif, ia menjadi kaya, kekayaan menjadikan kuat, kekuatan membawa kekuasaan. Inilah sebagian yang dikehendaki hedonisme ala orang Barat. Namun dibalik kesuksesan itu, ada suatu hal yang perlu dicatat bahwa itu semua telah memunculkan rasa khawatir, was-was, cemas, dan gelisah terhadap kekayaan materiil, kejayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ketenaran yang telah diperoleh akan terancam berkurang, hilang, bahkan punah baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Berkaitan dengan ini, dalam hedonisme ala orang Barat, pilihan keamanan (security) menjadi faktor penentu dalam upaya menjaga keutuhan apa yang telah diperoleh dan mengamankan praktik realisasi faham-faham yang dimaksud di kemudian hari. Artinya, faktor keamanan menjadi fokus berikutnya, upaya penciptaan alat mesin 132 berteknologi canggih, modern, efektif, dan efisien untuk menjaga, mengamankan apa yang telah digapai segera diwujudkan. Semua ini telah dihasilkan dan kini terus menerus dikembangmajukan, yang intinya adalah untuk menggapai dan mengamankan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang telah diperoleh secara berkesinambungan. Hedonisme telah merembes, menerabas, dan merebak ke seluruh bagian negara dan masyarakat di dunia, kecuali sebagian masyarakat lokal pedalaman, sehingga rasa khawatir tidak kaya, tidak tenar, tidak berkuasa semakin terasa di benak sebagian warga masyarakat luas, baik kalangan profesi, pejabat negara, pegawai negara maupun yang bukan ketiganya, hampir di semua lapisan dan lini kehidupan sosial. Hal ini semakin berlebihan ketika sumber daya yang selama ini dinikmati semakin terbatas, masa depan tidak begitu jelas, serta persaingan untuk memperoleh hal sama semakin ketat. Dengan kata lain, rasa kekhawatiran terhadap apa yang telah diperoleh dengan bekerja keras akan tidak diakui merupakan ancaman kerangkeng ketidaknyamanan, ketidakamanan. Jika demikian halnya, tentu, hal ini merupakan kekhawatiran umum yang melanda di setiap kognisi orang dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Hanya persoalannya adalah bagaimana mengatasi rasa kekhawatiran terhadap ancaman kerangkeng-kerangkeng ketidakamanan dan ketidaknyamanan itu seharusnya dilakukan. 133 Tindakan mengamankan terhadap apa yang telah diperoleh yang sesuai dengan pilar keadilan hukum, pilar keadilan sosiologis, dan filosofis, tentu ke depan menjadi aman adalah sertifikasi hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah demikian ini dapat diinterpretasi sebagai bukti upaya seseorang atau sekelompok orang yang mengamankan terhadap apa telah diperoleh dengan cara-cara yang sesuai undang-undang tertulis sehingga apa yang dilakukan dengan pensertifikatan lambat laun akan menjadi “kebudayaan”.38 Jika demikian halnya, maka sertifikasi dapat diinterpretasi sebagai sebuah fenomena hedonism. Artinya, ada tesis bahwa (1) di balik sertifikasi hak atas tanah terdapat individualisme dan hedonisme yang dibawa oleh globalisme. (2) Sertifikasi dipandang sebagai tindakan pengaman terhadap apa yang diperoleh dengan kerja keras di masa kini dan masa berikutnya. Kemudian, asumsi kedua dan ketiga, tentu tidak dapat dijelaskan mengingat sebagian warga yang tidak bersedia atau menolak (conflict) dan sebagian lain menghindar (avoid) dari kemungkinan interaksi hukum lokal berinteraksi dengan hukum negara. 38 Kebudayaan diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang diyakini benar oleh sebagian besar warga masyarakat dan dijadikan pedoman bertingkah laku. Selanjutnya, lihat juga Spradley, 1972 dalam Culture and Cognition: Rules, Map, and Plans. San Fransisco: Chandler Publishing Company dan Suparlan, 1999 “Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya” dalam Antropologi. Thn. XXIII. No. 59: 8-9 134 Hal ini juga dapat dibaca ketika sebagian warga masyarakat tetap bersikukuh mempertahankan tanah ulayat dari upaya “pentransformasian” status hukum tanah ulayat menjadi tanah negara. Dengan munculnya fenomena integrasi dan inkoorporasi39di daerah-daerah lainya di seluruh nusantara, tentu, akan berimplikasi pada pembangunan hukum nasional, dimana hukum nasional yang dihasilkan merupakan produk dialogis vertikal antara hukum lokal dan hukum negara, dan sekaligus dialogis horisontal antar-hukum lokal sehingga lewat proses seperti ini akan ikut serta mendorong penguatan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Di balik sertifikat itu juga lahir asumsi inkoorporasi yaitu hukum adat menerima sebagian unsur hukum negara dan hukum negara menerima sebagian hukum lokal (adat). Artinya, sebagian warga masyarakat tempatan bersedia menerima unsur hukum negara dan hukum negara pun “tidak keberatan” untuk mengakomodasi keinginan warga. Hal ini dapat ditafsir pada sebuah fenomena sertifikasi hak 39 Bandingkan dengan konsep neo-tradisionalism norm. Konsep ini menjelaskan bahwa di satu pihak dapat terjadi hukum yang diterapkan dan digunakan dipandang sebagai hukum negara, namun secara materiil hukum tersebut terdapat unsur hukum adat, agama maupun daerah. Di pihak lain, hukum yang dimaksud terdapat pula hukum yang diterapkan dan digunakan oleh warga masyarakat dipandang sebagai hukum adat, hukum agama ataupun hukum daerah, namun secara materiil terkandung pula unsur hukum negara. Selanjutnya lihat Saptomo (1995) dalam Berjenjang Naik Bertangga Turun: Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Masyarakat Minangkabau. Tesis 2 .Jakarta: PPs UI 135 atas tanah ulayat di mana di halaman depan sertifikat tertulis satu nama penghulu suku atau mamak kaum atas sebidang tanah, sementara di balik sertifikat dimaksud tertuang sejumlah nama-nama kemenakan penghulu suku sebagai pemilik bersama. Praktik pentransformasian status sebagian tanah adat menjadi tanah negara, misal ekstremnya, berlangsung pada bidang tanah yang kini dimiliki orang Jawa di lokasi transmigrasi sebelum menjadi milik perorangan. Tentu, sebelumnya tanah dimaksud berstatus tanah ulayat, kemudian dinegarakan menjadi tanah negara. Akhirnya, ia menjadi tanah milik perorangan dengan bukti selembar sertifikat hak atas tanah. 136 BAB V SENGKETA DAN BUDAYA HUKUM V.1 Pegertian Sengketa Untuk mengawali tulisan tentang sengketa ini, lebih dahulu ditampilkan konsep konflik atau sengketa yang sering digunakan dalam literatur ilmu-ilmu sosial. Dikalangan ahli sosiologi lebih terfokus pada konsep konflik. Sementara dikalangan penekun antropologi hukum cenderung memfokuskan pada konsep sengketa.40 Berkaitan dengan kedua konsep ini, penulis mengacu kepada pengertian konsep sengketa yang dikemukakan oleh Nader dan Todd. Dalam menguraikan pengertian tentang proses bersengketa (disputing process), mereka membagi tahap-tahapan bergulirnya suatu perselisihan dalam arena penyelesaian sengketa. Tahapan tersebut meliputi: tahap pra–konflik (pre-conflict) atau tahap keluhan, tahap konflik (conflict) dan akhirnya tahap sengketa (dispute). Pemilahan secara konseptual tersebut di atas mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengklasifikasian terhadap sejumlah aktivitas pihak-pihak yang terlibat sengketa. Mereka itu adalah yang terlibat langsung sebagai aktor sengketa maupun pihak ke-tiga 40 Nader and Todd, 1978. The Disputing Process: Law in Ten Societies. New: Colombia Press, hal. 4 137 sebagai mediator sengketa, sehingga mempermudah pula untuk mengelaborasikan tahapan bersengketa. Tahap Pra–Konflik. Pengertian tahapan ini adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang atau kelompok orang merasakan bahwa haknya dilanggar atau diberlakukan tidak adil. Pelanggaran terhadap suatu hak tersebut mengakibatkan perasaan tidak adil sehingga lahir keluhan, yang mengandung suatu potensi untuk konfrontasi. Jika perasaan demikian tidak dikonfrontasikan kepada pihak yang dianggap memperlakukan tidak adil atau telah dikonfrontasikan, namun pihak lain tidak menanggapi atau menghindari atau tidak mereaksi terhadap keluhan, tantangan, yang diajukan kepadanya, maka tahapan ini juga disebut tahapan monadic. 41 Tahap Konflik. Tahapan ini pada umumnya merupakan kelanjutan dari tahap pre-konflik. Tahapan ini terjadi apabila pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya, atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhannya, dan memperoleh tanggapan dari pihak lawan. Dengan ditanggapinya keluhan tersebut menjadikan kedua pihak sadar mengenai adanya suatu perselisihan diantara mereka, karena ada perbedaan intepretasi atau persepsi mengenai sesuatu hal. Ciri tahapan 41 Nader dan Todd, 1978. Op Cit. hal. 14 138 konflik ini, sebagaimana dikutip oleh Ihromi, adalah diadik atau kedua belah pihak telah saling berhadapan.42 Tahap Sengketa. Dalam tulisan ini penulis menggunakan pengertian konsep sengketa yang berasal dari rumusan Gulliver, sebagaimana dikutip oleh Nader dan Todd, bahwa sengketa hanya terjadi jika pihak yang mempunyai keluhan atau seseorang atas namanya telah meningkatkan peselisihan dari tingkat perdebatan ke tingkat arena publik. Dengan bergeraknya suatu peristiwa dari tahap para-konflik atau tahap konflik ke arah sengketa yang melibatkan pihak ke tiga, baik atas kemauannya sendiri atau tidak atas kemauannya, maka keterlibatan pihak ketiga ini pada jenjang tertentu bertindak sebagai pihak yang netral. Namun pada jenjang-jenjang tertentu ikut pula mewarnai tuntutan pihak-pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa tanah, ada baiknya diacu pada studi Comaroff dan Robert43 yang membahas mengenai penyelesaian sengketa pada masyarakat Tsawana di Afrika. Comaroff dan Roberts menyebutkan bahwa klasifikasi keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa tidak selalu sama. Penulis mengutip upaya pengklasifikasian tentang keterlibatan pihak ketiga sebagaimana telah dilakukan oleh Comaroff: Pihak ketiga yang berkedudukan sebagai orang 42 43 Ihromi, 1993, Op.Cit. hal. 209 Lihat Comaroff dan Robert, Op.Cit., hal. 1981. 139 yang dipercaya (confidant) untuk memberikan penjelasanpenjelasan yang berkaitan dengan obyek yang disengketakan (perceptual clarification). Pihak ketiga berkedudukan sebagai orang yang berperan aktif memberi suatu penyelesaian sengketa (to seek a settlement) dan selama itu bertindak netral. Ketiga, keterlibatan pihak ketiga sebagai orang yang diminta untuk mendukung dalam menyusun strategi (strategy purpose) bagi kemenangan pihak tertentu. V.2 Budaya Penyelesaian Sengketa Hingga kini mungkin tidak sedikit orang kurang mengetahui jawaban atas pertanyaan, mengapa dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada perselisihan, konflik, sengketa, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar tatanan susila, tatanan sosial, dan tatanan-tatanan sejenis lainnya, bahkan perbuatan sejenis lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan. Kualitas perselisihan hampir selalu menyesuaikan perkembangan masyarakat itu sendiri, sebuah perkembangan yang dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan; pertama, tahapan masyarakat sederhana; kedua, masyarakat kompleks, dan ketiga, masyarakat multikompleks. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat satu dengan yang lain dimaksud tidak lepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk keluhan, konflik maupun sengketa, yang 140 diakibatkan oleh serangkaian interaksi sosial antarwarga masyarakat itu sendiri. Namun, pengelolaan persoalan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat satu dengan yang lain berbeda tingkat dan corak cara penyelesaiannya. Pengamatan terhadap masyarakat sangat sederhana, seperti masyarakat pedesaan umumnya, di mana hubungan sosial antarorang perseorangan atau antar kelompok orang tidak begitu kompleks menunjukkan bahwa dalam hubungan sosial antara orang satu dengan yang lain jarang sekali ada perselisihan, meskipun terjadi perselisihan penyelesaianpun sederhana, seperti mengusir, menjauhi, sindiran, semonan, dan menghindar. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana demikian ini tidak serta merta dilakukan secara formal dan melibatkan aturan-aturan tertulis. Ini berbeda dengan kehidupan masyarakat sangat kompleks, di mana perselisihan semakin rumit, bahkan secara statistik angka tindak kejahatan cenderung bertambah, kualitas meningkat sebagai akibat logis dari kondisi seperti ini pengelolaan penyelesaiannya menjadi rumit. Dalam masyarakat yang disebut terakhir ini, meskipun infrastruktur ditingkatkan, bahkan suprastruktur seperti lembaga ekstra yudisial diterbitkan, persoalanpersoalan hukumpun tetap bermunculan. Dalam kasuskasus sengketa yang diselesaikan melalui peradilan formal, ternyata perkara semakin hari semakin menumpuk di atas meja pengadilan, penyelesaiannya pun membutuhkan 141 waktu lama, birokrasi berkepanjangan dan sebagian keputusan akhir tidak memuaskan banyak pihak. Orang tidak mudah menghapus citra bahwa dalam proses peradilan formal umumnya memiliki kelemahan44. Kelemahan yang dimaksud adalah (1) proses peradilan berlangsung atas dasar permusuhan atau pertikaian antarpihak yang bersengketa mengingat pihak satu diposisikan secara berseberangan dengan pihak lain. Proses peradilan demikian tentu menghasilkan bentuk penyelesaian yang menempatkan antarpihak secara tersubordinasi, dimana pihak satu sebagai pemenang dan sebaliknya pihak lain sebagai pihak yang kalah. (2) Proses peradilan berjalan atas dasar rel hukum formal, statis, kaku dan baku. Akibat keformalan demikian ini menjadikan para pihak yang bersengketa, biasanya lewat pengacara sering mempersoalkan jenjang-jenjang hukum prosedural hingga memakan waktu panjang. Kondisi demikian menyebabkan persoalan inti menjadi terabaikan atau setidak-tidaknya tertunda akibat melarutkan diri dalam persoalan prosedural formal. (3) Proses peradilan sering tidak mampu menangkap nilai-nilai sosial budaya yang muncul dalam 44 Di Indonesia, ada empat bentuk badan peradilan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Terakhir ini telah diganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 142 kasus sengketa akibat para hakim merujuk pada aturanaturan baku. (4) Proses peradilan berjenjang-jenjang dari institusi pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan institusi kasasi. Jika yang terakhir inipun putusan hukum dirasakan tidak puas, maka yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali dengan catatan ditemukan bukti baru (novum). Sebagai alternatif pemecahannya, penyelesaian konflik atau sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat langsung untuk mengatur proses dan menemukan keputusannya sendiri dengan atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini merupakan penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Pilihan Penyelesaian Sengketa-PPS (Alternatif Dispute ResolutianADR). Penyelesaian demikian ini dapat ditemukan dalam (1) masyarakat guyub (gemeinschaft) serta belum mempunyai peradilan negara yang merata dan melembaga. Dalam masyarakat guyub dimaksud, PPS dipandang sebagai kelanjutan dari praktik kebiasaan atau adat. (2) Masyarakat Gessellschaft, PPS banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih.45 Para pihak, umumnya merasa puas terhadap keputusan yang dihasilkan dengan cara ini karena perselisihan tidak menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini, 45 Hal ini pernah disinggung pula oleh Falakh dalam Desentralisasi Penyelesaian Sengketa Hukum” dalam KOMPAS. Jakarta. 1995. 143 para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, konsensus menuju keharmonisan sehingga cara-cara demikian dapat mempersingkat durasi waktu, menekan jumlah biaya serta dapat langsung dilaksanakan. Latar belakang ini mungkin untuk mendasari banyak orang mengharapkan agar pihak-pihak yang sedang berselisih menyelesaikan sengketa kembali ke jalur budaya masyarakat setempat. Apakah itu perselisihan yang diakibatkan oleh adanya perikatan utang-piutang, warisan, perceraian, pencemaran lingkungan, dan perselisihanperselisihan sumber daya alam sejenis. Budaya yang dimaksud adalah cara pengelolaan perselisihan yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan yang telah menjadi kebiasaan atau adat. Dalam konteks masyarakat guyub, biasanya orang menggunakan pola penyelesaian perselisihan dengan berembug, mediasi, negosiasi, musyawarah–mufakat menuju perdamaian. Perdamaian dalam praktik peradilan formal biasa disebut dengan terminologi dading. Artinya, lembaga dading dalam peradilan formal masih diberi ruang untuk dipratikkan pada kasus-kasus perdata dan selalu dianjurkan oleh hakim, bahkan telah menjadi langkah pertama yang ditempuh oleh seorang hakim apabila menyelesaikan suatu perselisihan perdata kepada pihakpihak yang bersengketa. Namun praktik dading dalam peradilan formal seperti ini dirasakan kurang berjalan efektif karena umumnya seorang hakim tidak berperan langsung untuk membimbing 144 persengketaan untuk menemukan proses penyelesaian dan vonisnya sendiri, sebagaimana kebiasaan yang terjadi di negara Singapura. Di negara disebut terakhir ini seorang hakim biasa menjadi mediator, negosiator, arbitrator yang secara aktif membimbing proses penyelesaian perselisihan dan mereka sekaligus menemukan vonisnya. Jadi, institusi pilihan penyelesaian sengketa sebenarnya telah terjadi di negara-negara maju, di Amerika Serikat misalnya, disebut Alternatif Dispute Resolution, di Singapura disebut Court Dispute Resolution, di Cina disebut People’s Mediation and Administration Mediation. Dalam konteks Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menghendaki perselisihan diselesaikan lewat mediasi atau negosiasi sebelum dibawa ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) atau Pusat (P4P). Lebih-lebih masyarakat Indonesia yang umumnya masih bersifat guyub, maka tulisan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan budaya Indonesia menjadi penting diruai kembali. V.3 Penyelesaian Sengketa Dalam Budaya Indonesia Substansi Pilihan Penyelesaian Sengketa adalah upaya kongkrit para pihak yang berselisih untuk menemukan hukumnya sendiri, maka upaya penyelesaian perselisihan atau sengketa yang mengujung pada perdamaian telah lama dikenal bengsa indonesia, bahkan upaya–upaya tersebut telah melembaga kedalam apa yang disebut peradilan desa (doorpsjustice). Pada masa silam peradilan desa ini ada di 145 seluruh wilayah Indonesia, dan pada dasarnya menjalankan kewenangan selain sebagai pengadilan pidana, juga hukum perdata. Apabila proses penyelesaian sengketa diukur dengan praktik penyelesaian sengketa pada masa yang ada sekarang, maka proses penyelesaian sengketa dimasa silam tampak sederhana. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa bentuk masyarakat saat itu merupakan masyarakat sederhana. Kesederhanaan proses penyelesaian sengketa dimaksud berhubungan dengan tingkat pengetahuan warga desa pada umumnya, sehingga bentuk dan cara menjalankan proses tampak sederhana pula. Namun demikian penyelesaian sengketa pada peradilan desa tersebut pada azasnya menjalankan pendidikan hukum yang didasarkan kepada suatu prinsip, bahwa hukum diciptakan tidak untuk dilanggar, akan tetapi untuk dihormati dan ditaati, agar tercapai perdamaian (dading). Pada saat itu, orang yang melanggar hukum dipandang sebagai melanggar ketertiban umum. Peradilan desa sebagai Disciplinaire Rechtspraak (Pengadilan Ketertiban), yang diselenggarakan bukan untuk membalas dendam atau membalas kesalahan tetapi untuk membangun perdamaian. Namun dalam perkembangannya, di mana kebijakankebijakan Pemerintah Kolonial mulai mempengaruhi kebijakan–kebijakan pemerintah desa. Akibatnya, mutu dan nilai pengadilan desa mulai mengalami perubahan, ini tampak ketika pada 1925–1927 diadakan penyelidikan 146 tentang perlu tidaknya dihidupkan kembali pengadilan ketertiban desa. Pada saat itu pamong praja terpaksa menyatakan kesangsiannya atas kemurnian jiwa pengadilan. Meskipun ada sarjana lain yang berpendapat bahwa pengadilan desa perlu dihidupkan kembali, namun harus didasarkan pada undang–undang yang sekaligus mengatur bidang–bidang pidana, perdata, bentuk materinya dan batas–batas kekuasaan pengadilan desa. Pada saat itu, dasar hukum yang melandasi berlakunya pengadilan desa adalah Pasal 25 ayat Reglement yang menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara penduduk desa di lapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka kepala desa dengan bantuan dewan panitia mengadili perselisihan itu dengan jalan mendamaikan. Pada umumnya, orang-orang yang berselisih menyetujui usulan kepala desanya. Dan sudah tentu pada kasus dan orang tertentu ada pengecualiannya, misalnya jika ada orang tidak setuju usulan kepala desanya maka perkara dimajukan kepada wedana. Pejabat ini sekali lagi akan mencoba untuk mendamaikan pihak–pihak yang berselisihan. Bilamana pada tahap ini tidak ada penyelesaian, maka wedana juga berkewajiban memajukan perkara ini kepada pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk itu sekaligus memberi petunjuk tentang tata cara pengajuannya. Apa yang dilakukan pengadilan desa pada saat itu adalah hukum dimaknai sebagai alat pendidikan dan pengadilan ketertiban yang diletakan diatas tangan warga 147 masyarakat bersangkutan sendiri. Pengadilan ketertiban itu mempunyai nilai tinggi dalam kenegaraan dan kemasyarakatan. Kondisi seperti ini ditanggapi positif oleh pemerintah kolonial. Bahkan, pemerintah kolonial pada waktu itu memberi dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Bijblaad 1246. Ini dilakukan karena substansi penyelesaian sengketa lewat pengadilan desa telah lahir, tumbuh, dan berkembang di berbagai daerah. Di setiap daerah ini memiliki tema–tema budaya yang pada dasarnya antara satu sama lain substansinya sama yaitu menjunjung tinggi budaya musyawarah. Sebagaimana yang disebut di depan bahwa pengadilan desa itu tidak ada di Jawa dan Madura saja, melainkan di kepulauan Indonesia hampir ada pengadilan desa. Misalnya, di Aceh. Di sana ada pengadilan yang sifatnya sebagai dewan pemisah, kekuasaan itu diberikan kepada kepala desa. Jika ada pihak yang berselisihan maka kepala desa bertindak dengan cara mendamaikan pihak–pihak yang berselisih. Di tanah Gayo, pangadilan desa ditaruh di atas tanggung jawab Raja-Raja. Pengadilan desa ditaruh di tanah Batak kekuasaan itu ada ditangan kepala pusat kota atau Raja padusunan. Di Tapanuli Selatan, kekuasaan itu diberikan kepada oleh Kepala Kuria, tetapi sejak tahun 1916 oleh Kepala Distrik. Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, di sana ada lembaga Kerapatan Adat Nagari. Bekerjanya lembaga perdamaian desa ini disemangati oleh budaya musyawarah mufakat. Dalam musyawarah tersebut pihak-pihak yang 148 berselisih dengan suka rela melunakkan sikap dan pendapat kakunya dan pada saat yang sama ia sekaligus menerima dan memahami pendapat pihak lain. Di Sumatera Selatan, pengadilan itu dipegang oleh kepala suku dengan bantuan pinitua. Dalam masyarakat kepulauan Ambon dan Banda yang yang memegang kekuasaan pengadilan adalah kepala negeri. Dalam masyarakat pulau Kei pengadilan di rumah kepala negeri. Sebagaimana pernah disebut di depan, secara substansial budaya Indonesia mengandung tema–tema budaya. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek musyawarah dalam masyarakat Minangkabau, nglurug tanpa bala, menang tanpo ngasorake (win–win solution) dalam masyarakat Jawa, harmoni jagad gede dan jagad cilik dalam masyarakat Bali untuk penyelesaian sengketa di luar peradilan formal. Tema-tema budaya demikian itu sebenarnya ada dan seringkali digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di daerah-daerah di seluruh Nusantara Indonesia, khususnya dalam lingkup yang kecil, dimana dalam lingkup kecil tersebut identitas tatap muka lebih menonjol dibanding masyakarat kompleks. Meskipun demikian, karakter masyarakat satu dengan yang lain berbeda sehingga intensitas penggunaan juga berbeda. Misalnya, tema-tema budaya, sangat menonjol dalam masyarakat Jawa, Bali, dan masyarakat Indonesia Bagian Timur dibanding di daerah-daerah lain. 149 Di dalam dua masyarakat pertama, pada dasarnya sengketa yang terjadi diselesaikan dengan penghindaran. Ini ditujukan untuk menjaga serta memelihara ketertiban dan memperkecil sifat emosional, sekaligus memperkecil setiap permusuhan, yang semuanya dipandang akan dapat mengganggu praktik-praktik hubungan sosial di masa mendatang. Pada masyarakat Jawa umumnya, ada kebiasaan dalam membuat keputusan yang dilakukan dalam rapat desa atau dahulu disebut sebagai dewan perapat atau prapat. Di dalam dewan yang warganya terdiri dari orang-orang perwakilan dari dukuh-dukuh, mereka berembug untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Pertemuanpertemuan dalam prapat untuk memutuskan usulan-usulan yang muncul dalam setiap prapat. Prapat memutuskan bukan berdasarkan suara mayoritas, tetapi keseluruhan usulan-usulan yang muncul dalam setiap rapat ditampung, dan pada prapat yang sekian kalinya akan diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat.46 Dalam masyarakat pedesaan hingga kini semangat musyawarah seperti ini masih hidup dan dalam pengamatan menunjukkan bahwa musyawarah memang dipandang lebih nalar dan para pihak tidak bertahan pada pendapatnya sendiri. Dalam konteks penyelesaian sengketa, win-win 46 Koentjaraningrat, 1990. Sejarah Antropologi II. Jakarta: UI Press 150 solution dalam musyawarah tidak ada pihak yang menjadi pihak yang dikalahkan atau dimenangkan. Di berbagai daerah lain masih ada lembaga perdamaian yang memiliki kewenangan berbagai bidang, seperti perdata, pidana, pelanggaran ketertiban sosial dan umum. Sudah tentu, dalam konteks sekarang bidang-bidang ini menjadi kewenangan lembaga sepanjang warga yang berkepentingan langsung mengadukannya kepada lembaga perdamaian ini. Dalam kegiatannya, di lembaga ini ada kepala adat atau kepala suku ikut bersama warganya serta akif memelihara, menjaga, menjalankan hukum adat berdasarkan niali-nilai masyarakat setempat di mana mereka menjadi pimpinan informalnya. Dalam menjalankan tugasnya, ia tidak menjadikan kewenangan dimaksud dijalankan sendirian, tetapi sebagai satu kesatuan dewan warga yang bekerja secara fungsional seperti dewan sedemikian rupa sehingga kepala adat dalam menjalankan tugasnya selalu bermusyawarah dengan warga-warga lain dalam dewan itu. Satu hal yang amat penting dalam penyelesaian sengketa, yaitu kepala adat berupaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Apabila terjadi perselisihan diantara warga dalam satu kelompok atau antarkelompok, maka kepala adat berkedudukan sebagai hakim perdamaian, yang menjalankan tugasnya berdasarkan hukum adat dan aktif menghimbau agar mereka bersedia memilih pilihan penyelesaian alternatif untuk memulihkan keadaan seperti sebelumnya. 151 Semua itu dilakukan untuk mencapai rasa keadilan. Penyelesaian sengketa di atas menunjukkan bahwa jika terjadi sengketa diantara warga masyarakat, mereka cenderung menyerahkan kapada pihak adat untuk menyelesaikan berdasarkan hukum adat secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di luar forum peradilan formal telah lama ada dan hingga kini masih hidup dalam budaya masyarakat Indonesia. V.4 Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Perdamaian, dalam lingkungan penstudi hukum perdata biasa disebut dading. Dalam salah satu kamus hukum yang disusun oleh Puspa.47 Dading diartikan sebagai perdamaian di sidang pengadilan atau perdamaian di hadapan sidang pengadilan. Upaya itu ditunjukkan oleh isi perjanjian yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak tergugat dan penggugat/tertuduh dan penuduh di mana kedua belah pihak melepaskan hak sementara untuk menghindari suatu perkara dihadapan sidang pengadilan. Dading biasanya dilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus perdata. Ini tampak dalam pasal 1888 KUH Perdata. Perdamaian dalam praktik peradilan formal biasa disebut dengan terminologi dading itu dipratikkan dan selalu dianjurkan oleh hakim, bahkan telah menjadi langkah pertama yang ditempuh seorang hakim apabila 47 Lihat Puspa, Y.P., 1987. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu 152 menyelesaikan suatu perselisihan perdata kepada pihakpihak yang bersengketa. Namun praktik dading dalam peradilan formal seperti ini dirasakan kurang berjalan efektif karena umumnya seorang hakim tidak berperan langsung untuk membimbing persengketaan untuk menemukan proses penyelesaian dan vonisnya sendiri. Namun demikian, ke depan diharapkan dengan dasar Perma 2 Tahun 2003 yang mengatur tentang peran hakim sebagai mediator akan lahir perdamaian baik kuantitas maupun kualitasnya. Meskipun demikian pengaturan lembaga dading dalam KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) yang berasal dari negeri Belanda ini menjadi dasar-dasar yuridis dalam penyelesaian sengketa dengan tujuan perdamaian. Apabiladasar-dasar yuridis tersebut diamati, maka dading akan terjadi apabila beberapa unsur penting dipenuhi; pertama, unsur kecenderungan perkara yang melibatkan dua belah pihak yang sedang berselisih dapat diteruskan menjadi perkara di pengadilan. Kedua, kedua belah pihak menghendaki agar perkara yang sedang berjalan segera diakhiri secara musyawarah mufakat. Untuk mencapai tujuan yang disebut terakhir itu kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjianperjanjian tertulis. Setelah perjanjian dimengerti dan dipahami, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui pihak ketiga. Dengan cara seperti ini, isi perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali. Artinya, kedua belah pihak harus 153 aktif menemukan hukumnya sendiri, memutuskan sendiri dan mengikatkan dirinya sendiri terhadap isi perjanjian. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak-pihak yang membuat seperti ini sebenarnya telah dikenal di negara di mana KUH Perdata berasal, yaitu negeri Belanda. Di negeri Belanda sana dikenal lembaga advis yang mengikat (binded advise). Sementara Indonesia sebagai negara koloni negeri Belanda telah pula mengadopsi KUH Perdata tersebut, sebuah kitab hukum yang beberapa pasalnya mengatur tentang lembaga dading. Dalam perkembangannya, lembaga dading terkesan kurang dikembangkan, meskipun telah tercantum dalam pasal 1831 sampai dengan 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III. Oleh sebab itu, sebenarnya penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah dengan tujuan damai telah ada dan diatur lengkap, namun dalam praktik-praktik proses peradilan di Indonesia terkesan kurang dikembangkan. Bahkan, dalam pasal 1858 KUH Perdata misalnya, disebutkan bahwa antara pihak-pihak dading mempunyai kekuatan tertinggi dan terakhir (Kracht van gewijste in het hooghste ressort). Secara yuridis formal, uraian di atas menunjukkan bahwa KUH Perdata masih berlaku sebagai hukum positif dan dipakai sebagai pedoman oleh praktisi hukum dalam menangani perkara yang diserahkan kepadanya. Oleh sebab itu, sekali lagi lembaga dading yang telah ada dan diatur dalam KUH Perdata sebagaimana disebut di atas bahwa hal itu dapat dipandang sebagai landasan hukum 154 diselenggarakannya upaya pengembangan lembaga dading lebih lanjut sebagai salah satu penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks “peradilan yang lebih luas, dading bukan saja berarti upaya perdamaian di sidang pengadilan, tetapi telah mempunyai masa sosio-yuridis, bahwa penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan tujuan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan. 155 BAB VI PENEGAKAN HUKUM DENGAN KEARIFAN LOKAL VI.1 Penegakan Hukum Sebelum dijelaskan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud Penegakan Hukum dengan Kearifan Lokal, perlu dikemukakan paradigma konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia harus didasarkan pada hukum. Makna ini telah tersirat secara eksplisit dalam Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan Hukum. Namun hukum yang berupa peraturan perundang-undangan itu sendiri tidak bermakna apa-apa jika tidak dapat diwujudkan oleh institusi pelaksananya. Pada konteks ini pula, institusi pelaksananya adalah Kepolisian, Kejaksaaan, Kehakiman, dan terakhir Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana. Dalam praktik penegakan hukum, keseluruhan pelaksana hukum itu telah mengalami perjalanan panjang yang pada setiap era pemerintahan diwarnai pendekatan yang berbeda sehingga efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri juga berbeda. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah pendekatan formal dari atas ke bawah (topdown approach). Dalam konteks penegakan hukum oleh Institusi Kepolisian pada era militeristik, ternyata, digunakan pendekatan yang sering diikuti kepentingan penguasa. 156 Selain itu, perilaku militeristik yang diperlihatkan Polisi cukup menonjol sehingga hasilnya sebuah ketidakefektifan dalam penegakan hukum. Pendekatan formal, rigid, dan kaku demikian ini menjadikan masyarakat sebagai obyek, bukan sebagai subyek aktif yang berpotensi ikut serta dalam proses penegakan hukum secara dini (preventive). Tentu, kondisi demikian ini semakin menjauhkan masyarakat dari peran pembantu tugas-tugas kepolisian yang semestinya. Padahal sebagaimana terjadi di negaranegara maju seperti Inggris, peran polisi tidak saja sebagai penegak hokum, tetapi juga pemberdaya masyarakat. Mereka mengetahui bahwa masyarakat sebenarnya telah mengetahui mengapa terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum, juga tahu apa yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran hukum. Demikian pula masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat komunal seperti Indonesia amat berpotensi untuk mendukung kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kearifan lokal dimaksud merupakan kekuatankekuatan sosial yang lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi pranata masyarakat setempat. Dengan pengertian demikian ini, penegakan hukum, misalnya penegakan hukum oleh polisi, maka akan mengenal beberapa pendekatan yang melibatkan kekuatan atau potensi masyarakat setempat dimana hukum ditegakkan. Namun potensi-potensi masyarakat dimaksud belum ditangkap sepenuhnya oleh Kepolisian Negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, politik hukum yang menyusul Gerakan 157 Reformasi yang terjadi dan dimulai tahun 1998 merupakan momentum besar bagi keseluruhan institusi hukum Indonesia untuk merubah paradigma penegakan hukum dari atas ke bawah (top down) menjadi bawah ke atas (buttom up). Hingga sekarang, pendekatan yang disebut pertama masih belum berubah secara signifikan, memang dalam beberapa hal bergeser ke pendekatan buttom up dan namun belum maksimal menggunakan potensi-potensi masyarakat untuk diikutsertakan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum masih dipandang sebagai tanggung jawab negara, sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, mestinya selain pemerintah, peran masyarakat juga diikutsertakan dalam perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan lainnya, di bawah ini dikemukakan empat pendekatan kepolisian yang digunakan dalam rangka penegakan hukum. Secara konstitusional, perjalanan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan negara Indonesia didasarkan pada hukum. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). Salah satu konsekuensi yuridis logis dari negara hukum dimaksud adalah supremasi 158 hukum. Artinya, penegakan hukum harus dilaksanakan.48 Dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum dimaksud, di satu sisi, dapat berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun di sisi lain, dapat juga terjadi tidak sesuai dengan peraturan perundangan, bahkan terjadi penyimpangan hukum. Jika terjadi yang terakhir, maka pilihan utamanya adalah penegakan hukum harus menjadi kenyataan. Satu hal amat penting berkenaan dengan wacana penegakan hukum ini adalah ketika tujuan hukum dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dan peran hukum itu dimainkan oleh penegak hukum. Dalam arti demikian ini, peran penegak hukum menjadi penting untuk dianalisis terutama penegakan hukum dalam arena peradilan yang dilakukan oleh hakim, jaksa, polisi, pengacara yang lazim disebut Catur Wangsa.49 Dengan kata lain, dalam konteks penegakan hukum oleh kepolisian misalnya, tentu penegakan hukum dikaitkan dengan 48 Ciri-ciri negara hukum ada pembagian kekuasaan dalam negara, hak azasi manusia diakui dalam konstitusi dan peraturan perundangundangan, dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan, peradilan bebas, merdeka tidak memihak, kedudukan hukum sama bagi semua warga. Lihat UUD 45, P4, GBHN dan Tap MPR 1993 49 Istilah ini dapat diartikan sebagai empat pilar penegak hukum yang akan bekerjasama menciptakan citra peradilan yang berwibawa, bebas, jujur, terbuka, cepat, dan murah. 159 perspektif kemasyarakatan, mengingat hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan sebaliknya.50 Dalam konteks kemasyarakatan, ketika fakta menunjukkan bahwa Polisi tidak dapat bekerja maksimal tanpa masyarakat maka asumsinya Polisi Sipil merupakan pilihan. Polisi Indonesia sendiri terdiri atas empat jenis, yaitu Polisi Sipil (Civilian Police), Polisi Militer (Military Police), Polisi Rahasia (Secret Service), dan Polisi Tidur (Ramp) sebagaimana dikemukakan oleh Chaeruddin Ismail.51 Salah satu jenis polisi yang diharapkan untuk diterapkan kedalam masyarakat Indonesia terutama dalam Era Reformasi dewasa ini adalah Polisi Sipil. Dalam perkembangannya, selain Polisi Sipil juga ada pendekatan lain yaitu Polisi Budaya. Peluang keberadaan Polisi Budaya ini dapat diinterpretasi pada pasal sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 57 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 50 Bertitik tolak dari pengertian ini, timbul kajian perubahan hukum dan perubahan sosial, sekaligus hubungan antarkeduanya. 51 Lihat pada Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian. Surabaya: laksbang Mediatama, hal. 273 160 (3) Pemerintah wajib memberikan jamin keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Point pertama dan kedua menjadi penting dalam era sekarang ini. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, tertarik untuk menjawab pertanyaan konsep penegakan hukum apakah yang harus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan agar masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penegakan hukum. Dalam upaya menjawab masalah utama tersebut ada beberapa konsep tentang apa yang seharusnya dilakukan institusi kepolisian telah diajukan oleh beberapa sarjana, namun konsep dimaksud masih digerakkan oleh suatu paradigma topdown meskipun substansi konsep sudah diwarnai nilai-nilai kemasyarakatan, seperti Polisi Sipil, Community Policing atau biasa disebut Polisi Masyarakat (Polmas). Ada pendekatan yang dipandang betul-betul buttom up. Artinya, ’polisi’ yang lahir dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri, bahkan kelahirannya sebelum Negara Republik Indonesia sendiri berdiri sehingga Polisi dimaksud pada setiap satuan masyarakat Indonesia berbeda-beda sebutannya. Untuk itu, dalam kesempatan ini diperkenalkan Polisi Budaya yang berasal dari masyarakat Indonesia, seperti Polisi Budaya Masyarakat Minangkabau, Bali, dan Madura. Keberadaan Polisi Budaya itu amat perlu diperdayakan untuk membantu tugas Kepolisian Negara 161 Indonesia. Namun untuk memperjelas perbedaannya, dikemukakan pendekatan penegakan hukum oleh hakim dengan konsep menggali nilai hukum yang hidup dan oleh Polisi dengan konsep-konsep Polisi Sipil, Community Policing, dan baru Polisi Budaya yang dimaksud. VI.2 Menggali Nilai dan Budaya Hukum Subjudul ini terinspirasi secara normatif oleh makna Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman Pasal (27) sebagaimana diperbaiki Pasal 28 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya diganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 (1), bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”52 Oleh sebab itu, tulisan ini akan lebih menitikberatkan tugas-tugas hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dibanding penegak hukum lainnya. Kini pertanyaannya, mengapa hakim mempunyai kewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara normatif jawabannya merujuk pada pengertian Pasal 22 Algemeene Bepalingen (AB) disebutkan : “Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157. 162 undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, idak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat ituntut untuk dihukum karena menolak mengadili.” Maknanya adalah hakim memang wajib memeriksa dan mengadili perkara perdata/perdata adat yang diajukan kepadanya. Prinsip demikian ini yang dipegang teguh oleh hakim sehingga hakim dianggap tahu hukumnya atas kasus hukum kongkrit yang diajukan kepadanya. Prinsip ini di dalam ajaran asas biasa dikenal dengan asas Ius Curia Novit yang biasa diartikan hakim diangap tahu hukum. Namun dalam kenyataannya, amat dimungkinkan bahwa hukum yang terdiri seperangkat aturan normatif itu tidak lengkap atau bahwa hukum belum mengatur. Jika hal ini yang terjadi, maka apa yang harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus hukum kongkrit. Dalam mengadili perkara-perkara hukum kongkrit dimaksud, maka hakim akan melakukan tiga langkah alternatif pendekatan, sebagai berikut: 1. Pendekatan legalistik, jika dalam kasus hukum kongkrit yang dihadapi hukumnya atau undang-undangnya sudah ada dan jelas, maka hakim secara preskriptif tinggal menerapkan saja hukum yang dimaksud; 2. Dalam kasus hukum kongkrit yang hukumnya tidak atau kurang jelas, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan cara menafsirkan hukum atau undang-undang yang masih samar-samar dimaksud melalui metode penafsiran yang sudah lazim dalam kajian ilmu hukum; 163 3. Dalam kasus hukum kongkrit yang hukumnya belum ada atau undang-undang belum mengatur, maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nomor dua dan tiga diatas, dilandasai asumsi bahwa dalam kenyataan yang ada Undang-Undang tidak ada yang sempurna dan lengkap untuk mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Dalam upaya menegakkan keadilan dan kebenaran hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).53 Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menemukan hukum dan bahkan menciptakan hukum (judge made law), terutama terhadap kasus-kasus hukum kongkrit yang hukumnya masih samar-samar atau bahkan yang sama sekali belum ada hukumnnya, tetapi telah masuk ke pengadilan. Jika nilai hukum yang dimaksud telah ditemukan dan dirumuskan sedemikian rupa maka selanjutnya dituangkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan putusan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diadilinya. Nilai hukum itu diposisikan sebagai sebagai hukum (premis mayor) untuk menyelesaikan suatu kasus 53 Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Lihat Sudikno Martokusumo, Op.Cit., hal. 32 164 hukum kongkrit atau pokok perkara (premis minor) dan dituangkan dalam amar putusan sebagai konklusi.54 Dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus hukum kongkrit yang belum ada aturan hukumnya, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan dipelihara baik di tengah-tengah masyarakat dan dijadikan pedoman bagi sebagian besar warga masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup itu antara lain: nilai-nilai ajaran agama, nilai-nilai adat istiadat yang masih terpelihara baik, budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat, keadan sosial dan ekonomi masyarakat. Hakim juga mempunyai kewenangan untuk menyimpang selain dari hukum yang hidup dan ketentuan hukum tertulis. Untuk melakukan hal itu, tentu jika aturan hukum yang tertulis telah usang dan ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut Contra Legem. Hakim dalam menggunakan lembaga Contra Legem, harus mencukupi pertimbangan-pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Keputusan hakim yang berisikan suatu pertimbanganpertimbangan sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pasal 22 AB, yang kemudian menjadi dasar putusan hakim lainnya di kemudian hari untuk mengadili 54 Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hal. 62 165 perkara yang memiliki unsur-unsur yang sama dan selanjutnya putusan hakim tersebut menjadi sumber hukum di pengadilan. Putusan hakim demikian disebut "Hukum Yurisprudensi". Tujuannya adalah untuk menghindari "Disparitas" putusan hakim dalam perkara yang sama.55 Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah dimana hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat bersifat lokal, berbeda daerah atau masyarakat yang satu dengan lainnya. Pepatah mengatakan “lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang”. Ada sifat-sifat spesifik dari nilai-nilai yang dianut dan hidup di tengah masyarakat. Sebagian hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri datang dari berbagai budaya yang melatar belakangi kehidupannya, kemudian bertugas selaku hakim di daerah yang sebelumnya hukum adatnya belum mereka kenal secara mendalam, mereka harus memutus perkara berdasarkan perintah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009. Mencermati pandangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, misalnya yang menyatakan bahwa putusan hakim kurang atau tidak mencerminkan rasa keadilan 55 Ahmad Kamil dkk, 2004. Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media, hal. 8-9 166 masyarakat. Pandangan demikian ini memang masih sering terdengar, bahkan pendapat sejenis tidak dapat diabaikan mengingat yang menjadi salah satu sasaran dari putusan hakim secara umum adalah masyarakat, terutama pencari keadilan. Memang persoalan keadilan masyarakat seperti yang diuraikan di atas merupakan permasalahan signifikan mengingat ada ekspetasi masyarakat luas terpenuhinya rasa keadilan bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan (the last fortress) yang seharusnya memiliki wibawa namun putusan yang dijatuhkan dirasakan oleh masyarakat justru tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat demikian itu juga sesuai dengan teori-teori hukum yang baik sebagaimana yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, Frederick Karl von Savigny, Sir Henry Maine, Nathan Roscoe Pound, Leopold Pospisil. Di bawah ini dikemukakan kriteria hukum yang baik menurut pandangan sarjana-sarjana tersebut sebagai berikut. Misalnya, Leopold Pospisil (1971) dalam bukunya The Anthropological of Law, mengemukakan bahwa hukum yang baik, materinya harus mencerminkan perilaku pengguna hukum dan memiliki empat elemen yaitu: adanya wewenang, ciri universalitas, kewajiban, dan pemberlakuan sanksi. Dengan demikian, sumber hukum yang paling utama bukan berasal dari negara melainkan dari perilaku masyarakat dan hukum harus mampu mewadahi pluralisme masyarakat. 167 Demikian pula Frederick Karl von Savigny bahwa hukum yang baik harus bersumber dari adat-istiadat, kebiasaan, dan kemauan masyarakat yang diwujudkan melalui lembaga perwakilan sehingga hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak masyarakat dalam rangka memenuhi kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, Sir Henry Maine mengemukakan bahwa hukum senantiasa mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Jeremy Bentham pun mengatakan bahwa negara yang menggunakan banyak aturan yang dijalankan oleh pemerintahan konstitusional (polity), hukum yang dibangun harus mampu mewujudkan sistem aturan yang memiliki resiko paling sedikit terhadap kehidupan masyarakat.56 John Rawls yang mengembangkan pemikiran Jeremy Bentham tersebut, lebih jauh mengemukakan teori keadilan (theory of justice) bahwa tujuan hukum yang paling penting adalah mewujudkan dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Sementara sarjana lain, M. Scheltema sebagai disebutkan Azhary misalnya mengemukakan pandangannya bahwa hukum yang baik harus memenuhi empat unsur yaitu: kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan untuk rakyat. Dengan kata lain, bahwa hukum harus mampu memenuhi tuntutan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial masyarakat. 57 56 Barnes, J. 1984. The Complete Works of Aristotle. Princeton, NY.: Princeton University Press. 57 Azhari, 1995. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI-Press. 168 Hal ini sejalan pula dengan konsep negara kesejahteraan modern (modern welfare state) bahwa hukum harus mencerminkan kesejahteraan yang menjadi “hak” bagi setiap warga negara untuk memperolehnya dan negara/pemerintah harus menjamin hak tersebut. Tugas dan kewajiban negara/pemerintah tersebut tercermin dalam setiap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dengan demikian, kriteria hukum yang baik menurut Jeremy Bentham adalah: (i) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa; (ii) harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat; (iii) mengandung kepastian hukum. VI.3 Penegakan Hukum Polisi Sipil Setelah Reformasi Tahun 1998, gerakan Polisi Indonesia sudah berada pada garis yang benar, misalnya kebijakan memisahkan posisinya dari militer. Pemisahan polisi dari militer tentu bukan sekedar pisah secara struktural, tetapi juga harus secara budaya. Mungkin perubahan budaya akan membutuhkan waktu panjang sehingga sebelum sampai pada pemisahan sebagaimana yang diangan-angankan masyarakat masih terdapat praktik-praktik militeristik. Kesan ini bukan mengada-ada begitu saja mengingat polisi yang sekarang masih memegang posisi strategis tidak lain merupakan produk pendidikan militeristik. Namun setidak-tidaknya, secara konseptual telah ada kebijakan pemisahan polisi dari militer perlu disambut secara posistif. Untuk itu, makna pemisahan polisi dari militer tidak berhenti pada tataran struktural, tetapi mensipilkan watak Polisi menjadi agenda utama di masa-masa mendatang. 169 Namun Pensipilan Polisi sebagai pendekatan penegakan hukum yang dimaksud Satjipto Rahardjo (2007) adalah bagaimana Polisi berwatak sipil. Satjipto Rahardjo mengajukan setidaknya empat (4) langkah yang harus dilakukan Polisi. Empat langkah dimaksud adalah (1) mendekatkan pada masyarakat; (2) menjadikan akuntabel terhadap masyarakat; (3) menggantikan dari mengandalkan pada penghancuran dengan melayani dan menolong (4) peka dan melibatkan kepada urusan sipil dari warga negara, seperti membantu orang lemah, tidak tahu dan kebingungan, frustasi, pengangguran, sakit, lapar, dan putus asa. Kesemua ini merupakan upaya yang disajikan oleh Satjipto Rahardjo yang menurutnya merupakan pekerjaan besar dan berat. Meskipun sedemikian besar dan berat, kebijakan yang harus diterbitkan oleh segenap pimpinan di tingkat markas Besar tetap merupakan pilihan penting dan perlu dan ditunggu di masa mendatang. Menurut pandangan penulis, konsep Polisi Sipil memang ditujukan agar dalam penegakan hukum, tidak mengalami resistensi dari masyarakat dan masyarakat tidak menganggap bahwa Polisi itu bagian dari militer. Untuk itu, sebenarnya ada konsep lain lebih tajam dan kongkrit, selain aparat kepolisian merubah pada tataran perilaku dan juga pada tataran budaya atau ideologis, tetapi juga pada pembagian peran kepolisian secara rapih kepada institusi kemasyarakatan yang secara budaya telah lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarkat lokal setempat. Tentu, tidak pada semua tugas kepolisian yang berkenaan kejahatan dan 170 pelanggaran hukum, tetapi tugas-tugas terbatas kepolisian yang menyangkut kasus hukum tertentu dan pada saat bersamaan polisi berada di garis kedua (second line) Polisi Budaya. VI.4 Penegakan Hukum Community Policing. Ada konsep yang berasal dari negeri Inggris, yang biasa disebut Community Policing (CP). Konsep CP ini tergolong konsep modern yang menekankan bagaimana Polisi itu bergerak manjalankan tugas-tugasnya yang harus dipertanggungjawabkan. Konsep dimaksud menekankan pada pemecahan persoalan hukum yang muncul (problem oriented). Maksudnya, Polisi dalam menjalankan tugasnya menekankan lebih dahulu persoalan-persoalan yang mendasari polisi untuk bertindak, bukan berorientasi pada sifat menunggu (waiting oriented), yaitu polisi menunggu adanya laporan atau permintaan masyarakat bahwa ada sesuatu yang harus ditangani polisi. Pendekatan demikian, menjadikan Polisi tidak aktif tetapi menunggu adanya pelaporan masyarakat yang masuk ke redaksi polisi, baru kemudian dilakukan tindakan kepolisian. Berdasarkan atas kondisi demikian, maka konsep CP merupakan pendekatan kepolisian yang mendekatkan diri pada masyarakat dan warganya (the police to society). Di sini polisi dipandang lebih penting untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berdasarkan adanya kebutuhan masyarakat ketimbang kepada atasan berdasarkan permintaan target-target jumlah yang harus diselesaikan polisi dalam waktu tertentu. Dalam pengertian 171 demikian ini, kembali pada tugas utama kepolisian, yaitu, pertama, polisi sebagai institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (sosial orde) dengan tujuan agar tercapai suasana kehidupan aman, tenteram, dan damai. Kedua, polisi sebagai institusi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep ini berbeda dengan Polisi Sipil yang dibahas oleh Satjipto Rahardjo di atas karena konsep Polisi Sipil itu lebih pada perubahan simbol-simbol yang dipakai polisi dan dengan simbol itu diharapkan dapat merubah perilaku polisi dalam menghadapi pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum. Sementara itu, konsep Community Policing atau biasa diartikan Pemolisian Masyarakat menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat dibanding kepada atasan sebagai korpsnya. Ini memang penting karena keterlibatan masyarakat untuk berani segera melaporkan warga masyarakatnya yang telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya. Namun inti dari konsep ini juga efektifitas tugas kepolisian dalam penegakan hukum tidak jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dalam konsep Polisi Sipil. Secara formal, memang institusi Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri menerapkan model Community Policing. Konsep ini 172 memang lebih menekankan pemberdayaan masyarakat agar ikut serta menjadikan dirinya sebagai polisi masyarakat dalam pengertian bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya dengan melaporkan. Namun di sisi lain, masyarakat hanya ditekankan untuk ikut aktif melaporkan saja, bukan ikut serta mencegah langsung suatu tindakan kejahatan yang dilakukan warganya. Untuk itu, penulis mengajukan konsep berikutnya yang dipandang lebih dalam, yaitu pemberdayaan polisi budaya dimana masyarakat tidak saja berhenti pada melaporkan, tetapi juga ikut serta mengatasi langsung kepada sebagaian warganya yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu karena masyarakat sebagai tempat kelahiran warga, tempat hidup warga, dan tempat berkembangnya warga lebih mengetahaui daripada polisi itu sendiri. Artinya, masyarakat melalui tua-tua masyarakatnya atau tua-tua adatnya akan lebih mengetahui jawaban mengapa ada kejahatan, mengapa warganya melakukan kejahatan, sekaligus bagaimana melakukan tindakan pencegahannya. VI.5 Penegakan Hukum Polisi Budaya Penulis pada berbagai tempat dan kesempatan pernah menyampaikan penegakan hukum dengan konsep Polisi Budaya. Memang dalam rangka penegakan hukum baik sebagai penerap hukum maupun sebagai pelayan masyarakat telah ada pendekatan yang pernah dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia dalam era reformasi. 173 Misalnya saja, perubahan paradigma topdown ke bottom up, dari dilayani menjadi melayani, dari gaya militeristik ke sipil. Namun tampaknya, masyarakat luas menghendaki tidak saja berhenti upaya perubahan perilaku militeristik menjadi sipil sebagaimana dikenal dengan Polisi Sipil. Konsep Polisi Sipil ini lebih menekankan pada perubahan simbol-simbol yang dipakai polisi dan dengan simbol itu diharapkan dapat merubah perilaku polisi dalam melayani masyarakat, demikian pula dalam menghadapi pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum. Bukan pula berhenti pada Community Policing (CP) yang sekarang digalakkan. CP lebih menekankan pemberdayaan masyarakat agar ikut serta menjadikan dirinya sebagai polisi masyarakat dalam pengertian bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya dengan cara melaporkan. Konsep yang disebut terakhir membawa konsekuensi bahwa masyarakat hanya ditekankan untuk ikut aktif melaporkan saja, bukan ikut mencegah langsung suatu tindakan kejahatan yang dilakukan warganya. Sehubungan dengan itu, menurut pandangan penulis, pendekatan penegakan hukum oleh kepolisian dalam era reformasi kali ini dan sesuai dengan kondisi plural dan multikultural bangsa Indonesia tidak sekedar pendekatan kepolisian berupa Polisi Sipil dengan menampilkan polisi berdasi, tidak cukup polisi bersopan santun dengan menyampaikan salam hormat kepada warga, tetapi lebih mendasar lagi dari 174 itu, yaitu berperan sebagai pemberdaya potensi kepolisian yang secara sosial dan budaya memang telah lahir, hidup, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Masyarakat seluruh Nusantara ini sebenarnya telah memiliki institusi informal yang menjalankan tugas-tugas terbatas kepolisian Republik Indonesia. Ubi Societas Ubi Ius, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Makna dibalik ungkapan itu adalah sebagian peran institusi kepolisian formal yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan dapat dimainkan oleh warga masyarakat itu sendiri. Warga terpilih dengan atribut adat atau simbol-simbol masyarakat setempat tersebut disebut sebagai Polisi Budaya. Dengan demikian, Polisi Budaya yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah subsistem dari sistem pengamanan yang lahir, tumbuh, berkembang dan terinternalisasi kedalam masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya Masyarakat Adat Nusantara. Misalnya dalam konteks masyarakat Bali, polisi budaya dimaksud dimainkan oleh Pecalang (aktif), dan masih banyak bentuk lain dalam masyarakat nusantara Indonesia ini. Itulah yang penulis maksud sebagai polisi budaya yang keberadaannya memang jauh lebih akrab dengan warga masyarakat dan jauh lebih mengendap kedalam Masyarakat Adat Nusantara mengingat ia lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dimana mereka berada. Dengan demikian, Polisi Budaya merupakan salah satu solusi alternatif strategis bagi kebijakan Kepolisian 175 Republik Indonesia ke depan, sementara konsep Community Policing lebih pas diterapkan pada masyarakat perkotaan yang melibatkan peran Ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), dan RK (Rukun Kampung). Dengan model polisi budaya demikian ini pula, alasan rasio jumlah personil polisi kurang memadai yang selama disampaikan untuk membangun argumentasi bahwa polisi kurang efektif menjadi kurang relevan karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah kewibawaan (gezag). Sebaliknya dengan Polisi Budaya kewibawaan polisi dalam masyarakat akan meningkat karena masyarakat terlibat secara sosial dan cultural. Implikasinya, pemerintah pada tataran tertentu tidak perlu buru-buru menambah jumlah personil polisi, tetapi konsep dan strategi jitu yang membumi akan meningkatkan kualitas dan citra kepolisian Republik Indonesia. Kesimpulannya, bahwa dengan kebijakan Polisi Budaya, masyarakat tidak saja berhenti pada melaporkan, tetapi juga diberi ruang gerak untuk ikut melayani kebutuhan hukum serta mengatasi langsung secara budaya kepada sebagian warganya yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Selain itu, Polisi budaya dipandang lebih mengerti, mengetahui, dan lebih memahami daripada polisi formal negara itu sendiri dalam hal tempat kelahiran warga, tempat hidup warga, dan tempat berkembangnya warga, sekaligus jawaban tepat atas pertanyaan mengapa melakukan kejahatan, untuk apa hasil kejahatan dan bagaimana mencegah dan mengatasinya. 176 Tentu, terhadap masyarakat modern atau metropolitan dapat memanfaatkan ketua RT, RW, dan RK atau dalam masyarakat tradisional dapat memanfaatkan tua-tua masyarakatnya atau tua-tua adatnya karena mereka akan lebih mengetahui jawaban mengapa ada kejahatan, siapa melakukan kejahatan, sekaligus bagaimana melakukan tindakan pencegahannya. Sementara pada saat bersamaan, posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepolisian Formal lebih berperan sebagai pendamping Polisi Budaya yang akan bekerja bilamana polisi yang disebut pertama tidak mampu menghadapi kebutuhan hukum atau tindak kejahatan ringan atau pelanggaran hukum lainnya. VI.6 Penegakan Hukum Kearifan Lokal Nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dapat dijadikan isi hukum biasanya berupa kearifan-kearifan lokal masyarakat setempat.58 Menurut Assoc. Prof. Chatcharee Naritoom dari Kasetsart University, Thailand, Kearifan Lokal yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Local Wisdom, mempunyai pengertian sebagai berikut:59 Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the 58 Lihat juga Ade Saptomo, 2010. Hukum dan Kearifan Lokal. Jakarta: Grasindo Press. 59 (pimd.iwmi.org/Library/pdf/PPT%20-%206%20Indigeneous% 20Knowledge%20Systems.ppt ) 177 understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation. (Kearifan Lokal adalah pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya. Kearifan Lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terkait dengan situasi global). Indonesia juga mempunyai banyak kearifan lokal yang sampai saat ini masih tumbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia. Kearifan lokal tersebut telah lahir dan berkembang dari generasi ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan sendirinya. Kearifan tersebut telah terpelihara dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri dari mata hati manusia atau nurani orang yang tergabung dalam satuan sosial yang disebut masyarakat itu sendiri. Sebagai tempat kelahiran kearifan lokal yang semula jangkauan keberlakuannya adalah diantara mereka sendiri, namun sebagai nilai jangkauannya selain memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan masyarakat setempat, namun juga meluas ke desa-desa tetangga bahkan dunia luas mengingat isinya bebas ruang dan waktu. Dengan demikian, kearifan lokal yang sekarang ini dimengerti telah dapat menjangkau dan menjadi nasional bahkan menjadi bagian pedoman internasional (ius societas ius ubi). 178 Kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap ketauladanan lainnya mulai banyak terkikis di dalam lingkungan budaya masyarakat. Visi dan ideologi pembangunan yang lebih mendepankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan material dibandingkan dengan nilai spritualitas dan kearifan lokal disana-sini dipropagandakan oleh mesinmesin negara sehingga dalam banyak hal mempengaruhi cara berfikir dan bertindak sebagian besar warga masyarakat. Akibatnya, kini keberhasilan dan kesuksesan seorang tokoh masyarakat (elite) tidak lagi diukur sejauhmana peran sosialnya dan pengabdiannya di tengah masyarakat, tetapi kekayaan yang dimilikinya yang menjadi ukuran. Masyarakat pada saat ini sudah teracuni oleh modernisme budaya konsumtif, egois dan praktik menghalalkan segala cara. Nilai-nilai kemodernan itu menggeser kearifan budaya lokal komunitas. Benturan nilai itu tidak jarang membuat masyarakat pun mulai mengalami krisis identitas. Untuk itu, kearifan lokal merupakan sebuah tema yang diajukan untuk memulihkan peradaban dari krisis modernitas. Ia diunggulkan sebagai pengetahuan yang benar berhadapan dengan standar saintisme modern, yaitu semua pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan positivisme (suatu cara penyusunan pengetahuan melalui observasi gejala untuk mencari hukum-hukumnya). Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobyektifkan semua segi kehidupan alamiah 179 dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur nilai dan moralitas masyarakat. Sains modern menganggap unsur nilai dan moralitas sebagai unsur yang tidak relevan untuk memahami ilmu pengetahuan. Bagi sains, hanya fakta-fakta yang dapat diukur boleh dijadikan dasar penyusunan pengetahuan. Dalam keadaan demikian, kearifan lokal adalah suatu pandangan untuk mengembalikan nilai dan moralitas sebagai pokok pengetahuan. Yang khas dari pandangan kearifan lokal adalah nilai dan moralitas itu tidak dicari melalui logika deduksi etika (misalnya dengan memeriksa asumsi suatu ajaran tentang “yang baik” dan “yang buruk”, “larangan” dan “suruhan”), atau dengan mencarinya dalam realitas peristiwa yang sedang dihadapinya (misalnya, mengekstrak prinsip-prinsip moral suatu peristiwa)60. Kearifan Lokal Reba. Kata Reba merupakan sebuah kata bahasa daerah yang lahir dari kelompok masyarakat adat Ngadha yang berarti Pesta. Upacara reba biasanya dilakukan setahun sekali (biasanya dimulai akhir tahun sampai dengan awal tahun baru), bertepatan dengan waktu bagi masyarakat Ngadha untuk memulai bercocok tanam. Mengapa Reba, hanya ada satu jawaban atas pertanyaan diatas yakni, karena Reba memiliki nilai, dan nilai tersebut tidak bisa dihargakan dengan uang. Nilai-nilai yang ada dalam Reba dimaksud sebagai berikut: 60 http://www.ireyogya.org 180 1. Nilai Ketuhanan. Nilai ketuhanan tampak dari aktifitas masyarakat Ngadha dalam upacara Reba khususnya pada bagian tarian O Uwi, dimana dengan uwi kayu (singkong/ubi kayu yang dibawah dan sekali-sekali diangkat ke arah langit sedang menunjukan bahwa orang Ngadha percaya akan sesuatu yang Lebih Tinggi. Mensyukuri hasil usaha pertanian mereka dan mempersembahkan hasil terbaik mereka pada yang Lebih Tinggi. Uwi tersebut tidak dipersembahkan secara pribadi ke Bhaga (rumah kecil) masing-masing suku, tapi ketengah kampung secara bersama-sama. Hal ini sedang menceriterakan kepercayaan orang Ngadha terhadap satu Tuhan yang sama buat semua suku dan kuasa Tuhan tersebut berada di ketinggian yang hanya bisa dipuji dan dimohonkan melalui tarian dan nyanyian. 2. Nilai Penghormatan terhadap Leluhur. Nilai ini selain mengajarkan kepada masyarakat Ngadha sendiri tentang bagaimana harus menghormati leluhurnya, nilai ini bisa diasumsikan untuk mengajak semua agar menghormati orang tua atau menghormati orang yang lebih tua. Selain itu semua orang diajarkan untuk mendoakan mereka semua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. 3. Nilai Kekeluargaan dan Fraternitas. Nilai ini paling sering muncul dalam Reba. Nilai ini nampak jelas dari kebersamaan, canda tawa dan gandengan tangan (dalam tarian O Uwi) yang selalu muncul dalam setiap tahapan 181 upacara Reba. Reba menghadirkan seluruh keluarga dan mengingatkan mereka untuk selalu dan senantiasa makan dan berkumpul bersama. Reba pulalah yang mempertemukan dan memperkenalkan keluarga yang satu dengan keluarga yang lain serta dengan para tamu yang hadir. 4. Nilai Penghormatan terhadap Tamu. Ketika siapa saja yang lewat di jalan diundang dan diajak untuk makan dan menjadikan makanan sebagai milik bersama, sebenarnya masyarakat Ngadha sedang menunjukan bahwa tamu adalah raja dan mereka harus dijadikan sebagai bagian dari diri kita. 5. Nilai keteraturan hidup. Mencermati tulisan-tulisan yang ada dalam papan yang memagari Bhaga, sebenarnya terdapat kalender hidup bagi masyarakat Ngadha. Bahwa sudah diatur apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Ngadha di tiap-tiap hari hidupnya. Aturan tersebut harus ditaati karena akan berpengaruh pada terpenuhnya atau tidak terpenuhnya kebutuhan hidup manusia. Beberapa nilai yang coba penulis temukan dalam pesta adat orang Ngadha (Reba) seyogyanya dicermati oleh Pemerintah Daerah ataupun pengambil kebijakan lainnya agar dalam membuat suatu peraturan daerah ataupun dalam bentuk hukum yang lain yang membutuhkan peran serta masyarakat hendaknya senantiasa memperhatikan nilainilai tersebut. Upaya penggalian nilai-nilai yang lahir dari kearifan lokal masyarakat akan berdampak pada efektifitas 182 dan efisiensi pelayanan publik serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Ngada. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut diatas kedalam hukum akan dapat meningkatkan peran budaya hukum masyarakat Ngada. Dengan demikian tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bisa tercapai. Langkah yang tidak sulit lagi untuk dilalui adalah terwujudnya tujuan negara sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Kearifan Lokal Sasi. Sasi, menurut Kreikhof, sebagaimana ditulis dalam Buletin Triwulan Mariayo terbitan Yayasan Hualopu, Maluku tahun 1993, adalah pranata tradisional yang mengandung ketentuan, penataan, dan larangan masyarakat dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam. Dalam kata lain Sasi adalah ketentuan hukum adat untuk memuliakan alam, sehingga alam lingkungan tidak rusak. Ada sanksi dalam hukum adat ini, di samping sanksi moral atau lebih tepat dikatakan kutukan, ada sanksi material.61 Sedangkan Elissya Kiesya, mengatakan bahwa Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut. Karena peraturan-peraturan dalam pelaksanaan larangan ini juga menyangkut 61 http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&jd=LOMBA+TUL IS+YPHL+%3A+DARI+SEBUAH+SASI%2C 183 pengaturan hubungan manusia dengan alam dan antar manusia dalam wilayah yang dikenakan larangan tersebut, maka sasi, pada hakekatnya, juga merupakan suatu upaya untuk memelihara tata-krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumberdaya alam sekitar kepada seluruh warga/penduduk setempat.62 Sasi dilambangkan dengan Janur kuning yang dianyam dan dililitkan ke dalam sebuah tonggak kayu, ataupun janur kuning yang dililitkan di pohon apabila sasi itu bertujuan untuk memelihara pohon. Penerapan Sasi di Maluku ini sebagai salah satu pranata adat seharusnya dilestarikan keberadaannya dikarenakan mengandung muatan kearifan lokal dimana masyarakat berusaha menjaga ekosistem sumber alam dan pranata sosialnya dari aksi anarkis dan perusakan yang akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sendiri. Makna Sasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Eliza Kisya yang pernah menjadi Polisi Adat atau disebut Kewang, pelaksanaan penerapan Sasi ini menyangkut hubungan manusia dengan alam yang selaras dan harmonis. Selain itu Sasi juga merupakan pranata sosial dimana mengatur pula tata karma berkehidupan di masyarakat. 63 Keluhuran budaya Sasi ini tidak saja memiliki kekuatan religious magis, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang 62 http://www.kewang-haruku.org/sasi.htm http://www2.kompas.com/kompascetak/0310/20/teropong/628812.htm 184 63 tinggi. Artinya, hukum Sasi ini berada di dalam aura yang sangat humanis, mengangkat harkat dan martabat hidup manusia di dalam sinerginya dengan lingkungan sekitar dan juga dengan alam. Saat ini, Sasi dimaknai juga sebagai salah satu bentuk konservasi terhadap sumber daya alam sehingga tidak terjadi perusakan yang sewenang-wenang dan anarkis dari masyarakat terhadap alam dan menjaga keseimbangan alam sehingga kelangsungan sumber alam akan dapat dipertahankan yang akhirnya pula akan menguntungkan manusia itu sendiri dikarenakan tetap akan mendapat pasokan sumber alam yang tersedia dan terkelola dengan baik. Kearifan Lokal Mapalus. Mapalus adalah suatu bentuk kerja bersama (korporasi) dan bentuk kerja sama ini bukan hanya dari sejarah orang tua terdahulu akan tetapi sampai saat ini pun masih dipertahankan kebersamaan untuk suatu usaha atau patungan di bidang usaha, lazimnya disebut Mapalus. Dikota kota besar di Indonesia masih sangat kental Mapalus ini diselenggarakan oleh kaum atau etnis-etnis Minahasa seperti, kumpulan kawanua Paston, Tumtons, Kaston, Kaymston, Langowan dan lain-lain yang jumlahnya diperkirakan ada 54 organisasi yang berbentuk mapalus. Dengan adanya perkembangan kumpulan-kumpulan atau Mapalus tadi bisa diambil kesimpulan bahwa Etnis Minahasa tidak bisa lepas atau telah mendarah daging dari keberadaan kerja bersama tersebut. Dengan kesimpulan di 185 atas tadi bisa dilihat satu modal bagi Masyarakat Etnis Minahasa (kawanua) bahwa sebenarnya mereka mempunyai suatu potensi untuk dikembangkan bukan sebatas mapalus hanya berupa pertemuan dan mengumpulkan uang seadanya, tetapi dapat ditingkatkan pada usaha bersama (kooperasi). Namun demikian, untuk mengganti usaha-usaha yang dimodali dari daerah lain untuk mengolah Sumber Daya Alam yang berlimpah di Minahasa. Potensi kearifan ini sebenarnya positif mengingat masyarakat Minahasa tampaknya tidak bisa lepas dari kebersamaan atau Mapalus64. Dalam Mapalus, prinsip yang kebersamaan juga kelihatan ketika para wanita memikul cangkul, sekop dll. Apa yang dilakukan kaum wanita ini bukan berarti wanita mempunyai kedudukan lebih rendah akan tetapi kaum pria justru mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan rombongan Mapalus itu. Bahkan, mereka diharuskan membawa parang, tombak dan alat perang lainnya. Ketentuan organisasi Mapalus ini di jalankan dengan ketat sama dengan ketentuan adat lainnya. Pada waktu pembentukan pimpinan (dalam bahasa Tontemboan Kumeter), sesudah terpilih, pemimpin harus dicambuk oleh salah satu pimpinan di kampung dengan rotan, sambil mengucapkan "sebagaimana kerasnya aku mencambukmu begitu juga kerasnya kau harus mencambuk anggota yang malas dan pelanggar peraturan". Dan 64 http://www.kawanuausa.org. 186 ketentuan ini masih berlangsung sampai sekarang di beberapa daerah di Minahasa65. Arti Mapalus telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Pada mulanya dalam masyarakat kuno, Mapalus masih mempunyai arti yang sama dengan gotong royong karena tanah pertanian masih milik bersama. Akan tetapi karena perkembangan masyarakat, dimana milik perorangan telah tercipta dan menonjol, maka arti Mapalus berubah menjadi tolong menolong. Seperti sekarang setiap anggota Mapalus berhak untuk mendapat bantuan dari anggota anggota lain sebagai jasa karena dia sudah membantu anggota lain dalam melakukan pekerjaan baik di sawah, ladang, rumah dan lain-lain66. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Mapalus merupakan salah satu kegiatan masyarakat Minahasa sejak tahun 670, eksistensi kegiatan tersebut hingga sampai sekarang tetap berjalan seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat adat Minahasa. Pada masyarakat kuno, Mapalus diartikan sebagai gotong royong karena tanah pertanian masih milik bersama. Setiap desa yang ada mempunyai organisasi Mapalus yang beranggotakan lebih dari 5 orang, dan organisasi Mapalus yang ada di setiap desa lebih dari 3 organisasi. Secara bergiliran melakukan 65 66 http://www.bode-talumewo.blogspot.com. http://www.kawanuausa.org. 187 pekerjaan menggarap sawah, mendirikan rumah para keluarga baru, dan lain-lain. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai kearifan di dalam masyarakat adat Minahasa yang melakukan kegiatan Mapalus, adalah nilai kebersamaan, ketertiban, taat akan hukum, dan saling tolong menolong antar kerabat atau masyarakat adat Minahasa dalam melakukan pekerjaan. Meskipun dalam kutipan di atas, masih adanya kekerasan fisik dalam pemilihan pemimpin Mapalus, akan tetapi tidak mengurungkan tekad/dan niat masyarakat adat Minahasa untuk mengikuti kegiatan Mapalus. Meskipun dalam perkembangan masyarakat telah terjadi perubahan, akan tetapi sanksi tersebut sudah diganti berupa denda administrasi. Kearifan Lokal maja labo dahu. Kearifan lokal masyarakat Bima Nusa Tenggara Barat berupa ungkapanungkapan yang terpampang di berbagai ruas jalan utama menggambarkan bahwa masyarakat Bima memiliki ajaran hidup masyarakat seperti ajaran kerukunan, keamanan, persatuan, kerja keras, dan beribadah kepada Tuhan. Contoh ungkapan maja labo dahu (malu sama takut). Artinya, warga masyarakat Bima malu kepada sesame dan takut kepada Tuhan. Ungkapan itu masih terpampang dalam tulisan besar yang melintang di jalan Sultan Salahuddin, Bima. Selain itu, ungkapan lain terpajang di sekitar Kantor Wali Kota Bima yaitu Katuda pu rawi ma tedi, katedi pu rawi ma tada yang berarti tunjukkan kerja yang giat dan 188 jangan mengambil hak orang lain. Ungkapan-ungkapan itu sebenarnya telah ada dan menjadi pedoman hidup rakyat Bima sejak zaman kerajaan Sultan Muhammad Salahuddin. Bahkan pada zaman kemerdekaan Republik Indonesiapun masih menjadi pedoman masyarakat Bima dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga warga masyarakat Bima dikenal sebagai masyarakat sopan, tenang, hormat kepada pimpinan baik itu kepada camat, kepala kepolisian, komandan koramil. Selain itu, rakyat menjadi bagian keamanan yang menjaga kantor-kantor milik pemerintah. Namun, nilai-nilai itu menjadi kurang bermakna dan sedikit tergerus ketika kerusuhan demi kerusuhan terjadi, misalnya saja kerusuhan berupa pembakaran rumah jabatan Bupati Bima tahun 2006, pelemparan bom Molotov terhahap kantor KPU (komisi Pemilihan Umum) dan pembakaran Kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) salah satu partai besar tahun 2010, pembakaran Kantor Camat Lambu tahun 2011, dan Januari 2012 terjadi lagi pembakaran Kantor Bupati Bima dan Kantor KPU Bima.67 Untuk itu, revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan kearifan lokal menjadi sebuah kebutuhan. Untuk merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran nenek moyang masyarakat Bima dalam hukum positif Negara Repblik Indonesia akan bekerja maksimal jika mendapat legitimasi peraturan perundang67 KOMPAS, Ketika Kearifan Lokal Tergerus Kepentingan, 30 Januari 2012, hal. 1, 15. 189 undangan, setidak-tidaknya dituangkan kedalam bentuk peraturan daerah. Tentu upaya demikian itu, dapat dimulai dari kerjasama antara Dewan Adat Masyarakat setempat dengan lembaga masyarakat adat bentukan pemerintah di desa desa. Selanjtunya, butir-butir kearifan lokal dimaksud diangkat dan dikuatkan pada tataran yang lebih tinggi semisal peraturan daerah setempat. Dengan demikian, mengisi setiap peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dapat dimaksimalkan dengan mengisi kearifan-kearifan lokal dimaksud. Kearifan Lokal Sasi Nggama.68 Tradisi sasi nggama begitu lekat pada masyarakat nelayan di Kabupaten Kalimana,Papua Barat. Berakar dari kearifan lokal, tradisi ini terus berkembang. Kini,larangan mengambil hasil laut menjadi “benteng” yang menjaga eksploitasi Laut Kaimana. Meskipun pemegang hak ulayat laut di pesisir Kaimana bisa membuka sasi (larangan) pengambilan hasil laut atau kebun (sanggama) “kepemilikan” lautnya kapan pun,umumnya para tetua adat membuka sasi hanya pada Februari–April. Awal Maret lalu, di sebuah teluk di kawasan Desa Kayu Merah,pembukaan sasi diawali dengan ritual melepas sepiring pinang, sirih dan kapur ke laut. Warga berbondong-bondong berdatangan dari Desa Kayu 68 Irene Saswindaningrum, 2014. “Ketika Sasi Nggama Menjaga Kaimana” dalam KOMPAS, 5 April 2014, hal.1, 15. 190 Merah yang letaknya di pulau kecil sekitar 30 menit dengan kapal cepat dari teluk itu. Dipimpin tokoh adat setempat,ritual digelar sebagai simbol syukur. Suasana berlangsung khidmat. Setelah ritual kecil usai,suasana berubah menjadi meriah. Warga beramai-ramai terjun ke laut. Tua, muda, pria, wanita, bahkan anak-anak belasan tahun ikut menyelam tanpa alat bantuan sama sekali.Membuka sasi ibarat panen raya untuk lola (kerang), batu laga, dan teripang. Sebab saat itu lah warga merayakan kekayaan lautnya, memanen beragam biaota laut yang sebelumnya pantang diambil. “Bukan sasi banyak dinanti warga karena hasinya bisa besar. Padahal,satu laut hanya buka sasi 1-2 kali setahun,” kata Kepala Desa Kayu Merah Mohammad Jen Karafey (38) yang disapa om Jen. Kabupaten Kaimana merupakan kabupaten kepulauan di bagian kepala burung palau Papua. Dari sekitar 330 pulau, hanya 8 pulau besar yang berpengaruhi. Pulau-pulau kecil yang terbesar di antara bukti-bukti kasrt itu menjadi benteng alam Kaimana. Dari keganasan gelombang laut Arafuru dan tempat berlindung beragam satwa. Laut dengan sebaran pulau-pulau kecil itu begitu kaya akan keanekaragaman hayati dan biota laut. Di sinilah disebutkan juga “kerajaan ikan” yang terpemdam pada pesisir Kalimana. Berdasarkan data Pemerintah tahun 2009, laut Kaimana memiliki 995 spesies ikan, 486 jenis terumbu karang yang 16 diantaranya merupakan jenis baru, dan 28 jenis udang mantis. Udang dan kakap merah menjadi 191 komoditas andalan nelayan setempat, selain lola dan teripang. Ulayat laut dan Ketergantungan pada laut Buka sasi merupakan puncak ritual sasi nggama yang artinya larangan mengambil hasil laut atau kebun . Biota laut yang dikenali larangan untuk diambil adalah jenis-jenis yang berharga tinggi, termaksuk tanaman kebun dan hutan. Dengan buka sasi, artinya laut dibuka untuk diambil hasilnya. Tentu hanya lola dan teripang dewasa yang boleh diambil. Untuk bermacam jenis ikan,warga tak dilarang menangkap atau memancingnya. Mereka boleh kapan pun mengambilnya. Sasi berlangsung 1-2 pekan saja. Mariam Waria (36), warga Kayu Merah, mengaku dapat mengumpulkan Rp 5 juta-Rp 6 juta setiap kali buka sasi. Hasilnya dibagi dengan pemegang hak sasi atau “pemilik” laut ulayat tempat sasi itu diberlakukan “Orang yang punya sasi bisa dapat Rp 20 juta dari bagian hasil semua orang yang ikut buka sasi,” ujarnya. Bagi warga di pesisir Kaimana, sasi nggama sebenarnya bentuk kesadaran yang tinggi untuk ikut menjaga kelestarian laut. Ketergantungan pada kekayaan laut begitu erat karena 80 persen penduduk adalah nelayan. Om Jen mengutarakan, sasi nggama berlaku sebagai upaya mencegah biota-biota yang termasuk langkah dan mahal dieskplorasi berlebihan. Larangan selama beberapa bulan dimaksudkan untuk memberikan waktu biota berkembang biak. Dengan demikian, ketersediaannya cukup terjaga. “kalau ikan, teripang dan lola habis di laut, kami sendiri 192 yang akan susuah. Tak ada uang dan tak ada makanan,” ucap Om Jen. Sasi nggama juga dimaknai sebagai sumber pendapatan di masa penceklik, seperti saat ikan sulit didapatkan atau musim badai dan gelombang tinggi, terutama pada Februari-April ini. Pada Mei-November, nelayan biasanya mendapat tangkapan ikan cakalang, tenggiri, dan bubara. Adapun Januari saatnya musim kakap merah. Namun, diluar bulanbulan itu, bukan sasi menjadi andalan menangkap lola dan teripang. Untuk menjaga kelestarian laut, warga pesisir Kaimana yang tinggal di pulau-pulau kecil juga melarang pengambilan ikan dangan cara menggunakan pukat harimau, potas, dan bom ikan. Hala ini demi melindungi terumbu karang yang vital. Pada perkembangan sasi manggama mengikuti zaman. Dulu, pelanggar sasi didenda membayar dengan piring keramik atau barang berharga lainnya.Karena itu, warga takut melanggar karena sulit mendapatkan piring keramik. Selain itu, mereka juga meyakini bakal bernasib buruk. Saat ini sistem denda berubah dengan uang dalam jumlah besar. “Ada yang menerapkan denda Rp 10 juta sampai Rp 100 juta untuk satu lola yang diambil,” kata Tajudin (26), petugas penyuluh lapangan dari Dinas Kelautan dan perikanan Kaimana. Perubahan sistem denda dilakukan karena semakin banyak kapal dari luar Kaimana masuk ke laut ulayat dan melanggar sasi. Sekretaris Desa Adi Jaya Hussein Sanggei (37) menuturkan, beberapa kapal besar itu pernah ditangkap dan digiring ke desa karena 193 melanggar sasi. “Mereka ketahuan melanggar sasi. Denda besar dikenakan agar mereka tak melanggar lagi ,” ujar dia Kesadaran warga untuk tak merusak laut juga diterapkan pada larangan menggunakan pukat harimau dan potas. Sayangnya, aturan-aturan yang dipegang masyarakat Kaimana justru dilarang kapal-kapal asing. Bahkan, berkali-kali warga konflik dengan kru kapal-kapal perusahaan penengkapan ikan karena mereka beroprasi dikawasan sasi.” Itu merugikan nelayan karena tangkapan jadi berkurang. Apalagi pukat hari mau, semua isi laut hancur terkena. Ikan kecil dan terumbu karang juga rusak,” ujar Tajudin. Agar siapa pun bisa menysuri pesisir Kaimana seraya menikmati kekayaan hati dan biota lautnya, selayaknya sasi nggama terus diterapkan. VI.7 Konstitusionalitas Kearifan Lokal Konstitusionalitas Kearifan Lokal yang berisikan nilai-nilai yang ada dibalik ungkapan dimaksud perlu diperjelas mengingat Negara Indonesia menganut selain paham Hukum Positivisme juga terdapat pengakuan dalam konstitusi, di bawah ini penjelasan berbagai tatarannya. VI.7.1 Tataran Filosofis Ungkapan filosofis yang cukup familiar dalam pendengaran masyarakat Indonesia, satu diantaranya adalah Semboyan Bhineka Tunggal Ika. Ungkapan tersebut terpampang melengkung pada sehelai "pita" yang dicengkram erat oleh kedua kaki Burung Garuda sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga mudah dijumpai mengingat ia tidak saja terpampang di ruangan-ruangan 194 kantor lembaga Negara tetapi juga kantor-kantor resmi pemerintah di berbagai tingkatan. Maknanya pun mudah dicernak mengingat ia merupakan gambaran langsung keberagaman Nusantara yang kasad inderawi, yaitu meski kita secara identitas amat beragam namun karena kita hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tuntutannya adalah kemampuan kita semua untuk mengabstraksi identitas-identitas keragaman tersebut menjadi satu kesamaan. Jika sudah berada pada tataran demikian ini, secara ideologis memunculkan keberagaman budaya hukum Nusantara itu dapat menjadi tunggal Budaya Hukum Nasional, yaitu Pancasila. Tuntutan filosofis dimaksud Bhineka Tunggal Ika tergambarkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perspektif perundang-undangan, maksudnya berbeda-beda identitas tetapi tetap satu itu dapat dibaca pada pengertian demokratis dalam UUD NRI 1945 sampai saat ini diartikan tunggal sebagai dipilih langsung oleh rakyat. Padahal sejatinya, konstitusi tersebut membuka kepada kita semua bahwa ada keragaman budaya memilih yang telah lama ada dan hidup di Nusantara ini. Artinya, demokrasi tersebut merupakan abstraksi dari beragamnya budaya memilih pimpinan. Dengan demikian, keragaman budaya hukum telah tersurat dan tersirat dalam ungkapan Bhineka Tunggal Ika. 195 VI.7.2 Tataran Konstitusi Jikalau konstitusi diartikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara suatu negara, maka Negara Republik Indonesia telah memilik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konteks konstitusi tersebut keberagaman budaya hukum telah tersurat dan tersirat dengan jelas pada Pasal 18B ayat (1) bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian, Pasal (2) bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal-pasal tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara pluralistis secara sosial dan setiap satuan sosial yang ada dalam daerah tersebut diyakini memiliki hukum tersendiri yang hidup, dipelihara, berkembang dan dijadikan pedoman berkehidupan oleh satuan-satuan sosial tersebut dan telah menjadi pedoman yang sudah membudaya (budaya hukum) bangsa Indonesia. Kondisi satuan-satuan sosial demikian inilah sebenarnya yang dimaksud von Savigny sebagai Volksgeist dan sudah seharusnya diakomodasi kedalam pembentukan pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kalau merujuk aturan lama yang berlaku dan diberlakukan saat itu adalah UUDS 1950, maka dapat 196 dijumpai bahwa pada Pasal 104 Ayat (1) disebutkan bahwa “segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman menyebut perkara undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”69. Pada umumnya, Kearifan Lokal sebagaimana terurai di atas tersimpan dan diterapkan dalam praktik hukum adat di seluruh Nusantara. Negara Indonesia dalam konstitusi sangat menghargai adanya hukum adat dan masyarakat adat seperti yang tertuang pada pasal 18B ayat 2 UndangUndang Dasar NRI 1945 hasil amandemen yang berbunyi sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur didalam Undang-Undang” Apabila melihat rumusan pasal 18B ayat 2 tersebut, Negara menghormati adanya hukum adat, budaya hukum berupa kearifan-kearifan lokal seperti Reba, Sasi, Mapalus, dan kearifan lokal lainnya yang masih ada hidup di negeri Nusantara Bangsa Indonesia ini. Misalnya dalam konteks lingkungan hidup, Sasi, sebagai sebuah pranata adat yang bertujuan untuk konservasi lingkungan hidup, merupakan 69 Dominikus Rato, 2009. Pengantar Hukum Adat, Edisi Pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hal. 146. 197 kekayaan isi hukum positif sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks hukum publik seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebenarnya juga telah mengakui adanya hakim adat selaku pemimpin hukum adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksud, khususnya pasal 76 ayat (1) misalnya, disebutkan bahwa “kecuali dalam putusan hakim dapat dirubah, maka orang tidak dapat dituntut sekali lagi sebab perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Indonesia dengan keputusan yang telah tetap. Yang dimaksud dengan hakim Indonesia di sini, termasuk juga hakim swapraja dan hakim adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut70. Dalam konteks Hukum Pidana Adat Indonesia, keberlakuan asas dan praktik hukum pidana adat didasarkan atas ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 yang menyebutkan bahwa: “Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut 70 R. Sugandhi, 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional, hal. 94. 198 hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”. Dalam konteks hukum yang hidup sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memiliki struktur sosial khas komunal, pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negeri membentuk peradilan desa dan putusannya diakui. Tentu, struktur peradilannya tidak persis seperti struktur peradilan negara tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dimana peradilan desa itu akan dibentuk 199 sehingga substansi peradilan desa Indonesia sebagai warisan budaya tidak hilang. Sementara ruang lingkup yuridisnya sebatas tindakan-tindakan yang dapat merusak pergaulan sosial, tatanan sosial masyarakat setempat. Untuk membentuk peradilan desa, yang sebenarnya pada zaman sebelum Indonesia merdeka telah ada, dan ruang lingkupnya, perlu dilakukan kajian perbandingan ke negeri-negeri Afrika, misalnya saja Negeri Sinegal. Di negeri itu, ada sejenis peradilan desa yang dimasukkan kedalam sruktur peradilan negara sebagai satuan peradilan paling terdepan. Keberadaan peradilan desa tersebut dapat mengurangi lajunya jumlah perkara ke jenjang peradilan yang lebih tinggi berikutnya. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia semakin menumpuknya jumlah perkara ke tingkat yang lebih tinggi mungkin saja disebabkan peradilan tingkat pertama kesulitan menemukan keadilan substansial mengingat peradilan tingkat pertama tidak menggunakan pendekatan induktif dan emik masyarakat dimana perbuatan yang diduga melanggar hukum itu terjadi. Dengan demikian, ada pandangan bahwa semakin ke atas jenjang suatu perbuatan melanggar hukum itu diselesaikan diduga semakin jauh pula keadilan substansial tersebut diperoleh. VI.7.3 Tataran Yuridis Keragaman budaya hukum juga tersurat dalam sejumlah undang-undang. Untuk itu, dasar-dasar yuridis dimaksud setidak-tidaknya tampak pada tataran peraturan perundangundangan, diantaranya pada Undang-Undang Nomor 32 200 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Misalnya saja Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, misalnya Pasal 5 Ayat (1) bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, juga tersurat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 6 Ayat (1) disebutkn bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. VI.7.4 Tataran Sosiologis Secara sosiologis, rentangan Nusantara ini tergelar selain ragam suku, agama, keyakinan, dan sebagainya juga ada satuan-satuan sosial yang disebut desa dengan beragam sifatnya, misalnya dalam masyarakat Aceh dinamakan Gampong, dalam masyarakat Batak disebut Kuria, dalam masyarakat Minangkabau dinamakan Nagari, dalam masyarakat Palembang dinamakan Marga, di Ambon Negory, dan seterusnya. Kebhinekaan sosial tersebut di atas 201 merupakan fakta sosial budaya bangsa Indonesia sehingga negara pun menghormati keberagaman itu dan sekaligus keragaman norma sosial Nusantara. Dalam konteks demikian ini, setiap entitas sosial memiliki budaya hukum yang terekspresi pada keseluruhan produk hukum merupakan turunan dari Prinsip-Prinsip Pancasila. Tentu tidak saja berhenti pada konstitusi seperti Undang-Undang Dasar 1945, tetapi seperangkat peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden hingga peraturan yang paling bawah di tingkat desa. Bahkan, setiap putusan hukum hakim dalam proses peradilan, serangkaian surat keputusan dalam lingkungan birokrasi pun juga memuat budaya hukum dimaksud. Semua itu merupakan norma yang menindaklanjuti pasalpasal konstitusi dan terkontrol oleh nilai Pancasila atau budaya bangsa sehingga nilai itu dapat kembali atau dikembalikan ke masing-masing budaya masyarakat Indonesia itu sendiri dan diterima seluruh warga Nusantara. 202 DAFTAR PUSTAKA Ade Saptomo, 2012 “Budaya Hukum dalam Masyarakat Plural dan Problem Implementasi” dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2012. --------,2010. Hukum Grassindo. dan Kearifan Lokal. Jakarta: ---------,2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni: sebuah alternatif. Jakarta: Universitas Trisakti Press. -------, 2004 “Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Antar Pemerintah Daerah dan Implikasi Hukumnya” dalam Membangun Paradigma Baru Pembangunan Hukum Nasional”, Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, Indonesia, 6-7 Desember 2004. -------, 2004, “Local Potential in Land Tenure and Other Natural Resources” in International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, Questioning The Answer, Jakarta, Kemala Foundation, October 11-13, 2004. --------, 2006, “Menyelamatkan Hukum Dari Ambang Kematian” dalam Revitalisasi Hak Ulayat: Tantangan Atau Peluang. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 203 --------, 1995. Berjenjang Naik Bertangga Turun: Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dalam Masyarakat Minangkabau. Tesis 2. Jakarta: PPs UI. A.P. d’Entreves, 1951. Natural law: An introduction of legal philosophy. Ahmad Fauzan, 2005. “Kata Pengantar” dalam Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Prenada Media. Ahmad Kamil dkk,, 2004. Kaedah-Kaedah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Prenada Media. Ali, Ahmad, 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: PT. Yarsif Watampoe. Asshiddiqie, J dan Safa’at, a., 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Azhari, 1995. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI-Press. Barnes, J., 1984. The Complete Works of Aristotle. Princeton, NY.: Princeton University Press. Bogdan, Michael, 2010. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (terjemahan Derta Srie Widowatie). Bandung: Nusa Media. Budiardjo, Miriam (penyunting), 1984. Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi. Jakarta: Gramedia. 204 Chambliss, William J & Robert B. Seidman, 1971. Law, Order and Power. Adison Wesly: Reading Mass. Daniel S. Lev, “Peradilan dan Kultur Hukum Indonesia” dalam PRISMA, Nomor 6 Tahun II, Desember 1973. Dominikus Rato, 2009. Pengantar Hukum Adat, Edisi Pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Ehrlich, Eugeun, 1936. Fundamental Principles of the Sociology of Law (translated by W.L. Moll). New York: Harvard University Press. Evan, Willian M (ed.), 1980. The sociology of Law: A Sosial-Structural Perspective. London: The Free Press. Falakh, Fajrul, 1995. “Desentralisasi Penyelesaian Sengketa Hukum”, dalam KOMPAS, Jakarta. Friedman Lawrence M. , 1986. “Legal Culture and Welfare State”, dalam Gunther Teubner (Ed), Dilemas of Law in the Welfere State. New York: Walter de Gruyter. -------, 1975. The Legal System: A Sosial Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation. Griffiths, J., 1986. “What is Legal Pluralism” in Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law. No. 24/1986. Hal. 1-55. Hart, H.L.A.,1961, The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press. 205 Ihromi,T.O., 1993 Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. --------, 1984. Pokok-pokok Antropologi Budaya. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Ilmu hukum76.wordpress.com/2008/04/14/ beberapadefinisi-hukum/ Kelsen, Hans., 2008. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Bandung: Nusa Media. Koentjaraningrat, 1986. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. Koesnoe, Mochammad, 1997. Hukum Adat: Dalam alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi. Surabaya: Ubhara Press. -------, 1989. Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positip. Surabaya: Universitas Bhayangkara Kriekhoff, Valerine J.L., 1990. Mediasi, Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum, Ceramah Ilmiah Antropologi Hukum, 19 Agustus 1991. Depok: FHUI. M. Solly Lubis, 1995. Landasan dan Teknik Perundang Undangan. Bandung: Mandar Maju. McInerny, R., 1996. Thomas Aquinas: Treatise on law (Summa Theologica, Quesions 90-97). Washington DC.: Regnery Publishing Inc. 206 Meuwissen, D.H.M., 1982. Recht en Vrijheid. Utrecht: Aula. Milosovic, Dragen, 1994. A Primer in The Sociology of Law. New York: Harrow and Newton. Moores, Stradford W dan Gordon R. Woodman, 1987. Indigeneous Law and State. Dordrecht Holland: Foris Publications. Nader, Laura and Harry F. Todd, Jr. 1978. The Disputing Process: Law in Ten Societies. New: Colombia Press. Prill-Brett, June., 2002, “The Interaction of National Law and Customary Law in Natural Resource Management in the Northern Philippines”. dalam Legal Pluralism and Unofficial Law in Sosial, Economic and Political Development. Papers of the XIIIth International Congress, 7-10 April, Chiang Mai, Thailand. Rafael Maran, 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta Rineka Cipta. Rahardjo, Satjipto, 1988. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. -------, 2002. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: UMS Press. -------, 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam dan Huma. -------, 1979. Hukum dan Perubahan Sosia. Bandung: Alumni. 207 Robert B Seidman, 1972. “Law and Development, A. General Model”, dalam Law and Society Review, Edisi VI. Silbey, S.S., 2001. “Legal Culture and Legal Consciousness” dalam International Encyclopedia of Sosial and Behavioral Sciences. New York: Elsevier, Pergamon Press, hal. 8623-8629. Soenarko, 1950. Djambatan. Susunan Negara Kita. Malang: Spradley, 1972. Culture and Cognition: Rules, Map, and Plans. San Fransisco: Chandler Publishing Company. Stratford W Moores dan Gordon R Woodman, 1987, Indigeneous Law and State. Dordrecht Holland: Foris Publications. Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar.Yogyakarta: Liberty. Sugandhi, R., 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan Pertama. Surabaya: Usaha Nasional. Sunaryati Hartono, 1975. “Peranan Kesadaran Hukum Rakyat Dalam Pembaharuan Hukum” Kertas kerja pada symposium Kesadaran Hukum masyarakat dalam Masa Transisi. Jakarta: BPHN – Bina Cipta. 208 Suparlan, Parsudi, 1999. “Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya” dalam Antropologi. Thn. XXIII. No. 59: 8-9. Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah. Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 48 Kekuasaan Kehakiman. Tahun 2009 Tentang Wignjosoebroto, Soetandya., 1996. Tanah Negara: Tanah Adat Yang Dinasionalisasi (paper tidak terbit). Jakarta: Elsam. 209 Penulis lahir di Klaten, 02/12/1957, Pendidikan Sarjana Hukum 1984 dari Universitas Gadjah Mada, Magister legal Anthropology 1995 Sandwich Program Universiteit te Leiden dan Universitas Indonesia, Doktor Ilmu Budaya 2002 diperoleh dari Fakultas Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Guru Besar Ilmu Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Andalas 1 Maret 2006, sejak 2012 sebagai Staf Ahli Hukum Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Tim Ahli Hukum Kemendikbud, selain itu sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Dengan bekal pengalaman transendensialisasi ilmu dan pengetahuan secara lintas bidang ilmu menjadikan penulis amat mengetahui, mengerti, dan memahami dan menghayati secara mendalam tentang hukum baik dari sudut ilmu sosial, budaya, filsafat maupun ilmu hukum sendiri. Oleh sebab ini pula, penulis dipercaya memegang mata kuliah Perbandingan Budaya Hukum, Filsafat Hukum, Metodologi Penelitian Hukum, Hukum dan Kearifan Lokal oleh Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Universitas Pancasila Jakarta, Universitas Andalas Padang, dan Program Pascasarjana Universitas ternama lainnya. Penulis juga menulis buku: Hukum dan Kearifan Lokal (2010), Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni (2009). Selain itu, penulis juga aktif sebagai nara sumber seminar nasional dan internasional, sebagai nara sumber dialog-dialog aktual stasiun televisi nasional. 210